Professional Documents
Culture Documents
Sejarah Ham
Uploaded by
Muhamad WisnuCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Sejarah Ham
Uploaded by
Muhamad WisnuCopyright:
Available Formats
Sejarah yang melatarbelakangi lahirnya uu 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM di Indonesia:
Sebagai bangsa yang pernah diinjak-injak imperialisme, bangsa Indonesia menyadari betul arti hak asasi manusia. Karena itu, para pendiri negara sudah memikirkannya sejak awal kemerdekaan. Masalah hak asasi manusia pun dicantumkan dalam Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945. Apa yang dicantumkan itu, tiga tahun lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam perkembangannya, pasal-pasal mengenai hak asasi manusia ini banyak dicantumkan dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, juga berhasil menyepakati seperangkat rancangan pasal mengenai hak asasi manusia untuk draf Undang-Undang Dasar baru yang sedang disiapkan. Namun dengan dikeluarkanya Dekrit Presiden 1959 yang menyatakan berlaku kembalinya UUD 1945 kesepakatan tersebut dihentikan. Secara horizontal pengaturan HAM dalam UUD 1945 relatif telah ditegaskan. Namun secara vertikal yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dibawah UUD, pengaturan HAM mengalami pasang surut yang tidak bisa dipisahkan dengan konfigurasi politik pemerintah pada era tertentu. Sebagaimana dimaklumi bahwa pengaturan hak-hak hukum (legal rights), yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD, mengalami era keterbukaan sejak pemerintahan Habibie dan seterusnya. Gambaran ini menunjukan bahwa semangat yang dikandung dalam nilai-nilai dasar HAM dalam UUD 1945 tidaklah serta-merta membuahkan political will pemerintah dalam menyiapkan ketentuan perundang-undangan, baik dalam tataran undang-undang dan sebagainya. Memang terdapat faktor yang kompleks, misalnya pada tahun keberlakuan UUD 1945 (periode I), Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, yakni tidak kondusifnya kehidupan pemerintahan sebagaimana lazimnya. Akibat, ketentuan tentang HAM yang diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan organik menjadi terkendala. Memasuki Orde Baru kepemimpinan Soeharto (1966-1998), rakyat menaruh harapan yang besar, khususnya dalam pemulihan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, tidak ketinggalan juga perhatian terhadap upaya-upaya perlindungan dan jaminan atas HAM. Meskipun, UUD 1945 telah berlaku pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, akan tetapi dirasa perlu untuk segera dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang sistematis dan strategis dalam penegakan HAM di Indonesia. Namun dengan rezim yang berkuasa saat itu terkesan otoriter maka pembicaraan mengenai HAM menjadi pembicaraan publik saja.
Di sinilah pertama kalinya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menetapkan sebuah ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia-Panitia Ad Hoc. Ketetapan ini memberikan perintah agar secepatnya membentuk panitia kecil yang akan membahas sebuah Piagam Hak Asasi Manusia. Menindaklanjuti hal itu, kemudian pimpinan MPRS menetapkan rancangan Piagam HAM yang tertuang dalam rancangan pimpinan MPRS RI No. A3/I/Ad HocB/MPRS/ 1966 diberinama, Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan hak-hak serta kewajiban warga Negara. Selengkapnya A. H. Nasution, ketua MPRS mengatakan sebagai berikut: Sebagaimana saudara-saudara kiranya telah ketahui, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966, MPRS telah membentuk empat buah panitia Ad Hoc MPRS, satu diantaranya yang saya ketuai yang mempunyai tugas, mempelajari Hak-hak Asasi Manusia dalam hubungannya Demokrasi Terpimpin, dan berdasarkan hasil-hasil tersebut menyusun perincian-perincian Hak-hak Asasi Manusia yang harus diperlakukan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Panitia termaksud di atas setelah mengadakan sidang-sidangnya sejak bulan Agustus-November yang lalu telah menghasilkan dua buah perumusan yang dituangkan dalam bentuk sebuah PIAGAM TENTANG HAK-HAK AZASI MANUSIA DAN HAK-HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA, yang dalam waktu dekat ini direncanakan akan dapat disebarluaskan kepada masyarakat guna mendapat penyempurnaan.
Rencana perumusan piagam HAM ini mendapat respon positif dari masyarakat. Setidaknya, hal tersebut dikarenakan rumusan HAM yang terdiri dari Mukaddimah dan 31 pasal mengandung muatan-muatan HAM yang lebih jelas dan tegas. Memang, terdapat kritikan terhadap rumusan Piagam HAM MPRS. Namun, hal tersebut, menurut Todung Mulya Lubis, tidak mengurangi arti pentingnya kehadiran Piagam HAM sebagai rule of the game of constitution. Todung mengatakan sebagai berikut: In spirit of the Charters ambiguity. It is clear that it formslly paved the way for the revival of human rights. It gave new momentumto the creation of a human rights policy and was an attempt to formulate what was called the rule of the game of the constitution.
Berdasarkan putusan MPRS tanggal 6 Maret 1967 Nomor 34/B/1967 hasil Panitia Ad Hoc diterima untuk dibahas pada persidangan berikutnya. Namun, pada Sidang Umum MPRS
tahun 1968, rancangan piagam tersebut tidak dibahas karena sidang lebih mengutamakan membahas masalah nasional setelah terjadi tragedi Gerakan 30 September dan menata kembali kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Disisi lain dengan semakin matangnya konsolidasi kekuatan Orde Baru, lembaga MPRS dinilai tidak bersih dari Demokrasi Terpimpin model Soekarno. Dalam perspektif Orde Baru, sebagai lembaga, MPRS tidak dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis meskipun menyangkut jaminan hak-hak asasi manusia. Karena itu, seiring dengan upaya mematangkan konsolidasi pemerintahan kearah pembangunan, maka apa yang telah direncanakan oleh MPRS ini menjadi deadlock tanpa diperoleh kejelasan yang berarti. Dalam kebijakan selanjutnya, pengaturan HAM dalam masa Orde Baru tidaklah dalam bentuk piagam HAM, melainkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sikap demikian menjadi bukti bahwa Orde Baru hanya mengakui hak-hak hukum masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk memajukan dan melindungi HAM yang sesuai dengan prinsip Negara berdasarkan atas hukum sekaligus agar langkah percepatan penegakan HAM berjalan efektif, maka pemerintah Orde Baru membentuk sebuah komisi yang bernama Komisi Nasional HAM, yang disebut juga Komisi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Dengan pembentukan KOMNAS HAM tersebut maka kelihatan dengan terang hubungan yang erat antara penegakan HAM disatu pihak dan penegakan hukum dipihak lainnya. Ada dua tujuan pokok Komisi Nasional. Pertama, membantu perkembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): dan kedua meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Seiring derasnya arus globalisasi, permasalahan HAM harus dimasukan dalam agenda nasional. Untuk menyambut sidang umum MPR tahun 1998, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) mengusulkan perlunya masalah HAM dijadikan ketetapan MPR yang akan diajukan dalam Sidang Umum MPR tahun 1998. Tahun 1998, melalui Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, kembali ditegas eksistensi HAM. Tap MPR ini memberikan penegasan bahwa penegakan HAM dilakukan secara struktural, kultural, dan
institusional. Tujuannya adalah agar terciptanya sikap menghormati, menegakan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Secara struktural, melibatkan peran serta lembaga-lembaga negara beserta aparatur pemerintah. Secara kultural, dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, dan secara institusional, penegakan HAM juga diperankan oleh Komisi Nasional HAM yang ditetapkan dengan undang-undang. Disini, terdapat pandangan baru bahwa penegakan HAM, ternyata tidaklah semata-mata dicapai melalui sebuah Piagam HAM saja, tetapi juga membutuhkan sebuah langkah kongkret dan sinergis dari segenap lapisan masyarakat. Peran serta ini merupakan sebuah kebulatan tekad bersama bahwa penegakan HAM adalah tanggung jawab bersama dari seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah sendiri. Pada masa pemerintahan Habibie (1998-1999) tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1998, diatur kerangka Kerja Komnas HAM melalui Kepres No.129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia. Tujuan Rencana Aksi Nasional adalah untuk menjamin peningkatan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rencana Aksi Nasional dilaksanakan secara bertahap dalam sebuah program lima tahunan. Hal ini menunjukan kesinambungan program yang sebenarnya dapat saja ditinjau dan disempurnakan. Dalam pelaksanaannya maka dibentuklah sebuah Panitia Nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pada tanggal 9 Oktober 1998 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Keluarnya kepres ini didorong oleh kesadaran yang tinggi tentang kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat sebagaiman amanat UUD 1945 bahwa warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Sebagai anggota PBB, pada tanggal 23 Oktober 1985 Indonesia turut serta menandatangani sebuah konvensi yang menentang segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi. Konvensi tersebut berhasil disepakati dalam sidang majelis umum PBB tanggal 10 Desember 1985 dan berlaku efektif sejak 26 Juni 1987. Komitmen Indonesia atas hal tersebut terlihat dari keluarnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Sebagai bagian dari HAM, pada tanggal 26 Oktober 1998 berlaku UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UU ini memiliki nilai penting dalam menjamin hak dan kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia. Sejalan dengan kegiatan RANHAM, maka pada tanggal 25 Mei 1999 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional PBB penghapusan diskriminasi rasial yang tertuang dalam UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Awalnya Konvensi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 21 Desember 1965 dengan Resolusi 2106A (XX). Majelis Umum PBB memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi semangat penghapusan diskriminasi rasial dengan menerima Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, tidak terkecuali bagi Indonesia. Maka, dengan pengesahan konvensi ini Indonesia semakin menyatakan komitmennya dalam penegakan HAM di Indonesia. Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, pada tanggal 23 September 1999 diberlakukanlah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang disingkat menjadi UU HAM. UU ini menegaskan dua hal yang prinsipil, yakni Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Dasar Manusia (KDM). Antara Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Kewajiban Dasar Manusia (KDM) terdapat korelasi. Korelasi keduanya menunjukan terdapatnya keseimbangan tatanan dalam kehidupan masyarakat. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negra, hukum, pemerintah, dan setiap orang dan demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagaimana layaknya hak menuntut adanya pula kewajiban bagi pihak yang lain. Adapun KDM adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Dalam hal kedudukannya, UU ini merupakan payung hukum dari seluruh peraturan perundang-undangan yang menyangkut HAM.
Selanjutnya, sesuai dengan amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, dibentuklah sebuah pengadilan khusus HAM yang dilingkungan Peradilan Umum. Maka, dengan adanya amanat tersebut pada tanggal 23 November 2000 secara resmi berlaku UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang disingkat menjadi UU Pengadilan HAM.
UU NO 26 Tahun 2000 dan hubungannya dengan hukum internasional
Pelanggaran HAM Berat dalam UU no.26 tahun 2000 sebagaimana tercantum dalam pasal 7 hanya meliputi dua macam kejahatan yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Implikasinya, secara teoretis, para pelanggar HAM yang bisa diadili menjadi semakin sedikit karena kejahatan yang dapat diadili oleh Pengadilan ini hanya meliputi dua jenis kejahatan itu saja, delik kejahatan Internasional (delicta juris gentium) diluar dua jenis kejahatan tersebut seperti misalnya kejahatan agresi dan kejahatan perang serta pelanggaran terhadap Konvensi Geneva tidak ter-cover di dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu Pengadilan HAM ini dikhawatirkan oleh banyak pihak tidak akan dapat memberikan effective remedy bagi korban pelanggaran HAM. Padahal penjelasan Undang-Undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa UU ini mengacu pada Statuta Roma. Jika memang demikian, mengapa tidak juga dimasukkan Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi ke dalam yurisdiksi pengadilan HAM dalam UU no.26/2000? Selain itu, ternyata ada ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara bentuk-bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia sebagaimana yang dicantumkan dalam UU no.26/2000 dengan definisi tindak kejahatan serupa menurut hukum internasional. a. Tentang Konsep Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sementara, dalam bagian mengenai definisi konsep-konsep tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tentang tanggung jawab komando UU No.26/2000 mengadopsi pengertian yang terdapat dalam Statuta Roma. Sayangnya adopsi tersebut dilakukan dengan beberapa distorsi yang pada akhirnya melemahkan konsep kejahatan terhadap kemanusian itu sendiri. Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pasal 9 UU no.26/2000 juga sumir karena tidak ada parameter yang tegas untuk mendefinisikan unsur meluas, sistematik dan intensi yang menjadi unsur utama bentuk kejahatan ini. Ketidakjelasan defenisi menyangkut ketiga elemen tersebut mengakibatkan (pembuktian) pemidanaan terhadap kejahatan-kejahatan yang dimaksud akan menjadi sulit. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) yang rumusannya terdapat dalam pasal 9 UU No 26 tahun 2000 berbunyi sebagai berikut: Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinyabahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil,
Dalam Statuta roma, unsur meluas atau sistematik juga dapat ditelusuri melalui unsur tindak pidana (element of crime) yang dilakukan pada korban sipil, artinya, meluas dapat tidak hanya mengacu pada massivitas korban atau luasan wilayah kejadian, melainkan juga bisa diacu pada intensivitas bentuk kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini terpapar dengan jelas dalam rumusan pasal 7 ayat 2 mengenai penjelasan definitif atas extermination (pemusnahan): includes the intentional infliction of conditions of life, inter alia the deprivation of access to food and medicine, calculated to bring about the destruction of part of a population. Dalam rumusan pasal 9 UU no.26/2000 terma calculated tidak disertakan. Dengan tidak adanya pertimbangan ini maka bisa dibilang secara otomatis membatasi pembuktian unsur meluas semata-mata pada jumlah korban dan luasan geografis. Selain itu dalam UU No.26/2000 tidak terdapat pencantuman secara detail dan eksplisit mengenai jenis tindakan kejahatan seksual yang masuk dalam yuisdiksi Pengadilan HAM. Dalam pasal 9g tidak menyertakan penjelasan definitif mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara Ini berimplikasi pada bisa diinterpretasikannya kejahatan seksual lain sebagai bentuknya yang setara, padahal di Statuta Roma yang setara adalah bobot kekerasan/kejahatannya (equal gravity). b. Konsep Tanggung Jawab Komando Ketentuan pidana dalam UU no.26/2000 juga melingkupi tanggung jawab komando (command responsibility). Namun pasal 42 ayat 1 Undang-Undang ini mempunyai beberapa kelemahan dengan konsekuensi hukum yang besar. Pengertian tanggung jawab komando dalam pasal ini dijabarkan sebagai berikut: komando militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komando militer dapatdipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah komando dan pengendaliannya yang efektif, Pengertian di atas, yang menggunakan kata dapat (could) dan bukannya akan (shall) atau harus (should), secara implisit menegaskan bahwa tanggung jawab komando dalam kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang diatur melalui UU ini bukanlah sebuah hal yang bersifat otomatis dan wajib. Pasal ini secara tegas menguatkan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pasal 9 yang cenderung ditujukan pada pelaku langsung di lapangan. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum harus dapat menunjukkan dan membuktikan adanya keperluan (urgensi) untuk mengadili para penanggung jawab komando, dan bukan hanya pelaku lapangan saja. Lebih lanjut, pasal 42 ayat 1 (a) mensyaratkan penanggung jawab komando untuk seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Padahal, sumber dari pasal spesifik tersebut, yaitu pasal 28 ayat 1 (a) Statuta Roma secara tegas menyatakan bahwa komandan militer seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut melakukan atau hendak melakukan kejahatan
Distorsi ini berarti mengabaikan adanya kewajiban dari pemegang tanggung jawab komando untuk mencegah terjadinya kejahatan. Meskipun dalam pasal 42 ayat 1 (b) pengabaian ini dikoreksi dengan kalimat komando militer tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah dan menghentikan perbuatan tersebut, namun tidak ada definisi dan batasan yang tegas tentang apa yang layak dan perlu dilakukan oleh penanggung jawab komando. Selain itu, pasal ini berimplikasi pada pengadilan terpaksa menekankan fokus perhatiannya pada proses, yaitu apakah tindakan yang dilakukan sudah layak atau tidak, apakah perlu atau tidak (obligation of conduct), dan secara otomatis mengabaikan pada kenyataan apakah tindakan yang diambil oleh penanggung jawab komando berhasil mencegah dan menghentikan kejahatan atau tidak (obligation of result). Padahal, selain harus bertanggung jawab jika menjadi pelaku langsung, penganjur, atau penyerta, seorang atasan seharusnya juga bertanggung jawab secara pidana atas kelalaian melaksanakan tugas (dereliction of duty) dan kealpaan (negligence). Standar hukum kebiasaan internasional untuk kealpaan dan kelalaian dalam arti yang luas menyatakan bahwa seorang atasan bertanggung jawab secara pidana jika: (1) ia seharusnya mengetahui (should have had knowledge) bahwa pelanggaran hukum telah dan atau sedang terjadi, atau akan terjadi dan dilakukan oleh bawahannya; (2) ia mempunyai kesempatan untuk mengambil tindakan; dan (3) ia gagal mengambil tindakan korektif yang seharusnya dilakukan sesuai keadaan yang ada atau terjadi saat itu. Tentang apakah seseorang tersebut seharusnya mengetahui harus diuji sesuai keadaan yang terjadi dan dengan melihat juga orang/pejabat lain yang setara dengan tertuduh. Pasal 7(3) Statuta ICTY juga secara interpretatif mencerminkan standar kebiasaan internasional tersebut. Pasal tersebut mengakui adanya pertanggungjawaban pidana jika seseorang mengetahui atau mempunyai alasan untuk tahu (knew or had reason to know) kelakuan bawahannya. Kalimat ini berkaitan dengan adanya kegagalan untuk mencegah suatu kejahatan atau menghalangi tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bawahannya atau menghukum mereka yang telah melakukan tindak pidana. Meskipun pasal ini memfokuskan pada keadaan dimana seorang bawahan akan melakukan suatu tindak pidana atau telah melakukannya, tidak ada indikasi bahwa tanggung jawab pidana tersebut akan dihilangkan jika ada tindakan yang telah dilakukan oleh si atasan namun pelanggaran / kejahatan oleh bawahan tetap terjadi. Selain Statute Roma banyak juga konvensi2 internasional yang diadaptasi dalam menunjang penegakan HAM diIndonesia,seperti :
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5795)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseFrom EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseRating: 4 out of 5 stars4/5 (1108)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20025)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19653)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (3278)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelFrom EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (5509)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2475)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2567)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12947)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceFrom EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceRating: 4 out of 5 stars4/5 (2556)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionFrom EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2507)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationFrom EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationRating: 4 out of 5 stars4/5 (2499)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)From EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9486)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6521)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderFrom EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderRating: 4 out of 5 stars4/5 (5718)












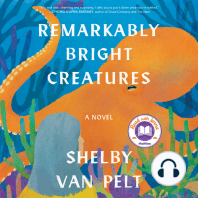
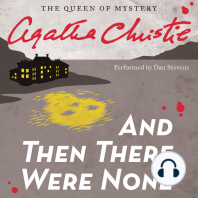






![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)





