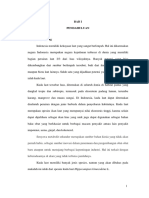Professional Documents
Culture Documents
Sistem Sosial Masyarakat Pantai
Uploaded by
Ahdiat CelebesCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Sistem Sosial Masyarakat Pantai
Uploaded by
Ahdiat CelebesCopyright:
Available Formats
SISTEM SOSIAL MASYARAKAT PANTAI
MAKALAH
AHDIAT P 0201212401
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH KONSENTRASI MANAJEMEN KELAUTAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2012
A. PENDAHULUAN Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau mencapai lebih kurang 17.500 buah dan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar, dengan kekayaan ragam flora dan faunanya, termasuk didalamnya endemik. Sebagai konsekuensinya, Indonesia secara komparatif memiliki keunggulan dibandingkan negara lain. Pertama adalah keunggulan sumberdaya alam. Sebagai negara kepulauan, tidaklah mengherankan jika lebih kurang dua pertiga dari luas keseluruhan teritorial negara kesatuan yang berbentuk republik ini merupakan perairan, dengan luas lebih kurang 5,8 juta km2. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, yang mencapai lebih kurang 81.000 km. Dan sudah barang tentu dengan luas perairan, panjang garis pantai dan jumlah pulau yang demikian besar, secara alami Indonesia mewarisi kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Kedua adalah keunggulan sumberdaya manusia. Secara kuantitas, jumlah penduduk Indonesia merupakan yang terbesar kelima di dunia, yaitu lebih kurang 220 juta jiwa. Dan, lebih kurang 60 persen diantaranya hidup dan bermukim di sekitar wilayah pesisir. Dan, sebagian besar diantaranya menggantungkan kehidupannya kepada keberadaan sumberdaya alam pesisir dan lautan. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa sebagian besar kegiatan dan aktivitas sehariharinya selalu berkaitan dengan keberadaan sumberdaya di sekitarnya. Sebagai konsekuensinya, sumberdaya pesisir dan laut semakin banyak dieksploitasi, mulai dengan menggunakan teknologi yang paling sederhana sampai teknologi moderen. Fenomena ini memberikan indikasi bahwa semakin tinggi tingkat penggunaan teknologi eksploitasi, maka semakin besar tekanan terhadap keberadaan sumberdaya tersebut. Bahkan tidaklah mengherankan bilamana tingkat teknologi yang digunakan sangat ekstraktif dan cenderung destruktif, maka hal ini akan menjadi ancaman yang sangat signifikan bagi keberlangsungnan sumberdaya pesisir dan laut Indonesia. Oleh karena itu, demi menjaga keberlanjutan sumberdaya tersebut, maka perlu kiranya dirancang dan diimplementasikan rambu-rambu atau batasanbatasan eksploitasi disesuaikan dengan keberadaan sumberdaya, zonasi dan karakteristik sumberdaya serta karakteristik daerahnya (propinsi / kabupaten / kota) sebagai satuan wilayah pembangunannya. Dalam hal ini, karena implikasi pemanfaatan sumberdaya dilakukan oleh masyarakat pesisir, maka perlu kiranya diketahui bagaimana sebenarnya karakteristik masyarakat pesisir, sehingga kebijakan, strategi dan program pengelolaan sumberdaya dapat mengakomodasi karakter masyarakat pesisir yang memang sangat dinamis dan sangat tergantung pada ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut di sekitarnya. B. KARAKTERISTIK MASYARAKAT PESISIR Masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat yang pluraristik tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Artinya bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan. Karena, struktur masyarakat pesisir sangat plurar, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya. Hal menarik adalah bahwa bagi masyarakat pesisir, hidup di dekat pantai merupakan hal yang paling diinginkan untuk dilakukan mengingat segenap aspek kemudahan dapat mereka peroleh dalam berbagai aktivitas kesehariannya. Dua
contoh sederhana dari kemudahan-kemudahan tersebut diantaranya: Pertama, bahwa kemudahan aksesibilitas dari dan ke sumber mata pencaharian lebih terjamin, mengingat sebagian masyarakat pesisir menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan potensi perikanan dan laut yang terdapat di sekitarnya, seperti penangkapan ikan, pengumpulan atau budidaya rumput laut, dan sebagainya. Kedua, bahwa mereka lebih mudah mendapatkan kebutuhan akan MCK (mandi, cuci dan kakus), dimana mereka dapat dengan serta merta menceburkan dirinya untuk membersihkan tubuhnya; mencuci segenap peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti pakaian, gelas dan piring; bahkan mereka lebih mudah membuang air (besar maupun kecil). Selain itu, mereka juga dapat dengan mudah membuang limbah domestiknya langsung ke pantai/laut. Masyarakat pesisir mempunyai sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang khas/unik. Sifat ini sangat erat kaitannya dengan sifat usaha di bidang perikanan itu sendiri. Karena sifat dari usaha-usaha perikanan sangat dipengaruhi oleh faktorfaktor seperti lingkungan, musim dan pasar, maka karakteristik masyarakat pesisir juga terpengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Beberapa sifat dan karakteristik usaha-usaha masyarakat pesisir diuraikan sebagai berikut. 1. Ketergantungan pada Kondisi Lingkungan Salah satu sifat usaha perikanan yang sangat menonjol adalah bahwa keberlanjutan atau keberhasilan usaha tersebut sangat bergantung pada kondisi lingkungan, khususnya air. Keadaan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bagi kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kehidupan masyarakat pesisir menjadi sangat tergantung pada kondisi lingkungan itu dan sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, khususnya pencemaran, karena limbah industri maupun tumpahan minyak, misalnya, dapat menggoncang sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pencemaran di pantai Jawa beberapa waktu lalu, contohnya, telah menyebabkan produksi udang tambak anjlok secara drastis. Hal ini tentu mempunyai konsekuensi yang besar terhadap kehidupan para petani tambak tersebut. 2. Ketergantungan pada Musim Karakteristik lain yang sangat menyolok di kalangan masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan, adalah ketergantungan mereka pada musim. Ketergantungan pada musim ini semakin besar bagi para nelayan kecil. Pada musim penangkapan para nelayan sangat sibuk melaut. Sebaliknya, pada musim peceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur. Kondisi ini mempunyai implikasi besar pula terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pantai secara umum dan kaum nelayan khususnya. Mereka mungkin mampu membeli barang-barang yang mahal seperti kursimeja, lemari, dan sebagainya. Sebaliknya, pada musim paceklik pendapatan mereka menurun drastis, sehingga kehidupan mereka juga semakin buruk. Secara umum pendapatan nelayan memang sangat berfluktuasi dari hari ke hari. Pada satu hari mungkin memperoleh tangkapan yang sangat tinggi, tapi pada hari berikutnya bisa saja kosong. Hasil tangkapan, dan pada gilirannya pendapatan nelayan, juga sangat dipengaruhi oleh jumlah nelayan yang beroperasi di suatu daerah penangkapan (fishing ground). Di daerah yang padat penduduknya seperti daerah pantai utara Jawa, misalnya, sudah terjadi kelebihan tangkap (overfishing). Hal ini mengakibatkan volume hasil tangkapan para nelayan menjadi semakin kecil, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan mereka.
Kondisi di atas turut pula mendorong munculnya pola hubungan tertentu yang sangat umum dijumpai di kalangan nelayan dan juga petani tambak, yakni pola hubungan yang bersifat patron-klien. Karena keadaan ekonomi yang buruk, maka para nelayan kecil, buruh nelayan, petani tambak kecil, dan buruh tambak seringkali terpaksa meminjam uang dan barang-barang kebutuhan hidup seharihari dari para juragan atau para pedagang pengumpul (tauke). Konsekuensinya, para peminjam tersebut menjadi terikat dengan pihak juragan atau pedagang. Keterikatan tersebut antara lain berupa keharusan menjual produknya kepada pedagang atau juragan tersebut. Pola hubungan yang tidak simetris ini tentu saja sangat mudah berubah menjadi alat dominansi dan eksploitasi. Stratifikasi sosial yang sangat menonjol pada masyarakat nelayan dan petani tambak adalah stratifikasi yang berdasarkan penguasaan alat produksi. Pada masyarakat nelayan, umumnya terdapat tiga strata kelompok yaitu : 1. Strata pertama dan yang paling atas adalah mereka yang memiliki kapal motor lengkap dengan alat tangkapnya. Mereka ini biasanya dikenal dengan nelayan besar atau modern. Biasanya mereka tidak ikut melaut. Operasi penangkapan diserahkan kepada orang lain. Buruh atau tenaga kerja yang digunakan cukup banyak, bisa sampai dua atau tiga puluhan. 2. Strata kedua adalah mereka yang memiliki perahu dengan motor tempel. Pada strata ini biasanya pemilik tersebut ikut melaut memimpin kegiatan penangkapan. Buruh yang ikut mungkin ada tapi terbatas dan seringkali merupakan anggota keluarga saja. 3. Strata terakhir adalah buruh nelayan. Meskipun para nelayan kecil bisa juga merangkap menjadi buruh, tetapi banyak pula buruh ini yang tidak memiliki sarana produksi apa-apa, hanya tenaga mereka itu sendiri. Seringkali nelayan besar juga merangkap sebagai pedagang pengumpul. Namun demikian, biasanya ada pula pedagang pengumpul yang bukan nelayan, sehingga pedagang ini merupakan kelas tersendiri. Mereka biasanya menempati posisi yang dominan ketika berhadapan dengan para nelayan kecil. Dalam masyarakat petani tambak, stratifikasi sosial berdasarkan penguasaan alat produksi ini juga menonjol. Mirip dengan strata sosial yang ada pada masyarakat nelayan, masyarakat petani tambak juga terdiri dari 3 strata sosial yang dominan yaitu : (1) Strata atas adalah mereka yang menguasai tambak yang luas, (2) Strata menengah yang memiliki luas tambak sedang/kecil, dan (3) Strata paling bawah adalah para pengelola/buruh. Bagi para nelayan, penguasaan alat produksi tadi sangat berhubungan dengan daya jelajah mereka dalam melakukan penangkapan. Mereka yang beroperasi dengan menggunakan kapal motor, misalnya, dapat melakukan penangkapan dan sekaligus pemasaran di daerah-daerah yang sangat jauh. Sementara nelayan kecil yang menggunakan perahu tanpa motor hanya mampu beroperasi di daerah yang dekat atau daerah pantai/pesisir saja. Sifat usaha penangkapan juga menyebabkan munculnya pola tertentu dalam hal kebersamaan antar anggota keluarga nelayan. Bagi para nelayan kecil, misalnya, seringkali mereka berangkat sore hari kemudian kembali besok harinya. Ada juga yang berangkat pagi-pagi sekali, kemudian kembali pada sore atau malam harinya. Sementara mereka yang beroperasi dengan kapal motor bisa meninggalkan rumah berminggu- minggu bahkan berbulan-bulan. Aspek lain yang perlu diperhatikan pada masyarakat pantai adalah aktivitas kaum wanita dan anak-anak. Pada masyarakat ini, umumnya
wanita dan anak-anak ikut bekerja mencari nafkah. Kaum wanita (orang tua maupun anak-anak) seringkali bekerja sebagai pedagang ikan (pengencer), baik pengencer ikan segar maupun ikan olahan. Mereka juga melakukan pengolahan ikan, baik kecil-kecilan di rumah untuk dijual sendiri maupun sebagai buruh pada pengusaha pengolahan ikan. Sementara itu, anak laki-laki seringkali sudah dilibatkan dalam kegiatan melaut. Ini antara lain yang menyebabkan anak-anak nelayan banyak yang tidak sekolah. 3. Ketergantungan pada Pasar Karakteristik lain dari usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir ini adalah ketergantungan pada pasar. Tidak seperti petani padi, para nelayan dan petani tambak ini sangat tergantung pada keadaan pasar. Hal ini disebabkan karena komoditas yang dihasilkan oleh mereka itu harus dijual baru bisa digunakan untuk memenuhi keperluan hidup. Jika petani padi yang bersifat tradisional bisa hidup tanpa menjual produknya atau hanya menjual sedikit saja, maka nelayan dan petani tambak harus menjual sebagian besar hasilnya. Setradisional atau sekecil apapun nelayan dan petani tambak tersebut, mereka harus menjual sebagian besar hasilnya demi memenuhi kebutuhan hidup. Karakteristik di atas mempunyai implikasi yang sangat penting, yakni masyarakat perikanan sangat peka terhadap harga. Perubahan harga produk perikanan sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat perikanan. C. SISTEM NILAI DAN PANDANGAN DUNIA MASYARAKAT PANTAI Sistem nilai dalam dalam suatu kebudayaan saling terkait dengan systemsistem gagasan, pengetahuan kepercayaan, aturan dan lain-lain dalam kebudayaan bersangkutan. System nilai juga berfungsi sebagai pedoman bagi warga dalam menentukan sikap, tindakan, hal atau benda yang dianggap baik, layak atau sebaliknya, berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungan, sosial ekonomi, kepercayaan, teknologi, seni, dan lain-lain. Ada banyak komunitas nelayan di dunia, antara lain seperti komunitas pulaupulau Pasifik dan kawasan Timur Indonesia masih mempertahankan nilai-nilai hubungan keseimbangan manusia dengan lingkungan. Bahkan linkungan flora dan fauna khususnya di laut dianggap sebagai subjek-subjek dengan mana manusia berhaul. Sebaliknya ada juga sebagian besar nelayan komunitas nelayan tidak mengindahkan nilai-nilai kearifan lingkungan seperti itu. Nilai-nilai tersebut didasari oleh pandangan manusia yang subjektif, dimana flora dan fauna difahami sebagai objek-objek lingkungan dan sumberdaya untuk dipelajari dan dimanfaatkan oleh manusia semata. Konsep manajemen sumberdaya secara saintis biasa perwujudan dari pandangan itu. Salah satu nilai yang menjadi kesadaran masyarakat nelayan ialah nilai praktis. Dalam hal rekrut anggota kelompok kerja, kekuatan fisik menjadi ukuran pertama, berikut pengetahuan dan keterampilan, kejujuran, kepatuhan dan kesetiaan pada kelompok dan pimpinan. Semua komponen nilai seperti ini merupakan penunjang dan penentu bagi berhasil dan bertahannya usaha perikanan atau pelayaran. Sistem nilai ini juga mencirikan kelembagaan punggawa-sawi pada masyarakat bahari bugis-makassar. Dalam hal teknologi kebaharian, nelayan dan pelaut Bugis Makassar sangat mengutamakan nilai pragmatisnya, sebaliknya cenderung mengabaikan nilai seninya. Itulah sebabnya sebagian tipe perahu Bugis Makassar sudah digantikan dengan tipe-tipe baru dengan pertimbangan laju, kecepatan, keseimbangan, volume dan kekuatan/lamanya usia produktif. Lain halnya dengan tipe perahu Jawa-
Madura dengan arsitektur penuh ukiran, gambar-gambar, symbol dan dengan paduan warna cet masih bertahan hingga saat ini. D. KELEMBAGAAN MASYARAKAT NELAYAN Kelembagaan nelayan terbentuk dari perilaku yang terus menerus hidup dalam komunitas nelayan, dan mengalami proses penyesuaian dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi serta potensi lingkungannya. Kelembagaan yang ada pada komunitas masyarakat nelayan dimaksudkan sebagai suatu sistem organisasi yang berlaku dan diakui oleh komunitas nelayan, baik yang termasuk kelembagaan formal maupun informal. Seperti halnya kelembagaan ekonomi dalam masyarakat nelayan terbentuk oleh adanya proses yang saling mempengaruhi antara lingkungan tempat hidup masyarakat dengan masyarakat itu sendiri (nelayan), dan peranan lembaga ini sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya kegiatan ekonomi masyarakat nelayan diantaranya adalah nelayan tangkap (Astuty, 2006). Masyarakat yang strukturnya masih sederhana (belum banyak dicampuri oleh pihak luar) memiliki sistem pengelolaan yang berakar pada masyarakat (community based management), di mana setiap proses-proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai kepada penerapan sanksi hukum, dilakukan secara bersama oleh masyarakat. Konsekuensinya, segala aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama cenderung dapat dilakukan dan ditaati dengan sepenuh hati. Di samping itu, setiap anggota masyarakat juga merasa memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dari aturan-aturan tersebut. Banyak contoh dari praktek-praktek kelembagaan tradisional yang dapat dikaji sebagai salah satu bentuk pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang melibatkan partisipasi luas dari masyarakat pesisir. 1. Seke di Desa Para, Kabupaten Sangihe Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. Salah satu contoh diterapkannya dengan mekanisme tradisional dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah tradisi Seke yang dijumpai di Desa Para, Kabupaten Sangihe Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. Dalam kasus Seke ini, sumberdaya alam yang dikelola adalah sumberdaya perikanan, karena memang sebagian besar masyarakat Desa Para memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Menurut Wahyono et.al (1992), masyarakat Desa Para mengenal 3 jenis wilayah perairan yang dijadikan sebagai tempat penangkapan ikan (fishing ground) yaitu (1) Sanghe, (2) Inahe dan (3) Elie. Sanghe adalah suatu wilayah laut tempat terdapatnya terumbu karang (bahasa lokal nyare), di mana pada perairan di sekitar terumbu karang banyak dihuni oleh ikan-ikan karang. Sedangkan Inahe adalah wilayah perairan yang menjadi batas antara wilayah Sanghe dan Elie. Sementara itu, Elie adalah suatu wilayah penangkapan ikan yang paling jauh dari daratan (off shore). Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tersebut, masyarakat Desa Para membentuk sebuah kelompok nelayan yang diberi nama Seke. Nama Seke ini diambil dari nama sebuah alat tangkap ikan layang yang berbentuk persegi panjang dan memiliki ukuran panjang 30 m dan lebar 82 cm. Alat ini dibuat dari tumbuh-tumbuhan lokal, yaitu bambu (bulo), kayu nibung, rotan (uwe), dan daun kelapa atau janur kuning (bango). Berdasarkan beberapa literatur seperti Wahyono et.al. (1992), organisasi tradisional Seke ini sudah terbentuk sejak tahun 1912. Dalam organisasi Seke, dikenal beberapa istilah keanggotaan berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing, yaitu Lekdeng, Tatalide,
Seke Kengkang, Matobo, Tonaas, Mandora, dan Mendoreso. Lekdeng adalah sebuah istilah lokal yang berarti anggota. Sedangkan Tatalide adalah sebutan untuk anggota yang ditugaskan memegang talontong (tongkat yang digunakan untuk menjaga Seke agar posisinya tegak lurus di atas permukaan laut). Tugas anggota ini menggerak-gerakan Seke suoaya ikan yang sudah berada di dalamnya tidak lari ke luar. Seke Kengkang adalah sebutan untuk anggota yang berada di atas perahu tempat meletakkan Seke (perahu kengkang). Anggota ini bertugas menurunkan Seke ke laut apabila ada aba-aba yang diberikan pemimpin pengoperasian Seke. Matobo adalah sebutan untuk anggota yang bertugas menyelam dan melihat posisi gerombolan ikan layang sebelum Seke diturunkan ke laut. Tonaas adalah sebutan untuk nelayan yang memimpin pengoperasian Seke, sedangkan wakilnya disebut Tonaseng Karuane. Mandore adalah sebutan local untuk orang yang selalu membangunkan anggota Seke setiap kali pergi beroperasi dan membagi hasil tangkapan kepada anggota. Mandore ini mempunyai kemampuan menaksir jumlah hasil tangkapan yang akan dibagikan ke seluruh anggota. Sementara itu, Mendoreso adalah sebutan untuk orang yang menjadi bendahara organisasi Seke (Wahyono et al.1992). Dari uraian tentang keanggotaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa walaupun bentuknya masih tradisional, tetapi organisasi Seke telah menerapkan konsep bagi hasil yang baik seperti ciri yang terdapat pada organisasi moderen. Salah satu variable penting yang dapat diketahui dari konsep pengelolaan sumberdaya perikanan berakar pada masyarakat di Desa Para ini adalah bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan betulbetul oleh, dari dan untuk masyarakat desa. Hal ini tercirikan dari konsep bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan Seke tersebut. Menurut Wahyono et al. (1992) sistem bagi hasil yang ada di Desa Para paling tidak diarahkan kepada 4 pertimbangan yaitu : (1) Bagi hasil tangkapan yang diberikan kepada warga desa yang sudah berkeluarga (termasuk janda/duda); (2) Bagi hasil tangkapan untuk warga desa yang belum berkeluarga; (3) Bagi hasil tangkapan yang didasarkan dari status sosial tertentu, antara lain seperti kepala desa, guru, pendeta, perawat dan sebagainya; serta (4) Bagi hasil tangkapan yang diberikan menurut status keanggotaan dalam organisasi Seke, yaitu tonaas, mandor, juru selam dan sebagainya. Kelompok Seke dalam operasinya menerapkan konsep lokasi penangkapan ikan yang eksklusif dalam arti bahwa terdapat kaitan antara satu lokasi dengan satu jenis alat tangkap. Dalam kelompok Seke terdapat juga pengaturan operasi di tempat-tempat penangkapan yang dilakukan secara bergilir. Dalam setiap harinya, kecuali Hari Minggu, ada empat Seke yang dioperasikan pada empat tempat penangkapan. Salah satu contoh pengaturan Seke dalam satu minggunya dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Jadwal Pengoperasian Empat Seke di Empat Lokasi Penangkapan di Desa Para, Sangihe Talaud Hari Lokasi Penangkapan Ikan Tatumban Binuwu Mangare Lanteke go ng Senin Ramenusa Balaba Lembo Lumairo Selasa Lembo Lumairo Lembe Ramenusa Rabu Lembe Ramenusa Kampiun Lembo Kamis Kampiun Lembo Balaba Lembe Jumat Balaba Lembe Lumairo Kampiun
Ramenus Balaba a Sumber : Wahyono et al., (1992). Apabila terdapat pelanggaran lokasi, pihak yang melanggar dikenakan sanksi ganti rugi berupa barang yaitu 5-10 zak semen atau uang senilai barang itu. Barang ini nantinya digunakan untuk keperluan pembangunan gereja atau fasilitas umum lainnya di Desa Para. Seke merupakan salah satu contoh pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan lautan, dalam hal ini adalah sumberdaya perikanan, yang muncul dan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Dalam kasus Seke ini, paling tidak ada dua pelajaran yang dapat dipetik dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam. Pertama, Seke mengatur sekelompok masyarakat untuk senantiasa memberikan perhatian kepada distribusi pemanfaatan sumberdaya alam kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya pembagian waktu dan lokasi untuk setiap kelompok Seke dalam satu periode waktu (misalnya 1 minggu). Dengan distribusi yang adil seperti ini maka konflik pemanfaatan akan semakin kecil potensinya. Kedua, selain distribusi penangkapan ikan, tradisi Seke juga mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari system bagi hasil yang diterapkan di mana seluruh komponen masyarakat mendapat bagi hasil dari penangkapan ikan yang diperoleh oleh sebuah kelompok Seke tertentu. Dalam konteks moderen, sistem distribusi pendapatan seperti ini mencirikan adanya konsep pemerataan yang kuat di kalangan masyarakat Desa Para. Secara umumsemangat pengelolaan sumberdaya perikanan yang murni oleh masyarakat seperti kelompok Seke ini perlu diadopsi dalam bentuk baru pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan lautan di Indonesia, sehingga kelestarian sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal tetap menjadi perhatian utama dibanding kepentingan ekonomi jangka pendek yang menguntungkan salah satu pengguna saja. 2. Sasi di Desa Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Contoh lain dari pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan lautan yang berakar pada masyarakat adalah tradisi Sasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pesisir di Propinsi Maluku. Salah satunya yang terkenal adalah tradisi Sasi di Desa Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi adalah suatu kesepakatan tradisional tentang pemanfaatan sumberdaya alam yang disusun oleh masyarakat dan disahkan melalui mekanisme struktural adat di suatu desa. Pelaksanaan sasi di Desa Nolloth pada saat ini berdasarkan atas Keputusan Desa tentang Peraturan Sasi Desa Nolloth yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 1994 dan disahkan oleh kepala desa dan kewang. Bersamaan dengan keputusan tersebut, juga dikeluarkan aturan tentang sanksi terhadap pelanggaran Sasi. Zona Sasi meliputi seluas 125.000 m2 pada pesisir pantai sepanjang 2,5 km, mulai dari pantai Umisin (batu berlubang) sampai dengan pantai Waillessy (batas dengan Desa Ihamahu). Sedangkan ke arah laut, zona ini mulai dari surut terendah sampai kedalaman 25 m. Dengan demikian sebuah zona sasi merupakan daerah terbatas bagi pemanfaatan sumberdaya alam laut yang sepenuhnya diatur melalui peraturan Sasi. Seperti yang telah dikemukakan di atas, Sasi merupakan salah satu institusi adat yang berisi kesepakatan-kesepakatan adat lengkap dengan
Sabtu
Lumairo
Kampiun
sangsi apabila terjadi pelanggaran terhadap adat tersebut. Sebagai contoh, dalam ayat 2 pasal 1 Peraturan Sasi dikatakan bahwa zona ini tertutup bagi anak negeri maupun orang luar. Kegiatan lain yang dilarang, yaitu memanah ikan serta kegiatan wisata bahari yang belum mendapat ijin dari kepala desa. Landasan institusi dan struktur organisasi pelaksanaan Sasi yang dipraktekkan di beberapa desa di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah disajikan pada Tabel 2. Tabel 2. Landasan Institusi Pelaksanaan Sasi di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah Landasan Desa Nolloth Paperu Siri Sori Tujuan Melindungi Melindungi Meningkatkan tradisi tradisi pendapatan desa Meningkatka meningkatka Melindungi n pendapatan n pendapatan sumberdaya dari desa desa eksploitasi oleh orang lain Melindungi lingkungan Norma (Kaidah) Dilarang mengambil : ola, batulaga, tiram, teripang, akar bahar ikan Pengambilan dapat dilaksanakan bila Sasi dibuka Daerah yang dilarang, yaitu pantai di depan desa (panjang 2,5 km, kedalaman air hingga 25 m) Dilarang menangkap ikan (semua jenis ikan) Alat yang hanya diijinkan adalah jala, bagan tancap dan pancing tangan Penangkapan ikan dilakukan bila Sasi dibuka Daerah yang dilarang adalah sekitar tanjung Paperu (untuk Sasi khusus) dan di sepanjang pantai desa (untuk Sasi umum) Buka Sasi dengan cara lelang Diatur secara tertulis dengan keputusan desa Dilaksanakan oleh pemerintah Dilarang mengambil teripang, lola dan caping-caping Penangkapan diijinkan bila Sasi dibuka Daerah yang dilarang adalah perairan pesisir sepanjang desa
Tingkah Laku Struktur Organisa si
Buka Sasi dikoordinir oleh desa Diatur secara tertulis dengan keputusan desa Dilaksanakan oleh pemerintah
Buka Sasi dengan cara lelang Diatur secara lisan dengan keputusan desa Dilaksanakan oleh pemerintah
desa desa Pelaksanaan Pelaksanaan dan pengawasan dan pengawasan oleh kewang oleh kewang (polisi desa) (polisi desa) Sumber : Nikijuluw (1994).
desa Pelaksanaan dan pengawasan oleh kewang (polisi desa)
Di Kawasan Desa Nolloth, Kecamatan Saparua, dikenal ada 2 sistem penyelenggaraan Sasi yaitu (1) Sasi Negeri (Sasi adat) dan (2) Sasi Gereja. Seperti yang telah tersirat pada namanya, perbedaan pokok antara 2 sistem Sasi tersebut terletak pada penyelenggara kesepakatan tradisional tersebut. Pada system Sasi Negeri, penyelenggara utamanya adalah Kewang dengan Kepala Desa, sedangkan pada Sasi Gereja pelaksanaan Sasi diorganisir oleh pendeta dan gereja. Secara alamiah, segenap peraturan yang terdapat pada sistem Sasi disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Berbeda dengan beberapa sistem tradisional di tempat lain, sistem Sasi di Desa Nolloth sudah diakomodasi pelaksanaannya oleh pemerintah formal melalui legitimasi secara tertulis dan formal oleh pemerintah desa pada tahun 1990. Dengan demikian sejak saat itu Sasi menjadi suatu pranata yang formal di ada tingkat desa. Sebagai layaknya sebuah peraturan, pada system Sasi juga diatur tentang mekanisme sangsi apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Sasi. Jika terjadi pelanggaran Sasi, maka orang yang bersangkutan akan ditangkap dan akan dijatuhi sanksi dengan cara membayar denda. Berdasarkan aturan yang dibakukan dalam bentuk tertulis, besarnya denda yang dikenakan terhadap pelanggaran Sasi disajikan secara lengkap pada Tabel 3. Tabel 3. Jenis Pengaturan Sanksi Pelanggaran Sasi Berdasarkan Jenis Pelanggaran dan Besarnya Denda Jenis Pelanggaran Besarnya Denda Buang jaring atau kegiatan lain 25.000/orang yang mengharuskan berenang dan menyelam Mengambil bia lola 7.500/buah Mengambil batu laga 25.000/buah Mengambil caping-caping 2.500/buah Mengambil tripang 1.000/ekor Mengambil akar bahar dan bunga 5.000/pohon karang Mengambil batu 5.000/m3 Mengambil pasir 7.500/m3 Mengambil krikil 10.000/m3 Menangkap ikan dengan racun 100.000 Sumber : Nikijuluw (1994). Sama dengan sistem Seke yang ada di Kabupaten Sangihe Talaud, sistem Sasi di Kabupaten Maluku Tengah ini pada dasarnya dibentuk berdasarkan kesepakatan adat dan disampaikan secara alamiah dari generasi ke generasi. Perbedaan sistem Sasi dengan sistem Seke ini adalah bahwa sistem Sasi ini kemudian dilegitimasi oleh pemerintah formal melalui
institusi desa yang membawahi praktek-praktek Sasi tersebut. Pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan sistem Sasi ini adalah bahwa masyarakat pesisir Desa Nolloth telah memiliki kesadaran betapa pentingnya kelestarian sumberdaya alam yang menjadi sumber penghidupannya. Dengan system Sasi ini, maka keseimbangan antara kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya alam dan aspek kelestarian sumberdaya alam itu sendiri dapat diwujudkan. Salah satu kelemahan yang mungkin suatu saat dapat mengancam pelaksanaan Sasi adalah adanya peraturan bahwa sistem Sasi hanya berlaku bagi masyarakat lokal dan tidak berlaku bagi masyarakat luar. Hal ini secara legal mempunyai posisi tawar menawar atau bargaining position yang lemah karena begitu ada pihak lain yang masuk ke kawasan Sasi dengan membawa legitimasi pemerintah yang lebih tinggi (misalnya tingkat Propinsi atau Pusat) maka pelaksanaan Sasi di kawasan tersebut potensial akan terganggu. Dalam konteks ini lah keterpaduan antara masyarakat lokal dengan pemerintah menjadi agenda yang sangat penting. 3. Komunitas Nelayan Rompong di Kawasan Pesisir Mandar, Sulawesi Selatan. Rompong adalah suatu tradisi penguasaan perairan pantai yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Bugis Makassar. Pemanfaatan perairan, baik sebagai sumberdaya alam maupun sebagai lahan untuk budidaya laut, semakin terasa kepentingannya. Bahkan di beberapa wilayah, seperti di perairan Selat Makassar, Teluk Bone dan Laut Flores perairan yang mengelilingi Propinsi Sulawesi Selatan sudah sejak lama berlangsung penguasaan perairan pantai untuk keperluan penangkapan ikan. Bahkan akhirakhir ini, mulai tampak penguasaan perairan pantai untuk kegiatan usaha budidaya laut. Rompong merupakan tradisi lokal masyarakat Bugis-Makassar, yang memiliki tradisi kebaharian dengan latar belakang sejarah yang dapat dijadikan rujukan apabila hendak menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai hak pemeliharaan dan penangkapan ikan. Secara fisik, Rompong diwujudkan dalam bentuk dua atau tiga batang bambu panjang yang diikat menjadi satu, kemudian pada salah satu ujungnya diikatkan batu besar pemberat, sehingga batang bambu tegak vertikal. Pada bagian tali yang menghubungkan ujung bawah bambu dengan batu pemberat diikatkan lagi daun-daun kelapa yang berfungsi sebagai tempat bermainnya ikan-ikan. Salah satu ujung bambu muncul di permukaan laut dan itulah yang dijadikan titik pusat untuk mengukur luas perairan yang akan diklaim oleh Perompong sebagai pemiliknya. Tradisi Rompong adalah suatu tradisi yang mengarah pada pemberian hak pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan di suatu kawasan yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kesepakatan adat. Dalam prakteknya, perairan di sekitar Rompong tertentu diklaim oleh nelayan pemilik Rompong sebagaimana layaknya hak milik. Konsekuensi dari klaim itu ialah di dalam radius kurang lebih satu hektar, tidak seorangpun yang boleh melakukan penangkapan ikan selain pemilik Rompong. Pengecualian terhadap larangan ini ialah penangkapan ikan dengan memakai alat tangkap pancing. Dilihat dari kacamata ekonomi, setiap perompong harus mengeluarkan modal sebesar Rp. 6.000.000 dengan rincian Rp. 1.000.000 untuk 5 unit rompong (@ Rp. 200.000) dan Rp. 5.000.000 untuk pembelian 1 unit perahu motor (tempel). Selain itu, dalam pelaksanaan sehari-hari nelayan perompong juga
membutuhkan 4 orang nelayan pembantu. Hubungan kerja antara perrompong dengan nelayan pembantu (anagguru) adalah dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan adalah 50 % dari hasil tangkapan bersih untuk nelayan perrompong dan sisanya sebesar 50 % untuk nelayan pembantu sebanyak 4 orang. Seperti yang telah dijelaskan di muka, esensi dari tradisi rompong di kawasan perairan Bugis adalah bahwa secara adat dan kebiasaan terdapat klaim penguasaan suatu kawasan perairan tertentu. Menurut Saad (1994), setiap rompong biasanya meliputi luas perairan kurang lebih 10.000 m2 yang diukur secara simetris masing- masing sepanjang 250 meter pada satu sisi (sejajar arus air) dan masing-masing sepuluh meter pada sisi lainnya. Luasan tersebut setara dengan satu hektar. Lebih lanjut Saad (1994) mengemukakan bahwa nelayan yang memiliki rompong tersebut memasang rompong secara berkelompok, dimana setiap nelayan rata-rata memiliki rompong antara lima dan enam unit (5,75 Ha). Besarnya kelompok tergantung dari lingkungan perairan yang dinilai oleh mereka memiliki potensi yang besar. Jadi, sebelum merompong, biasanya perairan tersebut diperiksa terlebih dahulu (seperti pola arus bawah dan permukaan, arah angin dan keadaan karang) dengan cara melakukan penyelaman. Tempat-tempat rompong dipasang, biasanya diberi nama seperti nama desa. Sebagai contoh, untuk kawasan yang dimiliki oleh para perrompong yang bermukim di Kelurahan Bantengnge terdiri atas enam kawasan, yaitu kawasan Sangnge, Mabelae, Rilau, Riase, Tengngae dan Lembang (Saad, 1994). Gambaran tentang penguasaan kawasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Luas Perairan yang Dikuasai oleh Para Parrompong di Kelurahan Bentengnge Luas Perairan (Ha) Frekuensi (orang) Persen (%) 1,00 3,49 8 40 3,50 5,99 1 5 > 6,00 11 55 Jumlah 20 100 Sumber : Saad (1994). Klaim penguasaan para parrompong, terutama dilatarbelakangi oleh kebiasaan yang telah berlangsung selama turun temurun. Kebiasaan tersebut biasanya berupa pewarisan rompong, penghibahan dan pengakuan masyarakat atas klaim tersebut. Berdasarkan deskripsi mengenai klaim penguasaan perairan oleh para perompong, maka dapat dirumuskan hak dan kewajibannya atas perairan pantai yang menjadi klaimnya sebagai berikut (Saad, 1994) : 1. Parrompong memiliki hak menguasai atas perairan untuk menangkap ikan dalam wilayah di sekitar rompongnya. Pengecualian terhadap monopoli ini ialah penangkapan ikan oleh nelayan lain yang menggunakan alat tangkap berupa pancing. 2. Klaim atas perairan pantai itu dapat diwariskan dan dihibahkan. 3. Terhadap romping yang tidak dimanfaatkan lagi (tidak ada kegiatan penangkapan ikan), pemilik rompong masih berhak dimintai
persetujuannya manakala ada orang yang bermaksud menangkap ikan di sekitar perairan tersebut. Sedangkan kewajiban para parrompong adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berlayar dalam wilayah yang diklaimnya. Selain itu, parrompong diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menangkap ikan apabila menggunakan alat tangkap pancing. Menurut Saad (1994), selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, tidak didapati kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh parrompong termasuk tidak ada kewajiban untuk membayar pungutan atau restribusi kepada pemerintah daerah sebagaimana lazimnya di tempat-tempat lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan. Jika terjadi pelanggaran oleh para nelayan bukan pemilik Rompong, para perompong akan menyerang para nelayan penyerobot. Bentuk penyerangan berupa pelemparan batu, kemudian perahu-perahu mereka ditenggelamkan dan jaring-jaring penangkap ikannya pun dibakar, yang semuanya dilakukan di laut. Kendati para parrompong mengklaim perairan di sekitar rompong milik mereka, tetapi secara empiris klaim tersebut belum dapat disejajarkan dengan hak milik dalam konteks Undang-Undang Pengelolaan Agraria (Saad, 1994). Selanjutnya Saad (1994) juga menegaskan bahwa hak pengelolaan rompong tersebut lebih tepat disebut dengan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Agraria (UUPA), yang kualitasnya masih berada di bawah hak milik. Dalam konteks ini, hak ulayat laut seperti rompong ini dapat ditingkatkan menjadi hukum nasional apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan asas persatuan dan kesatuan 2. Tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia 3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam UUPA dan perundang-undangan lainnya 4. Mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama. Saad (1994) juga menyatakan bahwa dalam konteks penguasaan perairan sebagai sumber daya hayati, maka klaim rompong merupakan hak milik bersama. Konsep milik bersama hanya merujuk pada hak untuk menggunakan sumberdaya, dan tidak termasuk di dalamnya hak untuk melimpahkannya. Ahli waris dari pemilik bersama memang mempunyai hak mewaris tetapi hak itu semata-mata hanya karena ia merupakan anggota dari kelompok (suku, desa, dan sebagainya). Dengan penjelasan tersebut, maka klaim penguasaan perairan oleh para parrompong, sesungguhnya tidak melanggar keempat rambu-rambu yang ditentukan oleh UUPA. 4. Panglima Laut di Aceh Provinsi Aceh (sekarang Nanggroe Aceh Darussalam) memiliki hukum adat laut yang berlaku secara turun temurun dan hingga saat ini masih dipertahankan. Hukum adat laut ini dibuat dan dirancang pada zaman Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Hukum adat laut di Nangroe Aceh Darussalam dikenal dengan istilah Panglima Laut, hal ini dikarenakan sistem tradisional tersebut di pimpin oleh seorang Panglima Laut. Tugas dari seorang Panglima Laut adalah memimpin adat, kebiasaan dan menyelesaikan persengketaan yang terjadi di bidang penangkapan ikan serta diberi tanggung jawab untuk
mempertahankan hukum adat laut agar tetap dilaksanakan sebagai pranata sosial dalam masyarakat nelayan. Pada daerah yang berlaku hukum adat laut ini, diatur secara lokal pada masing-masing wilayah kerjanya. Hukum adat laut ini mulanya tidak tertulis secara rinci dan ketentuan sanksi pada masingmasing lokasi sangat bervariasi, karena pada saat tersebut penangkapan ikan di laut masih menggunakan alat-alat yang sederhana dan tidak menggunakan mesin. Namun demikian, seiring dengan terjadinya perkembangan teknologi di bidang perikanan tangkap pada tahun 1970-an, maka keberadaan hukum adat laut pun mengalami perkembangan dan perubahan. Oleh karena itu, untuk mensikapi perkembangan yang terjadi di bidang perikanan, maka pada Bulan Januari 1972 masyarakat mengadakan musyawarah lembaga panglima laut se Kabupaten Aceh Besar. Hasil dari musyawarah ini adalah terbentuknya sebuah lembaga panglima laut kabupaten yang kemudian menjadi hukum adat laut motor boat atau motor tempel. Selain itu, hasil dari musyawarah tersebut adalah berhasil merumuskan ketentuan serta cara penangkapan ikan dengan mempergunakan alat tangkap payang, peraturan penangkapan ikan dengan motor boat dan peraturan dayung. Setelah itu, pada Bulan Desember 1978 kembali diadakan musyawarah kedua yang menghasilkan keputusan tentang perombakan dan penyempurnaan hukum adat laut yang menyangkut persidangan hukuman adat laut dalam tata cara penangkapan ikan dengan motor boat, ketertiban administrasi keuangan, serta sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelanggar ketentuan hukum adat laut. Perkembangan hukum adat laut ini semakin mendapatkan legitimasi yang kuat dari Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1990 melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan- kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya pada Bulan Januari 1992 diadakan kembali musyawarah panglima laut se Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang bertujuan untuk menyeragamkan aturan yang bersifat umum, seperti susunan organisasi dan lembaga hukum adat laut, tugas panglima laut dan lain-lain. Kekuatan hukum diperkuat lagi setelah Tahun 2000, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat (termasuk lembaga panglima laut di dalamnya) menjadi kegiatan penting dalam undang-undang ini. Namun sampai saat ini panglima laut secara formal belum merupakan hukum positif yang memiliki kekuatan hukum yang mutlak, walaupun dari panglima laut seAceh menyepakati untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hukum Adat Laut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 14, panglima laut didefinisikan sebagai orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat/areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa. Fungsi dan Tugas Panglima Laut : (1) Membantu pemerintah dalam pembangunan perikanan dan pelestarian adat istiadat dalam masyarakat nelayan.
(2) Memelihara dan mengawasi ketentuan hukum adat laut. (3) Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut. (4) Menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi antar sesama anggota nelayan atau kelompoknya. (5) Mengurus dan menyelenggarakan upacara adat laut. (6) Menjaga dan mengawasi hutan bakau dan pohon-pohon lain di tepi pantai agar jangan ditebang karena ikan akan menjauh ke tengah laut. (7) Merupakan badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah dan panglima laut. Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum adat laut diantaranya adalah (1) ketentuan tata cara penangkapan ikan dan sistem bagi hasil; (2) ketentuan tentang penyelesaian sengketa antar nelayan dalam penangkapan ikan; (3) pantangan turun ke laut; (4) ketentuan tentang adat social; serta (5) ketentuan adat tentang pemeliharaan lingkungan. (1) Ketentuan tata cara penangkapan ikan dan sistem bagi hasil Ketentuan tentang tata cara penangkapan ikan dan sistem bagi hasil diatur dalam 12 pasal. Dalam usaha penangkapan ikan di laut ada aturan tertentu yang mewajibkan agar satu perahu dengan perahu yang lainnya dapat bekerjasama dengan baik. Apabila sebuah perahu melihat segerombolan ikan maka anak buah kapal (ABK) harus mengangkat topi (tudong) atau tanda lain yang berarti bahwa gerombolan ikan tersebut sudah menjadi milik mereka, sehingga perahu lain tidak boleh memasang jaring pada gerombolan ikan tersebut. Bila perahu tersebut tetap mendekat maka hasilnya harus dibagi dua dengan pukat pertama setelah dipotong 5 % untuk perbaikan pukat. Apabila hasil yang diperoleh perahu kedua cukup banyak, maka perahu kedua harus langsung pulang dengan dikawal oleh salah seorang ABK dari perahu pertama dan hasil tangkapan tetap harus dibagi dua. Hukum adat laut tidak hanya berlaku untuk alat tangkap tradisional saja, tetapi juga berlaku bagi alat tangkap modern. Sedangkan sistem bagi hasil pada hukum adat laut dibedakan antara : (a) bagi hasil antara ABK dengan nelayan pemilik jaring; (b) bagi hasil karena perkongsian antara satu perahu dengan beberapa perahu yang mengadakan kerjasama penangkapan ikan. (2) Ketentuan tentang penyelesaian sengketa antar nelayan dalam penangkapan ikan Terjadinya sengketa antar nelayan dapat meliputi : - Dalam melakukan penangkapan ikan terjadi saling mendesak antar perahu atau memasang perahu berhimpitan; - Sengketa karena menguasai segerombolan ikan terlebih dahulu; - Sengketa karena kerusakan jaring; - Sengketa antara ABK dengan ABK dalam satu perahu atau dengan perahu lain; - Menangkap ikan dengan purse seine di daerah khusus bagi payang; - Sengketa antara purse seine dengan alat tangkap tradisional. (3) Pantangan turun ke laut Hari-hari yang termasuk pantang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut antara lain : - Setiap malam jumat (mulai kamis malam hingga jumat saat matahari tenggelam); - Hari Raya Iedul Fitri selama dua hari;
- Hari Raya Iedul Adha selama tiga hari; - Kenduri laut selama tiga hari; - Hari Proklamasi 17 Agustus selama satu hari; - Bila terjadi musibah di laut selama satu hari. Sedangkan sanksi bagi pelanggar pantang turun ke laut : - Seluruh hasil tangkapan disita; - Dilarang melaut selama 3-7 hari; - Bila dalam kurun waktu 6 bulan melakukan pelanggaran lagi, dilarang melaut selama 6-14 hari; - Bila dalam kurun waktu 6 bulan melakukan pelanggaran yang ketiga kali, maka tidak boleh melaut selama 9-21 hari; - Bila dalam kurun waktu 6 bulan masih melakukan pelanggaran lagi, maka tidak boleh beroperasi selama satu tahun dan izin penangkapannya dibatalkan. (4) Ketentuan tentang adat sosial Adat sosial dalam kehidupan nelayan adalah : - Pada saat terjadi kerusakan kapal di laut harus memberi tanda untuk meminta bantuan (SOS); - Perahu yang melihat aba-aba tersebut harus memberi bantuan; - Apabila ada perahu tenggelam di laut maka seluruh nelayan diharuskan mencarinya minimal satu hari penuh. Bagi yang menemukannya wajib membawanya ke darat. (5) Ketentuan adat tentang pemeliharaan lingkungan - Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bom, racun obat bius, aliran listrik; - Dilarang menebang atau merusak pohon kayu di pesisir pantai seperti bakau, nipah, cemara, ketapang dan lain-lain yang hidup di pantai; - Bila nelayan melihat ada pelanggaran harus melapor kepada panglima laut. 5. Awig-awig di Nusa Penida Bali Aturan pengelolaan sumberdaya perikanan pantai yang ada di Nusa Penida, Provinsi Bali disebut dengan awig-awig. Awig-awig tersebut merupakan aturan turun temurun yang tertulis dalam tulisan Kawi atau Jawa Kuno pada daun lontar, kemudian diterjemahkan ke dalam tulisan latin dengan menggunakan Bahasa Bali, pada Tahun 1982 menjadi delapan bab dan 92 pasal. Peraturan pemanfaatan dan pengelolaan pantai yang saat ini berlaku di Jungat Batu merupakan implementasi dari peraturan formal, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isi dari aturan yang menyangkut sumberdaya perikanan pantai ditetapkan oleh pemerintah desa, perangkat adat, dan tokoh-tokoh agama atau adat sebagai berikut : (1) Masyarakat Adat Desa Jungat Batu dilarang mengambil dan memanfaatkan kayu bakau untuk kepentingan apapun (2) Masyarakat Adat Desa Jungat Batu tidak diperkenankan mengambil batu karang karena dapat merusak ekosistem yang menyebabkan abrasi pantai dan merusak keindahan (3) Untuk kebutuhan pembangunan rumah tinggal, pengambilan pasir pantai dialokasikan di daerah tertentu di desa adat dengan sepengetahuan kepala adat
(4) Zonasi lahan budidaya rumput laut diatur agar tidak mengganggu alur pelayaran dan wisata bahari (5) Lahan budidaya rumput laut apabila tidak diusahakan selama tiga bulan harus dialihkan kepada orang lain Masyarakat nelayan penduduk pantai di Bali sangat mematuhi aturan yang ditetapkan, karena : (1) Masyarakat Bali merupakan masyarakat religius yang memiliki ikatan kuat terhadap agama dan adat, karena aturan yang ditetapkan agama dan adat mempunyai kekuatan hukum yang sama (2) Hukuman yang ditetapkan oleh adat mengarah pada hukuman non materi bagi masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan (3) Ada alternatif kegiatan usaha yang lebih ramah lingkungan dari pada kegiatan destruktif lainnya (4) Kesadaran akan menjaga kelestarian sudah dilakukan sejak adanya abrasi pantai yang parah diakibatkan pengambilan karang. 6. Awig-awig di Lombok Barat Masyarakat Lombok Barat telah mengenal aturan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan laut sejak Islam waktu telu. Hal tersebut tercermin dengan adanya kebiasaan adat istiadat yang disebut upacara adat sawen. Sawen adalah Bahasa Suku Sasak yang berarti tanda, isyarat atau larangan. Dengan demikian, setiap wilayah laut yang di sawen tidak boleh ditangkap sumberdaya ikan lautnya, sehingga sawen diartikan sebagai larangan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di suatu zona dalam waktu yang sudah ditetapkan melalui kesepakatan masyarakat lokal. Tujuan dilaksanakannya upacara adat sawen adalah agar ikan-ikan menjadi jinak sehingga akan tercapai hasil yang optimal. Aturan adat sawen dalam pengelolaan sumberdaya perikanan merupakan kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan tidak tertulis, namun masyarakat setempat sangat mematuhi aturan tersebut. Sementara itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan aturan-aturan lokal yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya perikanan laut diakui keberadaannya. Mengingat di era sentralistis (orde baru), masyarakat yang secara turun temurun melaksanakan hukum adat lokal merasa tidak dihargai oleh pemerintah. Adanya penguatan aturan lokal ini dipengaruhi oleh masalah pokok, yaitu konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut. Adapun konflik itu sendiri dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan (ekologi), pertambahan penduduk (demografi), lapangan pekerjaan yang makin sedikit, lingkungan politik legal, perubahan teknologi dan perubahan tingkat komersialisasi. Dengan diakuinya awig-awig sebagai aturan lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan laut telah memberikan jaminan bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, dikarenakan adanya aturan pembatasan alat tangkap, penentuan zona yang diperbolehkan dalam kegiatan penangkapan ikan, dan adanya sanksi yang tegas dan jelas serta adanya lembaga yang mampu mengakomodir aspirasi masyarakat nelayan. Wilayah yang diatur oleh awig-awig sejauh tiga mil dari garis pantai dan bersifat eksklusif, karena setiap kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya perikanan laut harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan alat tangkap yang dipergunakan adalah alat tangkap tradisional. Batasan zona tangkapan yang
diperuntukan bersifat imajiner, yaitu berdasarkan sejauh mata memandang dari pinggir pantai ke tengah laut dan masyarakat nelayan yakin jarak tersebut sejauh tiga mil dan sesuai pula dengan kemampuan armada perikanan yang digunakan nelayan tradisional. Adapun sifat kepemilikan hak dalam dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut bersifat individual, artinya setiap orang berhak untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan mempergunakan alat tangkap yang telah ditentukan sebagai hasil kesepakatan masyarakat lokal. Adapun awig-awig dari masyarakat nelayan adalah sebagai berikut : (1) Apabila ditemukan dan terbukti ada oknum yang melakukan pengeboman dan pemotasan serta penangkapan ikan dengan bahan beracun lainnya, maka oknum tersebut ditangkap oleh kelompok nelayan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib dimasing-masing wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta dibebani denda uang maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kemudian dilepas kembali. (2) Apabila oknum tersebut untuk kedua kalinya terbukti melakukan perbuatan ini lagi, maka kelompok nelayan akan bersama-sama menangkap oknum tersebut kemudian dilakukan pengrusakan atau pembakaran terhadap alat serta sarana dukung yang dipergunakan dalam kegiatannya. (3) Apabila setelah dikenakan sanksi pada point pertama dan kedua tersebut diatas, oknum tersebut masih melakukan kegiatannya dan terbukti, maka kelompok nelayan akan menghakiminya dengan pemukulan massal tidak sampai mati. Sedangkan lembaga yang disepakati oleh masyarakat untuk menyelenggarakan awig- awig dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut di Lombok Barat bagian Utara adalah Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) sesuai dengan Surat Nomor 06/LMNLU/V/2000 dengan susunan pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yaitu kemanan laut, kebersihan pantai, kesejahteraan sosial, serta konservasi dan rehabilitasi. 7. Awig-awig di Lombok Timur Di Kabupaten Lombok Timur juga dikenal awig-awig dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut berdasarkan hukum adat Lembaga Masyarakat Desa (LMD) Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur pada Tanggal 14 November 1994 telah mengeluarkan peraturan adat secara tertulis yang dituangkan dalam Keputusan Desa Nomor : 04/LMD/1994, peraturan tersebut mengatur tentang : (1) Batas dan jalur penangkapan ikan di Perairan Tanjung Luar (2) Sanksi terhadap pelanggaran batas dan jalur penangkapan ikan di Perairan Tanjung Luar Dasar pertimbangan dikeluarkan keputusan desa tersebut adalah : (1) Demi keamanan, ketertiban dan kenyamanan para nelayan dalam menangkap ikan di Perairan Tanjung Luar (2) Sering terjadi pertikaian dan perkelahian di laut antara sesama nelayan tradisional, akibat kurang jelasnya pembatasan jalur antara nelayan yang setingkat lebih modern. Keputusan desa tersebut dikenal dengan nama Awig-awig Pengaturan Jalurjalur Penangkapan Ikan bagi Nelayan atau Awig-awig Jalur Laut. adapun keputusan ini mengatur tentang adanya 4 (empat) jalur penangkapan ikan
bagi para nelayan tradisional yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Penentuan jalur tersebut meliputi : (1) Jalur penangkapan I adalah perairan selebar 3 mil laut ( 4,8 km) dari batas air titik terendah pada waktu air surut (surut terjauh) yang diperuntukan bagi nelayan tradisional. Ditentukan pula selama mereka tidak mengganggu nelayan setingkat lebih modern, mereka diperkenankan menangkap ikan pada jalur II. (2) Jalur penangkapan II adalah perairan selebar 3-6 mil laut ( 9,6 km) yang diperuntukan bagi nelayan setingkat lebih modern yang menggunakan alat tangkap purse seine, purse seine mini atau perahu bermesin dalam dengan sasaran apung (in board). Mereka tidak diperkenankan menangkap ikan dengan peralatan modern pada jalur I. Ditentukan selama mereka tidak mengganggu nelayan dengan peralatan setingkat lebih modern, mereka diperkenankan beroperasi pada jalur III. (3) Jalur penangkapan III adalah perairan selebar 6-12 mil laut ( 19 km) yang ditentukan untuk nelayan yang menggunakan gillnet selama mereka tidak mengganggu nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dipergunakan pada jalur IV, mereka tidak diperkenankan menangkap ikan pada jalur tradisional. (4) Jalur penangkapan IV adalah perairan selebar 12 mil sampai ke ZEE. Jalur ini diperuntukan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap long line apung. Pada keputusan desa tersebut ditentukan pula bahwa nelayan tradisional diperkenankan untuk menangkap ikan pada jalur II, III dan IV sampai ke ZEE selama mereka tidak mengganggu dan bisa dijangkau dengan alat tangkapnya tersebut. Pada keputusan Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur tentang Sanksi Pelanggaran Batas dan Jalur Penangkapan Ikan di Perairan Tanjung Luar ditentukan bahwa Bagi nelayan setingkat lebih modern yang menggunakan purse seine semi dan purse seine mini yang sengaja melakukan kegiatan penangkapan ikan pada jalur I akan dikenakan sanksi berupa : (1) Semua hasil tangkapan diambil oleh pemerintah desa untuk kebutuhan pembangunan desa tersebut. (2) Bagi nelayan setingkat lebih modern yang melakukan pelanggaran pada kegiatan penangkapan ikan 3 (tiga) kali berturut-turut, maka semua hasil tangkapannya diambil oleh pemerintah desa dan hasilnya akan dipergunakan desa tersebut, serta alat tangkap akan disita dan selanjutnya diajukan kepada pihak yang berwenang untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan awig-awig yang ini berlaku di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur pada dasarnya adalah suatu implementasi dari peraturan formal yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/KPTS/UM/1976 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan. Pemerintah dan pemuka adat desa menganggap bahwa apa yang dikemukakan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 607/KPTS/UM/1976 cukup sulit untuk diterapkan secara lokal. Menyadari hal tersebut maka keputusan Menteri Pertanian itu diterjemahkan secara parsial dalam aturan-aturan setempat yang bersifat lokal yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan sumberdaya alam sehingga mudah-mudahan dapat dimengerti, diimplementasikan dan diawasi di lapangan. Keputusan desa tentang awig-awig jalur laut yang dibuat berdasarkan hasil musyawarah Lembaga Masyarakat Desa
dihadiri oleh Pimpinan Resort Perikanan Kecamatan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Bidang Pembangunan, dan Ketua Bidang Keuangan, LKMD, Tokoh Nelayan, nelayan tradisional, dan nelayan setingkat modern. Keputusan desa ini disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Lombok Timur pada tanggal 8 Agustus 1995. Dalam rangka meningkatkan peranan masyarakat desa pantai untuk melakukan perlindungan kawasan laut dan mempertahankan serta meningkatkan produksi ikan melalui Gerbang Masa Depan (Gerakan Pembangunan Masyarakat Desa Pantai), maka Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Timur telah membuat pembagian areal dengan berbagai sanksinya, yaitu : sanksi inti, sanksi pemanfaatan dan sanksi penyangga. Pelaksanaan dari kegiatan ini sudah dimulai pada tahun 1998 dan pelaksanaannya dimulai tahun 2001. Adapun alat pendukung dari Gerbang Masa Depan di Desa Benteng, Kabupaten Lombok Timur terdiri dari Kepala Dinas Perikanan, PPS, tokoh masyarakat dan lain- lain sebanyak 80 orang. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah : (1) Terciptanya kondisi yang baik antar stakeholders atas perhatian mereka terhadap daerah perlindungan ditaati secara bersama-sama. (2) Terealisasinya konsep kelestarian lingkungan hidup yang menjadi harapan semua pihak. (3) Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat desa pantai agar dapat hidup layak dan sejahtera. 8. Sistem Tradisional Punggawa-Sawi di Sulawesi Selatan Sumberdaya yang menjadi perhatian utama masyarakat Sulawesi Selatan adalah wilayah laut. Hal ini dikarenakan doktrin atau asumsi lokal masyarakatnya yang menganggap bahwa laut sudah menjadi bagian dari hidup mereka, sehingga ini tidak dapat dipisahkan. Sistem tradisional punggawa-sawi telah dikenal di Sulawesi Selatan dalam memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya perikanan laut. Punggawa (patron) adalah orang yang selalu menyediakan bantuan sosial termasuk modal kepada sawinya, sedangkan sawi (klien) adalah orang yang bekerja pada punggawa tersebut. Menurut kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan, jika seseorang memberikan bantuan kepada orang lain, maka akan sangat sulit bagi orang yang menerima bantuan tersebut untuk menentang orang yang telah memberikan bantuan kepadanya. Mekanisme yang di terapkan dari sistem punggawa-sawi adalah pola bagi hasil. Sawi akan menggantungkan hidupnya pada punggawa, selama punggawa tersebut memberikan jaminan sosial melalui pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga sawi. Selain itu, norma hubungan sosial ini bukan hanya untuk sawi sendiri, melainkan juga diperuntukan para ponggawa agar dapat meningkatkan kesejahteraan para sawi. Tingkat kesejahteraan ini menjadi tolak ukur efektivitas hubungan norma sosial dan seberapa jauh suatu etnis dapat menjamin sumber hidup anggotanya dibandingkan dengan etnis lainnya. Hubungan antara ponggawa dan sawi tidak bersifat kaku, melainkan lebih bersifat fleksibel. Hal ini dicerminkan dengan sikap ponggawa yang bisa kapan saja memutuskan hubungan dengan pihak sawi, apabila sawi dianggap tidak lagi mematuhi dan menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati. Akan tetapi, sawi pun bisa meninggalkan ponggawa, jika
ponggawa tersebut tidak lagi mampu memberikan jaminan sosial terhadap kelangsungan hidup keluarga sawi. Umumnya ponggawa melakukan dua cara untuk mendapatkan sawi, yaitu : Pertama, transfer fungsi kerja. Cara ini terjadi apabila sawi mengalami musibah, sehingga tidak lagi mampu berperan sebagai buruh, maka orang tua akan melakukan trasfer fungsi kerjanya kepada anak-anaknya. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan membentuk hubungan patron-client baru dalam lingkungan etnisnya sendiri; dan ini terutama terjadi pada saat pertama kali ponggawa membentuk usaha baru. Sementara itu, dalam perkembangannya, sistem tradisional ponggawa-sawi ini berada dalam ketidakjelasan status kerangka kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan laut, sehingga eksistensi dari sistem ini semakin lama semakin melemah. Sebagai contoh, tidak dikenalinya sistem ini dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut pada UU No. 9 tahun 1985 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. No.5/75. Dari kedua undangundang tersebut tidak satu kata pun menyebutkan bahwa sistem tradisional ini adalah bagian dari institusi perikanan tradisional. Namun demikian, perubahan konstelasi politik Pemerintah Indonesia pada tahun 1998 telah merombak sistem pengelolaan yang sentralistis menjadi terdesentralisasi. Adanya perubahan tersebut telah memunculkan peluang keterlibatan masyarakat lokal untuk memberdayakan sistem tradisionalnya, termasuk ponggawa-sawi dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya perikanan laut. Walaupun sistem ponggawa-sawi tidak langsung berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan laut, akan tapi pelaksanaan sistem tradisional ini juga memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya. Hal ini tercermin dari adanya mekanisme selektivitas ponggawa dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan. Namun demikian, dengan adanya ketidakpastian status hukum, akan menyulitkan ponggawa-sawi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut. Kalau masalah ini diabaikan, maka masyarakat nelayan (users) dapat meningkatkan tekanan eksploitasi terhadap sumberdaya yang ada, ditambah dengan lemahnya aparat pemerintah dalam melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian serta penegakkan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga degradasi lingkungan dan over fisnhing akan mungkin sangat terjadi. Oleh karena itu, adanya pelibatan system ponggawa-sawi dalam aspek pengelolaan sumberdaya lokal, paling tidak ponggawa mempunyai kewajiban moral untuk melestarikan sumberdaya perikanan di daerahnya. Hal ini tidak saja bermanfaat pada keberlanjutan pelaksanaan sistem tradisional ponggawasawi, tetapi juga bermanfaat bagi keseluruhan masyarakat lokal. 9. Hak Ulayat Laut di Endokisi Kabupaten Jayapura Endokisi adalah sebuah desa pantai yang berada di Teluk Tanah Merah, yang secara administratif masuk wilayah Kecamatan Demta, Kabupaten Jayapura. Desa yang luasnya 774 km2 ini pada tahun 1992 dihuni oleh 309 orang dan 100% beragama Kristen Protestan. Desa ini bari dibentuk tahun 1991 dan merupakan pecahan dari Desa Senamay dan merupakan salah satu kampung (RW) yang dikenal dengan nama Kantumilena Kampung Endokisi (Kantumelana), dahulunya dipegang oleh dua koramo, yaitu Koramo Bowa dan Koramo Kantumilena.
Mata pencaharian penduduk Endokisi pada mulanya sebagai petani tetapi kemudian banyak yang beralih menjadi nelayan. Kepemimpinan di Desa Endokisi bertumpu pada tiga tungkai yaitu pemerintah, pemimpin tradisional dan gereja yang menyatu dalam dewan adat dan dibentuk tahun tahun 1986. Tugas Dewan Adat adalah menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan masalah adat. Wilayah perairan di Endokisi digolongkan menjadi dua, yaitu perairan dangkal (kedalaman 100 meter) dan periran dalam. Wilayah perairan ini dimiliki oleh empat suku, batas wilayah antara suku ditentukan oleh batu karang di tengah laut dan oleh tanjung di tepi laut serta tanda-tanda alam yang lain. Walaupun ada batas-batas wilayah hak ulayat laut yang dimiliki oleh sukusuku dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan mempergunakan panah, jaring dan tombak, namun orang di luar suku pemilik wilayah laut boleh menangkap ikan secara bebas. Dengan dikenalnya alat tangkap jaring dan sero apung yang dapat mengeksploitasi sumberdaya secara lebih besar, menimbulkan kesadaran para pemegang hak ulayat laut untuk memberlakukan aturan yang mengharuskan pemilik sero atau jaring yang akan mengoperasikan alat tangkapnya di wilayah suku lain untuk meminta izin kepada kepala suku yang bersangkutan melalui Dewan Adat. Keputusan Dewan Adat itulah yang merupakan sumber legalitas dari pelaksanaan hak ulayat laut disamping legenda tentang sejarah desa sebagai sumber legalitas pemilikan wilayah laut. Perubahan teknologi dalam kegiatan penangkapan ikan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hak ulayat laut, hal tersebut disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kelangsungan sumberdaya di wilayah pemilik hak ulayat laut terutama terhadap tingkat eksploitasi sero dan jaring yang dianggap lebih tinggi. Mengenai permohonan dan pemberian izin tidak dilakukan dalam bentuk tertulis dan tidak didasarkan pada perhitungan materi, hanya pemilik alat kerjanya akan menyerahkan sebagain uang dari hasil penjualan ikan kepada Dewan Adat. Sanksi oleh Dewan Adat hanya diberikan kepada para nelayan yang mengoperasikan jaring atau sero apung atau alat tangkap lain yang dianggap memiliki tingkat eksploitasi yang tinggi. Di Desa Endokisi dikenal empat tingkatan sanksi, yaitu (1) teguran, (2) tobu (disuruh mencari kelapa), (3) disuruh menangkap babi, dan (4) Hukuman mati. Hukuman tersebut sejak masuknya Injil tidak diberlakukan lagi. Pada saat ini sanksi terhadap pelanggaran hak ulayat laut hanya berupa denda saja. E. STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT PANTAI Struktur sosial dalam masyarakat nelayan umumnya dicirikan dengan kuatnya ikatan patron-klien. Kuatnya ikatan patron-klien tersebut merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Bagi nelayan menjalin ikatan dengan patron-klien merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan kegiatannya karena patronklien merupakan institusi jaminan sosial ekonomi. Hal ini terjadi karena hingga saat ini nelayan belum menemukan alternatif intuisi yang mampu menjamin kepentingan sosial ekonomi mereka. Hubungan patron-klien merupakan pertalian antara dua orang atau lebih, yakni seorang individu dari status golongan ekonomi tinggi (patron) dengan dan sumberdayanya memberikan perlindungan, keuntungan atau keduanya kepada individu dari status ekonomi yang lebih rendah (klien). Sebagai timbal baliknya,
individual dari status yang lebih rendah memberikan pelayanan menyeluruh termasuk pelayanan individu serta dukungan untuk kepentingan ekonomi maupun politis (Scott, 1985) dalam Adiwibowo, S (2001). Mengenai hubungan patron-klien ini, Legg (1983), dalam Najib (1990), mengungkapkan bahwa tata hubungan patron-klien umumnya berkaitan dengan : Hubungan antar pelaku yang menguasai sumberdaya yang tidak sama, Hubungan yang bersifat khusus yang merupakan hubungan pribadi dan mengandung keakraban, Hubungan yang didasarkan pada asas saling menguntungkan Sementara itu, Scott (1993) dalam Satria (2002), melihat hubungan patronklien sebagai fenomena yang terbentuk atas dasar ketidaksamaan dan sifat fleksibilitas yang tersebar sebagai sebuah sistem pertukaran pribadi. Dalam pertukaran itu, berarti ada arus dari patron-klien dan sebaliknya. Arus dari patronklien meliputi : a. penghidupan subsisten dasar, berupa pemberian pekerjaan tetap, penyediaan saprodi, jasa pemasaran, dan bantuan teknis, b. jaminan krisis subsisten berupa pinjaman yang diberikan pada saat klien menghadapi kesulitan ekonomi, c. perlindungan terhadap klien dari ancaman pribadi (musuh pribadi) maupun ancaman umum, d. memberikan jasa kolektif berupa bantuan untuk mendukung sarana umum setempat (sekolah, tempat ibadah, atau jalan) serta mendukung festifal serta perayaan desa. Lebih lanjut menurut Scott (1993) dalam Satria (2002), arus dari klien ke patron sulit dikategorisasi karena klien adalah milik patron yang menyediakan tenaga dan keahliannya untuk kepentingan patron apapun bentuknya, seperti jasa pekerjaan dasar, jasa tambahan bagi rumah tangga patron, jasa domestik pribadi. Selain itu, klien merupakan anggota setia dari faksi lokal tersebut. Berdasarkan tata hubungan tadi, jelaslah bahwa hubungan antar nelayan dengan patron yang menguasai sumberdaya tidak sama. Artinya, patron menguasai sumberdaya modal jauh lebih besar daripada nelayan. Dengan ketidaksamaan penguasaan sumberdaya itu, terjalinlah ikatan patron-klien. Masyhuri (1999) menggambarkan bahwa pada saat hasil tangkapan kurang baik, nelayan kekurangan uang. Pada akhirnya, ia melepas barang-barang yang mudah dijual dengan harga lebih murah kepada patron. Seringkali peran penjualan dilakukan isteri-isteri nelayan melalui mekanisme pegadaian sehingga mereka menjadi sering berhubungan dengan institusi pegadaian (Juwono, 1998). Selanjutnya, nelayan akan mencari hutang kepada patron dengan jaminan ikatan pekerjaan atau hasil tangkapan yang hanya akan dijual kepada patron dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Dengan pola patron-klien seperti ini, klien sering dihadapkan pada sejumlah masalah seperti pelunasan kredit yang tidak pernah berakhir. Hubungan patron-klien pada masyarakat pesisir dan lautan merupakan sistem sosial yang telah berakar pada masyarakat dan sulit untuk diubah dan hubungan tersebut cenderung menguntungkan pihak patron. Namun demikian pola patronklien terus terjadi dalam komunitas masyarakat nelayan karena memang belum ada institusi formal yang mampu berperan sebagai patron. Institusi tersebut belum berjalan secara efektif karena ada kesenjangan kultur intuisi yang dibangun secara formal dengan kultur nelayan yang masih menekankan aspek personalitas. Di sisi
lain, nelayan sendiri belum mampu membangun institusi baru secara mandiri. Meski diakui bahwa para nelayan itu memiliki etos kerja dan mobilitas tinggi serta solidaritas sesama yang kuat, tetap saja mereka masih memiliki sejumlah kelemahan, khususnya kemampuan dalam mengorganisasi diri untuk kepentingan ekonomi maupun profesi. F. DETERMINAN SISTEM SOSIAL MASYARAKAT PANTAI Darmawan Salman (2012) mengungkapkan bahwa Desa pantai dan pesisir terkonstruksi dalam siklus musim yang berimplikasi pada keterputusanketerputusan dalam ritme penghidupan. Pada komunitas nelayan tangkap di seantero Nusantara, jadwal melaut ada yang harian dan ada yang mingguan sesuai jenis teknologi tangkap yang digunakan. Pada komunitas penangkap ikan terbang di Takalar (Sulawesi Selatan) atau penyelam teripang di Sinjai (Sulawesi Selatan), mereka meninggalkan desa berhitung bulan. Pada komunitas pelayar di Bulukumba (Sulawesi Selatan) pada 1950-1970an mereka berlayar dalam siklus musim. (Salman, 2006:Rizal, 1979). Ini mengkondisikan adanya hari, munggu, bulan dan musim sepi dan ramai secara bergantian pada desa pantai dan pesisir. Ritme penghidupan yang demikian menciptakan keterputusan-keterputusan dalam gerak perubahan termasuk dalam bersentuhan dengan kebijakan Negara dan mekanisme pasar (Lihat juga, Pollnack, 1988). Siklus musim mengkondisikan pula keterputusanketerputusan dalam sumber penghidupan dan ekonomi rumah tangga sehingga saling ketergantungan dan pertukaran di antara mereka menjadi keniscayaan. Horizon laut yang tak terbatas melahirkan cara pandang yang berbeda dengan masyarakat desa pertanian/persawahan. Jika pada masyarakat pertanian pandangannya terkonstruksi dengan pola yang teratur karena determinasi lingkungan persawahan dengan sekat-sekat pematang mempengaruhi cara pandang yang tersekat-sekat sehingga ikatan sosialnya cenderung lemah, sedangkan pada masyarakat desa pantai menganggap bahwa laut itu adalah horizon yang luas tanpa sekat sehingga kesendirian di laut lepas melahirkan keberanian menghadapi tantangan dan karennya pula sehingga melahirkan keeratan dan solidaritas ikatan kelompok yang kuat. Di sisi lain, pandangan masyarakat desa pantai cenderung melihat laut sebagai sumberdaya yang boleh dimanfaatkan bersama (common proverty) tanpa ada yang harus merasa berhak untuk memilikinya. Pandangan ini tentunya melahirkan semangat eksploitatif di tengah tuntutan hidup yang semakin banyak. Semangat eksploitatif ini kemudian berefek pada ketimpangan sosial sehingga semakin membuka ruang konflik kepemilikan dan pengggunaan alat, dalam arti bahwa nelayan besar dan nelayan kecil berada pada pusara konflik sumberdaya dengan kondisi lingkungan yang semakin hari semakin terdegradasi. Dalam situasi seperti ini tentunya diharuskan adanya regulasi yang ketat serta pengawasannya tentang penggunaan alat tangkap dan fishing ground. Ritme produktivitas masyarakat desa pantai atau masyarakat nelayan yang sangat dipengaruhi oleh factor musim dimana karena determinasi pola produksinya yang menyebabkan ruang interaksi dan komunikasinya dengan komunitas masyarakat lainnya semakin sempit dan terbatas sehingga mengkondisikan entitas masyarakat ini menjadi masyarakat yang eksklusif. Karena sempitnya ruang interaksi dengan masyarakat di darat sehingga tidak jarang komunitas ini tidak diprioritaskan untuk mendapatkan pelayanan dan akses kebijakan. Pada akhirnya kita menemukan komunitas desa pantai yang dari tahun-ketahun tidak mengalami kemajuan yang signifikan.
Ritme produktivitas yang dipengaruhi factor musim juga mengkondisikan maraknya perilaku menyimpang bagi sebagian besar masyarakat desa pantai. Masyarakat desa pantai yang memiliki pola produksi seminggu di laut dan sehari di darat sebagian memiliki perilaku menyimpang dimana kebiasaan setiap minggu sehabis melaut menghabiskan uang dengan hura-hura. G. FORMASI SOSIAL MASYARAKAT PANTAI Formasi sosial menurut Darmawan Salman (2012) adalah Bentuk konfigurasi sosial yang dihasilkan oleh konstruksi tata produksi dan hubungan sosial produksi. Pada konteks masyarakat desa pantai khususnya masyarakat nelayan terdapat tiga bentuk formasi sosial, yaitu Formasi sosial Subsisten, Formasi sosial Komersial/Semi Kapitalis dan Formasi sosial Kapitalis. Pada masyarakat nelayan dengan formasi sosial subsisten memiliki ciri tata produksi dengan teknologi sederhana dan orientasi produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ciri tata produksi seperti ini biasanya banyak terdapat pada masyarakat nelayan kecil dimana hubungan sosial produksi diwarnai oleh ikatan keluarga dan kekerabatan dalam lingkup terbatas dan masih terdapat solidaritas berbasis kolektivitas kekerabatan dalam menanggulangi krisis subsistensi pada tingkat komunitas. Masyarakat desa pantai dengan formasi sosial komersil/semi kapitalis memiliki ciri tata produksi dengan teknologi yang lebih maju dibandingkan dengan masyarakat desa pantai dengan formasi sosial subsisten. Masyarakat desa pantai dengan formasi sosial komersil/semi kapitalis sudah berkemampuan menghasilkan surplus produksi berpasangan dgn orientasi produksi untuk diperdagangkan dalam mekanisme pasar. Kemampuan untuk menghasilkan surplus produksi dibangun sistem penggunaan teknologi (Kapal, mesin, alat tangkap) dengan kapasitas yang besar pula dengan jumlah tenaga kerja yang banyak. Biasanya, pada formasi sosial ini sering juga ditemukan hubungan produksi yang diwarnai oleh ikatan patron-klien yg basisnya adalah kombinasi antara kemampuan kerja dan ikatan kekerabatan. Meski tidak dalam konteks produktivitas, dalam proses sosialnya, ditemukan solidaritas vertikal antara patron dgn klien dalam mengatasi krisis subsistensi pada tingkat komunitas. Misalnya pada konteks masyarakat nelayan Bugis-Makassar yang hubungan produksinya ditemukan struktur Punggawa-Sawi dimana Punggawa sering diartikan sebagai Patron dan Sawi sebagai Klien, ketika pada musim paceklik dimana tidak ditemukan proses produksi penangkapan ikan sering saja ditemukan Sawi meminjam modal kepada Punggawa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehariharinya. Lain halnya dengan masyarakat desa pantai yang Formasi sosialnya berciri kapitalis dimana tata produksinya dibangun dengan teknologi canggih dan padat modal dibarengi dgn orientasi produksi pada pencapaian laba maksimum. Pencapaian laba maksimum ditujukan untuk investasi penambahan input kapasitas faktor produksi (mesin, kapal, alat tangkap dan tenaga kerja). Hubungan sosial produksi diwarnai oleh relasi majikan-pekerja dalam prinsip pemberian upah/sewamenyewa secara rasional-kalkulatif. Jika pekerjanya tidak bekerja maka tidak akan mendapatkan upah. Berlaku prinsip individualisme dalam mengatasi krisis subsistensi masing-masing berdasarkan nilai upah dari kerja yg dijalankan, dalam artian bahwa majikan tidak harus bertanggung jawab mengatasi krisis subsistensi jika pekerjanya mengalami kesulitan modal meskipun itu terjadi pada musim paceklik. H. IKATAN PATRON-KLIEN PADA MASYARAKAT PANTAI
Istilah patron dan klien berasal dari suatu model hubungan sosial yang berlangsung pada zaman Romawi kuno. Seorang patronus adalah bangsawan yang memiliki sejumlah warga dari tingkat lebih rendah, yang disebut clients, yang berada di bawah perlindungannya. Meski para clients secara hukum adalah orang bebas, mereka tidak sepenuhnya merdeka. Mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga pelindung mereka, yang nama keluarganya mereka gunakan dan upacara pemujaan keluarganya mereka ikuti. Ikatan antara patron dibangun berdasarkan hak dan kewajiban timbal balik yang biasanya bersifat turun temurun (Pelras, 2009). Menurut Burke (2003), patronase dapat didefinisikan sebagai sistem politik yang berlandaskan pada hubungan pribadi antara pihak-pihak yang tidak setara, antara pemimpin (patron) dan pengikutnya (klien). Masing-masing pihak mempunyai sesuatu untuk ditawarkan. Klien menawarkan dukungan politik dan penghormatan kepada patron, yang ditampilkan dalam berbagai bentuk simbolis (sikap kepatuhan, bahasa yang hormat, hadiah, dan lain-lain). Di sisi lain, patron menawarkan kebaikan, pekerjaan, dan perlindungan kepada kliennya. Ketika hubungan patronase terutama digunakan kepada hubungan ekonomi seperti pertanian, pertambakan, penangkapan ikan, perdagangan laut, dan kerajinan, maka istilah yang digunakan di Sulawesi Selatan adalah punggawa untuk patron dan sawi untuk klien. Kata punggawa disamakan dengan pemimpin atau bos. Istilah itu digunakan untuk menggambarkan hubungan dalam ruang lingkup yang luas antara atasan dengan bawahan yang disertai adanya ikatan pribadi. Istilah sawi adalah pelengkap punggawa, yang bisa ditafsirkan sebagai bawahan atau orang yang memiliki hubungan pribadi dengan atasan. Justru karena adanya hubungan pribadi, maka punggawa kerap merujuk kepada sawi mereka sebagai anaq-anaq (anak), anaq guru (murid atau pengikut) atau tau (orang) (Pelras, 2009). Secara singkat dapat dikemukakan pola-pola relasi patron-klien dalam kaitannya dengan teori stratifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Legg (1983) bahwa pada dasarnya hubungan patron-klien berkenaan dengan: (a) hubungan di antara para pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai sumber daya yang tidak sama, (b) hubungan yang bersifat khusus (particularistic), hubungan pribadi dan sedikit banyak mengandung kemesraan (affectivity), (c) hubungan yang berdasarkan asas saling menguntungkan dan saling memberi dan menerima. Sementara menurut Scott (1993) bahwa sumber daya yang dipertukarkan dalam hubungan patron-klien mencerminkan kebutuhan yang timbul dari masing-masing pihak. Kategori-kategori pertukaran dari patron ke klien mencakup pemberian: bantuan penghidupan subsistensi dasar, jaminan krisis subsistensi,perlindungan dari ancaman luar terhadap klien, dan memberikan sumbangan untukkepentingan umum. Sebaliknya, arus barang dan jasa dari klien ke patron pada umumnya dengan menyediakan tenaga dan keahliannya untuk kepentingan patron, apa pun bentuknya. Patron-klien merupakan sebuah pranata yang lahir dari adanya saling percaya antara beberapa golongan komunitas nelayan, yaitu pertama golongan pemilik kapal (modal ekonomi) yang di Sumatera Utara dikenal dengan sebutan toke yang berperan sebagai patron. Kedua, yaitu golongan komunitas nelayan yang tidak memiliki modal ekonomi tetapi memiliki modal lain diantaranya keahlian dan tenaga. Golongan yang memiliki modal keahlian dan tenaga ini biasanya dikenal dengan sebutan buruh yang berperan sebagai klien. Adanya saling percaya diantara beberapa golongan komunitas nelayan tersebut membuat mereka mampu membentuk jaringan sosial (Nasution, dkk., 2005).
Menurut Kusnadi, 2000, unsur-unsur sosial yang berpotensi sebagai patron adalah pedagang (ikan) berskala besar dan kaya, nelayan pemilik (perahu) (orenga, Madura), juru mudi (juragan laut atau pemimpin awak perahu), dan orang kaya lainnya. Mereka yang berpotensi menjadi klien adalah nelayan buruh (pandhiga, Madura) dan warga pesisir yang kurang mampu sumber dayanya. Secara intensif, relasi patron-klien ini terjadi di dalam aktivitas pranata ekonomi dan kehidupan sosial di kampung. Para patron ini memiliki status dan peranan sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat nelayan Kompleksitas relasi sosial patron-klien (vertikal) dan relasi sosial horisontal di antara mereka merupakan urat-urat struktur sosial masyarakat nelayan. Hubungan patron-klien sebagaimana dimaksud senantiasa menjadi fenomena perdebatan antara hubungan yang bersifat eksploitasi dan hubungan bersifat resiprositas. Eksploitasi menurut Scott (1981:239) adalah bahwa ada sementara individu, kelompok atau kelas yang secara tidak adil atau secara tidak wajar menarik keuntungan dari kerja, atau atas keinginan orang lain. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam pengertian ini ada dua cara eksploitasi yaitu pertama, harus dilihat sebagai satu tata hubungan antara perorangan, kelompok atau lembaga; adanya pihak yang dieksploitasi, mengimplikasikan adanya pihak yang mengeksploitasi. Kedua, merupakan distribusi tidak wajar dari usaha dan hasilnya. Sedangkan resiprositas menurut Scott (1981) mengandung prinsip bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidak-tidaknya jangan merugikannya. Artinya bahwa satu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan, bagi si penerima, satu kewajiban timbal balik untuk membalas dengan hadiah atau jasa dengan nilai yang setidak-tidaknya sebanding dikemudian hari. Dalam kaitan ini Malinowski dan Mauss, menemukan bahwa resiprositas berfungsi sebagai landasan bagi struktur persahabatan dan persekutuan dalam masyarakatmasyarakat tradisional (Scott, 1981). Dalam pandangan ekonomi resiprositas menunjuk pada bentuk pertukaran yang ditanamkan secara sosial dalam masyarakat simetris yang berskala kecil (Hettne, 2001). Dalam penelitian Purnamasari, dkk (2002) menunjukkan bahwa pertukaran sosial ponggawa-petambak penyakap merupakan bentuk pertukaran yang paling rentan sifat eksploitasi. Ponggawa dengan asset produksi yang dimilikinya berada di posisi yang berpotensi mengeksploitasi, sedangkan petambak penyakap berpotensi untuk di eksploitasi karena posisinya lemah dengan aset produksi terbatas. Namun, selama kehidupan ekonomi dan subsistensi petambak penyakap belum terancam dan masih diperhatikan oleh ponggawanya, eksploitasi yang terjadi belum dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan, melainkan masih dimaknai bersifat resiprositas (timbal-balik). Hal ini karena hubungan ponggawa-petambak telah tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat petambak, dan belum tergantikan dalam kelembagaan formal bentukan pemerintah, di samping hubungan ponggawapetambak tetap menjadi pilihan karena selain sesuai kebutuhan, prosesnya cepat (berlangsung setiap saat dan tanpa batas waktu). Pada umumnya, relasi patron-klien terjadi secara intensif pada suatu masyarakat yang menghadapi persoalan sosial dan kelangkaan sumber daya ekonomi yang kompleks. Di daerah pedesaan dan pinggiran kota yang berbasis pertanian, seorang patron (bapak buah) akan membantu klien (anak buah) kemudahan akses pada peluang kerja di sekor pertanian, mengatasi kebutuhan mendadak klien, atau meringankan beban utang klien pada pelepas uang. Klien menerima kebaikan tersebut sebagai hutang budi, menghargai, dan berkomitmen untuk membantu patron dengan sumberdaya jasa tenaga yang mereka miliki. Pola-
pola relasi sosial yang demikian dapat dilihat pada hubungan antara pemilik lahan pertanian luas (petani kaya) dengan para buruh taninya dan orang-orang di sekitarnya yang kemampuan ekonominya terbatas (Eisenstadt dan Roniger, 1984). Prinsip-prinsip relasi patron-klien berlaku juga pada masyarakat nelayan. Unsurunsur sosial yang berpotensi sebagai patron adalah pedagang (ikan) berskala besar dan kaya, nelayan pemilik (perahu) (orenga, Madura), juru mudi (juragan laut atau pemimpin awak perahu), dan orang kaya lainnya. Mereka yang berpotensi menjadi klien adalah nelayan buruh (pandhiga, Madura) dan warga pesisir yang kurang mampu sumber dayanya. Secara intensif, relasi patron-klien ini terjadi di dalam aktivitas pranata ekonomi dan kehidupan sosial di kampung. Para patron ini memiliki status dan peranan sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat nelayan (Kusnadi, 2000). Kompleksitas relasi sosial patron-klien (vertikal) dan relasi sosial horisontal di antara mereka merupakan urat-urat struktur sosial masyarakat nelayan. Dalam aktivitas ekonomi perikanan tangkap di kalangan nelayan Madura misalnya, terdapat tiga pihak yang berperan besar, yaitu pedagang perantara (pangamba), nelayan pemilik perahu, dan nelayan buruh (Kusnadi, 2000). Ketiga pihak terikat oleh hubungan kerja sama ekonomi yang erat. Pedagang perantara menyediakan bantuan dan pinjaman (uang) ikatan untuk nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan pemilik menyediakan bantuan dan pinjaman ikatan kepada nelayan buruh. Hubungan kerja sama ekonomi di antara mereka diikat oleh relasi patron-klien. Relasi sosial ekonomi bebasis patron-klien ini berlangsung intensif dan dalam jangka panjang. Relasi sosial ekonomi akan berakhir jika terjadi persoalan yang tidak bisa diatasi di antara mereka, sehingga pihak nelayan pemilik dan nelayan buruh harus melunasi utang-utangnya kepada pedagang perantara. Sedemikian dalamnya relasi patron-klien mendasari aktivitas ekonomi nelayan, sehingga ada peneliti yang menyebut organisasi ekonomi nelayan sebagai organisasi ekonomi patron-klien (Elfindri. 2002). Selain di sektor ekonomi, relasi-relasi patron-klien juga terjadi intensif di kampungkampung nelayan yang tingkat kemiskinannya tinggi. Sebagai contoh, dalam jaringan sosial berbasis hubungan ketetanggaan, orang-orang yang mampu (pedagang, nelayan pemilik, atau pihak lainnya) dan memiliki sumber daya ekonomi lebih dari cukup akan membantu tetangganya yang kekurangan. Biasanya bantuan tersebut berupa barang-barang natura, makanan, informasi, pakaian, dan upah jasa. Mereka yang telah ditolong itu akan membalas kebaikan tersebut dengan kesiapan menyediakan jasa tenaganya untuk membantu patron. Aktualisasi relasi patron-klien ini merupakan upaya menjaga kerukunan bersama, sehingga efek negatif kesenjangan sosial di kalangan masyarakat nelayan dapat diminimalisasi (Kusnadi, 2000). Realitas sosial demikian dan masih berfungsinya pranata-pranata budaya itu menunjukkan bahwa upaya sebagian akademisi memahami masalah sosial dalam masyarakat nelayan dari perspektif kelas, bukan hanya tidak tepat, tetapi juga menyesatkan secara akademis. I. KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK DALAM MASYARAKAT PANTAI Konflik dalam masyarakat pantai khususnya nelayan sering sekali kita temukan terutama konflik yang dipicu karena kepentingan terhadap sumberdaya. Tingginya kepentingan akses terhdap sumberdaya linear dengan semakin menurunnya hasil tangkapan ikan. Akibat menurunnya hasil tangkapan ikan ini diakibatkan oleh aktivitas penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan maka masyarakat nelayan menghendaki suatu aturan yang tegas dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga dapat menciptakan kelestarian
sumber daya dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Di Lombok misalnya dikenal Awig-awig yaitu aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat untuk mengatur pengelolaan akses terhadap sumberdaya laut. Awigawig difungsikan untuk pengelolaan kelautan agar kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan yang merusak lingkungan dan menyebabkan konflik dapat dihindari. (Solihin dan Satria, 2007) Dengan melihat factor-faktor yang menyebabkan terciptanya konflik di lingkungan pesisir yang berujung pada penghancuran sumberdaya ikan, maka masyarakat Lombok utara merasa terpanggil dan menyadari untuk mengadakan perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya. Oleh karena itu, dibentuklah Awig-awig secara tertulis sebagai aturan main dalam pengelolaan perikanan demi menciptakan pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Kekuatan Awig-awig yang mengatur sistem pengelolaan bersama itu merupakan suatu kesadaran kolektif dari masyarakat yang hidup di sekitar pesisir pantai Lombok. Kesadaran kolektif dalam pembentukan Awig-awig ini lebih cenderung dipengaruhi oleh lingkungan laut yang semakin rusak. Artinya, Awigawig merupakan strategi adaptasi masyarakat nelayan yang dimaksudkan untuk mengalokasikan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya guna mengatasi tekanan-tekanan sosial ekonomi. Proses pembentukan Awig-awig dimulai dari tahapan informal, yaitu berupa ungkapan-ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi perairan laut yang semakin rusak, sehingga mempengaruhi hasil tangkapan mereka dalam rangka menghidupi keluarganya sehari-hari. Sementara dalam tahapan formal, dimulai dari rapat-rapat internal kelompok hingga rapat besar yang melibatkan pemerintah dan masyarakat nelayan lainnya dengan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan local dalam mengatur kegiatan penangkapan ikan. Pemberlakuan Awig-awig telah meminimalisir konflik, baik konflik antar nelayan local yang disebabkan oleh perbedaan alat tangkap, maupun konflik antara nelayan local dengan nelayan luar. Sama halnya dengan masyarakat nelayan di Kalimantan Timur dimana konflik nelayan yang terjadi disebabkan oleh perbedaan alat tangkap antara nelayan mini trawl dengan Nelayan Parengge.. Beberapa konflik lain seperti konflik nelayan pejala dengan pebagan perahu, pemancing dengan pembom, nelayan tradisional dengan nelayan modern, bahkan konflik eksternal antara nelayan dengan korporasi pertambangan migas di Kalimantan Timur adalah sekelumit konflik masyarakat nelayan disebabkan karena arus degradasi lingkungan laut yang semakin cepat akibat dari overeksploitasi ikan, kesemuanya dipicu oleh perbedaan kemajuan teknologi alat tangkap ikan. Kesenjangan teknologi ini menyebabkan terjadinya dominasi nelayan yang lebih besar/modern terhadap nelayan yang lebih kecil atau tradisional. Dalam memperjuangkan untuk mempertahankan hak dan kehidupannya, para nelayan mampu melakukan berbagai strategi mulai dari dialog damai, demo, penyanderaan hingga pembakaran. Dengan kata lain, dalam melakukan perjuangan, para nelayan mampu melakukan jalan damai atau dengan kekerasan. Tingkat kebrutalan konflik dipengaruhi oleh apakah isu konflik tersebut menyangkut masalah sumber penghidupan atau tidak. Jika isunya menyangkut sumber penghidupan, meskipun bersifat realistic, cenderung mengakibatkan konflik yang brutal. Selain itu, kebrutalan konflik juga dipengaruhi oleh proses penyelesaiannya. Jika proses penyelesaiannya berlarut-larut dan jalan damai tidak berhasil, maka konflik cenderung brutal. (Kinseng, 2007) Daftar Pustaka
Astuty, Ernany Dwi dkk. 2006. Restrukturisasi Institusi Ekonomi. Jakarta, Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Burke, Peter. 2003. Sejarah Dan Teori Sosial. Edisi 2. Diterjemahkan oleh Mestika Zed & Zulfami. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Elfindri. 2002. Ekonomi Patron-Client: Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro. Padang: Andalas University Press. Eisenstadt, S.N. dan L. Roniger. 1984. Patrons, Clients, and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society. Cambridge: Cambridge University Press. Ginkel, Rob van. 2007. Coastal Cultures: An Anthropology of Fishing and Whaling Traditions. Apeldoorn: Het Spinhuis Publishers. Kingseng, R.A. 2007. Konflik-Konflik Sumberdaya Alam di Kalangan Nelayan Indonesia. Sodality : Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Kusnadi. 2000. Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial. Bandung: Humaniora Utama Press. Keesing, Roger M. 1989. Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer. Jakarta: Erlangga. Kluckhon, Clyde 1984. Cermin bagi Manusia, dalam Parsudi Suparlan (Ed.). Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 69109. Legg, Keith. R. 1983. Tuan, Hamba, danPolitisi. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. Masyhuri. 1995. Pasang Surut Usaha Perikanan Laut, Tinjauan Sosial Ekonomi Kenelayanan di Jawa dan Madura 1850-1940. Vrije Universiteit Academich Proefschrijft. Nasution, M.A.; Badaruddin; dan Subhilhar. 2005. Isus-isu Kelautan Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nikijuluw, V.P.H. 1994. Sasi sebagai Suatu Pengelolaan Sumberdaya Berdasarkan Komunitas (PSBK) di Pulau Saparua, Maluku. Jurnal Penelitian Perikanan Laut. Purnamasari, Elly; Sumantri, Titik; Kolopaking, Lala M. 2002. Pola Hubungan Produksi Ponggawa-Tambak: Suatu Bentuk Ikatan Patron-Klien (Studi Kasus Masyarakat Petambak Di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Pasir Kalimantan Timur. Jurnal Forum Pascasarjana Vol. 25.No. 2. April 2002. Pelras, Christian. 2009. Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan dalam Tol, Roger; van Dijk, Kees; Acciaioli, Greg.Kuasadan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan. Ininnawa. Makassar. Saad, S. 1994. Rompong : Suatu Tradisi Penguasaan Perairan Pantai pada Masyarakat Bugis-Makasar. Era Hukum, 2:35-47. Salman, D. 2012. Sosiologi Desa : Revolusi Senyap Dan Tarian Kompleksitas. Inninawa. Makassar _____________. Sistem Sosial Masyarakat Pesisir. Bahan Kuliah Sistem Sosial Masyarakat Pesisir. Universitas Hasanuddin.Makassar Solihin, A; Satria A. 2007. Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah Sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan : Kasus Awig-Awig di Lombok Barat. Sodality : Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Scott, James C. 1981. Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Cetakan Pertama Diterjemahkan Hasan Basari Dari Judul Asli
The Moral Economic Of The Peasant Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. Jakarta: LP3ES. _____________. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Wahyono, A., Sudiyono, dan F.I. Thufail. 1993. Aspek-aspek Sosial Budaya Masyarakat Maritim Indonesia Bagian Timur. Hak Ulayat Laut Desa Para, Kecamatan Manganitu, Sangihe Talaud. Seri Penelitian PMB-LIPI No.4 : 51 halaman.
You might also like
- Kemiskinan NelayanDocument6 pagesKemiskinan NelayanSepatu KusamNo ratings yet
- Klasifikasi LautDocument3 pagesKlasifikasi LautDaffa JuliantamaaNo ratings yet
- Makalah Ekologi Akuatik Intertidal 2015 FixDocument23 pagesMakalah Ekologi Akuatik Intertidal 2015 Fixbocah musikNo ratings yet
- Makalah Ekosistem MangroveDocument12 pagesMakalah Ekosistem MangroveHesti NurrohmahNo ratings yet
- Depurasi Logam Berat Pb dan Cd pada Kerang DarahDocument8 pagesDepurasi Logam Berat Pb dan Cd pada Kerang DarahDaniel Prakoso100% (1)
- Jurnal Fisiologi Biota LautDocument11 pagesJurnal Fisiologi Biota LautAz I SNo ratings yet
- Laporan Pelatihan Transplantasi KarangDocument8 pagesLaporan Pelatihan Transplantasi KarangEM Read-One LessyNo ratings yet
- Barrang LompoDocument7 pagesBarrang LompoSiti KamariahNo ratings yet
- EKOSISSTEM PERAIRANDocument6 pagesEKOSISSTEM PERAIRANIlham Sutandio AtjoNo ratings yet
- Estuaria EkosistemDocument23 pagesEstuaria EkosistemElfi AnaNo ratings yet
- Makalah Lamun 2Document29 pagesMakalah Lamun 2Kurniah TunnisaNo ratings yet
- MakrozoobenthosDocument11 pagesMakrozoobenthosDwi Kus PardiantoNo ratings yet
- PENGHANCURAN TERUMBU KARANGDocument32 pagesPENGHANCURAN TERUMBU KARANGistiqcuantexNo ratings yet
- Manual Monitorng LamunDocument29 pagesManual Monitorng LamunFannyKristiadhi100% (1)
- Terumbu KarangDocument6 pagesTerumbu KarangDara PermatasariNo ratings yet
- PlanktonDocument7 pagesPlanktonRizky AdipratamaNo ratings yet
- Koralogi Terumbu KarangDocument22 pagesKoralogi Terumbu KarangBeV100% (1)
- Taman Pesisir Ujungnegoro-RobanDocument6 pagesTaman Pesisir Ujungnegoro-RobanSoni AndriawanNo ratings yet
- Tugas PPT Pemamtauan HabitatDocument71 pagesTugas PPT Pemamtauan HabitatAndika Nst OfficialNo ratings yet
- Makalah Amkl (Tambak Udang)Document18 pagesMakalah Amkl (Tambak Udang)Putri Oktayanti Go'oNo ratings yet
- Karya Ilmiah Pertumbuhan Lamun Dan Dampak Pada PertumbuhannyaDocument11 pagesKarya Ilmiah Pertumbuhan Lamun Dan Dampak Pada PertumbuhannyaraflyNo ratings yet
- Zona Pesisir Dan Zona LautDocument8 pagesZona Pesisir Dan Zona LautAlfin El-mlipakiNo ratings yet
- Flora Air TawarDocument31 pagesFlora Air TawarJony KechapNo ratings yet
- Kesling PesisirDocument18 pagesKesling PesisirnilasariNo ratings yet
- Tugas Rehabilitasi Terumbu KarangDocument10 pagesTugas Rehabilitasi Terumbu KarangSandy Nur Eko Wibowo0% (1)
- Uts KSDHL 2021Document3 pagesUts KSDHL 2021Vetrus Octavianus MaNaluNo ratings yet
- Rangkuman Manajemen Das Dan Rawa GambutDocument11 pagesRangkuman Manajemen Das Dan Rawa GambutPratama Wira PutraNo ratings yet
- Kelompok 16 - DdmikDocument3 pagesKelompok 16 - DdmikDodi Tri Putra Sitompul 2004113327No ratings yet
- Terumbu Karang dan FungsinyaDocument4 pagesTerumbu Karang dan FungsinyaMuhammad Fahmi Djunaid AshariNo ratings yet
- Jurnalbl01169 Diakses 19102018Document95 pagesJurnalbl01169 Diakses 19102018ikhsan saputraNo ratings yet
- About KIMADocument28 pagesAbout KIMArizalbuntalNo ratings yet
- EKOSSTEM ESTUARIDocument6 pagesEKOSSTEM ESTUARIwarongNo ratings yet
- Rps LimnologiDocument10 pagesRps LimnologiFauzi MubarokNo ratings yet
- 2019smy PDFDocument49 pages2019smy PDFrachmad hidayatNo ratings yet
- EKOSISIRDocument34 pagesEKOSISIRMohamad RizwanNo ratings yet
- Protista EukariotikDocument30 pagesProtista EukariotiktadrisbiologiNo ratings yet
- Manfaat LamunDocument7 pagesManfaat LamunshintadspNo ratings yet
- Laporan Lengkap Fisbiola - RafsanjaniDocument24 pagesLaporan Lengkap Fisbiola - RafsanjaniRafsanjaniArNo ratings yet
- Makalah Senyawa Aktif Kuda LautDocument24 pagesMakalah Senyawa Aktif Kuda LautNabeela NurvitaNo ratings yet
- TERUMBUDocument21 pagesTERUMBUAhmad HidayatNo ratings yet
- Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan Dan Nelayan11Document16 pagesHak Guna Wilayah Hukum Perikanan Dan Nelayan11Ronald LeonardoNo ratings yet
- Bab I Biologi Laut Ekosistem Terumbu KarangDocument15 pagesBab I Biologi Laut Ekosistem Terumbu KarangNurhidayat Alverio100% (1)
- Laporan Pengamatan Ekosistem Pantai SulamandaDocument8 pagesLaporan Pengamatan Ekosistem Pantai SulamandaHendra WoluNo ratings yet
- PLANKTON PENTINGDocument8 pagesPLANKTON PENTINGShendy Aditya67% (3)
- Karang AnatomiDocument4 pagesKarang AnatomiNugraha AliNo ratings yet
- Jenis Ikan Hiu di DuniaDocument37 pagesJenis Ikan Hiu di DuniaMarten LukasNo ratings yet
- Ekosistem Laut TropisDocument24 pagesEkosistem Laut Tropisahmad lubbenNo ratings yet
- Aktivitas Manusia Dan Dampak Bagi Ekosistem Laut Dalam - Dyah Retno (55), Saylia (57), Vebry (60), Resti (65), SafuraDocument13 pagesAktivitas Manusia Dan Dampak Bagi Ekosistem Laut Dalam - Dyah Retno (55), Saylia (57), Vebry (60), Resti (65), SafuraRestiNo ratings yet
- PANTAI BUNAKENDocument22 pagesPANTAI BUNAKENmitaNo ratings yet
- EKOSISPERDocument18 pagesEKOSISPERJupriadiNo ratings yet
- Sumberdaya Ekosistem EstuariDocument18 pagesSumberdaya Ekosistem EstuariEriani ElegantyNo ratings yet
- Reptil, Burung, Dan Mamalia LautDocument9 pagesReptil, Burung, Dan Mamalia LautAdnan PandawaNo ratings yet
- Ikan Demersal dan KarangDocument52 pagesIkan Demersal dan KarangHolik SanjayaNo ratings yet
- Identifikasi Jenis Lamun, Tutupan, Morfometrik Dan Tegakan Lamun Di Perairan TablolongDocument7 pagesIdentifikasi Jenis Lamun, Tutupan, Morfometrik Dan Tegakan Lamun Di Perairan Tablolongselviana mboroNo ratings yet
- Jenis Jenis Penyu Di IndonesiaDocument61 pagesJenis Jenis Penyu Di IndonesiaVickyNo ratings yet
- Ekologi Air TawarDocument41 pagesEkologi Air TawarAsri Anto100% (1)
- Makalah Ekologi Pesisir Dan KelautanDocument14 pagesMakalah Ekologi Pesisir Dan KelautanIthaKadangNo ratings yet
- Karakteristik Masyarakat PesisirDocument9 pagesKarakteristik Masyarakat PesisirMiranda Claudya BasoNo ratings yet
- Sistem Sosial Dan Budaya Masyarakat MaritimDocument4 pagesSistem Sosial Dan Budaya Masyarakat MaritimFransiska HtbrNo ratings yet
- Tanaman Pepohonan Untuk Menjernihkan & Menetralisir Air Limbah Beracun Berbahaya Dari Kawasan Perairan Laut Sungai DanauFrom EverandTanaman Pepohonan Untuk Menjernihkan & Menetralisir Air Limbah Beracun Berbahaya Dari Kawasan Perairan Laut Sungai DanauNo ratings yet
- Management Effectiveness Evaluation of Kapoposang Marine Conservation Areas and Pangkep Marine Conservation AreasDocument214 pagesManagement Effectiveness Evaluation of Kapoposang Marine Conservation Areas and Pangkep Marine Conservation AreasAhdiat Celebes0% (1)
- Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Dan Zonasi KKP3KDocument10 pagesPedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Dan Zonasi KKP3KAhdiat CelebesNo ratings yet
- Pedoman Kelembagaan KKP3KDocument27 pagesPedoman Kelembagaan KKP3KAhdiat CelebesNo ratings yet
- Konservasi Laut Dalam Konteks Hukum PDFDocument10 pagesKonservasi Laut Dalam Konteks Hukum PDFAhdiat CelebesNo ratings yet
- PP 60/2007 Dan Hubungannya Dengan Penyelamatan Sumber Daya KelautanDocument9 pagesPP 60/2007 Dan Hubungannya Dengan Penyelamatan Sumber Daya KelautanAhdiat CelebesNo ratings yet
- Pedoman Tata Batas FinalDocument30 pagesPedoman Tata Batas Finaltinawati98No ratings yet
- Pedoman Pembiayaan Pengelolaan KKP3KDocument10 pagesPedoman Pembiayaan Pengelolaan KKP3KAhdiat CelebesNo ratings yet
- PP 60-2007 Dan Hubungannya Dengan Penyelamatan Sumber Daya Kelautan PDFDocument9 pagesPP 60-2007 Dan Hubungannya Dengan Penyelamatan Sumber Daya Kelautan PDFAhdiat CelebesNo ratings yet
- Dinamika Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Kab PangkepDocument52 pagesDinamika Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Kab PangkepAhdiat CelebesNo ratings yet
- Pelestarian SDA PDFDocument12 pagesPelestarian SDA PDFAhdiat CelebesNo ratings yet
- Dinamika Dan Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Di MajeneDocument40 pagesDinamika Dan Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Di MajeneAhdiat CelebesNo ratings yet
- Implementasi CCRF Di IndonesiaDocument8 pagesImplementasi CCRF Di IndonesiaAhdiat CelebesNo ratings yet
- Pencemaran Laut Dan Upaya Penegakan Hukumnya Di IndonesiaDocument7 pagesPencemaran Laut Dan Upaya Penegakan Hukumnya Di IndonesiaAhdiat CelebesNo ratings yet
- Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Dan Kemampuan Asimilasi LingkunganDocument7 pagesMeningkatkan Aktivitas Ekonomi Dan Kemampuan Asimilasi LingkunganAhdiat Celebes100% (1)
- METODE PENELITIAN KUALITATIF - PpsDocument19 pagesMETODE PENELITIAN KUALITATIF - PpsAhdiat CelebesNo ratings yet
- Kondisi Perairan Pantai Barat SulawesiDocument5 pagesKondisi Perairan Pantai Barat SulawesiAhdiat CelebesNo ratings yet
- Menteri Kelautan Dan Perikanan Terlalu GegabahDocument4 pagesMenteri Kelautan Dan Perikanan Terlalu GegabahAhdiat CelebesNo ratings yet
- Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRFDocument9 pagesCode of Conduct For Responsible Fisheries (CCRFAhdiat CelebesNo ratings yet
- Aliran Energi Dalam Ekosistem LamunDocument10 pagesAliran Energi Dalam Ekosistem LamunAhdiat CelebesNo ratings yet
- Insiden MontaraDocument3 pagesInsiden MontaraAhdiat CelebesNo ratings yet
- Pengelolaan Terumbu Karang Akibat Bleaching Dan SedimentasiDocument7 pagesPengelolaan Terumbu Karang Akibat Bleaching Dan SedimentasiAhdiat CelebesNo ratings yet
- Mercuri Di Teluk KaoDocument3 pagesMercuri Di Teluk KaoAhdiat Celebes100% (1)
- Reproduksi MangroveDocument15 pagesReproduksi MangroveAhdiat CelebesNo ratings yet
- Kemiskinan NelayanDocument11 pagesKemiskinan NelayanAhdiat CelebesNo ratings yet
- Pengelolaan Sumberdaya Dan KemiskinanDocument35 pagesPengelolaan Sumberdaya Dan KemiskinanAhdiat CelebesNo ratings yet
- ANALISA WACANA - PpsDocument18 pagesANALISA WACANA - PpsAhdiat CelebesNo ratings yet
- AdvocateDocument11 pagesAdvocateAhdiat CelebesNo ratings yet