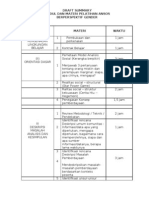Professional Documents
Culture Documents
Plot Dan Stilistika
Uploaded by
rezafajriCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Plot Dan Stilistika
Uploaded by
rezafajriCopyright:
Available Formats
1
Plot dan Stilistika Oleh Budi Darma (pokok-pokok pikiran dalam Lokakarya Penulisan Novel, Universitas Brawijaya, Malang, Minggu, 15 Mei 2005) Cerita dan Plot Dalam percakapan sehari-hari cerita (story) identik dengan plot (alur). Namun, dalam sastra, dua istilah itu mempunyai makna berbeda. Cerita adalah rangkaian peristiwa, sedangkan alur adalah rangkaian peristiwa yang diikat oleh hukum sebab-akibat. Tadi pagi saya bangun jam empat, lalu saya bersembahyang, dan sesudah itu saya membaca buku, lalu saya mandi, dan sesudah mandi saya makan pagi adalah cerita, karena antara satu peristiwa dan peristiwa lain merupakan kelanjutan. Plot, sebaliknya, mempunyai kaitan sebab-akibat, misalnya: Sebetulnya tadi pagi saya ingin bangun pukul empat, tapi karena tadi malam saya bekerja sampai larut malam, maka saya terlambat bangun. Segera setelah bangun saya lanngsung ke kamar mandi, namun ternyata, sebelum saya sampai di kamar mandi, tilpun berdering. Ada berita, ibu saya sakit keras. Setelah mendengar berita ini saya batalkan niat saya untuk mandi. Saya hanya gosok gigi sebentar, berpakaian, lalu dengan amat tergesa-gesa dan tanpa mandi, saya meninggalkan rumah untuk menuju ke terminal bis. Tiga jam kemudian, sampailah saya di rumah orang tua saya. Ternyata, ibu saya sama sekali tidak sakit. Beliau menyuruh pembantunya untuk menilpun saya semata karena beliau rindu. Plot dan karakterisasi Tanpa karakter (tokoh), dengan sendirinya plot tidak mungkin ada. Plot terjadi karena masing-masing karakter mempunyai watak sendiri, dan karena itu, pada suatu saat mereka akan berbeda pemandangan. Perbedaan pandangan dapat muncul dalam bentuk dialog, pikiran, dan juga tindakan. Dialog, pikiran, dan tindakan inilah yang kemudian melahirkan plot. Plot juga tidak akan terjadi manakala karakter tidak didramatisasikan. Dengan didramatisasikan dimaksud, masing-masing karakter tidak hanya diam semata-mata, namun hidup, sebagaimana yang nampak dalam drama. Karakter harus, berbicara, berpikir, dan bertindak. Karena karakter berbicara, berpikir, dan bertindak itulah, sekali lagi, plot dapat tercipta. Ukuran apakah seorang karakter itu berhasil atau tidak juga diambil dari sini: kata-katanya, pikirannya atau apa yang bergejolak di otaknya, dan tindakan-tindakannya. Masih ada lagi satu butir yang perlu dipikirkan dalam
menciptakan seorang karakter yang baik, yaitu, apa pendapat dan sikap karakter-karakter lain terhadap karakter tententu itu. Eksposisi Sebelum masuk ke plot, penulis drama tradisional biasanya menuliskan sebuah eksposisi terlebih dahulu. Melalui eksposisi pembaca akan tahu kira-kira drama ini nanti mengenai apa, siapa saja karakterkarakternya yang penting, apa watak masing-masing karakter itu, dan apa saja kira-kira yang akan terjadi dalam drama ini. Setelah eksposisi berakhir, barulah drama masuk ke dalam plot. Apakah eksposisi diperlukan atau tidak dalam novel, tergantung pada pengarangnya sendiri. Dalam novel-novel sastra dunia abad ke-19 sampai dengan sekitar tahun 1850-an, pada umumnya pengarang memulainya dengan eksposisi terlebih dahulu. Eksposisi bisa panjang, bisa pendek, bisa eksplisit, bisa pula implisit. Kalau ada eskposisi, eskposisi ini dapat diungkapkan dalam berbagai cara. Beberapa cara itu antara lain dikskripsi mengenai setting tempat, termasuk nama, waktu, dan suasana tempat itu, diskripsi ringkas mengenai beberapa karakter penting, dan lain-lain. Eksposisi tidak perlu panjang, cukup ringkas dan padat, dan tidak perlu ditulis dalam satu bab khusus, tapi merupakan awal dari bab satu. Konflik Karena masing-masing karakter mempunyai watak masing-masing, kepentingan yang berbeda, suasana hati yang tidak sama, maka terciptalah konflik. Watak berbeda, misalnya, yang satu suka marah, yang lain tidak. Kepentingan yang berbeda, misalnya, yang satu memerlukan berita dari channel berita TV karena pekerjaannya berhubungan dengan berita, yang lain memilih channel musik karena dia dalam keadaan lelah dan karena itu ingin menghibur diri. Suasana hati berbeda, misalnya, yang satu sedih karena tidak lulus ujian, yang lain bahagia karena baru mendapat surat dari pacarnya. Konflik bisa keras bisa pula tidak, bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan tindakan. Biasanya, konflik yang baik tidak dalam bentuk perkelahian fisik, namun dalam bentuk lain, misalnya memilih untuk menghindar. Sumber konflik juga macam-macam, antara lain masalah moral, masalah sikap yang berbeda, masalah dendam, dan sebagainya. Konflik masalah moral, misalnya, yang satu suka minum-minum sedangkan yang lain amat alim. Konflik mengenai pendapat yang berbeda, misalnya, yang
satu ekstrovert, sedangkan yang lain introvert. Konflik karena balas dendam, sementara itu, bisa dicari banyak contohnya dari film-film silat Hongkong. Krisis Dengan adanya konflik, akan terciptalah krisis. Misalnya, sepasang pacar konflik karena cemburu. Mereka bertengkar, dan pertengkaran ini menimbulkan ketegangan, bahkan, kadang-kadang sampai menjurus ke perpisahan. Inilah krisis. Namun, krisis sering menurun dengan sendirinya, karena sepasang pacar yang bertengkar hebat ini kemudian diam-diam berdamai lagi, dan kembali mesra seperti sebelumnya. Krisis bisa kecil bisa besar, dan bisa terjadi berulang-ulang. Klimaks Akhir krisis adalah klimaks. Karena krisis bisa terjadi beberapa kali, maka klimaks pun bisa pula terjadi beberapa kali. Namun akhirnya, krisis yang berulang-ulang itu akan mencapai satu krisis besar. Krisis besar inilah yang menciptakan puncak klimaks. Baik krisis besar maupun puncak klimaks hanya terjadi satu kali, tidak berkali-kali. Puncak klimaks selalu menentukan akhir/penutup novel. Kalau puncak klimaksnya begini, maka penutup novelnya akan begini, dan kalau puncak klimaksnya tidak begini, maka penutup novelnya juga tidak begini. Salah satu tolok ukur novel yang baik adalah hubungan antara puncak klimaks dan penutup novel. Contoh klimaks dalam cerpen dapat dilihat dalam karya D.H. Lawrence, pengarang Inggris awal abad ke-20, berjudul The Rocking Horse Winner. Dalam cerpen ini terceritalah ada sebuah keluarga yang gaya hidupnya berada jauh di atas penghasilannya. Gajih keluarga ini kecil, namun mereka ingin hidup di rumah mewah di daerah mewah pula, lengkap dengan kolam renangnya, dan sebagainya. Karena gaya hidup mereka terlalu tinggi, mereka selalu kekurangan uang. Perasaan tertekan karena kekurangan uang ini menyebabkan mereka dihantui oleh halusinasi, khususnya pada saat-saat menjelang Natal, karena pada waktu Natal mereka memerlukan jumlah uang yang jauh lebih besar. Mereka merasa, seolah semua benda di rumah berteriak-teriak kami perlu uang lagi, kami perlu uang lagi, kami perlu uang lagi, tanpa henti. Dinding berteriak, almari berteriak, sepatu berteriak, dan semuanya tanpa kecuali berteriak minta uang. Keluarga ini mempunyai seorang anak laki-laki kecil, Paul namanya. Pada suatu hari dengan nada polos Paul bertanya kepada ibunya: Bu, mengapa kita tidak punya mobil sendiri? Mengapa kita selalu tidak punya
uang? Ibunya menjawab: Karena kita tidak punya keberuntungan. Paul bertanya: Keberuntungan? Apa keberuntungan itu berarti uang? Ibunya tidak menjawab. Paul berdialog dengan dirinya sendiri: Kalau begitu, saya akan mencari keberuntungan. Sementara itu, ibunya membelikan Paul kuda mainan dari kayu. Dengan senang hati Paul menerima kuda mainan itu, lalu dia naik dan menjungkat-jungkitkan kudanya. Demikianlah, setiap hari dia bermain-main dengan kuda mainannya. Pada suatu hari, tukang kebun keluarga ini melihat sesuatu yang aneh pada Paul. Setiap kali akan mencapai puncaknya dalam bermain-main dengan kudanya, Paul selalu meneriakkan satu nama. Tukang kebun ini berpikir keras untuk mengetahui apa makna nama itu sebetulnya. Akhirnya, sebuah jawaban ditemukan oleh tukang kebun ini. Nama yang diteriakkan Paul tidak lain adalah nama kuda yang akan menang dalam balap kuda. Maka, tukang kebun ini pun memasang taruhan setiap kali ada balap kuda, dan selalu menang. Demikianlah, tukang kebun dan Paul akhirnya menjadi kaya. Baik Paul maupun tukang kebun itu tidak mau mengatakan kepada orang tua Paul mengenai keajaiban ini. Maka melalui pengacaranya, dengan tanpa menyebut nama, Paul secara berkala mengirim uang yang banyak jumlahnya kepada ibunya. Namun, setiap kali menerima uang, ibunya hanya mau menerima uang tanpa keinginan untuk mengetahui dari mana sebetulnya uang itu datag. Keluarga ini tetap hidup boros, namun kaya raya. Pada suatu hari, orang tua Paul menghadiri pesta. Dalam pesta itu sekonyong-konyong ibunya merawa was-was. Maka, dia pun pulang sendirian. Ternyata, rumahnya gelap. Ibunya merasa heran, karena dari kamar Paul terdengar sayup-sayup suara ganjil. Maka, dengan mengendap-endap dia mendekati kamar Paul. Makin dekat dengan kamar Paul, suara ganjil itu terdengar semakin keras. Setelah sampai di depan kamar Paul, dengan sangat cepat sekali ibunya membuka pintu, menyalakan lampu, dan langsung berteriak: Paul, apa yang kau lakukan? Paul sedang menggoncang-goncang kuda mainannya. Ketika ibunya sekonyong masuk, menyalakan lampu, dan berteriak, Paul sedang mencapai puncaknya. Paul sempat meneriakkan sebuah nama. Namun, ibunya tidak tahu apa-apa. Ibunya justru mengira, Paul yang sudah cukup besar ini sudah menjadi sinting karena masih suka main kuda mainan.
Karena amat terkejut, setelah meneriakkan sebuah nama Paul terjatuh, tidak sadar, dan suhu badannya mendadak melonjak menjadi tinggi sekali. Tiga hari kemudian, Paul meninggal. Puncak klimaks terjadi, ketika dengan mendadak ibu Paul membuka kamar, menyalakan lampu, dan berteriak. Seandainya ibunya tidak berbuat itu, maka Paul tetap hidup. Demikianlah, puncak klimaks menentukan penutup novel. Klimaks eksplisit Seperti halnya dalam cerpen, tidak semua novel mempunyai klimaks yang jelas. Sebagai contoh, ambillah sebuah cerpen karya mahasiswa UNESA di Jawa Pos beberapa tahun yang lalu. Siapa pengarang dan apa judulnya, maaf, tidak dapat dilacak kembali. Terceritalah, aku seorang mahasiswa, pada saat-saat kegiatan akademis mencapai puncak. Aku harus menyiapkan banyak makalah, mencari data, membaca, dan seterusnya, yang membuat aku benar-benar lelah. Maka, meskipun tugas masih banyak sekali dan semuanya harus cepat aku selesaikan, aku putuskan untuk tidur sebentar. Tiba-tiba aku terjaga, karena mendengar ibuku berteriak-teriak sambil terus-menerus menyebut namaku. Aku pun membuka pintu kamar, dan tahulah aku, bahwa ibuku menangis keras-keras karena melihat aku sudah mati. Itu, di tengah ruang tamu itu, mayatku tergeletak di atas dipan. Lalu, kakak saya datang. Sambil meneriak-neriakkan namaku, kakakku lari ke arah mayatku. Seperti ibu, dia pun menggoncang-goncangkan mayatku, menyatakan keheranannya mengapa aku yang masih semuda ini, meninggal. Tidak lama kemudian, para pelayat pun datang. Sebagian besar pelayat adalah orang-orang yang sudah aku kenal dengan akrab. Mereka mengobrol, membicarakan tentang kematianku, sebagaimana layaknya para pelayat pada umumnya. Aku berjalan-jalan di antara para pelayat, dan tidak satu pun di antara mereka yang tahu bahwa saya berada di antara mereka. Upacara demi upacara dilakukan, termasuk pidato-pidato teman-temanku dan tetanggatetanggaku. Setelah acara pemberangkatan selesai, mayatku pun diusung ke makam. Di makam, setelah melalui berbagai upacara lagi, mereka memasukkan mayatku ke dalam liang lahat. Aku pun ikut berdesak-desakan di antara para pelayat untuk menyaksikan mayatku diturunkan perlahanlahan. Setelah upacara pemakaman selesai, pergilah semua orang meninggalkan makam, termasuk aku pula.
Aku pun pulang, sampai akhirnya, sampailah aku di rumah kembali. Aku terbangun, dan aku sangka, semua yang aku saksikan tadi hanyalah mimpi, namun, tidak mungkin. Seandainya tadi aku benar-benar bermimpi, tidak mungkin pakaianku kotor, penuh dengan lumpur makam. Dalam cerpen ini mungkin puncak klimaksnya ada, mungkin pula tidak ada. Seandainya memang ada, di mana letaknya, tidak jelas. Alasannuya, tidak lain, karena hakikat cerpen ini berbeda dengan The Rocking Horse Winner. Lalu, apakah novel yang baik harus memiliki puncak klimaks yang jelas atau tidak, tergantung pada pengarangnya sendiri. Namun dalam perkembangan penulisan sastra, baik dalam cerpen maupun dalam novel, ada kecenderungan untuk membuat puncak klimaks terselubung. Bahkan, nampaknya, akhir-akhir ini, para pengarang, sadar atau tidak, meniadakan puncak klimaks. Non-konflik Sebagaimana yang sering diungkapkan oleh bebagai pihak, baik cerpen maupun novel Indonesia kurang mampu untuk menampilkan konflik yang signifikan. Ada gejala, kata bebagai pihak tersebut, bahwa pengarang justru menghinadari konflik antar-karakternya. Menurut Kuntowijoyo dalam esainya di majalah kebudayaan Basis awal tahun 1980-an, sadar atau tidak para pengarang Indonesia masih terikat tradisi wayang, dan karena itu, cenderung untuk menghindari konflik. Dalam wayang hanya ada dua macam karakter, yaitu karakter hitam dan karakter putih. Plot disusun untuk memperkuat karakterisasi hitam putih itu. Akibatnya, konflik signifikan tidak ada, karena bisa diselesaikan dengan pola hitam putih. Ketiadaan konflik yang signifikan ini mendorong berbagai fihak untuk menuduh sastra Indonesia sebagai sastra yang lemah. Apa betul lemah atau tidak, biarlah khalayak menilainya sendiri. Namun, kecenderungan untuk meniadakan konflik yang signifikan merupakan gejala umum baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Gaya bahasa emotif Sebagai sarana ekspresi, dengan sendirinya bahasa mencerminkan logika pengguna bahasa itu. Sementara itu, seorang skolar Perancis abad ke17, Buffon namanya, menyatakan, le style, cest lhomme. Gaya bahasa sebagai refleksi dari logika seseorang, menurut Buffon, tidak lain merupakan pencerminan orang itu sendiri.
Karena novel bukan cerpen, maka bahasanya pun, pada umumnya, tidak sama dengan bahasa koran atau bahasa percakapan sehari-hari. Kendati sementara pihak menganggap bahwa novel adalah cerminan realita, realita dalam novel sudah tidak murni lagi. Betapa kuat pun pengarang diikat oleh realita, instink kepengarangan seorang pengarang pasti mendorong dia untuk mempergunakan imajinasinya. Disamping penggunaan imajinasi, pengarang pun terikat oleh faktor lain, yaitu tuntutan estetika. Sebagimana halnya dalam seni lukis, lukisan dibuat lebih indah daripada objeknya sendiri. Lukisan dan novel, dengan demikian, dianggap sebagai metaphora realita. Untuk mencapai tahap metaphoris, pengarang novel mempermainkan penggunaan bahasanya dengan kemahiran seni yang tinggi. Karena itulah, kemudian tercipta bahasa emotif. Bahasa emotif, sementara itu, adalah bahasa yang dipergunakan oleh pengarang untuk menarik empati pembacanya. Pembaca dibuat bersimpati, berantipati, ikut marah-marah, kecewa, bahagia, dan lai-lain, itulah fungsi bahasa emotif. Dengan demikian, pembaca, tanpa sadar, merasa terlibat dalam dunia novel itu sendiri. Tentu saja, bahasa emotif bukan satu-satunya sarana untuk menarik empati, sebab, bahasa yang deskriptif pun, yaitu menggambarkan realita sebagaimana adanya, dapat juga mengajak pembaca untuk ikut sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Pengarang yang nampak gigih memperjuangkan bahasa emotif adalah Nukila Amal, sebagaimana yang nampak dalam novel Cala Ibi. Sebelum diterbitkan dalam bentuk novel, beberapa bagian Cala Ibi pernah dimuat di jurnal Kalam, dan karena itu memberi kesan sebagai cerpen. Nukila berjuang keras, agar bahasa benar-benar puitik, karena, bahasa puitik adalah salah satu komponen penting dalam bahasa emotif:
"Bapakku anggrek bulan, putih dari hutan. Ibuku mawar merah di taman, dekat pagar pekarangan. Bertemu suatu pagi di pelabuhan. Melahirkanku. Bayi merah muda kemboja. Bunga kuburan"
Untuk kepentingan menarik empati pembaca, oleh Nukila Amal, logika dikorbankan, tentu saja dengan catatan, bahwa Cala Ibi bukan novel realis. Ingat, yang dikorbankan adalah logika, bukan pengurangan atau penambahan realita. Sementara itu, dalam New Criticism yang biasa ngurusi puisi namun akhirnya masuk pula ke prosa, bahasa emotif dapat pula menciptakan fallacy alias pemalsuan untuk menarik empati pembaca.
Dalam New Criticism, dengan demikian, ada berbagai fallacy, yang semuanya merupakan pemalsuan realita guna menciptakan bahasa emotif. Intentional fallacy, misalnya, mengacu pada tujuan pengarang dalam menulis. Dengan mengadakan pemalsuan realita, maka tujuan pengarang menjadi samar, namun justru menjadi lebih efektif dalam menarik empati pembaca. Lalu, ada pula affective fallacy, yaitu mengacu pada pemalsuan realita agar pembaca, setelah menangkap tujuan pengarang, akan jatuh cinta pada karya itu. Realita orang yang sangat marah digambarkan menjadi dia amat sangat marah, dan karena itu seluruh wajahnya menjadi merah bagaikan darah, adalah pemalsuan atau fallacy, namun bukan pelanggaran terhadap logika. Fallacy semacam ini dapat pula dipergunakan untuk tekanan, sebagaimana yang pernah dipakai oleh Djenar Maesa Ayu dalam Waktu Nayla:
Ia hanya pingsan keletihan dan belum jua siuman. Ia hanya terhipnotis bandul jam yang bergerak kiri kanan dan berdetak dalam keteraturan. Membuat raganya beku. Lidahnya kelu. Hatinya membatu. Imajinasinya buntu.
Fallacy dengan bahasa puisi, yaitu dengan mempermainkan bunyi akhir suku kata telah menjadi kebiasaan dalam penulisan cerpen, sebagaimana yang nampak pula dalam cerpen Radhar Panca Dahana, Sepi Pun Menari Di Tepi Hari:
Sudah tak kukenali lagi diriku sendiri. Perkawinan adalah rumah sia-sia ketika tak ada lagi yang dapat atau pantas dikenali. Bukan saja segala menjadi asing, bahkan hidup yang harus dihidupi itu pun mengasingkan diri.
Agus Noor dalam cerpen Kupu-Kupu Seribu Peluru (Kompas Minggu) juga mempergunakan bahasa puisi untuk menarik empati pembaca, sebagaimana misalnya, ia melihat gadis kecil menggigil, bugil, seperti peri mungil yang usil dengan catatan, bahwa Agus Noor tidak memililih cerita realis. Gaya bahasa lakonik Awalnya gaya bahasa lakonik hanya dipergunakan dalam esai, dan bukan dalam fiksi. Namun ingat, kendati esai bukan fiksi, esai dapat pula dikategorikan sebagai karya sastra. Mengepa demikian, tidak lain, karena esai yang baik pasti ditulis dengan cita rasa seni yang tinggi pula.
Esai pertama kali dipraktekkan oleh seorang filsuf Perancis abad ke16, Michel Eyquem de Montaigne namanya. Kecuali dikenal sebagai filsuf, Montaigne juga dikenal sebagai sastrawan. Dengan menggabungkan kehebatannya sebagai filsof di satu pihak dan sastrawan di pihak lain itulah, maka esai Montaigne dikenal sebagai karya sastra yang cemerlang. Titik berat esai adalah penyampaian pikiran kepada pembaca, sedangkan titik berat novel adalah penyampaian kisah tertentu kepada pembaca. Gaya bahasa emotif dipergunakan untuk memancing empati pembaca yang berada di kawasan emosi dan perasaan, sedangkan bahasa lakonik esai lebih banyak dipergunakan untuk membangkitkan keterlibatan intelektual pembaca. Mengapa demikian, tidak lain karena novel adalah dunia kisah, sedangkan esai adalah dunia logika intelektual. Dari Perancis esai masuk ke Inggris, dan di Inggris esai kemudian dikembangkan oleh Francis Bacon. Sebagai halnya Montaigne, Francis Bacon juga seorang filsul dan saintis. Francis Baconlah yang pertama kali menganjurkan, agar segala sesuatu dalam sains tidak didasarkan pada asumsi-asumsi semata, namun harus didasarkan pada eksperimen. Untuk mengetahui contoh esai yang sebenarnya, tengoklah misalnya satu petikan esai Francis Bacon mengenai ambisi, suatu topik yang selamanya hangat baik dalam filsafat maupun psikologi:
Ambition is like choler; which is an humour that makes men active, earnest, full of alacitry, and stirring, if it be not stopped. But if it be stopped, and cannot have his way, it becomes adust, and thereby malign and venomenous. So ambitious men, if they find the way open for their rising, and still get forward, they are rather busy than dangerous; but if they be check in their desires, they become secretly discontent, and look upon men and matters with an evil eye, and are best please when things go backward .
Inilah ambisi, dan ini pulalah manusia ambisius. Dia punya semangat tinggi, penuh aktivitas, dan berkobar-kobar selama ambisinya tidak dihambat. Dalam keadaan ambisinya tidak dihambat dia akan benar-benar sibuk dan tidak berbahaya, namun ingat, begitu ambisinya terhambat, dia akan berubah. Dia akan lebih senang melihat segala sesuatunya mundur, sehingga dialah yang paling menonjol. Dalam tahap ini, tentu saja seseorang yang ambisius bukan hanya sibuk, namun cenderung berbahaya. Dia merupakan ancaman bagi sekelilingnya. Gagasan esai ini kompleks, diam-diam tapi pasti mengurai dengan cermat masalah ambisi dan manusia ambisius, serta menelusurinya sampai
10
mencapai titik kesimpulan yang sahih: Inilah ambisi, dan inilah manusia ambisius. Bahasanya laconic, yaitu patah-patah, seolah seperti kepak-kepak burung elang yang sedang melayang-layang di angkasa, kadang naik, kadang turun, kadang mengambang di udara. Kendati gaya bahasa lakonik awalnya dipergunakan dalam esai, gaya bahasa lakonik kemudian masuk pula ke dalam novel, sebagaimana yang nampak dalam novel Jane Austen, Pride and Prejudice. Di sana-sini dia mempergunakan esai sebagai senjata untuk menulis fiksi yang bagus. Nampaklah, bahwa esai bukan hanya bermanfaat dalam non-fiksi, sebab dalam novel pun, ternyata esai dapat dipergunakan dengan baik. Tengoklah, misalnya, bagian pertama Pride and Prejudice, suatu bagian dengan gaya laconic, dan benar-benar esaistik:
It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife. However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighbourhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered as the rightful property of some one or other of their daughters.
Inilah kisah kedatangan seorang bujangan kaya di suatu daerah, di mana tinggal beberapa perawan yang sudah saatnya menikah. Bujangan ini pasti akan memerlukan isteri, dan para orang tua perawan di daearah ini pasti akan berbahagia apabila salah seorang perawan mereka dipilih. Berbeda dengan kalimat-kalimat argumentatif Francis Bacon, dan karena itu tidak berhubungan dengan plot, dua kalimat Jane Austen ini dimaksudkan untuk menampung plot. Ingat, Jane Austen menyampaikan sebuah berita kebenaran untuk konteks abad ke-19, yang memang tepat. Gaya laconic dikuasainya dengan baik, dan karena itu, ke-esai-an kalimat-kalimatnya sebagai sarana pengucapan gagasannya juga memenuhi sasaran. Gagasannya cemerlang, demikian pula cara penyampaian gagasannya. Ernest Hemingway berbeda. Dia juga mempergunakan esai dalam bagian-bagian tertentu novelnya, sebagaimana yang nampak dalam adikaryanya, The Old Man and the Sea. Sepintas dia nampak tergelincir ke penggunaan slogan, namun, sebetulnya tidak: But man is not made of defeat, he said. A man can be destroyed
but not be defeated.
11
Inilah kisah mengenai seorang nelayan tua yang dijauhi sesama nelayan, karena dia dianggap sebagai orang sial, dan karena itu, barang siapa bergaul dengannya, pasti akan menjadi sial pula. Telah berkali-kali dia berlayar untuk menangkap ikan, namun selalu gagal. Dalam berlayar biasanya dia ditemani seorang anak kecil, namun sekarang anak kecil ini sudah dilarang ayahnya untuk menemaninya lagi. Demikianlah, dia berlayar sendirian, menghadapi kesepian, masa lalu yang indah, dan kesialan yang sekarang menimpanya. Bahaya demi bahaya dihadapinya sendiri, dengan mengandalkan tubuhnya yang sudah tua. Baginya, manusia tidak diciptakan untuk dikalahkan, dan dia sendiri yakin bahwa dia bisa saja dihancurkan, namun tidak mungkin bisa dikalahkan. Jane Austen telah membuktikan bahwa esai tidak tabu terhadap plot, demikian pula Ernest Hemingway, kendati dengan cara berbeda. Esai tidak tabu terhadap kontemplasi (Fancis Bacon), tidak tabu terhadap kontemplasi dan argumentasi (Francis Bacon dan Bertrand Russel), tidak tabu terhadap plot (Jane Austen), tidak pula tabu terhadap plot yang berbaur dengan pandangan hidup dan karena itu menyerempet sloganisme (Ernest Hemingway). Dalam berhadapan dengan semua dunia pemikiran, sesuai dengan hakikatnya sebagai sebuah karya seni, esai tidak melanggar kaedah mendasar karya seni, yaitu dulce atau kenikmatan, dan utile, yaitu kegunaan. =0= Rujukan Utama Budi Darma. Esai adalah Sebuah Jendela Terbuka. Dalam Jendela Terbuka: Antologi Esai Mastera. Eds. Dendy Sugono dan Budi Darma. 2005. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Hlm. IX-XX Budi Darma. Mensonge. Pengantar Cerpen Pilihan Kompas. 2005. Ed. Kompas. Jakarta: Kompas, akan diluncurkan pada tanggal 28 Juni 2005 di Jakarta =0=
You might also like
- Sepuluh Jurus Menulis Berita EkonomiDocument15 pagesSepuluh Jurus Menulis Berita EkonomirezafajriNo ratings yet
- Kritik Yang Berwawasan Humor Dalam KarikaturDocument2 pagesKritik Yang Berwawasan Humor Dalam KarikaturrezafajriNo ratings yet
- TOR Penulisan NovelDocument1 pageTOR Penulisan NovelrezafajriNo ratings yet
- Menuangkan Ide Melalui TulisanDocument2 pagesMenuangkan Ide Melalui TulisanrezafajriNo ratings yet
- Menuangkan Ide Dalam Tulisan (HIMA)Document1 pageMenuangkan Ide Dalam Tulisan (HIMA)rezafajriNo ratings yet
- Missing Link Gerakan Mahasiswa IndonesiaDocument5 pagesMissing Link Gerakan Mahasiswa IndonesiarezafajriNo ratings yet
- Sket Proposal Materi Penulisan NovelDocument4 pagesSket Proposal Materi Penulisan NovelrezafajriNo ratings yet
- Teknik Investigasi 2Document2 pagesTeknik Investigasi 2rezafajriNo ratings yet
- Pers Baru Dapat Dipidana Apabila Ada Unsur KengajaanDocument2 pagesPers Baru Dapat Dipidana Apabila Ada Unsur KengajaanrezafajriNo ratings yet
- Penulisan Resensi BukuDocument1 pagePenulisan Resensi BukurezafajriNo ratings yet
- Teknik Ar TikelDocument3 pagesTeknik Ar TikelrezafajriNo ratings yet
- Model AnsosDocument4 pagesModel AnsosrezafajriNo ratings yet
- Undang Undang PersDocument7 pagesUndang Undang PersrezafajriNo ratings yet
- Menumpulkan Pers Atau MemberdayakannyaDocument4 pagesMenumpulkan Pers Atau MemberdayakannyarezafajriNo ratings yet
- Peran Dan Eksistensi NovelisDocument5 pagesPeran Dan Eksistensi NovelisrezafajriNo ratings yet
- Ringkasan Modul CTDocument2 pagesRingkasan Modul CTrezafajriNo ratings yet
- Media Massa Dari Politik Ke BisnisDocument2 pagesMedia Massa Dari Politik Ke BisnisrezafajriNo ratings yet
- Memahami Alur Liputan InvestigatifDocument6 pagesMemahami Alur Liputan InvestigatifrezafajriNo ratings yet
- Nurdin Kalim - Sekadar PengantarDocument5 pagesNurdin Kalim - Sekadar PengantarrezafajriNo ratings yet
- JurnalDocument9 pagesJurnalrezafajriNo ratings yet
- Sekilas IndikatorDocument5 pagesSekilas IndikatorrezafajriNo ratings yet
- Silabus Diskusi Milis Litbangnas PPMI 2004Document3 pagesSilabus Diskusi Milis Litbangnas PPMI 2004rezafajriNo ratings yet
- Jurnalisme EmpatiDocument3 pagesJurnalisme EmpatirezafajriNo ratings yet
- Pers Mahasiswa Bukan Journalism SchoolDocument4 pagesPers Mahasiswa Bukan Journalism SchoolrezafajriNo ratings yet
- Teknik WawancaraDocument4 pagesTeknik WawancararezafajriNo ratings yet
- Nyanyian Cinta Persma Dan PergerakanDocument4 pagesNyanyian Cinta Persma Dan PergerakanrezafajriNo ratings yet
- Media KapitalisDocument6 pagesMedia KapitalisrezafajriNo ratings yet
- Persma Dan Dinamika PendidikanDocument2 pagesPersma Dan Dinamika PendidikanrezafajriNo ratings yet
- Mahasiswa Dan Tradisi BerpikirDocument3 pagesMahasiswa Dan Tradisi BerpikirrezafajriNo ratings yet