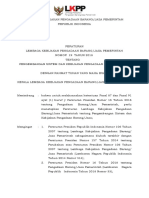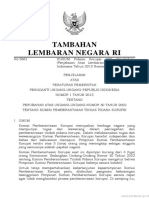Professional Documents
Culture Documents
Mencari Roh Taman Siswa Di Antara Komersialisasi Pendidikan Kita
Uploaded by
bangnono0 ratings0% found this document useful (0 votes)
27 views4 pagesOriginal Title
d
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
27 views4 pagesMencari Roh Taman Siswa Di Antara Komersialisasi Pendidikan Kita
Uploaded by
bangnonoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 4
MENCARI ROH TAMAN SISWA DI ANTARA
KOMERSIALISASI PENDIDIKAN KITA
Tidak tahu lagi seberapa resahnya laki-laki ini akan nasib bangsa
kala itu. Penjajahan telah mengerdilkan bukan cuma tubuh-tubuh rakyatnya, tapi
juga menggantikan akal-akal raksasa warisan kearifan kuno nenek moyang kita,
menjadi tak lebih ringkih dari budak. Sungguh, ketika dalam suatu masa selalu
saja (sengaja di)lahir(kan) orang-orang seperti Raden Mas Soewardi
Soeryaningrat (2 Mei 1889-28 April 1959), yang kemudian ketika berusia 40
tahun menemukan jati dirinya dalam Ki Hajar Dewantara setelah lama keluar
dari istana Paku Alaman Jogja dan menanggalkan status darah birunya. Persis
seperti ketika Mohandas K Gandhi, yang menemukan Mahatma-nya dari
sarangkaian perjalanan panjang dari seorang pengacara kaya di Afrika Selatan
untuk sekali waktu kembali ke negeri India. Sederet perjalanan mencari akar
permasalahan bangsanya, sebelum akhirnya menjadi Mahatma Gandhi, Gandhi
yang berjiwa besar. Jika Gandhi ini kemudian mengidentifikasi solusi
kemerdekaan bangsanya dengan Ahimsa, garis perjuangan nir-kekerasan. Lain
halnya Ki Hajar melihat kecenderungan elitisme pendidikan, yang dimonopoli
kaum berada dalam hal ini kaum bengsawan dan orang bule ini sebagai
penghalang raksasa jalan ke cita-cita Indonesia merdeka. Pada masa penjajahan
Belanda sistem pendidikannya disebut “Three Tracts System” yaitu pendidikan
yang dibagi menjadi tiga segmen, yang pertama untuk rakyat jelata dan kaum
pribumi miskin, kedua untuk bangsawan dan kaum borjuis dan terakhir untuk
orang Belanda, Eropa dan Timur Asing lainnya (termasuk Cina). Ketimpangan
yang terjadi karena pembagian ini berdasarkan strata sosial dan status ekonomi
(ada gejala kemiripan dengan sekarang?) yang mamberikan pengajaran kepada
kaum pribumi/rakyat jelata pendidikan yang ala kadarnya, disamping itu bagi
pendidikan bagi kelas kere ini hanya sampai pada jenjang sekolah menengah,
bandingkan dengan dua rekannya yang sampai pada tingkat sekolah tinggi. Ki
hajar pun dengan mati-matian berjuang pada jalur pencerdasan rakyat;
memberikan mereka pendidikan yang layak, menanamkan padanya kesadaran
nasib sebagai pemantik untuk bergerak, sebagai realisasinya ia lalu membuat
tujuh jenjang persekolahan, mulai Taman Indria (taman kanak-kanak), sampai
tingkatan Pra Sarjana dan Sarjana Wiyata (Akandemi dan Perguruan Tinggi)
semua dalam satu naungan perguruan yang didirikannya. Muncul dan membesar
mulai 3 Juli 1922, Taman Siswa, sebuah produk pendidikan yang berangkat
dari kegelisahan pada zamannya.
Taman Siswa, Simbol Perlawanan Pada Pembodohan Sistemik
Barangkali yang paling populer di telinga kita sampai sekarang
adalah corak sistem among-nya, yaitu Tut Wuri Handayani, Ing Ngarso Sung
Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso, atau mungkin Sistem Tri Kon-nya yang
menitik-beratkan pada pembinaan yang bersifat terus menerus (kontinu),
Berpusat pada kepribadian asli milik bangsa sendiri (konsentris), yang berfungsi
sebagai filter untuk berinteraksi dengan kebudayaan asing (konvergen). Namun
lebih dari itu, dalam praktiknya Taman siswa tak sekedar memberikan ilmu
pengetahuan bagi rakyat pribumi sebagai perangkat mengelola hidup, lebih dari
itu semangat perlawanan kepada penjajahan secara intens dan terkurikulum
dialirkan ke setiap peserta didik. Seorang alumni Taman Siswa, Ibu Desak Gede
Rakha Nada yang sempat mengenyam pendidikan di Taman Dewasa ( salah satu
sekolah di bawah naungan Taman Siswa, setingkat SMP) tahun 1939
menuturkan, para siswa di Taman Siswa kala itu dididik menjadi manusia
mandiri, sampai hal-hal kecil pun seperti membuat tempe, tahu dan salep. Di sisi
lain mereka juga diajarkan berpikir kritis, supaya bisa berdebat dengan
argumentasi aktual. Selain itu untuk tetap mengobarkan api perjuangan bangsa,
setiap hari Rabu Wage semuanya dikumpulkan untuk mendengar ceramah dari
sesepuh Taman Siswa, termasuk Presiden Soekarno tentang keadaan bangsa.
Inilah tugas pendidikan (yang sejati), salah satunya memberikan penyadaran
ketika suatu bangsa/kaum sedang dalam posisi dihinakan, diperas dan dibodohi
oleh sebuah sistem, bukan malah seperti sekarang yang seringkali malah
menjelma menjadi director pemerasan itu sendiri, atau memenjarakan peserta
didik/mahasiswa dengan kerangkeng akademik serta iming-iming duit.
Parahnya lagi ketika para mahasiswa yang katanya kaum Raushan Fikr di
dalamnya tenang-tenang saja melihat ketakberesan sekeliling, patutlah kiranya
me-muhasabah diri sendiri barangkali kita telah menjadi contoh par excellence
produk gagal tujuan pendidikan yang sebenarnya, sekaligus produk mekanik dari
pola pendidikan yang disorientasi dan kering idealisme.
Ada baiknya bercermin dari pemikiran gerakan taman siswa Ki
Hajar Dewantara yang Non Cooperation, sikap menolak kompromi dengan
kemauan penjajah yang menindas, Self-Help, lambang kemandirian sistem yang
bersandar pada kemampuan sendiri (bedakan dengan propaganda kemandirian
kampus-nya BHP) , selaiknya coba kita telaah bagaimana nilai-nilai kesadaran
perjuangan itu ditanamkan. Watak bangsa Indonesia sebelum penjajahan yang
jelasnya bukanlah watak bangsa yang kerdil dan dungu, siapa menyangsikan
kemegahan peradaban majapahit, sriwijaya, dan Islam yang dibangun oleh
kejeniusan manusia paripurna. Inilah satu sisi yang dilihat dengan penuh
keresahan oleh Taman Siswa, seperti ada sesuatu yang hilang dari jati diri
Indonesia. Tergantikan dengan watak inferior sebagai bangsa terjajah, yang
merasuk dan mencengkeram kuat-kuat ke jantung pertiwi. Perguruan inilah
selanjutnya yang berjalan tertatih berupaya menghidupkan semangat yang hilang
itu.
Satu hal yang menarik dari Taman Siswa, yaitu proses
pembelajaran yang dilakukan bukan cuma transfer pengetahuan seperti ketika
seseorang memasukkan minyak tanah ke jerigen. Pendidikan yang dialirkan bisa
dikatakan berpangkal dari kesadaran bahwa hanya dengan jalan pencerdasanlah
suatu bangsa bisa terbebas dari proyek raksasa pembodohan yang sistemik,
Saatnya untuk kita selami, boleh jadi ada kesamaan realita dulu dan kini,
perbedaannya sebatas siapa menjajah siapa, boleh jadi sekarang agressor
(pendidikan) itu (se)bangsa kita sendiri.
Gejala Disorientasi Pendidikan
Ketika seseorang dari strata pendidikan terendah sampai yang
paling tinggi coba ditanyakan untuk apa mengenyam pendidikan dalam satu
institusi? maka tentunya kita sudah mahfum kalau jawabannya akan sangat ala
kadarnya, kering dan rata-rata beorientasi pada materi semata. Itu bukan
sepenuhnya kesalahan pribadi mereka. Pabrik sabun pastinya juga akan
memproduksi sabun, begitu juga halnya dengan pendidikan kapitalistik-
komersial menghasilkan output siswa/mahasiswa yang sesuai cetakan asalnya.
Kecuali satu-dua yang masih tetap yakin pada kemurnian akal sehatnya untuk
berontak pada keadaan. Sadarkah kita pendidikan hari ini bukan lagi diukur dari
serangkaian proses yang dilaluinya, antara proses transferring dan sharing serta
dialog-dialog yang membuatnya lebih membumi. Tapi menjadi semacam pintu
gerbang yang mesti dilewati bagaimanapun caranya, untuk melegitimasi bahwa
orang yang telah memasukinya, mendekam sejenak di dalam, untuk kemudian
keluar dengan surat lulus, sudah cukup berkompeten untuk “dijual” di pasar
global. Jadinya akan lebih mirip barang dagangan. Maka jangan heran---seperti
halnya barang dagangan------ semuanya bisa diukur dari sejauh mana anda bisa
merogoh kocek dalam-dalam. Ketika pendidikan telah masuk dalam wilayah-
wilayah komersial tunggulah kehancuran bangunannya.
Menilik ke Unhas misalnya, kampus dimana kemajuan suatu
institusi pendidikan diukur dari seberapa banyak tegel yang dibongkar kemudian
dipasang lagi setiap harinya, semakin mantap saja mempertegas diri sebagai
lahan penjualan identitas pendidikan yang sebenar-benarnya, terang-terangan,
bahkan dilembagakan. Mega proyek BHP adalah sebuah bukti ketidak becusan
pemerintah mengurusi pendidikan kita, sampai berlepas tangan dari tanggung
jawab seperti yang diamanahkan dalam UUD, sungguh satu pelanggaran yang
terang-terangan namun selalu saja ditampik dengan alasan perbaikan kualitas
dengan jalan kemandirian institusi pendidikan, semua resources diorientasikan
untuk citra. Bersolek secantik-cantiknya dari segi infrastuktur, namun apa yang
bisa kita harapkan (meskipun sedikit) dari segi peningkatan kualitas pengajaran?
Jangan bertanya apalagi berteriak, karena anda segera akan dianggap mencoreng
citra Universitas Celakanya hal lagi malah dijadikan kebanggaan besar oleh
Birokrat kampus merah ini
Mencari spirit yang hilang
Seperti dikutip dari seorang Benjamin Bloom, bahwa (sejatinya)
pendidikan menggarap tiga wilayah vital dari pemikiran dan kepribadian
manusia: 1.Pembentukan watak dan sikap (Affective Domain) 2.
mengembangkan pengetahuan (cognitive domain) 3. melatih
keterampilan/keahlian ( psychomotoric /conative domain). Apakah pendidikan
kita hari ini cukup ampuh mewujudkannya? Pembentukan watak dan sikap, yang
bagaimana? Jelasnya bukan watak dan sikap pragmatis, apatis serta membebek
hormat di bawah bendera kapitalisasi pendidikan yang tegar berkibar.
Pengembangan pengetahuan bukan cuma sekedar teori-teori di kelas yang kaku
saja pastinya, pengembngan wilayah sasaran dan sumbangsihnya kepada rakyat
pun dinanti agar tidak merupa diri menjadi menara gading, begitu pun pada sisi
keahlian. Menimbang-nimbang jejak taman siswa dalam pergulatannya dalam
tiga fungsi pendidikan di atas, sepertinya banyak hal yang perlu disadari dari
realita pendidikan kita hari ini, bangunan pendidikan yang baik tak hanya
menghasilkan ilmuwan yang piawai dalam kepakaran, lebih dari itu, tugasnyalah
menghasilkan cendekiawan-cendekiawan yang kiritis, analitik, sekaligus solutif,
dan itu tak lahir dari rahim pendidikan yang kapitalistik dan komersial.
Kepasrahan kepada sistem yang diterapkan sebab dianggap sudah merupakan
pilihan yang terbaik, serta telah (bisa ya bisa tidak) dipikirkan matang-matang
oleh pemegang kebijakan pendidikan kita, bukanlah pilihan cerdas. Pendidikan
bukan pabrikan, yang menghasilkan produk-produk kaku dan mekanik.
Seharusnya proses pendidikan juga menitiskan nilai-nilai moral, kemanusiaan,
kebajikan alam semesta, kerendahan hati, kepekaan, cinta dan perlawanan!
You might also like
- PMK No. 43 TTG Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan PDFDocument79 pagesPMK No. 43 TTG Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan PDFKurnia Saktiawan100% (1)
- Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Langsung Obat 2019Document5 pagesKerangka Acuan Kerja Pengadaan Langsung Obat 2019bangnonoNo ratings yet
- Draft Syaratsyarat Khusus KontrakDocument6 pagesDraft Syaratsyarat Khusus KontrakbangnonoNo ratings yet
- User GuideDocument1 pageUser GuidebangnonoNo ratings yet
- Mekanisme PenganggaranDocument9 pagesMekanisme PenganggaranbangnonoNo ratings yet
- PermenPUPR07 2019Document36 pagesPermenPUPR07 2019Jito PrastikawaNo ratings yet
- USER GUIDE E-Purchasing v.5 Pejabat Pembuat KomitmenDocument66 pagesUSER GUIDE E-Purchasing v.5 Pejabat Pembuat KomitmenRyoNo ratings yet
- 06b - Kemen PUPERA - Format Proposal DAK BIdang InfrastrukturDocument61 pages06b - Kemen PUPERA - Format Proposal DAK BIdang InfrastrukturbangnonoNo ratings yet
- Draft Syaratsyarat Khusus KontrakDocument6 pagesDraft Syaratsyarat Khusus KontrakbangnonoNo ratings yet
- PermenPUPR07 2019Document36 pagesPermenPUPR07 2019Jito PrastikawaNo ratings yet
- PermenPUPR07 2019Document36 pagesPermenPUPR07 2019Jito PrastikawaNo ratings yet
- SDP Prakualifikasi Jasa Lainnya Dokumen TenderDocument94 pagesSDP Prakualifikasi Jasa Lainnya Dokumen TenderbangnonoNo ratings yet
- Hasil Riskesdas 2013Document306 pagesHasil Riskesdas 2013NdHy_Windhy_340391% (11)
- Makalah UmkmDocument22 pagesMakalah UmkmbangnonoNo ratings yet
- (CAP) 3055 - Pendampingan Pengusulan DAK Afirmasi Tahun 2019 PDFDocument10 pages(CAP) 3055 - Pendampingan Pengusulan DAK Afirmasi Tahun 2019 PDFbangnonoNo ratings yet
- Kelembagaan RS - Dirjen OtdaDocument15 pagesKelembagaan RS - Dirjen Otdadiah anjariniNo ratings yet
- Permendagri No.12 TH 2017 PDFDocument26 pagesPermendagri No.12 TH 2017 PDFKiswoyo Masadi Sukirno100% (9)
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018Document90 pagesPerpres Nomor 16 Tahun 2018Trisna Hidayat100% (4)
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018Document90 pagesPerpres Nomor 16 Tahun 2018Trisna Hidayat100% (4)
- Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2018 - 1017 - 1 PDFDocument5 pagesPeraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2018 - 1017 - 1 PDFbangnonoNo ratings yet
- PERPU Nomor 1 Tahun 2015 (Perpu1-2015 Penjelasan)Document2 pagesPERPU Nomor 1 Tahun 2015 (Perpu1-2015 Penjelasan)bangnonoNo ratings yet
- Kasus KeluargaDocument1 pageKasus KeluargabangnonoNo ratings yet
- 06b - Kemen PUPERA - Format Proposal DAK BIdang InfrastrukturDocument26 pages06b - Kemen PUPERA - Format Proposal DAK BIdang InfrastrukturAriNo ratings yet
- (CAP) 3055 - Pendampingan Pengusulan DAK Afirmasi Tahun 2019Document9 pages(CAP) 3055 - Pendampingan Pengusulan DAK Afirmasi Tahun 2019bangnonoNo ratings yet
- Gambar Sarana Air Bersih & SanitasiDocument40 pagesGambar Sarana Air Bersih & SanitasibangnonoNo ratings yet
- Permenkes No 10 Tahun 2017 Pengundangan PDFDocument8 pagesPermenkes No 10 Tahun 2017 Pengundangan PDFRobbi RustamNo ratings yet
- KS-1Document72 pagesKS-1bangnonoNo ratings yet
- Presentasi SurveilansDocument37 pagesPresentasi SurveilansbangnonoNo ratings yet
- Stiker PHBSDocument3 pagesStiker PHBSbangnonoNo ratings yet