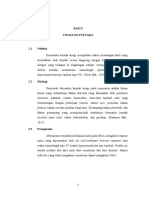Professional Documents
Culture Documents
Dermatitis Kontak Alergi
Uploaded by
Dera Fakhrunnisa RukmanaCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Dermatitis Kontak Alergi
Uploaded by
Dera Fakhrunnisa RukmanaCopyright:
Available Formats
A. Dermatitis Kontak Alergi 1.
Definisi Menurut Siregar (2004) dermatitis kontak alergi (DKA) adalah suatu dermatitis (peradangan kulit) yang timbul setelah kontak dengan alergen melalui proses sensitisasi. Menurut National Occupational Health and Safety Commision (2006) DKA adalah dermatitis yang disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas tipe lambat terhadap bahanbahan kimia yang kontak dengan kulit dan dapat mengaktivasi reaksi alergi.
2. Etiologi Penyebab dermatitis kontak alergi adalah alergen, paling sering berupa bahan kimia dengan berat molekul kurang dari 500-1000 Da, yang juga disebut bahan kimia sederhana. Dermatitis yang timbul dipengaruhi oleh potensi sensitisasi alergen, derajat pajanan, dan luasnya penetrasi di kulit (Sularsito, 2010). Berbagai faktor berpengaruh dalam timbulnya dermatitis kontak alergi. Misalnya antara lain (Sularsito, 2010): a. Faktor eksternal 1) Potensi sensitisasi alergen 2) Dosis per unit area 3) Luas daerah yang terkena 4) Lama pajanan 5) Oklusi 6) Suhu dan kelembaban lingkungan 7) Vehikulum 8) pH b. Faktor internal 1) Keadaan kulit pada lokasi kontak Contohnya ialah ketebalan epidermis dan keadaan stratum korneum. 2) Status imunologik Misal orang tersebut sedang menderita sakit, atau terpajan sinar matahari. 3) Genetik
Faktor predisposisi genetik berperan kecil, meskipun misalnya mutasi null pada kompleks gen fillagrin lebih berperan karena alergi nikel (Thyssen, 2009). 4) Status higinitas dan gizi.
3. Epidemiologi Bila dibandingkan dengan DKI, jumlah penderita DKA lebih sedikit, karena hanya mengenai orang yang keadaan kulitnya sangat peka (hipersensitif). Diramalkan bahwa jumlah DKA maupun DKI makin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah produk yang mengandung bahan kimia yang dipakai oleh masyarakat. Namun inforasi mengenai prevalensi dan insidensi DKA di masyarakat sangat sedikit, sehingga beberapa angka yang mendekati kebenaran belum didapat (Sularsito, 2010). Kejadian DKA di Amerika Serikat terhitung sebesar 7% dari penyakit yang terkait dengan pekerjaan1. Berdasarkan beberapa studi yang dilakukan, insiden dan tingkat prevalensi DKA dipengaruhi oleh allergen- allergen tertentu. Dalam data terakhir, lebih banyak perempuan (18,8%) ditemukan memiliki DKA dibandingkan laki-laki (11,5%). Namun, harus dipahami bahwa angka ini mengacu pada prevalensi DKA dalam populasi (yaitu, jumlah individu yang potensial menderita DKA bila terkena alergen), dan ini bukan merupakan angka insiden (yaitu, jumlah individu yang menderita DKA setelah jangka waktu tertentu) (Belsito, 2003). Dalam studi tentang reaktivitas Rhus, individu yang lebih muda (18 sampai 25 tahun) memiliki onset lebih cepat dan resolusi cepat untuk terjadi dermatitis dibandingkan orang tua. Kompetensi reaksi imun yang dimediasi sel T pada anak-anak masih kontroversi. Studi ini masih menganggap bahwa anak-anak jarang mengalami DKA karena sistem kekebalan tubuh yang belum matang, namun Strauss menyarankan bahwa hiporesponsifitas yang jelas pada anak-anak mungkin karena terbatasnya paparan dan bukan karena kurangnya imunitas (Belsito, 2003).
4. Patogenesis Mekanisme terjadinya kelainan kulit pada DKA adalah mengikuti respons imun yang diperantarai oleh sel (cell-mediated immune respons) atau reaksi imunologik tipe IV, suatu hipersensitivitas tipe lambat. Reaksi ini terjadi melalui dua fase, yaitu fase
sensitisasi dan fase elisitasi. Hanya individu yang telah mengalami sensitisasi dapat menderita DKA (Sularsito, 2010). Fase sensitisasi Hapten yang masuk ke dalam epidermis melewati stratum korneum akan ditangkap oleh sel Langerhans dengan cara pinositosis, dan diproses secara kimiawi oleh enzim lisosom atau sitosol serta dikonjugasikan pada molekul HLA-DR menjadi antigen lengkap. Pada awalnya sel Langerhans dalam keadaan istirahat, dan hanya berfungsi sebagai makrofag dengan sedikit kemampuan menstimulasi sel T. Tetapi, setelah keratinosit terpajan oleh hapten yang juga mempunyai sifat iritan, akan melepaskan sitokin (IL-1) yang akan mengaktifkan sel Langerhans sehingga mampu menstimulasi sel T. Aktivasi tersebut akan mengubah fenotip sel Langerhans dan meningkatkan sekresi sitokin tertentu (misalnya IL-1) secara ekspresi molekul permukaan sel termasuk MHC kelas I dan II, ICAM-1, LFA-3 dan B7. Sitokin proinflamasi lain yang dilepaskan oleh keratinosit yaitu TNF, yang dapat mengaktifasi sel T, makrofag dan granulosit, menginduksi perubahan molekul adesi sel dan pelepasan sitokin juga meningkatkan MHC kelas I dan II (Sularsito, 2010). TNF menekan produksi E-cadherin yang mengikat sel Langerhans pada epidermis, juga menginduksi aktivitas gelatinolisis sehingga memperlancar sel Langerhans melewati membran basalis bermigrasi ke kelenjar getah bening setempat melalui saluran limfe. Di dalam kelenjar limfe, sel Langerhans mempresentasikan kompleks HLA-DR-antigen kepada sel T penolong spesifik, yaitu yang mengekspresikan molekul CD4 yang mengenali HLA-DR sel Langerhans, dan kompleks reseptor sel TCD3 yang mengenali antigen yang telah diproses. Ada atau tidak adanya sel T spesifik ini ditentukan secara genetik (Sularsito, 2010). Sel Langerhans mensekresi IL-1 yang menstimulasi sel-T untuk mensekresi IL-2 dan mengekspresi reseptor-IL-2 (IL-2R). Sitokin ini akan menstimulasi proliferasi sel T spesifik, sehingga menjadi lebih banyak. Turunan sel ini yaitu sel T memori (sel T teraktivasi) akan meninggalkan kelenjar getah bening dan beredar keseluruh tubuh. Pada saat tersebut individu menjadi tersensitisasi. Fase ini rata-rata berlangsung selama 2-3 minggu (Sularsito, 2010).
Menurut konsep danger signal (sinyal bahaya) bahwa sinyal antigenik murni suatu hapten cenderung menyebabkan toleransi, sedangkan sinyal iritannya menimbulkan sensitisasi. Dengan demikian terjadinya sensitisasi kontak bergantung pada adanya sinyal iritan yang dapat berasal dari alergen kontak sendiri, dari ambang rangsang yang rendah terhadap respons iritan, dari bahan kimia inflamasi pada kulit yang meradang, atau kombinasi dari ketiganya. Jadi sinyal bahaya yang menyebabkan sensitisasi tidak berasal dari sinyal antigenik sendiri, melainkan dari iritasi yang menyertainya. Suatu tindakan mengurangi iritasi akan menurunkan potensi sensitisasi (Sularsito, 2010). Fase elisitasi Fase kedua (elisitasi) hipersensitivitas tipe lambat terjadi pada pajanan ulang alergen (hapten). Seperti pada fase sensitisasi, hapten akan ditangkap oleh sel Langerhans dan diproses secara kimiawi menjadi antigen, diikat oleh HLA-DR kemudian diekspresikan di permukaan sel. Selanjutnya kompleks HLA-DR-antigen akan dipresentasikan kepada sel T yang telah tersensitisasi (sel T memori) baik di kulit maupun di kelenjar limfe sehingga terjadi proses aktivasi. Di kulit proses aktivasi lebih kompleks dengan hadirnya sel-sel lain. Sel Langerhans mensekresi IL-1 yang menstimulasi sel T untuk memproduksi IL-2 dan mengekspresi IL-2R, yang akan menyebabkan proliferasi dan ekspansi populasi sel T di kulit. Sel T teraktivasi juga mengeluarkan IFN yang akan mengaktifkan keratinosit mengekspresi ICAM-1 dan HLA-DR. Adanya ICAM-1 memungkinkan keratinosit untuk berinteraksi dengan sel T dan leukosit yang lain yang mengekspresi molekul IFA-1. Sedangkan HLA-DR memungkinkan keratinosit untuk berinteraksi langsung dengan sel T CD4+, dan juga memungkinkan presentasi antigen kepada sel tersebut. HLA-DR juga dapat merupakan target sel T sitotoksik pada keratinosit. Keratinosit menghasilkan juga sejumlah sitokin antara lain IL-1, IL-6, TNF, dan GMCSF, semuanya dapat mengaktivasi sel T. IL-1 dapat menstimulasi keratinosit menghasilkan eikosanoid. Sitokin dan eikosanoid ini akan mengaktifkan sel mas dan makrofag. Sel mas yang berada di dekat pembuluh darah dermis akam melepaskan antara lain histamin, berbagai jenis faktor kemotaktik, PGE2 dan PGD2, dan leukotrien B4 (LTB4). Eikosanoid baik yang berasal dari sel mas (prostaglandin) maupun dari keratinosit atau leukosit menyebabkan dilatasi vaskuler dan meningkatkan permeabilitas
sehingga molekul laut seperti komplemen dan kinin mudah berdifusi ke dalam dermis dan epidermis. Selain itu faktor kemotaktik dan eikosanoid akan menarik neutrofil, monosit dan sel darah lain dari pembuluh darah masuk ke dalam dermis. Rentetan kejadian tersebut akan menimbulkan respons klinik DKA. Fase elisitasi umumnya
berlangsung antara 24-48 jam (Sularsito, 2010).
Gambar 1. Patogenesis DKA
5. Gejala Klinis Penderita umumnya mengeluh gatal. Kelainan kulit bergantung pada keparahan dermatitis dan lokalisasinya. Pada yang akut dimulai dengan bercak eritematosa yang berbatas jelas kemudian diikuti edema, papulovesikel, vesikel atau bula. Vesikel atau bula dapat pecah menimbulkan erosi dan eksudasi (basah). DKA akut di tempat tertentu, misalnya kelopak mata, penis, skrotum, eritema dan edema lebih dominan daripada vesikel. Pada yang kronis terlihat kulit kering, berskuama, papul, likenifikasi dan mungkin jyga fisur, batasnya tidak jelas. Kelainan ini sulit dibedakan dengan dermatitis kontak iritan kronis; mungkin penyebabnya campuran. DKA dapat meluas ke tempat lain, misalnya dengan cara autosensitisasi. Skalp, telapak tangan dan kaki relatif resistenterhadap DKA (Sularsito, 2010).
6. Penegakan Diagnosis a. Anamnesis Dari anamnesis dapat ditanyakan mengenai kontaktan yang dicurigai didasarkan kelainan kulit, selain itu ditanyakan pula riwayat pekerjaan, hobi, obat topikal yang pernah digunakan, obat sistemik, kosmetika, bahan-bahan yang diketahui
menimbulkan alergi, penyakit kulit yang pernah dialami, riwayat atopi, baik dari yang bersangkutan maupun keluarganya (Sularsito, 2010). b. Pemeriksaan Fisik Penampilan klinis DKA dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan durasi. Pada kebanyakan kasus, erupsi akut ditandai dengan macula dan papula eritema, vesikel, atau bula, tergantung pada intensitas dari respon alergi. Namun, dalam DKA akut di daerah tertentu dari t ubuh, seperti kelopak mata, penis, dan skrotum, eritema dan edema biasanya mendominasi dibandingkan vesikel. Batas-batas dermatitis umumnya tidak tegas. DKA pada wajah dapat mengakibatkan pembengkakan periorbital yang menyerupai angioedema. Pada fase subakut, vesikel kurang menonjol, dan pengerasan kulit, skala, dan lichenifikasi dini bisa saja terjadi. Pada DKA kronis hampir semua kulit muncul scaling, lichenifikasi, dermatitis yang pecahpecah (membentuk fisura), dengan atau tanpa papulovesikelisasi yang menyertainya (Belsito, 2003; Scheman, 2002).
Gambar 2. Dermatitis kontak alergi
c. Pemeriksaan Penunjang 1) Uji Tempel Tempat untuk melakukan uji tempel biasanya di punggung. Bahan yang secara rutin dan dibiarkan menempel di kulit, misalnya kosmetik, pelembab, bila dipakai untuk uji tempel, dapat langsung digunakan apa adanya. Bila menggunakan bahan yang secara rutin dipakai dengan air untuk membilasnya, misalnya sampo, pasta gigi, harus diencerkan terlebih dahulu. Bahan yang tidak larut dalam air diencerkan atau dilarutkan dalam vaselin atau minyak mineral. Produk yang diketahui bersifat iritan, misalnya deterjen, hanya boleh diuji bila diduga keras penyebab alergi. Apabila pakaian, sepatu, atau sarung tangan yang dicurigai penyebab alergi, maka uji tempel dilakukan dengan potongan kecil bahan tersebut yang direndam dalam air garam yang tidak dibubuhi bahan pengawet, atau air, dan ditempelkan di kulit dengan memakai Finn chamber, dibiarkan sekurang-kurangnya 48 jam. Perlu diingat bahwa hasil positif dengan alergen bukan standar perlu kontrol (5 sampai 10 orang) untuk menyingkirkan kemungkinan terkena iritasi (Sularsito, 2010).
Gambar 3. Aplikasi Uji Tempel pada pasien
Setelah dibiarkan menempel selama 48 jam, uji tempel dilepas. Pembacaan pertama dilakukan 15-30 menit setelah dilepas, agar efek tekanan bahan yang diuji telah menghilang atau minimal. Hasilnya dicatat seperti berikut (Sularsito, 2010):
1 = reaksi lemah (nonvesikular) : eritema, infiltrat, papul (+) 2 = reaksi kuat : edema atau vesikel (++) 3 = reaksi sangat kuat (ekstrim) : bula atau ulkus (+++) 4 = meragukan : hanya makula eritematosa 5 = iritasi : seperti terbakar, pustul, atau purpura (IR) 6 = reaksi negatif (-) 7 = excited skin 8 = tidak dites (NT=non tested)
Gambar 4. Hasil Uji Tempel setelah 72 jam. A: Hasil uji positif terhadap picaridin (KBR) 2,5% B: Hasil uji positif terhadap methyl glucose diolate (MGD) 10% Pembacaan kedua perlu dilakukan sampai satu minggu setelah aplikasi, biasanya 72 atau 96 jam setelah aplikasi. Pembacaan kedua ini penting untuk membantu membedakan antara respons alergik atau iritasi, dan juga
mengidentifikasi lebih banyak lagi respons positif alergen. Hasil positif dapat bertambah setelah 96 jam aplikasi, oleh karena itu perlu dipesan kepada pasien untuk melapor, bila hal itu terjadi sampai satu minggu setelah aplikasi (Sularsito, 2010). Untuk menginterpretasi hasil uji tempel tidak mudah. Interpretasi dilakukan setelah pembacaan kedua. Respon alergik biasanya menjadi lebih jelas antara pembacaan kesatu dan kedua, berawal dari +/- ke + atau ++ bahkan ke +++
(reaksi tipe crescendo), sedangkan respon iritan cenderung menurun (reaksi tipe decrescendo) (Sularsito, 2010). 2) Pemeriksaan Histopalogi Pemeriksaan histopatologi pada dermatitis kontak dapat ditemukan gambaran sebagai berikut (Sularsito, 2010): a) Epidermis: Hiperkeratosis, serum sering terjebak dalam stratum korneum, hiperplastik, akantosis yang luas serta spongiosis, yang kadang vesikuler. Manifestasi dini ditandai dengan penonjol dari jembatan antar sel di lapisan spinosus kemudian ada epidermotropism dari limfosit yang muncul normal. b) Dermis: Limfosit perivesikuler, eosinofil: bervariasi, muncul awal dan karena sebab alergi serta edema
Gambar 5. Histopatologik dermatitis kontak alergi
DAFTAR PUSTAKA
Belsito DV. 2003. Allergic Contact Dermatitis dalam Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, Austen KF, Goldsmith LA, Katz SI (eds) Fitzpatricks Dermatology in General Medicine 6th ed. New York: The McGraw-Hill. Scheman AJ. 2002. Contact Dermatitis dalam Grammer LC, Greenberger PA (eds) Pattersons Allergic Disease 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Siregar, R.S,. 2004. Atlas Berwarna Saripati Penyakit Kulit Edisi 2. Jakarta: EGC Sularsito, Sri Adi dan Suria Djuanda. 2010. Dermatitis dalam Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin Edisi 6. Jakarta : FKUI Thyssen, Jacob Pontoppidan. 2009. The Prevalence and Risk Factors of Contact Allergy in the Adult General Population. Denmark : National Allergy Research Centre, Departement of Dermato-Allergology, Genofte Hospital, University of Copenhagen . .
You might also like
- Laporan Kasus Dka Kulit Dan KelaminDocument22 pagesLaporan Kasus Dka Kulit Dan KelaminNana Novia SiktianiNo ratings yet
- PaDocument2 pagesPaBu NagiahNo ratings yet
- Neurobiologi KulitDocument14 pagesNeurobiologi Kulitchristia_iskandarNo ratings yet
- Systemic Lupus Erythematosus (Sle)Document28 pagesSystemic Lupus Erythematosus (Sle)Kristina Anita Meilani100% (1)
- Referat Pemeriksaan KulitDocument96 pagesReferat Pemeriksaan KulitFatimah FitrianiNo ratings yet
- DermatitisDocument26 pagesDermatitisDianNo ratings yet
- Tenosinovitis Supuratif Musculo BelaDocument3 pagesTenosinovitis Supuratif Musculo BelaBeladiena Citra SiregarNo ratings yet
- Dermatitis Kontak AlergiDocument26 pagesDermatitis Kontak AlergiRahmi FikriahNo ratings yet
- Skin Prick TestDocument6 pagesSkin Prick TestnuniatmandaNo ratings yet
- KulitDocument12 pagesKulitputriNo ratings yet
- PBL Bercak PutihDocument37 pagesPBL Bercak PutihAlfina Alfiani100% (1)
- Liken PlanusDocument14 pagesLiken PlanusbungacitralestariNo ratings yet
- DD Dermatitis Dan DiagnosisDocument3 pagesDD Dermatitis Dan DiagnosisNurul NajibNo ratings yet
- Referat - Pemeriksaan Penunjang KulitDocument24 pagesReferat - Pemeriksaan Penunjang Kulitrajess100% (1)
- Patogenesis HipersensitivitasDocument4 pagesPatogenesis HipersensitivitasGinoviaTrimaharaniNo ratings yet
- Napkin Eczema UpdateDocument29 pagesNapkin Eczema UpdaterusydeeNo ratings yet
- Klasifikasi Lupus EritematosusDocument9 pagesKlasifikasi Lupus Eritematosusthejoys_manNo ratings yet
- 1.1. Punya JejeDocument3 pages1.1. Punya JejeAkhtar SredNo ratings yet
- Dermatitis Numularis - FixDocument18 pagesDermatitis Numularis - Fixm.avif ababilNo ratings yet
- Dermatitis Kontak IritanDocument4 pagesDermatitis Kontak Iritanaisyah bNo ratings yet
- Dermatitis Kontak Alergi Dan Dermatitis Kontak IritanDocument4 pagesDermatitis Kontak Alergi Dan Dermatitis Kontak IritanHendrikus Surya Adhi Putra100% (1)
- Referat Reaksi KustaDocument24 pagesReferat Reaksi KustaSelena SeptianriNo ratings yet
- DermaDocument6 pagesDermaepidersNo ratings yet
- Anam + PF + PP VenerologiDocument68 pagesAnam + PF + PP VenerologighisqyNo ratings yet
- Hubungan Penyakit Sistemik Dengan Penyakit Kulit FixDocument26 pagesHubungan Penyakit Sistemik Dengan Penyakit Kulit FixKevin PinartoNo ratings yet
- Dermatomiositis Adalah Miopati Inflamasi IdiopatikDocument4 pagesDermatomiositis Adalah Miopati Inflamasi IdiopatikCristino NayNo ratings yet
- Erupsi Alergi ObatDocument17 pagesErupsi Alergi ObatFazlia AdamNo ratings yet
- Alergodermi 1Document2 pagesAlergodermi 1ghaliNo ratings yet
- DermatitisDocument14 pagesDermatitisFadia Rasyiddah0% (1)
- Fitzpatrick (Part 1 Terjemahan)Document2 pagesFitzpatrick (Part 1 Terjemahan)benedictusNo ratings yet
- REFERAD Reaksi KustaDocument23 pagesREFERAD Reaksi KustaSilviana SariNo ratings yet
- Dermatitis Kontak IritanDocument17 pagesDermatitis Kontak IritanAndi Yaumil Aliyah TriningdityaNo ratings yet
- Hipersensitivitas Tipe 3Document3 pagesHipersensitivitas Tipe 3yulia melisa ritongaNo ratings yet
- Kulit TebalDocument3 pagesKulit TebalNiken KhuzaimaNo ratings yet
- Referat SSSSDocument19 pagesReferat SSSSIndraArdanaNo ratings yet
- Veruka VulgarisDocument12 pagesVeruka VulgarisDini Anggreini WahyudiNo ratings yet
- Hipopigmentasi Pasca InflamasiDocument1 pageHipopigmentasi Pasca Inflamasiatikaindahsari0% (1)
- Erupsi ObatDocument32 pagesErupsi ObatBenita Putri MDNo ratings yet
- SLE (Systemic Lupus Erithematosus)Document18 pagesSLE (Systemic Lupus Erithematosus)adiNo ratings yet
- Presentasi Eritema MultiformDocument18 pagesPresentasi Eritema MultiformLeonita Budi UtamiNo ratings yet
- Kasus Alergi MakananDocument12 pagesKasus Alergi MakananEva KhairunnisaNo ratings yet
- Batuk Berdahak Dan Sesak Nafas PneumoniaDocument26 pagesBatuk Berdahak Dan Sesak Nafas PneumoniaRiska ULy100% (2)
- Reaksi KustaDocument20 pagesReaksi KustaMonazzt AsshagabNo ratings yet
- Patofisiologi Gatal PruritusDocument15 pagesPatofisiologi Gatal PruritusNila hermawatiNo ratings yet
- Referat Paronikia WORDDocument18 pagesReferat Paronikia WORDTiti Anjasmoro100% (1)
- LP Eritroderma Tn.aDocument10 pagesLP Eritroderma Tn.aVhyra MakaramaNo ratings yet
- Konjungtivitis AlergiDocument29 pagesKonjungtivitis AlergiSiti Ardina SariNo ratings yet
- UrtikariaDocument21 pagesUrtikariaLuthfi Akhyar SpiritNo ratings yet
- Efloresensi KulitDocument12 pagesEfloresensi KulitDini YulidarNo ratings yet
- Case 6 MakalahDocument5 pagesCase 6 Makalahrahmanita kamilaNo ratings yet
- Staphylococcal Scalded Skin SyndromeDocument7 pagesStaphylococcal Scalded Skin SyndromeiNo ratings yet
- Fase Fase DBDDocument7 pagesFase Fase DBDRachmawan FiryanaNo ratings yet
- Komplikasi Keratitis BDocument11 pagesKomplikasi Keratitis BSepti Yanti AmaliaNo ratings yet
- Dermatitis Kontak Alergik (DKA) 1. EpidemiologiDocument11 pagesDermatitis Kontak Alergik (DKA) 1. EpidemiologiJamaluddinLukmanNo ratings yet
- Laporan Pendahuluan Dermatitis Kontak AlergiDocument25 pagesLaporan Pendahuluan Dermatitis Kontak AlergiMarlin Hemri RanglalinNo ratings yet
- Lapsus DKIDocument28 pagesLapsus DKIDevi_dvdvNo ratings yet
- BAB II FIX Patogenesis DKADocument16 pagesBAB II FIX Patogenesis DKABagas AnandaNo ratings yet
- Referat Dka Dki LarasDocument24 pagesReferat Dka Dki LarasnurindryanikusumadewNo ratings yet
- Dermatitis Kontak AlergikaDocument14 pagesDermatitis Kontak AlergikaMuhamad Fadlie SetyajiNo ratings yet
- Askep DermatitisDocument24 pagesAskep DermatitisMustika Dwi AgustinNo ratings yet
- BPH DeraDocument19 pagesBPH DeraDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Presus Retensi Urin Ec BPHDocument40 pagesPresus Retensi Urin Ec BPHDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Primary HeadacheDocument20 pagesPrimary HeadacheDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- SepsisDocument23 pagesSepsisDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Presus EklampsiaDocument38 pagesPresus EklampsiaDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- BPH DeraDocument34 pagesBPH DeraDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Patofisiologi Hipertensi Dalam KehamilanDocument3 pagesPatofisiologi Hipertensi Dalam KehamilanDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Etiologi Dan Klasifikasi AnemiaDocument6 pagesEtiologi Dan Klasifikasi AnemiaDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Portofolio Anemia HemolitikDocument10 pagesPortofolio Anemia HemolitikDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- PORTOFOLIO Retensi UrineDocument6 pagesPORTOFOLIO Retensi UrineDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Patomekanisme HemolisisDocument2 pagesPatomekanisme HemolisisDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Portofolio Anemia HemolitikDocument10 pagesPortofolio Anemia HemolitikDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Case Presentation EklampsiaDocument37 pagesCase Presentation EklampsiaDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Portofolio EklampsiaDocument11 pagesPortofolio EklampsiaDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Pedoman TataLaksana Gagal Jantung - 2015Document56 pagesPedoman TataLaksana Gagal Jantung - 2015novaladrian100% (3)
- Pedoman Tatalksana DislipidemiaDocument76 pagesPedoman Tatalksana DislipidemiaGideon Abdi Tombokan100% (1)
- Racun Ular BerbisaDocument5 pagesRacun Ular BerbisaIlham Hilmi MutaqinNo ratings yet
- Proposal Mini ProjectDocument29 pagesProposal Mini ProjectDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Mini Project PresentationDocument74 pagesMini Project PresentationDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Mini ProjectDocument65 pagesMini ProjectDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- PpokDocument32 pagesPpokOm ZainulNo ratings yet
- Af PerkiDocument99 pagesAf PerkiTri Widhiyono Pamungkas0% (1)
- Mini Project PresentationDocument74 pagesMini Project PresentationDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Pedoman Diagnosis Dan Penatalaksanaan Asma Di IndonesiaDocument105 pagesPedoman Diagnosis Dan Penatalaksanaan Asma Di IndonesiaFadhli Quzwain100% (3)
- Presentasi Kasus VaginitisDocument37 pagesPresentasi Kasus VaginitisDera Fakhrunnisa Rukmana67% (3)
- 2015 AHA Guidelines Highlights Indonesian PDFDocument36 pages2015 AHA Guidelines Highlights Indonesian PDFRafles SimbolonNo ratings yet
- Limfoma MalignaDocument20 pagesLimfoma MalignaDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Presus Tumor LidahDocument18 pagesPresus Tumor LidahDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- REFERAT UrologiDocument20 pagesREFERAT UrologiDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet
- Limfoma MalignaDocument20 pagesLimfoma MalignaDera Fakhrunnisa RukmanaNo ratings yet