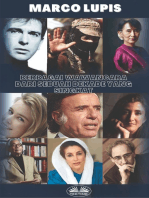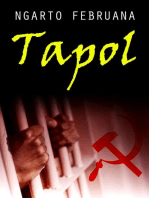Professional Documents
Culture Documents
Caping + Kolom Tempo 17.8.2014-23.8.2014
Uploaded by
ekho1090 ratings0% found this document useful (0 votes)
31 views39 pagesdiambil dari situs tempo.co
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentdiambil dari situs tempo.co
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
31 views39 pagesCaping + Kolom Tempo 17.8.2014-23.8.2014
Uploaded by
ekho109diambil dari situs tempo.co
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 39
Digul
Senin, 18 Agustus 2014
Tanah Merah, sebuah desa cantik di atas Sungai Digul---Surat Van der Plas kepada Van
Mook, 18 April 1943
Di bekas wilayah hukuman itu saya melangkah masuk ke halaman penjara tua yang didirikan
pemerintah kolonial untuk para tahanan politik pada tahun 1920-an: ruang sempit, kawat
berduri di atas tembok, sel di bawah tanah tempat orang hukuman yang bandel dikurung. Di
bawah matahari yang terik dan udara yang gerah di Boven Digul, yang sama sekali tak mirip
"desa cantik", sejauh mana yang terhukum bisa bertahan?
Saya tergetar, sebentar. Pernahkah ayah saya disekap di bui itu? Saya tak bisa
membayangkannya. Saya tak pernah dengar ceritanya. Ia dibuang ke tempat yang terpencil
itu, bersama ibu saya, setelah dipenjara dan ditahan di rumah sejak pemberontakan tahun
1927. Saya baru dilahirkan sekitar sembilan tahun semenjak mereka dipulangkan ke Jawa.
Bapak tak sempat bercerita banyak tentang masa lalunya kepada saya: ia ditembak mati
tentara Belanda ketika saya berumur lima tahun. Ibu terlalu sibuk membesarkan kami. Yang
membekas dari Digul pada keluarga kami sesuatu yang tanpa kata-kata: salah satu kakak lahir
di pembuangan itu.
Mungkin itu sebabnya di keluarga kami, masa lalu itu jarang jadi percakapan.
Jangan-jangan Digul sebenarnya bukanlah sebuah drama yang menarik untuk dikisahkan
berulang kali?
Ibu cuma kadang-kadang bercerita tentang penduduk Papua setempat yang disebut "orang
Kaya-Kaya" yang datang dari hutan, "para hantu rimba" yang ikut membantu kerja, dan
memanggil Ibu "mama kuminis" dan Bapak "papa kuminis"; tentang para tahanan politik
yang dengan sengaja membuang obat yang didapat dari Rumah Sakit Wilhelmina (dengan
harapan pemerintah kolonial akan bangkrut membiayai kamp tahanannya); tentang orang
buangan yang berani, terutama seorang pemuda bernama Salim.
Kakak saya pernah menyebutkan, dalam album keluarga ada potret Ayah di antara teman-
temannya dalam kamp, tapi potret itu lenyap ketika pasukan Belanda menggeledah rumah
kami dan Ayah ditangkap, kemudian dieksekusi.
Kenangan mirip potret yang kabur, bahkan lenyap. Ia masa lalu yang berubah bersama yang
terjadi di hari ini. Dalam A Certain Age, sebuah buku "sejarah" yang memukau sebab tak
lazim, Rudolf Mrazek mengeluarkan catatan wawancaranya dengan bekas-bekas buangan
Digul. Kita ketemu dengan Sukarsih Moerwoto, misalnya. Aktivis pergerakan nasional ini
yang selama tujuh tahun dibuang merasa bahwa di Digul "tak cukup ada makanan. Tak cukup
ada kebahagiaan". Tapi ia juga mengatakan tak ada rasa tertekan. Tak ada kawat berduri di
sekitar kamp mereka. "Kami sering berpiknik, dan kadang-kadang naik kanu di sungai. Kami
mendayung dan kemudian makan siang."
Ada surat kabar yang datang tiap enam pekan, dan ketika Bung Hatta diinternir di sana, ia
tidak hanya membawa enam peti buku, tapi juga sebuah gramofon. Hatta mengajar ekonomi,
Sjahrir, kadang-kadang, mengajar bahasa Inggris dan menyanyi.
Seperti diuraikan Mrazek dalam tulisan yang lain, "Sjahrir in Boven Digoel", dalam buku
Making Indonesia (editor Daniel S. Lev dkk.), di kamp itu ada klub debat; para tahanan
mendiskusikan buku Ramsay MacDonald, Socialism: Critical and Constructive, dan karya
Firmin Riz, L'energie americaine. Mereka membentuk grup gamelan dan musik Sumatera,
bahkan ada kelompok jazz yang disebut "Digoel Buseneert". Pelajaran bahasa Inggris maju;
di sana-sini ada penawaran jasa laundry dan barbershop.
Ada sekolah buat anak-anak: sekolah Katolik dan Protestan, dan sebuah sekolah yang diajar
seorang bekas tokoh komunis, Soetan Said Ali, yang dalam sebuah laporan resmi disebut
"sebuah sekolah kecil komunis di Tanah Tinggi".
Tapi tentu tak semua diperkenankan berkembang. Para tahanan yang keras kepala dipisahkan
di tempat yang jauh. Tokoh PKI Aliarcham, salah satu pelopor pemberontakan tahun 1926,
adalah salah satunya. Ia meninggal di tempat sunyi itu.
Pada akhirnya, Digul adalah proyek penjinakan. Gubernur Jenderal De Graeff
mengemukakan tujuan itu ketika kamp itu dibuka: "Ambisi politik yang ada harus diatasi
dengan ketertarikan akan hal-hal yang lebih bersifat rumah tangga dan sosial."
Tapi bagaimana mungkin penjinakan ala borjuis itu terjadi ketika Digul, betapapun jauh
bedanya dengan kamp konsentrasi Hitler, tetap menunjukkan sifat dasar kekuasaan. Apalagi
kekuasaan kolonial: sebuah kekuatan yang mengecualikan diri dari tuntutan kesetaraan. Ia
membangun kamp, ia memisah-misahkan sesama manusia. Tapi tiap kali tuntutan melawan
itu tak bisa diredam, dan politik bangkit.
Maka apa pun desain pemerintah Hindia Belanda, sebuah kamp selalu menyiapkan hari
akhirnya sendiri. Dalam sejarah kolonialisme di Indonesia, hari akhir itu 17 Agustus 1945.
Goenawan Mohamad
Elegi Assaat
Senin, 18 Agustus 2014
Muhidin M. Dahlan, kerani @warungarsip
Kehadiran Assaat dalam sejarah Republik Indonesia, sebagai (acting) Presiden RI, tak
ubahnya seperti elegi, kalau bukan tragedi. Pasalnya, sosok yang lahir di Agam, Sumatera
Barat, 18 September 1904, ini adalah "noktah semangka" (PSI-Masjumi) yang tak boleh ada
dalam sejarah kepresidenan RI.
Hitunglah, berapa jumlah presiden RI dari Agustus 1945 hingga Oktober 2014. Maka
jawaban umum adalah enam: Sukarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid,
Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sosok Assaat tak ada di sana.
Jika kita merujuk ke kronik Indonesia, setelah nota kesepakatan Konferensi Meja Bundar
(KMB) ditandatangani pada 27 Desember 1949, Assaat ditunjuk sebagai Presiden Republik
Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, menggantikan Sukarno yang dalam waktu
bersamaan menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).
Walau hanya menjabat hingga 15 Agustus 1950, Assaat adalah salah satu patok penting
ketika Indonesia sedang dalam pergolakan perang, pertarungan diplomasi, dan pencarian
bentuk negara. Assaat menjadi saksi bagaimana Republik berada dalam simpang revolusi
yang pelik menuju liberalisme.
Setelah Presiden RIS Sukarno dilantik, sebagaimana kronik koran Tanah Air edisi 19
Desember 1949 menuliskan, Assaat yang menjadi pejabat Presiden RI segera mengambil
tindakan pertama mengubah model parlemen menjadi parlemen nasional, yang memberi
tempat bagi kaum progresif.
RI, yang menjadi negara bagian dari RIS, adalah ejawantah bahwa kronik sejarah RI yang
lahir dari Revolusi Agustus 1945 tak terputus. Sebab, RIS yang merupakan kemenangan
terbaru dari Belanda di meja diplomasi itu memiliki bentuk dan konstitusi sendiri yang
berbeda dengan konstitusi RI 18 Agustus 1945. Beruntunglah ada Assaat. Rantai sejarah RI
itu tetap tersambung dalam kekuasaannya yang berumur sangat pendek, 9 bulan.
Namun revolusi memakan anaknya sendiri. Ketika Demokrasi Terpimpin mulai dipraktekkan
dan ketidakpuasan merebak di daerah, terutama di Sumatera Barat, Assaat memilih masuk
hutan. Ia bergabung dengan gerilyawan PSI-Masjumi (hijau-merah, semangka) yang
menamakan diri Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dan nama Assaat
pun padam bersama ditumpasnya gerakan ini dalam operasi militer yang sistematis dan
masif.
Pergantian rezim dari Sukarno ke Soeharto menjadi momentum dan kesempatan baru bagi
Assaat. Ia muncul lagi untuk pertama kalinya ke publik di hari penguburan sahabat
politiknya, Sjahrir. Bersama Sjafruddin Prawiranegara-sekondan politiknya di PRRI-Assaat
berdiri di sisi kuburan Sutan Sjahrir saat Hatta mengucapkan kata-kata pungkas sebagaimana
dicatat koran Pelopor Baru, 20 April 1966: "Sjahrir berjuang untuk Indonesia merdeka, tetapi
ia sakit dan meninggal dalam tahanan Republik Indonesia jang merdeka ... bukankah itu suatu
tragedi?"
Assaat-selain Sjahrir dan Sjafruddin-adalah nama di tapal revolusi yang menjadi musuh
politik dan dipenjarakan Sukarno sejak 1962 hingga 1966. Pergantian rezim tak jua
memulihkan nasib Assaat. Sejarah yang disusun Sukarno dan diwariskan hingga kini tak
pernah lagi memberi tempat bagi Assaat untuk dikenang dalam memori kepresidenan,
lantaran keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Bahkan hingga diresmikannya
Museum Presiden pada Agustus 2014, Assaat tak pernah ada di sana.
Antara Relawan dan Aktivis
Senin, 18 Agustus 2014
Seno Gumira Ajidarma, wartawan
Relawan, dengan mukjizat kata "rela" di sana, telah menjadi keberdayaan sosial yang
penting. Yakni ketika ia terbukti mampu mengorganisasikan dirinya sendiri menjadi gejala
umum yang berpengaruh, sehingga tak kalah mangkus dan sangkil untuk bersaing dengan
mesin politik ampuh dari sebuah partai.
Gerakan para relawan memang suatu bentuk kepedulian, tapi yang menuntut untuk
diwujudkan secara konkret: waktu, dana, tenaga, sebagai bentuk keberpihakan berdasarkan
tujuan bersama yang mengatasi tujuan partai, berdasarkan kesadaran untuk bersikap radikal-
yakni berpihak dengan total, tanpa kompromi apa pun.
Apakah ini yang disebut aktivisme?
Dalam bahasa Jerman, istilah "Aktivismus" mulai muncul pada akhir Perang Dunia I, untuk
menandai prinsip keterlibatan politik secara aktif oleh kaum intelektual. Dengan kata lain,
privilese intelektual untuk berada di menara gading, dan cukup "hanya berpikir" saja, tentu
harus ditinggalkan. Jadi, bukan hanya pemikiran, tapi juga usaha untuk membela dan
mewujudkan pemikiran itulah yang membuatnya disebut aktivisme.
Dalam konteks Jerman, Aktivismus ini merupakan bagian dari ekspresionisme, yang sayap
politiknya waktu itu kuat. Biasanya dihubungkan dengan Kurt Hiller, pengarah organisasi
Neuer Club yang menaungi para penyair ekspresionis awal; maupun Franz Pfemfert, pendiri
majalah Die Aktion pada 1911 yang sangat politis.
Lantas, diingat maupun tidak asal-usulnya ini, aktivisme dipahami sebagai sikap berapi-api
terhadap aksi politik, yang menghasilkan praktek politik dengan semangat tinggi-yang
mengandaikan terdapatnya peran khusus bagi aktivis. Ini tercatat berlangsung dalam gerakan
revolusi, dan terutama penting dalam partai-partai politik radikal. Tidak aneh jika bentuk
ekstremnya adalah penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik.
Bagi aliran politik sayap kiri, istilah militan disebut secara bergantian dalam pengertian yang
sama dengan aktivis, tapi yang pertama mengacu dengan selayaknya kepada derajat
radikalisme dalam politik seseorang, sedangkan yang kedua kepada derajat keterlibatannya-
jadi, meskipun berkorelasi, keduanya dapat dipisahkan. Menurut Leopold Labedz, aktivis di
semua partai lebih peduli kepada kemurnian deklarasi daripada para anggotanya, seperti
terjadi pada semua partai komunis sebelum mereka berkuasa, dan peran kaum aparat menjadi
sangat penting (Bullock & Tromley, 1999: 7).
Dengan berbagai pengertian ini, kaum militan maupun para aktivis jelas adalah juga relawan.
Tapi, yang berbeda dari relawan, mereka merupakan anggota partai. Sedangkan relawan,
selain bukan anggota partai, memang tidak mengacukan kegiatannya kepada ideologi partai,
melainkan kepada ideologi dalam pengertian yang lebih luas, dengan ideologi partai tercakup
di dalamnya. Ini berarti, meskipun relawan tidak merupakan anggota partai, sebetulnya lebih
radikal karena keterikatan ideologisnya berada di atas kepentingan partai.
Dalam proses politik praktis, keduanya bisa bersimbiosis dalam tujuan-tujuan praktis pula,
ketika para relawan seperti mendapatkan institusi praktis bagi cita-cita ideologisnya, dan para
aktivis jelas teruntungkan dalam perebutan kursi kekuasaan. Namun simbiosis ini bisa
berhenti justru ketika sudah menang dan berkuasa, ketika dalam perkembangannya tujuan-
tujuan praktis itu tidak sejalan dengan cita-cita ideologis. Di satu pihak bisa merupakan
fungsi kontrol yang berguna, di lain pihak bisa mengganggu pekerjaan praktis. Demikianlah,
bulan madu yang manis berpotensi menjadi kenyataan pahit, apabila partai yang
termenangkan tidak dapat mempertahankan integritasnya dalam praktek kekuasaan.
Artinya, terdapat proses politik maupun proses budaya di sini, dengan proses politik sebagai
salah satu faktor yang membentuk proses budaya itu. Sebagai bagian dari proses budaya,
sebetulnya proses politik merupakan bagian dari gerakan kebudayaan yang berlangsung
bersama aktivisme para relawan. Tapi, ketika memegang tampuk kekuasaan, kepentingan
politik bisa sangat menentukan proses budaya itu. Dengan demikian, menjadi penting bahwa
kepentingan politik-terutama bila berarti kepentingan partai-tetap tinggal 0 persen dalam
penyelenggaraan kekuasaan.
Disebutkan, "Posisi kebudayaan dalam menghadapi strategi tidak menyimpulkan suatu
strategi kebudayaan. Apa yang telah terjadi hanyalah dukungan terbatas kepada strategi tanpa
melanggar prinsip bahwa tiada paksaan dalam kebudayaan." (Soekito, 04/01/1985: 4). Ini
menunjukkan betapa proses budaya memang sangat sensitif terhadap proses politik.
Keputusan relawan untuk mendukung aktivis partai bukanlah keputusan strategis-mereka
baru berstrategi setelah terlibat pusaran politik. Tapi relawan jelas berpolitik hanya untuk
sementara waktu.
Kepanduan dan Mangkunegara VII
Senin, 18 Agustus 2014
Heri Priyatmoko, alumnus pascasarjana sejarah FIB, UGM
Saban kali memperingati Hari Pramuka, nama Lord Baden Powell sekonyong-konyong
melintas dalam benak anak negeri. Pertanyaan penting: apakah kita tidak punya tokoh bangsa
yang patut dikenang dan ditutur-ulangkan dalam riwayat dunia kepanduan?
Mari kita buka almari sejarah yang berdebu untuk membedah bundelan arsip lokal yang
kusam di Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran. Bakal kita temukan kisah historis
keberanian Mangkunegara VII menentang pemerintah kolonial Belanda yang hendak
membumikan Persatuan Pandu Hindia Belanda atau Nederlans Indische Padvinders
Vereeniging (NIPV) di tanah jajahan.
Orang nomor satu di praja Mangkunegaran ini emoh memenuhi permintaan pejabat kolonial
lantaran syarat mutlak anggota NIPV ialah kudu setia dan patuh kepada Ratu Belanda sebagai
junjungan. Tata tertib itu sengaja dipasang supaya tunas muda dari bangsa Eropa, Indo, dan
pribumi turut melanggengkan kekuasaan politik kolonial dan sendika dawuh kepada Belanda.
Organisasi tersebut jelas berpeluang melemahkan loyalitas kawula-gusti dan mengganggu
virus nasionalisme yang tengah ditiupkan para aktivis. Apabila NIPV merebak, kekuasaan,
wibawa, dan pengaruh Mangkunegara VII bakal melorot. Alih-alih mengikuti kemauan
pejabat Belanda mendirikan NIPV, raja yang juga seorang intelektual ini malah mendirikan
Javaansche Padvinders Organisatie (JPO), yang bercorak Jawa dan digarap secara mandiri
pada 1916.
Gusti yang pernah bersekolah di negeri Belanda itu paham bahwa kepanduan merupakan cara
jitu membangun "negara" yang kokoh dan mentalitas manusia yang bagus. Kegiatan positif
ini memperluas cakrawala para pemuda di luar jam sekolah dan di luar rumah. Juga
meningkatkan budi pekerti, jasmani, rohani, serta menambah aneka rupa kepandaian. Gusti
punya mimpi, yakni pemuda-pemudi anggota JPO hidupnya berfaedah bagi penduduk dan
menjadi warga negara yang baik, kelak.
Himodigdoyo (1950) menyebutkan bahwa pendidikan kepanduan ada yang berwujud
keterampilan dan permainan. Tapi tujuan pokoknya ialah pendidikan mental, berupa disiplin,
kepemimpinan, ketaatan, kesetiaan, kepatuhan atau loyalitas, ketahanan hidup, dan memupuk
rasa welas asih terhadap sesama. Kepanduan menyuntikkan spirit universalisme, humanisme,
sekaligus nasionalisme.
JPO ikut diterjunkan sewaktu Mangkunegara VII membasmi buta sastra dan membangun
sekolahan di area pedesaan. Wong ndeso dibekali bermacam keterampilan yang sederhana
dan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Bahkan diterbitkan pula majalah Kepandoean,
Pemimpin-JPO, dan Korban. Inilah bukti konkret usaha penguasa pribumi menebalkan rasa
cinta rakyat kepada negeri. Propaganda lewat aneka majalah memang sangat efektif selepas
rakyat melek huruf. Apalagi majalah tersebut dikonsumsi masyarakat umum. Buahnya,
jumlah anggota JPO kian membengkak dan secara diam-diam sukses menyelipkan misi
terselubung tanpa sepengetahuan pemerintah kolonial.
Dari pengkisahan sejarah di atas, kita diajak berpikir ulang bahwa kemajuan suatu negeri
tidak hanya bergantung pada kekuatan bala tentara dan para politikus andal. Ia bergantung
pula pada tabiat anak muda yang telah disiapkan jauh hari oleh pemimpin negeri. Lewat
Pramuka, mental dan kemandirian tunas muda digembleng.
Yamin dan Konstitusi
Selasa, 19 Agustus 2014
Bandung Mawardi, penulis
Empat belas tahun setelah pengesahan UUD 1945, 18 Agustus 1945, Muhammad Yamin
menerbitkan buku fenomenal berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Buku
sengaja diterbitkan agar ada dokumentasi lengkap tentang kesejarahan konstitusi, meski tak
lengkap dan mengandung kelemahan. Yamin bermaksud: " mendalamlah pengertian kita
kepada penulisan pertama dari sedjarah ketatanegaraan Indonesia jang disusun oleh ahli 62
pemikir Indonesia dalam abad ke-20 jang kita huni."
Selama puluhan tahun, buku susunan Yamin itu menjadi bacaan penting untuk studi
konstitusi. Sekarang, kita bisa membaca secara kritis dan mengomentari keterangan-
keterangan berlebihan dari ambisi imajinatif Yamin untuk membesarkan sejarah Indonesia.
Yamin memang rajin menulis kajian-kajian hukum dan sejarah bermisi memberi pemaknaan
Indonesia. Kritik pun diarahkan ke Yamin akibat "kegemaran" membawa semangat imajinatif
bercampur fakta. Ingat, Yamin adalah pujangga, sejak masa 1920-an. Sides Sudiyarto D.S.
(1979), dalam puisi berjudul Prof. Muhammad Yamin S.H. - 1962, memberi julukan dan
pujian: Wahai penyair madah kelana putra Indonesia/ Dikau pemikir hukum dan keadilan/
Pejuang nasib negara pembela bahasa/ tegas lurus membela bangsa. Puisi wagu tapi
informatif mengenai peran Yamin bagi Indonesia. Yamin adalah pujangga, ahli bahasa, ahli
hukum, dan ahli sejarah. Yamin juga mendapat julukan sebagai pembuat "mitos-mitos"
modern di Indonesia.
Yamin berjasa, meski sering berlaku berlebihan dalam urusan literasi sejarah Indonesia.
Penerbitan buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi bukti keinginan
Yamin untuk "mengakrabkan" sejarah konstitusi bagi publik. Buku itu bermakna, saat kita
memperingati 18 Agustus 1945 sebagai acuan Hari Konstitusi. Sukarno memberi anjuran
untuk membaca buku susunan Yamin: "Membolak-balik halaman buku ini sama dengan
menggali tambang emas Konstitusi-Proklamasi. Pada hakekatnja sama pula hal itu dengan
membatja penuh chidmat epos Revolusi Indonesia jang merintis djalan kebesaran bangsa
Indonesia."
Sukarno tampak memberi sanjungan dan menempatkan Yamin sebagai "pengisah" mumpuni
mengenai arus sejarah Indonesia, bermula dari Proklamasi dan UUD 1945. Yamin tentu
pantas diakui sebagai penulis ampuh, mendokumentasikan dan memberi penjelasan-
penjelasan konstitusi melalui publikasi buku Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia,
Konstitusi Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi, Uraian tentang Undang-Undang Dasar
1945, Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yamin adalah pelopor
literasi konstitusi.
Ambisi menggerakkan literasi untuk sejarah dan konstitusi sudah diumumkan Yamin dalam
Kongres Pemuda II (1928). Yamin menantang peminggiran sejarah Indonesia oleh para
intelektual Barat. Yamin menginginkan ada rintisan penulisan sejarah Indonesia. Penulisan
dan publikasi buku dari Yamin adalah ombak literasi agar sejarah dan konstitusi bisa
dipelajari secara reflektif dan kritis.
Kita mulai membuat tradisi peringatan Hari Konstitusi. Peringatan tentu mengacu ke
peristiwa bersejarah 18 Agustus 1945. Kita pun pantas memberi penghormatan bagi Yamin
saat mengingat agenda literasi konstitusi demi pembelajaran publik.
Pungo
Selasa, 19 Agustus 2014
Mustafa Ismail, pegiat kebudayaan, @musismail
Dalam bahasa Aceh, pungo memiliki arti generik "gila". Namun sesungguhnya makna kata
itu lebih luas, bahkan tidak melulu negatif. Meskipun seratus persen waras, seseorang yang
berkendaraan secara ugal-ugalan kerap diserapahi dengan kalimat "pungo" alias gila. Begitu
pula laku sosial lain, yang dianggap tak sesuai dengan tatanan atau kaidah-kaidah normal,
disebut sebagai pungo--meskipun orang itu tidak gila.
Pungo menjadi terminologi untuk menjelaskan sebuah laku sosial maupun pemikiran yang
keluar dari "keumuman" atau kesepakatan umum. Kata itu menjadi semacam saringan untuk
menilai kepantasan. "Pungo" menampung semua tingkatan gangguan jiwa--mulai dari yang
pura-pura gila, kelihatan gila, tak sadar telah gila, hingga yang benar-benar gila.
Dalam dunia psikologi, gangguan jiwa dijelaskan sebagai gangguan cara berpikir (cognitive),
kemauan (volition), emosi (affective), dan perilaku (psychomotor). Penyebabnya, macam-
macam. Ada yang karena merasa diperlakukan tidak adil, cinta tak berbalas, kehilangan
orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, tidak terpenuhinya keinginan, dan sebagainya.
Dan semua orang berpotensi pungo alias mengalami gangguan jiwa.
Maka, menjadi logis jika ada orang yang tampak sehat, necis, gagah, pintar, namun tak
disadari mengalami guncangan jiwa. Pasca-pemilu legislatif, misalnya, media ramai
memberitakan sebagian calon legislator yang tidak terpilih bertingkah aneh-aneh. Mereka
tidak bisa mengontrol emosi.
Yang lebih menarik, belakangan politik tidak hanya mengganggu kewarasan aktornya,
bahkan pendukungnya. Jika kita amati media sosial, kita akan menemukan bagaimana
pendukung capres meluapkan dukungannya yang lebih menonjolkan emosi ketimbang logika.
Pembelaan-pembelaan mereka kadang cenderung brutal dan di luar patokan normal. Bahkan
ada yang merasa lebih baik mati jika calon presidennya kalah.
Sekilas, seolah-olah itu cetusan spontan. Namun itu memperlihatkan betapa politik mudah
membuat akal sehat menjadi tumpul. Politik telah mengombang-ambingkan hidup dan
harapan sebagian orang. Boleh jadi, mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan
manfaat langsung dari terpilih atau tidaknya calon yang mereka dukung. Namun doktrin-
doktrin yang mereka terima dari lingkungan mereka bisa memberi angin bahwa apa yang
mereka lakukan adalah memperjuangkan kebenaran, bahkan jihad.
Bahkan, pasca-pilpres, laku orang-orang tak puas tetap saja unik-unik. Ada yang beranggapan
cuma calonnya yang luar biasa, sambil membangun imaji-imaji buruk dalam pikirannya
tentang calon lain. Bahkan ada yang seperti mengalami halusinasi dan delusi.
Frank G. Goble, penulis buku Mazhab Ketiga (Psikologi Humanistik Abraham Maslow),
menyebutkan salah satu ciri penting orang sehat mental adalah persepsinya terhadap semesta
itu realistis. Adapun pada orang yang tak sehat mental, tidak cuma sakit secara emosional,
pemikirannya pun serba keliru. Ia tidak berpijak pada realitas, melainkan lebih banyak
bermain dalam ruang imajinatif. Celakanya, ia susah membedakan antara realitas dan
imajinasi, antara harapan dan kenyataan.
Sebetulnya, itu urusan mereka sendiri. Masalahnya, mereka berlomba-lomba hadir di tengah
kita--lewat berbagai medium. Lama-lama mengganggu juga. Tapi, saya tak berani menyebut
mereka pungo.
Membangun Kota Cerdas dan
Berketahanan
Selasa, 19 Agustus 2014
Nirwono Joga, Koordinator Gerakan Indonesia Menghijau
Abad ke-21 adalah abad perkotaan, lebih dari setengah penduduk dunia telah tinggal di
kota/kawasan perkotaan. Kota kecil berkembang menjadi kota sedang, ke kota besar, kota
raya (metropolis), kota mega (megapolis), hingga mencapai kota dunia (ecumenopolis).
Sebuah kehormatan, Jakarta menjadi tuan rumah Kongres Dunia Ke-24 Organisasi Perencana
Kota dan Permukiman di Asia-Pasifik (Eastern Regional Organization for Planning and
Human Settlements), dengan tema "Menuju Perkotaan yang Berketahanan dan Pintar:
Inovasi, Perencanaan, dan Determinasi dalam Mengelola Kota-kota Besar di Dunia", yang
berlangsung selama 10-13 Agustus 2014.
Pertemuan ini membahas perkembangan kota yang cerdas dalam arti hijau, memanfaatkan
teknologi, serta memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana kota. Kegiatan ini
menjadi ajang saling berbagi pengetahuan dan pengalaman lintas negara dalam pengelolaan
kota hijau, seperti konsumsi energi terbarukan, serta model sistem transportasi yang cerdas,
efisien, dan ramah lingkungan.
Kota-kota di Indonesia tengah menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menghadapi
dampak perubahan iklim dan degradasi kualitas lingkungan, perkembangan kota yang cepat
dan dinamis, pertumbuhan jumlah penduduk dan penambahan jumlah pendatang, serta
dukungan media sosial dan tarikan kepentingan politik penguasa dan pengusaha. Untuk itu,
pemerintah harus mengembangkan kota cerdas dan berketahanan.
Ada lima langkah untuk mewujudkan kota cerdas dan berketahanan. Pertama, setiap warga
harus diberi kesempatan ikut bicara tentang nasib dan masa depan kotanya (city-citizen).
Pemerintah kota harus melakukan inovasi bersama penduduk. Warga didorong melaksanakan
perubahan gaya hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan kota dengan sepenuh hati,
membangun budaya perilaku positif, dan menularkan virus perubahan gaya hidup hijau.
Para perencana kota harus berhenti sejenak, merenung, dan mawas diri, untuk kemudian
meningkatkan kadar profesionalisme, pemikiran, penalaran, kepekaan, dan kesadaran batin,
intuisi, serta insting, untuk serius mewujudkan kota cerdas dan berketahanan.
Kedua, keberagaman mosaik masyarakat perkotaan harus diwadahi dan tecermin dalam tata
ruangnya. Kota bersifat jamak (plural) dan rakyat diberi pilihan-pilihan alternatif secara
terbuka. Hal ini tecermin pada tingkat keamanan/kriminalitas, keterhubungan secara
internasional, cuaca/sinar matahari, kualitas arsitektur bangunan-lanskap-kota, isu
lingkungan, akses terhadap ruang terbuka hijau, desain urban, transportasi publik, toleransi,
kondisi bisnis, pengembangan kebijakan yang proaktif, dan layanan kesehatan.
Ketiga, pusat-pusat lingkungan sebagai simpul jasa transportasi umum harus berada dalam
jarak jangkau berjalan kaki atau bersepeda (otomobilitas-aksesibilitas). Pengembangan
kawasan terpadu meliputi hunian vertikal (rusun, apartemen), perkantoran, pasar, dan
sekolah. Penghuni cukup berjalan kaki atau bersepeda dalam kawasan dan menggunakan
transportasi publik (bus, KA) ke luar kawasan.
Keempat, pembangunan dan pelestarian RTH berupa taman kota sebagai surga perkotaan.
Kehadiran taman-taman kota ibarat bak oasis di padang gurun, sebagai daerah resapan dan
tangkapan air, paru-paru kota untuk menyerap polusi udara dan menciptakan iklim mikro,
serta wadah berinteraksi sosial, rekreasi, dan berolahraga.
Kelima, perencanaan tata lingkungan perumahan dan permukiman diarahkan ke terciptanya
rasa-tempat dan semangat komunitas agar tumbuh rasa memiliki, solidaritas sosial yang
tinggi, suasana yang guyub dan rukun antarwarga kota.
Kota menumbuhkan semangat kewargaan dan rasa memiliki yang kuat, menciptakan
keseimbangan lingkungan yang mendukung keberlanjutan pembangunan, membentuk kohesi
sosial yang kental, guyub, dan tidak mudah terprovokasi dari luar, menyediakan perluasan
kesempatan kerja, menumbuhkan rasa aman, menggulirkan perekonomian kota, serta
dirmeriahkan dengan kegiatan seni budaya masyarakat.
Saatnya, kota-kota menjalin komunikasi yang erat, saling bertukar informasi, berbagi
pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola kota/kawasan perkotaan. Wali kota/bupati
dituntut piawai mengidentifikasi aset dan mengembangkan potensi kota, termasuk warga,
sebagai investasi pengembangan kota ke depan.
Prinsip kerja sama antarkota berupa kompetisi yang sehat, bersahabat, dan hubungan yang
setara dengan mengoptimalkan keunikan kota/kabupaten masing-masing untuk saling
mendukung dan melengkapi, bukan saling melemahkan pertumbuhan ekonomi dan
perkembangan kota/kabupaten tetangga.
Ke depan, para pengelola kota harus bertekad membuat kotanya menjadi tempat tinggal yang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Mereka harus merencanakan dan merancang
kota yang berwawasan lingkungan, menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 persen,
mengolah air yang lestari, mengelola sampah dan limbah ramah lingkungan,
mengembangkan transportasi publik berkelanjutan, menerapkan persyaratan bangunan hijau,
memanfaatkan energi terbarukan, dan memberdayakan komunitas hijau masyarakat.
Bahasa Negara
Rabu, 20 Agustus 2014
Maryanto, pemerhati politik bahasa
Sehari setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 berkumandang, bahasa Indonesia diresmikan
menjadi bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hari jadi bahasa negara ini
sayangnya masih sepi dari perhatian publik. Urusan publik seolah selesai ketika bahasa ini
digunakan sebagai infrastruktur komunikasi formal antara rakyat dan aparat negara. Pasal 36
Undang-Undang Dasar 1945 menyiratkan bahasa Indonesia adalah identitas negara dengan
ciri kebinekaan bangsa.
Untuk mendirikan negara bangsa ini, sejak awal bangunan Indonesia dirancang tidak
berlandaskan strategi kesukuan. Refleksi kesukuan Indonesia adalah sejumlah bahasa daerah
yang--dengan istilah Ferdinand de Saussure--disebut parole. Saussure (1916)
menggambarkan parole sangat beragam dalam tuturan masyarakat: gambarannya seperti
bentuk pion, kuda, dan sebagainya, dalam wujud permainan catur. Kehadiran bahasa negara
menjadi strategi menemukan kesatuan muasal. Sebagai contoh, kata aku, kula, kulo, ulon, dan
ulun bisa dicari kesamaan asalnya meski bentuk tuturan semua itu beragam.
Atas keanekaragaman tuturan masyarakat Indonesia, bahasa negara perlu hadir memberikan
ruang apresiasi bagi semua bentuk parole. Bahasa negara-bahasa Indonesia-pernah dituding
sebagai bagian strategi "jawanisasi" ketika zaman Orde Baru. Apresiasi bahasa Indonesia
condong berpihak hanya pada penutur suku Jawa. Ketika itu, kualitas kebinekaan Indonesia
merosot tajam.
Sama bahayanya, klaim kesukuan yang sering terlontar bahwa bahasa Indonesia masih
termasuk bahasa Melayu. Klaim itu masih dicoba untuk menguatkan anggapan bahwa orang
Indonesia merupakan kelompok etnis Melayu Austronesia. Walhasil, sebagian warga
Indonesia sekarang melakukan gerakan kontra-identitas. Misalnya, di wilayah Papua sudah
muncul gerakan membentuk pola pikir mereka sebagai orang Melanesia.
Ungkapan "Dirgahayu Indonesia" harus tetap bergema. Republik Indonesia tak boleh
terjerembap dalam strategi kesukuan dan/atau keagamaan. Caranya: kerja bahasa negara ini
harus dioptimalkan untuk strategi berbangsa dan bernegara Indonesia.
Kelembagaan bahasa negara sekarang tampak lebih optimal dengan terbentuknya Pusat
Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (sebuah unit kerja baru pada Badan
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) di kawasan Pusat Perdamaian dan
Keamanan Indonesia (Indonesia Peace and Security Center/IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Tergabungnya kelembagaan bahasa ini sebagai salah satu instalasi strategis nasional di
kawasan IPSC, jika nantinya dikelola dengan baik, akan mengoptimalkan pemanfaatan
potensi bahasa sebagai bentuk diplomasi.
Dalam waktu dekat, kawasan IPSC itu bakal diwariskan oleh pemerintah Susilo Bambang
Yudhoyono sebagai pekerjaan besar kepada pemerintahan baru. Presiden terpilih dalam
pemilihan presiden 2014-Joko Widodo-terlihat siap menerima warisan ini. Dalam debat
capres soal hubungan internasional dan ketahanan nasional, Jokowi menyatakan tekadnya
untuk mengedepankan diplomasi. Sudah semestinya, ia menyiapkan langkah-langkah yang
terukur melalui kegiatan diplomasi kebahasaan.
Untuk hubungan internasional, misalnya, Jokowi perlu berani secara tegas menginstruksikan
semua pejabat Indonesia agar berbahasa negara dalam dinas di luar negeri. Janganlah malu
berbahasa Indonesia di forum resmi antarbangsa.Kegiatan diplomasi kebahasaan,
sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 16 Tahun 2010 mengenai bahasa pejabat, masih perlu
diperkuat.
Untuk ketahanan nasional, kegiatan diplomasi kebahasaan juga tidak kalah penting. Ini
karena bahasa tidak selamanya mendamaikan. Dalam ranah forensik, dikenal adanya tuturan
kebencian atas seorang/sekelompok warga komunitas. Tidak jarang, tindakan kebencian yang
berujung pada perbuatan jahat bermula dengan kata-kata yang berbau tidak menyenangkan
atau, bahkan, menyerang kehormatan harkat manusia. Dalam proses pemilihan presiden
2014, Jokowi pernah menjadi korban kejahatan itu.
Seperti halnya teori kejahatan, susur galur motif perbuatan verbal bisa dilakukan dalam dunia
kebahasaan. Dengan karya How to Things With Words, J.L. Austin (1962) mengabadikan
teori mengenai bagaimana setiap tindakan bahasa dibuat, termasuk untuk membuat situasi
konflik atau damai. Mengingat besarnya potensi konflik warga komunitas, diplomasi bahasa
negara sangat penting dipraktekkan di dalam negeri.
Terjadi kejahatan terbesar terhadap negara apabila ada sekelompok warga Indonesia yang
berbuat makar; mengingkari cita-cita terbentuknya NKRI. Di era otonomi daerah, perbedaan
parole berbahasa daerah kerap dibenturkan agar tercipta situasi konflik komunitas dengan
negara. Untuk itu, melalui strategi dan diplomasi kebahasaan, kerja bahasa negara perlu
dikelola-seperti disebutkan Kepala Badan Bahasa Prof Mahsun (2014 dalam komunikasi
pribadi)-sebagai "politik identitas".
Sebuah kemauan politik untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas negara pada 18
Agustus 1945. Hikmah hari jadi bahasa negara itu sekarang masih sepi dalam ingatan publik.
Sebab, bahasa Indonesia baru resmi bagi kuasa negara; belum sepenuhnya merdeka menjadi
bahasa rakyat.
Gapura
Rabu, 20 Agustus 2014
Musyafak, Staf Balai Litbang Agama Semarang
Menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI, biasanya masyarakat sibuk merias
desa atau kompleks huniannya. Agustus adalah bulan ketika suasana permukiman disegarkan.
Parit atau selokan dibersihkan, umbul-umbul dipasang di sisi jalan, pagar-pagar dicat ulang,
juga lampu kerlap-kerlip dipasang. Gapura pun kerap kena sentuhan warna baru atau hiasan
anyar. Bahkan gapura kerap menjadi perhatian utama untuk disolek seindah mungkin.
Banyak dalih mengapa pengindahan gapura didahulukan. Sebagai pintu masukkeluar
kampung atau lingkungan perumahan, gapura adalah hal pertama yang menyapa mata orang.
Dengan gapura, citra muka suatu area dirancang. Sebagai garis batas wilayah, gapura
sekaligus menjadi penanda hidupnya sebuah komunitas. Bentuk, warna, dan aksesori gapura
adalah penanda identitas kultural bagi komunitas di dalamnya. Status sosial ekonomi suatu
komunitas juga bisa ditangkap lewat gapura.
Menurut riwayat (Wardhana, 2008), gapura atau pintu gerbang sudah ada sejak zaman
Kerajaan Majapahit. Gapura Bajangratu, bagian dari Situs Trowulan, adalah bukti historis
keberadaan gapura di zaman baheula.
Gapura, dengan bermacam desain arsitekturalnya, dibangun untuk menandai batas wilayah,
pintu gerbang kerajaan atau tempat ibadah, juga pintu pertama memasuki rumah. Tiap-tiap
daerah punya corak gapura yang khas. Gapura di Jawa lain dengan di Bali. Gerbang masjid
berbeda dengan gapura kelenteng atau pura.
Kini bentuk dan corak gapura kian variatif. Gapura bisa mewah dengan tekstur dan bahan
bangunan yang wah. Bisa pula sesederhana portal besi atau beton. Fungsi gapura juga
semakin beragam. Pada waktu yang sama, satu gapura bisa berfungsi sebagai batas atau tanda
nama wilayah, pos keamanan, monumen, dan tempat iklan.
Tapi gapura bukan sekadar perkara bentuk fisik ataupun fungsi praktis semata. Selain
identitas kultural, gapura memuat anasir-anasir sosial dan politik lainnya. Gapura adalah
infrastruktur untuk menjaga tertib sosial. Gapura menjadi sarana penubuhan kekuasaan dan
penyuntikan ideologi. Ketika Orde Baru berkuasa, banyak gapura dibubuhi tulisan butir-butir
P4, slogan keluarga berencana, atau program-program pokok PPK.
Bagi suatu kawasan, gapura memang pintu masuk. Tapi, di waktu yang sama, gapura juga
mencegah orang-orang tertentu agar tidak masuk. Semacam benteng, gapura memproteksi
potensi gangguan dari luar. Bagi sebuah kawasan dan komunitasnya, gapura adalah pengukuh
tata tertib yang mesti dipatuhi. Kita mudah menjumpai hal itu pada gapura-gapura gang,
kampung, atau perumahan yang memperingatkan pemulung atau pengamen untuk tidak
masuk.
Begitulah gapura berfaedah untuk menyaring dan memilah orang yang datang. Satu sisi
gapura menyambut tamu, dalam waktu yang sama juga menolak mereka yang disinyalir
berpotensi mengoyak rajutan keamanan dan kenyamanan.
Gapura juga bisa merepresentasikan ideologi serta afiliasi politik suatu komunitas. Warna dan
simbol-simbol yang dilekatkan pada gapura tidak jarang mengusung ide dan cita politik
khusus.
Sampai hari ini gapura dibangun dalam pelbagai bentuk. Orang-orang yang membuatnya
hendak melesakkan berbagai simbol kultural, kode sosial, juga ide politik. Gapura bukan
hanya besi atau beton yang mati. Gapura hidup dan bicara mengudarkan makna yang kadang
tidak kita sadari.
Merdeka dari Impor Pangan
Rabu, 20 Agustus 2014
Kadir, bekerja di BPS
Tahun ini, Badan Urusan Logistik (Bulog) berencana mengimpor beras sebesar 500 ribu ton
untuk memperkuat cadangan beras nasional. Dari rencana impor sebanyak itu, yang sudah
direalisasi sekitar 50 ribu ton (Antara, 8 Agustus).
Di tengah ingar-bingar perayaan hari kemerdekaan nasional, impor beras tersebut kembali
mempertegas satu hal: Indonesia belum merdeka dari jebakan impor pangan. Padahal, negeri
yang luas daratannya mencapai 188 juta hektare ini telah diberkahi Tuhan dengan kesuburan
tanah yang melegenda. Bukankah di negeri yang subur ini, "tongkat kayu bisa jadi tanaman"?
Ironisnya, bukan hanya beras yang kita impor. Data statistik menunjukkan, nyaris semua
komoditas pangan strategis negeri ini harus dicukupi dari impor. Selama dasawarsa terakhir,
tujuh komoditas pangan utama yang mencakup gula, kedelai, jagung, beras, bawang merah,
daging sapi, dan cabai harus dicukupi dari impor.
Seolah tak bisa direm, tren impor pangan juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam
sepuluh tahun terakhir, impor tujuh komoditas pangan utama tersebut meningkat rata-rata 58
persen per tahun. Seandainya ketujuh komoditas pangan tersebut tak bisa dihasilkan oleh
petani kita, mungkin bisa dimaklumi. Tapi, faktanya, negeri ini pernah swasembada, bahkan
berjaya, sebagai eksportir pada sebagian besar komoditas tersebut. Tengoklah catatan
berikut.
Sebelum merdeka, Nusantara adalah pengekspor gula terbesar di dunia. Hingga 1970-an, kita
termasuk salah satu pengekspor sapi. Pada 1984, kita swasembada beras dan gula, bahkan
mampu mengekspor beras ke luar negeri, sehingga membikin harga beras di pasar
internasional jatuh dari US$ 250 per ton menjadi US$ 150 per ton. Satu tahun kemudian
hingga 1995, kita juga berhasil swasembada kedelai.
Kini, situasinya justru terbalik. Secara faktual, lebih dari separuh kebutuhan gula nasional
harus diimpor. Tahun lalu, kita juga harus mengimpor setara dengan 700 ribu ekor sapi untuk
memenuhi kebutuhan daging nasional. Dalam soal beras, kita sering dituduh sebagai biang
kerok melambungnya harga beras di pasar internasional karena terlalu banyak mengimpor.
Kita juga kerap dipusingkan dengan harga kedelai yang melambung karena 70 persen
kebutuhan kedelai nasional harus diimpor.
Miris! Itulah faktanya. Pemerintah saat ini boleh saja berbangga dengan segala pencapaian
pembangunan yang berhasil direngkuh selama sepuluh tahun terakhir. Namun, dalam soal
kemandirian pangan, nyaris tak ada prestasi yang bisa dibanggakan.
Kapasitas produksi pangan memang berhasil digenjot. Tapi, pada saat yang sama, hal itu tak
mampu memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan perbaikan daya
beli masyarakat, dan jumlah penduduk kelas menengah yang terus bertumbuh. Alhasil,
pemerintah terbukti telah gagal dalam mewujudkan swasembada beras, jagung, kedelai, gula,
dan daging sapi.
Karena itu, harapan agar negeri ini merdeka dari impor pangan ada pada pemerintah
mendatang. Janji duet Jokowi-JK untuk mewujudkan swasembada pangan, setidaknya untuk
komoditas strategis seperti beras dan gula, harus dibuktikan.
Desakralisasi Otoritas Media
Kamis, 21 Agustus 2014
Muhamad Heychael, Koordinator Divisi Penelitian Remotivi
Satu hal yang patut disyukuri pasca-kampanye pemilu presiden lalu adalah literasi media.
Pertarungan dua poros politik yang melibatkan peran media secara tidak langsung mengajak
publik memahami bahwa media bukanlah produsen informasi yang bebas nilai.
Kita tentu ingat bagaimana berita TV One yang membingkai PDIP sebagai partai komunis
dan kader-kadernya sebagai keturunan anggota PKI. Pemberitaan Metro TV juga bukan tanpa
masalah. Persoalan pelanggaran hak asasi manusia hingga kasus penyalahgunaan lambang
negara (logo kampanye Koalisi Merah Putih) menjadi informasi yang terus dilekatkan pada
calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto.
Akibat keberpihakan yang telanjang tersebut, publik menyadari bahwa informasi yang
diusung stasiun televisi bias. Kesadaran ini mencuat antara lain lewat berbagai perdebatan
publik di media sosial. Masing-masing pendukung kubu capres/cawapres mengkritik sumber
informasi yang diusung sang lawan politik. Publik kerap melihat media semata sebagai
produk kerja politik, sehingga gagal melihat hasil kerja jurnalistik dengan jernih.
Sebenarnya terdapat perbedaan yang mendasar antara pembingkaian berita dan informasi
sesat. Sebuah berita bisa saja berpihak, tapi tetap dikerjakan berdasarkan kaidah jurnalistik,
sehingga tetap merupakan sebuah fakta. Bingkai dalam pemberitaan adalah pemilahan dan
penonjolan fakta tertentu. Misalnya, berita berjudul "Prabowo-Hatta Menang di Penjara
Khusus Koruptor" (Tempo.co, 9 Juli 2014) atau "Di Lokalisasi Gang Dolly, Jokowi-JK
Menang" (Viva.co.id, 5 Agustus 2014) jelas merupakan strategi pembingkaian media. Meski
demikian, keduanya dikerjakan dengan kaidah jurnalistik: memiliki sumber yang jelas dan
data yang akurat.
Hal berbeda bisa ditemui pada Seputar Indonesia edisi 11 Juni 2014 mengenai dugaan
bocornya materi debat capres dan cawapres yang dituduhkan kepada kubu Jokowi-Jusuf
Kalla. Berita tersebut jelas cacat secara jurnalistik karena didasari sumber yang sumir, bukan
prinsip cover both sides. Cacat jurnalistik yang sama kita temui pada berita-berita VOA Islam
atau Obor Rakyat yang memberitakan bahwa Jokowi berasal dari etnis Tionghoa serta
beragama non-Islam.
Pada kenyataannya, publik seringkali mengabaikan kualitas informasi media dan
mengedepankan preferensi politik atau ideologi. Kebenaran informasi tidak diukur dari
validitasnya, melainkan ditentukan oleh kesesuaian dengan pilihan politik. Dari sini kita
melihat bahwa hal yang luput dari kritik publik atas media adalah diterimanya asumsi media
sebagai sumber informasi yang "benar". Kritik atas keberpihakan media tidak dilanjutkan
menjadi kritik atas kredibilitas informasi media. Dalam kata lain, maraknya kritik publik
lebih merupakan kritik atas preferensi politik media, bukan kritik terhadap otoritas media
dalam menyampaikan informasi.
Apa yang kita perlukan dalam waktu-waktu ke depan adalah desakralisasi otoritas media,
sehingga publik memahami bahwa informasi yang dihasilkan media bukan wahyu yang tak
bisa dipertanyakan. Idealnya, diskusi atau perdebatan publik dilakukan di atas pertanyaan
mengenai validitas informasi media. Hanya dengan begitu dialog bisa dicapai, karena
tanpanya yang terjadi adalah seolah berdiskusi padahal masing-masing pihak bercakap
sendiri.
Masjid Cheng Hoo
Kamis, 21 Agustus 2014
Achmad Fauzi, Aktivis Multikulturalisme
Masjid Muhammad Cheng Hoo memberikan keteladanan penting tentang inklusivisme
beragama. Masjid yang terletak di Kota Surabaya ini bisa dijadikan referensi bagi masjid dan
tempat ibadah lain dalam mengatur pola interaksi dengan umat agama lain. Ketika
mengumandangkan azan subuh, misalnya, muazin tidak menggunakan pengeras suara,
sehingga warga sekitar yang mayoritas non-muslim tidak terganggu. Eksplanasi tersebut
untuk menghindari pola-pola konflik yang berbasis perebutan aset massa. Apalagi, ketika
pergumulan penyiaran agama telah melampaui batas-batas demarkasi teologi masing-masing
agama, masjid menjadi momentum terbaik untuk menyebarkan ajaran agama yang moderat,
toleran, dan menjunjung tinggi kepelbagaian.
Masjid Muhammad Cheng Hoo merupakan rumah ibadah yang bercorak unik dan
multikultural. Ide penamaannya diilhami oleh tokoh legendaris Tionghoa, Laksamana Cheng
Hoo, yang dikenal saleh dan toleran dalam beragama. Jejak historis dari ekspedisi Laksamana
Cheng Hoo pada abad ke-15 diakui telah menaburkan benih-benih ajaran Islam yang penuh
kelembutan, yang di dalamnya menyeruak aroma toleransi dan penghormatan terhadap
budaya-budaya lokal. Keberadaan Masjid Muhammad Cheng Hoo terbuka untuk siapa saja
tanpa memandang agama, ras, warna kulit, ataupun golongan. Dulu, Nabi Muhammad juga
memperlakukan masjid secara terbuka dan menjadikannya tempat dialog lintas agama.
Masjid Muhammad Cheng Hoo berhasil menjadi simbol keragaman. Ini menjadi aset bagi
masyarakat dalam mewujudkan inspirasi semangat kepelbagaian. Zaman dulu, masjid berdiri
berdampingan secara damai di antara gereja. Kelenteng berdiri di antara vihara dan pura.
Tapi kini suasana yang ada sudah berbeda. GKI Yasmin saja hingga kini masih menjadi
objek konflik antar-agama meski putusan MA telah berkekuatan hukum tetap.
Padahal Presiden berharap GKI Yasmin dan masjid di dekatnya dapat berdiri secara
berdampingan sehingga menjadi miniatur kerukunan antar-umat beragama di Indonesia.
Itulah tantangan kita bersama untuk beragama secara toleran. Sentimen negatif itu dapat
tereliminasi jika tempat ibadah sebagai pusat peradaban selalu menggemakan tema
kerukunan sebagai isu utama. Rumah ibadah seharusnya menjadi tempat menyemai
kedamaian, inklusivisme, dan rasa saling menghargai antar-umat beragama.
Banyak prestasi gemilang yang telah diraih oleh masjid monumental ini dalam menghadirkan
wajah Islam yang ramah. Tak hanya dalam bidang penggemblengan akidah, dalam aspek
kemasyarakatan pun Masjid Muhammad Cheng Hoo membangun jembatan komunikasi
dengan warga sekitar. Hal itu terlihat dari ragam kegiatan yang ada, seperti pembagian buku
serta alat tulis kepada anak-anak kecil yang berada lingkungan di sekitar, pembagian bahan
pokok murah, perayaan Nuzulul Quran, donor darah, serta pengobatan tradisional akupunktur
Tiongkok. Di bidang pendidikan, mereka telah mendirikan Istana Balita dan usaha-usaha
lainnya. Ini sebuah kemajuan yang menggembirakan. Masjid Muhammad Cheng Hoo tak
kenal lelah dalam memancangkan pilar-pilar kesalehan sebagai mercusuar bagi umat dan
menjadi "kiblat" bagi masjid-masjid lain di Indonesia.
Ke depan, lembaga-lembaga keagamaan harus proaktif meneladani dan merumuskan kembali
strategi dakwah bernapaskan toleransi, inklusivisme, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Walhasil, dari masjid, jalan spiritual yang sejuk dan mengayomi seluruh umat manusia
kembali menemui jalan terang.
Arah Pertanian dan 'Tepungisasi'
Kamis, 21 Agustus 2014
Agus Pakpahan, Ekonom Kelembagaan dan Sumber Daya Alam
Era Revolusi Industri ketiga menurut Rifkin akan dicirikan antara lain oleh Internet-energi,
yang berasal dari bermacam sumber energi, khususnya bioenergi. Reiner Kmmel (2011),
dalam bukunya The Second Law of Economics: Energy, Entropy, and the Origins of Wealth,
menunjukkan bahwa kunci utama kemajuan suatu negara secara dominan adalah dukungan
energinya.
Kmmel menunjukkan bahwa elastisitas perubahan output terhadap perubahan input energi
untuk industri di Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat (ekonomi keseluruhan) masing-
masing adalah 0,73, 0,52, dan 0,35. Jadi, selain masalah pangan, yang juga berada dalam
kondisi tertinggal sebagaimana diperlihatkan oleh Global Food Security Index (GFSI) dari
The Economist dan Global Hunger Index (GHI) dari IFPRI, Indonesia perlu berkonsentrasi
pada pembangunan pertanian dengan manfaat multidimensi, sebagaimana peran dan fungsi
pertanian itu sendiri yang bersifat multidimensi.
Walau fakta dunia menunjukkan bahwa hampir semua negara yang berada di garis
khatulistiwa dan beriklim tropis ini-di belahan bagian utara maupun selatan khatulistiwa-
merupakan negara miskin (Sachs, 2000), kita punya potensi besar untuk bisa melepaskan diri
dari kemiskinan dan ketertinggalan selama ini.
Karena itu, kita perlu membangun kerangka dasar cara berpikir kita sendiri. Sumber daya
utama pertanian adalah sinar matahari, yang kemudian diolah oleh tanaman menjadi hasil-
hasil pertanian. Selama ribuan tahun, telah terjadi evolusi tanaman lokal yang telah berhasil
beradaptasi dengan lingkungan setempat. Namun, mengingat kita mengikuti pihak pendatang
yang mengusahakan komoditas-komoditas untuk kepentingan mereka di tanah Nusantara,
sampai sekarang flora dan fauna asli tidak termanfaatkan atau bahkan semakin terdesak dan
banyak yang sudah punah atau mendekati kepunahan.Apa artinya semua itu bagi kepentingan
jangka panjang Indonesia?
Apabila tidak ada perubahan yang mendasar dalam kerangka berpikir tersebut, sudah dapat
dipastikan pertanian Indonesia tidak akan berkelanjutan atau hanya akan bergantung pada
input dari luar.Mengingat pertanian merupakan fondasi peradaban yang dibangun di atasnya,
maka ketidakmandirian dalam budaya membangun pertanian Nusantara akan membuat
kemiskinan permanen bangsa-bangsa di wilayah tropis menjadi kenyataan.
Sifat wilayah tropis adalah memiliki banyak jenis tanaman atau hewan (biodiversitas tinggi).
Berbeda dengan sifat alam temperate, yaitu sedikit jenis tanaman atau hewannya tapi
volumenya per unit wilayah besar. Karena itu, pemikiran yang berkembang di negara
temperate adalah pemikiran skala ekonomi sebagai basis industrialisasi. Bagi kita, untuk
mencapai skala ekonomi yang tinggi, diperlukan proses transformasi dari banyak jenis
komoditas ke jenis sekunder sebagai kombinasi, atau campuran dari banyak komoditas
menjadi satu atau dua jenis komoditas baru. Dalam berbagai kesempatan, saya menamakan
proses ini sebagai "tepungisasi", yaitu membuat tepung Nusantara berdasarkan seluruh
produk lokal, seperti sagu, sukun, jagung, dan ubi sebagai basis ketahanan pangan, energi,
dan ekologi Indonesia pada masa yang akan datang.
Tepungisasi, selain penting untuk pangan dan energi, turut mengurangi tekanan pertanian
terhadap lingkungan, khususnya terhadap sumber daya air dan kemungkinan konflik akibat
berbagai kepentingan terhadap sumber daya air. Perlu diingat bahwa Indonesia terdiri atas
pulau-pulau. Sistem kepulauan dengan sendirinya memiliki potensi air lebih terbatas
dibanding sistem benua. Sebagai ilustrasi, Chapagain dan Hoekstra (2011) menunjukkan
bahwa rata-rata water footprint untuk produksi padi adalah 1325 meter kubik/ton. Artinya,
dengan produksi padi 70 juta ton/tahun, air yang digunakan sebanyak 92.75 miliar meter
kubik.
Jelas, meningkatnya jumlah penduduk Indonesia akan meningkatkan pula kebutuhan air.
Dengan model tepung tersebut, kita tidak perlu menambah jumlah sawah secara besar-
besaran, melainkan cukup mengolah hasil-hasil pertanian lokal yang sudah adaptif dengan
lingkungannya, misalnya sagu yang sekarang jumlahnya masih jutaan hektare. Mulai
sekarang, kita harus mempersiapkan sistem pertanian yang hemat air, hemat ruang, serta
hemat energi. Hal ini akan berdampak positif, selain ketahanan pangan dan energi serta
industrialisasi, terhadap sistem ekologi kepulauan dan menjadi faktor pemicu pertumbuhan
serta pemerataan ekonomi secara regional.
Mengingat Muhammad Yamin
Jum'at, 22 Agustus 2014
L.R Baskoro, wartawan Tempo
Jika dia masih hidup, hari ini, Jumat 22 Agustus, umurnya 111 tahun. Dialah Muhammad
Yamin. Mungkin sebagian besar dari kita pertama kali mengenal namanya saat duduk di
bangku SD atau SMP, kala mulai membaca buku sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia
dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) yang gemuruh dengan pidato dan perdebatan itu.
Dia, Yamin, salah satu bapak bangsa yang ikut menyumbangkan pikirannya di sana. Dia
menunjuk bentuk kesatuan ("tidak federasi!" kata dia) yang paling tepat untuk negeri ini dan
mendesak UUD mesti memuat perlindungan HAM. Sebagai ahli hukum, dia sadar konstitusi
yang akan menjadi landasan bangsa ini mesti berisi hal yang melindungi sekaligus
merekatkan bangsa sebagai kesatuan.
Kesadaran pentingnya kesatuan ini jelas diwacanakan karena dia pencinta berat sejarah.
Berbeda dengan para bapak bangsa yang lain, kelebihan Yamin adalah "kegilaannya" akan
sejarah dan sastra. Pada usianya yang belum genap 17 tahun, puisinya bertaburan di majalah
Jong Sumatra dan bertahun kemudian dia menerjemahkan karya-karya William Shakespeare
dan Rabindranath Tagore.
Kegilaannya akan sejarah tak hanya tampak pada keseriusan mempelajari Kerajaan
Sriwijaya, Majapahit, atau kemudian menulis berbagai buku sejarah, termasuk Tata Negara
Majapahit sebanyak empat jilid (dari tujuh jilid yang direncanakan), tapi juga bagaimana ia
hingga perlu mengambil les privat kepada sejarawan Poerbatjaraka untuk belajar bahasa
Sanskerta.
Yamin sangat yakin sejarah adalah masa lampau yang tak bisa ditinggalkan untuk
membentuk masa depan. Dalam konteks ini, tak mengherankan jika kemudian Sukarno cocok
dengan Yamin. Keduanya senang mencari dan menciptakan simbol-simbol untuk merekatkan
bangsa, sekaligus menggagas kebesaran bangsa ini-dengan berkaca pada kejayaan masa lalu.
Di sinilah bangsa ini memerlukan pengetahuan sejarah-juga kepiawaian menulis-Yamin.
Ketika menjelang hari-hari akhir Kongres Pemuda II pada Oktober 1928, ratusan pemuda
kebingungan akan "melahirkan" apa dari perhelatan itu, Yamin menyodorkan "teks sumpah
pemuda", naskah yang kita kenal hingga sekarang sebagai puncak dari Kongres 1928. Ketika
Bung Karno letih mencari nama yang pas untuk gagasan lima silanya, Yamin menyodorkan
Pancasila-bukan Pancadharma seperti yang sebelumnya dipikirkan Bung Karno. Kata
Pancasila dijumput Yamin dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, pujangga pada era
Raja Hayamwuruk.
Kita tahu pengetahuan sejarah Yamin ini terus mewarnai perjalanan negeri ini-hingga dia
wafat pada 17 Oktober 1962. Dia tak saja terlibat dalam pembuatan simbol burung Garuda,
termasuk melahirkan tulisan Bhinneka Tunggal Ika, juga pada hal lain: menciptakan simbol
dan sumpah Polisi Militer dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Yamin, seperti yang ditulis oleh majalah Tempo dalam edisi khususnya yang terbit pekan ini,
adalah tokoh kontroversial. Sejumlah tindakannya dianggap berupaya melencengkan sejarah.
Tapi, betapapun, sumbangsihnya tetap lebih besar daripada "dosa"-nya. Dari Yamin, yang
perlu kita petik: kecintaan dan antusiasmenya akan sejarah dan sastra. Dua hal ini makin
diabaikan oleh sebagian pendidik kita.
Agenda Prioritas Bidang Pers
Jum'at, 22 Agustus 2014
Agus Sudibyo, Direktur Eksekutif Matriks Indonesia
Perkembangan kebebasan pers di Indonesia sesungguhnya mendapat banyak pengakuan dari
dunia internasional. Indonesia dianggap berhasil melakukan transisi demokrasi dan
melembagakan kebebasan pers. Pelembagaan kebebasan pers di Indonesia bahkan dijadikan
model bagi negara-negara lain, seperti Malaysia, Myanmar, dan Timor Leste. Namun ada
satu masalah yang membuat indeks kebebasan pers Indonesia tidak kunjung meningkat,
bahkan beberapa kali menurun. Masalah tersebut adalah tingginya angka kekerasan terhadap
wartawan, sebagaimana selalu mewarnai laporan akhir tahun asosiasi jurnalis dan Dewan
Pers.
Pemerintah yang baru harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini.
Apalagi fakta menunjukkan pelaku kekerasan terhadap wartawan umumnya adalah kalangan
pemerintah dan aparat penegak hukum. Yang paling dibutuhkan dalam konteks ini adalah
penegakan hukum secara tegas dan konsekuen. Para pelaku kekerasan harus diberi hukuman
yang setimpal dan diberi efek jera. Harus ada penyelesaian yang jelas secara hukum ataupun
politis atas kasus pembunuhan Udin, wartawan Bernas Yogyakarta. Kasus ini sudah terlalu
lama mengambang. Sudah lima presiden tidak berhasil menyelesaikannya.
Para pejabat pemerintah dan penegak hukum juga harus dididik dalam hal fungsi-fungsi pers
serta mekanisme penyelesaian sengketa dengan pers. Mereka perlu diajari bagaimana
menyelesaikan masalah dengan media atau wartawan, bagaimana menghindari tindakan main
hakim sendiri kepada wartawan, bagaimana menghadapi wartawan abal-abal, dan seterusnya.
Upaya-upaya untuk melakukan kampanye media literasi di kalangan badan publik harus
menjadi prioritas pemerintah.
Selanjutnya, presiden yang baru harus memilih Menteri Komunikasi dan Informasi yang
menguasai persoalan dan relatif bebas kepentingan politik. Jika Menkominfo masih dipilih
dengan pertimbangan bagi-bagi jabatan politis dalam koalisi partai politik pendukung
pemerintahan, kinerjanya akan tetap mengecewakan. Mereka suka membuat kontroversi
sendiri, gamang dalam mengambil tindakan saat situasi genting, dan sering menunjukkan
gelagat kepentingan politik tertentu saat membuat keputusan atau pernyataan publik.
Persoalan pers, penyiaran, serta teknologi informasi dan media sosial sangat menentukan ke
depan. Karena itu, dibutuhkan menteri yang benar-benar mumpuni, profesional, dan visioner.
Untuk meningkatkan profesionalisme dan etika pers ataupun penyiaran, pemerintah juga
perlu memperkuat kedudukan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. Kedua lembaga
ini harus menjadi "wasit" sekaligus pembuat kebijakan dalam bidang pers dan penyiaran. KPI
harus dibuat semakin independen dari intervensi industri dan pemerintah. Fungsi KPI sebagai
regulator bidang penyiaran harus dipulihkan. Pada sisi lain, Dewan Pers perlu diberi daya
dukung administrasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia yang memadai agar dapat
meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pembinaan profesionalisme, etika media, serta
lembaga penyelesaian sengketa pers.
Di sisi lain, TVRI dan RRI harus diselamatkan kedudukannya sebagai lembaga penyiaran
publik. Berbeda dengan RRI yang kondisinya relatif baik, kondisi TVRI saat ini sangat
memprihatinkan. TVRI berjalan di tempat, bahkan dalam beberapa hal mengalami
kemunduran akibat konflik yang tak kunjung padam. Tarik-menarik kepentingan politik
antara unsur-unsur DPR, pemerintah, dan kalangan internal TVRI bahkan belakangan
semakin kusut. Masalah ini bagaimanapun harus diselesaikan. Namun penyelesaiannya jelas
bukan dengan cara mengembalikan kedudukan TVRI sebagai lembaga corong pemerintah,
tapi mengembalikan khitah TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Presiden yang baru
perlu memahami persoalan itu.
Jika lima tahun ke depan dilakukan amendemen terhadap UU Pers, harus dipastikan
amendemen ini memperkuat pelembagaan kebebasan pers, bukan sebaliknya. UU Pers
Nomor 40 Tahun 1999 masih mengandung beberapa kekurangan sehingga gagasan
amendemen menjadi relevan. Namun, fakta juga menunjukkan, belakangan ini sering terjadi
amendemen sebuah undang-undang yang tujuannya baik, tapi justru berakhir dengan
keburukan. Undang-undang baru hasil amendemen mengandung substansi-substansi yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan HAM, kebebasan berpendapat,
atau keterbukaan informasi.
Amendemen UU Pers yang menganulir prinsip-prinsip kebebasan pers hanya akan
menghadapkan pemerintah dan DPR pada hubungan yang antagonistik dengan komunitas
pers nasional. Amendemen itu juga akan membuat buruk citra Indonesia di mata dunia
internasional. Pemerintah yang baru harus menghindari amendemen semacam ini.
Noken
Jum'at, 22 Agustus 2014
Amiruddin al-Rahab, Pemerhati politik di Papua
Noken, barang sederhana yang terbuat dari rajutan rumput, atau kini benang sintetis, telah
menjadi leksikon politik nasional. Noken "manggung" di Mahkamah Konstitusi. Seluruh
Nusantara kini berkenalan dengan noken. Terima kasih MK.
Jika Anda blusukan ke kampung-kampung di pedalaman Papua, Anda akan mudah berjumpa
dengan iringan mama-mama yang memikul noken di kepala, dengan ditahan oleh tengkuk
dan punggung. Noken ini sesak oleh isi hasil kebun, bayi, atau hewan piaraan kesayangan.
Juga ada noken laki-laki, berbentuk kecil, yang dipakai dengan menyelempangkannya di
pundak. Isinya perlengkapan kecil-kecil, seperti pisau, sirih-pinang, rokok, pemantik api,
bahkan ponsel.
Bagi mama-mama di pegunungan Papua, noken yang terisi penuh mengisyaratkan bahwa
harapan baru akan datang. Mereka bergembira. Untuk itu, itu jika ada pesta adat, atau bakar
batu untuk makan bersama, mama-mama akan datang dengan noken yang penuh. Jika noken
kosong, itu pertanda datangnya masa paceklik atau komunitas itu berada dalam kesusahan.
Kembali ke urusan di MK. Jika Anda menangkap makna mendalam dari apa isi noken yang
dipersoalkan di MK itu, tampaklah isi noken itu menunjukkan harapan baru. Mengenai
persoalan prosedur dan hukum formal bukan lagi urusan mama-mama pemilik noken itu.
Noken kecemplung ke dalam politik adalah kecelakaan, bukan sesuatu yang dirancang. Ketika
pemilu pada 1971, dua tahun setelah Pepera, harus dilaksanakan, semua orang di Papua harus
pula dilibatkan.
Kepada dunia internasional, pesan harus disampaikan bahwa rakyat di Papua bisa
berpartisipasi dalam pesta demokrasi Indonesia. Lantas bagaimana caranya hal itu dilakukan
di tengah keterbatasan transportasi, komunikasi, serta akses ke pedalaman? Akibat populasi
tidak melek huruf yang tinggi, kampanye tidak bisa dilakukan secara sempurna. Tak ada cara
lain, sistem perwakilan harus ditempuh.
Dalam kondisi keterpaksaan dan keterbatasan itulah noken berjasa. Ingat, Golkar menang
telak karena waktu itu Golkar menggunakan lambang cermin di pegunungan Papua, bukan
pohon beringin. Tentu tangan aparatur pemerintah bermain leluasa pula. Sejak 1971 sampai
1997, hal itu terus berlangsung dengan pemenang yang sama pula.
Reformasi datang, sistem berubah, namun jasa noken tetap diperlukan oleh aktor-aktor
politik. Bahkan, noken tetap dipakai ketika diterapkannya sistem pemilihan langsung kepala
daerah dan kepala negara. Tapi aparatur negara tidak lagi bisa bersikap dominan. Elite atau
orang besar dari klan-klan dan suku-suku telah menjadi bagian dari sistem politik baru yang
dominan. Mereka menjadi tokoh protagonis dalam menjalankan sistem noken dalam politik.
Itu terjadi karena politik masuk sampai ke dalam honai, yang sebelumnya tidak pernah
terjadi.
Noken dan politik pada era reformasi ini tidak bisa dipisahkan lagi. Dulu karena
keterpaksaan, sekarang menjadi kebutuhan. Kebutuhan akan noken kian mendesak ketika
sarana dan prasarana untuk menjalankan pemilu secara langsung tidak berkembang sesuai
dengan perkembangan sistem politik yang ada.
Karena itu, mempersoalkan sistem noken di Papua bak pepatah lama, "menepuk air di dulang,
terciprat muka sendiri". Untuk itu, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu lebih baik
berterima kasih kepada noken ketimbang mempersoalkannya.
Ketidakpercayaan Sosial
Sabtu, 23 Agustus 2014
Candra Malik, peminat tasawuf
Kehilangan terbesar adalah kehilangan rasa percaya diri. Namun, kehilangan yang lebih besar
lagi adalah kehilangan kepercayaan dari orang lain, apalagi jika disusul dengan sanksi sosial.
Yang kurang-lebih sama besarnya adalah kehilangan kepercayaan kepada orang lain, yang
bisa menyebabkan sikap antisosial. Satu dan lainnya sama-sama berpotensi mencerabut
kodrat kita sebagai makhluk sosial. Kita menjadi penyendiri. Kita menyendiri.
Saat ini, kita hidup dalam suasana batin yang mengarah ke sana ketika gotong-royong
semakin mahal. Siskamling mulai digantikan oleh portal-portal di mulut gang, baik di
kampung-kampung maupun kompleks-kompleks perumahan, terutama di kota-kota.
Ketidakbersediaan sebagian warga untuk begadang di gardu ronda memicu kesepakatan
untuk membuka peluang kerja jasa keamanan, dan kita cukup membayar kompensasi
ketidakbersediaan untuk meronda malam.
Padahal, sesungguhnya kita sedang mengalami kehilangan; kehilangan rasa percaya diri,
kehilangan kepercayaan kepada orang lain, dan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kita
tidak lagi saling percaya. Pagar-pagar rumah semakin tinggi, pintu-pintu rumah siang-malam
dikunci, dan penghuni rumah tidak serta-merta membukakan pintu jika diketuk. Jangankan
pengamen, tamu pun kesulitan mendapat akses untuk ditemui oleh tuan rumah.
Di sebagian rumah, penghuninya masih menyambut ucapan salam dari luar rumah. Sebagian
lainnya telah menutup pintu rapat-rapat dan hanya memberi lonceng mesin suara. Semakin
sulit menemukan rumah dengan keakraban penghuninya, bahkan kepada orang-orang yang
lalu-lalang, melalui bahasa pelepas dahaga, yaitu ketersediaan kendi air minum di pagar.
Rukun tetangga dan rukun warga menjadi alat sosial belaka untuk mengurus surat-surat.
Musyawarah warga menjadi barang mewah. Warga menjadi berkelompok berdasarkan selera
sosial, entah itu dalam kegiatan beragama, berkesenian, berolahraga, atau berekreasi. Masih
ada pemersatu itu yang, syukurlah, bisa bertahan meski batasannya makin longgar. Bukan
lagi melulu berdasarkan tempat tinggal, tapi lebih pada kesamaan selera sosial. Dinamika ini
meretas keberagaman sekaligus keseragaman sosial.
Menjadi beragam karena memang aneka rupa selera sosial memunculkan warna-warni itu.
Menjadi seragam karena setiap komunitas kemudian melahirkan simbol-simbol identitas. Jika
dalam wilayah sosial yang melintas batas itu terus terjadi krisis kehilangan kepercayaan,
kondisinya bisa semakin runyam. Keberagaman justru bisa memicu kecurigaan
antarkomunitas dan kerukunan antarmanusia menjadi semakin jauh panggang dari api.
Lahirnya tokoh-tokoh sosial yang mendobrak kebekuan itu sungguh melegakan, dan kita
butuh lebih banyak dan lebih banyak lagi tokoh-tokoh itu. Mereka tidak harus aparatur
negara, tidak harus wakil rakyat. Apalagi kita sama-sama tahu betapa birokrasi dan protokol
begitu menyebalkan dan melelahkan. Masyarakat memerlukan terobosan dan kepemimpinan
untuk menjaga nyala api Bhinneka Tunggal Ika dan gotong-royong agar tidak padam.
Ketahanan yang Berbasis Tepung
Sabtu, 23 Agustus 2014
Rofandi Hartanto, Pengajar Ilmu dan Teknologi Pangan UNS Surakarta
Selama ini ada kebijakan yang kurang tepat yang dilaksanakan pemerintah kita. Kebijakan
pilihan tunggal atas pangan, yaitu beras, sebenarnya telah mengorbankan biodiversitas
alamiah pangan kita. Stigma underdog atas jenis-jenis pangan lain seperti jagung, sagu, dan
singkong tanpa terasa telah membebani orientasi pangan tunggal yang menjadi sangat mahal
dan relatif sulit dikendalikan.
Ketika kebijakan pangan nasional berbasis beras, permasalahan suplai dari tahun ke tahun
bertambah berat, akibat pertambahan penduduk yang makin besar. Angka 250 juta jiwa,
populasi terpadat keempat dunia, menjadi beban terus-menerus setiap periode pemerintahan,
tidak terkecuali pemerintah mendatang.
Untuk itu, sebagai ilustrasi, pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri dengan menerapkan
kebijakan pencetakan sawah baru sejumlah 400 ribu hektare, untuk memenuhi defisit pangan
sebesar 2 juta ton per tahun, haruslah dianggap sebagai strategi jangka pendek.
Untuk strategi jangka menengah dan jangka panjang, alternatif lain harus dicari, yang salah
satunya adalah kebijakan pangan berbasis tepung. Mengapa berbasis tepung? Karena jika kita
tengok kebijakan pangan dunia, (tepung) gandum meliputi lebih dari dua pertiga penduduk
dunia. Adapun pangan berbasis beras hanya didominasi oleh negara-negara Asia Selatan,
Asia Tenggara, Asia Timur Jauh, serta Cina. Kebijakan pangan berbasis tepung dirasa tepat,
karena sebenarnya kebijakan ini bersinggungan dengan kebutuhan tepung dan ketersediaan
tepung yang sangat melimpah di negeri ini.
Mengapa pangan nasional sebaiknya berbasis tepung? Pertama, tepung adalah sumber
karbohidrat utama, sama seperti beras, jagung, dan singkong. Tepung sendiri adalah produk
antara dari sumber-sumber pangan seperti disebutkan sebelumnya. Keunggulan tepung dari
sumber asalnya adalah pengolahan lebih lanjut menjadi berbagai pangan dalam bentuk basah
dan kering, bergantung pada tujuan kita mengolah bahan pangan. Tepung, dengan demikian,
bisa menjadi cadangan pangan masa depan. Adapun sumber-sumber tepung kita jauh lebih
berlimpah dibanding beras yang selalu membebani anggaran untuk ketahanan pangan.
Untuk sedikit membandingkan atau sedikit mempertimbangkan bagi pemenuhan pangan
nasional, jika program beras nasional adalah pemenuhan dalam jangka pendek pengamanan
kebutuhan beras dalam negeri seperti disebutkan sebelumnya, tepung akan menjadi cadangan
pangan nasional dalam jangka menengah dan panjang. Karena, untuk mengambil contoh,
ketersediaan tepung sagu akan 50 kali lebih besar dibanding beras.
Sebenarnya, apa yang menjadi konsep pemerintah selama ini dalam ketahanan pangan dan
energi sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara sudah tepat. Tapi, sebagai sebuah visi ke
depan, barangkali ini kurang menggigit. Maksudnya, visi pangan hanya untuk kebutuhan
sendiri tidaklah cukup memadai sebagai sebuah negara yang dikaruniai Tuhan dengan
sumber daya alam yang sangat melimpah.
Bayangkan kita memiliki 90 juta hektare lahan hutan produktif, 59 juta hektare lahan kritis,
dan 10 juta hektare lahan pertanian produktif. Dengan potensi yang ada, Indonesia nantinya
harus menjadi lumbung pangan dunia. Kita tidak boleh berpuas diri hanya dengan memenuhi
kebutuhan pangan sendiri. Kemandirian pangan, sebagai sebuah negara besar, adalah sebuah
keniscayaan. Tapi, sebagai sebuah visi negara besar, kecukupan pangan ditambah
ketersediaan pangan bagi dunia tampaknya merupakan keharusan. Masalah pangan dan
energi yang telah menjadi isu penting dalam dua dasawarsa terakhir agaknya harus menjadi
tantangan yang mesti dijawab.
Dengan itu, urgensi ketahanan pangan berbasis tepung menemukan muaranya. Pertama,
tepung dapat diproduksi dari aneka macam komoditas utama, seperti singkong dan sagu, serta
komoditas lainnya seperti umbi-umbian talas, ganyong, irut, gembili, gadung, dan iles-iles,
baik sebagai pangan alternatif maupun pangan fungsional.
Kedua, tepung sebagai cadangan pangan sekaligus sebagai cadangan energi hijau.
Bergantung pada cara pengolahan yang dipilih, tepung dapat menjadi aneka pangan basah
seperti kue, pangan kering untuk penyimpanan yang lama, seperti biskuit dan bahan baku
utama mi dan bihun, sekaligus sebagai cadangan energi (bioetanol).
Ketiga, daya simpan tepung dapat mencapai bulanan bahkan tahunan. Dengan penurunan
kadar air dan dan teknik penyimpanan tertentu, ini akan mencegah invasi bakteri dan kapang
untuk masa yang lama. Keempat, teknologi pengolahan/pemanfaatan tepung dari teknologi
konvensional (bagaimana membuat adonan kue yang cocok) hingga teknologi nano, nantinya
akan menjadi tantangan.
Jangan sampai, kiranya, kita yang mempunyai sumber daya tepung yang luar biasa namun
bergantung pada negara lain karena kurang mampu mengelola dan mengembangkannya-yang
pada gilirannya membuat ketahanan pangan ataupun kelimpahan pangan hanya menjadi
mimpi di siang bolong.
ISIS di Antara Kita
Sabtu, 23 Agustus 2014
Ahmad Taufik, Pendiri Garda Kemerdekaan
Video ajakan bergabung dengan Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) sekarang disebut
Islamic State (IS) disambut gegap gempita di berbagai pelosok Indonesia. Banyak orang
berbondong-bondong masuk, melalui acara baiat (sumpah setia). Selain janji surga dengan
jalan jihad, ada rindu cerita masa lalu, juga akibat kekuatan propaganda. Tak mengherankan
jika rekaman video kegiatan mereka selalu diunggah ke situs termasyhur saat ini, YouTube.
Bukti tersebarnya ISIS diketahui belakangan setelah populer dan dijadikan musuh bersama.
Polisi menemukan sejumlah identitas ISIS di berbagai tempat publik, dari bendera sampai
mural (seni gambar di tembok). Padahal, sebenarnya, sebelum sepopuler sekarang, ISIS
sudah berusaha bereksistensi. Bendera hitam dengan kalimat la ilaha ilallah terlihat berkibar
saat hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di Solo dan Jakarta.
Kenapa IS mendapat sambutan? Selain propaganda media, utopia negara Islam, dan janji
surga, bibit IS tumbuh subur di negeri ini. Ada beberapa asumsi penyebab tumbuh suburnya
kelompok itu. Bekas Perdana Menteri Inggris Tony Blair (2001) menyebut, "...negara gagal,
kemiskinan, dan pemutusan hubungan kerja (PHK)." Alan B. Krueger, dalam buku What a
Makes a Terrorist, (kalau kita mau menyebut ISIS teroris), berkata menjadi teroris adalah
pilihan hidup, cita-cita atau karier, seperti menjadi dokter, jurnalis, dan jenis pekerjaan lain.
Menurut Mohamad Guntur Romli (2009), berkembangnya kelompok radikal yang
mengedepankan kekerasan merupakan jalan lahir dari ketegangan, perebutan kekuasaan,
hingga konflik di Timur Tengah. Di Indonesia, banyak alumnus dari perguruan tinggi atau
pesantren di Timur Tengah yang pulang membawa "semangat kekerasan" dari tempat
pendidikannya itu. Kemudian, pihak yang berkonflik, melalui alumnus, mengajak pihak lain
untuk menjadi sekutu.
Satu faktor lagi penyebab tumbuh suburnya kelompok pro-kekerasan adalah peran aparat
keamanan (polisi). Aparat gamang menindak penyeru penyebar kebencian (hate crime). Hal
ini merupakan sumbangan bagi berkembangnya kelompok "jalan kekerasan", seperti ISIS
sekarang ini, sehingga pelakunya merasa mendapat perlindungan.
Sebenarnya, hanya memusuhi ISIS adalah salah, karena kelompok ini bisa berubah rupa.
Sebelum ini kita mengenal Al-Qaidah di Timur Tengah dan Jamaah Islamiyah (JI) di
Nusantara. Saat ini yang terpenting adalah mengidentifikasinya. Ada tiga ciri untuk
mengetahui kelompok seperti ISIS itu.
Pertama, kemantapan niat untuk mendirikan negara Islam dengan memberlakukan syariat
Islam sesuai dengan pemahaman kelompok mereka sendiri, sehingga seluruh konsep
kehidupan bernegara, selain pemberlakuan syariat Islam seperti yang mereka pahami,
menjadi batil (wajib diperangi). Kedua, tafsir kebenaran bersifat tunggal, sesuai dengan
pemahaman kelompok mereka. Untuk itu, siapa pun yang tidak menerima pemahaman tafsir
kebenaran mereka dianggap sesat dan kafir. Karena itu, setiap yang kafir, halal darahnya
untuk dibunuh. Ketiga, penganut agama selain Islam yang mereka pahami, agar tidak
dibunuh atau dipersekusi, diwajibkan membayar jizyah atau pajak perlindungan.
Nah, dengan tiga identifikasi tersebut, jangan-jangan kita juga turut serta menumbuhsuburkan
"ISIS-ISIS" lain di negeri ini. Jika asumsi itu benar, sia-sialah 69 tahun kemerdekaan yang
telah kita capai sekarang ini.
You might also like
- Nahdlatul Ulama Dan Pancasila (Oleh Einar M. Sitompul)Document259 pagesNahdlatul Ulama Dan Pancasila (Oleh Einar M. Sitompul)ekho109No ratings yet
- Biografi Sutan Syahrir Perdana Menteri Pertama IndonesiaDocument4 pagesBiografi Sutan Syahrir Perdana Menteri Pertama IndonesiaRenoRamadhaniNo ratings yet
- Sjarifuddin Antara Negaradan Revolusioleh Jacques LeclercDocument27 pagesSjarifuddin Antara Negaradan Revolusioleh Jacques LeclercHary TafianotoNo ratings yet
- Tokoh PahlawanDocument12 pagesTokoh PahlawanNovta PrisisyliaNo ratings yet
- Biografi Sutan SyahrirDocument4 pagesBiografi Sutan SyahrirRosaria Nikasari100% (1)
- PKIDocument22 pagesPKIImam FauzanNo ratings yet
- Biografi Sutan SyahrirDocument6 pagesBiografi Sutan SyahrirMia JayantiNo ratings yet
- Tokoh Pergerakan Nasional1Document12 pagesTokoh Pergerakan Nasional1anayusudNo ratings yet
- Perjuangan Politik Dan Pendidikan Ki Hajar DewantaraDocument6 pagesPerjuangan Politik Dan Pendidikan Ki Hajar Dewantaraade yuniedaNo ratings yet
- Misteri Tiga Orang KiriDocument4 pagesMisteri Tiga Orang KiriIsla SummerNo ratings yet
- Biografi Sutan SyahrirDocument7 pagesBiografi Sutan SyahrirSuci indrianiNo ratings yet
- Antara Negara Dan Revolusi Amir SjarifuddinDocument22 pagesAntara Negara Dan Revolusi Amir SjarifuddinSurachMan MamanNo ratings yet
- Amir Sjarifuddin Antara Negara Dan RevolusiDocument36 pagesAmir Sjarifuddin Antara Negara Dan RevolusiMuhammad AmriNo ratings yet
- Sutan SyahrirDocument5 pagesSutan SyahrirSyffa Rizki TriwulandariNo ratings yet
- Gie Lewat GieDocument7 pagesGie Lewat GieHilmar FaridNo ratings yet
- Disintegrasi Berbagai Peristiwa Pergolakan Di Dalam NegeriDocument11 pagesDisintegrasi Berbagai Peristiwa Pergolakan Di Dalam Negerisejarah smandaNo ratings yet
- Biografi Hos CokroaminotoDocument6 pagesBiografi Hos CokroaminotoFu JoNo ratings yet
- Kemunculan Orde Baru Dan Pembunuhan Massal1 OLEH BONNIE TRIYANA2 Gestapu 1965Document33 pagesKemunculan Orde Baru Dan Pembunuhan Massal1 OLEH BONNIE TRIYANA2 Gestapu 1965dianwangiNo ratings yet
- Soal Bacaan Teks Cerita SejarahDocument2 pagesSoal Bacaan Teks Cerita SejarahListia Ningsih75% (4)
- Sutan SyahrirDocument1 pageSutan SyahrirLia IronclawNo ratings yet
- Bab 1Document43 pagesBab 1Taufik AhmadNo ratings yet
- Laporan Novel SejarahDocument7 pagesLaporan Novel SejarahRezafadilah RohmanNo ratings yet
- Bab I - FinalDocument43 pagesBab I - FinalTaufik AhmadNo ratings yet
- Biografi Sayuti Melik (Deniyanti)Document3 pagesBiografi Sayuti Melik (Deniyanti)Hafiz Maulana100% (1)
- H.O.S Cokroaminoto Guru Bangsa Dan NegaraDocument9 pagesH.O.S Cokroaminoto Guru Bangsa Dan NegaraRizka AmaliaNo ratings yet
- Benedict Anderson - Nasionalisme Indonesia Kini Dan Di Masa DepanDocument42 pagesBenedict Anderson - Nasionalisme Indonesia Kini Dan Di Masa DepanROWLAND PASARIBU100% (11)
- Pahlawan Yang TerlupakanDocument2 pagesPahlawan Yang TerlupakanIzzuddin Ar RofiNo ratings yet
- Salsabila Istiningrum - Cipto MangunkusumoDocument3 pagesSalsabila Istiningrum - Cipto Mangunkusumoulfha nishaNo ratings yet
- Makalah TentangDocument45 pagesMakalah TentangAdin BmNo ratings yet
- TelahTerbitBuku G30SdanKejahatanNegaraDocument6 pagesTelahTerbitBuku G30SdanKejahatanNegaraFaihaNo ratings yet
- A. Indikator Pencapaian KompetensiDocument24 pagesA. Indikator Pencapaian KompetensiTeuku Zaldi MaulanaNo ratings yet
- Artikel Peran Tokoh Pahlawan IndonesiaDocument15 pagesArtikel Peran Tokoh Pahlawan IndonesiaRosyid FerdiansyahNo ratings yet
- Sejarah Singkat Gerakan Kiri Di IndonesiaDocument5 pagesSejarah Singkat Gerakan Kiri Di IndonesiaAwal HanajNo ratings yet
- Terjemahan THE DISPUTES BETWEEN TJIPTO MANGOENKOESOEMO AND SOETATMO SOERIOKOESOEMO - SATRIA VSDocument18 pagesTerjemahan THE DISPUTES BETWEEN TJIPTO MANGOENKOESOEMO AND SOETATMO SOERIOKOESOEMO - SATRIA VSM Faisal AdnanNo ratings yet
- Review Per. 4Document4 pagesReview Per. 4Sry HandayaniNo ratings yet
- Jepretan Layar 2023-11-30 Pada 18.00.15Document19 pagesJepretan Layar 2023-11-30 Pada 18.00.15I Dewa Ayu / X-3No ratings yet
- Tan MalakaDocument6 pagesTan MalakaMuhammad Iqbal PurwanaNo ratings yet
- Wiji ThukulDocument4 pagesWiji ThukulFattan FaydzulhaqNo ratings yet
- Biografi Dan Profil Mohammad HattaDocument8 pagesBiografi Dan Profil Mohammad HattaRidwan Condensate100% (1)
- New Sejarah G 30 S PKIDocument12 pagesNew Sejarah G 30 S PKISarita SaraswatiNo ratings yet
- Biografi PahlawanDocument6 pagesBiografi PahlawanarsyaNo ratings yet
- Jatuh-Bangun Gerakan Kiri Di IndonesiaDocument6 pagesJatuh-Bangun Gerakan Kiri Di IndonesiaDhanie Ardhan Alvar PosposNo ratings yet
- Perang Indonesia Vs Belanda Belum BerakhirDocument15 pagesPerang Indonesia Vs Belanda Belum BerakhirKencana WinedNo ratings yet
- Tokoh Pejuang Sayuti MelikDocument4 pagesTokoh Pejuang Sayuti MelikepalayukanNo ratings yet
- 20 Tokoh Proklamasi Dan KemerdekaanDocument10 pages20 Tokoh Proklamasi Dan KemerdekaanVideo Kocak BolaNo ratings yet
- Ki Hajar DewantaraDocument5 pagesKi Hajar Dewantarauzumaki_nratNo ratings yet
- Tugas Membuat Soal AKM Sejarah Indonesia Latihan AnakDocument12 pagesTugas Membuat Soal AKM Sejarah Indonesia Latihan AnakRahman MaulanaNo ratings yet
- Pahlawan NasionalDocument6 pagesPahlawan NasionalArya SuprihatinNo ratings yet
- Raja Tanpa MahkotaDocument8 pagesRaja Tanpa MahkotaMuhammad AsroruddinNo ratings yet
- Wicaksono Adi - Dalam Pusaran Kabut Dan Darah 807086Document9 pagesWicaksono Adi - Dalam Pusaran Kabut Dan Darah 807086simonSapalaNo ratings yet
- PDF Memoar Perempuan Revolusioner Francisca C. FanggidaejDocument199 pagesPDF Memoar Perempuan Revolusioner Francisca C. Fanggidaejaditya maulanaNo ratings yet
- Kaidah KebahasaanDocument3 pagesKaidah KebahasaanasyrafnbNo ratings yet
- Peran Besar Bung Kecil Biografi SjahrirDocument135 pagesPeran Besar Bung Kecil Biografi SjahrirRioMacNo ratings yet
- Soekarno DN Aidit Dan PKIDocument38 pagesSoekarno DN Aidit Dan PKIPeter Kasenda100% (1)
- Si Jalak Harupat Penyeru Perdana Kata MerdekaDocument3 pagesSi Jalak Harupat Penyeru Perdana Kata MerdekaMohammad Nurul MausufNo ratings yet
- Biografi Bung TomoDocument3 pagesBiografi Bung TomoAMELIA HUDAEBANo ratings yet
- Berbagai Wawancara Dari Sebuah Dekade Yang Singkat: Mengenal Lebih Dekat Tokoh-Tokoh Terkemuka Abad Ke-20 Dari Dunia Politik, Budaya, Dan SeniFrom EverandBerbagai Wawancara Dari Sebuah Dekade Yang Singkat: Mengenal Lebih Dekat Tokoh-Tokoh Terkemuka Abad Ke-20 Dari Dunia Politik, Budaya, Dan SeniNo ratings yet
- Pelarian Amoy: Sepenggal Tragedi Jakarta '98 dan Kengerian di BaliknyaFrom EverandPelarian Amoy: Sepenggal Tragedi Jakarta '98 dan Kengerian di BaliknyaNo ratings yet
- Habitat Kaum Sosialis Di IndonesiaDocument1 pageHabitat Kaum Sosialis Di Indonesiaekho109No ratings yet
- Pendapat 2016Document339 pagesPendapat 2016ekho109No ratings yet
- Pendapat 2017Document155 pagesPendapat 2017ekho109No ratings yet
- Bismar Nasution - Reformasi Pendidikan Hukum Untuk Menghasilkan SH Yg Kompeten Dan ProfesionalDocument18 pagesBismar Nasution - Reformasi Pendidikan Hukum Untuk Menghasilkan SH Yg Kompeten Dan Profesionalekho109No ratings yet
- Quraish Shihab - Membumikan Al QuranDocument219 pagesQuraish Shihab - Membumikan Al Quranekho109100% (5)
- (Sindonews - Com) Opini Hukum-Politik 28 Maret 2016-9 Mei 2016Document189 pages(Sindonews - Com) Opini Hukum-Politik 28 Maret 2016-9 Mei 2016ekho109No ratings yet
- Puisi-Puisi Goenawan Mohamad Di Kompas 20 September 2015Document6 pagesPuisi-Puisi Goenawan Mohamad Di Kompas 20 September 2015ekho109No ratings yet
- Tan Malaka - ThesisDocument112 pagesTan Malaka - Thesisekho109No ratings yet
- (Sindonews - Com) Opini Hukum-Politik 25 Juli 2015-5 September 2015Document163 pages(Sindonews - Com) Opini Hukum-Politik 25 Juli 2015-5 September 2015ekho109No ratings yet
- Sutan Syahrir - Perjuangan KitaDocument17 pagesSutan Syahrir - Perjuangan Kitaekho109No ratings yet
- Resonansi Azyumardi Azra 2015Document136 pagesResonansi Azyumardi Azra 2015ekho109No ratings yet
- Imam Al-Ghazali - Kitab Kimyatusy Sya'Adah (Kimia Kebahagiaan)Document66 pagesImam Al-Ghazali - Kitab Kimyatusy Sya'Adah (Kimia Kebahagiaan)ekho109100% (1)
- Resonansi Asma Nadia 2015Document151 pagesResonansi Asma Nadia 2015ekho109No ratings yet
- Pendapat 1-26 Februari 2015Document39 pagesPendapat 1-26 Februari 2015ekho109No ratings yet
- Metamorfosis NU Dan Politisasi Islam Di IndonesiaDocument194 pagesMetamorfosis NU Dan Politisasi Islam Di Indonesiaekho109No ratings yet
- Tan Malaka - Aksi MassaDocument111 pagesTan Malaka - Aksi Massaekho109No ratings yet
- Tan Malaka - Menuju Republik IndonesiaDocument71 pagesTan Malaka - Menuju Republik Indonesiaekho109No ratings yet
- (Sindonews - Com) Opini Ekonomi Koran Sindo 15 Juni 2015-1 September 2015Document156 pages(Sindonews - Com) Opini Ekonomi Koran Sindo 15 Juni 2015-1 September 2015ekho109No ratings yet
- Daoed Joesoef - EmakDocument231 pagesDaoed Joesoef - Emakekho109100% (2)
- Al-Ghazali - Kitab Bidayatul HidayahDocument52 pagesAl-Ghazali - Kitab Bidayatul Hidayahekho109100% (2)
- (Sindonews - Com) Opini Sosial-Budaya 21 Juli 2015-3 September 2015Document162 pages(Sindonews - Com) Opini Sosial-Budaya 21 Juli 2015-3 September 2015ekho109No ratings yet
- Artikel Pilihan Media Indonesia 17 Maret 2015Document76 pagesArtikel Pilihan Media Indonesia 17 Maret 2015ekho109No ratings yet
- Artikel Pilihan Media Indonesia 17 Februari 2015Document67 pagesArtikel Pilihan Media Indonesia 17 Februari 2015ekho109No ratings yet
- (Sindonews - Com) Opini Sosial-Budaya 6 Juni 2015-20 Juli 2015Document155 pages(Sindonews - Com) Opini Sosial-Budaya 6 Juni 2015-20 Juli 2015ekho109No ratings yet
- (Sindonews - Com) Opini Hukum-Politik 22 Mei 2015-24 Juli 2015Document153 pages(Sindonews - Com) Opini Hukum-Politik 22 Mei 2015-24 Juli 2015ekho109No ratings yet
- (Sindonews - Com) Opini Ekonomi 11 April 2015-13 Juni 2015Document158 pages(Sindonews - Com) Opini Ekonomi 11 April 2015-13 Juni 2015ekho109No ratings yet
- Artikel Pilihan Media Indonesia Minggu 3 Mei 2015Document55 pagesArtikel Pilihan Media Indonesia Minggu 3 Mei 2015ekho109No ratings yet
- (Sindonews - Com) Opini Ekonomi Koran Sindo 27 November 2014-11 Februari 2015Document154 pages(Sindonews - Com) Opini Ekonomi Koran Sindo 27 November 2014-11 Februari 2015ekho109No ratings yet