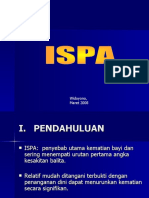Professional Documents
Culture Documents
Sejarah Kegilaan Dan Konstruksi Kebenaran
Uploaded by
nezapurnamasariCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Sejarah Kegilaan Dan Konstruksi Kebenaran
Uploaded by
nezapurnamasariCopyright:
Available Formats
Kamis, 11 Desember 2008
Sejarah Kegilaan dan Konstruksi Kebenaran
Anda mungkin ingat, pada tahun 2002, sebuah film berjudul A Beautiful Mind
John Nash peraih Nobel matematika yang juga penderita schizophrenia. Asal
tahu saja, film itu lalu dikritik habis-habisan oleh beberapa pengamat film dan
perusahaan film pesaing, gara-gara dianggap mengabaikan sisi homoseksualitas
dan kecenderungan anti-Semit yang ada pada diri Nash. Sementara itu, penulis
biografi Nash, Sylvia Nasar, meskipun membelanya namun ia malah menulis
bahwa karya-karya tulis anti-Semit dari Nash lebih merupakan wujud dari sakit
jiwanya ketimbang kefanatikannya. dinominasikan meraih piala Oscar.
Kisah dalam film tersebut adalah karya
Pernyataan para pengkritik Nash ini, bahkan juga penulis biografinya (yang
tampak membelanya) adalah contoh gambaran nyata tentang citra negatif dan
perlakuan yang tidak mengenakkan terhadap orang yang mengalami
schizophrenia, yang malahan disebut oleh penulis biografi Nash sebagai sakit
jiwa. Bukan hanya itu, perilaku homoseksual dianggap sebagai praktek yang
menyimpang dan abnormal sehingga perlu dikenai sanksi sosial, atau setidaknya
disembuhkan.
Nasib orang gila dalam keseharian
Dalam kehidupan sehari-hari kisah-kisah lain tentang orang-orang gila, orang
yang mengalami masalah kejiwaan atau kelainan mental seperti penderita
psikosis, schizophrenia, stress, depresi, dan sebagainya seringkali mengalami
nasib yang jauh mengenaskan. Gejala-gejala seperti ini dipandang sebagai
penyakit yang secara medis perlu disembuhkan. Masih beruntung bagi seorang
Nash. Orang-orang yang selama ini dibilang gila dan tidak waras oleh
masyarakat berkeliaran di pinggiran jalan dan menjadi obyek cemoohan. Mereka
berada dalam kondisi yang benar-benar menyedihkan.
Orang-orang gila ini seringkali dikonsepsikan sebagai mereka yang menyimpang
dari mayoritas masyarakat. Mereka dianggap defiant dalam kategori abnormal.
Terhadap mereka, masyarakat menghardiknya sementara pemerintah pun
menyingkirkannya, setidaknya mengasingkannya secara tidak manusiawi. Di
Jakarta dan di kota-kota metropolitan pada umumnya, mereka dianggap sebagai
sampah yang mengganggu keindahan, kenyamanan, dan ketertiban kota. Tidak
jarang kita jumpai aparat Trantib pemerintah daerah setempat menggaruk
mereka tanpa rasa prikemanusiaan sedikitpun.
Perlakuan buruk masyarakat dan aparat pemerintah terhadap orang-orang yang
disebut gila ini ternyata juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh
kalangan akademis dan orang-orang terpelajar yang menempuh studi bidang
kedokteran. Atas nama penelitian ilmiah, kegilaan dipahami dan diajarkan
sebagai penyakit yang harus disembuhkan secara medis. Mereka, para ahli
psikiatri, sibuk menciptakan kategori-kategori dan definisi-definisi kegilaan
berikut cara-cara penanganannya. Melalui definisi dan kategori itu lantas mereka
merasa berhak menentukan mana orang gila dan mana yang waras, siapa yang
sehat dan siapa yang sakit, serta apa yang normal dan apa yang abnormal.
Pada gilirannya lalu mereka mengintrodusir mekanisme-mekanisme tertentu dan
berbeda tentang bagaimana seharusnya memperlakukan mereka.
Perlakuan terhadap orang gila yang semena-mena ini biasanya ditentukan oleh
persepsi dan konsepsi masyarakat atau pemerintah terhadap kegilaan. Oleh
karena itu sebuah konsepsi yang keliru tentang kegilaan pasti akan
membuahkan penanganan yang keliru pula. Dan pada gilirannya cara
penanganan yang salah ini akan menyebabkan orang yang mengalami kegilaan
sendiri malah bertambah menderita, bukannya dipulihkan.
Nah, dalam paparan ini saya ingin menunjukkan bahwa dalam sejarahnya
konsep kegilaan telah dipahami secara berbeda-beda oleh masyarakat. Setiap
masa dan periode memiliki konsep tersendiri mengenai kegilaan dan bagaimana
ia harus ditangani, serta bagaimana dampak penanganan itu bagi penderita
sendiri. Paparan ini sekaligus memperlihatkan bahwa konsep kegilaan sebagai
penyakit yang harus disembuhkan secara medis adalah fenomena baru dalam
dunia modern sekarang ini. Demikian juga kategori-kategori abnormalitas dan
menyimpang merupakan konstruksi sosial yang telah menjadi mitos. Sebuah
mitos rasionalitas yang dibangun oleh aparat-aparat kemajuan, rezim
pengetahuan, dan modernisme.
Dalam hal ini tidak bisa tidak kita berhutang jasa pada Michel Foucault yang
berhasil menggali bukti sejarah melalui serangkaian penelitiannya tentang
sejarah kegilaan di Eropa.
Konsep kegilaan dalam lembaran sejarah: Orang Gila dan Penyakit Lepra
Pada abad Tengah, sebelum abad ke-15, di Eropa orang-orang gila dihubungkan
dengan terjadinya penghilangan dan pengeksklusian terhadap para penderita
lepra dari masyarakat umum, dan mereka ditempatkan pada rumah-rumah sakit
terpisah. Di seluruh daerah kekristenan ternyata jumlah rumah sakitnya
mencapai 19.000 buah. Sekitar tahun 1226 ketika Louis VIII membuat undang-
undang rumah sakit lepra bagi Perancis, lebih dari 2000 kantor pendaftaran
muncul. Di keuskupan Paris sendiri terdapat 43 kantor. Dua kantor paling besar
sekitar Paris adalah Saint-Germain dan Saint-Lazare. Sementara itu pada abad
ke-12, Inggris dan Skotlandia memiliki sedikitnya 220 rumah sakit bagi setengah
juta penduduknya.
Lalu memasuki abad ke-15 semua rumah sakit itu perlahan-lahan mulai kosong.
Dengan mulai menghilangnya penyakit lepra ini di Eropa, masyarakat
menyelenggarakan pesta sukacita dan syukuran yang sangat meriah. Namun
sesuatu telah berubah. Ada fenomena baru yang muncul seiring dengan
menghilangnya lepra. Pada abad berikutnya kantor Saint-Germain di Paris
bergeser menjadi tempat untuk mereformasi anak-anak nakal. Sementara itu di
Inggris institusi-institusi rumah sakit itu digunakan untuk menangani orang-orang
miskin. Adapun di Stuttgart Jerman, sebuah laporan pengadilan tahun 1589
mengindikasikan bahwa selama lima puluh tahun tidak ada lagi penderita lepra di
rumah-rumah sakit. Tapi di Lipplingen, rumah sakit lepra berubah dipakai untuk
menampung orang-orang yang tidak bisa disembuhkan dan orang-orang gila.
Pada awal abad ke-17, lepra benar-benar lenyap dari daratan Eropa. Meski
demikian ada hal yang masih tersisa yang menarik dari hilangnya lepra ini dan
terus berlanjut ke periode berikutnya. Yakni suatu struktur yang tetap tinggal
dalam imaji-imaji masyarakat yang dilekatkan pada ciri penderita lepra, yakni
struktur pengucilan atau eksklusi itu sendiri. Mengapa struktur ini masih bertahan
meski penderita lepra telah tiada?.
Berlanjutnya “tradisi” pengucilan ini sebenarnya bisa ditemukan akarnya pada
kosmologi gereja Abad Pertengahan yang mengenal konsep penyerahan diri
sebagai kunci penyelamatan. Penyakit merupakan tanda kemarahan sekaligus
anugerah Tuhan. Menerima dengan sabar segala penderitaan serta menerima
konsekuensi pengucilan akibat penyakitnya memiliki makna sebentuk komuni
kepada Allah. Pandangan semacam inilah yang ikut memungkinkan struktur
pengucilan itu terus terjadi dan “direproduksi” bersamaan dengan kepercayaan
reintegrasi spiritual Gereja. Dengan demikian sebenarnya hilangnya penderita
lepra ini telah menyebabkan kekosongan obyek pemberlakuan hukum moral
dalam spiritual Gereja. Sehingga konsekuensinya nilai-nilai moral yang semula
dikenakan kepada penderita lepra yang kini telah lenyap harus mendapatkan
kambing hitam lainnya. Pertanyaannya siapa kambing hitamnya? Mari kita ikuti
kisah orang gila pada abad berikutnya.
Orang Gila dan Parodi Kritik Sosial
Memasuki periode renaisans, kisah tentang orang-orang gila mulai beragam.
Dalam beberapa karya sastra klasik digambarkan mengenai orang-orang gila
yang yang dinavigasikan dalam kapal di lautan. Namun gambaran kapal-kapal itu
bersifat romantik dan satiris yang secara simbolis membawa orang-orang gila ke
pulau keberuntungan dan kebenaran mereka. Di antara karya-karya ini adalah
Symphorien Champier yang memadukan Ship of Princes and Battles of Nability
pada tahun 1502 dengan Ship of Virtous Ladies tahun 1503.
Terdapat juga Ship of Health bersama dengan Bauwe Schute Jacob van
Oestvoren tahun 1413.
Adapun dalam Narranschiff, orang-orang gila itu bebas berlayar dari kota ke
kota. Mereka berlayar dengan mudah dan diijinkan mengembara di daerah
terbuka. Pada masa renaisance ini, orang-orang gila diperlakukan secara baik,
dirawat sedemikian rupa di tengah-tengan warga kota, seperti di Jerman. Selain
itu bahtera-bahtera ziarah dan kargo-kargo menjadi perlambang orang-orang gila
yang tengah mencari rasionya.
Masa ini disebut juga “fase ambang” bagi orang-orang gila. Mereka yang di
samping sebagai tahanan, juga memiliki ruang bebas.
Dalam karya sastra, semisal Praise of Folly karangan Erasmus, dan The Cure of
Madnes dan Ship of Fools karangan Hieronymus Bosch, kegilaan sering
dimainkan sebagai parodi atau satire dalam pertunjukan drama-drama. Justeru
mereka yang dilekati status gila adalah mereka yang dengan keanehannya
membawa kabar kebenaran dan pesan kebijaksanaan. Foucault menyebutnya
orang-orang yang dikaruniai hikmat. Orang gila, orang bodoh atau orang tolol
inilah yang justeru memiliki eksistensi penting sebagai penjaga moral dan
kebenaran. Dalam spontanitas parodi, mereka melontarkan kritisisme sosial dan
moral. Mereka menjungkirbalikkan norma-norma, asumsi-asumsi, dan
pandangan-pandangan umum yang dianut masyarakat. Orang gila macam ini
dibiarkan berkeliaran. Ia menjadi lambang/simbol kebijaksanaan, atau semacam
Kebodohan yang melawan dan berdialog dengan supremasi kepintaran rasio.
Orang Gila dan Hospital Generale
Seiring bergulirnya waktu, makna positif kegilaan era renaisans yang menandai
dialog kritis antara “kebodohan” dan rasio ini pelan-pelan lenyap. Tema-tema
kapal kegilaan berakhir dan muncullah tema “Rumah Sakit Jiwa”.
Pada abad ke-17 terjadi pergeseran makna dan posisi orang-orang gila ini.
Di Paris, Inggris, Skotlandia, dan juga Jerman, tiba-tiba secara serentak hampir
bersamaan, orang-orang gila ditempatkan dalam “Hospital Generale”; sebuah
rumah pengurungan yang dibangun atas biaya pemerintah.
Di Paris, pendirian Hospital Generale ini sengaja didekritkan pada tahun 27 April
1656. Bersamaan dengan itu, gudang-gudang senjata, rumah tinggal, balai-balai
kota, dan rumah-rumah sakit difungsikan sebagai rumah pengurungan. Ruang di
mana orang miskin Paris, orang-orang cacat dengan segala jenis kelamin dan
keturunan, dalam kondisi sehat atau tidak sehat ditempatkan di dalamnya. Pinel,
misalnya menemukan orang-orang Gila dalam Hospital Generale di Bicetre
(rumah prajurit) dan La Salpetriere (gudang senjata). Di sana hukuman dan
represi diberlakukan dengan sadis oleh raja, polisi dan pengadilan.
Di Paris, Hopital Generale ini sama sekali tidak terkait dengan dengan suatu
konsep medis tertentu untuk merawat orang-orang gila, melainkan kekuasaan.
Kenyataan ini ditunjukkan dari peristiwa pembubaran Pusat Yayasan Sosial
Gereja Seluruh Negara (Grand Almonry of the Realm) yang bertugas memberi
bantuan sosial dan kesejahteraan kepada masyarakat oleh penguasa raja..
Dengan penghapusan ini diharapkan pemerintah akan lebih leluasa menerapkan
proses pengurungan tanpa intervensi hukum dari lembaga-lembaga lain. Dengan
demikian sesungguhnya Hospital Generale tidak lain merupakan instansi aturan
dari tatanan monakhial dan borjuis belaka yang dijalankan di Perancis selama
periode tersebut.
Adapun di Jerman, rumah-rumah pengoreksian atau Zuchthausern, semacam
Hospital Generale didirikan
di Hamburg sekitar tahun 1620,
Basel (1667), Breslau (1668),
Frankfurt (1684),
Spandau (1684) dan
Konigsberg (1691).
Jumlah ini pun masih berkembang di Leipzig, Halle, Cassel, Brieg, Osnabruck
dan Torgau. Bangunan kurungan ini mirip struktur semi-pengadilan, yang
memiliki aparat-aparat administratif yang memiliki kekuasaan mutlak dan aturan-
aturan yang independen di luar peradilan, kehakiman, dan keputusan raja.
Orang-orang gila dikurung bersama-sama dengan para tuna-wisma,
pengangguran, orang sakit, orang tua, orang yang tidak waras, dan kaum miskin.
Di Inggris, asal-usul pengurungan ini diperoleh dengan penemuan akta pada
tahun 1575 yang berisi “hukuman atas para gelandangan dan pembebasan
orang-orang miskin”. Rumah-rumah pengoreksian dibangun mencapai angka
satu rumah setiap desanya. “Akta proyek” ini telah menempatkan para
pengangguran, gelandangan, dan orang-orang miskin ke dalam rumah-rumah
pengoreksian. Mereka dikurung dan dipekerjakan di dalamnya. Yang paling
mengerikan mereka berada di bawah tanggungan pribadi-pribadi sehingga
sering diperlakukan sewenang-wenang.
Sebuah akta tahun 1670
pengadilan menegaskan status mereka dalam rumah-rumah kerja. Tidak kalah
juga pada tahun 1697 beberapa jemaah gereja Bristol bersatu padu membentuk
rumah-rumah kerja pertama di Inggris. Rumah kerja kedua dibangun di
Worcester tahun 1703 dan ketiga di Dublin, lalu di Plymouth, Norwich, Hull dan
Exester. Hingga pada akhir abad ke-18, rumah-rumah kerja ini sudah mencapai
terdapat 126 buah. Rumah-rumah kerja ini lalu meluas sampai Belanda, Italia,
dan Spanyol. Penghuninya pun mulai heterogen. Dari orang-orang yang dituduh
melanggar hukum dalam masyarakat, anak nakal, pemboros, orang yang tidak
memiliki profesi sampai mereka yang dianggap tidak waras.
Perlu ditekankan di sini, bahwa pada abad tersebut masyarakat industri yang
menekankan sebesar-besarnya produksi mulai terbentuk di Eropa. Karenanya
lalu kriteria kegilaan pun ditujukan bagi mereka yang tidak mampu bekerja, para
peminta, orang-orang malas, atau mereka yang tidak lagi produktif.
Pada tahun 1532, Parlemen Paris memutuskan menangkap pengemis dan
memaksa mereka bekerja di pabrik tenun dengan kaki di rantai.
Tahun 1534, para pengemis dan gelandangan harus meninggalkan kota dan
dilarang menyanyi himne di jalan-jalan. Pada tahun 1657 keluar sebuah
maklumat berisi larangan kepada siapapun untuk mengemis di kota dan di desa
sekitar Paris.
Bahkan pada tahun 1622 muncul pamflet Grievous Groan for the Poor (Rintihan
yang menyedihkan bagi orang-orang miskin) dibuat oleh Thomas Dekker yang
menekankan bahaya yang akan terjadi atas keberadaan orang-orang miskin dan
merekomendasikan agar mereka dibuang ke tanah baru India Barat dan Timur.
Atau mereka ditempatkan dalam rumah-rumah pengoreksian.
Tampak kemudian apa yang disebut sebagai Hospital Generale ini adalah
tempat pengurungan bagi orang-orang yang dianggap abnormal, gila, dan
menyimpang. Mereka adalah pengangguran, pengemis, pemalas, orang-orang
cacat, juga orang yang tidak waras dan tidak mampu bekerja. Di dalam Hospital
Generale ini lalu mereka ditempatkan untuk diberikan pekerjaan oleh penguasa.
Tujuannya bukan untuk menjamin kesejahteraan mereka, melainkan sebagai
disposisi penguasa tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Tepatnya
sebuah etika bahwa manusia harus melakukan kerja sebagai sebuah hukuman.
Menjadi kewajiban moral penguasa untuk membuat manusia itu bekerja. Dengan
bekerja, manusia membedakan dirinya dengan binatang, yakni sebagai manusia
yang waras.
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa fungsi Hospital Generale adalah alat
koreksi belaka terhadap status kegilaan seseorang; yakni mencegah
kesemrawutan tatanan dari orang-orang malas, pengemis dan pengangguran,
yang notabene dianggap sebagai dimensi kebinatangan manusia. Atas nama
“kewajiban moral” ini penguasa melakukan serangkaian praktek pendisiplinan
dan represi fisik terhadap orang-orang gila. Mereka diikat dengan rantai, dipukuli,
berada dalam pasungan, digantung, dan dtempatkan dalam penjara-penjara
untuk mentaati kerja.
Peristiwa ini bisa dihubungkan dengan pengkambinghitaman atas hilangnya
subyek moral setelah penyakit lepra di daratan Eropa menghilang.
Orang Gila dan Disiplin Psikiatri
Memasuki abad 19, orang-orang gila dikelompokkan dan dikategorisasikan ke
dalam mereka yang mengalami gangguan mental, stres, neurosis, melankolis,
atau schizoprenia dimasukkan dalam rumah-rumah sakit jiwa. Mereka menjalani
proses “penyembuhan”. Mereka tidak lagi mengalami represi fisik (diikat pada
rantai atau dicambuk seperti seabad sebelumnya), juga mereka tidak menjadi
tanggung jawab masyarakat bersama, melainkan kegilaan itu ditangani oleh
seorang dokter, seorang terapist atau seorang psikiater untuk disembuhkan bak
suatu penyakit.
Bagaimana mekanismenya?
Adapun mekanismenya adalah melalui kesunyian dan penyadaran layaknya
orang yang bertatapan dengan “cermin”. Maksudnya: orang-orang gila ini
ditempatkan dalam kesunyian, berbicara, menatap dan mengoreksi dirinya
sendiri, bagaikan berada dihadapan sebuah cermin, sehingga menyadari
kegilaannya. Melalui percakapan, bahasa dan kata-kata, terapi mencoba
meyakinkan orang gila akan status kegilaannya dan menyadari dirinya sendiri
benar-benar gila supaya bebas dari kegilaan tersebut. Melalui terapi itu mereka
dihinakan karena status kegilaannya itu.
Di sini tentu saja sang terapis-lah (dokter) yang menentukan disposisi gila dan
tidak, rasional atau tidak rasional. Dan perlahan-lahan cara-cara, aturan-aturan,
dan pengetahuan terapi ini diinstitusionalisasikan dalam suatu disiplin ilmu yang
kita kenal sekarang ini sebagai disiplin ilmu psikiatri, berikut teknik
psikoanalisisnya.
Penilaian kegilaan ini dilakukan secara terus menerus! Apa yang dilakukan oleh
tokoh medis ini dalam teknik psikiatrinya bukanlah diagnosa obyektif dan ketat
atas kegilaan itu sendiri, melainkan mengobservasi dan mempercakapkan
kegilaan itu sendiri pada penderitanya. Tokoh medis itu mengorek sumber-
sumber kegilaan, mengungkap kesalahan-kesalahan tersembunyi, dan biasanya
berusaha menghadirkan rasionalitas menggantikan unsur-unsur atau perasaan
irasionalitas penyebab kegilaan. Dokter, melalui otoritas keilmuannya,
mengontrol, mengawasi, dan menentukan kehendak, moralitas dan makna
keteraturan atau kewarasan dalam diri pasien.
Menurut Foucault, tahap ini merupakan tindakan yang lebih menyakitkan
daripada represi fisik sebagaimana terjadi sebelumnya. Mengapa?
Karena disiplin psikiatri justeru menjadi alat represi paling paripurna yang
langsung menusuk ke jantung batin, mengawasi perasaan dan pikiran manusia.
Jika pada abad klasik orang gila dibiarkan berkeliaran atau dihempaskan
berlayar dalam samudra kebebasan, lalu pada abad berikutnya mereka dikurung
dalam penjara Hospital Generale yang represif dan mematikan, maka pada abad
19 ini kegilaan adalah sebuah penyakit dan penderitanya mesti ditempatkan
dalam rumah sakit jiwa untuk disembuhkan secara medis. Bukan hanya itu,
sekarang telah muncul suatu otoritas baru yang memiliki otoritas tunggal
menentukan status kegilaan seseorang.
Yakni: para ahli dan dokter. Tidak berhenti di situ mereka pun menciptakan
disiplin keilmuan baru untuk melegitimasi kekuasaannya. Yakni: disiplin ilmu
psikiatri.
Dengan demikian pada jaman modern ada tiga institusi yang saling terkait dan
dianggap paling berhak menghakimi status kegilaan seseorang.
Pertama, dokter atau ahli medis;
kedua, disiplin ilmu psikiatri; dan ketiga, sebuah struktur aneh yang disebut
rumah sakit jiwa. Foucault menyebut fenomena ini sebagai pendewaan atas
tokoh medis dalam struktur penanganan kegilaan.
Tiga institusi inilah yang akhirnya memberikan label baru terhadap orang-orang
gila ini sebagai orang yang berpenyakit jiwa.
Kesimpulan: Sensitifitas terhadap kuasa/pengetahuan
Dalam terang hasil penelitian Michel Foucault mengenai sejarah kegilaan di atas,
sekarang kita bisa pahami bagaimana sebuah kegilaan telah dikonsepsikan dan
ditangani secara berbeda-beda dalam setiap periode sejarah tertentu. Ada
pergeseran-pergeseran tentang makna kegilaan berikut posisi orang-orang gila
dalam masyarakat. Di situ pula ditunjukkan kekuasaan macam apa yang
mengklaim punya hak menentukan kategori-kategori kegilaan dan cara
penanganannya.
Dalam kapal-kapal kegilaan abad renaisans, misalnya, orang-orang gila adalah
mereka kaum bijak yang bebas menyampaikan khotbah-khotbah satiris dan kritis
terhadap kekuasaan. Dalam Hospital Generale orang-orang gila didefinisikan
dan dikendalikan oleh kuasa obligasi etis negara. Sedangkan dalam rumah sakit
jiwa mereka diawasi, dikontrol dan dikendalikan para tokoh medis dan ilmu
psikiatrinya.
Kini disiplin psikiatri sangat sentral dalam penanganan masalah kelainan mental
atau kegilaan ini. Dengan mudahnya kegilaan dipersepsi sebagai penyakit yang
mesti disembuhkan secara medis. Lihatlah misalnya laporan Scientific American
1999. Dengan mengutip hasil penelitian W.W. Eaton, laporan ini menyatakan
bahwa pada tahun 1985 terdapat sekitar 1 % penduduk dunia yang berumur
antara 15 hingga 30 tahun mengidap penyakit Schizoperenia. Angka tersebut
akan terus membesar karena hingga kini belum ditemukan metoda
penyembuhan dan obat penyembuh yang manjur dan meyakinkan. Lalu laporan
itupun mengajukan tiga pendekatan untuk mengenali gejala penyakit jiwa ini.
Yaitu pendekatan genetika, pendekatan kejiwaan, dan pendekatan anatomis
keorganan otak. Pendekatan genetika, katanya, cenderung mengkaitkan
penderita penyakit Schizoprenia berdasarkan garis keturunan dengan genetika
generasi sebelumnya seperti ayah-bunda, kakek-nenek dan seterusnya,
mengenai kemungkinan mengidap penyakit yang sama. Adapun pendekatan
kejiwaan menyimpulkan bahwa penyebab penyakit schizoprenia berasal dari
ketidakberesan mental (mental disorder).
Masalah kejiwaan ini (pathophysiology) berkaitan timbal balik dengan kerja
fungsional otak melalui jaringan sistem persyarafan. Dan pada akhir laporan
tersebut dinyatakan bahwa uji coba perawatan medis terhadap gejala-gejala
kejiwaan tersebut (penyakit-penyakit itu, kata mereka) terkadang menimbulkan
dampak yang mengerikan, terutama bagi penderita yang berusia produktif,
karena dapat menimbulkan kekurangan pathognomonic yang berpengaruh pada
tingkat kesuburan penderita.
Oleh karena itu, diharapkan pengobatan alternatif dapat berperan
Dari laporan tersebut setidaknya secara implisit menunjukkan bahwa
penanganan medis terhadap gejala kegilaan atau sakit mental tidaklah berhasil.
Bisa jadi (atau malahan mungkin bisa dipastikan), ketidakberhasilan ini akibat
salah diagnosa terhadap gejala kegilaan. Ia dianggap sebuah penyakit. Padahal
bisa jadi gejala-gejala yang ahli medis anggap sebagai sakit jiwa, kelainan
mental, atau kegilaan tersebut adalah produk atau pengaruh dari sistem sosial
kita yang sebenarnya fasis dan tidak memberi ruang sejengkalpun pada manusia
untuk membangun proyek imajinasinya. Bisa jadi mereka adalah jiwa-jiwa yang
kosong yang meratap dan mengalami histeria ketakutan oleh situasi masyarakat
dan sistem sosial kita yang telah sakit parah. Sayangnya orang-orang yang
mengaku sehat (padahal sebenarnya sakit ini) malahan menghakimi mereka
sebagai penderita penyakit jiwa.
Sejarah kegilaan dan bagaimana ia ditangani secara berbeda-beda di atas
memberi pelajaran mengenai kejatuhan kita dalam berbagai asumsi naif.
Asumsi-asumsi yang berakibat fatal bagi kehidupan manusia. Karenanya, kita
seyogyanya perlu curiga terhadap asumsi-asumsi itu dan kekuasaan (kuasa
pengetahuan, kuasa institusi, kuasa otoritas tertentu) di baliknya. Ini artinya, kita
dituntut memiliki sensitifitas dan kepekaan dalam melihat kenyataan: apakah
suatu konsep atau sistem pengetahuan tertentu lebih humanis dan
emansipatoris atau, sebaliknya, justeru melakukan dehumanisasi?
Jelasnya, kita patut mempertanyakan jangan-jangan persepsi dan cara kita
memperlakukan orang gila, tidak waras, gangguan mental, dan sebagainya
selama ini adalah konstruksi belaka dari sebuah “rezim kebenaran” yang
diciptakan oleh para ahli medis dan disiplin ilmu psikiatri yang sekarang ini giat
diintrodusir melalui sekolah-sekolah dan perguruan tinggi kita. Jika benar
demikian, maka tibalah kita pada kesimpulan hipotetis, bahwa pengetahuan dan
tindakan kita sepenuhnya dikendalikan rezim kekuasaan/pengetahuan yang fasis
dan yang tak henti-hentinya mencengkeram kehidupan kita.
Diposkan oleh Serpihan Jiwa di 21.56 0 komentar
Studi Kasus
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, maka semakin tinggi
tingkat persaingan hidup, ditandai dengan banyaknya pengangguran, tersisihnya kaum
yang lemah secara ekonomi dan pendidikan, penggusuran, krisis ekonomi serta masalah
penyimpangan sosial lainnya. Hal ini berdampak pada peningkatan angka penderita
gangguan jiwa. Selama ratusan tahun sejarah bangsa Indonesia bergulir, mulai zaman
kolonial Hindia Belanda yang menerapkan Custodial Care sampai zaman reformasi. Hal
ini memberikan dampak pada perjalanan keperawatan jiwa di Indonesia. Dalam
memasuki abad 20 ini, pandangan dunia dan Indonesia terhadap keperawatan jiwa sudah
berubah. Pada saat ini telah dikembangkan konsep Publich Health, Envolving Process
Specialization, dan Deinstitusionalisasi.
Pertanyaan Diskusi
1. Jumlah penduduk Indonesia 120 juta jiwa, 2% nya diprediksikan mengalami gangguan
jiwa berat, bila 50% nya harus di rawat, berapa tempat tidur yang dibutuhkan?
2. Jelaskan tindakan yang dilakukan pada klien gangguan jiwa pada zaman dulu bila klien
tersebut dianggap membahayakan atau tidak membahayakan?
3. Dimana rumah sakit jiwa pertama yang dibangun pada zaman kolonial, dan apa latar
belakangnya?
4. Pemerintah Hindia Belanda mengenal 4 macam perawatan klien psikiatrik, jelaskan
jenis-jenisnya, tempat mana yang dikepalai seorang perawat?
5. Mengapa Custodial Care yang dahulu dianut sekarang ditinggalkan?
6. Bagaimana perkembangan usaha kesehatan jiwa antara tahun 1947 – 1975 di
Indonesia?
7. Apa perbedaan pandangan dan perlakuan dunia terhadap klien gangguan jiwa pada
awal sejarah, abad pertengahan, dan abad 20?
8. Apa pengaruh perubahan pelayanan public health service terhadap keperawatan jiwa?
9. Mengapa daat ini keperawatan jiwa lebih berfokus pada preventif dibanding kuratif?
10. Apa yang dimaksud deinstitusionalisasi dan spesialisasi dalam keperawatan jiwa
masa kini?
Sumber: Studi Kasus dari Bagian Keperawatan Jiwa FIK UNPAD
http://serpihan-jiwa.blogspot.com/
You might also like
- Abs TrakDocument2 pagesAbs TraknezapurnamasariNo ratings yet
- Lokakarya MiniDocument29 pagesLokakarya MininezapurnamasariNo ratings yet
- ISPADocument16 pagesISPAHart Dwi AsmanaNo ratings yet
- Reflik Susi Bin SomadDocument2 pagesReflik Susi Bin SomadnezapurnamasariNo ratings yet
- CoverDocument9 pagesCovernezapurnamasariNo ratings yet
- Kaki Pecah2Document1 pageKaki Pecah2nezapurnamasariNo ratings yet
- 4 AbstrakDocument2 pages4 AbstraknezapurnamasariNo ratings yet
- Jurnal Breast CancerDocument11 pagesJurnal Breast Cancerolien_42No ratings yet
- Gangguan Jiwa Mengancam BangsaDocument7 pagesGangguan Jiwa Mengancam BangsanezapurnamasariNo ratings yet
- Epitop BiomedDocument8 pagesEpitop BiomednezapurnamasariNo ratings yet
- Uud JiwaDocument5 pagesUud JiwanezapurnamasariNo ratings yet
- Bentuk Muka BumiDocument39 pagesBentuk Muka BumiNiko Anugerah Putra60% (5)