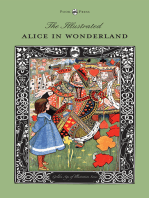Professional Documents
Culture Documents
Sisa2 Benturan Peradaban
Uploaded by
Ade Maman AlamgirOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Sisa2 Benturan Peradaban
Uploaded by
Ade Maman AlamgirCopyright:
Available Formats
Sisa-sisa Benturan Perabadan di
Indonesia (Phänomenologie des Geistes)
“Sejarah bukan hanya masa lampau,
namun juga menjadi unsur perubahan dari masa ke masa.”
-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-
Hegel menyatakan bahwa sejarah merupakan konsepsi sederhana
Rasio. Rasio sendiri merupakan penguasa dunia, sehingga sejarah dunia
memberikan suatu proses rasional kepada kita. Yang mana sejarah asli
memiliki warna yang khas,yang perajalanannya berkisar pada perbuatan,
peristiwa, dan keadaan. Dan setiap perjalanan sejarah tersebut melahirkan
pemikiran-pemikiran manusia yang pada akhirnya dijadikan sebagai sistem-
sistem budaya, nilai-nilai sosial, adat-istiadat, dan politik.
Fenomenologi mengenai keberadaan etnis tionghoa di Indonesia-pun
tak lepas dari sudut pandang sejarah. Perjalanan etnis tionghoa di Indonesia
dari masa ke masa menjadi suatu kajian menarik dalam menciptakan
semangat nasionalisme serta pembangunan demokaratisasi bangsa
Indonesia yang berasaskan pada paham – paham pluralisme dan
multikulturalisme.
Sebagai warga negara “pendatang,” warga tionghoa seringkali
mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat maupun pemerintah,
bahkan berbagai tindakan kekerasan kepada warga tionghoa tercatat
beberapa kali terjadi di Indonesia. Sejarah politik diskriminatif terhadap etnis
Tionghoa terus berlangsung sejak zaman kolonial, era Orde Lama dan Orde
Baru. Kerusuhan-kerusuhan yang menimpa etnis Tionghoa antara lain
pembunuhan massal di Jawa 1946-1948, peristiwa rasialis 10 Mei 1963 di
Bandung, 5 Agustus 1973 di Jakarta, Malari 1974 di Jakarta dan Kerusuhan
Mei 1998 di beberapa kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Solo.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia).
Pasca reformasi, dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai
presiden ke 4 RI, telah membawa angin segar bagi pluralisme di Indonesia
sekaligus tonggak awal perubahan nasib bagi warga tionghoa di Indonesia.
Walaupun pada awalnya dimulai dengan keputusan B.J. Habibi, melalui
Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan
Istilah Pribumi dan Non-Pribumi. Namun, berkat jasa Gus Dur lah, akhirnya
warga tionghoa mendapatkan pengakuan politis sebagai warga negara
Indonesia, dan berhak memeluk agamanya (Kong Hu Cu) serta merayakan
hari raya Imlek. Sesuai Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, orang Tionghoa yang
berkewarganegaraan Indonesia digolongkan sebagai salah satu suku dalam
lingkup nasional Indonesia. (Trisnanto, AM Adhy (Minggu, 18 Februari 2007),
"Etnis Tionghoa Juga Bangsa Indonesia", Suara Merdeka)
Akan tetapi, hingga saat ini sterotip-sterotip masyarakat kepada warga
tionghoa masih terus hidup di akar rumput masyarakat Indonesia. Bahkan
berbagai pandangan mengenai perbedaan dan isu-isu yang bermuatan rasial
terus tumbuh dibawah permukaan. Banyak tuduhan miring dialamatkan
kepada golongan minoritas, keturunan Cina, seolah-olah mereka adalah
sekelompok masyarakat yang hanya peduli terhadap komunitasnya semata,
mendekati kekuasaan demi menumpuk kekayaan materi untuk diri sendiri
dan kelompoknya. Bahkan ada pendapat yang lebih ekstrem menyatakan
bahwa golongan Cina adalah kelompok yang membuat kemiskinan bagi
masyarakat pribumi. Singkatnya, kalangan keturunan Cina enggan
berpartisipasi, sebagian besar bersikap apatis.
Samuel P. Huntington dalam bukunya class of civilaztion (1989),
menyebutkan bahwa tantangan kehidupan masyarakat dunia setelah perang
dingin berakhir bukan lagi pada sebuah ideology negara, akan tetapi
benturan-benturan peradaban dan agama dalam arus globalisasi.
Permasalahan benturan kebudayaan inilah yang dikhawtirkan akan sangat
kental oleh nuansa konflik horizontal di masyarakat, namun disatu sisi
benturan budaya-budaya di masyarakat ini juga dapat melahirkan sistem
multikultaralisme dan landasan sosial yang kokoh di masyarakat. Oleh
karena itulah integrasi masyarakat tionghoa di Indonesia harus dikaji secara
empirik dan komprehensif melalui telaah budaya dan sejarah perjalanan
masyarakat tionghoa di Indonesia.
Dalam tulisan ini, penulis sama sekali tidak ada maksud untuk
memperlihatkan mengenai baik atau buruknya budaya suatu etnis. Karena
hal-hal yang ingin penulis ketahui adalah sebagai berikut; apakah
kebanyakan Masyarakat Tionghoa sudah merasa seperti satu bangsa dengan
masyarakat Pribumi, dan apakah mereka masih memiliki hubungan yang
kuat dengan kebudayaan Tionghoa, dan yang terakhir apakah ada hasil dari
dibuatnya kebijakan dan undang undang tersebut di atas.
Sejarah Masuknya Warga Tionghoa di Indonesia
Tionghoa atau tionghwa, adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang
keturunan Cina di Indonesia, yang berasal dari kata zhonghua dalam bahasa
mandarin. Zhonghua dalam dialek Hokkian dilafalkan sebagai Tionghoa.
Wacana Cung Hwa setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1880, yaitu adanya
keinginan dari orang-orang di Cina untuk terbebas dari kekuasaan dinasti
kerajaan dan membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat.
Wacana ini sampai terdengar oleh orang asal Cina yang bermukim di Hindia
Belanda yang ketika itu dinamakan Orang Cina. (Vlekke, Nusantara, 2006)
Ramainya interaksi perdagangan di daerah pesisir tenggara Cina,
menyebabkan banyak sekali orang-orang yang juga merasa perlu keluar
berlayar untuk berdagang. Tujuan utama saat itu adalah Asia Tenggara.
Karena pelayaran sangat tergantung pada angin musim, maka setiap
tahunnya para pedagang akan bermukim di wilayah-wilayah Asia Tenggara
yang disinggahi mereka. Demikian seterusnya ada pedagang yang
memutuskan untuk menetap dan menikahi wanita setempat, ada pula
pedagang yang pulang ke Cina untuk terus berdagang.
Orang-orang Tionghoa di Indonesia, umumnya berasal dari tenggara
Cina. Mereka termasuk suku-suku: Hakka, Hainan, Hokkien, Kantonis,
Hokchia, dan Tiochiu. Beberapa etnis tersebut sebagaiamana dikutip dari
website www.wikipedia.com adalah sebagai berikut:
Suku Hakka (Kèjiā 客家; khek) yang berada di Asia Tenggara, termasuk
Indonesia, merupakan salah satu cabang suku Han yang memiliki ciri khas
dan penyebaran serta pengaruh paling luas di seluruh dunia. Di Cina sendiri,
orang Hakka menyebar sampai ke provinsi-provinsi lebih jauh seperti
Provinsi Sichuan, Chongqing dan Guangxi. Sedangkan diseluruh dunia, boleh
dikatakan hampir dimerata tempat dapat ditemukan jejak orang Hakka.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Hakka)
Orang Hokkian merupakan mayoritas perantau di Indonesia. Di zaman
kolonial Belanda, pemerintah Batavia menetapkan kuota perantau yang
diperbolehkan merantau ke Indonesia. Pemerintah Batavia juga mendata
jumlah pendatang menurut daerah asal, yang pada zaman tersebut
dikelompokkan menjadi empat kelompok besar; Hokkian, Tiochiu, Konghu
dan Hakka. Daerah asal pendatang dari Hokkian pada dasarnya hampir
meliputi seluruh wilayah provinsi Fujian, namun mayoritas berasal dari
daerah pesisir seperti Zhangzhou, Quanzhou, Fuzhou dan Amoy. Zhangzhou
dan Quanzhou menjadi daerah asal utama dikarenakan kedua tempat ini
telah lama menjadi pelabuhan utama yang melayani perdagangan lewat
laut. (http://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Hokkian)
Orang-orang Tiochiu di Indonesia berasal dari berbagai kota di Provinsi
Guangdong, Republik Rakyat Cina, antara lain: Jieyang (ejaan Tiochiu: Kek-
nyo), Chaozhou (ejaan Tiochiu: Tio-chiu) dan Shantou (ejaan Tiochiu: Sua-
thau). Daerah asal orang Tiochiu biasa disebut sebagai Chaoshan, gabungan
dari kata Chaozhou dan Shantou. Di Indonesia, terdapat banyak penutur
Tiochiu di Pontianak dan Ketapang, Kalimantan Barat; Jambi, Riau, Kepri dan
Sumatera Utara serta Selatan.
Mulai pada masa pemerintahan Dinasti Song, penduduk di pusat Cina
(utara) mulai melakukan transmigrasi secara besar-besaran ke daerah
selatan. Mulai dari daerah Gàn Selatan, Mǐn Barat sampai Méizhōu, akhirnya
membentuk suatu kelompok suku tersendiri, suku Kèjiā (secara harafiah
berarti keluarga tamu). Kemudian orang Kèjiā (Hakka) memakai Méizhōu
sebagai pusat, mulai menyebar lagi keseluruh wilayah Cina lainnya.
Masa-masa awal
Beberapa catatan tertua ditulis oleh para agamawan, seperti Fa Hien
pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7. Fa Hien melaporkan suatu
kerajaan di Jawa ("To lo mo") dan I Ching ingin datang ke India untuk
mempelajari agama Buddha dan singgah dulu di Nusantara untuk belajar
bahasa Sansekerta dahulu. Di Jawa ia berguru pada seseorang bernama
Jñânabhadra. (www.wikipedia.com)
Dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, para imigran
Tiongkok pun mulai berdatangan, terutama untuk kepentingan perdagangan.
Pada prasasti-prasasti dari Jawa orang Cina disebut-sebut sebagai warga
asing yang menetap di samping nama-nama sukubangsa dari Nusantara,
daratan Asia Tenggara dan anak benua India. Dalam suatu prasasti
perunggu bertahun 860 dari Jawa Timur disebut suatu istilah, Juru Cina, yang
berkait dengan jabatan pengurus orang-orang Tionghoa yang tinggal di sana.
Beberapa motif relief di Candi Sewu diduga juga mendapat pengaruh dari
motif-motif kain sutera Tiongkok. (Rustopo 2008. Jawa Sejati. Otobiografi Go
Tik Swan. Penerbit Ombak Yogyakarta).
Catatan Ma Huan, ketika turut serta dalam ekspedisi Cheng Ho,
menyebut secara jelas bahwa pedagang Cina muslim menghuni ibukota dan
kota-kota bandar Majapahit (abad ke-15) dan membentuk satu dari tiga
komponen penduduk kerajaan itu, (Arismunandar A 2007. Kerajaan
Majapahit abad XIV dan XV. Artikel pada laman Majapahit Kingdom).
Ekspedisi Cheng Ho juga meninggalkan jejak di Semarang, ketika orang
keduanya, Wang Jinghong, sakit dan memaksa rombongan melepas sauh di
Simongan (sekarang bagian dari Kota Semarang). Wang kemudian menetap
karena tidak mampu mengikuti ekspedisi selanjutnya. Ia dan pengikutnya
menjadi salah satu cikal-bakal warga Tionghoa Semarang. Wang
mengabadikan Cheng Ho menjadi sebuah patung (disebut "Mbah Ledakar
Juragan Dampo Awang Sam Po Kong"), serta membangun kelenteng Sam Po
Kong atau Gedung Batu. Di komplek ini Wang juga dikuburkan dan dijuluki
"Mbah Jurumudi Dampo Awang". ( Zulkifli AA. Laksamana Cheng Ho pernah
singgah di Surabaya)
Sejumlah sejarawan juga menunjukkan bahwa Raden Patah, pendiri
Kesultanan Demak, memiliki darah Tiongkok selain keturunan Majapahit.
Beberapa wali penyebar agama Islam di Jawa juga memiliki darah Tiongkok,
meskipun mereka memeluk Islam dan tidak lagi secara aktif mempraktekkan
kultur Tionghoa.
Kitab Sunda Tina Layang Parahyang menyebutkan kedatangan
rombongan Tionghoa ke muara Ci Sadane (sekarang Teluknaga) pada tahun
1407, di masa daerah itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda
(Pajajaran). Pemimpinnya adalah Halung dan mereka terdampar sebelum
mencapai tujuan di Kalapa.
Era kolonial
Di masa kolonial, Belanda pernah mengangkat beberapa pemimpin
komunitas dengan gelar Kapiten Cina, yang diwajibkan setia dan menjadi
penghubung antara pemerintah dengan komunitas Tionghoa. Beberapa
diantara mereka ternyata juga telah berjasa bagi masyarakat umum,
misalnya So Beng Kong dan Phoa Beng Gan yang membangun kanal di
Batavia. Di Yogyakarta, Kapiten Tan Djin Sing sempat menjadi Bupati
Yogyakarta. (Setiono, Benny G. "Tionghoa Dalam Pusaran Politik", hal. 167,
Transmedia)
Sebetulnya terdapat juga kelompok Tionghoa yang pernah berjuang
melawan Belanda, baik sendiri maupun bersama etnis lain. Bersama etnis
Jawa, kelompok Tionghoa berperang melawan VOC tahun 1740-1743. Di
Kalimantan Barat, komunitas Tionghoa yang tergabung dalam "Republik"
Lanfong berperang dengan pasukan Belanda pada abad XIX. (Vleke,
Nusantara; 2006)
Dalam perjalanan sejarah pra kemerdekaan, beberapa kali etnis
Tionghoa menjadi sasaran pembunuhan massal atau penjarahan, seperti
pembantaian di Batavia 1740 dan pembantaian masa perang Jawa 1825-
1830. Pembantaian di Batavia tersebut
(http://www.obor.co.id/DetailBuku.asp?Bk_ISBN=979-461-556) melahirkan
gerakan perlawanan dari etnis Tionghoa yang bergerak di beberapa kota di
Jawa Tengah yang dibantu pula oleh etnis Jawa. Pada gilirannya ini
mengakibatkan pecahnya kerajaan Mataram. Orang Tionghoa tidak lagi
diperbolehkan bermukim di sembarang tempat. Aturan Wijkenstelsel ini
menciptakan pemukiman etnis Tionghoa atau pecinan di sejumlah kota
besar di Hindia Belanda.
Target pemerintah kolonial untuk mencegah interaksi pribumi dengan
etnis Tionghoa melalui aturan passenstelsel dan Wijkenstelsel itu ternyata
menciptakan konsentrasi kegiatan ekonomi orang Tionghoa di perkotaan.
Ketika perekonomian dunia beralih ke sektor industri, orang-orang Tionghoa
paling siap berusaha dengan spesialisasi usaha makanan-minuman, jamu,
peralatan rumah tangga, bahan bangunan, pemintalan, batik, kretek dan
transportasi. Tahun 1909 di Buitenzorg (Bogor) Sarekat Dagang Islamiyah
didirikan oleh RA Tirtoadisuryo mengikuti model Siang Hwee (kamar dagang
orang Tionghoa) yang dibentuk tahun 1906 di Batavia. Bahkan pembentukan
Sarekat Islam (SI) di Surakarta tidak terlepas dari pengaruh asosiasi yang
lebih dulu dibuat oleh warga Tionghoa. Pendiri SI, Haji Samanhudi, pada
mulanya adalah anggota Kong Sing, organisasi paguyuban tolong-menolong
orang Tionghoa di Surakarta. Samanhudi juga kemudian membentuk Rekso
Rumekso yaitu Kong Sing-nya orang Jawa. (Soe Hok Gie, Dibawah Lentera
Merah).
Pemerintah kolonial Belanda makin kuatir karena Sun Yat Sen
memproklamasikan Republik Cina, Januari 1912. Organisasi Tionghoa yang
pada mulanya berkecimpung dalam bidang sosial-budaya mulai mengarah
kepada politik. Tujuannya menghapuskan perlakukan diskriminatif terhadap
orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam bidang pendidikan,
hukum/peradilan, status sipil, beban pajak, hambatan bergerak dan
bertempat tinggal.
Dalam rangka pelaksanaan Politik Etis, pemerintah kolonial berusaha
memajukan pendidikan, namun warga Tionghoa tidak diikutkan dalam
program tersebut. Padahal orang Tionghoa membayar pajak ganda (pajak
penghasilan dan pajak kekayaan). Pajak penghasilan diwajibkan kepada
warga pribumi yang bukan petani. Pajak kekayaan (rumah, kuda, kereta,
kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga) dikenakan hanya bagi
Orang Eropa dan Timur Asing (termasuk orang etnis Tionghoa). Hambatan
untuk bergerak dikenakan bagi warga Tionghoa dengan adanya
passenstelsel.
Pada waktu terjadinya Sumpah Pemuda, ada beberapa nama dari
kelompok Tionghoa sempat hadir, antara lain Kwee Tiam Hong dan tiga
pemuda Tionghoa lainnya. Sin Po sebagai koran Melayu Tionghoa juga
sangat banyak memberikan sumbangan dalam menyebarkan informasi yang
bersifat nasionalis. Pada 1920-an itu, harian Sin Po memelopori penggunaan
kata Indonesia bumiputera sebagai pengganti kata Belanda inlander di
semua penerbitannya. Langkah ini kemudian diikuti oleh banyak harian lain.
Sebagai balas budi, semua pers lokal kemudian mengganti kata "Tjina"
dengan kata Tionghoa. Pada 1931 Liem Koen Hian mendirikan PTI, Partai
Tionghoa Indonesia (dan bukan Partai Tjina Indonesia).
Masa revolusi
Pada masa revolusi tahun 1945-an, Mayor John Lie yang
menyelundupkan barang-barang ke Singapura untuk kepentingan
pembiayaan Republik. Rumah Djiaw Kie Siong di Rengasdengklok, dekat
Karawang, diambil-alih oleh Tentara Pembela Tanah Air (PETA), kemudian
penghuninya dipindahkan agar Bung Karno dan Bung Hatta dapat
beristirahat setelah "disingkirkan" dari Jakarta pada tanggal 16 Agustus
1945. Di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
yang merumuskan UUD'45 terdapat 4 orang Tionghoa yaitu; Liem Koen Hian,
Tan Eng Hoa, Oey Tiang Tjoe, Oey Tjong Hauw, dan di Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdapat 1 orang Tionghoa yaitu Drs.Yap
Tjwan Bing. Liem Koen Hian yang meninggal dalam status sebagai
warganegara asing, sesungguhnya ikut merancang UUD 1945. Lagu
Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, pun pertama kali
dipublikasikan oleh Koran Sin Po.
Dalam perjuangan fisik ada beberapa pejuang dari kalangan Tionghoa,
namun nama mereka tidak banyak dicatat dan diberitakan. Salah seorang
yang dikenali ialah Tony Wen, yaitu orang yang terlibat dalam penurunan
bendera Belanda di Hotel Oranye Surabaya, (www.wikipedia.com).
Pasca Kemerdekaan
Sejarah politik diskriminatif terhadap etnis Tionghoa terus berlangsung
pada era Orde Lama dan Orde Baru. Kerusuhan-kerusuhan yang menimpa
etnis Tionghoa antara lain pembunuhan massal di Jawa 1946-1948, peristiwa
rasialis 10 Mei 1963 di Bandung, 5 Agustus 1973 di Jakarta, Malari 1974 di
Jakarta dan Kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota besar seperti Jakarta,
Medan, Bandung, Solo, (www.wikipedia.com). Pada Orde Lama keluar
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang melarang WNA Tionghoa
untuk berdagang eceran di daerah di luar ibukota provinsi dan kabupaten.
Hal ini menimbulkan dampak yang luas terhadap distribusi barang dan pada
akhirnya menjadi salah satu sebab keterpurukan ekonomi menjelang tahun
1965.
Selama Orde Baru juga terdapat penerapan ketentuan tentang Surat
Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atau yang lebih populer disebut
SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia (WNI) etnis
Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat
administratif, secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya
yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang
"masih dipertanyakan".
Reformasi yang digulirkan pada 1998 telah banyak menyebabkan
perubahan bagi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia. Walau belum 100%
perubahan tersebut terjadi, namun hal ini sudah menunjukkan adanya tren
perubahan pandangan pemerintah dan warga pribumi terhadap masyarakat
Tionghoa. Bila pada masa Orde Baru aksara, budaya, ataupun atraksi
Tionghoa dilarang dipertontonkan di depan publik, saat ini telah menjadi
pemandangan umum hal tersebut dilakukan. Di Medan, Sumatera Utara,
misalnya, adalah hal yang biasa ketika warga Tionghoa menggunakan
bahasa Hokkien ataupun memajang aksara Tionghoa di toko atau rumahnya.
Selain itu, pada Pemilu 2004 lalu, kandidat presiden dan wakil presiden
Megawati-Wahid Hasyim menggunakan aksara Tionghoa dalam selebaran
kampanyenya untuk menarik minat warga Tionghoa.
Sejarah Kebijakan Pemerintahan Terhadap Masyarakat Tionghoa Di
Indonesia
Banyak dari kebijakan dan undang-undang yang mengenai keturunan
Tionghoa menyebabkan timbulnya batasan-batasan yang menahan
perkembangan identitas kebudayaan Tionghoa. Pada bagian ini saya akan
membahas mengenai alasan-alasan diterapkannya kebijakan dan undang-
undang tersebut, sebelum mendiskusikan berhasil mencapai tujuannya.
Untuk mengetahui alasan-alasan tersebut, menurut penulis, sangat penting
untuk mempelajari sejarah dan kebiasaan masyarakat yang mendasari
dibuatnya undang-undang tersebut.
Bahkan sebelum penjajah Belanda menciptakan tiga kelompok etnik
sosial yang memiliki peraturan peraturan yang berbeda sama satu lainnya,
imigran Tionghoa yang sudah tiba di Indonesia dan memiliki derajat yang
berbeda-beda, masih mencoba mempertahankan identitas etnis aslinya.
Beberapa dari keturunan Tionghoa ini memutuskan untuk menikah dan
membangun keluarga dengan warga pribumi. Hal ini disebabkan karena di
masa dinasti Ming (Qing) di Tiongkok, keturunan Tionghoa yang
meninggalkan tanah airnya akan dilarang untuk kembali lagi ke daratan
Tiongkok (Suryadinata; 2002; hal 70). Oleh karena itu mereka berusaha
untuk menciptakan dan membangun keluarga baru di Indonesia. Kelompok
tersebut menggunakan bahasa daerah di tempat tinggalnya sebagai bahasa
sehari-hari, di lain pihak mereka masih menganut adat istiadat Tionghoa
seperti berdoa menurut kepercayaan Tionghoa tradisional (Greif; 1991; hal
1-3) atau memperingati tahun Tionghoa baru (Imlek). Kelompok ini disebut
‘Peranakan’ Tionghoa.
Selanjutnya, pada saat pengusaha-pengusaha Belanda membutuhkan
pekerja-pekerja kasar atau ‘kuli’ untuk bekerja di perkebunan dan
pertambangan, akan didatangkan orang orang keturunan Tionghoa yang
berasal dari kelompok yang berbeda. Kelompok ini berbeda dari kelompok
Peranakan Tionghoa karena kelompok ini akan diantarkan keluarganya ke
Indonesia dan mereka akan mempertahankan ‘kemurnian’ keturunannya
(Greif; 1991; hal 3). Kelompok ini disebut ‘Totok’ Tionghoa. Dan kelompok ini
tidak memiliki kesetiaan terhadap penjajah Belanda atau penduduk
setempat, karena menurut mereka Indonesia hanya tempat sementara
(Greif; 1991; hal 3) di mana mereka bisa mendapatkan dan mengirim cukup
dana ke tanah airnya Tiongkok. Mereka merasa akan lebih baik jika mereka
dapat kembali ke Tiongkok setelah mereka berhasil memperoleh apa yang
mereka inginkan. Dapat diketahui bahwa Peranakan dan Totok masih ingin
memelihara identitas Tionghoanya, yang terpisah dari orang Pribumi.
Keputusan ini membuat mereka menjadi sumber kecurigaan bagi
masyarakat Pribumi, selama dan sesudah perjuangan Kemerdekaan
Indonesia dan periode periode selanjutnya.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada tahun 1907,
pemerintah Belanda membagi kependudukan di Indonesia dalam tiga
kelompok. Peranakan dan Totok Tionghoa berada pada kelompok yang
dinamakan ‘Timur Asing’ atau ‘Eastern Orientals’ (Greif; 1991; hal xi).
Kedudukan kelompok ini berada di antara kelompok orang-orang Pribumi
dan kelompok warga negara Belanda, yang tentu saja menduduki posisi
paling utama. Ini adalah usaha yang sengaja dilakukan oleh penjajah
Belanda untuk mempertahankan keterpisahan masyarakat Tionghoa dan
penduduk Pribumi yang disebut ‘Divide and Rule’. Hal ini disebabkan oleh
adanya kekhawatiran jikalau masyarakat Tionghoa bersatu dengan orang
Pribumi, sebab jika mereka bersatu mereka akan memiliki kekuatan untuk
menentang penjajahan Belanda di Indonesia (Suryadinata; 2002; hal 8).
Usaha ini dimaksudkan penjajah Belanda untuk memperburuk pandangan
orang Pribumi terhadap keturunan Tionghoa. Salah satu contoh dari usaha
tersebut adalah hak istemiwa terhadap keturunan Tionghoa seperti
pendidikan dan kesempatan untuk menjadi warga negara Belanda, yang
dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Keuntungan yang lain
sebagai keturunan Tionghoa, khususnya kelompok Peranakan, memilih
peluang bekerja untuk pemerintahan dan pengusaha Belanda sebagai
perantara, karena sebagian dari mereka menguasai bahasa Belanda dan
bahasa setempat. Akibat dari perbedaan status ini, penduduk setempat
merasa adanya ketidakadilan yang membuat mereka iri dan marah. Jadi
tidak hanya keinginan identitas terpisah saja yang menciptakan perasaan
curiga di antara penduduk setempat, tetapi juga, proses pemisahan dan
timbulnya prasangka yang dengan sengaja diciptakan oleh penjajah
Belanda. Perasaan inilah yang terbawa hingga saat ini.
Kelompok Peranakan terbagi menjadi dua kelompok politik, kelompok
pertama adalah Chung Hwa Hui (CHH) ini, mereka mendukung penjajah
Belanda (Suryadinata; 1978; hal 54). Kelompok kedua adalah Partai
Tionghoa Indonesia (PTI) yang mendukung Gerakan Kemerdekaan Indonesia
(Suryadinata; 1978; hal 56). Beberapa tokoh dari partai ini berjuang bersama
dengan tokoh tokoh lain bukan keturunan Tionghoa untuk kemerdekaan
Indonesia. Namun Kenyataan ini sering dilupakan oleh masyarakat Indonesia
dan Penulis sejarah (Suryadinata; 2002; hal 21-23). Pada sisi lain sebagian
besar masyarakat Totok merasa hanya daratan Tiongkok yang bisa mewakili
dan melindungi kepentingan merkeka, sehingga mereka tidak memiliki
kesetiaan politik terhadap penjajah Belanda atau kependudukan setempat
(Suryadinata; 1978; hal 53). Oleh karena itu keturunan Tionghoa dianggap
tidak memiliki ketentuan politik, yang pada akhirnya menimbulkan kesan
bahwa kesetiaan dan kesungguhan hati mereka terhadap Indonesia tidak
bisa diandalkan (Suryadinata; 1978; hal 21-22). Terlebih lagi dengan adanya
Gerakan Nasionalis Cina yang mempengaruhi kelompk Totok untuk lebih
men-cina-kan diri lagi dari warga Pribumi pada masa sebelum penjajahan
Jepang (Greif; 1991; hal 6), yang memberi kesan kesetiaan masyarakat
Tionghoa lebih besar terhadap Tiongkok daripada Indonesia.
Metode ‘Divide and Rule’ terhadap keturunan Tionghoa terbawa terus
sampai masa penjajahan Jepang pada periode Perang Dunia Kedua (PDII).
Penjajah Jepang dengan sengaja memisahkan dan memaksa orang-orang
keturunan Tionghoa untuk belajar di sekolah yang dibuat khusus untuk
mereka, dan mereka diharuskan untuk menggunakan bahasa Mandarin
dalam proses belajar mengajar (Suryadinata; 1978; hal 147). Lebih dari itu
mereka juga diharapkan untuk berbahasa Mandarin di luar jam sekolah.
Beberapa orang keturunan Tionghoa juga diperkerjakan oleh tentara Jepang
sebagai seorang mata mata. Hal ini menyebabkan bertambahnya pandangan
buruk terhadap Keturunan Tionghoa. Karena mereka dianggap membantu
penjajah Jepang, yang tentu saja sangat dibenci karena perlakuan mereka
yang sangat kejam terhadap masyarakat pribumi. Selain itu penduduk
keturunan Tionghoa merasa bimbang dan mengalami kesulitan dalam
menentukan masa depan mereka. Beberapa dari mereka masih merasa
seperti penduduk asing di Indonesia, walaupun mereka memiliki kehidupan
di Indonesia. Dengan adanya penjajahan oleh Belanda dan Jepang, serta
hubungan batin yang masih ada dengan Tiongkok, tetapi Indonesia juga,
mereka tidak memiliki kepastian harus mendukung pihak yang mana.
Seperti yang diucapkan Liem Koen Hian, pendiri PTI (Partai Tionghoa
Indonesia), walaupun Peranakan Tionghoa memiliki kebudayaan yang
cenderung lebih mencerminkan Indonesia, kedudukan keturunan Tionghoa
akan terombang ambing selama situasi Indonesia dan luar negeri yang
berubah ubah (Suryadinata; 1978; hal 59). Dan seperti yang telah dibahas
sebelumnya, faktor-faktor di ataslah yang menyebabkan timbulnya
ketidaktentuan pilihan masyarakat Tionghoa di bidang politik.
Mengingat adanya kejadian-kejadian tersebut, tidaklah mengherankan
apabila pada periode saat ‘Dutch East Indies’ menjadi Republik Indonesia,
Presiden dan wakilnya, Soekarno dan Hatta, tidak percayai bahwa
masyarakat Tionghoa memiliki kesetiaan terhadap Republik Indonesia
(Suryadinata; 1978; hal 25-33). Prasangka yang diakibatkan oleh kejadian
bersejarah yang tersebut di atas juga dipengaruhi oleh undang-undang yang
dibuat oleh penjajah Belanda dan Jepang telah menyebabkan timbulnya
perasaan tidak percaya terhadap keturunan Tionghoa selama Zaman ini.
Pada tanggal 30 September 1965 (dikenal G30S/PKI) terjadi sebuah
kudeta yang menimpa Indonesia, dan Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI) dan pemerintahan Soekarno mencurigai PKI (Partai Komunis
Indonesia) berusaha mengambil alih kekuasaan dan kepemimpinan
Indonesia. Kejadian ini menyebabkan meninggal dunia wafatnya beberapa
tokoh-tokoh utama ABRI. Sebagai negara Komunis terbesar, Tiongkok yang
juga merupakan salah satu tetangga Indonesia, diduga terlibat dalam
G30S/PKI dan keberadaan serta pendukungnya menjadi ancaman terhadap
keamanan nasional Indonesia. Keturunan Tionhghoa masih ingin
mempertahankan status kebudayaan mereka walaupun pada periode-
periode sebelumnya mereka masih memiliki ketidakpastian dalam hal politik.
Akibatnya, pemerintah merasa terancam oleh keadaan tersebut di atas
karena mereka mengira bahwa keturunan Tionghoa masih bagian dari Cina
Komunis (Suryadinata; 1978; hal 45-47). Oleh karena itu pemerintahan
Republik Indonesia harus mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat
Tionghoa untuk menjamin keselamatan Indonesia. Sebab kebanyakan
pemimpin termasuk Soekarno dan Hatta, beranggapan bahwa Indonesia
dapat kembali aman apabila seluruh rakyatnya bersatu (Suryadinata; 1978;
hal 47). Dan untuk itu, diharapkan tidak adanya perbedaan suku, status, dan
kebudayaan. Akibatnya pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan Asimilasi
atau Pembauran lengkap terhadap keturunan Tionghoa (Greif; 1991; hal xii-
xiii) dan memutuskan untuk mengeluarkan undang-undang guna mencapai
tujuan mereka. Berapa undang-undang diciptakan untuk mendukung
keputusan mereka adalah:
Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966. Undang
undang ini mengenai penggantian nama untuk Warga Negara Indonesia
yang memakai nama Tionghoa. Penggantian nama ini tidaklah wajib untuk
keturunan Tionghoa, akan tetapi, pemerintah Orde Baru berpendapat bahwa
usaha ini akan membantu pembauran menjadi lebih cepat. Kebanyakan
anggota masyarakat Tionghoa menentukan untuk mengganti namanya,
tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka memakai nama Tionghoanya
(Greif; 1991; hal xvii).
Instruksi Presiden No.14 1967 tentang Agama, Kepercayaan
dan Adat istiadat Cina. Undang-undang ini melarang mengamalkan
perayaan Hari Raya Tionghoa, penggunaan bahasa Tionghoa, dan adat
istiadat yang sama, di depan umum. Selain ini, undang ini, walaupun tidak
langsung, menolak agama Kong Hu Chu sebagai agama resmi Indonesia.
Instruksi ini dicabut oleh Keputusan Presiden tentang Pencabutan Instruksi
Presiden No.14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat
Cina (Burchell; 2004; hal 56).
Surat edaran SE.02/SE Ditjen/PPG/K/1998. Ini melarang
penerbitan dan percetakan tulisan atau iklan beraksara dan yang
menggunakan bahasa Mandarin di depan umum (Tempo; 17 August 2004;
hal 36–37). Undang ini dicabut oleh Instruksi Presiden No.4/1999 dan
memperbolehkan pelajaran dan penggunaan Bahasa Tionghoa (Tempo; 17
August 2004; hal 36-37).
Peraturan Menteri Perumahan No.455.2-360/1988. Ini melarang
penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbarui
Klenteng Tionghoa (Tempo; 17 August 2004; hal 36-37).
Keppres 240/1967 tgl. April 1967 tentang Kebijaksanaan pokok
yang menyangkut WNI Keturunan Asing (Greif; 1991; hal xx).
Akan tetapi walaupun undang-undang ini diciptakan untuk mendorong
adanya tujuan pencapaian pembauran lengkap, masih ada beberapa hukum-
hukum, khususnya di bidang perekonomian, yang menentang tujuan
tersebut (Suryadinata; 1978; hal 4). Ini adalah salah satu alasan utama yang
menjelaskan kegagalan undang-undang di atas mencapai pembauran
lengkap. Contoh yang paling jelas yang memperlihatkan fenomena ini adalah
keputusan yang diambil di Seminar Angkatan darat untuk Jenderal-jenderal
yang paling tinggi pada tahun 1966 (Suryadinata; 2002; hal 92). Keputusan
ini menyebutkan bahwa masyarakat keturunan Tionghoa seharusnya
dibatasi dalam bidang perekonimian sehingga keterlibatannya dalam bidang
yang lain, misalnya, bidang politik bisa dihindari. Jenderal-jenderal ini juga
mendorong adanya tindakan tersebut karena mereka mengetahui bahwa
masyarakat dan perusahaannya bisa membantu perekonomian Indonesia
yang pada waktu itu sangat lemah (Suryadinata; 2002; hal 92-93). Dari ini,
bisa dilihat bahwa walaupun pemerintahan Suharto menginginkan
pembauran lengkap antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat bukan
Tionghoa, mereka masih memperbolehkan aktivitas dan undang-undang
yang mendorong dan memperkuat identitas etnis Tionghoa yang terpisah.
Misalnya perbedaan perlakuan yang diterima masyarakat Tiongoa
dicerminkan dalam:
Keppres No. 14A/1980. Undang ini berarti bahwa semua lembaga
pemerintah dan kementerian harus memberikan perlakuan istemewa kepada
pengusaha pribumi. Itu juga mewajibkan bahwa di mana ada patungan
antara seorang Pribumi dan seorang bukan pribumi, pengusaha Pribumi
harus memilik 50% dari nilai perusahaan dan juga harus memegang peranan
aktif dalam menjalankan perusahaannya (Suryadinata; 2002; hal 91).
UU No 12 Tahun 2006. Undang-undang itu telah membuat terobosan
besar dengan meninggalkan peraturan-peraturan sisa peninggalan Belanda
yang diskriminatif, yang memisahkan penduduk menjadi tiga golongan yang
terpisah satu sama lain. UU No 12 Tahun 2006 tidak sekadar mengatur siapa
dan bagaimana cara menjadi warganegara dan kehilangan status
kewarganegaraan, tetapi juga mengubah konsep bangsa Indonesia asli.
Konsep bangsa Indonesia asli dijelaskan sebagai orang Indonesia yang
menjadi warganegara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Konsep itu mengubah
paradigma, status kewarganegaraan yang tadinya ditentukan atas dasar
etnis dan ras, menjadi atas dasar status juridis. Dengan demikian perbedaan
WNI Indonesia asli dan tidak asli bagi WNI peranakan Tionghoa dapat
dikatakan tidak ada lagi.
Dengan berlakunya UU No 12 Tahun 2006, peranakan Tionghoa di
Indonesia disetarakan dengan saudara-saudaranya sesama bangsa
Indonesia. Berbahagialah peranakan Tionghoa yang sekarang sudah diakui
kembali sebagai bangsa Indonesia asli, artinya diakui sebagai bangsa
Indonesia keturunan dari kakek-moyangnya atau nenek-morangnya yang
pribumi.
Dinamika Pencarian Identitas Etnis Cina Dalam Persektif Teori
Identitas Sosial
Dinamika pencarian identitas etnis Cina sebenarnya terkait perlakuan
yang diterima dari pihak penguasa. Dalam Sarwono (1999), dan Susetyo
(2002) dikemukakan bahwa pada jaman pemerintahan kolonial Belanda,
perbedaan status etnis diberlakukan dengan tegas. Orang Eropa diberi
status tertinggi dan mempunyai hak dan fasilitas terbaik. Orang Cina yang
waktu itu disebut orang Timur Asing (vreemde osterlingen) mempunyai
status di bawah orang Eropa dan golongan pribumi (inlander) diberi status
yang paling rendah (kecuali bangsawan yang diberi status seperti Eropa).
Dalam statusnya yang di tengah ini, orang Cina meningkatkan citranya
dengan melakukan mobilitas sosial, yaitu mengadopsi berbagai identitas
yang melekat pada orang Eropa ataupun Belanda. Banyak orang Cina yang
berpendidikan ala Eropa, cara mereka berpakaian juga ala Eropa, mereka
juga mengadopsi agama Kristen dan Katolik seperti orang Eropa disamping
keyakinan yang mereka bawa dari tanah leluhurnya, dan lain sebagainya.
Amat jarang orang Cina yang mengidentifikasi dengan identitas pribumi,
karena status pribumi yang lebih rendah. Interaksi dengan orang pribumi
nampaknya lebih untuk kepentingan dagang dan kepentingan lain yang bisa
menguntungkan. Dalam hal tertentu orang pribumi malah terangkat
derajatnya, misalnya ketika ada perempuan pribumi yang dinikahi orang
Cina. Dengan demikian, yang menonjol pada orang Cina di era kolonial
Belanda adalah perpaduan antara identitas Cina tradisionil dan identitas ala
Eropa.
Namun demikian situasinya nampak berbeda sama sekali ketika
memasuki era kemerdekaan. Persoalan yang mengedepan terutama adalah
tentang kepastian status kewarganegaraan. Dikemukakan oleh Coppel
(1994) orang Cina pada masa itu terjepit antara berbagai kepentingan baik
yang berskala nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia pada
waktu itu tidak bisa segera memberikan kepastian. Bahkan undang-undang
yang mengatur hal ini ditengarai akan membatasi jumlah orang Cina yang
bisa menjadi warganegara. Sementara pemerintah RRC pada waktu itu
masih memberlakukan kewarganegaraan ganda bagi orang Cina di
perantauan, yaitu disamping menjadi warganegara di negara tempat
merantau juga melekat kewarganegaraan Cina. Sebagai reaksi terhadap
keadaan tersebut maka sejumlah tokoh Cina mendirikan Baperki (Badan
Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang inti perjuangannya
ingin menempatkan etnis Cina sejajar dengan etnis/suku lain dengan konsep
integrasi. Sementara kelompok Cina yang lain menghendaki asimilasi
sebagai solusi.
Namun demikian sejak terjadinya peristiwa pemberontakan PKI 1965,
keadaannya berbalik sama sekali. Konsep integrasi secara politis telah
dikategorikan sebagai bagian dari ideologi komunis sosialis (Lan, 1998).
Dengan demikian pilihan satu satunya yang diberi ruang oleh penguasa
adalah dengan asimilasi. Sebenarnya disinilah akar permasalahannya
mengapa pencarian identitas etnis Cina menjadi sedemikian rumit.
Pasca peristiwa 1965 status etnis Cina sedang dalam kondisi terendah.
Mereka dipojokkan oleh penguasa maupun masyarakat bukan Cina. Pada
saat itu berbagai kekerasan massa anti Cina mulai marak. Mengacu pada
teori identitas sosial, maka ketika suatu kelompok citranya sedang terpuruk
selalu ada upaya untuk bereaksi terhadap keadaan ini dalam rangka meraih
kembali citra / identitas sosial yang positif. Adapun modus yang biasa terjadi
adalah dengan mobilitas sosial dan perubahan sosial.
Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang dilakukan nampaknya cukup
bervariasi tergantung dari persepsi masing-masing kelompok tentang
bagaimana harus memperbaiki citra. Salah satu reaksi yang muncul adalah
dengan eksodus ke luar negeri seperti ke Belanda, kembali ke RRC dan
sebagainya. Sementara kelompok asimilasi nampaknya mendapat angin,
salah satu tokohnya Junus Jahja mendorong orang Cina untuk memeluk
agama Islam sebagai kunci pembauran total.
Pada akhirnya kita akan menemukan identitas Cina yang Jawa, Cina
yang Batak, Cina yang Padang, Cina yang Sunda dan sebagainya. Namun
demikian ketika mereka tidak dapat menemukan hal-hal yang mendukung
perbaikan citra dirinya sebagaimana hal di atas, banyak juga yang akhirnya
pindah keluar negeri menjadi kelompok yang beridentitas kosmopolitas,
internasional, lintas etnis maupun lintas negara. Dinamika tersebut
nampaknya dapat tergambarkan dari penelitian dari Lan (1998) tentang
orientasi identifikasi diri ataupun dari Tan (1998) tentang aspirasi politik di
atas.
Selain melalui mobilitas sosial, nampaknya juga ada kecenderungan
melakukan perubahan sosial, yaitu dengan memperbaiki citra dari ke-Cina-
an. Salah satunya adalah dengan menggeser orientasi ke-Cina-an dari yang
berorientasi tradisionil menjadi ke-Cina-an yang berorientasi nasional.
Barangkali kecenderungan ini lebih banyak berkembang di kalangan
generasi yang lebih muda, dimana mereka sudah begitu menguasai lagi adat
istiadat Cina tradisionil, tidak bisa berbicara dalam bahasa mandarin,
memiliki pendidikan yang modern. Dengan demikian ke-Cina-an sekarang
tampil dalam kemasan dan citra baru yang lebih bisa diterima dan tidak lagi
berasosiasi dengan masa lalu yang traumatis.
Ke-Cinaan Vs Ke-Indonesiaan (Hipotesa Awal)
Menurut Lan (1998) pencarian jati diri orang Cina di Indonesia
dihadapkan pada beberapa pilihan – menjadi Indonesia, tetap Cina atau
mengadopsi identitas lain. Namun demikian nampaknya pilihan-pilihan tidak
selalu menempatkan orang Cina pada keadaan yang mudah. Pilihan dengan
identitas Indonesia telah difasilitasi pemerintah Orde Baru yang
memberlakukan asimilasi inkorporasi (total) bagi orang Cina untuk
menghilangkan identitas Cina-nya dan menjadi Indonesia. Namun demikian
motivasi pemberlakuan asimilasi inkorporasi nampaknya lebih bernuansa
‘hukuman’ karena sangkaan keterlibatan orang Cina dalam pemberontakan
PKI tahun 1965. Pada kenyataannya kebijakan tersebut justru memberikan
kontribusi terhadap berbagai kerawanan dan gejolak sosial yang
memprihatinkan seperti prasangka, kerusuhan-kekerasan massa dengan
sasaran etnis Cina. Kebijakan tersebut juga menyisakan trauma bagi
golongan minoritas ini , selain akibat berbagai tindakan kekerasan yang
dialaminya, juga akibat perlakuan diskriminatif yang membelenggu gerak
hidup masyarakat Cina ini (Susetyo, 1999) Asimilasi inkorporasi (total) itu
sendiri pada kenyataannya telah gagal, sebagaimana asimilasi Melting Pot
yang pernah diberlakukan di Amerika. Pada kenyataannya tidaklah mungkin
untuk meniadakan akar budaya suatu golongan masyarakat begitu saja.
Memilih mempertahankan identitas sebagai orang Cina juga bukan
persoalan yang mudah, karena ke-Cina-an lekat dengan berbagai citra yang
kurang menguntungkan di mata etnis pribumi maupun kalangan birokrasi
pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari berkembangnya stereotip,
prasangka dan diskriminasi yang semakin mempertegas citra buruk etnis
Cina di mata etnis Indonesia lainnya. Sementara di kalangan aparat,
birokrasi pemerintahan, sampai sekarang mereka nampaknya masih
menggunakan paradigma lama dengan perlakuan diskriminatif terhadap
etnis Cina misalnya dalam hal status kependudukan ataupun status
kewarganegaraan.
Di kalangan internal masyarakat Cina sendiri juga sedang terjadi
pergeseran dalam memaknai arti identitas Cina itu sendiri dalam format
yang berubah. Menurut Lan (1998) pergeseran tersebut dari ke-Cina-an yang
tradisionil dan berorientasi etnis dan negeri leluhur menjadi ke-Cina-an yang
modern dan berorientasi nasional dan lokal (dalam hal ini Indonesia).
Pergeseran ini nampaknya juga terkait dengan upaya meninggalkan trauma
masa lalu, dimana identitas Cina yang berorientasi pada budaya negeri
leluhur tidak jarang terjebak pada persoalan-persoalan yang bernuansa
politik, misalnya ketika hubungan antara Indonesia dengan RRC memburuk.
Keberadaan etnis Cina sebagai etnis minoritas juga sering kurang
menguntungkan dalam konteks relasi minoritas – mayoritas. Etnis minoritas
selalu menjadi sasaran prasangka dan diskriminasi dari kalangan mayoritas.
Beberapa kali etnis Cina menjadi sasaran pengganti (displacement), kambing
hitam bagi rakyat yang frustrasi di era pemerintahan Orde Baru yang
represif dalam bentuk kerusuhan anti Cina yang sempat marak. Kedudukan
sebagai minoritas bagaimanapun selalu rawan, baik itu dalam posisi sebagai
minoritas yang lemah maupun minoritas yang kuat.
Jika dilihat dari format negara Indonesia yang indigeneus nation
(negara suku) maka sudah selayaknya format yang pas adalah
menempatkan etnis Cina sama kedudukannya dengan suku-suku lainnya
(Suryadinata, 1999). Di jaman Orde Lama, Bung Karno pernah memunculkan
ide bahwa orang Cina adalah salah satu suku di Indonesia yang setara
dengan suku Jawa, Sunda, Minang, Batak dan sebagainya. Dengan demikian
orang Cina telah menjadi orang Indonesia sejati tanpa asimilasi total. Namun
akibat meletusnya pemberontakan G30S PKI ide tersebut kandas untuk
diwujudkan ( Suryadinata, 1993). Bahkan di era Orde Baru orang Cina harus
melakukan asimilasi total dengan meleburkan identitas etnisnya ke dalam
identitas etnis Indonesia (Susetyo, 2002). Namun demikian konsep tentang
identitas Indonesia sendiri menurut Lan (1999) juga belum jelas. Apakah
sosok Rudy Hartono, Kwik Kian Gie dan orang Cina lainnya yang telah
mengharumkan nama bangsa sebagai model bagi identitas Indonesia
tersebut ?
Karena berbagai tekanan dan ketidakpastian tersebut, maka orang
Cina berada di persimpangan jalan. Hal tersebut setidaknya tergambarkan
dari temuan penelitian dari Lan (1998) yang menunjukkan bahwa sekarang
ini berkembang berbagai orientasi identifikasi diri di kalangan orang Cina di
Indonesia. Setidaknya ada 4 orientasi yang ditemukan,
Kelompok pertama, adalah mereka yang percaya bahwa mereka
adalah etnis Cina dan akan selalu menjadi etnis Cina. Oleh karena itu
dalam mengidentifikasikan diri, mereka selalu kembali ke asal usul dan
warisan budaya etnis Cina.
Kelompok kedua, adalah mereka yang merasa telah berhasil
berasimilasi ke dalam masyarakat Indonesia. Mereka ini adalah orang-
orang yang merasa asal usul etnis dan budaya mereka merupakan
kutukan yang menyulitkan posisi mereka untuk menjadi bagian yang
utuh dari masyarakat dimana mereka tinggal.
Kelompok ketiga, adalah mereka yang berkeyakinan bahwa mereka
telah melampaui batas etnis, negara dan bangsa serta telah menjadi
seorang yang globalis dan internasionalis.
Kelompok keempat, adalah mereka yang cenderung beranggapan
bahwa hidup mereka ditentukan oleh pekerjaan mereka, sehingga
mereka lebih suka menghindari pengidentifikasian diri secara budaya
maupun politis.
Demikian pula dari temuan dari Tan (1998) yang meneliti tentang
aspirasi dan partisipasi politik orang Cina, ternyata terpilah-pilah menjadi
lima kelompok cara pandang, yaitu :
Kelompok pertama adalah yang merasa perlu menonjolkan identitas
etnis mereka dan memperjuangkan hak mereka sebagai golongan,
misalnya dengan mendirikan Partai Tionghoa.
Kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau menjadikan etnis atau
agama sebagai basis gerakan, melainkan melalu platform persamaan
hak, misalnya dengan mendirikan Partai Bhineka Tunggal Ika.
Kelompok ketiga adalah kelompok yang lebih menyukai sebuah forum
yang tujuan utamanya lebih sebagai pressure group.
Kelompok keempat adalah mereka yang membentuk paguyuban
kelompok karena perasaan senasib sepenanggunan. Misalnya dengan
mendirikan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia.
Kelompok kelima adalah mereka yang bergabung dalam partai politik
yang terbuka seperti PDI Perjuangan, PAN dan lain sebagainya.
Dari paparan di atas kiranya dapat diperoleh gambaran tentang
bagaimana dinamika pencarian identitas etnis Cina di Indonesia. Pada
kenyataannya di tengah masyarakat etnis Cina telah berkembang subkultur-
subkultur baru yang merupakan respon terhadap realitas sosial yang
berkembang dan semakin menggambarkan identitas etnis Cina yang plural.
Namun dapat kita lihat pula, bahwa krisis identitas yang terjadi di kalangan
etnis Cina di Indonesia sangat terkait dengan nuansa kebijakan politik
penguasa, dimana mereka memiliki kepentingan tertentu untuk
menempatkan etnis Cina sesuai dengan kemauan politiknya. Posisi minoritas
yang cenderung rentan, selalu memojokkan etnis Cina dari waktu ke waktu.
Krisis identitas etnis Cina terutama memuncak pasca pemberontakan G30S
PKI yang menempatkan status etnis Cina dalam tataran terburuk. Dalam
upaya menemukan kembali citra identitas sosial yang positif, etnis Cina
menggunakan modus yang variatif baik dalam bentuk mobilitas sosial
maupun dengan perubahan sosial.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20020)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2475)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19653)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookRating: 4 out of 5 stars4/5 (2515)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (3275)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceFrom EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceRating: 4 out of 5 stars4/5 (2556)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12946)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2566)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionFrom EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (726)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksFrom EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksRating: 4 out of 5 stars4/5 (7086)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)From EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (7770)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6520)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleFrom EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HoleRating: 4 out of 5 stars4/5 (4609)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)From EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (4345)







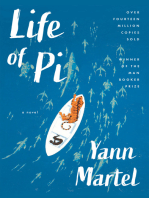
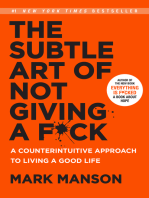





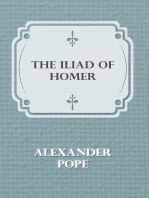





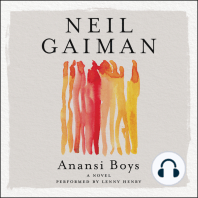






![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)