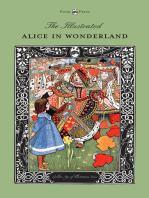Professional Documents
Culture Documents
Qur'an Abu Zayd
Uploaded by
harizfocus9259Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Qur'an Abu Zayd
Uploaded by
harizfocus9259Copyright:
Available Formats
1
Quran Abu Zayd
Oleh Abd Moqsith Ghazali
30/08/2004
Dalam membaca Alquran, Abu Zayd berseru agar mengambil posisi yang benar. Sebagai pembaca, kita mesti sadar akan ideologi dan subyektifitas diri kita sendiri, sehingga tidak mudah terjerembab pada sikap pemutlakan. Seorang pembaca tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang dalam memaknai sebuah teks, umpamanya dengan mensubordinasi teks ke dalam kehendak-kehendak si pembaca. Hubungan antara teks dan pembaca tak terpisahkan. Tanggal 28-29 Agustus 2004 ini, Jaringan Islam Liberal (JIL) bekerja sama dengan International Center for Islam and Pluralism (ICIP) menyelenggarakan workshop pemikiran bertitel Kritik Wacana Agama. Workshop ini dihadiri Nasr Hamid Abu Zayd, intelektual muslim asal Mesir yang kini tinggal di Leiden, Belanda. Dalam forum ini, Abu Zayd secara langsung akan mempresentasikan pikiran-pikirannya yang selama ini terlanjur dianggap keluar pakem alias melenceng. Oleh sejumlah ulama Mesir, Abu Zayd memang telah divonis murtad (keluar dari Islam). Vonis tersebut disebabkan pandangannya yang dianggap terlampau berani dalam soal Alquran. Misalnya, Alquran menurutnya adalah teks linguistik yang bersifat kemanusiaan, betapapun ia memiliki unsur keilahian. Alquran, ketika diujar dengan menggunakan piranti kultural dalam bentuk bahasa, diakui atau tidak telah bermetamorfosa menjadi teks yang terkena hukum sejarah. Makanya, Alquran adalah produk budaya, tandasnnya dalam buku Mafhmun Nash. Dengan demikian, Alquran tak bisa diposisikan pada hirarki transendental, dilucuti dari konteks budaya yang melingkupinya. Dalam membaca Alquran, Abu Zayd berseru agar mengambil posisi yang benar. Sebagai pembaca, kita mesti sadar akan ideologi dan subyektifitas diri kita sendiri, sehingga tidak mudah terjerembab pada sikap pemutlakan. Seorang pembaca tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang dalam memaknai sebuah teks, umpamanya dengan mensubordinasi teks ke dalam kehendak-kehendak si pembaca. Hubungan antara teks dan pembaca tak terpisahkan. Selalu ada jalinan yang dialektis antara teks dan pembaca. Bagi Abu Zayd, relasi antara teks dan pembaca bersifat dialektis (jadaliyah), bukan penundukan (ikhdha). Dengan cara ini, subyektivisme dalam proses pemaknaan diharapkan dapat diminimalisasi. Berbeda dengan Farid Esack, Asghar Ali Engineer, Hassan Hanafi, dan lain-lain, Abu Zayd masih meyakini adanya makna obyektif di balik suatu teks. Baginya, makna obyektif yang bersembunyi di balik teks-teks Alquran, mungkin ditemukan setelah proses obyektifikasi melalui piranti hermeneutika. Ia mengusulkan agar hermeneutika selalu berpijak pada pemilahan yang tegas antara makna kesejarahan suatu teks (al-manat trkh) dan pengertian atau interpretasi baru (al-maghz) yang ditarik dari makna kesejarahan-obyektif tersebut. Menurutnya, makna historis itulah yang pertama-tama harus diungkap seorang penafsir, dengan pembacaan pada struktur internal dan dimensi historis (al-budut trkh) teks tersebut. Setelah itu, baru dilakukan penafsiran yang mungkin menjawab problem-problem kehidupan masa kini. Metode tafsir ini memungkinkan Alquran terbuka untuk makna-makna yang baru (qbil litajaddudil fahm). Abu Zayd telah memberi perspektif lain tentang kedudukan Alquran, plus cara membaca dan memahaminya. Setiap kita bisa bersetuju atau menolak. Penerimaan dan penolakan suatu pemikiran tentu hal yang lazim dalam dunia akamedis-intelektual. Yang tidak lazim adalah penolakan atas orang yang berbeda pikiran dengan kita, disertai caci maki, lebih-lebih vonis kafir atau murtad. [Abd Moqsith Ghazali]
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20018)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19653)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookRating: 4 out of 5 stars4/5 (2515)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2566)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceFrom EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceRating: 4 out of 5 stars4/5 (2556)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12945)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6520)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionFrom EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (726)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksFrom EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksRating: 4 out of 5 stars4/5 (7086)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)From EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (7770)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (3275)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleFrom EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HoleRating: 4 out of 5 stars4/5 (4609)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersFrom EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersRating: 4 out of 5 stars4/5 (2314)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)From EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (4345)







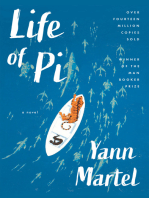
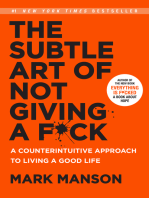





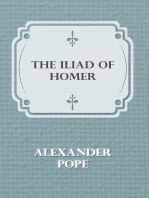





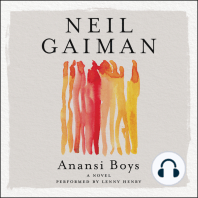

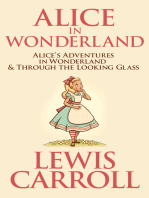



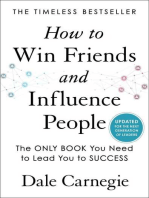
![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)