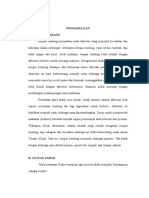Professional Documents
Culture Documents
Tugas La Idi
Uploaded by
La RamanCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Tugas La Idi
Uploaded by
La RamanCopyright:
Available Formats
1.
Pendahuluan
Yang ang pertama terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Itu terjadi pada
bulan Januari dan Februari 1997. Koran-koran memberitakan bahwa penduduk asli Dayak
mulai menyerang para pendatang Madura di rumah-rumah mereka di kota kecil Sanggau
Ledo, kemudian bergerak ke kota-kota kecil di sekitar kabupaten itu, sehingga membuat
puluhan ribu orang lari untuk menyelamatkan nyawa. Orang-orang Indonesia tersentak.
Kekerasan kolektiI antarwarga Indonesia mengenai identitas komunal belum pernah terjadi
sebelum itu. Atau lebih tepat lagi, hal itu tidak membekas dalam kesadaran publik sampai
sekuat itu, sebab pada bulan-bulan sebelum itu telah terjadi huru-hara sehari atau dua hari
dengan sasaran orang-orang Kristen dan Cina di Jawa. Yang satu ini terjadi dengan skala
jauh lebih besar. Kekerasan sepihak itu berlangsung selama berminggu-minggu, dan
merambah sampai ke beberapa kabupaten.
Pertumpahan darah itu sendiri sudah meresahkan, tetapi ada hal lain yang lebih
menggelisahkan. Kejadian itu sangat tidak terduga. Hal itu membuat pikiran rata-rata orang
Indonesia terperangah, karena mereka tidak memiliki penjelasan sama sekali. Orang-orang
Indonesia sudah lama mengenal kekerasan di tiga tempat yang terpencil di negeri mereka
Aceh, Papua (waktu itu masih disebut Irian Jaya), dan Timor Timur. Meskipun sebagian
besar tertutup bagi para wartawan, masyarakat tahu bahwa sentimen pemisahan diri
menjadi pendorong gerakan resistansi gerilya di sana, dan bahwa militer Indonesia telah
membunuh banyak orang dalam operasi-operasi penumpasan pemberontakan tersebut.
Negara sebagai sumber kekerasan: ini mudah dipahami bagi pejabat-pejabat rezim maupun
para aktivis hak-hak asasi manusia. Itu adalah bagian dari wacana umum mengenai dosa
Orde Baru. Dan hal sejenis juga terjadi di tempat yang tidak jauh. Huru-hara besar di
Jakarta setelah serangan yang didukung oleh militer terhadap markas besar partai oposisi
PDI pada bulan Juli 1996 cocok dengan pola tadi. Begitu pula sederetan insiden
pelanggaran hak asasi lain oleh militer, misalnya penembakan di pinggir pelabuhan
terhadap ratusan orang di Tanjung Priok, Jakarta, pada tahun 1984, dan pembunuhan
massal di Desa Talangsari, Lampung, pada tahun 1989. Sebuah negara demokratis dengan
militer yang terkendali dengan ketat adalah idaman setiap orang, bahkan idaman anggota-
anggota rezim, walaupun mereka percaya bahwa ideal itu masih memerlukan waktu begitu
panjang untuk diwujudkan. Tetapi emosi yang digugah oleh berita-berita tentang Sambas
itu lain. Siapa yang menjadi penjahat dalam kisah ini? Itu tidak jelas. Militer sekarang
disalahkan bukan karena menjadi penyebabnya, melainkan karena tidak berbuat cukup
banyak untuk menghentikan kerusuhan itu. Pers ibukota melaporkan kisah itu, tetapi
kolom-kolom opini tetap bungkam mengenai masalah moral mendalam serius yang
dihadapkannya. Tentu saja masalahnya adalah bagaimana Indonesia bisa menjadi negara
demokratis jika di Sambas warga negara biasa menyerang satu sama lain hanya karena
perbedaan budaya yang tidak disukai? SetiaLonesia men elaskann a, mereka seringkali
menyebutbut budaya kebuasan orang-orang Dayak atau (belakangan) watak pemarah
orang-orang Ambon. Itu tidak menjelaskan apa pun selain menunjukkan prasangka yang
ada di kepala para komentator itu, dan mengaburkan drama yang sebenarnya dengan jalan
menutup aktor-aktor penyebab kisah tragis itu. Setiap kali para pembuat kebijakan mulai
mempercayai penjelasan berdasarkan stereotip budayadan itu memang mereka lakukan di
Kalimantan Barat dan Tengahmereka justru membuat berbagai hal jadi kacau dengan jalan
melembagakan sentimen-sentimen rasis.
Kekacauan dalam kolom-kolom opini Indonesia menjadi alasan yang cukup kuat
untuk menulis buku ini. Hidup di negeri itu memungkinkan saya mengapresiasi seberapa
serius para intelektual publik negeri itu menjalankan panggilan mereka. Andaikata mereka
kebingungan, hal itu karena mereka tidak mempunyai cukup bahan untuk dijadikan dasar
kesimpulan. Sejak itu kesenjangan tersebut dengan cepat diisi oleh terbitan-terbitan baik
oleh orang Indonesia maupun asing. Dalam bab berikut kita akan menyaksikan sebagian
dari wacana-wacana konIerensi, artikel-artikel jurnal dan laporan-laporan teknis yang
mengalir deras ini (lihat bibliograIi oleh Smith, G. dan Bouvier-Smith 2003). Beberapa
buku bunga rampai menggambarkan kekerasan selama periode itu (Anderson 2001;
Colombijn dan Lindblad 2002; Coppel 2006; Tornquist 2000; Wessel dan WimhoIer 2001).
Meskipun begitu, tidak satu pun yang diIokuskan pada kekerasan komunal pasca-otoriter
sebagai Ienomena tunggal. Hal yang sama bisa disimpulkan mengenai dua buku yang
disusun oleh seorang penulis. Bertrand (2004) mengelompokkan konIlik Muslim-Kristen di
Maluku dengan konIlik separatis di Aceh, Papua dan Timor Timur sebagai bagian dari
sebuah krisis umum dalam nasionalisme Indonesia. Buku Sidel (2006) akan dibaca
terutama sebagai sebuah pengkajian tentang kekerasan Islamis.
Dua tahun setelah peristiwa Sambas, pecah pertempuran antara orangorang Muslim
dan Kristen di Ambon, pusat urban terbesar di timur Makasar. Ini jauh lebih menyakitkan
bagi publik Indonesia. Dahulu Ambon adalah kota pelabuhan yang ramai dan tidak dapat
dibayangkan menjadi medan pertempuran belantara. Para penyanyi Ambon terkenal di
lingkaran kabaret sophisticated Jakarta. Terlebih lagi, ini adalah era ReIormasi. Presiden
Soeharto telah mengundurkan diri pada bulan Mei sebelumnya di tengah-tengah
demonstrasi besar-besaran. Hari demi hari dipenuhi dengan pembaharuanpembaharuan di
setiap sektor. Peristiwa Ambon adalah pukulan berat bagi optimisme yang mengikuti
berakhirnya Orde Baru yang otoriter. Peristiwa itu juga bukan disebabkan oleh sesuatu
kebudayaan kesukuan yang primitiI, sebagaimana banyak orang ibukota memandang
orang-orang Dayak dengan perasaan benci, melainkan melibatkan dua agama yang sama-
sama dianut oleh orang-orang Indonesia. Meskipun begitu, kolom-kolom opini tidak
menyodorkan banyak jawaban yang demokratis, meskipun opini-opini yang tidak
demokratis tumbuh menjamur dalam pers sektarian.
Pada saat yang hampir bersamaan, akhir tahun 1998 dan awal 1999, pertempuran
komunal juga meledak di dua tempat lain. Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat,
kekerasan kembali meletus, di daerah yang agak berbeda tetapi sekali lagi mengakibatkan
penggusuran terhadap orang-orang Madura, kali ini dipicu oleh penduduk asli Melayu. Dan
di Poso, sebuah kota kecil di Kalimantan Tengah, kekerasan meledak antara orang-orang
Muslim dan Kristen. Kabar buruk itu tidak berhenti sampai di situ. Setahun kemudian, pada
akhir tahun 1999, ketegangan yang memuncak meledak di Maluku Utara yang melibatkan
berbagai macam medan, antara Muslim dengan Kristen, dan antara Muslim dengan Muslim
yang lain. Daerah itu terletak 400 km dari Ambon dan memiliki dinamika tersendiri.
Kemudian kekerasan terjadi di Kalimantan Tengah. Dengan pola yang mirip dengan
Kalimantan Barat, penduduk asli Dayak menyerang para pendatang Madura di kota
pelabuhan Sampit pada bulan Februari 2001, kemudian bergerak ke seantero provinsi
sambil mengusiri orang-orang Madura.
Secara keseluruhan, keenam episode kekerasan di lima tempat ituKalimantan Barat,
Maluku (Ambon), Sulawesi Tengah (Poso), Maluku Utara, dan Kalimantan Tengah
memberikan gambaran pola kekerasan yang cukup jelas. Mereka menjadi subjek buku ini.
Berbeda dari kekerasan gerakan pemisahan di tiga daerah pinggiran tersebut di atas, yang
sudah berlangsung selama puluhan tahun, kekerasan di lima tempat itu benar-benar baru.
Maksudnya, kekerasan itu tidak sepenuhnya tanpa preseden. Orang-orang Dayak
Kalimantan Barat mengingatkan kembali tentang insiden-insiden yang terjadi bertahun-
tahun sebelumnya dengan orang-orang Madura, dan orangorang Muslim Ambon juga ingat
bahwa pemberontakan 1950 juga melibatkan sentimen agama. Tetapi kali ini kekejamannya
melebihi yang sudah pernah terjadi, sementara identitas-identitas yang terlibat sebagian
besar terlepas dari klaim-klaim tentang bangsa, dan dengan demikian berbeda dari
pengalaman di Ambon pada tahun 1950. Setiap konIlik berjangka panjang dari beberapa
minggu sampai bertahun-tahun. Setiap konIlik memakan banyak korbanratusan atau ribuan
orang mati dan puluhan atau ratusan tergusur. Setiap konIlik menyebar luasantara seantero
kabupaten atau seantero provinsi. Dan tiap-tiap konIlik bersiIat komunalantara kelompok-
kelompok dalam masyarakat mengikuti garis-garis asal-usul etnis atau agama, tidak secara
eksplisit tentang kelas, dan tidak menentang negara.
Pendek kata, buku ini membahas kekerasan komunal skala besar, sebab hal ini baru di
negeri ini dan perlu dijelaskan. Tetapi ini bukanlah satu-satunya kekerasan kolektiI yang
terjadi dengan bentuk-bentuk menonjol pada waktu itu. Salah satu persoalan penting bagi
buku mendatang adalah melihat bagaimana semua kesulitan itu berkaitan dengan satu sama
lain. Kita bisa membedakan adanya empat tipe:
1. Kekerasan sepemisahan diri. Yang paling terkenal adalah ledakan-ledakan kekerasan
yang disponsori oleh militer di Timor Timur yang mempermasalahkan jajak
pendapat pada 1999 (Greenlees dan Garran 2002; Tanter, Ball dan Klinken 2006).
Kekerasan represiIserupa tengah terjadi di Aceh dan, di tingkat yang lebih rendah,
Papua sepanjang masa itu.
2. Kekerasan komunal skala besar, baik antar-agama dan antar-etnis (yang menjadi
subjek buku ini).
3. Huru-hara komunal lokal. Beberapa insiden kekerasan terjadi dengan skala kota
kecil atau kota besar dan berlangsung selama beberapa hari. Yang paling terkenal
adalah huru-hara besar-besaran di Jakarta pada Mei 1998 yang mengarah pada
pengunduran diri Soeharto (Aspinall, Feith dan Klinken 1999). Sebelum itu,
berbagai huru-hara anti-Gina yang pendek tetapi sengit terjadi pada tahun 1996-7 di
kota-kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Situbondo
(Jawa Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan) (Sidel 2006). Setelah itu berbagai
huru-hara Kristen-Muslim terjadi di Ketapang (Jakarta) dan Kupang (Timor Barat)
pada November 1998 (Mas'oed, Maksum dan Soehadha 2001).
4. Kekerasan sosial. Yang tidak begitu menonjol, tetapi menuntut korban lumayan
besar, adalah Ienomena "sosial" seperti vigilantisme (main hakim sendiri terhadap
para pencuri) dan perselisihan-perselisihan antardesa. Kekerasan-kekerasan ini juga
memuncak setelah jatuhnya Orde Baru, tetapi tanpa hubungan "politis" yang jelas
(Barron, Kaiser dan Pradhan 2004; Welsh 2003). Ini terjadi khususnya di Jawa,
Lombok dan Sulawesi Selatan (Varshney, Panggabean dan Tadjoeddin 2004:33).
Serangkaian pembunuhan yang menggegerkan terhadap orang-orang yang dituduh
sebagai tukang santet di Jawa Timur pada akhir 1998 agaknya bisa digolongkan di
antara huru-hara komunal yang kurang lebih terorganisir di satu pihak dan kekerasan
sosial di pihak lain (Campbell dan Connor 2000; Siegel 2001).
Kekerasan teroris bisa dianggap sebagai tipe kelima. Kekerasan yang satu ini menarik
perhatian seluruh dunia setelah 11 September 2001, dan kekerasan
itu telah terjadi di Indonesia (Sidel 2006). Meskipun begitu, kekerasan itu dilakukan oleh
kelompok-kelompok kecil yang bertindak secara sangat rahasia, jadi tidak dapat dianggap
sebagai kekerasan kolektiI sampai di tingkat yang sama. Dibandingkan dengan tipe-tipe
kekerasan yang lain, kekerasan ini juga menuntut korban tewas lebih kecil, meskipun
dampak goncangan dari para korban yang tewas tentu saja tidak sebanding dengan
angkanya.
Berapa banyak yang mati? Kekerasan kolektiI non-pemisahan diperkirakan oleh United
Nations Support Facility Ior Indonesian Recovery (UNSFIR) telah melenyapkan nyawa
lebih dari 10.000 orang di Indonesia pada periode 19902003 (Varshney, Panggabean dan
Tadjoeddin 2004). Ini hanya perkiraan nasional per provinsi, dan mencakup keseluruhan
periode transisional. Perkiraan itu didasarkan pada pemberitaan koran tingkat provinsi. Itu
adalah perkiraan konservatiI. Sebuah pengkajian oleh World Bank mengenai korankoran
tingkat kabupaten di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur selama 2001-2003
menunjukkan bahwa koran-koran provinsi sering menyebut angka yang terlalu rendah dari
para korban tewas yang terkait dengan konIlik kekerasan, khususnya dari jenis yang oleh
Varshney dan kawan-kawan digolongkan kekerasan sosial (Barron dan Sharpe 2005).
Meskipun begitu, statistik kekerasan sosial yang dikumpulkan oleh pengkajian lokal World
Bank ini menghitung kematian-kematian kejahatan sebagai terkait dengan konIlik, yang bisa
menjadi asumsi yang patut dipertanyakan. Sementara itu kekerasan pemisahan diri di Timor
Timur diperkirakan telah melenyapkan nyawa 1.4001.500 orang pada 1999 (dengan 250.000
orang dipaksa pindah ke Timor Barat) (CAVR 2005: 7.2 hlm.245). Angka korban kekerasan
pemisahan diri di Aceh tetap tidak didokumentasikan dengan baik, tetapi diperkirakan
mencapai sekitar 7.200 dari akhir Orde Baru sampai pertengahan 2005.
1
Angka-angka untuk
Papua jauh lebih rendah, dan diabaikan dalam penghitungan ini. Secara keseluruhan (dan
dengan mempertahankan perkiraanperkiraan konservatiI UNSFIR), sebuah perkiraan kasar
untuk korban tewas akibat kekerasan yang terkait dengan transisi Indonesia 1998 hampir
mencapai 19.000, lebih dari separuhnya tewas akibat konIlik komunal dan sebagian besar
dari sisanya akibat kekerasan pemisahan diri. Orang-orang yang tergusur adalah dampak
sosial yang lain lagi dari perselisihan itu. Mendekati puncaknya
pada Juli 2002, sekitar 1,3 juta orang tergusur dari rumahnya terutama akibat kekerasan
komunal dan kekerasan pemisahan diri (Norwegian ReIugee Council 2002). Angka total
dari orang yang tergusur sebenarnya jauh lebih besar.
Dengan hanya menuliskan kekerasan non-pemisahan diri, dan mengesampingkan
kekerasan sosial, laporan UNSFIR menarik kesimpulan berikut ini:
O Baik jumlah kejadian maupun jumlah korban tewas meningkat tajam pada tahun
1996, dan mencapai puncaknya pada tahun 1999-2000, dan setelah itu menurun
dengan cepat (Varshney, Panggabean dan Tadjoeddin 2004:25) (Gambar 1.1).
Dengan demikian puncak itu terjadi langsung sesudah runtuhnya Orde Baru, tetapi
kekerasannya mulai menanjak sekitar dua tahun sebelum itu.
O Hampir 90 dari korban tewas itu akibat kekerasan komunal, baik yang skala besar
maupun lokal. Dari korban tewas itu, 57 akibat kekerasan Kristen-Muslim, 29
anti-Madura, dan 13 anti-Cina (Varshney, Panggabean dan Tadjoeddin 2004:26).
Dengan kata lain, kekerasan komunal skala besar yang dibahas dalam buku ini, yaitu
kekerasan Kristen-Muslim dan anti-Madura, sejauh itu menuntut korban tewas
terbesar dari semua kekerasan kolektiI tipe apa pun.
O Keenam provinsi dengan kekerasan terbesar adalah Maluku Utara (25 dari korban
tewas), Maluku (sekitar Ambon, 18,3), Kalimantan Barat (13,6), Jakarta (11,8),
Kalimantan Tengah (11,5), dan Sulawesi Tengah (6,0) (Varshney, Panggabean
dan Tadjoeddin 2004:30). Kecuali untuk Jakarta, tempat-tempat ini adalah lokasi
kekerasan komunal skala besar, dan menjadi Iokus dari buku ini.
Huru hara anti-Cina terjadi dalam ledakan-ledakan pendek kekerasan urban yang
dilokalisir. Itu sudah menjadi pola yang terulang-ulang sepanjang Orde Baru (Chirot dan
Reid 1997; Coppel 2002). Yang mengherankan, kekerasan itu ikut menghilang bersamaan
dengan jatuhnya Orde Baru. Kejadian besar terakhir adalah huru-hara di Jakarta (dan Solo)
yang mengakibatkan kejatuhan Soeharto pada Mei 1998. John Sidel (2001, 2006)
menyatakan bahwa huru-hara anti-Cina adalah bagian dari naik daunnya elite
Muslim yang bergantung pada negara, dan bahwa huru-hara tipe ini mendadak berhenti
ketika kelompok itu meningkatkan taruhan dalam usaha memanIaatkan peluang lebar pasca-
1998 dengan jalan melancarkan persaingan agama secara langsung. Huru-hara anti-Gina
tidak dibahas lebih jauh dalam buku
Dengan demikian kekerasan komunal menuntut korban lebih besar daripada kekerasan
tipe lain manapun dalam periode itu sedikit melebihi kekerasan pemisahan diri, melebihi
pula "kekerasan sosial" (sebuah kategori abu-abu yang membayangi kriminalitas "biasa" dan
yang juga melonjak pada waktu itu), jauh lebih besar daripada huru-hara lokasi-tunggal
lokal dari tahuntahun terakhir Orde Baru, dan jauh melebihi kekerasan teroris yang begitu
menyibukkan pikiran para komentator Indonesia pasca 11 September.
Dalam hal skala dan durasi, satu-satunya pembunuhan yang lebih mengerikan daripada
yang satu ini yang pernah terjadi di Indonesia adalah pembantaian anti-komunis pada tahun
1965-66 (Cribb 1990). Pembunuhan ini menyebar lebih luas dan menewaskan lebih dari
setengah juta orang, tetapi yang terburuk di Jawa dan Bali. Militer mengorganisir
pembunuhan-
pembunuhan itu, tetapi aktor-aktor masyarakat seperti organisasi-organisasi keagamaan juga
ikut ambil bagian. Sebuah perbandingan yang seksama mengenai kedua masa tragis akan
menjadi kegiatan yang sangat berharga. Di balik ideologi yang jelas berbasis kelas, yang
absen dalam peristiwa-peristiwa pasca-1998, kejadian-kejadian 1965/66 melibatkan
identitas-identitas askriptiI, terutama penganut aliran-aliran Islam yang berlainan. Yang
terpenting, pembasmian-pembasmian itu terjadi pada saat pergantian rezim, dari
kepresidenan Sukarno ke Soeharto, persis sebagaimana episode-episode yang digambarkan
dalam buku ini terjadi selama transisi dari Soeharto ke era ReIormasi. Episode-episode
kekerasan kolektiI lain dalam sejarah Indonesia juga mempunyai ideologi-ideologi politik
bangsa atau kelas yang berbaur dengan identitas-identitas etnis atau religius misalnya
pemberontakan Darul Islam pada masa 1950-an (Dijk 1981), dan tentu saja revolusi
nasional 194550 (Reid 1974). Yang membedakan kekerasan pasca-Orde Baru adalah bahwa
masalah-masalah kelas dan bangsa Indonesia praktis tidak ada dan pertarungan dilakukan
hampir sepenuhnya berdasarkan identitas-identitas komunal. Inilah yang mengguncang
publik Indonesia, yang sebelumnya percaya betul bahwa menjadi orang Indonesia tidak
banyak berkaitan dengan etnisitas atau agama.
Kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari kekerasan komunal ini? Wacana publik
Indonesia beredar di seputar istilah "disintegrasi." Dengan menghitung Irekuensi istilah ini
di berbagai waktu dalam koleksi saya yang luas mengenai kliping koran elektronik
Indonesia, saya mendapatkan bahwa istilah itu masuk secara mendadak ke kosakata berita
pada bulan Juni 1998, hanya beberapa hari sejak huru-hara besar-besaran yang
mengakibatkan jatuhnya Presiden Soeharto. Istilah itu terus didengung-dengungkan selama
masa itu, tetapi kemudian mengabur menjelang akhir tahun 2001. Pada waktu itu sebagian
besar dari pertarungan komunal itu telah berakhir, dan seorang presiden baru telah dipilih,
yaitu Megawati Sukarnoputri, yang luas dipandang sebagai pemimpin yang akan
memulihkan ketertiban. Istilah itu tidak hanya mengisyaratkan bahwa kesepakatan politis
yang disebut Indonesia itu tengah berantakan, tetapi begitu pula ikatan-ikatan sosial biasa di
antara orang-orang yang saling bertetangga. Istilah lain yang saya temui adalah "Pancasila,"
ideologi semi-sekuler yang agak banal dan yang sering didengung-dengungkan oleh
Orde Baru. Frekuensinya menurun secara dramatis setelah tahun 1998, yang
mengisyaratkan adanya krisis dalam nasionalisme "resmi." Para Islamis telah lama
mengecam sikap Soeharto yang mengedepankan Pancasila, dengan menyatakan bahwa
Soeharto lebih menghormati karya manusia dengan menomorduakan wahyu Tuhan, tetapi
sekarang kritik mereka terdengar secara lebih terbuka. Para pakar asing mengenai Indonesia
menggemakan perasaan tentang perpecahan ini dalam tulisan-tulisan mereka (Dijk 2001;
Kingsbury dan Aveling 2003). Bertrand (2004) melacak berbagai jenis kekerasan kolektiI
di Insonesia sampai ke krisis identitas ini. Kesigapan dengan mana kata disintegrasi masuk
ke benak para pengarah opini utama mengisyaratkan pengaruh kuat tradisi intelektual yang
menganggap kekerasan komunal sebagai berasal dari perpecahan dalam ikatan-ikatan
sosial. Pandangan yang disebut social strain and breakdown ini memandang huru-hara
sebagai sebuah penyakit sosial, seperti perilaku massa agresiIdan irasional yang didorong
oleh ketakutan atau Irustrasi. Horowitz (2001: 7, 34-42) memberikan ulasan yang
bermanIaat mengenai literatur luas yang didasarkan pada ide-ide seperti itu, dan
mengungkapkan bahwa sampai sejauh tertentu is sendiri menganut pandangan itu.
Meskipun begitu, ketika saya memperluas penghitungan itu sehingga mencakup kata-
kata kunci lain, saya menemukan tanda-tanda adanya trend kedua. Trend ini membantah
pandangan bahwa segala sesuatu tengah pecah berantakan, dan sebagai gantinya malah
mencerminkan sebuah ideologi alternatiItentang kebangsaan yang mulai muncul di tingkat
lokal. Istilah "putra daerah," yang dikaitkan dengan lokalisme etnis, menanjak dengan cepat
sesudah tahun 1998. Begitu pula istilah "adat." Kedua istilah cenderung menurun lagi
dalam pers mainstream sesudah tahun 2001. Semua itu menjadi petunjuk, yang bisa dengan
mudah dikonIirmasikan hanya dengan mengunjungi daerah-daerah luar Jawa, bahwa apa
yang dulu dipandang sebagai perpecahan sosial di Jakarta bisa secara lokal dianggap
sebagai sebuah awal baru.
2
Pandangan yang naiI tetapi tersebar luas di Jakarta adalah
bahwa orangorang Indonesia luar Jawa itu tradisional, religius, dan pasiI. Tetapi di luar
sana ada kehidupan dan harapan yang mengekspresikan diri dalam suatu wacana yang tidak
didengar oleh Jakarta. Seringkali hal itu memiliki karakter lokalis, bahkan xenoIobis, dan
toleransi bagi agama-agama dan etnisitas-
etnisitas yang berbeda memang tipis. Kekerasan sebenarnya tinggal mencuat saja ke
permukaan. Tetapi intinya adalah bahwa hal ini sepenuhnya bersiIat politis, dan bukan
hanya anomis (artinya bukan hanya penyakit sosial). Yang terpenting adalah bahwa hal itu
menyangkut usaha mengklaim kembali pemerintahan daerah bagi komunitas lokal.
Hal itu membawa saya pada upaya mencari literatur teoretis alternatiI, yang akan
memberikan ruang bagi karakter politis episode-episode kekerasan komunal tersebut. Saya
menemukan beberapa perkembangan baru dalam teori gerakan-gerakan sosial (social
movements theory) yang sangat menarik dalam hal ini. Dalam pengertian yang agak
mengerikan, kekerasan adalah salah satu bagian dari politik normal. Meskipun hal ini
kedengaran mengejutkan, saya percaya Iakta-Iakta yang ada akan membenarkannya.
3
Para editor The Blackwell Companion to Social Movements (Snow, Soule dan Kriesi
2004b:11) mendeIinisikan gerakan sosial, dengan cara yang tidak begitu anggun tetapi
komprehensiI, sebagai:
"...kolektivitas-kolektivitas yang dengan organisasi dan kontinuitas tertentu bertindak di
luar saluran-saluran institusional atau organisasional dengan tujuan menggugat atau
mempertahankan otoritas, entah yang didasarkan secara institusional atau kultural, dan
berlaku dalam kelompok, organisasi, masyarakat, kebudayaan atau tatanan dunia di mana
mereka merupakan salah satu bagiannya."
Konseptualisasi ini melibatkan lima poros, dan setiap gerakan harus menunjukkan
sedikit-dikitnya tiga poros agar bisa dianggap sebagai gerakan sosial. Kelima poros itu
adalah:
O tindakan kolektiI atau gabungan; tujuan-tujuan atau klaim-klaim yang berorientasi
pada perubahan;
O sesuatu tindakan kolektiI yang bersiIat ekstra-institusional atau non institusional;
O organisasi sampai tingkat tertentu;
O keberlanjutan dalam hal waktu, sampai tingkat tertentu.
Sebagaimana akan diilustrasikan oleh buku ini, kejadian-kejadian di Indonesia itu
memiliki beberapa dari karakteristik-karakteristik itu. Massa yang menyerang para pemukim
Madura di Kalimantan di waktu-waktu yang berlainan, massa yang berkelahi di jalanan kota
Ambon atau desa-desa di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara mereka itu jelas merupakan
contoh tentang tindakan kolektiI. Perilaku massa seperti itu tentu saja mempunyai tempat
juga dalam literatur social strain, di mana perilaku itu dianggap sebagai "perilaku kolektiI"
yang irasional (Gurr 1970; Smelser 1962; Turner, R.H. dan Killian 1987). Tetapi gerakan-
gerakan di Indonesia itu memiliki karakteristik-karakteristik lain yang membuat gerakan-
gerakan itu nyaris nalar. Mereka memiliki tujuan-tujuan yang jelas. Beberapa tujuan bersiIat
taktis, misalnya mengusir atau mengalahkan kolektivitas-kolektivitas lain yang dipandang
asing atau berbahaya, maupun (khususnya) mengusahakan agar anggota-anggota mereka
sendiri diangkat ke posisi-posisi penting dalam pemerintahan daerah. Tujuan yang lain
bersiIat strategis, misalnya menuntut agar kelompok-kelompok pendatang tunduk pada
dominasi kultural "putra daerah," dan agar mereka sendiri diakui oleh pemerintah pusat
sebagai pemegang kekuasaan yang sah di daerah itu. Tak diragukan lagi itu adalah tujuan-
tujuan yang xenoIobis, tetapi dalam konteks Orde Baru yang berwatak militer, top-down dan
kaku itu, tujuan-tujuan itu juga mewakili perubahan, tuntutan akan demokrasi dan otonomi
lokal.
SiIat ekstra-institusional dari tindakan kolektiI gerakan-gerakan tersebut adalah salah
satu aspek-aspek dari tindakan kolektiI ini yang paling menarik. Mereka menggunakan
ruang-ruang publikjalananuntuk tujuan-tujuan yang berbeda dari tujuan perancangan
ruang-ruang itu. Namun, seperti demonstrasi-demonstrasi yang merebak di seantero negeri
itu sejak tahun 1998, mereka membawakan agenda yang jelas politis di suatu masa ketika
kebanyakan institusi berada dalam keadaan kacau balau. Selain itu, ini merupakan salah satu
butir utama, gerakan-gerakan yang melibatkan kekerasan komunal itu setidak-tidaknya
bersiIat semi terorganisir. Sebagian besar dari apa yang terjadi bersiIat ad hoc atau tidak
terkendali, tetapi banyak juga yang terjadi secara sengaja. Wacana Indonesia pada waktu itu
menudingkan telunjuk pada para "provokator" misterius yang ditugaskan oleh Jakarta untuk
menciptakan kerusuhan di tempat-tempat terpencil, tetapi sebuah penyelidikan kecil akan
segera berhasil mengungkapkan adanya hubungan-hubungan institusional lokal yang lebih
meyakinkan. Persisnya bagaimana para elite lokal dan partai-partai politik, gereja-gereja,
organisasi-organisasi mesjid, LSM-LSM dan kelompokkelompok penekan membantu
mengorganisir massa di jalanan adalah inti pembahasan buku ini. Keberlanjutan dalam hal
waktu, poros kelima yang mendeIinisikan gerakan sosial, menghadirkan masalah lebih besar
dalam kasuskasus Indonesia yang kami simak. Salah sate dari ciri-ciri mencengangkan dari
episode-episode ini adalah timbul-tenggelamnya mereka. Banyak pengamat mengatakan
kejadian tersebut muncul entah dari mana, dan setelah itu tidak meninggalkan bekas-bekas
sama sekali pada lanskap sosialnya selain komunitaskomunitas yang terpecah-belah. Tetapi
bahkan di sini kesan-kesan pertamanya cenderung mengelabui. Kenyataannya, organisasi-
organisasi etnis di Kalimantan bekerja secara diam-diam selama beberapa tahun sebelum
terjadinya ledakan besar tersebut. Organisasi-organisasi keagamaan, dengan segala sikap
eksklusiI mereka yang kompetitiI, ada di jantung setiap komunitas lokal sepanjang abad ke-
20 ini.
Pendek kata, teori gerakan sosial, dengan perhatian utama yang tertuju pada organisasi
dan hubungan dengan politik normal dalam keadaan krisis, menyodorkan perspektiI yang
lebih positiImengenai episode-episode kekerasan komunal Indonesia daripada yang bisa
ditemukan dalam buku-buku teks standar mengenai kekerasan kolektiIseperti yang ditulis
oleh Horowiotz (1985, 2001). Saya telah memperoleh banyak pelajaran dari karya-karyanya,
maupun dari karya Gurr (1993) dan dari aneka pengkajian sejumlah Indonesianis, kapan-
kapan akan mengutip mereka, dan masih akan mendapatkan pelajaran lebih banyak lagi dari
mereka.
4
Tetapi janji menggunakan sejumlah kecil konstruk teoretis untuk berbicara tentang
sejumlah besar kejadian-kejadian nyata tingkat dunia, yang inheren dalam program
penelitian gerakan sosial, mengedepankan godaan menjadi spesialis dalam literatur tentang
kekerasan kolektiI.
Perkembangan baru pertama dalam teori gerakan sosial adalah sebuah inovasi
strukturalis pada 1970-an yang disebut resource mobili:ation. Ini didasarkan pada
pengakuan bahwa sukses tidaknya perjuangan orang bukannya didorong oleh keluhan-
keluhan dari para peserta gerakan, melainkan dari kemampuan mereka untuk
memaksimalkan akses menuju sumber-sumber organisasional. Semua jenis setting kolektiI
di tingkat akar rumputdari gereja sampai jaringan-jaringan persahabatanbisa menjadi
titik tolak untuk mengorganisir sesuatu gerakan. Perkembangan kedua datang dari
pengakuan bahwa bukan hanya sumber-sumber, tetapi juga kesempatan-kesempatan
(peluang) politis menentukan momen kapan sebuah gerakan sosial memiliki peluang terbaik
untuk mendapatkan kemajuan-kemajuan signiIikan. Kesempatan-kesempatan memberikan
penghubung antara politik Iormal dengan gerakan-gerakan sosial. Kesempatan bisa
menjelaskan, misalnya, bahwa gerakan-gerakan merebak di Indonesia pada tahun 1998
karena pengunduran diri Presiden yang mendadak itu mengarah pada perpecahan
institusional dalam tubuh pemerintah. Lemahnya lembaga pemerintahan membuka peluang
bagi orang yang menginginkan perubahan. Perkembangan yang ketiga memperhitungkan
semakin besarnya kesadaran bahwa apa yang sampai saat itu selalu digambarkan sebagai
struktur-struktur pada dasarnya adalah ide-ide yang ditentukan secara kultural dalam kepala
orang-orang. "Framing" (pembingkaian) nPemusatkan perhatian pada peranan usaha
menguasai ideide dan identitas-identitas baru dalam membentuk gerakan-gerakan sosial. Hal
itu mencerminkan kemunculan "gerakan kultural" dalam ilmu sosial. Para organisator
gerakan melakukan mobilisasi dengan jalan melukiskan isu-isu untuk para calon peserta
gerakan dengan cara yang memberikan makna bagi mereka. Ancaman-ancaman yang
dianggap berasal dari kelompok-kelompok etnis atau agama dari luar, misalnya, adalah
piranti-pirantiIi-amingutama dalam kekerasan komunal di Indonesia. Yang terkait
denganIramingini adalah gagasan dramaturgis tentang repertoires of action. Gagasan ini
dibawa masuk ke dalam `nasi camput teoretis' ini untuk mengisyaratkan bahwa aksi-aksi
yang dijalankan oleh gerakan-gerakan itu, misalnya demonstrasi, menjelek-jelekkan pihak
lawan dan pembersihan etnis, sebaiknya dipandang sebagai sandiwara, yang bertujuan untuk
memberikan kesan kuat baik pada lawan maupun peserta gerakangerakan itu sendiri. Semua
ide itu, yang datang dari berbagai tradisi teoretis yang berlainan, dibaurkan dalam sebuah
bunga rampai yang berjudul Comparative perspectives on social movements (McAdam,
McCarthy dan Zald 1996). Tidak semua orang puas bahwa ini adalah sebuah "sintesis"
teoretis dan bukan sekadar gado-gado dari berbagai teknik yang berlainan, tetapi sebagian
besar dari mereka tetap memandang buku ini sebagai sebuah titik tumpu penting. Sebagian
besar dari buku ini memang terasa menjanjikan untuk masalah kekerasan komunal di
Indonesia. Yang saya ingin lakukan adalah membawa gerakan-gerakan non-institusional dan
kadang-kadang diwarnai kekerasan ini ke dalam bidang politik normal.
Meskipun begitu, dalam hal-hal lain teori itu rupanya tidak cocok dengan masalah-
masalah dalam buku ini. Sebagian dari penelitian yang menghasilkan teori gerakan sosial
baru diIokuskan pada gerakan-gerakan emansipatoris di dunia Barat yang serba berlimpah
itu, yang memperjuangkan kesetaraan ras atau gender, penyelamatan lingkungan hidup,
dunia bebas-nuklir, dan sebagainya. Tujuan inti dari teori ini adalah untuk menjelaskan
mengapa para demonstrator muda di Amerika Utara dan Eropa Barat pada tahun 1960-an
sama sekali tidak berkesan sakit melainkan sangat politis. Protes oleh orangorang yang
terpinggirkan ada di pusat kisah itu, tetapi salah sate Iaktor pembatas yang penting adalah
bahwa gerakan-gerakan ini semua beroperasi di ruang yang demokratis, yang mencakup
peranan terke'muka dan eIektiI daripada media massa dan peranan institusi-institusi negara
yang mengurusi legislasi, keadilan dan keamanan. Hanya sedikit dari asumsi-asumsi itu
yang bisa diterapkan untuk Indonesia. Gerakan-gerakan yang akan kita simak lebih bersiIat
chauvinistis daripada emansipatoris. Orang-orang seringkali berpartisipasi dalam gerakan-
gerakan itu ketika dicengkam suatu kepanikan moral. Protes-protes mereka bukannya secara
langsung diarahkan pada pemerintah, melainkan pada kelompok-kelompok lain dalam
komunitas lokal, meskipun secara tidak langsung serangan-serangan itu dimaksudkan untuk
membuktikan kekuatan dan dengan demikian membangun klaim-klaim atas negara lokal.
Arus inIormasi terutama bersiIat lisankasak-kusuk memainkan peranan besardan bukan
lewat media massa. Hubungan-hubungan patron-client, yang nyaris tidak dipahami di dunia
Barat, mendominasi lanskap sosial di daerah-daerah luar Jawa di mana kekerasan terjadi.
Organisasi-organisasi yang berdiri di belakang kekerasan komunal itu tidak menyerupai
"organisaiorganisasi gerakan sosial" yang businesslike dan yang bertindak di pasar bebas
gerakan-gerakan, seperti yang begitu disenangi oleh beberapa teoris gerakan sosial. Di
Indonesia organisasi tersebut adalah "Iorum-Iorum" dan "front-front" yang bersiIat
oportunistis dan transitoris, meskipun mereka sering secara rahasia terkait dengan institusi-
institusi yang lebih permanen. Selain itu, mereka merebak dalam suasana perpecahan
mungkin bukan perpecahan hubungan-hubungan sosial, tetapi yang jelas perpecahan negara.
Tidak satupun dari institusi-institusi negara bekerja dengan baik, apalagi institusi-institusi
yang demokratis. Kekhawatiran-kekhawatiran mengenai keselamatan menjadi keprihatinan
utama dalam pikiran para peserta gerakan. Barangkali literatur mengenai social strain
mempunyai sesuatu yang bisa disumbangkan di sini. Teori ini pada mulanya dirancang
untuk menjelaskan mengapa orang-orang Nazi dan Stalin is mampu memobilisasi massa
begitu besar untuk mendukung sebuah agenda yang nyaris tidak sesuai dengan kepentingan-
kepentingan jangka-panjang anggota masyarakat biasa. Jawabannya ada pada ketakutan-
ketakutan dan Irustrasi, bukan pada politik rasional. Masalah teoretis ini, antara teori social
strain dan teori gerakan sosial, adalah masalah yang pelik, dan tidak mungkin kita pecahkan
di sini. Kita akan kembali ke masalah ini di berbagai waktu dalam bab-bab berikut, misalnya
ketika kita membahas apa yang disebut dilema keamanan (bab 6). Untuk sekarang ini
cukuplah dikatakan bahwa dalam pandangan saya, bahkan di tengah-tengah krisis-krisis
keamanan seperti itu, banyak orang masih menjalankan politik sebagaimana biasa,
meskipun dalam mode krisis dan yang di Barat jelas dianggap abnormal. Krisiskrisis seperti
itu menjadi bagian dari sebuah permainan kejam setan yang seringkali dimainkan di negeri-
negeri di mana negara institusional lemah. Dengan kata lain, pelajarannya adalah bahwa
semangat dalam mana para teoris gerakan sosial bekerja tetap bisa diterapkan, meskipun
dalam beberapa aspek kita membutuhkan sebuah kerangka teori baru.
Titik tumpu kedua dalam sejarah penelitian gerakan sosial itu membuka kemungkinan-
kemungkinan untuk mengatasi masalah-masalah ini, dan itu ditulis oleh beberapa dari
individu-individu yang sama. Dynamics ofcontention (DoC) (McAdam, Tarrow dan Tilly
2001) memperluas Ienomena yang ingin dijelaskan sampai keluar dari gerakan-gerakan
sosial sehingga juga mencakup konIlik industrial, nasionalisme, revolusi-revolusi, dan
demokratisasi. Kesemuanya dikelompokkan di bawah label "contentious politics.", yang
mungkin dapat diterjemahkan "politik seteru". Kelimabelas studi kasus dalam buku ini
mencakup beberapa perseteruan non-Barat (misalnya proses-proses Tienanmen 1989),
perseteruan non-demokratis (huru-hara Hindu-Muslim di India), maupun gerakan-gerakan
di bawah kondisi-kondisi negara yang lemah (Pemberontakan Mau Mau di Kenya). Untuk
memahami Ienomena yang berbeda ragam sampai begitu jauh itu hanya dengan satu
perangkat alat adalah proyek penelitian yang benar-benar berani dan menarik. Hal itu
langsung mendatangkan pujian terhadap DoC sebagai "tak pelak lagi buku paling ambisius
dan jelas paling penting mengenai gerakan-gerakan sosial (dan Ienomena-Ienomena yang
terkait) yang ditulis dalam dua dekade terakhir ini" (Tindall 2003).
Bukan hanya cakupannya, tetapi juga pendekatan DoC bergerak keluar dari
Comparative perspectives on social movements. Banyak bagian dari DoC menyangkut apa
yang disebut "transgressive contention," yaitu perseteruan yang terjadi di luar batas-batas
politik Iormal dan bisa mencakup protes-protes yang diwarnai kekerasan. DoC dengan tepat
menganggap bahwa literatur terdahulu dalam bidang ini terlalu statis, cocok untuk
memahami siklus hidup dari sebuah aktor organisasional tunggal tetapi tidak untuk
memahami dinamika yang lebih luas di mana banyak aktor berinteraksi dengan satu sama
lain. Sekarang proses (dengan mengandalkan teori proses politik), dan bukan struktur,
menjadi pemikiran kunci. Tujuannya adalah untuk mengidentiIikasi sejumlah kecil
perangkat mekanisme-mekanisme dan proses-proses dasar yang terjadi secara berulang-
ulang dalam aneka macam setting yang berlainan. Mekanisme dideIinisikan sebagai sebuah
kejadian yang mengubah hubunganhubungan di antara elemen-elemen tertentu dan cara-cara
serupa (McAdam, Tarrow dan Tilly 2001:25). Sebagian besar mekanisme dalam DoC
bersiIat relasional (yakni menyangkut hubungan), meskipun beberapa bersiIat
environmental (menyangkut lingkungan) dan yang lain kognitiI (menyangkut kesadaran).
Sebuah contoh sentral tentang mekanisme relasional adalah brokerage, di mana dua unit
sosial dibawa memasuki sesuatu hubungan dengan satu sama lain oleh unit ketiga. Lebih
jauh lagi, proses adalah serangkaian mekanisme-mekanisme yang lebih elemental. Proses
tidak sama dengan sebuah hukum universal. Sebuah proses bisa berakibat banyak hasil yang
berlainan. Dalam rangka bereksperimen, dan tanpa berpura-pura komprehensiI, DoC
mengemukakan lima proses kunci dalam contentious politics. Kelima proses itu adalah:
O Identity Iormation (pembentukan identitas)Bagaimana sesuatu identitas bersama
berkembang dalarri sebuah kelompok?
O Scale shiIt (atau escalation) eskalasi) Bagaimana sebuah konIlik yang muncul
kecil mengalami eskalasi sehingga melibatkan aktor-aktor yang jauh lebih banyak?
O Polarization (Polarisasi)Bagaimana ruang politis antara pihak-pihak yang saling
berseteru meluas ketika para peserta itu saling menjauh dan bergeser ke arah titik-
titik ekstrim?
O Mobilization (Mobilisasi) Bagaimana orang yang biasanya bersikap acuh-tak
acuh dapat digerakkan untuk terjun ke jalan?
O Actor constitution (pembentukan aktor) Bagaimana sebuah kelompok yang
sebelumnya tidak terorganisir atau apolitis berubah menjadi sebuah aktor politik
tunggal?
Dynamics of contention mengundang banyak kritik. Jumlah mekanisme dan prosesnya
terlalu banyakseorang penulis menghitung ada 44 jumlahnya jauh dari 'sejumlah kecil'.
Selain itu, proses serta mekanisme yang diusulkan bersiIat terlalu kompleks untuk bisa
mereduksi Ienomena kehidupan nyata ke tingkat-tingkat yang lebih konkrit. Hasilnya adalah
seperangkat konsep yang sudah mengarah ke sebuah hukum umum, tetapi belum cukup
memiliki kejelasan sehingga bisa menumbuhkan harapan nyata untuk mewujudkan hukum
umum tersebut (Barker 2003; Tindall 2003). Kritikus yang lain-lain menemukan bias
strukturalis yang sangat mendalam, dan hal itu membuat teori ini mustahil memberikan
perhitungan yang benar mengenai kebebasan seorang agen untuk bertindak, mengingat teori
itu mengabaikan kebudayaan dan emosi-emosi (Jaspers 2004; Platt 2004). Kritik-kritik itu
dan kritik-kritik yang lain tak pelak lagi menyodorkan masalah-masalah penting. Tetapi,
penulis mereka tidak menyodorkan piranti-piranti yang sama-sama komprehensiI untuk
menggantikan DoC. Untuk saat ini, DoC adalah seperangkat alat paling maju yang kita
miliki mengenai Ienomena-Ienomena yang menjadi pusat perhatian buku ini.
Untuk tujuan-tujuan saya sendiri, DoC menyodorkan kategori-kategori yang sangat
bermanIaat untuk menganalisis kejadian-kejadian itu di tingkat generalitas yang bisa
dicapai. Saya menginginkan sebuah pendekatan yang tetap dekat dengan cerita kejadiannya.
Tetapi saya tidak ingin sekadar mempertebal tumpukan kertas-kerta laporan penelitian yang
secara tak kritis mengiangkan kembali kisah-kisah jurnalistis, seakan-akan kejadian-
kejadian itu begitu unik sehingga tidak memiliki keberaturan yang mendasar.
Tujuan dalam buku ini bukanlah untuk memberikan pembahasan yang komprehensiI
mengenai setiap episode. Satu buku kecil seperti ini tidak akan memadai untuk itu. Banyak
detail sudah tersedia dalam laporan-laporan mengenai episode-episode individual, dan lebih
banyak lagi sedang ditulis. Lebih tepat lagi, tujuannya adalah untuk memahami dinamika
kejadiankejadian terbesar dalam sebuah kelas konIlik yang belum pernah disaksikan di
Indonesia selama beberapa dekade. Saya memutuskan untuk menulis masingmasing episode
melalui lensa salah satu proses saja. Ada episode-episode di lima tempat di Indonesia, dan
kebetulan jumlah proses yang disajikan dalam DoC juga lima. Kenyataannya semua proses
itueskalasi, polarisasi, mobilisasi, dan sebagainyatidak diragukan lagi diketemukan
dalam setiap konIlik. Tetapi mereka sering melibatkan mekanisme-mekanisme elemental
yang sama, dan adalah tidak perlu meneliti mereka semua untuk memahami sesuatu yang
penting mengenai sesuatu episode tertentu. Pilihan untuk menghubungkan sebuah episode
Indonesia dengan sebuah proses teoretis adalah arbitrer (acak). Tidak ada indikasi, misalnya,
bahwa Ambon adalah contoh mobilisasi yang lebih kuat daripada Poso. Begitu pula bab-bab
di sini tidak harus dibaca sebagai sebuah buku resep yang akan berhasil di mana saja. Lebih
tepat lagi, saya berharap secara heuristik untuk membangun sebuah visi yang lebih umum
mengenai bagaimana konIlik komunal pasca-Orde Baru terjadi, dengan cara mengkaji
masing-masing episode secara berdisiplin, dengan menggunakan lensa sebuah proses.
Masing-masing akan menyumbang pada keseluruhan tujuan, yaitu untuk memahami
dinamika sosial dan politis yang mendorong munculnya pola contentious politics tertentu
seperti yang kita saksikan di beberapa tempat di Indonesia.
Sekarang ada beberapa komentar mengenai layout buku ini. Dua bab berikutnya adalah
mengenai konteks. Mereka menyiapkan latar bagi pembahasan terperinci mengenai
naratiInya. Bab 2 dimulai dengan konteks temporal mengapa kekerasan terjadi pada saat
itu? Bab ini mensurvei aneka proses perubahan sosial yang memuncak pada tahun 1998.
Semuanya telah dikutip oleh para peneliti dari berbagai disiplin yang berlainan sebagai
bahan penting untuk memahami kekerasan komunal. Bab ini mempunyai tujuan Banda,
yaitu memperkenalkan perkembangan-perkembangan latar belakang dan secara kritis
mengulas beberapa literatur dasar mengenai kekerasan kolektiIpasca-Orde Baru di
Indonesia. Bab sesudah itu (3) membahas konteks geograIis mengapa kekerasan terjadi di
tempat-tempat itu dan bukan di tempat yang lain? Ini secara langsung mengarah pada situs
sosial tipikal dari kekerasan komunal pasca-Orde Baru, yang sudah dijanjikan dalam judul
buku ini, yaitu kota-kota kecil di luar Jawa. Metode yang dipakai di sini terus terang bersiIat
strukturalis. Metode ini juga cukup iris, dalam arti pembahasan ini ingin menunjukkan
bahwa kita hanya membutuhkan dua Iaktor untuk mengidentiIikasikan tempat-tempat yang
rawan terhadap kekerasan komunal urbanisasi cepat (dari basis yang rendah), dan
ketergantungan besar pada sektor negara. Bab ini kemudian membahas negara macam apa
yang bisa mendatangkan kekerasan seperti itu di saat-saat puncak instabilitas. Nadanya
berbeda tajam dari pendekatan contentious politics yang lebih dinamis di bagian lain buku
ini. Bab ini tidak mengklaim untuk menjelaskan segala sesuatu, tetapi saya berharap bab ini
akan menjelaskan beberapa hal dan akan membantu menyiapkan panggung bagi bab-bab
berikutnya yang lebih berorientasi pada proses.
Setelah itu, lima bab (4-8) menceritakan dengan agak rinci apa yang terjadi selama
episode-episode konIlik di tiap-tiap tempat itu. Bab-bab itu secara umum disajikan secara
kronologis sejak tanggal permulaan konIlik. Ini agak arbitrer, karena episode-episode terjadi
dalam Iase-Iase dengan intensitas yang berlainan dan paralel dengan satu sama lain.
Kalimantan Barat, misalnya, mempunyai dua episode tetapi dibahas hanya dalam satu bab
yang diatur oleh episode yang pertama. Secara kronologis ini adalah yang pertama. Fase
pertama dalam episode Poso (Sulawesi Tengah), yang digunakan untuk menempatkan Poso
ke tempat kedua dalam susunan kronologis, sebenarnya cukup kecil dibandingkan dengan
Ease keduanya, yang terjadi ketika pertempuran sudah berlangsung di tempat ketika,
Ambon. Bab pertama mengenai proses-proses kekerasan (4) membahas pembentukan
identitas (di Kalimantan Barat). Ini adalah masalah yang kompleks dan sulit tetapi
ditempatkan di sini karena identitas adalah Iundamental bagi bab-bab berikutnya. Masing-
masing bab ini mengajukan pertanyaan lain. Bagaimana sebuah konIlik bereskalasi dari
pertengkaran lingkungan tetangga menjadi sebuah masalah internasional, yang melibatkan
lebih banyak orang (bab 5, mengenai Poso)? Bagaimana orang-orang yang biasanya apatis
berkembang menjadi terlibat (bab 6, mengenai Ambon)? Bagaimana orang-orang yang
biasanya bekerja sama lalu terpecah-belah menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan (bab
7, tentang Maluku Utara)? Bagaimana seorang aktor kolektiI dilahirkan (bab 8, mengenai
Kalimantan Tengah)? Adalah usaha yang berat untuk mencoba menjawab semua pertanyaan
yang berlainan (meskipun masih terkait) itu untuk setiap episode. Masing-masing menuntut
pendekatan analitis yang sedikit beda, yang ditempatkan di tingkat menengah dalam
penjelasannya. Secara cermat menciptakan kembali sebuah proses tingkat menengah dengan
cara ini akan memberi kita kepuasan karena kita telah membuat sebuah episode bisa
dipahami tanpa harus mempersalahkan sesuatu karakteristik yang unik dari tempat dan
waktu yang bersangkutan. Bab terakhir (9) menyatukan kesimpulan-kesimpulan mengenai
hubungan antara episode-episode kekerasan di lima tempat itu dengan demokratisasi pasca-
Orde Baru, dan menunjuk pada beberapa dari implikasi-implikasi terpenting bagi para
aktivis demokrasi Indonesia.
Sehubungan dengan sumber-sumber, tujuan asli saya adalah untuk menggunakan
laporan-laporan khusus yang sudah ada mengenai masingmasing episode untuk
membangun sebuah gambaran yang lebih umum dan komparatiI mengenai konIlik-konIlik
komunal Indonesia pasca-Orde Baru. Itu ternyata lebih sulit daripada yang saya duga
semula. Di beberapa tempat seperti Kalimantan Tengah sedikit sekali penelitian ilmiah
yang sudah dilakukan. Di daerah-daerah lain para spesialis melakukan penelitian yang
cukup mengesankan. Namun setiap kali saya mengunjungi daerah itu, saya mendapatkan
hal-hal baru yang tidak ada dalam laporan-laporan penelitian. Kadang-kadang itu hanya
berupa inIormasi sebuah database elektronik berisi kliping-kliping berita yang telah saya
kumpulkan ternyata membuahkan detail-detail baru. Yang lebih sering terjadi adalah
mendekati sesuatu masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Orang-orang yang
saya temui kebanyakan kelas menengahselama kunjungan-kunjungan pendek itu para
cendekiawan, wartawan, birokrat, politikus, aktivis dan para pengkhotbahjuga memandang
berbagai hal secara lain dari para petani dan pelaku huruhara yang bertemu dengan
pengamat-pengamat lain. Jelaslah, saya tidak bias menipu diri saya sendiri dengan ambisi-
ambisi mencapai sesuatu yang komplit, dan tak pelak lagi saya cukup keliru dalam
beberapa dari interpretasi-interpretasi yang disodorkan di sini. Masih banyak penelitian
yang harus dilakukan.
Terakhir, sebuah catatan mengenai soal istilah. Subjudul buku ini menggunakan istilah
"komunal" yang berarti baik "etnis" maupun "religius." KonIlik kekerasan terjadi melewati
batas-batas kedua jenis solidaritas di Indonesia pada waktu itu. Yang satu sering mengalir
memasuki yang lain, sebagaimana akan ditunjukkan oleh pembahasan buku ini nanti, dan
kekerasan etnis serta religius mempunyai banyak dinamika serupa. Memang, solidaritas-
solidaritas etnis, yaitu ikatan yang terkait dengan tempat asal-usul dan bukan keyakinan-
keyakinan keagamaankurang begitu terlembagakan daripada solidaritas-solidaritas
keagamaan di negeri ini. Juga betul bahwa secara teoretis orang bisa memilih agamanya
sendiri tetapi tidak bisa memilih etnisitasnya. Tetapi perbedaan-perbedaan itu seyogyanya
tidak dibesar-besarkan. Dalam praktik, orang-orang jarang memilih agama mereka,
sementara mereka kadangkadang diketahui memilih sesuatu etnisitas baru, bahkan etnisitas-
etnisitas baru diciptakan sepanjang masa. Mengapa mesti ada konIlik komunal dari jenis
etnis yang lebih besar di Kalimantan, dan dari jenis religius di daerah timurnya, tetap
merupakan sebuah misteri bagi saya, selain hanya bisa mengakui bahwa masing-masing
pola muncul dari sebuah sejarah panjang aktivitas organisasional. Pikiran orang-orang Barat
telah diajar oleh sejarah mutakhir di Balkan dan AIrika untuk menganggap politik identitas
internal yang diwarnai kekerasan sebagai "etnis." Karena itu beberapa penulis lebih suka
memperluas istilah "etnis" sehingga mencakup baik tempat asal-usul maupun agama
(Bertrand 2004:9; Horowitz 1985: 41, 53). Tetapi di Indonesia ada wacana-wacana yang
terpisah dan sudah dewasa mengenai etnisitas dan agama. tnis adalah ekuivalen umum
untuk istilah yang lebih tua, yaitu kesukuan (tribalisme), yang dari dulu dianggap sama
berbahayanya bagi integrasi nasional. Sebaliknya, agama dipandang sebagai sebuah hal
sosial yang positiI, asalkan agama dipraktekkan dengan menghormati orang-orang lain.
Akan membingungkan jika menempatkan agama sebagai bagian dari etnisitas. Namun
peranan-peranan politis yang dimainkan oleh kedua hal itu jelas mempunyai banyak
kesamaan. Istilah "komunal," yang digunakan untuk pertama kalinya di India, memecahkan
masalah ini dengan jalan
memperkenalkan sebuah istilah baru untuk mencakup kedua tipe politik identitas tersebut.
Dua istilah lain yang umum digunakan di Indonesia untuk menggambarkan tipe
kekerasan yang dibahas dalam buku ini adalah "primordial" dan "horizontal." Pada hemat
saya kedua istilah itu menyodorkan lebih banyak masalah daripada istilah "komunal." Yang
pertama seringkali dilacak sampai pada sebuah bab dalam buku Geertz (1963) yang ditulis
lebih dari 40 tahun yang lalu, yang asumsi dasarnya sekarang dianggap tidak memadai lagi.
Sekarang ini "primordialisme" menjadi istilah yang terlalu sering disalahgunakan oleh para
ilmuwan sosial untuk pandangan-pandangan yang merengkuh identitas-identitas etnis dan
religius sebagai instinktual dan tak tergambarkan, padahal dalam realitanya mereka itu
"dibangun," bisa dirundingkan, dan terbuka bagi penalaran. Sementara itu, gagasan tentang
kekerasan "horizontal" tidak diIokuskan pada identitas, melainkan pada ketiadaan negara
dalam pertarungan seperti ini, kontras dengan kekerasan "vertikal" seperti separatisme.
Jelaslah negara sama sekali tidak absen dalam kekerasan yang digambarkan dalam buku ini,
karena itu istilah "horizontal" itu tidak cocok. Bahkan hal itu bisa dipandang sebagai usaha
para wakil negara untuk mengaburkan kehadiran negara dalam kekerasan ini dan untuk
hanya mengkambinghitamkan "rakyat." Sebenarnya istilah "komunal" mempunyai kerugian
yang serupa, karena istilah itu dulu digunakan oleh penjajah Inggris untuk menenggarai
ketidakhadiran yang sama (Freitag 1989). Dengan Tatar belakang itu kita masih belum
memiliki istilah yang cocok untuk kekerasan jenis ini. Tetapi rasanya lebih mudah
menjernihkan istilah "komunal" dari kesalahpahaman semacam itu dibanding istilah
"horizontal", sebab kata "horizontal" mengandung makna yang salah di dalam semantiknya
sendiri.
You might also like
- BKI, Tahun 1961Document1 pageBKI, Tahun 1961La RamanNo ratings yet
- Sumber Nieuw-GuineaDocument1 pageSumber Nieuw-GuineaLa RamanNo ratings yet
- Pertanian Dan PeternakanDocument1 pagePertanian Dan PeternakanLa RamanNo ratings yet
- Muskatnus JermanDocument1 pageMuskatnus JermanLa RamanNo ratings yet
- Hati Nurani Masyarakat Dalam Pola Pemilikan Tanah Di MKWDocument1 pageHati Nurani Masyarakat Dalam Pola Pemilikan Tanah Di MKWLa RamanNo ratings yet
- Werkplan Nieuw Guinea 1954-1956Document2 pagesWerkplan Nieuw Guinea 1954-1956La RamanNo ratings yet
- SUMBER NIEUW - GUINEA. 4Document1 pageSUMBER NIEUW - GUINEA. 4La RamanNo ratings yet
- Silabus Mata Kuliah Sejarah Australia Dan OceaniaDocument5 pagesSilabus Mata Kuliah Sejarah Australia Dan OceaniaLa RamanNo ratings yet
- Arsip Agraria 1Document1 pageArsip Agraria 1La RamanNo ratings yet
- Silabus Mata Kuliah Kapita Selekta Sejarah IndonesiaDocument3 pagesSilabus Mata Kuliah Kapita Selekta Sejarah IndonesiaLa RamanNo ratings yet
- Silabus Mata Kuliah Sejarah Australia Dan OceaniaDocument7 pagesSilabus Mata Kuliah Sejarah Australia Dan OceaniaLa RamanNo ratings yet
- Silabus Mata Kuliah Sejarah Australia Dan OceaniaDocument7 pagesSilabus Mata Kuliah Sejarah Australia Dan OceaniaLa RamanNo ratings yet
- George MillerDocument1 pageGeorge MillerLa RamanNo ratings yet
- SILABUS MATA KULIAH SEJARAH INDONESIA SD 1500Document4 pagesSILABUS MATA KULIAH SEJARAH INDONESIA SD 1500La RamanNo ratings yet
- Format Laporan Pengembangan DiriDocument6 pagesFormat Laporan Pengembangan DiriLa RamanNo ratings yet
- Model Dan Contoh Pengembangan Diri Sekolah Dasar Pusat KurikulumDocument4 pagesModel Dan Contoh Pengembangan Diri Sekolah Dasar Pusat KurikulumLa RamanNo ratings yet
- Laporan Pengembangan Diri BerkelanjutanDocument6 pagesLaporan Pengembangan Diri BerkelanjutanLa RamanNo ratings yet
- Kapita Selekta Sejarah DuniaDocument7 pagesKapita Selekta Sejarah DuniaInsanNo ratings yet
- Sejarah Maritim IndonesiaDocument362 pagesSejarah Maritim IndonesiaLa RamanNo ratings yet
- Pengembangan DiriDocument23 pagesPengembangan DiriLa RamanNo ratings yet
- Commonwealth of AustraliaDocument6 pagesCommonwealth of AustraliaLa RamanNo ratings yet
- RPS Pendidikan MultikulturalDocument10 pagesRPS Pendidikan MultikulturalLa Raman100% (2)
- Materi Mata Kuliah Filsafat Sejarah ADocument28 pagesMateri Mata Kuliah Filsafat Sejarah ALa RamanNo ratings yet
- Dinasti TangDocument14 pagesDinasti TangLa RamanNo ratings yet
- Sejarah AmbonDocument13 pagesSejarah AmbonLa RamanNo ratings yet
- Makassar Kekuatan Maritim Pada Periode Akhir KolonialDocument29 pagesMakassar Kekuatan Maritim Pada Periode Akhir KolonialLa RamanNo ratings yet
- Jurnal ManDocument6 pagesJurnal ManLa RamanNo ratings yet
- ProposalDocument17 pagesProposalLa RamanNo ratings yet
- Silabus Mata Kuliah Sejarah IntelektualDocument1 pageSilabus Mata Kuliah Sejarah IntelektualLa RamanNo ratings yet
- Rumphius Dan ValentynDocument2 pagesRumphius Dan ValentynLa RamanNo ratings yet