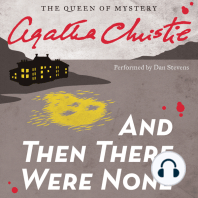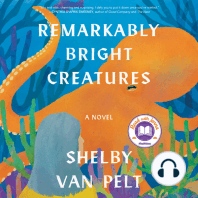Professional Documents
Culture Documents
Hutan Desa
Uploaded by
Ranung Mario KalesuCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Hutan Desa
Uploaded by
Ranung Mario KalesuCopyright:
Available Formats
Hutan Desa: Wujud implementasi desentralisasi kebijakan pengelolaan hutan Oleh : Gladi Hardiyanto Indonesia Tanah Airku, Tanahku
Sewa, Airku Beli Wajah kebijakan
pengelolaan sumberdaya alam kita masih silang-sengkarut. Tarik menarik kepentingan antara negara- tentu saja didukung kekuatan korporasi besar- dan rakyat dipihak yang dilemahkan masih terus berlangsung. Hegemoni negara masih mewujud dalam berbagai aturan kebijakan yang state based, sentralistik, sektoral, eksploitatif. Perubahan paradigma yang digelindingkan banyak pihak menjadi pengelolaan berbasis masyarakat, desentralisasi, local specifik, lebih banyak menjadi tumpukan dokumen saja. Tengoklah berbagai perundangan sektoral seperti kehutanan, pertambangan, dan air disamping masih sentralistik juga kentara sekali berpihak pada pemodal besar. Kasus yang masih hangat diperdebatkan adalah desakan pengusaha tambang untuk mengamandemen Undang-undang kehutanan No. 41/1999 yang melarang pertambangan terbuka di areal hutan lindung. Kasus lainnya adalah molornya pengesahaan RUU Sumberdaya air karena ada klausul tentang privatisasi sumberdaya air, yang memungkinkan para pengusaha menguasai sumber daya air yang mestinya sebagai barang publik. Ujung-ujungnyanya rakyat juga yang akan menanggung semua deritanya. Ketika hutan semakin rusak akibat over eksploitasi dan konversinya menjadi berbagai areal transmigrasi, perkebunan, bahkan pertambangan, maka rakyat sekitar hutanlah yang paling dulu mengalami dampak ekologis maupun sosialnya. Ketika benar nanti sumber daya air diprivatisasi dan rakyat harus beli maka genaplah sudah penderitaannya. Semestinya pemerintah sebagai salah satu representasi negara mampu melindungi eksistensi dan kelestarian SDA . Bukan malah mengobral dengan harga murah, tidak mau susah sekedar ingin mendapatkan fee dan pajak hasil. Tragedi sumberdaya yang diramalkan Hardin di Afrika, cepat atau lambat-atau bahkan sudah- terjadi di negeri ini. Berbagai fenomena alam seperti perubahan musim, bencana alam, diakui atau tidak adalah akibat terdegradasinya sumber-sumber daya alam akibat salah urus dan kelola kita juga. Tulisan ini akan mencoba melihat adakah peluang masyarakat mengelola sumberdaya alam, khususnya hutan, dan sejauh mana dukungan, terutama kebijakan serta sudah adakah partisipasi rakyat pada implementasinya. Model yang ingin didiskusikan adalah pengelolaan Hutan Desa sebagai satu alternatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat terutama dalam kaitanya dengan wacana otonomi daerah, khususnya otonomi desa. Kebijakan Pengelolaan sumberdaya hutan; Dari negara pada negara.. Bersamaan dengan dimulainya era orde baru, pada tahun 1967 lahir Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5/1967 sebagai unifikasi hukum nasional kehutanan. Undang-undang ini lahir dengan semangat bagaimana dalam jangka pendek mampu 1 Disampaikan pada diskusi Analisis Kebijakan yang mendorong percepatan tata perekonomian desa di LAPPERA, 8 September 2003. 2 Staf Yayasan Damar (www.damar.or.id; damaryogya@ygy.centrin.net.idThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ) 3 Salah satu spanduk yang dipasang penduduk Jakarta Utara untuk memperingati Hari
Kemerdekaan RI ke-58 1 mengumpulkan pendapatan bagi negara. Terlihat sekali dari diabaikannya UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang tidak dijadikan konsideran dalam penyusunannya. Kebijakan ini disusun dengan dibukanya kran pemodal besar, terutama asing untuk turut serta mengeksploitasi SDA. Sampai tahun 1999, berbagai kebijakan yang menyertainya pun silih berganti, tetapi tidak mengubah paradigma state based dan eksploitasi. Sulaiman Sembiring (2002)4, mencatat 14 karakteristik-negatif- yang terdapat kebijakan kehutanan-khususnya UU No 5/1967- sebelum tahun 1999, yaitu (1) Hak Menguasai Pemerintah Pusat (bukan negara), (2) Sentralistik, (3) Sektoral, (4) eksploitatif, (5) Skala Besar-masif, misalnya pembangunan HPH & HTI-pen-, (6) Monopoli dan oligopoli, (7) Tidak ada transparansi, (8) tidak ada pelibatan masyarakat/publik, (9) tidak ada pertanggunggutan, (10) militeristik/kekerasan, (11) penyeragaman, (12) tidak ada pengakuan atas hak adat- ada pasal yang membekukan hak adat jika bertentangan dengan kepentingan umum-pen-, (13) tidak ada supremasi hukum tidak ada sanksi pidana dalam UU itu-, (14) tidak ada mekanisme resolusi konflik. Karakteristik diatas tidak terlepas dari kuatnya rejim yang berkuasa saat itu, yang memang mendewakan stabilitas politik dan peningkatan ekonomi pendukungnya. Meskipun sejak tahun 1999 sudah ditetapkan UU No. 22 tentang Pemerintah Daerah dan juga UU kehutanan baru-UU No. 41/1999-, tetapi beberapa semangat dan karakteristik diatas masih sangat kentara dan belum ada perubahan. Sentralisasi perijinan di tangan menteri, tidak ada klausul dalam batang tubuh yang mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat adalah beberapa contoh bahwa sejak reformasi pun belum ada perubahan yang siginifikan pada substansi kebijakan pengelolaan hutan dan SDA umumnya. Beberapa kebijakan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat, seperti Hutan Kemasyarakatan, Pembangunan Masyarakat Desa Hutan, Perhutanan Sosial (Social Forestry), belum menjadi mainstream perubahan di pengambil kebijakan. Yang pasti kebijakan tersebut lebih menjadi kebijakan populis menteri. Ketika terjadi pergantian menteri dan perubahan keorganisasi departemen maka kebijakan tersebut pun ikut muncul dan tenggelam. Kasus Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang sejak tahun 1995 sudah 5 kali terjadi pergantian SK Menteri (dari SK Menhut No. 622/1995 SK Menhut No. 31/2001), menjadi contoh bahwa kebijakan2 yang mengatasnamakan rakyat masih pada dataran populis guna mencari dukungan massa politik belaka. Sekarang ketika berganti menteri pun Hutan Kemasyarakatan (HKm), berubah nama menjadi Social Forestry meskipun secara substansi juga setali tiga uang dengan HKm. Di level Undang-undang, diakui banyak pihak terdapat beberapa kontradiksi dalam undangundang No.22/1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Kehutanan. Semangat otonomi daerahbahkan secara implisit sampai desa-, dimana daerah Kabupaten mampu mengelola wilayahnya sendiri, termasuk kawasan hutannya, tidak terjadi pada Undang-undang Kehutanan, dimana perijinan masih dominan berada di tangan Menteri. Dibanyak daerah-termasuk Yogyakarta- tarik ulur kewenangan pengelolaan sumberdaya alam-khususnya hutan- masih terjadi. Di Yogyakarta sendiri, provinsi masih berpegang mengelola hutan negara, dan kabupaten hanya mengurus hutan rakyat. Padahal kondisi hutan negara di Kabupaten di Yogyakarta pada umumnya kritis dan butuh penanganan rehabilitasi secara cepat. Kasus Kabupaten Kulon Progo yang Bupatinya sudah berani menerbitkan ijin sementara HKm pada kelompok tani dan kasus Pemda Sleman yang meminta pengelolaan kawasan wisata Kaliurang menjadi contoh tarik menarik kewenangan kebijakan di Yogyakarta 4 Sulaiman Sembiring :Otonomi, Hukum, dan Orientasi Kebijakan Kehutanan Nasional, presentasi pada Dialog Membedah Carut Marut Kebijakan Kehutanan yang diadakan oleh LEMFKT UGM dan Yayasan Damar, 30 Juli 2003
2 Sebenarnya tanpa tergantung pemerintah pun pada dasarnya rakyat telah mempunyai bentuk dan model pengelolaan SDA sendiri. Bentuk dan model pengelolaan hutan adat, Hutan Kampung, Simpunk (di Kalimantan), Parak (sebagai salah satu aset nagari di Sumbar), Repong Damar, Hutan Pekon, Hutan Desa, dan lain-lain, sudah eksis dan sebagai sumber penghidupan dan perekonomian lokal. Berbagai model pengelolaan hutan oleh masyarakat tersebut, disamping berbasis individu juga kental dengan semangat komunalisme, karena merupakan aset wilayah desa, kampung, atau nagari. Aset-aset tersebut jika dicermati adalah sebagai sumber kekayaan desa yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembaharuan desa dan masyarakatnya. Idealita Hutan Desa : Apa itu hutan desa? Desa sejak dahulu tidak sekedar dipahami sebagai pemerintahan desa, tetapi seperti negara juga mencakup wilayah, masyarakat/rakyat dan juga pengakuan dari luar-dalam hal ini bisa negara-. Desa biasanya mempunyai wewengkon atau wilayah pangkuan desa yang dikelola baik sebagai sumber pendapatan ekonomi, konservasi maupun kedaulatan desa. Wewengkon itu bisa berwujud hutan dan atau tanah desa-atau sering disebut tanah ulayat atau tanah adat di luar Jawa-.Tanah desa sendiri sekarang terdiri bermacam2 seperti tanah bengkok, titi sara, tanah kas desa yang seringkali juga berwujud hutan atau kebun. Kemudian karena kondisi sosial politik negara yang kemudian menetapkan semua wilayah hutan yang secara formal tidak dibebani hak milik menjadi kawasan hutan negara, mengakibatkan wilayah pangkuan desa pun secara otomatis diambil alih oleh negara menjadi yang kita kenal sekarang adalah Hutan Negara. Di Jawa-selain Yogyakarta- semua hutan negara pengelolaannya diserahkan kepada BUMN Perum Perhutani. Padahal kalau kita baca monografi desa-desa pasti masih terdapat hutan-hutan yang masuk wilayah administrasi desanya. Tetapi realitanya desa dan masyrakatnya hanya menjadi penonton dan kena getah pertama kali jika terjadi masalah pada hutan2 tersebut. Konfigurasi penyeragaman seperti terlihat dalam UU No. 5 tahun 1974-yang disusul pelemahan desa menjadi hanya sekedar wilayah administrasi terkecil di bawah Kecamatan yang tidak mempunyai kekuasaan mengatur diri sendiri, mengakibatkan berubahnya struktur, posisi, bahkan wilayah desa. Terjadi banyak pemekaran dan atau penggabungan desa-desa yang sering kali tidak memandang faktor asal usul dan kesejarahan, sehingga praktis identitas desa asal sebagai suatu wilayah otonom menjadi kabur dan bahkan hilang. Sejak tumbangnya pemerintahan orde baru, kemudian memasuki era reformasi timbul semangat dan tuntutan baik dari arus bawah maupun tekanan internasional untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis pada semua sektor. Wacana otonomi daerah mulai diimplementasikan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. UU Kehutanan meski belum sepenuhnya ideal tetapi sudah ditetapkan dan menjadi acuan pengelolaan hutan Indonesia. Undang-undang kehutanan yang pada konsideran juga mengacu Undang-undang Agraria dan Undang-undang pemerintahan daerah, meski tidak konsisten tetapi sedikit banyak terdapat semangat pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan penyerahan sebagian urusan kehutanan kepada daerah kabupaten. Entah faktor dan latar belakang apa pada penjelasan pasal 5 UU Kehutanan muncul istilah dan definisi HUTAN DESA bersama-sama dengan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Adat. Hutan desa disebutkan sebagai hutan negara yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut-karena ini memang diletakkan di 3 penjelasan-. Definisi tersebut tentu saja masih multi interpretasi, terutama menyangkut kelembagaan dan aktor pengelola, wilayah dan unit pengelolaan hutan desa, serta tujuan dan sistem pengelolaannya. Ketika desa hanya dipahami sebagai pemerintahan desa maka definisi ini
masih berbasis negara. Bagaimanapun pemerintahan desa adalah representasi negara yang mau atau tidak mau dibebani hak dan kewajiban layaknya negara. Ketika desa dipahami utuh, mencakup pemerintahan, wilayah dan rakyat maka definisi tersebut bisa menjadi satu model baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Awang (2003) membagi pengertian hutan desa dari beberapa sisi pandang, yaitu (a) dilihat dari aspek teritorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat, (b) dilihat dari aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa, (c) dilihat dari aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah(hutan negara) yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa. Awang sendiri lebih cenderung pada pengertian (c) sebagai definisi ideal hutan desa. Sementara itu Alam (2003) yang sedang mengembangkan hutan desa di Sulawesi Selatan mendefinisikan hutan desa sebagai kawasan hutan negara, hutan rakyat, dan tanah negara yang berada dalam wilayah administrasi desa yang dikelola oleh lembaga ekonomi yang ada di desa, antara lain rumah tangga petani, usaha kelompok, badan usaha milik swasta, atau badan usaha milik desa yang khusus dibentuk untuk itu, dimana lembaga desa memberikan pelayanan publik terkait dengan pengurusan dan pengelolaan hutan. Definisi dari Universitas Hasannudin ini bahkan sudah menyebutkan kelembagaan dan aktor pengelolaannya, yang tetntu saja akan tergantung pada kondisi lokal tiap-tiap desa. DAMAR (1999) pada awal menggulirkan konsep hutan desa mendefinisikan hutan desa sebagai kawasan hutan negara yang masuk dalam wilayah desa tertentu dan dikelola oleh masyarakat desa tertentu. Satu definisi yang masih umum dan cenderung mengikuti bahasa undang-undang. Dalam perjalananannya ketika ketika berinteraksi langsung di lapangan, membicarakan pengelolaan hutan di desa memang harus holistik dan integrasi dengan pembangunan pedesaan. Sebagai satu kesatuan wilayah maka dari aspek status pengelolaan hutan desa harus mencakup status hutan negara dan hutan rakyat yang ada di desa tersebut. Lembaga dan aktor pengelola akan tergantung kesiapan dan kondisi masing-masing lokasi. Yang pasti masyarakatlah sebagai aktor utama pengelola, meskipun nantinya berbentuk kelompok tani, badan hukum perkumpulan, koperasi, dan sebagainya. Pada tingkat peraturan, seperti Kepmendagri No. 64/1999 dan juga berbagai peraturan daerah turunan PP No. 25/2000, menyebutkan hutan desa sebagai salah satu sumber kekayaan desa. Penyebutan tanpa penjelasan tersebut disamping menimbulkan berbagai pertanyaan tetapi juga menjadi peluang untuk mengimplementasikan konsepsi hutan desa, tidak mesti menunggu definisi baku dari pemerintah, tetapi bisa berangkat dari kesepakatan masing-masing elemen di desa, yang mestinya bisa diperkuat hanya dengan peraturan desa. Tabel. Realita dan Kebutuhan Kebijakan Pengelolaan Hutan Desa No. Realita Kebijakan yang mengatur Hutan Desa Substansi kebijakan Kebutuhan Kebijakan 1. UU No.41/1999 tentang Kehutanan pada Penjelasan Pasal 5 Hutan Desa, didefinisikan hutan negara yang dikelola oleh desa & dimanfaatkan untuk kesejahteraan Turunan kebijakannya, misalnya Peraturan Pemerintah atau aturan 4 desa
lain yang menjelaskan lebih jauh Hutan Desa 2. Kepmendagri No. 64/1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pasal 53 Hutan Desa, termasuk Kekayaan Desa Peraturan Daerah dan atau Peraturan Desa yang mengatur sumber pendapatan dan Kekayaan Desa 3. Perda kabupaten yang mengatur tentang Desa, juga menyebutkan adanya Hutan Desa sebagai salah satu sumber pendapatan dan kekayaan Hutan desa seringkali hanya disebutkan, tapi tanpa pendefinisian dan penjelasan apa itu Hutan Desa dan bagaimana mekanisme pengelolaannya Perda tanpa penjelasan seperti ini, memungkinkan banyak tafsir dan interpretasi. Pada tingkat desa bisa menjadi peluang untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Desa yang partisipatif tentang pengaturan Kekayaan desa, baik hutan maupun sumberdaya alam lainnya. Tabel. Beberapa istilah kekayaan desa dalam bentuk hutan5 No. Daerah Kabupaten Istilah 1. Kabupaten Agam (Sumatera Barat) Hutan yang menjadi ulayat nagari ada istilah Parak-pen2. Kabupaten Lampung Barat Hutan Pekon 3. Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur) Hutan Kampung 4. Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan) Hutan Desa Sumber : Sejumlah Perda paska UU No. 22/1999 Mengapa Hutan desa? Diatas sudah disinggung, bahwa pengelolaan hutan berbasis negara yang menyerahkan pada pengusaha swasta & BUMN dalam bentuk HPH & HTI diakui telah gagal. Alih-alih sebagai sumber pundi pemasukan negara ternyata lebih menguntungkan pengusaha dan oknum-oknum di pemerintahan sendiri. Masyarakat di sekitar hutan seakan tidak mendapat apa-apa dan harus menanggung beban kerusakan hutan dan lingkungan yang tidak tersembuhkan. Sementara itu desakan untuk melaksanakan otonomi sampai tingkat desa terus digelindingkan. Meskipun secara eksplisit UU No. 22/1999 tidak menyebutkan desa sebagai daerah otonom,tetapi secara implisist dari definisi desa yang baru dalam undang-undang itu jelas menyebutkan desa sebagai kesatuan wilayah hukum yang bisa mengatur dirinya sendiri, termasuk mestinya mempunyai kewenangan wilayah pengelolaan. Negara meskipun mempunyai sumberdaya pendukung tetapi sampai sekarang belum bisa dan berhasil merehabilitasi kembali hutan-hutan yang sudah dieksploitasi. 5 Sulaiman Sembiring : Aspek Hukum Desa & Hutan Desa, SIKLUS Edisi Khusus Februari 2003 5 Sementara itu dilapangan banyak terdapat kawasan yang kosong hukum akibat lemahnya peran
dan fungsi kontrol negara. Yang kemudian terjadi adalah semakin banyak kerusakan hutan akibat penjarahan dan penebangan liar. Ironisnya hal ini melibatkan semua pihak, dari masyarakat sebagai operator, cukong, sampai jajaran birokrasi pemerintah. Dua kondisi diatas ditambah kondisi lain seperti sempitnya kepemilikan lahan dan besarnya jumlah penduduk yang bergantung pada hutan-lebih banyak terjadi di Jawa- mengakibatkan banyak masyarakat yang kemudian berani melakukan okupasi lahan-bibrikan (Jawa)-. Keberanian tersebut, disamping akibat tekanan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, juga sebagian diakibatkan faktor kesejarahan yang memandang wilayah hutan yang diokupasi adalah juga tanah leluhurnya/tanah ulayat dan bahkan ada yang beranggapan sebagai milik mereka, karena dahulu pemerintah Belanda merebut paksa dan menjadikannya sebagai hutan negara. Hal lain yang mendasari adalah keberhasilan masyarakat mengelola dan menghijaukan tanahtanah milik mereka menjadi hutan rakyat. Kondisi kontras ini antara lain dapat disaksikan di Kulon Progo, hutan rakyat tumbuh menghijau-sebagian juga dengan proyek-proyek pemerintah-, tetapi hutan negaranya gersang merana. Keadaan ini diyakini masyarakat bahwa jika masyarakat diberi kepercayaan untuk mengelola hutan negara yang telah rusak itu, maka rasa memilikirumangsa handarbeni- akan tumbuh dan dengan sendirinya akan mau dan mampu melakukan rehabilitasi. Prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan-keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan. Mubyarto (2000) menyebutkan ciri paling kuat pemerintahan desa-desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong royong. Modal sosial ini jelas jauh lebih penting dibanding dengan berbagai insentif materi seperti yang diberikan pemerintah diatasnya. Hutan desa dapat menjadi salah satu pilihan kemandirian pendanaan otonomi desa jangka panjang. Dalam konteks ini hutan desa diarahkan menyeimbangkan 3 aspek, yaitu ekonomi, ekologi, dan equity (keadilan)6. Selanjutnya sebagai aset desa pengembangan hutan desa pasti memerlukan beberapa prasyarat,antara lain (diadaptasi dari pendapat Raharjo,2003) : a. Kepastian wilayah kelola jangka panjang, terutama menyangkut legalitas jika kawasan hutannya adalah hutan negara. b. Adanya kelembagaan usaha kehutanan masyarakat. c. Kepastian usaha kehutanan masyarakat, berkaitan dengan skema ekonomi pengembangan hutan desa. Unsur-unsur seperti modal,pengetahuan lokal, akses informasi, pengembangan komoditi, dan pasar menjadi substansi dasar. d. Kapasitas sumber daya manusia. e. Mekanisme penyelesaian sengketa , baik lahan maupun sosial. f. Kebijakan yang mendorong dan melindungi kepastian hak pengelolaan dan UKM jangka panjang. Idealnya kebijakan-point f- ini berasal dari negara (atas) seperti dalam bentuk peraturan pemerintah atau SK Menteri. Akan tetapi di era otonomi daerah maka suatu Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan hutan-didalamnya trcakup Hutan Desa- jelas dibutuhkan. Atau minimal ada suatu peraturan di tingkat desa (Perdes) yang mampu memberi kepastian pengelolaan dan usaha Hutan desa tersebut. Pengembangan hutan desa jika berhasil adalah tonggak perubahan tata kelola sumberdaya hutan dan bisa jadi merupakan substansi pembaharuan desa itu sendiri. Khusus di Jawa saja, ketika kita 6 Diah Raharjo : Kebijakan Hutan Desa di era Otonomi daerah..., SIKLUS Edisi Khusus, 2003 6 berkunjung ke desa dan melihat monografi desa, hampir semua desa mempunyai wilayah yang masih berupa hutan, baik itu hutan negara maupun hutan rakyat. Ironisnya selama ini desa dan masyarakatnya sering menjadi penonton, karena hutan2nya dikelola Perhutani dan atau Dinas
Kehutanan. Desa paling banter hanya dimintai legalitas dalam perdagangan kayu rakyat, yang itupun mestinya hanya sampai tingkat desa tidak harus membayar lagi di Dinas Kehutanan. Terakhir dengan itikad baik tentu saja dibutuhkan dukungan semua pihak, khususnya pemerintah. Bagaimanapun masyarakat hanya mempunyai sedikit sumberdaya, terutama sumberdana. Semangat dan tenaga saja dirasakan belum cukup, tanpa dukungan dan peningkatan kapasitas. Kolaborasi menjadi alternatif pilihan dimana masing-masing pihak yang terlibat mampu berbuat, mengambil, dan berbagi peran dan fungsi sesuai kompetensi masing-masing. Bahan Bacaan : Budi Baik Siregar & Wahono. Kembali ke Akar Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli. FPPM. Jakarta.2002. Diah Raharjo. Kebijaka
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5794)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20024)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceFrom EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceRating: 4 out of 5 stars4/5 (2556)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (3277)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2475)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12946)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionFrom EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2507)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19653)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationFrom EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationRating: 4 out of 5 stars4/5 (2499)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2567)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6521)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelFrom EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (5506)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseFrom EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseRating: 4 out of 5 stars4/5 (1107)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)From EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9486)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderFrom EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderRating: 4 out of 5 stars4/5 (5718)



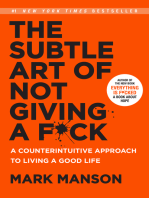







![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)