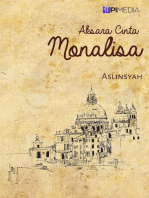Professional Documents
Culture Documents
BUAH RINDU
Uploaded by
Wendy Rega GumelarOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
BUAH RINDU
Uploaded by
Wendy Rega GumelarCopyright:
Available Formats
Buah Rindu (1941)
Walaupun baru diterbitkan pada tahun 1941, namun puisi-puisi Amir Hamzah yang terhimpun dalam Buah Rindu telah ditulis lebih dulu daripada puisi-puisi dalam Nyanyi Sunyi yang diterbitkan pada tahun 1937. Antologi Buah Rindu berisi 28 judul puisi*. Pada halaman terakhir, yang merupakan halaman persembahan, tercantum: Ke Ke Ke Sementara itu, di bawah bawah bawah bawahnya tercantum paduka lebu kaki titimangsa: Indonesia-Raya Ibu-Ratu Sendari-Dewi 1928-1935.
Jakarta-Solo-Jakarta
Achdiat K. Mihardja, yang kenal secara pribadi dengan Amir, menjelaskan bahwa dalam antologi ini nampak oleh kita bayangan jiwa Amir di dalam masa tujuh tahun ia berada di dua kota [yaitu] Jakarta dan Solo itu (Achdiat K. Mihardja dalam Abrar Yusra, 1996:92). Sementara itu, Ajip Rosidi (dalam Yusra, 1996:95) menduga bahwa Amir sendiri masih menganggap Buah Rindu sebagai latihan untuk kemudian menulis Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu adalah percobaan-percobaan pertama Amir menulis sajak. A. Teeuw (1959:116), ketika membahas antologi ini dalam Pokok dan Tokoh I (Jakarta, 1959) menyatakan bahwa dalam antologi ini, pembaca akan bertemu dengan penyanyi kesunyian, penyanyi kerinduan kepada kampung halaman. Kerinduan itu dilukiskan dalam berbagai bentuk dan masih ditujukan kepada berbagai hal di negeri ini (Indonesia, waktu itu masih bernama resmi Hindia-Belanda). Kadang-kadang kerinduan itu tertuju kepada tanah airnya (Sumatra) sebab sanjak-sanjak [sic] itu dituliskan pada masa Hamzah belajar di Jawa. Dari puisi-puisi dalam Buah Rindu dan biografi-biografinya, memang muncul kesan bahwa selama di Jawa, Amir merasa menjadi orang asing, namun keasingan itu kemudian dirasakannya bukan hanya karena ia berada di Jawa saja, tetapi juga karena ia berada di sini, di dunia ini. Inilah yang kemudian menjadi dasar-corak puisinya: diri yang merasa asing dan sepi serta sunyi. Keistimewaan Amir sebagai penyair adalah bahwa ia mengungkapkan hal ini menurut kebiasaan lama, misalnya dengan menamakan dirinya sebagai dagang, musafir lata, hina, fakir, dan kelana, tetapi dengan arti dan nuansa yang baru. Achdiat (dalam Yusra, 1996:91) mencermati bahwa kekuatan Amir terutama terletak dalam menyusun suara dan kiasan. Ia sangat pandai menyusun kata-kata yang merupakan rangkaian suara yang sangat merdu. Amir sangat bebas memasukkan kata-kata Jawa, Kawi atau Sanskerta ke dalam sajak-sajaknya, misalnya dewangga, dewala, sura, prawira, estu, ningrum, padma, cendera, deksina, purwa, jampi, sekar, alas, maskumambang, rangkum-rinangkum dan lain-lain. Intensifikasi keasingan, kesepian, dan kesunyian dalam diri Amir terepresentasikan juga, misalnya, dalam panggilan-panggilannya kepada ibu: Amir dalam Buah Rindu berkali-kali menggunakan panggilan Ibu dan Bonda. Teeuw (1959:116) menduga bahwa, walaupun mulamula tidak bisa dipastikan apakah ibu biologis Amir atau tanah air yang mesti mendengarkan
ratapan si penyair, pembaca dapat segera tahu bahwa yang dua itu satu saja bagi Amir. Hal ini terasa kuat dalam bait ini: Bunda, Pada Adakah Bahwa waktu subuh ibu begini tuan melahirkan kembang menaruh peminta beta cempaka sangka anakda?
Demikian sunyi dan pedihnya nasib si penyair hingga hanya maut saja yang patut diinginkan karena dianggap akan dapat melepaskan diri dari derita: Datanglah Lepaskan Engkau Di engkau, aku lagi waktu ini wahai dari tempatku gelap maut nestapa berpaut gulita.
Amir memang masih menggunakan lambang-lambang yang bisa digunakan oleh para penyair mana pun, baik para penyair dari dunia Barat maupun Timur, misalnya bunga dan burung mungkin inilah sebabnya mengapa H.B. Jassin menyebutnya sebagai wakil dari zaman (Melayu) lama. Akan tetapi, meskipun kedua lambang lazim ini berulang-ulang dipakainya untuk mengungkapkan kesunyian, ragam atau cara pengungkapannya berbeda-beda. Lambanglambang itu diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan corak khas bahasa Melayu/Indonesia yang lebih segar. Amir menghayatinya dengan sedemikian rupa sehingga ia mampu dengan hemat dan tepat mempergunakannya dan alangkah indahnya pula sekonyong-konyong jadinya perumpamaan yang tua dan usang itu (Teeuw, 1959:118): Tuan Yang Berhentilah Anak Sesaat, Padamu Arah Di Sampaikan Bisikkan Liputi Serupa aduhai meliputi tuan Langkat sekejap tuan manakah negeri rinduku rayuanku lututnya beta manakan mega dewangga atas musyafir beta aduhai tuan tuan pada pada muda memeluk berarak raya teratak lata berpesan awan berjalan, bertahan? adinda juita kencana dia.
di
mata
Secara panjang lebar, A. Teeuw mengomentari pembaruan Amir terhadap bahasa Melayu/Indonesia melalui puisi-puisi dalam Buah Rindu ini sebagai berikut: Dalam artinya yang lebih terbatas, Amir Hamzah mempergunakan secara sangat menguntungkan sekali kemungkinan-kemungkinan yang didapatkan pada bahasa, tetapi caranya bercorak
kepribadian dirinya dan bersifat hidup gembira. Untaian yang kebanyakan berbaris empat dengan sajak-ujung itu ialah untaian syair. Baris yang mengandung empat kata itu pun, yang tidak mungkin ditiru dalam bahasa lain, dengan keindahannya yang sederhana, dengan sajak-antara, dengan aliterasi yang semuanya memperlihatkan sifat-sifat yang terkenal pada kesusastraan Melayu-kuno [sic], tetapi yang di sini tidak dipakai secara klise saja. Di sini, ilham tidak dirusakkan hanya karena hendak memelihara sajak, tak ada tambahan-tambahan yang tak berarti, atau yang diadakan asal saja baris dapat dipenuhkan, tak ada barang suatu yang ditinggalkan saja dengan tak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena baris itu telah penuh, tak pula ada hanya bunyi yang menyembunyikan kekosongan batin saja. Tidak, di sini seorang penyair muda telah dapat menciptakan persesuaian yang indah antara tua dan muda, antara kekunoan dan kebebasan, antara aturan dan ilham (Teeuw, 1959:119). Pilihan Amir untuk menulis puisi yang kemudian disiarkannya dalam bahasa Melayu/Indonesia, pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan Indonesia itu, adalah pilihan yang sangat berani dan maju. Ketika ditanya oleh Achdiat yang keheranan, Sajakmu dalam bahasa Indonesia?, Amir menjawab, Habis dalam bahasa apa aku harus berlagu? (Mihardja dalam Yusra, 1996:89-90). Pada zaman itu, belum banyak pemuda terpelajar yang membikin sajak dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan masih mencurahkan isi hatinya atau buah pikirannya dalam bahasa Belanda. Tengara perjuangan untuk bahasa Indonesia baru saja berbunyi. Hanya sekali-sekali saja dapat dijumpai sajak-sajak berbahasa Indonesia dalam majalah Indonesia Moeda atau Timboel yang setengah berbahasa Belanda, setengah lagi berbahasa Indonesia. Pujangga-pujangga yang terkenal baru Sanusi Pane dan [Muhammad] Yamin (Mihardja dalam Yusra, 1996: 90). Namun, Achidat menegaskan bahwa pilihan itu dipengaruhi juga kenyataan bahwa Amir lebih dulu membiasakan diri mempergunakan bahasa Indonesia karena bagi anak-anak Sumatra, bahasa Indonesia itu tidak begitu asing seperti misalnya bagi anak-anak dari Jawa atau Sunda (Mihardja dalam Yusra, 1996: 90). (An. Ismanto/1/TAH/05-2010)
Home Tokoh Sastra Kumpulan Puisi Kumpulan Cerpen Download
Puisi Amir Hamzah IBUKU DAHULU
6Share 4 Mei 2010
Ibuku dahulu marah padaku Diam ia tiada berkata Aku pun lalu merajuk pilu Tiada perduli apa yang terjadi. Matanya terus mengawas daku Walaupun bibirnya tiada bergerak Mukanya masam menahan sedan Hatinya pedih karena lakuku Terus aku berkesal hati Menurutkan setan mengacau-balau Jurang celaka terpandang di muka Kusongsong juga biar cedera Bangkit ibu dipegangnya aku Dirangkumnya segera dikecupnya serta Dahiku berapi pancaran neraka Sejuk sentosa turun ke kalbu Demikian engkau :
Ibu, bapa kekasih pula Berpadu satu dalam dirimu Mengawas daku dalam dunia.
You might also like
- Bahasa Dan SastraDocument12 pagesBahasa Dan SastraSpirulina TiensNo ratings yet
- BUAHRINDUDocument8 pagesBUAHRINDUAmir Daeng GassingNo ratings yet
- Bahasa IndonesiaDocument14 pagesBahasa Indonesiawahyuni thu teh uniNo ratings yet
- Membaca Puisi IndonesiaDocument23 pagesMembaca Puisi IndonesiaHijrana APNo ratings yet
- Amir Hamza 4 PUISIDocument7 pagesAmir Hamza 4 PUISINur RahmanNo ratings yet
- Materi B.indinesia Puisi RakyatDocument21 pagesMateri B.indinesia Puisi RakyatAtikahNo ratings yet
- Bentuk PuisiDocument15 pagesBentuk Puisifa_tomodachiNo ratings yet
- PUISI INDONESIADocument4 pagesPUISI INDONESIAYulia DarsihNo ratings yet
- Karya Amir HamzahDocument1 pageKarya Amir Hamzahsihatm291No ratings yet
- Njanji SoenjiDocument4 pagesNjanji SoenjiMuhammadRomlyMutakinNo ratings yet
- Esaimen BMM KesusasteraanDocument9 pagesEsaimen BMM Kesusasteraanaminah kiprawi0% (1)
- Apresiasi PuisiDocument12 pagesApresiasi PuisiKIKI NOPITANo ratings yet
- Teknik Mendeklamasikan PuisiDocument17 pagesTeknik Mendeklamasikan PuisiruddyansjahNo ratings yet
- KaryaAmirHamzahDocument41 pagesKaryaAmirHamzahIjaaNo ratings yet
- Resensi Buku Tulisan Pada TembokDocument4 pagesResensi Buku Tulisan Pada TembokZulkifliSongyananNo ratings yet
- Biografi Amir Hamzah Sastrawan IndonesiaDocument2 pagesBiografi Amir Hamzah Sastrawan IndonesiaNirmala Eka Nareswara100% (1)
- Analisis Puisi Surat Dari Ibu Karya Asrul SaniDocument4 pagesAnalisis Puisi Surat Dari Ibu Karya Asrul SaniAmanah FotocopyNo ratings yet
- UNSUR INTRINSIK PUISIDocument18 pagesUNSUR INTRINSIK PUISIIkacieboru PoelunganNo ratings yet
- PUISI 40Document11 pagesPUISI 40Anjing kamuNo ratings yet
- Sajak PengertianDocument18 pagesSajak PengertianShellashel LbsNo ratings yet
- Amir Hamzah Lahir Di Tanjung PuraDocument6 pagesAmir Hamzah Lahir Di Tanjung PuraMuh Ridwan ViscaNo ratings yet
- Pengertian Puisi Baru Beserta ContohnyaDocument8 pagesPengertian Puisi Baru Beserta ContohnyaJoanne HendersonNo ratings yet
- Pujangga BaruDocument19 pagesPujangga BaruMahmud YunusNo ratings yet
- ANALISISDocument43 pagesANALISISMismis Vava100% (2)
- Aliran KesusasteraanDocument11 pagesAliran KesusasteraanCikgu Jorasmin IsaNo ratings yet
- Gairah Lokalitas Dan Sufistik Dalam Puisi-Puisi Akhmad TabraniDocument4 pagesGairah Lokalitas Dan Sufistik Dalam Puisi-Puisi Akhmad TabraniMuhammad DandyNo ratings yet
- TEKS PUISIDocument9 pagesTEKS PUISIzura maruNo ratings yet
- Bindo PDFDocument36 pagesBindo PDFgilbertmanoppoNo ratings yet
- Resensi PuisiDocument5 pagesResensi PuisiHesti Wahyuningtyas100% (1)
- Nota Puisi TradisionalDocument8 pagesNota Puisi TradisionalAmalin RahimNo ratings yet
- Contoh Puisi Beserta Unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik LengkapDocument7 pagesContoh Puisi Beserta Unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik LengkapSujatmikoNo ratings yet
- Tugas01 AndrianMelmamBesy 048926834Document3 pagesTugas01 AndrianMelmamBesy 048926834AndrianMelmamBesyNo ratings yet
- MENGEKSPRESIKAN DIRI LEWAT PUISIDocument14 pagesMENGEKSPRESIKAN DIRI LEWAT PUISIDettaNo ratings yet
- PUISI, PANTUN, SYAIR DAN GURINDAMDocument6 pagesPUISI, PANTUN, SYAIR DAN GURINDAMGhanivy IndriNo ratings yet
- Karya Sastra Yang Dikaitkan Dengan Pendekatan Ekspresif (Puisi Berdiri Aku Karya Amir Hamzah)Document5 pagesKarya Sastra Yang Dikaitkan Dengan Pendekatan Ekspresif (Puisi Berdiri Aku Karya Amir Hamzah)RatuNo ratings yet
- Analisa SajakDocument3 pagesAnalisa SajakManjae CamielaNo ratings yet
- ANALISIS PUISIDocument3 pagesANALISIS PUISIRayhan DewaNo ratings yet
- Revisi Puisi TerjemahanhfDocument3 pagesRevisi Puisi TerjemahanhfzulfaNo ratings yet
- REVISI 2 Biografi Amir HamzahDocument3 pagesREVISI 2 Biografi Amir HamzahrieNo ratings yet
- Sinonim Dan Puisi RakyatDocument6 pagesSinonim Dan Puisi RakyatDarin farah NabilahNo ratings yet
- Lukman - Puisi Serenada HijauDocument3 pagesLukman - Puisi Serenada HijauLukmanLatopas0% (2)
- Sastra Indonesia Di Masa JepangDocument12 pagesSastra Indonesia Di Masa JepangDevina Athalia MirantiNo ratings yet
- PUISI LAMA SEJARAHDocument7 pagesPUISI LAMA SEJARAHIrvan Zein RevenantNo ratings yet
- Para Pujangga Puisi Angkatan 45 Sampai SekarangDocument16 pagesPara Pujangga Puisi Angkatan 45 Sampai SekarangFasyaRubbySyahPutraNo ratings yet
- Pembagian KesusastraanDocument14 pagesPembagian KesusastraanRei SakakiNo ratings yet
- Tugas Bahasa Indonesia Ervina Yunita Zahra VIICDocument37 pagesTugas Bahasa Indonesia Ervina Yunita Zahra VIICNurulUyunNo ratings yet
- Analisis Stilistika Puisi "Senja Di Pelabuhan Kecil " Karya Chairil AnwarDocument8 pagesAnalisis Stilistika Puisi "Senja Di Pelabuhan Kecil " Karya Chairil AnwarGareng Jelek Dan IrengNo ratings yet
- HANG TUAHDocument15 pagesHANG TUAHKebetulan LöiNo ratings yet
- ANALISIS PUISI AMIR HAMZAHDocument3 pagesANALISIS PUISI AMIR HAMZAHnajibNo ratings yet
- B.indo Puisi ModernDocument9 pagesB.indo Puisi ModernNurdiansyah dienNo ratings yet
- BAB VII-VIII Puisi Dan BiografiDocument14 pagesBAB VII-VIII Puisi Dan BiografiAndri YuliantoNo ratings yet
- Analisis Puisi Chairil AnwarDocument12 pagesAnalisis Puisi Chairil Anwarsri mulyaniNo ratings yet
- Biografi Muhammad YaminDocument6 pagesBiografi Muhammad Yaminنور زمزميNo ratings yet
- Makalah Derai-Derai Cemara Karya Chairil AnwarDocument15 pagesMakalah Derai-Derai Cemara Karya Chairil AnwarVicka AsterinaNo ratings yet
- STRUKTUR PUISIDocument5 pagesSTRUKTUR PUISIAnggara PutraNo ratings yet
- Biografi Amir HamzahDocument16 pagesBiografi Amir HamzahMiyura100% (1)
- Ulasan Puisi 'Bunga PopiDocument6 pagesUlasan Puisi 'Bunga Popiikan otekNo ratings yet
- Proposal Penggajian AngsuranDocument19 pagesProposal Penggajian AngsuranWendy Rega GumelarNo ratings yet
- ILMU EKONOMIDocument44 pagesILMU EKONOMIafenalosa50% (2)
- Penerapan Teori Ekonomi MakroDocument1 pagePenerapan Teori Ekonomi MakroWendy Rega GumelarNo ratings yet
- S I L A B U S Kelas 4Document10 pagesS I L A B U S Kelas 4Wendy Rega GumelarNo ratings yet
- TEKNIK MENGAJARDocument8 pagesTEKNIK MENGAJARWendy Rega GumelarNo ratings yet
- PUISIDocument118 pagesPUISIWendy Rega GumelarNo ratings yet