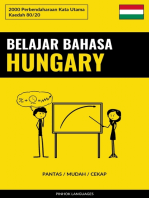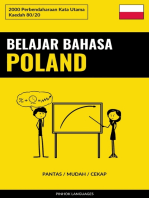Professional Documents
Culture Documents
Bahasa Banjar
Uploaded by
fatchulibnusihyarCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Bahasa Banjar
Uploaded by
fatchulibnusihyarCopyright:
Available Formats
DIALOG BORNEO-KALIMANTAN VII: SUATU KILAS BALIK Fatchul Muin
Dialog Borneo-Kalimantan VII berlangsung mulai tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 2003 di Hotel Borneo. Dialog itu menyoal budaya Melayu, termasuk di dalamnya bahasa Banjar. Adalah Ersis Warmansyah Abbas dengan gayanya yang khas, telah mengulas dialog itu dari berbagai sisi, antara lain, berkenaan dengan pelestarian budaya dan bahasa Banjar. Kali ini, saya melihat bahasa Banjar dari sisi yang lain. Dalam diskusi itu terungkap, antara lain, bahwa penggunaan bahasa Banjar sekarang menunjukkan gejala yang memprihatinkan. Dikhawatirkan bahwa bahasa Banjar akan tidak berkembang dan lama kelamaan akan lenyap bila tidak diadakan pembinaan. Sejumlah kalangan justeru tidak mengkhawatirkan akan lenyapnya bahasa Banjar. Hal ini karena bahasa daerah ini masih banyak pendukungnya. Di kantor-kantor, di kampung-kampung, di tempat-tempat mangkal para pengojek, dalam pandiran ala warung kopi dan lain-lain, yang pernah saya amati, bahasa Banjar selalu digunakan, khususnya, bila peserta tuturnya beretnis Banjar. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan etnis lain ikut menggunakan bahasa Banjar bila bergabung dengan mereka. Mereka ini sebenarnya para pelestari bahasa Banjar itu sendiri. Penggunaan bahasa Banjar dalam siaran berita RRI terkena tohok. Menurut salah seorang penyaji, bahasa Banjar dalam siaran berita RRI itu adalah bahasa Banjar yang tidak murni (terpengaruh oleh bahasa Indonesia) dan (ciri yang jelas) dibacakan dengan lagu bahasa Indonesia. Bagi penutur asli bahasa Banjar yang punya kepedulian terhadap hidupmatinya bahasa Banjar, siaran berita dalam bahasa daerah ini dipandang cacat dan bisa memanaskan telinga. Namun sayang, model dan lagu membacakan berita dalam bahasa Banjar yang benar tidak dicontohkan (misalnya, dengan memutar kaset rekaman siaran itu).
Padahal, kawan di sebelah saya ingin mendengar model dan lagu pembacaan berita dalam bahasa Banjar yang benar. Beranjak dari statement di atas, untuk kepentingan penyiaran berita dalam bahasa Banjar ini, kiranya perlu bagi pihak RRI untuk merekrut penulis dan atau pembaca berita dari penutur asli (native speaker) bahasa Banjar yang betul-betul memiliki linguistic competence dan performance yang memadai. Linguistic competence adalah kemampuan terhadap bahasa dan aturan-aturan atau kaidah-kaidahnya (the users knowledge about the language and its system); sedangkan linguistic performance adalah penggunaan bahasa secara nyata (the actual use of the language) yang secara langsung dapat diamati (didengar atau dibaca). Atau, kalau perlu ia merekrut penutur asli bahasa Banjar yang monolingual. Namun, apa mungkin mengambil penutur yang monolingual itu? Jika seorang penutur bahasa akan menyampaikan pesan kepada orang lain, dia perlu mengetahui dan menguasai bahasa dan kaidahnya yang akan digunakan sebagai alat komunikasinya. Pengetahuan dan kemampuan terhadap kaidah bahasa itu akan sangat menentukan apakah kata-kata, kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang diucapkan atau dihasilkannya itu benar atau tidak, dan baik atau tidak. Dengan demikian, penggunaan bahasa secara nyata (linguistic performance) yang didukung oleh pengetahuan dan kemampuan bahasa yang tidak atau kurang sempurna, akan memanaskan telinga penutur asli bahasa itu. Dalam arti, penggunaan bahasa secara nyata tidak berkesesuaian dengan kaidah bahasa yang bersangkutan, misalnya: bahasa Indonesia yang di-Banjar-kan atau bahasa Indonesia yang dilagu-Banjar-kan. Dalam diskusi tersebut terungkap pula bahwa rusaknya bahasa Banjar karena para penutur selain memiliki kemampuan bahasa Banjar juga kemampuan bahasa-(bahasa) lain. Mereka in disebut dwibahasawan. Penggunaan dua (atau lebih) bahasa disebut kedwibahasawan atau bilingualisme.
Kedwibahasaan dibatasi oleh Bloomfield sebagai penggunaan dua bahasa yang sama baiknya antara bahasa ibu (asli) dan bahasa kedua. Dengan demikian, pengertian kedwibahasaan semacam ini menyaran pada kelancaran dan ketepatan yang sama seperti penggunaan bahasa oleh penutur asli dari setiap bahasa itu. Munculnya unsur-unsur dari
bahasa lain (bahasa Indonesia) dalam tuturan pembawa berita dalam bahasa Banjar, seperti yang disinyalir terjadi di RRI, yang memiliki pengetahuan atau penguasaan lebih dari satu bahasa itu, kiranya perlu kita ikuti penjelasan sebagai berikut. Jika seorang dwibahasawan akan menyampaikan suatu pesan lewat bahasa kepada pendengarnya, ada dua faktor yang menghambat perjalanan pesan itu sebelum ia dapat diujarkan oleh penuturnya. Pertama adalah faktor dari kaidah beberapa bahasa yang dikenalnya, tentunya berbeda satu dari yang lainnya. Faktor ini tampaknya dapat untuk menanggapi penggunaan bahasa Banjar oleh penulis dan atau pembaca berita dalam bahasa Banjar di RRI. Saya berkeyakinan bahwa penulis dan atau pembaca berita dalam bahasa Banjar di RRI itu adalah dwibahasawan. Mampukah dia membedakan dan memilah-milahkan setiap kaidah itu, sehingga ketika dia menggunakan salah satu bahasa, kaidah bahasa lain tidak mengganggu? Jika dia tidak mampu, maka sementara dia menggunakan salah satu bahasa yang dikenalnya, bahasa lain dapat saja muncul dalam tuturannya. Terjadilah apa yang disebut interferensi, alih kode/campur kode. Sebaliknya, bila dia dapat memisah-misahkan kaidah bahasa-bahasa yang dikenalnya, maka terjadilah tunggal-bahasa dalam tuturan si penutur tersebut. Beranjak dari statement yang muncul dalam diskusi tersebut, dia tidak mampu membedakan dan memilah-milahkan setiap kaidah dari bahasa-bahasa yang dikenalnya. Akibatnya, ya itu tadi: the actual use of Banjarese language memanaskan telinga penutur aslinya. Kedua adalah faktor yang berasal dari pertimbangan komunikasi. Faktor ini kiranya dapat digunakan untuk menanggapi penggunaan bahasa Banjar yang ter-distorsi oleh bahasa-
(bahasa) lain. Ini berkait dengan statement yang juga muncul dalam diskusi tersebut, bahwa bahasa Banjar berfungsi sebagai lingua franca untuk berbagai suku yang tinggal/menetap di Kalimantan Selatan, Timur dan Tengah , dan sebagian Kalimantan Barat. Bahasa Banjar digunakan mereka untuk alat komunikasi dalam upayanya berinteraksi antar mereka. Dalam kenyataannya, dia tidak bebas sama sekali. Ada seperangkat peraturan berbahasa yang telah disepakati oleh masyarakat di mana dia hidup dan bergaul dengan anggota-anggota lain sesuai dengan tata-nilai yang menjadi pedoman mereka. Pertimbangan komunikasi ini menentukan apakah dia akan bertutur dengan tunggal-bahasa, atau melakukan alih-kode (code-switching) atau bisa juga campur-kode (code-mixing). Dalam hal ini, mungkin kita dapati alih kode atau campur kode: Banjar-Jawa, BanjarMadura, Banjar-Bugis, Banjar-Bakumpai Banjar-Indonesia, dan sebagainya atau Banjar logat Jawa, Banjar logat Madura, Banjar logat Bugis, Banjar logat Bakumpai, Banjar lagu Indonesia-nya pembaca berita dalam bahasa Banjar di RRI dan sebagainya. Kekhawatiran akan lenyapnya bahasa dan budaya Banjar memang perlu disikapi, misalnya, seperti kata Ersis, dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah, menulis buku-buku dalam bahasa Banjar. Untuk melestarikan bahasa perlu dilakukan language planning dalam rangka untuk membakukan bahasa itu sendiri. Agar lagu bahasa bisa dipertahankan sesuai lagu aslinya, kiranya perlu dilakukan pelisanan bahasa itu oleh native speaker yang benar-benar bagus bahasa lisannya, atau bila perlu dilakukan recording terhadap bahasa lisan itu sendiri. Sebetulnya, amburadulnya penggunaan bahasa Banjar tidak sendirian. Penggunaan Jawa yang memiliki sejumlah tingkat tutur itu, misalnya, juga telah banyak mengalami pergeseran dari penggunaannya yang ideal. Sejumlah orang bertutur dengan tingkat ngoko padahal semestinya dengan tingkat tutur krama. Celakanya lagi, dalam pandangan saya, penguasaan tingkat tutur krama (madya dan inggil) pada kalangan kawula muda dalam kondisi memprihatikan (untuk tidak mengatakan jelek). Tampaknya, mereka kurang
kompetensinya dalam bahasa Jawa, khususnya tingkat tutur krama, yang memancarkan konotasi hormat itu. Sehingga, performansi dalam bahasa itu juga memprihatinkan. Yang lebih memprihatinkan lagi, --mungkin menganggap bahasa Jawa sebagai bahasa tradisional dan biar dianggap sebagai orang-orang yang modern, educated -- ada sejumlah orang tua di kampung tempat kelahiran saya membiasakan anak-anak mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan Jawa mereka yang medok--, padahal mereka hidup di lingkungan masyarakat bahasa (speech community) bahasa Jawa. (Telinga saya juga panas bila mendengarnya). Mereka tampak begitu bangga ketika memperhatikan anak-anak mereka berbahasa Indonesia. Hal yang demikian, di samping tidak mendidik anak-anak untuk mampu berbahasa Jawa, menyusahkan mereka dalam bergaul dengan sesama mereka, tetapi juga membutakan mereka terhadap budaya yang terpancar dari bahasa Jawa itu sendiri, seperti adap asor, dan unggah-ungguh. Anak-anak yang hidup dan bergaul dalam masyarakat tutur bahasa Jawa, ajarilah -- atau jika tidak--biarkanlah mereka berbahasa dan berbudaya Jawa. Secara adat Jawa, tata cara perkawinan, misalnya, menyangkut hal-hal: (1) nakokake, (2) nontoni, (3) yaitu, peningsetan, (4) perkawinan, dan (5) ngunduh mantu (Suryadikara, 1989). Dalam situasi sekarang, bila kedua bakal calon pengantin belum saling kenal, maka semua tata cara perkawinan di atas tetap saja dilalui, kendati di sana sini terdapat penyederhanaan. Namun, karena umumnya muda-mudi melangkah ke jenjang perkawinan sudah saling mengenal (tepatnya, berpacaran) maka sebagian tata cara tersebut tidak dilakukan. Tampaknya, tata cara yang ada adalah (1) lamaran, (2) peningsetan, (3) perkawinan (yang tidak diikuti macam-macam aktivitas, kecuali walimah), dan (4) ngunduh mantu (yang tidak selalu dilakukan). Dalam kaitan dengan budaya, mungkin kita sepakat bahwa budaya bisa saja tetap ajeg, bergeser, berubah atau bahkan musnah. Bila kita menginginkan keajegan budaya itu, kita tentu perlu usaha yang kongkret. Bagaimana menurut sampeyan? Tulisan ini pernah dimuat di SKH Radar Banjarmasin, 13 Mei 2003
You might also like
- 120-Article Text-173-1-10-20180525Document13 pages120-Article Text-173-1-10-20180525sakthiNo ratings yet
- Esai Using Dialek JawaDocument3 pagesEsai Using Dialek JawaAna Cahya99No ratings yet
- Konsep Komunikasi Bahasa BanjarDocument2 pagesKonsep Komunikasi Bahasa BanjarSuci AmaliaNo ratings yet
- Bab 2 Mini Riset BiokimiaDocument9 pagesBab 2 Mini Riset Biokimiasindi lestariNo ratings yet
- Tesis Siap Ujian TutupDocument114 pagesTesis Siap Ujian TutupamirahnurwafiqahNo ratings yet
- Uts Pemertahanan Bahasa (R001) - Yessa Yuliana (A1j221019)Document10 pagesUts Pemertahanan Bahasa (R001) - Yessa Yuliana (A1j221019)Yessa YulianaNo ratings yet
- Bab I - 2Document10 pagesBab I - 2aingediteditNo ratings yet
- Materi 2 Ragam BahasaDocument7 pagesMateri 2 Ragam Bahasaayunurul382No ratings yet
- MC-lestarikan BahasaDocument9 pagesMC-lestarikan BahasaAkang AidiNo ratings yet
- Bahasa Indonesia (PDF - Io)Document37 pagesBahasa Indonesia (PDF - Io)Mutiara SuhaidiNo ratings yet
- Essay Joleha Nacikit-DikonversiDocument9 pagesEssay Joleha Nacikit-Dikonversiscott karamoy24No ratings yet
- BAB I PENDAHULUANDocument27 pagesBAB I PENDAHULUANPangihutan ManullangNo ratings yet
- Perbandingan Bi DGN Bahasa BanjarDocument32 pagesPerbandingan Bi DGN Bahasa BanjarfikkomNo ratings yet
- RagamBahasaBakuDocument10 pagesRagamBahasaBakudwi aryaniNo ratings yet
- Pergantian Makna Dalam Bahasa Jawa Krama Oleh: Kustri Sumiyardana AbstrakDocument6 pagesPergantian Makna Dalam Bahasa Jawa Krama Oleh: Kustri Sumiyardana AbstraksaifulNo ratings yet
- ARTIKEL BAHASA DAERAH - KELOMPOK 1-FixDocument12 pagesARTIKEL BAHASA DAERAH - KELOMPOK 1-FixEka JayantiiNo ratings yet
- Artikel Bahasa BanjarDocument2 pagesArtikel Bahasa Banjarridhoni lampardNo ratings yet
- Makalah Bahasa BaliDocument44 pagesMakalah Bahasa Balijumbopande123No ratings yet
- Bindo MkuDocument57 pagesBindo MkuKhika WangoNo ratings yet
- BAHASA INDONESIADocument14 pagesBAHASA INDONESIAMurjani TbnNo ratings yet
- Bahasa Dan DialekDocument16 pagesBahasa Dan DialekKey AzkayraNo ratings yet
- Kalimat EfektifDocument13 pagesKalimat Efektifsyerina adeliaNo ratings yet
- Bahasa BanyumasanDocument17 pagesBahasa BanyumasanBry ChandraNo ratings yet
- Pergeseran dan Pemertahanan BahasaDocument7 pagesPergeseran dan Pemertahanan BahasaNova Hari SaputroNo ratings yet
- Variasi Bahasa Bugis di DuampanuaDocument41 pagesVariasi Bahasa Bugis di DuampanuaNovi Yanti100% (1)
- Basa JawaDocument4 pagesBasa Jawapramanta_hertaNo ratings yet
- OPTIMALKAN BAHASA INDONESIADocument12 pagesOPTIMALKAN BAHASA INDONESIAEdisons_Sony_6825No ratings yet
- Pentingnya Bahasa IndonesiaDocument2 pagesPentingnya Bahasa IndonesiaRafi' MuhammadNo ratings yet
- Bahasa Sunda Sebagai Bahasa DaerahDocument2 pagesBahasa Sunda Sebagai Bahasa DaerahIhsan MuhamadNo ratings yet
- S PAUD 1005011 Chapter1Document10 pagesS PAUD 1005011 Chapter1halim abdeeNo ratings yet
- Perubahan Bahasa Secara DinamisDocument14 pagesPerubahan Bahasa Secara DinamisAbu SalikNo ratings yet
- Laporan KeuanganDocument13 pagesLaporan KeuanganRheina Siee SulLungNo ratings yet
- Dampak Positif Dan Negatif Bahasa Daerah Terhadap Bahasa IndonesiaDocument5 pagesDampak Positif Dan Negatif Bahasa Daerah Terhadap Bahasa IndonesiaYolanda SiNo ratings yet
- Bahasa IndonesiaDocument50 pagesBahasa Indonesiadamianus renyaanNo ratings yet
- Sejarah Bahasa IndonesiaDocument5 pagesSejarah Bahasa Indonesiadiah0109No ratings yet
- Proposal Riduan HalamanDocument42 pagesProposal Riduan HalamanErico SetiadiNo ratings yet
- MateriDocument4 pagesMateriDINDA HUMAIRANo ratings yet
- Ragam Bahasa IndonesiaDocument36 pagesRagam Bahasa IndonesiaAjeng ViolietaNo ratings yet
- Bab IDocument8 pagesBab IMuhammad SabilNo ratings yet
- Wasbang IndividuDocument5 pagesWasbang IndividuSalsabila AufaNo ratings yet
- Dialek Sebagai Identitas Masyarakat Bahasa Di Pulau Lombok: Muhammad Dedad Bisaraguna AkastanggaDocument8 pagesDialek Sebagai Identitas Masyarakat Bahasa Di Pulau Lombok: Muhammad Dedad Bisaraguna AkastanggaBaiq AgustinaNo ratings yet
- Editor - MahilungDocument30 pagesEditor - Mahilungrico rubenNo ratings yet
- Makalah Arti Bahasa SundaDocument11 pagesMakalah Arti Bahasa Sundaadi riawanNo ratings yet
- Budaya dan BahasaDocument5 pagesBudaya dan BahasaAndini PuspaNo ratings yet
- Putri IndriyaniDocument2 pagesPutri IndriyaniPutri IndriyaniNo ratings yet
- Fenomena PenggunaanDocument10 pagesFenomena PenggunaanAfrizal lNo ratings yet
- Aspek dan Struktur BahasaDocument5 pagesAspek dan Struktur BahasaSukixyz HaNo ratings yet
- MAHILUNGDocument278 pagesMAHILUNGNagara DahaNo ratings yet
- Bab I: Provided by Repository Universitas Negeri MakassarDocument83 pagesBab I: Provided by Repository Universitas Negeri MakassarTraaNo ratings yet
- Menurunnya Tingkat Penggunaan Bahasa Jawa Dalam Kehidupan MilenialDocument14 pagesMenurunnya Tingkat Penggunaan Bahasa Jawa Dalam Kehidupan Milenialkharisma putriNo ratings yet
- Konsep Plural Dalam Bahasa SundaDocument21 pagesKonsep Plural Dalam Bahasa SundaAndalusia Neneng Permatasari100% (2)
- 1 - Afri Risyofa Rahim - Wujud Sapaan Dalam Bahasa Banjar - Revisi NewDocument13 pages1 - Afri Risyofa Rahim - Wujud Sapaan Dalam Bahasa Banjar - Revisi NewMuhammad Sidiq Al-WafaNo ratings yet
- Jurnal Dewi AfrianiDocument8 pagesJurnal Dewi AfrianiFifianti FifiantiNo ratings yet
- 2172 26448 1 PBDocument8 pages2172 26448 1 PBAlfan AsnunNo ratings yet
- Tugas Bahasa Daerah D'GarnisDocument7 pagesTugas Bahasa Daerah D'GarnisDwi GarnisNo ratings yet
- Putri - Pengaruh Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kehidupan Sehari-HariDocument10 pagesPutri - Pengaruh Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kehidupan Sehari-Hariazizafauru889No ratings yet
- Belajar Bahasa Hungary - Pantas / Mudah / Cekap: 2000 Perbendaharaan Kata UtamaFrom EverandBelajar Bahasa Hungary - Pantas / Mudah / Cekap: 2000 Perbendaharaan Kata UtamaNo ratings yet
- Belajar Bahasa Poland - Pantas / Mudah / Cekap: 2000 Perbendaharaan Kata UtamaFrom EverandBelajar Bahasa Poland - Pantas / Mudah / Cekap: 2000 Perbendaharaan Kata UtamaNo ratings yet
- TRADISI ALAMDocument13 pagesTRADISI ALAMFatchul Mu'inNo ratings yet
- Mengkaji Budaya For RadarDocument5 pagesMengkaji Budaya For RadarFatchul Mu'inNo ratings yet
- Analisis DataDocument2 pagesAnalisis DataFatchul Mu'inNo ratings yet
- Artikel For JurnalDocument9 pagesArtikel For JurnalFatchul Mu'inNo ratings yet