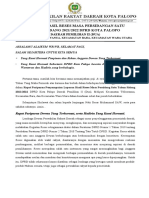Professional Documents
Culture Documents
Pernikahan Dan Tradisi Uang Panaik
Uploaded by
AsdharCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Pernikahan Dan Tradisi Uang Panaik
Uploaded by
AsdharCopyright:
Available Formats
Pernikahan dan Tradisi Uang Panaik Apa yang ada dipikiran Anda tentang uang panaik atau uang
hantaran yang disediakan pihak laki-laki ketika ingin menikahi seorang perempuan di masyarakat Bugis dan Makassar? Saya kira jawaban spontannya adalah mahal dan sangat membebankan laki-laki. Tapi apakah tradisi itu memang bermaksud demikian? Mari menilisiknya dari dekat. Pada awal 2012, seorang sepupu laki-laki saya melangsungkan pernikahan. Acara dibuat sederhana, tapi dihadiri banyak orang. Doa-doa berseliweran dari mulut ke mulut, ada yang melafalkannya dengan keras, sembari menepuk-nepuk pundak. Kurru sumanga (arti bebasnya; semoga jiwamu selalu tegar). Sepupu saya cengengesan saja, memegang tangan orang-orang yang datang, atau menunduk mencium punggung tangan. Selama prosesi perhelatan itu, cerita mengenai uang panaik bersembunyi dari dalam diri masing-masing keluarga dekat. Uang panaik yang selalu jadi momok menakutkan kaum laki-laki seperti tertelan ucapan syukur. Menikah akan membantumu berani, menikah akan membantumu menemukan diri sendiri, kata beberapa orang tua di kampung. Jadi apa sebenarnya uang panaik itu? Benarkah pengertiannya adalah salah satu syarat untuk mendapatkan perempuan. Syarat untuk dengan halal meniduri perempuan. Atau uang panaik atau seperti arti kesehariannya adalah uang naik? Ternyata saya keliru. Uang panaik tidaklah seburuk itu. Cristian Pelras, seorang Doktor Antropolog Prancis, dalam bukunya The Bugis menuliskan bila uang panaik adalah uang hantaran untuk menunjukkan kesanggupan dan keseriusan laki-laki. Menurut dia, harga diri masyarakat Bugis tidak dapat dinilai perempuan pun demikian. Perempuan dalam beberapa hal penting, luwes dan sangat fleksibel. Perempuan bahkan dalam urusan rumah tangga, melainkan punya ruang pendapat dan mengajukan pikiran. melalui uang. Untuk mendapatkan posisi tak dibatasi hanya untuk menentukan
Dalam tradisi Bugis, kedudukan rumah, sebagai tempat asal muasal rencana dan target menentukan kebutuhan dan tempat berlindung, sebagian besar dikuasai perempuan. Masyarakat Bugis bahkan membaginya ruang-ruang dalam sebuah rumah untuk menunjukkan peran-peran dan kekuasaan laki-laki atau suami dan perempuan atau iastri. Bagian teras dan ruang tamu adalah kekuasaan laki-laki. Sementara ruang keluarga, kamar, ruang belakang, dan lantai dua rumah (loteng) wilayah kekuasaan perempuan - lantai dua pun tak boleh dipandang sebelah mata, sebab digunakan menyimpan benih dan perbekalan. Dalam pemahaman Bugis, tidak berarti bahwa wilayah atau ruang kekuasaan perempuan menentukan posisinya sebagai orang yang seharusnya berada di
dalam rumah khususnya dapur dan tidak seharusnya berada di ruang publik. Namun secara simbolis, perempuan merupakan penguasa wilayah rumah dan sekitarnya. Dan laki-laki berada di luar rumah hingga "menjulang ke langit". Tapi pembagian itu tidak berlaku secara kaku. Laki-laki sebagai pencari nafkah. Tapi perempuan juga tak sebatas penunggu nafkah. Dalam keadaan tertentu laki-laki bisa memasuki dapur. Tapi perempuan juga bisa membantu laki-laki, seperti mengarit padi, menumbuk padi atau berdagang. Pembagian wilayah kekuasaan seperti ini mencerminkan pembagian peran yang bersifat cair. Tak heran, konsep keseimbangan antara laki-laki dan perempuan seperti inilah yang menjadikan Bugis selalu mendapat sanjungan dan kekaguman. Di BUKU The Bugis itu, Pelras menulis dan menganalisis masyarakat Bugis melalui pendalaman dari epik I La Galigo. Sebuah mitologi spiritual milik masyarakat Sulawesi Selatan. Mitologi yang diperkirakan muncul saat kerajaan Luwu mencapai masa jaya, pada abad 12. Beberapa orang menganggap mitologi La Galigo adalah kejadian nyata yang pernah terjadi. Kejadian tentang pengisian dunia tengah oleh para dewa dari langit dan penghuni dari dunia bawah. Meskipun saya sendiri, menganggap La Galigo hanyalah karya yang begitu mengagumkan. Saya bertemu dengan Andi Anton Pangerang, seorang tokoh masyarakat di Luwu. Dia banyak bercerita tentang isi mitologi itu. Menurutnya, La Galigo sebagai sebuah mitologi yang lahir dan dibungkus dengan spiritual. Jadi masyarakat menganggapnya ada. Ramayana di Jawa adalah sebuah mitologi, tapi bukan mitologi spiritual. Makanya di Jawa tak ada yang mengaku sebagai keturunan Bima, Rama, atau tokoh-tokoh lainnya. Tapi di Bugis, masyarakat kita masih manyatakan diri mereka sebagai keturunan Sawerigading atau La Galigo, katanya. Saya tercenung dengan penjelasannya itu. Akhirnya saya menemukan keasyikan tersendiri membaca terjemahan epik I La Galigo itu. Epik itu tak sekedar bercerita tentang lingkungan, melainkan merentang hingga pergaulan hidup, keuletan, ketekunan, intrik, hingga tingkah laku. Salah satunya, dikisah penebangan pohon Walenrenge - pohon kehidupan oleh Sawerigading (tokoh utama dalam epik) mendapat pertentangan masyarakat. Kisah ini mengisahkan drama penting tentang keteguhan hingga keserakahan manusia. Sebab Sawerigading membutuhkan pohon besar itu untuk membuat perahu menuju kerajaan Tanete dalam rangka mempersunting putri cantik We Cudai. Ketika perahu siap berlayar, bersama rombongan dan pengikut, dia mengunjungi We Cudai. Alhasil Sawerigading ditolak. Lalu dengan geram dan berbagai strategi, hingga terjadi perang, kerajaan Tanete ditundukkan. Namun siapa sangka, kekuasan akan wilayah, tak semudah menundukan hati.
Akhirnya proses lamaran tetap dilakukan. Rombongan kapal dari kerajaan Luwu menuju Tanete membawa erang-erang (seserahan) untuk menyenangkan We Cudai pun tak berhasil. Sawerigading tak patah semangat, melalui bantuan saudari perempuannya, We Tenriabeng ketika itu sudah bermukim di langit We Cudai akhirnya takluk. Tapi persoalan tak sesederhana itu, untuk mendapatkan persetujuan tidur bersama, Sawerigading membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tradisi membujuk pasangan setelah menikah, ternyata bertahan hingga periode tahun 1980-an. Dari mulai mengetuk pintu kamar, membuka helai kelambu,dan izin untuk tidur sekamar. Untuk melakukan itu, dibutuhkan kesabaran dan tahapan yang panjang. Hingga akhirnya pasangan tersebut bisa melakukan hubungan suami istri. Namun bila tak berhasil membujuk, pernikahan bisa saja berujung perceraian. Menurut saya, laku ini menunjukan derajat perempuan yang tak mudah ditaklukkan. Hal ini pun mengingatkan kita, ketika menonton pertunjukan tari Pakarena dari Makassar, dengan gerakan yang lembut, halus dan tenang. Tapi membutuhkan kekuatan yang besar. Dimana perempuan memperlihatkan konsistensi dan pertahanan. Semakin keras musik berdentang, semakin lembut gerakan tarinya. Bahkan ketika pesta pernikahan di rumah perempuan, orang tua mempelai lakilaki tidak dibolehkan mendatangi rumah pengantin perempuan. Kemudian saat marola atau mengunjungi rumah suami, biasanya tetap dilakukan pesta dan hajatan pernikahan, tapi pembacaan akad nikah sudah tak ada lagi sebab sudah dilakukan di rumah perempuan. Dan setelah marola, perempuan akan tetap pada harga dirinya. Tidak diperbolehkan menginap di rumah suami. Harus tetap di rumahnya hingga dijemput oleh suami dan keluarganya. Setelah pesta penikahan usai, laki-laki untuk sementara waktu tinggal di rumah perempuan, yang merupakan daerah utama kekuasannya. Di rumah perempuan, laki-laki atau suami tentu tak dapat melakukan apa-apa sebab tidak menguasai rumah istri. Laki-laki kebanyakan duduk di ruang tamu dan teras atau bahkan di kamar. Dan hanya bicara seadanya. Tapi sekarang mulai pudar, sebab pasangan yang dinikahkan tidak lah melalui perjodohan yang panjang, atau penunjukan secara langsung oleh anggota keluarga yang memiliki kewenangan. Melainkan melalui pacaran atau pengenalan yang sudah lama, masing-masing calon. TAHUN ini saya berencana akan menikah. Mempersunting seorang perempuan. Dan apakah tetap menyiapkan uang panaik? Seberapa besar dan seberapa pantas kah nilainya. Jika uang panaik menjadi penentu atau syarat perkawinan, saat ini tentu hal itu tak begitu ketat. Meskipun tetap menjadi tanggungjawab sang laki-laki, namun sudah dapat dilakukan kompromi. Misalnya pasangan laki-laki dan perempuan akan saling membantu.
Tapi, meski demikian saya masih merasa gusar dengan embel-embel tersebut. Di kalangan anak muda sebaya saya, uang panaik masih menjadi beban. Sebab bisa dijadikan sebagai standar status sosial, ajang pamer dan bahkan bahan gunjingan. Saat ini, besaran uang panaik tak main-main dan ditentukan oleh keluarga perempuan. Bisa mencapai puluhan juta rupiah. Uang panaik yang jumlahnya tak mencapai puluhan juta rupiah tak akan diumumkan saat melakukan prosesi akad nikah. Bahkan kadang-kadang jumlah nilai uang panaik diumumkan lebih dari sebenarnya. Artinya uang panaik saat ini, telah bergeser makna menjadi ajang pamer kemampuan bagi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Biasanya masyarakat akan membicarakan nilai uang panaik yang besar, hingga berbulanbulan. Uang panaik itu penting, untuk biaya operasional. Tapi jika menjadi ajang pamer itu yang salah, kata Akbar Thalib yang sudah menikah empat tahun lalu. Eko Rusdianto
You might also like
- Paripurna HASIL RESES MASDING I TAHUN 2021-2022 DAPIL IIDocument4 pagesParipurna HASIL RESES MASDING I TAHUN 2021-2022 DAPIL IIAsdharNo ratings yet
- Laporan PendampingDocument5 pagesLaporan PendampingAsdharNo ratings yet
- Hasil Uji Asumsi KlasikDocument5 pagesHasil Uji Asumsi KlasikAsdharNo ratings yet
- Hasil Uji Asumsi KlasikDocument5 pagesHasil Uji Asumsi KlasikAsdharNo ratings yet
- Lampiran Penelitian Muh. Syaiful. SDocument13 pagesLampiran Penelitian Muh. Syaiful. SAsdharNo ratings yet
- Laporan Reses - Alfri JamilDocument4 pagesLaporan Reses - Alfri JamilAsdharNo ratings yet
- PerpaniDocument1 pagePerpaniAsdharNo ratings yet
- Apa Yang Anda Ketahui Tentang Feature Dan ArtikelDocument1 pageApa Yang Anda Ketahui Tentang Feature Dan ArtikelAsdharNo ratings yet