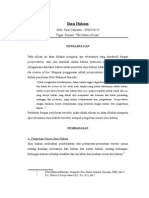Professional Documents
Culture Documents
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Berdasarkan Persepektif Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dan Pendekatan Filsafat Hukum
Uploaded by
fajarcsOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Berdasarkan Persepektif Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dan Pendekatan Filsafat Hukum
Uploaded by
fajarcsCopyright:
Available Formats
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan ada dua pandangan
yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan
perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya
merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah
perkawinan. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan
perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan
1
.
Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa menurut
pandangan yang pertama, sahnya suatu perkawinan hanya didasarkan pada
aturan-aturan agama, sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 2 ayat (1) UUP.
Artinya pencatatan perkawinan pada Kantor Pencatatan Perkawinan secara
hukum tidak menjadi syarat sahnya suatu perkawinan, sedangkan menurut
pandangan yang kedua, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP harus dipandang
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Terhadap dua pandangan tersebut,
hingga saat ini belum ditemukan suatu titik temu.
Terkait dengan adanya dualisme pencatatan perkawinan tersebut di atas,
ditemukan putusan hakim yaitu Putusan No. : 05 / Pdt.G/ 2011 / PN. Kbj,
dimana di dalamnya ditemukan indikasi permasalahan terkait pencatatan
perkawinan.
B. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:
1. Bagaimana akibat hukum pencatatan perkawinan terhadap hak waris?
2. Bagaimana kesesuaian Putusan Nomor terhadap mazhab pencatatan
perkawinan yang berlaku di Indonesia?
1
Faizah Bafadhal, Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan, Jurnal Ilmu
Hukum Vol. 2 No. 2, (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2012), hal. 25.
C. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Membahas dengan detil mengenai akibat hukum pencatatan perkawinan
terhadap hak waris.
2. Membahas dengan detil kesesuaian putusan hakim No. : 05 / Pdt.G/ 2011 /
PN. Kbj terhadap mazhab pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia.
D. Metode Penelitian
Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian
E. Sistematika Penulisan
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. PENCATATAN PERKAWINAN
1. Menurut Undang-Undang
a. Pengertian Perkawinan
Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(UU No. 1/1974) ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
b. Syarat-Syarat Perkawinan
Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal
12 UU No. 1/1974. Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut dapat
dibedakan menjadi 2, yaitu:
1) Syarat Materiil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan
diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang
harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan.
2
Syarat-
syarat materiil terdiri dari:
3
a) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak
(Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
b) harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing
calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU
Perkawinan).
c) bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun,
kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat
2
Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 21.
3
Jurnal Hukum, Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perkawinan
(http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan)
lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat
(1) dan (2) UU Perkawinan).
d) bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi
mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9
Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan).
e) bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua
kali dan seterusnya, udang-undang mensyaratkan setelah lewatnya
masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus
perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus
perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UU
Perkawinan).
2) Syarat Formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara
pelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun
syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan.
4
Syarat-syarat
formil terdiri dari:
5
a) Laporan
b) Pengumuman
c) Pencegahan
d) Pelangsungan
c. Syarat Sahnya Perkawinan
Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu.
Penjelasan Pasal 2 menentukan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat
(1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945,
yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan
4
Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 21.
5
Jurnal Hukum, Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perkawinan
(http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan)
yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang
tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
6
Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974, Tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan perkawinan selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai
Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil, sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UU No. 1/1974 (PP No. 9/1975).
Perkawinan yang sah juga wajib dilaporkan kepada Instansi
Pelaksana di tempat dilaksanakannya perkawinan paling lambat 60 hari
sejak tanggal perkawinan yang dicatat pada Register Akta Perkawinan
dan atas pencatatan tersebut maka dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan,
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (UU No. 23/2006)
Pasal 34 ayat (1) berbunyi:
Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang- undangan wajib
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat
terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
perkawinan.
ayat (2) berbunyi:
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan
menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
Apabila suami atau istri tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan
Akta perkawinan maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah
adanya penetapan pengadilan.
Pasal 36 PP No. 1/1975, berbunyi:
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan,
pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan
pengadilan.
Akte perkawinan adalah sama dengan akta yang lain yang penting seperti
akte kelahiran, akte kematian, berarti bahwa akte perkawinan pun adalah
alat bukti tentang peristiwa yang diterangkan di dalamnya, yang
membuktikan bahwa perkawinan yang dimaksud di dalam perkawinan
itu benar telah dilangsungkan.
Oleh karenanya dapat disimpulkan syarat sahnya perkawinan adalah
dilakukan menurut agamanya masing-masing dan perkawinan tersebut
harus dicatat.
7
6
Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 12.
Undang-undang perkawinan tidak secara rinci mengatur mengenai bukti
perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 100-102 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata. Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
menentukan bahwa: Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan
dengan cara lain, melainkan dengan akta pelangsungan perkawinan itu,
yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil.
8
Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa:
Apabila ternyata, bahwa register-register itu tak pernah ada, atau telah
hilang atau pula akta perkawinanlah yang taka da di dalamnya, maka
terserahlah pada pertimbangan hakim soal cukup atau tidaknya bukti-
bukti itu, asal saja hubungam selaku suami-isteri jelas nampaklah
adanya.
9
2. Concurring Opinion
10
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memuat
mengenai permohonan uji materiil yang dilakukan oleh Machica Mochtar
terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.
Terkait hal tersebut, dalam makalah ini akan difokuskan pada permohonan
uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai
pencatatan perkawinan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pokok permasalahan
hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-
undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan
perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4
huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan
menyatakan:
... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping
itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama
7
Ibid., hal. 57.
8
Ibid.
9
Ibid.
10
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan
seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-
surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan
perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya
perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang
diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-
syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon
mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui
peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna
pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut,
menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif.
Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan
dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang
merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD
1945). Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan,
pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan
ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-
Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).
Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara
dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam
kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi
terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat
dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga
perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul
dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif
dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak
yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani
dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan
waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian
mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang
mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta
otentik, maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan
yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan
efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.
Dengan melihat sikap Mahkamah Konstitusi yang menolak
membatalkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dapat
dibaca bahwa Mahkamah Konstitusi masih menghendaki dan setuju bahwa
semua perkawinan di Indonesia haruslah tercatat. Alias tercatat di hadapan
hukum Negara (baik oleh aparat Kantor Urusan Agama maupun Kantor
Catatan Sipil). Lebih jauh lagi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut dimuat alasan berbeda (concurring opinion) dari Prof. Maria Farida
Indrati, yaitu sebagai berikut:
Pertama
Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kemudian mengenai syarat sahnya perkawinan, Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun
1974 menyatakan bahwa:
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan
ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974
karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun
1974 tersebut tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara
administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan
yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing,
ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya
perkawinan yang dilakukan. Keberadaan norma agama dan norma hukum
dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi
untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi
saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU
Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin
bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya
juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya
mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika
telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.
Jika Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dimaknai sebagai
pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau
tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan
UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan.
Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga
perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan
kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya
hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat di
masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan
kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang
memiliki kekuatan pemaksa.
Kedua
Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara
kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari
kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan
secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama
dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan
diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan
kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk
melegitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga
pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya
penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena
kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain
sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan
perkawinan secara utuh. Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi,
adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan
perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks
utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari
perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan
sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari
penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat
agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat
dihindari dan ditolak.
Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai
upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum
perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang
pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya
Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Dalam hal ini Prof.
Maria Farida Indrati berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan
dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi
kependudukan. Ia berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama
dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi
kependudukan.
Ketiga
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu
dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada
kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang
mengabaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan hanya
menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan
kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau
kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974
yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan
dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita
sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan
tersebut.
Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1
Tahun 1974 yang menyatakan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah bertentangan dengan
Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Prof.
Maria Farida Indrati menilai, Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974
tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2
ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan pencatatan, meskipun
faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun
ketiadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan
ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal
dari sejumlah pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi
tidak dicatatkan. Selain itu, hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat
(2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2
ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan pencatatan
perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal
28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat
dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan, sehingga dengan
mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban
terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang
dimaksudkan untuk memberikan jaminan at as status dan akibat hukum dari
suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan
kematian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Prof. Maria Farida
Indrati tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon
sebagai akibat keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.
Keempat
Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya
pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam
hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau
secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan
hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum
ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak
bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai
implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-
friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek
hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan
semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-
friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan
perundang-undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme
hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang
mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi
pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan
semacam ini mendapatkan pembenarannya dalam paham
konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan
dengan tegas bahwa:
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang
hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang
pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau
kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai
bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu
perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita,
sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait
dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-anak sebagaimana telah
diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak
didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi
wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan
dimaksud.
Kelima
Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat
dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau
kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat
privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya, sedangkan
norma hukum, dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974, merupakan
ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga
(masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya
oleh negara (Pemerintah). Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak
didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974, bagi wanita (istri) sangat
beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut
dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU Nomor 1 Tahun
1974, terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam
konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah)
terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai
istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai
dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang salah satu syaratnya adalah
perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974).
Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa
dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status
perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari
sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri)
harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri)
dengan suaminya.
Keenam
Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974
juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak
diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya,
yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak
kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak
keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya
mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga selalu
merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu
keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak
dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau
tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma
negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi
kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang
sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan
bapak biologisnya.
Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan
terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan
diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai
tindakan yang diskriminatif. Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan
ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan,
Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Keberadaan Pasal tersebut
menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan
dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang
tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU
Nomor 1 Tahun 1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut
menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua
orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun
hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak
harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua
orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah dosa turunan. Dengan kata
lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai
dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan
wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus
ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan
demikian, menurut Prof. Maria Farida Indrati, pemenuhan hak-hak anak
yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya
perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua
orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.
3. Penyelundupan Hukum dan Itikad Baik
Secara sederhana sesungguhnya, pengertian penyelundupan hukum
dapat dipahami sebagai berikut:
Penyelundupan hukum adalah proses, cara, perbuatan menyelundup
11
.
Samuel W. Buell juga membahas penyelundupan hukum atau law evasion
dengan definisi: A common understanding of evasion is that it involves
something like violating the spirit of the law.
12
Dalam memahami penjelasan penyelundupan hukum di atas, perlulah
dibahas pula mengenai sifat melawan hukum. Melawan hukum dalam
hukum keperdataan saat ini diartikan dalam arti luas sebagai berikut
13
:
a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau
11
Aditya Wirawan, Kajian Yuridis Perkawinan Semu sebagai Upaya untuk Memperoleh
Kewarganegaraan Indonesia, (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 2008), hal. 45.
12
Samuel w. Buell, Good Faith and Law Evasion, UCLA Law Review 58, (February
2011), hal. 622.
13
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), (Bandung:
Citra Aditya bakti, 2005), hal. 11.
e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam
bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist
tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt
ten aanzien van anders persoon of goed)
Sementara itu, mengenai sifat melawan hukum, juga dapat dilihat dari
sudut hukum pidana. Terkait hal tersebut terdapat dua ajaran, yaitu ajaran
formal dan ajaran materiel, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Secara singkat ajaran sifat melawan-hukum yang formal mengatakan
bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang
termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak
pidana. Jika ada alasan-asalan pembenar, maka alasan-alasan tersebut
harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang
14
.
b. Ajaran materiel mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat
formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan
delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai
perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini
mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan
perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak
tertulis
15
.
Jadi, sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa Penyelundupan Hukum
dalam kaitannya dengan sifat Melawan Hukum terjadi apabila suatu
perbuatan secara menyelundup bersesuaian dengan (tidak melanggar)
ketentuan hukum secara formal, namun secara materiel bertentangan dengan
semangat yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum baik itu hukum
tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Untuk mengatasi penyelundupan hukum, Samuel W. Buell
menyatakan bahwa dapat digunakan doktrin itikad baik untuk mencegah
penyelundupan hukum itu. Menurutnya, good faith, used in this fashion,
14
Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel dalam Hukum
Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 25.
15
Ibid.
is an anti-evasion device.
16
. The duty to act in good faith prevents sharp
dealing and opportunistic behavior.
17
.
B. PEMBAGIAN HARTA WARISAN
1. Hukum Waris Perdata/Barat
a) Pengertian
Dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) hukum waris
merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengertian
mengenai hukum waris terdapat pada buku II, tentang benda.
Pengertian mengenai hukum kewarisan pada KUH Perdata tidak
disebutkan secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan
pengertian hukum waris menurut KUH Perdata, sebagai berikut:
1) Pitlo
Kumpulan pengaturan yang mengatur hukum yang mengatur
kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan
kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat hubungan
antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara
mereka dengan pihak ketiga.
18
2) Sudarsono dalam bukunya menuliskan beberapa pengertian hukum
waris menurut beberapa ahli hukum, yaitu:
a. Mr. Dr. H. D. M. Knol, menyatakan bahwa hukum waris
mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta
peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada seorang
ahli waris atau lebih.
b. A. Wrinkle Prins, menyatakan bahwa hukum waris adalah
seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan
sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan
16
Samuel W. Buell, Good Faith and Law Evasion, UCLA Law Review 58, hal. 630.
17
Ibid., hal. 629.
18
Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (alih
bahasa M. Isa Arief, SH), (Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 1.
hukum dari seorang yang telah meninggal dunia pindah ke
orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh
keturunannya.
19
c. Vollmar, menyatakan bahwa hukum waris adalah perpindahan
dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban, dari orang yang mewariskan
kepada warisnya.
20
Menurut Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya berlangsung
karena kematian. Jadi pewarisan akan terjadi ketika pewaris meninggal
dunia dan pada saat terjadinya pewarisan tersebut ahli warisnya masih
hidup.
b) Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata
Menurut Wirjono Prodjodikoro unsur-unsur kewarisan dalam KUH
Perdata ada beberapa hal, yaitu:
1. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan
kekayaan,
2. Seseorang atau beberapa orng ahli waris yang berhak menerima
kekayaan yang ditinggalkan itu
3. Harta warisan, yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih
kepada ahli waris
21
c) Syarat Terjadinya Pewarisan kepada Ahli Waris
1. Syarat yang berhubungan dengan pewaris:
Untuk terjadinya pewarisan, maka pewaris harus meninggal dunia
terlebi dahulu, sesuai dengan pasal 830 KUH Perdata. Meninggal
dunia dari pewaris dapat dibedakan menjadi:
19
Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal.
12
20
Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta,
(Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hal. 373.
21
M. Ramulyo Idris, Perbadingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 85.
a. Maeninggalnya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh,
yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-
benar telah meninggal dunia,
b. Meninggal/mati demi hukum yang dinyatakan oleh pengadilan,
yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut
kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.
2. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris:
Orang-orang yang berhak menjadi ahli waris harus sudah ada atau
masih hidup saat meninggalnya pewaris. Hidupnya ahli waris dapat
dimungkinan dengan hal-hal sebagai berikut:
a. Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang
masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra,
b. Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan
masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam
kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata)
d) Tidak Patut Menerima Warisan (Onwaardig)
1. Ahli waris yang tidak patut menurut undang-undang untuk
menerima warisan dalam Pasal 838 KUH Perdata adalah:
a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah
membunuh atau mencoba membunuh pewaris,
b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan
karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si
pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan
kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun atau
lebih.
c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah
si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan
surat wasiat si pewaris.
2. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk
menerima warisan sesuai dengan Pasal 912 KUH Perdata adalah:
a. Mereka yang telah dihukum karena membunuh pewaris
b. Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan, atau
memalsukan surat wasiat si pewaris.
c. Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si
pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.
22
e) Cara Mendapatkan Warisan
Dalam undang-undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan,
yaitu:
1. Ab intestato ( ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832
KUH Perdata, yaitu yang berhak menerima bagian warisan adalah
para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami
atau istri yang hidup terlama.
2. Testamentair (ahli waris karena ditunjuk melalui wasiat testamen)
dalam Pasal 899 KUH Perdata, yaitu pewaris membuat wasiat
dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.
f) Asas Hukum Waris Perdata
1. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan
harta benda saja yang dapat diwariskan
2. Adanya saisine bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan
sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik
atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari
seorang yang meninggal dunia
3. Asas kematian, yaitu pewarisan hanya karena kematian
4. Asas individual, yaitu ahli waris adalah perorangan (secara pribadi)
bukan kelompok ahli waris
5. Asas bilateral, yaitu seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga
pihak ibu
22
Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hal. 58.
6. Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya dekat dengan
pewaris, menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.
23
g) Ahli Waris Pengganti
Hal ini diatur dalam Pasal 854-857 KUH Perdata dihubungkan dengan
Pasal 860 dan 866 KUH Perdata. Penggantian ahli waris atau
Plaatsvervulling adalah memberikan hak kepada orang yang
menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan
dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam
Pasal 841 KUH Perdata, yang misalnya seorang cucu yang
menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku
anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis
lurus kebawah yang sah,berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat
1 KUH Perdata).
Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan
anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah
meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan
paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan
paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama
(Pasal 844 KUH Perdata).
C. PENGGOLONGAN AHLI WARIS
Para ahli waris yang sah karena kematian terpanggil untuk mewaris
menurut urutan dimana mereka itu terpanggil untuk mewaris. Urutan tersebut
dikenal ada empat macam yang disebut golongan ahli waris.
24
Golongan ahli
waris tersebut terdiri dari:
1 Ahli Waris Golongan Pertama
Ahli waris golongan pertama terdiri dari:
a. Anak-anak dan keturunannya
Perkataan dan/atau disini dimaksudkan karena anak-anak tidak
dapat mewaris bersama-sama dengan keturunan, satu akan
23
M. Ramulyo Idris, Perbadingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 95-96.
24
Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan
Menurut Undang-Undang, (Depok: Prenada Media Group, 2010), hlm. 49.
menutup yang lain.
25
Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan
bahwa anak mewaris bersama keturunan yaitu dalam hal terjadi
penggantian.
b. Suami atau istri yang hidup terlama
Di Indonesia sejak Januari 1936, istri atau suami yang hidup
terlama sebagai ahli waris termasuk golongan I, besarnya bagian
istri/suami yang hidup terlama dalam Pasal 852a KUHPerdata
ditentukan sama dengan bagian anak.
2 Ahli Waris Golongan Kedua
Ahli waris golongan kedua yaitu:
orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan dan keturunan saudara
laki dan perempuan tersebut.
Ahli waris golongan kedua diatur dalam pasal berikut ini:
Pasal 854 ayat (1) KUHPerdata, menentukan:
Apabila seorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan
maupun suami istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka
masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal
hanya meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan, yang mana
mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing
mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang
saudara laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya
menjadi bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu.
3 Ahli Waris Golongan Ketiga
Ahli waris golongan ketiga terdiri dari : keluarga sedarah dalam garis lurus
ke atas, sesudah orang tua.
Pasal 853 KUHPerdata mengatakan bahwa ahli waris golongan ketiga ini
terdiri dari sekalian keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah
maupun ibu.
Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan garis ibu ke atas
adalah kakek dan nenek, yakni ayah dan ibu dari ayah dan ibu dan ayah
dari ibu pewaris.
26
4 Ahli Waris golongan Keempat
Ahli waris golongan keempat yaitu keluarga sedarah lainnya dalam garis
menyimpang sampai derajat ke enam.
27
25
Ibid., hal. 50.
26
Ibid., hal. 72.
27
Ibid., hal. 76.
Golongan keempat diatur dalam pasal 858 KUHPerdata sebagaimana
menyatakan:
Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada
keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka
separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam
garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi
bagian keluarga sedarah garis ke samping dan garis ke atas lainnya kecuali
dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut.
BAB III
PEMBAHASAN
A. Kasus Posisi
Pewaris adalah anak laki-laki dari Penggugat. Selama hidupnya, pewaris
pernah melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan di catatan sipil dengan
Tergugat. Sebagai bukti bahwa Pewaris dan Tergugat pernah melaksanakan
perkawinan, terdapat akta pemberkatan nikah yang dikeluarkan oleh pendeta
Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Dari hubungan tersebut tidak terdapat anak.
Penggugat menuntut agar harta waris diberikan padanya, dengan
mendalilkan bahwa Pewaris dan Tergugat hanyalah hidup serumah, tidak ada
pencatatan di catatan sipil dan tidak terdapat surat nikah, Tergugat bukanlah istri,
dengan demikian bukan merupakan ahli waris.
Sementara itu, Tergugat menyatakan bahwa dirinya adalah istri, bahwa
benar walaupun tidak dicatatkan di catatan sipil, namun terdapat perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan agama Kristen dan adat Batak, dengan demikian
perkawinannya telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, dan mengemukakan
bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif saja.
Tergugat mendalilkan bahwa dirinya adalah istri dan ahli waris sah satu-satunya,
oleh karena tidak ada anak.
Berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim
kemudian menyetujui pandangan bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan
tindakan administratif saja, namun kemudian Majelis hakim juga mengakui bahwa
baik Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris, bahwa kemudian Majelis Hakim
juga memutuskan bahwa Penggugat (bersama dengan saudara-saudara Pewaris)
dan Tergugat secara bersama berhak atas harta waris, yaitu bagi Penggugat (dan
saudara Pewaris) sebesar 7/8 bagian, sementara Tergugat berhak atas 1/8 bagian.
B. Pencatatan Perkawinan
B.1. Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang
Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Perumusan undang-
undang seperti ini berdasarkan ilmu perundang-undangan merupakan norma
hukum tunggal, artinya adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak
diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya merupakan suatu
suruhan (das Sollen) tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau
bertingkah laku
28
.
Perumusan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 tersebut,
merupakan tindakan yang dikehendaki, namun tidak secara tegas mengandung
perintah, kebolehan, atau larangan. Hal ini menyebabkan adanya ambiguitas.
Namun demikian, dapat diketahui bahwa Pasal 66 UU No. 1/1974
menyatakan, Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya
Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen
(Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan
Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158),
dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah
diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
Masalah pembuktian perkawinan, adalah tidak diatur berdasarkan Undang-
undang Perkawinan, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, maka
dikembalikan pada peraturan lain. Peraturan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal
100 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa: Adanya
suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta
pelangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register
catatan sipil. Kemudian, pasal 101 KUHPerdata lebih lanjut menerangkan
bahwa: apabila ternyata, bahwa register-register itu tak pernah ada, atau telah
hilang atau pula akta perkawinanlah yang tak ada di dalamnya, maka terserahlah
28
Maria Farida Indrtati, Ilmu Perundang-undangan, Jilid 1, (Yogyakarta: Kanisius, 2007),
hal. 31.
pada pertimbangan hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti itu, asal saja
hubungan selaku suami isteri jelas nampaklah adanya.
Pada peraturan perundang-undangan yang lebih modern, yaitu Pada
Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: Perkawinan yang sah
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh
Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Terhadap ketentuan ini,
terdapat sanksi, yaitu padal Pasal 90 ayat (1) huruf b, Setiap Penduduk dikenai
sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan
Peristiwa Penting dalam hal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4). Sayangnya ketentuan ini hanya merupakan sanksi
administratif saja.
Baik pengaturan pada UU Perkawinan maupun UU Adminduk, keduanya
secara tidak langsung telah mempertegas bahwa pencatatan perkawinan
merupakan tindakan administratif. Pun demikian, dapatlah diketahui bahwa
tindakan administratif tersebut adalah diwajibkan. Hal ini dapat diketahui
berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau
prinsip-prinsip perkawinan menyatakan:
... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di
samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah
sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan
dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar
pencatatan.
Hal mengenai pencatatan perkawinan ini penting oleh karena, apabila
suami atau istri tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta
perkawinan maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah adanya
penetapan pengadilan.
Pasal 36 PP No. 1/1975, berbunyi:
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan,
pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa bukti-bukti lain, selain akta
perkawinan, tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa perkawinan telah lahir
dan akibat dari perkawinan tersebut harus dilaksanakan (misalnya, kewajiban
suami isteri). Artinya, bukti sebagaimana disebutkan pada Pasal 101 KUHPerdata,
misalnya: hubungan selaku suami istri nampak jelas adanya, hanya dapat
digunakan untuk mendapatkan penetapan pengadilan terkait adanya perkawinan.
Jika kemudian perkawinan atas penetapan pengadilan tersebut sudah ada, haruslah
ia dicatatkan berdasarkan Pasal 35 jo. Pasal 34 UU Adminduk, barulah
perkawinan tersebut memenuhi kewajiban administratif dan mendapatkan
perlindungan hukum dari negara.
B.2. Pencatatan Perkawinan menurut Doktrin
1. Ahmad Rofiq
29
Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan
tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu
pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya
hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan
yang dilangsungkannya.
2. Wahyono Darmabrata
30
Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974, Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan perkawinan selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai
Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil, sebagaimana yang tercantum
dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.
1/1974 (PP No. 9/1975).
Perkawinan yang sah juga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di
tempat dilaksanakannya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal
perkawinan yang dicatat pada Register Akta Perkawinan dan atas pencatatan
tersebut maka dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan, sebagaimana yang
29
Faizah Bafadhal, Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan, Jurnal Ilmu
Hukum Vol. 2 No. 2, (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2012), hal. 27.
30
Ibid., hal. 57
tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006)
Pasal 34 ayat (1) berbunyi:
Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang- undangan wajib
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya
perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
ayat (2) berbunyi:
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan
Kutipan Akta Perkawinan.
Apabila suami atau istri tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan
Akta perkawinan maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah adanya
penetapan pengadilan.
Pasal 36 PP No. 1/1975, berbunyi:
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan,
pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
Akte perkawinan adalah sama dengan akta yang lain yang penting seperti
akte kelahiran, akte kematian, berarti bahwa akte perkawinan pun adalah alat
bukti tentang peristiwa yang diterangkan di dalamnya, yang membuktikan bahwa
perkawinan yang dimaksud di dalam perkawinan itu benar telah dilangsungkan.
Oleh karenanya dapat disimpulkan syarat sahnya perkawinan adalah
dilakukan menurut agamanya masing-masing dan perkawinan tersebut harus
dicatat.
3. Maria Farida Indrati
31
Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat
yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.
Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-
undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban
administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat
dilihat dari dua perspektif.
Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam
rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung
jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang
31
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
(vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan dimaksud
dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak
bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan
dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (vide
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).
Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara
dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam
kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya
akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti
yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan
oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang
bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.
4. Gouw Giok Siong
32
Menurut Gouw Giok Siong perkawinan dibawah tangan adalah suatu
bentuk perkawinan yang merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang
diam-diam pada sebagian masyarakat muslim Indonesia. Mereka berusaha
menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan
menurut Undang-undang Perkawinan yang birokratis dan berbelit-belit serta lama
pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan
dengan hukum Islam (hukum agamanya). Dalam ilmu hukum, cara seperti ini
dikenal dengan istilah Penyelundupan Hukum, yaitu suatu cara menghindari diri
dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh UU dan peraturan yang berlaku
dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum
yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang
dikehendaki.
32
Faizah Bafadhal, Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan, Jurnal Ilmu
Hukum Vol. 2 No. 2, (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2012), hal. 28.
5. Kesimpulan
Dari doktrin-doktrin yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa
pencatatan perkawinan sebagai tindakan administratif merupakan kewajiban,
dimana jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, selain terdapat sanksi
administratif, maka perkawinan tersebut sah menurut agama, namun tidak
memiliki kekuatan secara hukum negara.
C. Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dan Penyelundupan Hukum
Menurut Gouw Giok Siong, perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan
Penyelundupan Hukum, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan
hukum yang ditentukan oleh UU dan peraturan yang berlaku dengan tujuan
perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak
dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.
Samuel W. Buell juga membahas penyelundupan hukum atau law evasion
dengan definisi: A common understanding of evasion is that it involves
something like violating the spirit of the law.
33
Dalam memahami penjelasan penyelundupan hukum di atas, perlulah
dibahas pula mengenai sifat melawan hukum. Melawan hukum dalam
hukum keperdataan saat ini diartikan dalam arti luas sebagai berikut
34
:
a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau
e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam
bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist
tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt
ten aanzien van anders persoon of goed)
33
Samuel w. Buell, Good Faith and Law Evasion, UCLA Law Review 58, (February
2011), hal. 622.
34
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), (Bandung:
Citra Aditya bakti, 2005), hal. 11.
Sementara itu, mengenai sifat melawan hukum, juga dapat dilihat dari
sudut hukum pidana. Terkait hal tersebut terdapat dua ajaran, yaitu ajaran
formal dan ajaran materiel, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Secara singkat ajaran sifat melawan-hukum yang formal mengatakan
bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang
termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak
pidana. Jika ada alasan-asalan pembenar, maka alasan-alasan tersebut
harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang
35
.
b. Ajaran materiel mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat
formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan
delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai
perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini
mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan
perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak
tertulis
36
.
Jadi, sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa Penyelundupan Hukum
dalam kaitannya dengan sifat Melawan Hukum terjadi apabila suatu
perbuatan secara menyelundup bersesuaian dengan (tidak melanggar)
ketentuan hukum secara formal, namun secara materiel bertentangan dengan
semangat yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum baik itu hukum
tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Seperti telah dikemukakan, bahwa menurut undang-undang, ketentuan
mengenai kewajiban pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat
multitafsir. Namun, berdasarkan penjelasan undang-undang perkawinan dan
doktrin yang ada, dapat diketahui bahwa jiwa (spirit) yang dikehendaki dari
adanya pencatatan adalah kepastian hukum pembuktian akan adanya
perkawinan dan perlindungan terhadap pihak yang terkait dengan
perkawinan itu serta pihak ketiga. Jika kemudian, lembaga perkawinan yang
secara redaksional memungkinkan adanya perkawinan tak tercatat, namun
35
Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel dalam Hukum
Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 25.
36
Ibid.
melanggar jiwa (spirit) dari pencatatan perkawinan tersebut, maka
perkawinan tersebut merupakan penyelundupan hukum.
Samuel W. Buell menyatakan bahwa dapat digunakan doktrin itikad
baik untuk mencegah penyelundupan hukum itu. Menurutnya, good
faith, used in this fashion, is an anti-evasion device.
37
. The duty to act in
good faith prevents sharp dealing and opportunistic behavior.
38
.
Artinya, doktrin itikad baik dapat dijadikan ukuran apakah suatu perbuatan
atau peristiwa (termasuk perkawinan tak tercatat) merupakan suatu
penyelundupan hukum.
Dalam suatu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, sangat
dimungkinkan absennya pegawai pencatat nikah untuk melaksanakan
pencatatan perkawinan di daerah tersebut. Dalam hal demikian, tidak
dilaksanakannya pencatatan perkawinan tersebut memiliki itikad baik,
bahwa tidak dilaksankannya pencatatan perkawinan memang disebabkan
oleh keadaan absennya pegawai pencatat nikah.
Itikad buruk adalah nyata, dalam hal perkawinan tidak dicatatkan oleh
pihak yang melangsungkan perkawinan, padahal ia berada dalam jangkauan
pegawai pencatat nikah (misalnya, ia tinggal di kota besar), dengan tujuan
tertentu, menghindari atau memperoleh akibat hukum tertentu.
D. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan terhadap Hak Waris
Terhadap pencatatan perkawinan, terdapat dua pandangan, yaitu: Pertama,
pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi
syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif
sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. Kedua, pandangan yang
menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan
sebuah perkawinan
39
.
37
Samuel W. Buell, Good Faith and Law Evasion, UCLA Law Review 58, hal. 630.
38
Ibid., hal. 629.
39
Faizah Bafadhal, Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan, Jurnal Ilmu
Hukum Vol. 2 No. 2, (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2012), hal. 25.
Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa menurut pandangan
yang pertama, sahnya suatu perkawinan hanya didasarkan pada aturan-aturan
agama, sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 2 ayat (1) UUP. Artinya
pencatatan perkawinan pada Kantor Pencatatan Perkawinan secara hukum tidak
menjadi syarat sahnya suatu perkawinan, sedangkan menurut pandangan yang
kedua, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP harus dipandang sebagai satu kesatuan
yang tidak terpisah.
Jika Hakim menganut bahwa pencatatan perkawinan pada Kantor
Pencatatan Perkawinan secara hukum tidak menjadi syarat sahnya suatu
perkawinan, dalam hal seseorang meninggal maka istri/suami yang hidup terlama
dan anak yang lahir dalam perkawinan tak tercatat tersebut akan muncul sebagai
ahli waris golongan pertama. Dengan demikian, ia menutup ahli waris golongan
yang lebih jauh derajatnya.
Sementara itu, jika Hakim berpandangan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(2) UUP harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah, dalam hal
seseorang meninggal maka istri/suami yang hidup terlama dan anak yang lahir
dalam perkawinan tak tercatat tersebut tidak diakui sebagai ahli waris golongan
pertama, dengan demikian, ahli waris derajat yang lebih jauh secara berurutan
tampil sebagai ahli waris.
E. Putusan Hakim No. : 05 / Pdt.G/ 2011 / PN. Kbj dan Pencatatan
Perkawinan
Menurut putusannya, Majelis Hakim mengakui perkawinan yang telah
dilangsungkan oleh Pewaris dan Tergugat, dan kemudian menetapkan bahwa
Penggugat dan Tergugat mewaris secara bersama-sama. Hal ini merupakan bentuk
ketidaksesuaian putusan terhadap ketentuan sebagaimana terdapat dalam
KUHPerdata
40
:
Ahli waris golongan pertama terdiri dari:
Anak-anak dan keturunannya
Perkataan dan/atau disini dimaksudkan karena anak-anak tidak dapat mewaris
bersama-sama dengan keturunan, satu akan menutup yang lain.
41
Dalam hal ini
tidak menutup kemungkinan bahwa anak mewaris bersama keturunan yaitu dalam
hal terjadi penggantian.
Suami atau istri yang hidup terlama
Di Indonesia sejak Januari 1936, istri atau suami yang hidup terlama sebagai ahli
waris termasuk golongan I, besarnya bagian istri/suami yang hidup terlama dalam
Pasal 852a KUHPerdata ditentukan sama dengan bagian anak.
Ahli waris golongan kedua yaitu:
orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan dan keturunan saudara laki dan
perempuan tersebut.
Ahli waris golongan kedua diatur dalam pasal berikut ini:
Pasal 854 ayat (1) KUHPerdata, menentukan:
Apabila seorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan
maupun suami istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-
masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya
meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan, yang mana mendapat
sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat seperempat,
jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau perempuan,
sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki
atau perempuan itu.
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Penggugat selaku orangtua
(bersama dengan saudara) dari Pewaris merupakan ahli waris golongan kedua.
Sementara itu, Tergugat (oleh karena Majelis Hakim mengakui adanya
40
Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan
Menurut Undang-Undang, (Depok: Prenada Media Group, 2010), hlm. 49.
41
Ibid., hal. 50.
perkawinan antara Pewaris dan Tergugat), adalah istri yang hidup terlama dan
merupakan ahli waris golongan pertama.
Berdasarkan asas penderajatan, ahli waris golongan pertama tidak
mungkin mewaris bersama dengan ahli waris golongan kedua, oleh karena asas
penderajatan menentukan ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris,
menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya
42
.
Oleh sebab itu, dalam putusan No. : 05 / Pdt.G/ 2011 / PN. Kbj, yang
menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menerima
waris, dapat ditemukan bahwa terdapat inkonsistensi pendapat hakim, apakah
akan mengakui perkawinan antara Pewaris dan Tergugat. Jika Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah walaupun tidak dicatatkan,
seharusnya Tergugat merupakan satu-satunya ahli waris. Namun, jika Majelis
Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah oleh karena tidak
dilakukan pencatatan, maka seharusnya ahli waris golongan kedua (yaitu
Penggugat selaku orangtua, beserta saudara-saudara Pewaris) merupakan pihak
yang tampil sebagai ahli waris.
42
M. Ramulyo Idris, Perbadingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 95-96.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Terdapat dualisme pendapat, apakah ketiadaan pencatatan perkawinan
menyebabkan istri/suami yang hidup terlama menjadi ahli waris golongan
pertama. Jika istri/suami yang hidup terlama diakui menjadi ahli waris golongan
pertama, maka berdasarkan asas penderajatan ia menutup derajat yang lebih jauh.
Sementara itu, jika pencatatan diwajibkan, maka istri/suami perkawinan tak
tercatat bukanlah ahli waris.
Pembahasan secara doktrinal, mengarah kepada keadaan bahwa
perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak memenuhi jiwa (spirit) dari pencatatan
perkawinan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas
perkawinan. Jika tidak terdapat alasan itikad baik (alasan bahwa pencatatan tidak
mungkin dilaksanakan), ia merupakan suatu penyelundupan hukum. Oleh karena
ia merupakan penyelundupan hukum, maka akibat dari perkawinan yang tidak
dicatatkan seharusnya perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
Putusan No. : 05 / Pdt.G/ 2011 / PN. Kbj, yang menyatakan bahwa
Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menerima waris, dapat ditemukan
bahwa terdapat inkonsistensi pendapat hakim, apakah akan mengakui perkawinan
dari Pewaris dan Tergugat. Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan
tersebut adalah sah walaupun tidak dicatatkan, seharusnya Tergugat merupakan
satu-satunya ahli waris. Namun, jika Majelis Hakim berpendapat bahwa
perkawinan tersebut tidak sah oleh karena tidak dilakukan pencatatan, maka
seharusnya ahli waris golongan kedua (yaitu Penggugat selaku orangtua, beserta
saudara-saudara Pewaris) merupakan pihak yang tampil sebagai ahli waris.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan perkawinan sebagai syarat
administratif yang wajib dilaksanakan dalam memperoleh perlindungan hukum
dari negara, memiliki sifat yang lebih baik dan sesuai dengan jiwa (spirit) dari
pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
terhadap pihak terkait perkawinan, sehingga lebih ideal untuk diterapkan dalam
menafsirkan lembaga perkawinan itu sendiri.
Adapun permasalahan terdapat pada perumusan peraturan perundang-
undangan yang mengatur permasalahan mengenai pencatatan perkawinan, bahwa
diantara peraturan-peraturan tersebut secara redaksional adalah multitafsir dan
tidak tegas.
Dalam menghindari permasalahan tersebut, maka tindakan yang
disarankan adalah:
1. perbaikan redaksional peraturan perundang-undangan sehingga tidak
dapat ditafsirkan lain, bahwa jika pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan,
maka perlindungan hukum tidak didapatkan.
2. pemberian sanksi pidana dan penegakan hukum bagi pelanggar
kewajiban pencatatan perkawinan, yang berlaku umum, terkecuali terdapat alasan
pembenar atau alasan pemaaf untuk itu.
You might also like
- Bab Ii Perkawinan Dan Putusnya Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanDocument11 pagesBab Ii Perkawinan Dan Putusnya Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanSaepul LohNo ratings yet
- Makalah Perkawinan CampuranDocument16 pagesMakalah Perkawinan Campuraneza amaliaNo ratings yet
- Bab 2Document45 pagesBab 2Wibowo DwiNo ratings yet
- 1452 2477 1 SMDocument17 pages1452 2477 1 SMPutri Marantika Dwi ArdaniNo ratings yet
- Pembatalan PerkawinanDocument25 pagesPembatalan PerkawinanAndi M E WirambaraNo ratings yet
- Contoh Laporan Isbad NikahDocument15 pagesContoh Laporan Isbad NikahRay coronaNo ratings yet
- T2 Belum RevisiDocument16 pagesT2 Belum RevisiTegar Prakosa WilisNo ratings yet
- Hukum Perkawinan Di IndDocument26 pagesHukum Perkawinan Di Inddg2fNo ratings yet
- UAS PerkawinanDocument5 pagesUAS PerkawinanokiNo ratings yet
- Esyera Claudia G.Document42 pagesEsyera Claudia G.Chariri MushofaNo ratings yet
- Perkawinan CampurDocument22 pagesPerkawinan CampurHadi Sugoro100% (2)
- Hkum4202 Hukum Perdata OkiDocument4 pagesHkum4202 Hukum Perdata OkiCeppy BangunNo ratings yet
- Hukum PerkawinanDocument74 pagesHukum PerkawinanReza Kurnia AkbarNo ratings yet
- Implementasi UUP2Document15 pagesImplementasi UUP2qomaruddinNo ratings yet
- Perkawinan CampuranDocument8 pagesPerkawinan CampuranRodhiins furnitureNo ratings yet
- 4206 9014 1 SMDocument10 pages4206 9014 1 SMAl KinNo ratings yet
- Analisis Pertimbangan Hukum Dalam PenetaDocument101 pagesAnalisis Pertimbangan Hukum Dalam PenetaaliNo ratings yet
- Pencatatan Perkawinan5 Dan Akta Nikah5Document18 pagesPencatatan Perkawinan5 Dan Akta Nikah5LOMarvelaw 2023No ratings yet
- AbsrtarkDocument3 pagesAbsrtarkMasturlubis 23No ratings yet
- Tata Cara Melangsungkan PerkawinanDocument5 pagesTata Cara Melangsungkan PerkawinanSri Saranghae CiebieberMaurerloverholicNo ratings yet
- Kd. 3.13 Dan 4.13 Perkawinan PegawaiDocument10 pagesKd. 3.13 Dan 4.13 Perkawinan PegawaiFiranitanita 1306No ratings yet
- Pencatatan PerkawinanDocument10 pagesPencatatan PerkawinanBunda Faraz CornerNo ratings yet
- Achmad Taufiq Hidayat 1119124 UTS HAPPADocument13 pagesAchmad Taufiq Hidayat 1119124 UTS HAPPAal kimNo ratings yet
- Makalah Fiqh Munakahat 2Document10 pagesMakalah Fiqh Munakahat 2Ashabul YaminNo ratings yet
- Presentasi Kasus Posisi MachicaDocument13 pagesPresentasi Kasus Posisi MachicaMIndraSukarnaNo ratings yet
- Kuliah 4 - Hukum KeluargaDocument6 pagesKuliah 4 - Hukum KeluargaGitha Dwi DamaraNo ratings yet
- Kelompok 3 Pencatatan PerkawinanDocument9 pagesKelompok 3 Pencatatan Perkawinanhaswin muhari nasutionNo ratings yet
- Tugas Hukum Keluarga Dan Harta Perkawinan Bagian CDocument3 pagesTugas Hukum Keluarga Dan Harta Perkawinan Bagian Cmuhammadnaufalnadhir3No ratings yet
- LINDRI PURBOWATI SH MH 21032023153427 Mata Kuliah Hukum Perdata Pertemuan 34Document38 pagesLINDRI PURBOWATI SH MH 21032023153427 Mata Kuliah Hukum Perdata Pertemuan 34Mabes JanuariNo ratings yet
- 1 SMDocument14 pages1 SMArie ApriyantoNo ratings yet
- 2) Tpa III - Pengantar Hukum Perkawinan & KeluargaDocument57 pages2) Tpa III - Pengantar Hukum Perkawinan & KeluargaFatwa Dea Ramdani OctaviyasminNo ratings yet
- 1 Tutiek RetnowatiDocument16 pages1 Tutiek RetnowatiKiki Na'ichanNo ratings yet
- Narasi Elearning - Isbat Nikah - ElearDocument12 pagesNarasi Elearning - Isbat Nikah - ElearFikri NurfauziNo ratings yet
- Definisi Harta GonoDocument35 pagesDefinisi Harta GonoAgus RiedwanNo ratings yet
- Undang-Undang PerkawinanDocument16 pagesUndang-Undang PerkawinanDekky T PrasetiaNo ratings yet
- Nikah PaksaDocument10 pagesNikah Paksawandawolena.salampessyNo ratings yet
- Bab 4Document50 pagesBab 4Muzaki Ahmad ZayadiNo ratings yet
- 194 382 1 SMDocument12 pages194 382 1 SMFriskaNo ratings yet
- ID Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang Undangan Di IndonesiaDocument11 pagesID Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang Undangan Di IndonesiaPuypearceNo ratings yet
- Hukum Perkawinan Di IndonesiaDocument9 pagesHukum Perkawinan Di IndonesiaaffhtassyaNo ratings yet
- Mata Kuliah Hukum Perdata Pertemuan 3Document29 pagesMata Kuliah Hukum Perdata Pertemuan 3AdyNo ratings yet
- Rangkuman Pertemuan Keenam Hk. PerdataDocument3 pagesRangkuman Pertemuan Keenam Hk. PerdataAlivia AdzhaniNo ratings yet
- HukumDocument33 pagesHukumNila Rizki Anisa09No ratings yet
- Makalah H Keluarga BaratDocument10 pagesMakalah H Keluarga BaratFarah SalmaNo ratings yet
- Materi Video Pembelajaran Hukum PerdataDocument4 pagesMateri Video Pembelajaran Hukum Perdataharrypribadi garpesNo ratings yet
- Bab IDocument31 pagesBab IHasan CahyonoNo ratings yet
- Tata Cara Akad Pernikahan Beda AgamaDocument3 pagesTata Cara Akad Pernikahan Beda AgamaIlham NaufalNo ratings yet
- Bab 3Document31 pagesBab 3Wrangler JeansNo ratings yet
- Itsbat Nikah THD Pelaku PerceraianDocument18 pagesItsbat Nikah THD Pelaku PerceraianRom WayNo ratings yet
- Tugas Hukum Keluarga Dan Permasalahannya - Kelompok 1-1Document17 pagesTugas Hukum Keluarga Dan Permasalahannya - Kelompok 1-1arsy FilesteNo ratings yet
- Tugas Resume Perkawinan InternasionalDocument5 pagesTugas Resume Perkawinan InternasionalNurul safitriNo ratings yet
- Bab 1Document13 pagesBab 1Putri SekariniNo ratings yet
- Hukum Keluarga & PerkawinanDocument22 pagesHukum Keluarga & PerkawinanRadifya Indri Safinka100% (1)
- Tugas 3 Kelompok Legal OpinionDocument8 pagesTugas 3 Kelompok Legal OpinionbendryNo ratings yet
- Hukum PerkawinanDocument3 pagesHukum PerkawinanGadis AdiatiNo ratings yet
- HK PerkawinanDocument7 pagesHK PerkawinanWieRobyNo ratings yet
- TUGAS 2 KONS PERKAWINAN Naufal Fawwaz Ramadhan 19006189Document6 pagesTUGAS 2 KONS PERKAWINAN Naufal Fawwaz Ramadhan 19006189Zulhelma BoerNo ratings yet
- Perkawinan CampuranDocument17 pagesPerkawinan CampuranYunia Asta DewiNo ratings yet
- 80 388 1 PBDocument27 pages80 388 1 PBkua kalapanunggalNo ratings yet
- Tugas 5 KoperasiDocument9 pagesTugas 5 KoperasifajarcsNo ratings yet
- Sapi PotongDocument12 pagesSapi PotongNyesel KaptenNo ratings yet
- The Nature of JurisprudenceDocument4 pagesThe Nature of JurisprudencefajarcsNo ratings yet
- Pemberhentian Presiden Atau Wakil PresidenDocument8 pagesPemberhentian Presiden Atau Wakil PresidenfajarcsNo ratings yet
- Medieval MusicDocument2 pagesMedieval MusicfajarcsNo ratings yet
- Musik Era BarokDocument2 pagesMusik Era BarokFajar Cahyanto SantosaNo ratings yet