Professional Documents
Culture Documents
Artikel Kembalikan Hutan Pada Rakyat
Uploaded by
Dk-fisipuksw KristiantoCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Artikel Kembalikan Hutan Pada Rakyat
Uploaded by
Dk-fisipuksw KristiantoCopyright:
Available Formats
Merintis Lumbung Dari Sela-Sela Kebun Kayu Perhutani Oleh Daud Kristianto, S.
Sos Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan penduduk pada saat paceklik dan mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, diperlukan system pengelolaan cadangan pangan. Salah satu caranya ialah dengan menumbuh-kembangkan sekaligus memelihara tradisi petani untuk menyisihkan sebagian hasil panen sebagai cadangan pangan dengan membangun suatu lumbung pangan. Akan tetapi berbicara dalam konteks petani konsep lumbung menjadi hal yang niscaya dilakukan. Oleh karena dalam kepemilikan factor produksi berupa lahan, petani di jawa khususnya petani di desa hutan memiliki lahan yang sempit, bahkan sebagian besar petani di republic ini hanya berprofesi sebagai petani penggarap. Bagaimana Petani Lahan Sempit dan Tak-Berlahan Bisa Punya Lumbung Sebagai gambaran kongkret tentang kondisi kepemilikan lahan yang sempit, disini penulis mengambil contoh dari desa Randurejo Kec.Pulokulon Kab. Grobogan. Dimana dengan luas Desa : 2.593,600 Ha tata guna lahan yang ada: Sawah Tadah Hujan : 420,082 Ha, Pekarangan/Bangunan : 172,800 Ha, Tegalan/Kebun : 301,118 Ha, Hutan Negara : 1.649,900 Ha, Lainnya : 49,700 Ha. Dari data tersebut kita dapat melihat proporsi lahan milik Negara yang dikelola Perhutani di Desa Randurejo lebih luas yaitu 1.649,900 Ha (63,61%) dan kepemilikan lahan Masyarakat rata-rata per kepala keluarga di Desa Randurejo hanya sekitar 0,46 Ha. Dengan kondisi lahan kering yang dimiliki 0,49 ha apabila di tanam jagung akan menghasilkan sekitar 2-2,5ton, sementara apabila di jual dengan harga 1500/kg dalam masa panen akan menghasilkan uang sekitar 3.000.000,- per 6 bulan. Sementara dalam satu tahun 2 kali masa tanam, apabila dipukul rata penghasilan kotor hanya 500.000,- per bulan (wawancara dengan Bpk. Parno Ketua LMDH, pada tanggal 19-02-2010). Dengan penghasilan kotor 500.000,- per bulan yang belum dikurangi biaya produksi dan biaya kebutuhan hidup serta biaya lain-2, dapat dipastikan bahwa petani tidak akan mau menyisihkan hasil panen dan dapat membuat lumbung pangannya dari hasil panen di lahannya yang sempit, terlebih bagi petani tak berlahan. Atas dasar tersebut perlu adanya aksesibilitas masyarakat desa hutan (MDH) terhadap tanah yang di klaim sebagai hutan negara dalam upaya membangun kedaulatan pangan keluarga, kedaulatan pangan desa dan pada level yang lebih besar ketahanan pangan nasional. Aksesibilitas MDH terhadap Hutan Negara Dalam hal hutan negara, Perhutani merupakan PT (dahulu BUMN) yang telah diberi mandat di wilayah Jawa untuk mengelola hutan negara tersebut. Pada lingkup wilayah Jateng Perhutani mengelola sekitar 2.566.145 ha hutan negara. Dalam pengelolaan hutan negara tersebut Perhutani mencoba hadir dengan icon perubahan paradigma penggelolaan hutan dari State Based Forest Management menjadi Community Based Forest Management dengan meluncurkan PHBM di tahun 2001 dan disempurnakan di tahun 2007 melalui PHBM Plus. Dengan konsep PHBM Negara
melalui Perhutani memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk mendapatkan akses pengelolaan lahan Perhutani. Masyarakat diijinkan menggarap lahan disela-sela pohon pokok secara tumpang sari sehingga bisa memperoleh hasil dari hutan. Selain itu masyarakat juga akan memperoleh bagi hasil, yaitu dari bagi hasil panen kayu. Menilik dari program yang sudah berjalan selama 10 tahun tersebut terkait dengan dampak PHBM terhadap masyarakat. Ungkapan rich forest, poor people (dalam Syahyuti, 2006), mungkin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi hutan kaitannya dengan kondisi ekonomi masyarakat khususnya masyarakat desa hutan. Dimana, hutan telah dieksploitasi bahkan selama beberapa abad dari masa kolonialisme sampai indonesia merdeka hingga saat ini, lingkungan sudah mengalami kehancuran, dan berbagai kebijakan oleh Perhutani telah dikeluarkan, akan tetapi kondisi masyarakat khususnya masyarakat desa hutan tetaplah pada kondisi miskin. Hal tersebut ditunjukan oleh kondisi dimana terdapat sekitar 6000 desa hutan atau desa yang berbatasan dengan hutan di bawah penggelolaan Perum Perhutani, pada kenyataan masih dalam kondisi miskin (Awang, 2004: 134). Kondisi real masyarakat desa hutan dapat dilihat di desa randurejo yang masuk dalam wilayah kerja Kesatuan Pangkuan Hutan (KPH) Gundih yang tetap dalam selimut kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang nampak diantaranya ditandai oleh: kurangnya lapangan pekerjaan (pengangguran), minimnya lahan pertanian, kurang modal, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang, makan dua kali sehari dan makanan tidak bergizi, infrastruktur dan sarana transportasi yang tidak memadai (hasil FGD kemiskinan, 2008). Terlepas dari hasil PHBM yang masih jauh panggang dari api dalam upaya pencapaian tujuan program dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena memang PHBM hadir lebih karena peredam konflik supaya kayu-kayu Perhutani aman dan dalam konteks yang lebih luas adalah mengalihkan isu Landreform dalam pengertian redistribusi lahan untuk petani. Tetapi penulis melihat adanya peluang positif MDH dengan dibukannya aksesibilitas terhadap hutan negara untuk kegiatan produksi sumber pangan. Melalui sistem polong-polong di lahan negara yang diatur dalam PLDT (Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan) masyarakat dapat menanam komoditas pangan seperti jagung disela-sela kebun kayu Perhutani. Lumbung sebagai Food Security MDH Dengan mata pencaharian utama masyarakat sebagai petani, dan dibukanya aksesibilitas hutan untuk MDH. Seharusnya hutan dapat menjadi aset penting dan penyangga eksistensi masyarakat desa hutan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Melalui sumber makanan yang tersedia, hutan dapat berfungsi sebagai kedaulatan pangan atau food security di saat sulit. Selain itu hutan juga merupakan alternatif perluasan lahan garap usaha tani penduduk sekitar hutan dimana kepemilikan lahan petani desa hutan cenderung terbatas dan juga dapat sebagai pembuka peluang kerja baru dalam setiap usaha produktifnya ketika kesempatan kerja yang ada di kota terbatas. Dalam hal ini tentunya kebutuhan akan hutan melalui pemanfaatan kayu bakar, sumber air, obat-obatan, bahan baku konstruksi, dan berbagai sumberdaya yang ada di dalamnya sebenarnya hutan akan memasok kebutuhan rumah tangga miskin di desa hutan. (Mubyarto, 1992: 4-6). Oleh karena hutan produksi di Jawa khusunya di Jateng merupakan hutan homogen dengan hamparan kebun kayu dimana food security yang digambarkan
oleh Murbyarto tidak mungkin ada, apabila tidak diupayakan sendiri oleh MDH. Maka disini perlu ada upaya membuat Sistem dan Kelembagaan Lumbung MDH dengan point perjuangan: 1. Menanam komoditas di hutan negara yang mendukung kedaulatan pangan petani yang pro-lingkungan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, singkong, dll (tolak tebunisasi). 2. Mengusulkan alokasi dana pembangunan lumbung dari hasil sharing hasil produksi kebun kayu lewat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). 3. Re-negosiasi MDH melaui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) tentang proporsi sharing bagi hasil jagung dimana pada kenyataannya MDH diwajibkan membayar yang disebut sebagai sewa lahan 600.000,- per ha per satu kali masa tanam (6 bulan). Supaya diperjuangkan paling tidak 1/3 nya atau sebesar (200.000,-) atau dalam hitungan jagung sekitar 133 kg diserahkan ke Lembaga Lumbung MDH. Apabila per ha pessangem menyetorkan 133 kg jagung maka apabila luasan pangkuan hutan desa adalah sebesar1.649,900 Ha secara hitungan kasar akan ada sekitar 219 ton cadangan pangan yang terakumulasi selama 6 bulan di desa Randurejo. 4. Pembuatan lumbung yang bukan hanya sebagai food security mongso paceklik akan tetapi juga sebagai lumbung bibit, pupuk, obat bagi MDH. 5. Pembentukan kelompok lumbung yang dilegalisasi dalam perdes. Sehingga dengan munculnya produk kebijakan di tingkat pemerintahan desa, keberadaan Lumbung Desa mempunyai aspek keberlakuan hukum yang diharapkan secara konsensus akan ditaati bersama. Dari wacana tersebut diatas, kiranya dapat menjadi saatnya masyarakat secara kolektif membangun kedaulatannya pangannya sendiri dan model kebijakan ketahanan pangan seperti blt
You might also like
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseFrom EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseRating: 4 out of 5 stars4/5 (1108)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5795)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionFrom EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2507)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20025)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceFrom EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceRating: 4 out of 5 stars4/5 (2556)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (3278)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19653)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelFrom EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (5509)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6521)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2567)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2475)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationFrom EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationRating: 4 out of 5 stars4/5 (2499)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12947)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)From EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9486)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderFrom EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderRating: 4 out of 5 stars4/5 (5718)












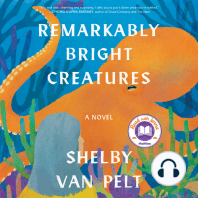






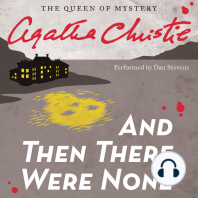


![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)



