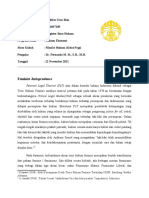Professional Documents
Culture Documents
Etika Kepedulian
Uploaded by
fulan_khanOriginal Description:
Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Etika Kepedulian
Uploaded by
fulan_khanCopyright:
Available Formats
A Feminist Psychologist's Blog
Home CONSULTATION DICTIONARY MY GUEST
Psikologi Hukum Feminis (Etika Kepedulian), dan Keadilan Sebagai YangTak-Mungkin
April 18, 2011 Oleh: Donny Danardono Buku Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: KDRT Perspektif Psikologi Feminis [2009] yang ditulis oleh Ester Lianawati, pengajar Fakultas Psikologi Universitas Kristen Krida Wacana ini menarik dalam sejumlah hal. Pertama, buku ini adalah studi interdisiplin psikologi dan hukum, dan bahkan filsafat moral [etika kepedulian]. Kedua, buku ini adalah evaluasi terhadap UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [PKDRT] yang ia anggap sebagai norma hukum pendekonstruksi relasi dikotomis publik-privat (h. 2), tapi yang sekaligus lemah dalam hal menganggap kekerasan seksual, penelantaran ekonomi dan fisik terpisah dari kekerasan psikis. Kekerasan psikis hanya dianggap sebagai dampak dari ketiga bentuk kekerasan sebelumnya (h. 7). Padahal seperti yang banyak diketahui, kekerasan psikis bukan sekedar dampak, tapi menyatu dengan ketiga bentuk kekerasan itu. Ketiga, Ester dengan berangkat dari mazab realisme hukum yang tak memisahkan hukum dari moral, politik, psikologi atau pun sosiologi menganggap para penegak hukum dan khususnya hakim saat membuat keputusan senantiasa dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum tersebut. Ia memberi contoh, bahwa cara seorang hakim mengkarakterisasikan korban dapat menimbulkan variasi dalam respons dan putusan hukumnya (h. 6). Keempat, berdasarkan ketiga hal tersebut, Ester mengusulkan perlunya aparat penegak hukum mengkaitkan etika kepedulian yang oleh pencetusnya, Carol Gilligan, dianggap sebagai etika yang khas perempuan. Menurut Gilligan, berbeda dari pria, perempuan cenderung mendasarkan perilakunya pada kepedulian yang berupa kemampuan mendengarkan kisah-kisah orang lain dan diri sendiri karena perbedaan status sosial, relasi kuasa dan bentuk reproduksi antara peremuan dan pria: Clearly, these differences arise in a social context where factors of social status and power combine with reproductive biology to shape experience of males and females and the relations between sexes. My interest lies in the interaction of experience and thought, in different voices and the dialogues to which they give rise, in the way we listen to ourselves and to others, in the stories we tell about our lives.[1]
Dengan demikian Ester mengusulkan perlunya menggabungkan hukum (yang berorientasi pada penegakan keadilan) dengan psikologi (yang berorientasi pada kepedulian atau kemampuan mendengarkan orang lain dan diri sendiri). Setidaknya hal ini tercermin dari keempat permasalahan penelitian yang ia ajukan (h. 9-10). Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian Untuk bisa mengungkap bagaimana para penegak hukum menetapkan siapa pelaku dan korban, memproses kasus-kasus mereka, dan membuat keputusan hukum; serta bagaimana tanggapan para perempuan yang menjadi korban KDRT tersebut terhadap segala proses hukum yang mereka lalui, Ester tekun mengumpulkan dan menelaah transkrip pertemuan, surat dan buku harian, jawaban di lembar kuesioner, dan bahkan mewawancari para korban, pendamping mereka, dan beberapa aparat penegak hukum (h. 13). Saya menganggap strategi (metode) pengumpulan dan analisa berbagai data tersebut berangkat dari etika kepedulian, yaitu kemauan untuk mendengarkan kisah orang lain yang dalam hal ini para perempuan korban KDRT. Ini adalah bentuk keterkaitan atau konsistensi antara teori dan praksis. Etika kepedulian ini, saya kira, telah memberinya kritisisme saat mempraktekkan psikologi feminis. Ia tak semata-mata menggunakan psikologi untuk mengkonstruksikan identitas perempuan, karena tetap berpeluang menyalahkan perempuan dan melestarikan budaya patriarki (h. 21-22). Tapi ia berorientasi pada pemahaman terhadap ketertindasan perempuan (h. 22). Maka, begitulah Ester berusaha mendengarkan para nara sumbernya (perempuan-perempuan korban KDRT). Ia berusaha mengetahui mengapa mereka walau telah berkali-kali menjadi korban KDRT tetap bertahan dalam perkawinannya tersebut? Ia menemukan berbagai alasannya yang ia sebut sebagai penyebab-penyebab struktural (h. 34). Ia mengetahui, bahwa kisah keenam perempuan korban itu tak hanya membenarkan teori sikuls kekerasan-bulan madu yang memberi kesan para perempuan korban itu tak berdaya dan pasif, tapi mereka juga aktif melakukan perlawanan seperti yang diteorikan oleh Gondolf yaitu dengan meninggalkan pelaku atau meminta atasan pelaku untuk menindaknya (h. 23 dan 35). Ester pun juga mendengarkan kisah para perempuan korban tersebut ketika mereka memproses kasusnya secara hukum. Dan ia mengetahui bagaimana perspektif bias gender para penegak hukum itu memengaruhi cara pandang mereka terhadap para perempuan tersebut. Ester pun dengan tekun mencatat berbagai kisah pendampingan para korban itu. Ia pun tahu, bahwa berbagai perspektif negatif para pendamping tentang pandangan Tuhan dan perceraian telah memengaruhi perempuan korban dalam melangkah (h. 105), jenis kelamin pendamping juga memengaruhi perspektif para perempuan korban tentang kasus yang mereka alami (h. 107). Dan akhirnya ia pun mencatat perspektif para pelaku tentang korbannya. Sesuatu yang luar biasa. Tak semua peneliti bisa dan tekun dalam mencatat perspektif pelaku (h. 119). Namun, pada akhirnya, tujuan Ester adalah menunjukkan faktor apa saja yang memengaruhi para penegak hukum dalam memeriksa kasus-kasus KDRT ini. Di sinilah Ester mengusulkan, bahwa
para pendamping korban dan para penegak hukum perlu memiliki etika kepedulian agar mereka dapat menangkap persoalan, kebutuhan, dan harapan korban (h. 177). * Sejauh saya membaca buku tersebut, saya tak menemukan perspektif Ester tentang penegakan hukum (keadilan) dan kepedulian. Saya hanya mendapat kesan, bahwa menurutnya apabila para penegak hukum punya etika kepedulian, maka mereka mampu mendengarkan segala persoalan, kebutuhan dan harapan korban, sehingga mereka bisa menegakkan hukum (keadilan) secara baik. Jadi apa yang ditulis oleh Ester adalah sebuah tafsir terhadap realisme hukum, yaitu menggabungkan hukum dan etika kepedulian. Tawaran Ester ini sebenarnya sama dan sebangun dengan tafsir Franz Magnis-Suseno tentang etika kepedulian Carol Gilligan.[2] Franz Magnis mengatakan, bahwa etika kepedulian berbeda dari etika keadilan. Etika keadilan berorientasi pada sesuatu yang abstrak, yaitu hak, otonomi individu (sebuah otonomi yang dibentuk oleh hak) dan penegakan hak. Sebaliknya etika kepedulian berangkat dari sesuatu yang nyata, yaitu anggapan bahwa setiap manusia adalah makhluk yang lemah dan karenanya saling membutuhkan. Penindasan dan dominasi berasal dari pengabaian diri sebagai makhluk yang lemah. Karena itu etika kepedulian menawarkan kepedulian atau kesadaran tentang anggapan bahwa setiap orang mudah tersakiti perasaannya dan tak terabaikannya relasi antar individu.[3] Berdasarkan kedua perspektif itu, Franz Magnis-Suseno yang mendasarkan diri pada perkembangan pemikiran Gilligan dan Frankena bahwa etika kepedulian mengandaikan etika keadilan dan begitu sebaliknya. Argumentasi Magnis adalah seseorang hanya akan mampu bertindak adil, bila ia terlebih dulu peduli pada orang lain. Orang yang tidak peduli pada orang lain, secara a-priori tertutup pada kemungkinan bertindak secara moral (adil).[4] Penggabungan etika keadilan dan kepedulian yang memang canggih dan meyakinkan ini, menunjukkan bahwa etika kepedulian tak bisa menyelesaikan masalah bila tak disertai etika keadilan, dan sebaliknya etika keadilan menjadi tak mungkin tanpa etika kepedulian. Sebuah anggapan yang muncul dari refleksi penuh terhadap teori komunikasi Habermas. Bagi Habermas, dalam sebuah masyarakat majemuk, keadilan tak dapat dirumuskan sendirian oleh filsuf atau negarawan tertentu, tapi secara komunikatif oleh orang-orang yang tengah menghadapi persoalan. Sebab komunikasi akan bisa menjamin kemajemukan pandangan hidup dan sekaligus merumuskan apa yang adil dan tak adil dalam waktu dan tempat tertentu. Komunikasi, dengan kata lain, adalah cara untuk bersikap peduli pada orang lain yang berbeda dari kita. Ester memang tak secara eksplisit menguraikan argumentasinya seperti Franz Magnis tersebut, tapi saya yakin ia tak keberatan dengan argumentasi Franz Magnis tersebut. Etika Kepedulian dan Keadilan Sebagai Yang-Tak-Mungkin Tapi justru itulah persoalannya, mungkinkah keadilan dirumuskan? Bagaimana mungkin pelaku dan korban yang memiliki relasi kuasa (bahasa) yang berbeda bisa merumuskan apa yang adil
dan tidak adil? Bagaimana mungkin penindas dan tertindas bisa merumuskan apa yang adil dan tak adil bagi mereka? Apakah keadilan juga bisa ditetapkan oleh pihak ketiga penegak hukum setelah berdasarkan etika kepedulian mendengarkan persoalan, kebutuhan dan harapan korban seperti yang disampaikan oleh Kristi Purwandari di Pengantar Buku?[5] Tapi persoalan berikutnya adalah bagaimana mengidentifikasi korban, pelaku, dan bukan korban? Ester tak menguraikan hal ini. Mungkin di sini sudah waktunya kita menelaah pemahaman Jacques Derrida tentang keadilan. Derrida menganggap keadilan adalah penting, tapi tak mungkin dirumuskan dan diwadahi dalam institusi apapun, termasuk tak mungkin diwadahi oleh hukum. Karena mewujudkan dan menjamin keadilan dalam hukum bukan hanya akan mereduksi pengalaman seseorang terhadap keadilan, tapi juga merupakan tindakan yang kontradiktoris. Sebab baginya proses pembentukan dan penegakan hukum merupakan proses yang mengkaitkan kekuasaan negara (yang baginya tak pernah didirikan berdasarkan hukum tertentu, tapi revolusi, karena itu setiap norma hukum yang dibuat oleh negara selalu ada dalam posisi ambigu, yaitu tidak sah dan sah sekaligus) berbagai kekuasaan non-negara dan kekerasan (yang antara lain berupa praktek pendefinisian yang dianggapnya sebagai bentuk kekerasan, karena mereduksi identitas seseorang atau sesuatu yang didefinisikan). Jadi, bagaimana mungkin keadilan yang anti kekerasan bisa dirumuskan oleh kekerasan? Kata Derrida tentang hal ini: How are we to distinguish between the force of law of a legitimate power and the supposedly originary violence that must have established this authority and that could not itself have been authorized by any anterior legitimacy, so that, in this initial moment, it is neither legal nor legal or, others would quickly say, neither just nor unjust?[6] Karena itu dengan mendasarkan diri pada dekonstruksi sebagai sebuah strategi untuk menunjukkan ambiguitas, ketidakpastian, the other (the difference) dan paradoks sebuah teks Derrida menunjukkan bahwa dekonstruksi tak berakhir pada nihilisme, tapi pada kemungkinan manusia mengetahui atau tepatnya mengalami yang tak mungkin (the impossible), yakni sesuatu yang tak bisa dirumuskan secara tekstual. Jadi, baginya keadilan adalah pengalaman tentang yang tak mungkin, sebuah pengalaman yang kira-kira sama dengan situasi ketika seseorang mengalami dilema atau makan buah simalakama (bila buah itu dimakan ibu akan mati, bila tidak ayah yang mati, dan bila dikulum saja ayah dan ibu akan sekarat). Dalam situasi dilematis ini semua keputusan yang diambil atau akan diambil akan sama kelirunya: The sufference of deconstruction, what makes it suffer and what makes those it torments suffers, is perhaps the absence of rules, of norms, and definitive criteria that would allow one to distinguish unequivocally between droit and justice. That is the choice of either/or, yes or no [...]. Needless to say, from this point on I can offer no response, at least no reassuring response, to any questions put in this way (either/or, yes or no), to either party or to either partys expectations formalized in this way.[7] Maka penegakan hukum adalah wujud relasi kuasa yang jauh dari keadilan. Ia adalah penegakan tafsir-tafsir tertentu tentang hukum dan relasi para pihak yang berperkara. Tapi bukan berarti keadilan tak penting lagi. Keadilan memang penting, tapi selalu tertunda ketika
mau diwujudkan. Ia ibarat horison yang memberi wawasan geografis tentang sebuah wilayah, tapi selalu menjauh ketika didekati. Dengan demikian semua teori keadilan atau upaya mewujudkan keadilan melalui keputusan hukum tak lain dari praktek kekuasaan tertentu. Ia merupakan bentuk kekerasan, bukan keadilan yang anti dan mau mengakhiri kekerasan itu sendiri. Hukum dan pengadilan memang penting, tapi di kedua institusi itu keadilan selalu tertunda. Kedua institusi itu hanya mampu mempraktekkan relasi kuasa. Dampak negatif relasi kuasa hanya bisa dikurangi oleh etika kepedulian (keinginan untuk membahagiakan orang lain, musuh dan diri sendiri). Tulisan ini adalah karya Donny Danardono, pengajar filsafat hukum dan Ketua PMLP (Program Magister Lingkungan dan Perkotaan) Unika Soegijapranata, Semarang. Tulisan ini disampaikan dalam bedah buku Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: KDRT, Perspektif Psikologi Feminis di Auditorium Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, 11 Maret 2010. Terima kasih untuk Mas Donny, untuk semua masukannya yang sangat berguna, untuk diskusidiskusinya yang selalu mencerahkan, untuk dekonstruksi-dekonstruksi yg mengagumkan, untuk semua kiriman artikel-artikelnya, dan untuk terus menyemangati saya untuk menulis, dan tentunya untuk mengizinkan saya memuat tulisan ini
[1] Carol Gilligan,1982, In Different Voice: Psychological Theory and Womens Development, Cambridge, Harvard University Press, h. 2. [2] Frans Magnis-Suseno, 2005, Etika Kepedulian, Etika, dan Laki-Laki dalam Franz MagnisSuseno (ed.) Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatoloco ke filsafat Perempuan, dari Adam Mller ke Postmodernism, h. 236-244. [3] Ibid. hal. 237-238. [4] Ibid. hal. 243. [5] h. xv. [6] Jacques Derrida, 1992, Force of Law: the Mystical Foundation of Authority dalam Drucilla Cornell, Michel Resenfeld, David G. Carlson (eds.), Deconstruction and the Possibility of Justice, New York, Routledge, h. 6 [7] Ibid., h. 4. Like One blogger likes this post.
from Psikologi dan hukum Perubahan? Hadapi dan Nikmati Saja Dampak Psikis Kekerasan dalam Rumah Tangga 6 Comments leave one
1. Batavusqu permalink May 5, 2011 4:27 am Kangen euy dengan warnanya Reply
Ester Lianawati permalink* May 7, 2011 8:13 am warna apa, mas ^^ pa kbr, mas? mksh dah mampir ya Reply
2. Didin Septa Rahmadi permalink October 21, 2011 10:06 pm haiiiii. suatu hal yang masih membuat saya bingung sampe sekarang!!! perbedaan tingkat sexsualitas antara pria dan wanita apakah ada kaitannya feminisme? sehingga adanya tuntutan kesetaraan gender?!!! dan terima kasih atas tulisannya untuk menambah refrensi!!! Reply
Ester Lianawati permalink* October 22, 2011 10:06 am mas Donny, tlg bantu jelasin ya. makasih Reply
3. Donny Danardono permalink October 23, 2011 6:32 am Saya kira tak ada perbedaan tingkat seksualitas antara pria dan wanita. Tak ada data yang mengatakan tingkat seksualitas pria lebih besar daripada wanita. Kalau pada zaman dulu, dan mungkin sekarang, pria mereasa lebih bebas membicarakan dan mengumbar hasrat seksnya, itu karena didasarkan pada anggapan yang bias gender tentang seksualitas pria yang lebih besar daripada wanita. Banyak sudah buku yang mengulas ini. Reply
Ester Lianawati permalink* October 23, 2011 8:13 am mksh mas Donny. nah kaitannya dgn feminisme, krn bias gender ttg seksualitas perempuan laki2 ini jg menjadi penyebab penindasan perempuan (misalnya memaksakan hub seksual pd pacar/istri dgn alasan bhw perempuan hrs memenuhi hasrat seksualnya yg lbh besar sbg laki2, melegitimasi perselingkuhan laki2, pemuasan kebutuhan seksual dari sudut pandang laki2-laki smntr laki2 tdk merasa wajib memahami seksualitas perempuan, menjadikan perempuan sbg objek seksual yg slh satunya bs kita liat dlm pencitraan iklan2 di media dsb). perlu dicatat jg kesetaraan gender yg dimksd dlm perjuangan feminisme bukan untuk membalik situasi, misalnya kl laki2
memaksakan hub seksual maka perempuan pun bisa, atau perempuan pun berselingkuh atas dsr kebutuhan seksual yg besar. tp kesetaraan dlm arti tidak ada lg opresi thd perempuan khususnya yg berakar pd mslh seksualitas ini tdk pula menciptakan opresi baru thd laki2, dan jg dlm relasi dgn pasangan bs lbh menghargai seksualitas masing2. Ini versi sederhana nya ,ya Didin, spt kata mas Donny, kl km tertarik dgn topik ini bisa cari-cari bukunya salam Reply
Leave a Reply
Email (Address never made public) Name Website
Notify me of follow-up comments via email.
Ester Lianawati
Buku Saku Untuk Penegak Hukum
Bagi yang memerlukan buku ini, dapat menghubungi Program Studi Kajian Wanita (Kajian Gender) UI Jl Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat di 021-3160788
Recent Posts
o o o o o o o
Psychological & subjective well-being, apa bedanya? Date of Death : Dua puluh lima februari Mengungkap Preferensi Pasien, Merangkul Model-model Relasi Dokter-Pasien Robert Zajonc dan Israel Waynbaum, Kerendahan hati untuk yang Terlupakan Menyambut Tahun Baru dengan Tersenyum Kita Layak Dicintai dengan benar Kematian Cinta Dampak Psikis Kekerasan dalam Rumah Tangga Anda Perfeksionis ? Memahami Komitmen Perkawinan : Bersama Hingga Ujung Umur Memahami Psikologi Korban KDRT: Mengapa Perempuan Bertahan? Psychological & subjective well-being, apa bedanya? Psikologi dalam Ranah Hukum Perjalanan Psikologi Feminis Perempuan Jawa, Konco Wingking atau Sigaraning Nyawa? Dapatkah Bunuh Diri Dicegah? Kekerasan Terhadap Perempuan Di Seluruh Dunia
Top Posts
o o o o o o o o o o
type and pr
Recent Comments
Ester Lianawati on CONSULTATION Ester Lianawati on Mengungkap Preferensi Pasien,
Ester Lianawati on Memahami Komitmen Perkawinan : Riri on CONSULTATION Cahya on Mengungkap Preferensi Pasien, Cahya on Memahami Komitmen Perkawinan : Ester Lianawati on Memahami Lebih Jauh Teori Ester Lianawati on CONSULTATION
Flickr Photos
More Photos
Blogroll
o o o o o o
Abie Hakim Batavusqu examenfrancais Galeri Taufik Hijau Bumiku Julia
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Kajian Gender Laki-laki Baru LBH APIK Parlez Francais POPsy Pulih Punya Taufik Neh Riza- Jiwitlah Daku Kau Kutabok ;) Sandy Vidia Paramita WordPress.com WordPress.org Kehidupan sehari-hari Psikologi dan hukum Psikologi perempuan dan gender Psikologi positif Puisi Relasi personal Tentang feminisme Tentang psikologi Uncategorized
Categories
Blog at WordPress.com. Theme: Vigilance by The Theme Foundry. Follow
Follow A Feminist Psychologist's Blog
Get every new post delivered to your Inbox.
Enter your
Powered by WordPress.com
You might also like
- Pengertian KebenaranDocument11 pagesPengertian KebenaranAndiPandiNo ratings yet
- Kelompok Psi Pesantren 3-1Document15 pagesKelompok Psi Pesantren 3-1faliaznahasima1104No ratings yet
- Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah TanggaDocument24 pagesKekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tanggacatalist87100% (1)
- PERSEPSI TERHADAP ORANG LAINlDocument4 pagesPERSEPSI TERHADAP ORANG LAINlDilanNo ratings yet
- Hakekat KebenaranDocument4 pagesHakekat KebenaranNerdi NababanNo ratings yet
- Buana Mahasiswa - Makalah Pendidikan Pancasila - Analisis Kasus AhokDocument11 pagesBuana Mahasiswa - Makalah Pendidikan Pancasila - Analisis Kasus AhokSonya NANo ratings yet
- Filsafat Abad Ke 19Document11 pagesFilsafat Abad Ke 19Egy Andhika RizkyNo ratings yet
- Teori Hasil Interaksi Dan Teori Fungsional Dari Interaksi OtoriterDocument3 pagesTeori Hasil Interaksi Dan Teori Fungsional Dari Interaksi OtoriterMuhammad SubarudinNo ratings yet
- Makalah Komunikasi Konseling.Document17 pagesMakalah Komunikasi Konseling.Mirul BeibhiNo ratings yet
- Carol GilliganDocument5 pagesCarol GilliganheruhannisugiartoNo ratings yet
- KritikanDocument9 pagesKritikanVeyronickaSunshineNicqaNo ratings yet
- Buku Agama HinduDocument93 pagesBuku Agama HinduG P Surya Govinda ANo ratings yet
- Motif Dan MotivasiDocument6 pagesMotif Dan MotivasiRila winarniNo ratings yet
- Apakah Pengertian KebudayaanDocument10 pagesApakah Pengertian KebudayaanMunirahHairudinNo ratings yet
- Konsep Teori Humanistik EksistensialDocument16 pagesKonsep Teori Humanistik EksistensialAnindhiaNo ratings yet
- Konsep Teori AdlerDocument3 pagesKonsep Teori AdlerhanumzaraNo ratings yet
- Pertemuan PertamaDocument5 pagesPertemuan PertamaJansori AndestaNo ratings yet
- Makalah Ilmu Sosial Dan Budaya DasarDocument13 pagesMakalah Ilmu Sosial Dan Budaya DasarAgus Rabialdi50% (2)
- Perilaku MenyimpangDocument33 pagesPerilaku MenyimpangMuhammad HudaNo ratings yet
- Kel 2C - Makalah Peran Mahasiswa Sebagai Agent of ChangeDocument23 pagesKel 2C - Makalah Peran Mahasiswa Sebagai Agent of ChangeLETHAN MEALSNo ratings yet
- Psiko KomunitasDocument1 pagePsiko KomunitashsnlNo ratings yet
- Teori Pertukaran SosialDocument6 pagesTeori Pertukaran SosialRahma Dinantia JunaidiNo ratings yet
- Teori Komunikasi - Bella AmaliaDocument34 pagesTeori Komunikasi - Bella AmaliaBella AmaliaNo ratings yet
- FenomenologiDocument27 pagesFenomenologiNurhalimah Febrianti100% (1)
- SomatologiDocument3 pagesSomatologiAmy KochNo ratings yet
- Teori KognitifDocument29 pagesTeori KognitifMuhammad NofriansyahNo ratings yet
- Filsafat Pendidikan EksistensialismeDocument16 pagesFilsafat Pendidikan EksistensialismeIzmi AgstnNo ratings yet
- Makalah Psikologi Sosial Prasangka DiskriminasiDocument20 pagesMakalah Psikologi Sosial Prasangka DiskriminasiguzzNo ratings yet
- Bab 2Document25 pagesBab 2Iknih0No ratings yet
- Kode Etik ProfesiDocument12 pagesKode Etik Profesineti kusumawatiNo ratings yet
- Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Pembelaan DiriDocument39 pagesTindak Pidana Pembunuhan Untuk Pembelaan DiriLitaNo ratings yet
- Tulisan Ilmiah PedofiliaDocument10 pagesTulisan Ilmiah Pedofiliaretno widyastuti100% (1)
- Salinan Terjemahan Buku SOCIAL WORK With GroupDocument71 pagesSalinan Terjemahan Buku SOCIAL WORK With GroupAnggara Dwi RahmanNo ratings yet
- Pembentukan SikapDocument1 pagePembentukan Sikappuskesmas panungganganNo ratings yet
- Teori PeksosDocument17 pagesTeori PeksosErika Tania GintingNo ratings yet
- Penelitian Eksperimen Dan Kuasi Eksperimen - 5Document13 pagesPenelitian Eksperimen Dan Kuasi Eksperimen - 5Ilham HudoriNo ratings yet
- Ethic, Emic, Sosialisasi, Dan EnkulturasiDocument7 pagesEthic, Emic, Sosialisasi, Dan Enkulturasianu raffiNo ratings yet
- Makalah Teori Sosiologi PendidikanDocument22 pagesMakalah Teori Sosiologi PendidikanMuhammad RidzuanNo ratings yet
- Makalah Kelompok 9 Ilmu KewarganegaraanDocument16 pagesMakalah Kelompok 9 Ilmu KewarganegaraanRohmi ArdiansahNo ratings yet
- Hak LGBT Di MalaysiaDocument16 pagesHak LGBT Di MalaysiaMohdFirdausAmirHamjaNo ratings yet
- Fungsi Hukum PDFDocument35 pagesFungsi Hukum PDFShafira Indah PrawestiNo ratings yet
- Materi Ansos MusoDocument13 pagesMateri Ansos MusoMusoffa Basyir-RasyadNo ratings yet
- Seksual Disorder FixDocument14 pagesSeksual Disorder FixMEY PAMUNGKASTYNo ratings yet
- Kel. 1 - Kognisi Sosial IDocument18 pagesKel. 1 - Kognisi Sosial ISalsadila Dwi ZaniNo ratings yet
- Sosialisasi, Nilai Dan NormaDocument40 pagesSosialisasi, Nilai Dan NormaRakhman HakimNo ratings yet
- Institusi Sosial EdtDocument17 pagesInstitusi Sosial Edthanim syuhanaNo ratings yet
- Kertas Kerja GenogramDocument23 pagesKertas Kerja GenogramRissa Fadhilla RakhmiNo ratings yet
- NILAI-NILAI Tata Krama (Bu Anita)Document29 pagesNILAI-NILAI Tata Krama (Bu Anita)kartika wijayantiNo ratings yet
- Bab 7Document46 pagesBab 7Nadia BohariNo ratings yet
- Makalah Teori DisposisiDocument13 pagesMakalah Teori DisposisiRizal WardNo ratings yet
- Etika Jual Organ Dan HukumDocument21 pagesEtika Jual Organ Dan HukumRieYouNo ratings yet
- Aswaja Kelompok 4Document15 pagesAswaja Kelompok 4NURUL KOMARIAHNo ratings yet
- Psikoterapi HumanistikDocument7 pagesPsikoterapi HumanistikNuril Nofiya100% (1)
- METAFISIKADocument5 pagesMETAFISIKAsaifudinZ stikesmuklaNo ratings yet
- Feminist JurisprudenceDocument2 pagesFeminist JurisprudenceJordi BecNo ratings yet
- Teori Hukum FeminisDocument12 pagesTeori Hukum FeminisSadvika CokrodiharjoNo ratings yet
- Resensi Filsafat HukumDocument6 pagesResensi Filsafat HukumUbunk Brukucuts100% (1)
- Teori Sosiologi HukumDocument6 pagesTeori Sosiologi HukumMahesa M PNo ratings yet
- Pemikiran Tokoh-Tokoh Dan Teori-Teori Sosiologi HukumDocument14 pagesPemikiran Tokoh-Tokoh Dan Teori-Teori Sosiologi HukumMochamad BilalNo ratings yet
- TMK 1Document11 pagesTMK 1tri.kora2322No ratings yet
- Fungsi KotaDocument8 pagesFungsi Kotafulan_khanNo ratings yet
- Struktur AljabariDocument13 pagesStruktur AljabariNurdin Hugo FavianNo ratings yet
- Makalah BumsDocument2 pagesMakalah Bumsfulan_khan100% (1)
- Makalah BumsDocument2 pagesMakalah Bumsfulan_khan100% (1)
- Jenis Dan Bentuk KoperasiDocument12 pagesJenis Dan Bentuk Koperasifulan_khanNo ratings yet
- Gelombang Suara Handphone Pancarkan Radiasi Terhadap OtakDocument17 pagesGelombang Suara Handphone Pancarkan Radiasi Terhadap Otakfulan_khanNo ratings yet