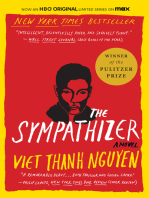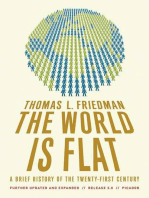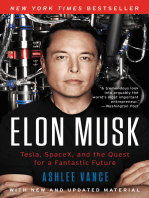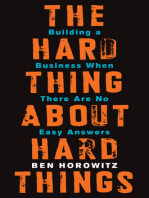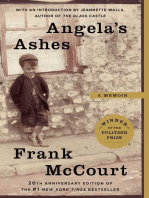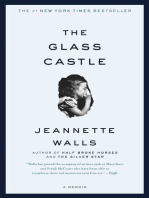Professional Documents
Culture Documents
Amor Fati PDF
Uploaded by
VENUS AUDYTE PUSTAKA0 ratings0% found this document useful (0 votes)
14 views442 pagesOriginal Title
Amor Fati.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
14 views442 pagesAmor Fati PDF
Uploaded by
VENUS AUDYTE PUSTAKACopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 442
¢
ig \\ 16-1 -1m a
CeO}
SYAHID MUHAMMAD
(ELEFTHERIAWORDS)
AMOR FATI
KITA ADALAH SEPASANG SALAH
YANG MENOLAK PASRAH
Tentang KALA. Tentang proses, romansa. Ya hidup. Dengan
penyampaian yang.. ah, baca saja. Semoga tenggelam.
~ @ghumaydha
Novel yang sungguh puitis, bahkan untuk orang-orang yang
menyukai puisi dan terlalu manis untuk dilewatkan mereka yang
tidak menyukai puisi. Novel ini untuk semua orang yang sempat
kehilangan sesuatu dalam dirinya, dan tetap percaya bahwa kelak
nanti akan menemukannya kembali.
~ Tia Setiawati (Penulis Buku Perempuan Penggenggam Rindu)
Kisah cinta yang lahir dari kolaborasi 2 penulis muda berbakat. Diksi
yang indah dari 2 sudut pandang yang berbeda dikemas dengan
alur yang menarik membuat pembaca tidak sulit untuk memahami
karakter Saka dan Lara. Bacalah, maka kau akan tau bagaimana
indahnya menginterpretasikan gambar ke dalam aksara.
~ Hani (bookstagrammer)
Satu kisah romansa dari dua penulis muda berbakat yang bisa
dikategorikan unik, dengan pemilihan diksi yang tidak umum
digunakan oleh penulis-penulis muda zaman sekarang. Alur kisah
yang manis, diceritakan dalam sudut pandang masing-masing (Saka
dan Lara).
~ F. Annisa (bookstagramer, guru)
Sebuah kisah sederhana yang mencerminkan kehidupan sehari-
hari, tetapi dengan pemilihan kata yang luar biasa indah. Kisah
yang ingin terkubur, namun dia akan selalu menemukan celah untuk
muncul dalam memorimu. Sebab Saka dan Lara adalah kau dan dia.
~ Elmaria (Master Student in Acturial Science, Kent University)
Novel ini recomended banget bagi kalian yang suka bacaan berbau-
bau sastra puisi dan yang gagal move on dalam percintaan.
~ Amberr
Untuk para penikmat sastra, buku ini bisa menjadi salah satu pilihan
untuk dibaca untuk mengisi waktu senggang, dan untuk awam
yang baru atau ingin belajar memahami sastra, buku ini merupakan
pilihan yang tepat.
~ alineafajr
Untuk pecinta genre romance buku ini sangat romantis. Saya
membaca buku ini layaknya orang gila, senyum-senyum sendiri.
Diksi dalam cerita ini amat sangat pas bikin baper. Covernya lucu
hitam manis gimana gitu.
~ Syabillaptr
Aku masih begitu terpukau dengan deretan kalimatnya. Menambah
perbendaharaan kataku juga seperti: entitas, enigma, nisbi, dsb.
Banyak kata-kata baru yang berseliweran, senang aku mendapatkan
pengetahuan lebih. Sekali lagi, tidak picisan.
~ @ra.juwita
Cocok buat yang suka novel yang agak puisi-puisi gitu, setelah
kamu baca halaman pertama, aku yakin kamu gakan bisa berhenti
sampai halaman terakhir.
~ @putridinaryr
Kisah cinta dengan akhir yang lucu. Aku pun mau punya ending
kaya dibuku ini. Semesta yang tidak mau meninggalkan sepasang
manusia yang terluka.
~ irhammaladi (http://www.penar.org)
AMOR FATI
KITA ADALAH SEPASANG SALAH
YANG MENOLAK PASRAH
STEFANI BELLA
{HUJANMIMPI)
SYAHID MUHAMMAD
({ELEFTHERIAWORDS)
€
GRADIEN MEDIATAMA
AMOR FATI
Penulis:
Stefani Bella & Syahid Muhammad
ISBN: 978-602-208-161-6
Penyunting:
flo
Penyelaras Aksara:
Tri Prasetyo
Desain Sampul dan Tata Letak:
eleftheriawords, Techno
Penerbit:
Gradien Mediatama
Redak:
Jl. Wora-Wari A-74 Baciro,
Yogyakarta 55225
Telp/Faks: (0274) 583 421
E-mail: redaksi@gradienmediatama.com
Web: www.gradienmediatama.com
Distributor Tunggal:
TransMedia Pustaka
Jin, Moh, Kahfi 2 No.13-14 Cipedak,
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
: (021) 7888 1000 Fax: (021) 7888 2000
emasaran@distributortransmedia.com
Cetakan Pertama, November 2017
Cetakan Kedua, Januari 2018
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apa pun tanpa izin dari penerbit
Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Stefani Bella & Syahid Muhammad
AMOR FATI /Penulis, Stefani Bella & Syahid Muhammad —
Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2017.
440 him. ; 13 x 19. cm
ISBN 978-602-208-161-6
1. AMOR FATI 1, Judul
I. flo
895
“Dalam sebuah KALA tempat kita bermula,
pada sebuah percaya kita ingin bermuara.”
Thanks To
\\
AMOR FATI tak pernah direncanakan sebelumnya.
Setelah kelahiran KALA, Tuhan dengan rencana-rencananya
membawa kami pada kesempatan yang tidak pernah kami
semogakan. Dengan Keromantisan Tuhan, hinggaplah kami
pada masa yang siap untuk akhirnya AMOR FATI dapat
terlahir dari dua pasang jari-jari kami.
Oleh karena itu, kembali kami ingin memanjatkan syukur
yang tiada henti tercurah. Izinkan kami mengucapkan terima
kasih untuk setiap hal yang sempat bersinggungan di hidup
kami.
Terima kasih kepada Allah SWT, atas segala kesempatan
lainnya, kekuatan, dan seluruh hal yang diberikan kepada
kami hingga detik ini. Sebab, jika bukan karena izin-Nya
karya ini tidak akan bisa lahir.
Kepada keluarga kami, terima kasih atas doa, kasih
sayang, dan support yang tidak pernah ada habisnya.
Kepada editor kami, Mbak Aning, terima kasih sudah
menemukan dan memberikan kesempatan kepada kami
untuk menjadikan kolaborasi ini nyata. Dan, tentunya kepada
seluruh tim Penerbit Gradien Mediatama yang terlibat—Mas
Tepe, Mas Tikno, dan mereka-mereka yang belum kami kenal
namanya—terima kasih. Sebab, tanpa kerja keras mereka
buku ini tidak akan hadir.
Kepada semua pembaca KALA dan tulisan kami lainnya,
kalianlah yang sesungguhnya membuat AMOR FATI punya
kesempatan untuk hidup di hati kalian.
Kepada Fadil dan rekan-rekan di The Point Coffee & Drama
di Jogja, terima kasih telah memberikan kami izin untuk
menggunakan nama tempat coffee shop-nya. Juga, kepada
Kyotown Coffee di Bandung yang menjadi tempat penulis
untuk bisa meramu AMOR FATI.
Dan, kepada Andry Bem Mandariana terima kasih untuk
dukungannya yang tiada henti terhadap kami, juga terhadap
KALA. Terima kasih atas kreativitas dan karyanya karena
telah dengan luar biasa membuatkan sebuah lagu tentang
SAKA dan LARA.
Last but not least, kepada seluruh sahabat, teman, dan
orang-orang yang mengenal kami—baik yang hanya singgah
dan masih bertahan hingga sekarang—terima kasih sudah
hadir dan memberikan banyak pelajaran akan kehidupan.
Darl Kami with Camu
\\
Hai, selamat berjumpa lagi! Bagaimana, sudah
bosan dengan kisahku? Atau, justru semakin
penasaran dengan ceritaku dengannya? Sebab,
menurut kabar yang kudengar, kamu bahkan teman-
temanmu cukup gemas dengan akhir yang katanya
menggantung.
Padahal siapa bilang itu menggantung? Menurutku,
yang kemarin itu adalah akhir terbaik yang bisa aku
ceritakan. Kamu tahu kan, meminta lebih terkadang justru
tak akan berakhir baik? Bagaimana jika nanti pada apa
yang kuceritakan ini, malah akan kamu temui hal-hal yang
mengecewakan? Jangan protes! Ingat, ini juga maumu kan?
Maka, saat ini aku putuskan untuk kembali,
menyelesaikan apa-apa yang belum selesai. Ya, aku kembali,
pada rangkaian kisah yang belum jua usai. Aku kembali,
pada potongan-potongan kejadian yang membawaku untuk
mengurai kembali segalanya agar lebih jelas. Bila pada kisah
Jalu katamu aku terlalu egois dan menuntut, maka kali ini
mungkin saja masih akan atau malah berubah. Entah aku tak
tahu juga.
Sudahlah, aku tahu kamu tak ingin berlama-lama
membaca ini. Justru kamu mungkin lebih tertarik untuk
membalik halamannya. Maka, segeralah balik halamannya
Jalu lanjutkan cerita yang kemarin sempat tertunda. Tapi
ingat, tak usah gemas sendiri. Ajak saja temanmu untuk ikut
serta merasakannya.
Sebab, kisahku ini bukan hanya tentang perjalanan
melainkan juga tentang pelajaran. Sebab, kisahku ini bukan
hanya perihal kisah cinta yang manis atau penuh kemelut, tapi
juga tentang sebuah penerimaan akan hidup. Tenggelamlah
bersama barisan aksaranya, tapi jangan sampai hanyut,
karena pagi masih menantimu untuk kembali.
Oh ya, jangan selalu berharap akhir dari kisahku ini
akan penuh kebahagiaan. Sebab mungkin, definisi bahagiaku
denganmu memang tak pernah sama.
Salam rindu,
Lara
10
\\
=, Kudengar banyak yang sebal denganku pada kisah
= Bd sebelumnya? Ayolah, jangan egois. Aku ini lelaki.
Aku yang harusnya egois, bukan?
Sebetulnya kisah yang lalu sudah selesai, bahkan
menurutku tidak menggantung. Karena di sini, perjalananku
berbeda. Tidak akan seperti yang kalian harapkan. Oh
tentu, kini aku sudah berteman baik dengan semesta untuk
mengacaukan harapan kalian. Hanya untuk kalian yang mau
untuk menerjemahkan makna di balik semua yang akan aku
persembahkan, yang dapat memahaminya.
Aku tidak berpikir aku akan berhenti menyebalkan pada
kisah ini. Karena, jika beberapa orang terlihat baik, mungkin
mereka cukup pandai menyembunyikan keburukannya. Jadi,
jika aku terlihat menyebalkan di mata kalian, sempurnakan
pandangan kalian. Mubazir rasanya memiliki sepasang mata
sempurna nan indah tapi hanya digunakan memandang
dengan sebelah mata.
Semesta, masih akan mengajak kalian berjelajah.
Cerita kami hanya sebuah portal pengingat perihal takdir
a
yang menuju diri kalian masing-masing. Apakah semua
yang terjadi memang sepatutnya demi kebaikan kalian?
Atau, justru adalah sebuah tantangan? Bahwa, kalian perlu
melakukan hal yang lebih. Karena, hanya kalian yang dapat
memahami, kapan kiranya sebuah cukup akhirnya bisa
disepakati.
Salam syahdu,
Saka
12
DAFTAR ISI
Thanks to
Dari Kami untuk Kamu
Semesta
CHAPTER |
“Kelak Setiap Kenangan Hanya
Akan Berakhir Pada Ingatan"
CHAPTER Il
“Dekat yang Tak Melekat,
Tetapi Hanya Memberi Sekat"
CHAPTER III
“Pergi, dari Satu Titik Ragu
Menuju Satu Titik Percaya”
CHAPTER IV
“Hingga Kemudian Kembali Meragu,
Pada Satu Titik yang Berujung Temu"
15
21
87
143
217
13
CHAPTER V 265
“Masing-Masing Kita Membawa Rahasia,
yang Menanti untuk Diungkap"
CHAPTER VI 319
“Pada Jarak yang Sempat Tercipta,
Sebuah Renung Seharusnya Berkuasa”
CHAPTER VII 375
“Pada Sebuah Kembali yang Seutuhnya,
Ada Sebuah Penerimaan yang Sepenuhnya"
Tentang Penulis 437
14
SEMESTA
“Mas, iced chocolate satu, ya.” pesan seorang wanita yang
baru datang. Ia duduk di kursi bar sambil tersenyum.
“Siap, Mbak. Gulanya mau manis aja apa manis banget?”
tanya seorang barista sedikit menggoda untuk mencairkan
dan mengakrabkan suasana. Terlebih, perempuan itu
sepertinya bukan salah satu tamu reguler yang sering datang
ke coffee shop tersebut.
“Manisnya yang cukup aja, asal nyaman.” Si perempuan
balik menggoda.
Sambil tersenyum, barista tadi dengan sigap menyiapkan
gelas untuk membuat pesanan perempuan itu. Tidak butuh
waktu lama, segelas iced chocolate pun ready.
“Silakan Mbak, iced chocolate-nya. Gulanya sengaja saya
pisahin aja. Saya enggak punya hak untuk nentuin seberapa
manisnya Mbak. Eh, seberapa manis minumannya buat
Mbak.”
15
Perempuan itu kemudian tertawa mendengar kelakar si
barista.
“Eh, Kev. Gue cabut ya.” Barista itu mendadak pamit
seraya melepaskan vest berwarna biru tuanya.
“Lah, tumben balik cepet lu.” Lelaki yang bernama Kevin
itu menjawab keheranan.
“Yoi, ada janji gue,” ucap barista itu sambil memamerkan
senyuman yang menyiratkan tanda tanya bagi yang melihat.
“Mas Saka pasti mau ketemu cewek sih ini. Enggak pernah
kayaknya Mas Saka pamit pulang on time,” timpal seorang
perempuan bernama Narni dari salah satu kursi yang tidak
jauh dari bar. Di mejanya tampak segelas Americano dingin di
samping buku dan tumpukan diktat.
“Serius lu? Ajegilee... akhirnya, pergi sama cewek lagi
doi,” goda Kevin.
“Ah, kalian enggak bisa apa liat temennya seneng? Udah
ya, gue cabut dulu.” Saka meninggalkan teman-temannya
setelah sebelumnya sempat kembali menyapa barista yang
lain.
“Eh, Gil, cabut duluan ya!”
Yang disapa kemudian ikut tersenyum sambil menggoda
Saka, “Mas Saka, sukses ya! Lain kali diajak ke sini toh temen
perempuannya.”
“lya, diajak Mas. Jangan disembunyiin lagi, terus tiba-
tiba cerita udah putus aja.” Narni masih menggoda.
Saka tersenyum namun tak mengindahkan godaan
16
teman-temannya. Ia hanya melambaikan satu tangannya
sebagai tanda pamit.
YO.
“Siaaal...! Kok, ilustrasinya enggak kayak yang diharepin
sih,” gerutu seorang perempuan dari balik mejanya.
Mata perempuan itu terus menatap kertas-kertas yang
menampilkan sederet gambar. Ia acuh saja meski jam di
dinding sudah menunjukkan hari semakin malam.
“Kenapa, Ra? Enggak sesuai lagi? Udah dibilang kalau
buat ilustrasi buku romance tuh mending sama yang freelancer
satunya lagi aja.” Temannya kemudian menasihati.
“Ya, masalahnya kemarin tuh udah ditanya sanggup apa
enggak? Doi jawab sanggup. Ya, udah aja kasih ke dia. Lagian
juga, gue pikir enggak ada salahnya ngasih kesempatan
buat orang lain biar bisa berkembang. Eh, enggak tahunya,
hasilnya bikin naik darah gini. Mampus, deh!”
Perempuan itu terlihat kesal. Ia membanting kertas-
kertas yang ada di mejanya, “Kalau dia belum paham konsep-
nya tuh harusnya bilang, elah. Mana deadline besok lagi.
Minggu depan harus udah up buat cetak. Sekarang, kalau
begini jadinya, kan kacau semua.”
Si perempuan lalu menghempaskan diri ke kursi sambil
memijat pelipisnya.
17
“Coba lu tanyain sama ilustrator satu lagi, keburu enggak
kira-kira kalau dia yang handle?”
“Raniiii... ini bukan masalah keburu enggaknya. Tapi, gue
telanjur deal sama yang ini. Kalau harus gue tolak padahal
udah bolak-balik revisi, kan kasian juga. Lagian, kalau
sekarang gue hubungin ilustrator yang itu, bisa kena mahal
kali bayarannya. Ya, lu pikir aja, semalem harus selesain
sekian ilustrasi, dikira lagi bikin candi?”
“Lara, gini deh mending nolak karena enggak sesuai sama
konsep. Atau, diterima tapi setengah hati? Ngejalanin yang
setengah hati tuh enggak enak loh.” Perempuan bernama
Rani itu kembali mengomentari kemarahan si perempuan,
Lara, dengan menggodanya.
“Lah, kenapa malah curhat? Haha,” Lara kemudian
tertawa sambil melirik ke jam tangannya. “Sial, udah hampir
telat. Gue cabut duluan deh ya. Ntar malem di rumah aja baru
gue pikirin lagi enaknya gimana. Atau, kalau enggak besok
lagi baru gue kerjain.” Lara berpamitan seraya membereskan
meja kerjanya.
“Lah, mau ke mana lu? Tumben amat. Ntaran lagi, Ra.
Gue masih nanggung nih. Masa lu tega, gue lembur sendirian
sekarang.”
“Gue ada janji makan malem. Lupa gue,” ucap Lara sambil
meringis memamerkan deretan giginya.
Rani sontak menghentikan kegiatannya sambil mem-
belalakkan mata menatap Lara.
18
“DEMI APA? Been centuries, akhirnya lu punya janjimakan
malem sama cowok?”
“Enggak usah lebay dih. Lagian siapa yang bilang, gue
janjiannya sama cowok?”
“Alah, udah santai kali. Muka lu enggak usah merah kalau
emang bukan sama cowok. Lagian, kalau emang iya sama
cowok juga enggak apa-apa. Gue malah seneng dengernya.”
“Hmm... Ya, udah ah, gue cabut ya. Sampe ketemu besok,
Sayang.” Lara kemudian mencium pipi teman kerjanya lalu
bergegas pergi.
~”
19
20
Semoga separuh aku yang kamu bawa dapat menemanimu.
Karena kamu pergi membawa doa-doa yang aku titipkan.
Semoga, doa-doa itu akan selalu bisa menemanimu,
bukan hanya saat kamu kesepian.
Namun, juga saat kamu bersama seseorang meski tetap
merasa sepi.
Kupastikan, aku tak kehilangan apa pun kecuali
kehadiranmu.
Percayalah, kini aku telah menerima kehilanganmu,
menerima luka yang tersisa dari kepergianmu.
Tak ada yang lebih menenangkan dari sebuah penerimaan.
Karena tak ada yang lebih menyiksa dari mempertahankan
kebencian.
Melangkahlah dengan tegap,
tak perlu lagi kamu pikirkan bagaimana aku tanpamu.
Nikmatilah kamu yang kini tanpaku.
se
CHAPTER I.
“KELAK SETIAP KENANGAN HANYA
AAU laa a CA
;°
“Thad it all figured out. So I cut out a little early, who cares? Its
probably a good thing. Life sucks, anyway. But I met you and it
got weird. And, you were so... Amazing. And I?”
“What? What?”
“I just wanted a little more time. So all in all, I'd say you’re the
worst thing that’s ever happened to me. Goodbye partner.”
“I’m staying with you until you leave. I don’t care how much
time we have! Give up you stupid jerk.”
“th, Mas Saka nangis yaaaa...?” celetuk Narni.
“Anjriiiiit... sialan, Narniiii...!” Aku yang tengah
“ menikmati scene goodbye dari film Keith harus
terganggu oleh celetukan Narni yang tiba-tiba.
“Hahahahahahahahahahahahahaha....
terbahak-bahak.
“Anjrit, mata lu kok juga basah gitu, Nyet? Hahahaha.”
Kevin tertawa
Giliran aku menggoda Kevin.
“ya, apa? Masa sih?” Kevin segera mengelap genangan
di kedua matanya.
“Duh, kalian nih ya, cowok-cowok lembut. Bisa banget
nangis nonton film drama gini.” Narni masih saja menggoda.
“Kita enggak nangis, Narni! Enggak sempet nangis
karena udah keburu kamu ganggu duluan!” Aku protes
sembari diam-diam menyeka mataku.
23
“Lagian kamu bisa-bisanya lagi nonton malah merhatiin
orang sih?” Kevin protes dan berdiri dari tempatnya duduk.
Ja menuju dapur, mungkin mau mengambil minum.
“Ya, gimana mau merhatiin, Mas? Udah kalian berdua
nonton paling depan, berisik bener sama idung. Kukira
ingusan, ternyata lagi siap-siap mau nangis. Gimana aku mau
konsen coba?” canda Narni.
Film yang seharusnya membuatku tergugah, puas akan
aksi kedua tokoh dari Natalie dan Keith, harus berakhir
mengesalkan karena Narni. Kami masih saja_berisik
menyalahkan Narni. Namun, gadis itu sama sekali tidak
merasa berdosa. Dia malah asyik menggoda kami terus. Dia
yang perempuan seharusnya lebih terharu menonton film
drama bukan?
Ini malam terakhirku di Jogja. Sebelum pulang, kami
ngumpul di rumah Narni. Dia yang memaksaku, karena
setelah sekian lama saling kenal tak pernah sempat
mengunjungi rumahnya.
“Rame juga tapi ya filmnya. Narni nanti nonton sendiri
aja ah, biar enggak ada yang ledekin kalau nangis. Hehehe.”
Narni berdiri dari ranjang tempatnya duduk.
“Ah, sialan Narni. Harusnya aku pulang ke Bandung
dalam keadaan bahagia nih. Udah bisa terharu nonton film.
Lah, malah jadi mentah gini deh.” Aku kembali protes, lalu
segera berdiri menyiapkan barang-barangku.
“Lu bawa laptop bukan? Lu nonton aja di kereta
24
ntar. Download dulu aja, bentaran juga kelar pasti.” Kevin
menyarankan.
“Yakali Sob, terus gimana ntar kalau gue di kereta
terenyuh mau nangis gara-gara filmnya? Bayangin
penumpang lain harus nahan ketawa ngeliat gue yang
gondrong gini, tapi matanya berair nonton drama. Enggak
keren lagi gue.” Aku menjawab.
“Mas Saka, lakik yang berani nangis tuh keren!
Yang enggak keren tuh lakik yang bikin nangis.” Narni
membalasku.
“Hahaaaaaaaaaa.... Kenaa lu, Nyet. Kena lu! Skak mat!
Hahahahaha....” Kevin tak bisa menahan tawa mendengar
ucapan Narni.
“Eh, Narni salah ngomong ya?” Narni belagak polos.
“Enggak, Narni. Kamu... bener.. banget....” Aku menjawab
pelan dengan wajah yang tak keruan.
Aku teringat Lara. Teringat apa yang pernah membuatnya
menangis. Sebuah penyesalan yang tidak bisa aku bayar.
Namun, kini setidaknya keadaan kami sudah cukup untuk
membuatku sedikit tenang dari rasa bersalah yang bisa saja
masih menghantuiku.
“Udah tenang, Sob. Lu sama Lara kan udah baikan.
Udah saling merelakan dan saling nerima lagi.” Kevin coba
menenangkan. Dia sepertinya bisa membaca pikiranku.
“Saling nerima lagi sebagai teman ya, Mas Saka.” Narni
masih saja menggodaku dengan ucapannya.
25
“Duh, kok gue dengernya nyelekit gitu ya.”
“Man, gue baik-baik aja. Kata-kata lu yang bikin seolah
itu nyelekit. Jangan gitu dong. Stop saying like I’m not okay. You
guys who make me not okay!”
Aku mengeluh sebal sembari mengecek perlengkapanku.
Memastikan tidak ada barang yang tertinggal.
“Eh, sori-sori, Sob. Gue enggak maksud, sumpah!
Keceplosan gue. Sori!” Kevin meminta maaf.
“Mas Kevin tuh, dijaga coba omongannya sama sahabat
sendiri.” Narni menyalahkan Kevin.
Aku hanya diam dan mengacuhkan permintaan maaf
Kevin.
“Heh! Kamu juga tuh, Narni. Mentang-mentang cewek
bisanya nyalahin doang. Hih,” jawab Kevin ketus.
Sementara mereka berseteru, aku masih sibuk dengan
barang-barangku untuk menyembunyikan wajahku, dan
mencoba memastikan apa aku benar baik-baik saja, atau
sebetulnya tidak. Meski sebenarnya tidak apa jika memang
aku masih menyimpan sisa-sisa luka. Tidak apa jika aku
memang tidak baik-baik saja. Tapi, jika aku harus berpura-
pura saat ini, aku memilih untuk berpura-pura baik-baik
saja. Ya, dari pada berpura-pura tidak baik-baik saja.
“Udah napa, pada berisik mulu. Just please stop making
fun of it. Gue tuh enggak kenapa-napa. Lu pada boleh
becandain hal itu, tapi please jangan ngomong apa pun yang
menyudutkan gue, atau seolah gue nyesek dan enggak baik-
26
baik aja. Becandanya enggak usah nyampah, please.” Aku
memberi nada tegas, meski sedikit tidak enak. Tapi, mereka
perlu tahu bahwa tidak semua orang bisa menerima gurauan.
“Siap, Pak Bos! Maafkan kami!” seru Narni dan Kevin
bersamaan.
Meski kadang menyebalkan atau kadang ada perkataan
dan gurauan mereka yang menyinggung, yang membuatku
senang adalah mereka begitu bisa menerima teguran dariku.
Bukan teman yang hanya akan lebih menyudutkanku jika
aku marah, atau tidak terima atas gurauan mereka.
Setelah selesai bersiap, kami melaju menuju Stasiun
Tugu untuk mengantarkanku pulang. Jalanan Jogja di tengah
malam selalu melambaikan kerinduan. Mengejekku dengan
riang, seolah aku akan pulang dengan berat. Aku terhibur
saat memandang lampu-lampu jalan yang seolah tersenyum
mengantarkan kepulanganku.
“Gue balik dulu ya!”
Aku pamit setelah menukarkan boarding pass di stasiun
Tugu. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kereta
yang akan membawaku pulang ke Bandung akan berangkat
30 menit lagi.
“Mas Saka, ini Narni tadi dibawain nasi kucing sama
Mama. Buat Mas Saka kalau laper di jalan. Kucingnya udah
Narni pisahin kok. Sama ini juga semangka buat makanan
penutupnya. Atau, kalau enggak mau repot, makan
semangkanya pake nasi aja biar sekalian telan.” Narni
27
tersenyum polos.
“Kapan kamu bawa semangka? Kok, enggak ketahuan?
Anyway, terima kasih Narni.” Aku berkata dengan gemas,
sedang Narni hanya tersenyum.
“Tiati, Sob. Jangan lupa bentar lagi gue lulus. Terus, yang
gue omongin kemarin dipikirin. Siapa tahu ya, siapa tahu lu
masih pengen perjuangin Lara. Kan, biar sekalian. Haha.”
Kevin memelukku.
“Hahaha... kampret! Ya, gampang lah...”
“th! Kalian ngobrolin apaan kemarin. Kok, Narni enggak
tahu sih?” Belum selesai aku menjawab, Narni langsung
memotong. Mukanya cemberut.
“Sstt.... Itu urusan lelaki, kamu jangan dulu ikut-ikutan!”
tukas Kevin.
“Lah, itu ngomongin Mbak Lara juga, berarti ada urusan
perempuannya juga dong,” balas Narni.
“th, nih anak enggak bisa dikit aja enggak bawel. Udah,
ntar juga kamu tahu. Ini masih rencana, belum bisa dikasih
tahu siapa-siapa. Nanti kalau enggak jadi kan malah malu,”
jelas Kevin berharap Narni bisa diam.
“Yo Mas, mumpung masih rencana siapa tahu aku bisa
bantu. Aku nih lagi dilanda tekanan proposal skripsi, sedang
teraniaya. Amin dariku tuh bakal didenger ribuan malaikat
Joh. Bisa bikin rencana yang kalian obrolin jadi diijabah sama
Tuhan.” Narni bersikeras ingin tahu.
Aku hanya bisa tertawa terbahak mendengar debat
28
mereka.
“Heh, Narni. Itu enggak ada apa-apanya dibanding aku
yang bentar lagi mau sidang tesis. Deg-deganku lebih kenceng
daripada kamu. Aku nih lebih teraniaya. Amin dariku bisa
bikin isi surga ikut ngaminin! Sstt, udah diem!” Kevin kali ini
benar-benar gemas.
“Emm, penghuni surga sama malaikat banyakan mana
ya, Mas?” Narni bertanya polos.
Kevin mengelap wajah dengan kedua tangan, tanda tak
lagi bisa menahan gemas. Aku masih tertawa melihat mereka
berdua. Pulang memang selalu menjadi hal terberat. Harus
membawa rindu yang tak bisa aku bawa sendirian. Aku yakin
rindu yang aku bawa akan cukup membuatku sendu dalam
beberapa hari ke depan. Sejak nanti aku kembali tiba di
Bandung.
Tidak lama, kami benar-benar berpisah. Aku melangkah
masuk ke ruang tunggu penumpang. Terlihat para
penumpang yang sedang beristirahat. Entah untuk pulang
atau melanjutkan perjalanan.
“Bu, air mineralnya satu,” pintaku kepada ibu-ibu di
kantin stasiun.
Aku lalu melongok isi bungkusan yang diberikan Narni
kepadaku. Nasi kucing dan potongan buah semangka. Aku
tertawa kecil. Sungguh ada-ada saja kelakuan gadis itu.
Langkahku gontai mencari tempat duduk yang menurutku
nyaman. Lalu, tak bisa kutolak pikiranku menyapa ingatan
29
tentang Lara.
Bahagia dan rindu sedang berpesta dalam diriku.
Perutku dibuat geli karena kupu-kupu baru saja keluar dari
kepompong. Saat seperti ini, sulit sekali menahan bibirku
untuk tidak keras kepala tersenyum. Orang-orang di stasiun
bisa menganggapku sedang jatuh cinta. Memang iya. Tapi,
mereka tidak tahu bahwa aku tidak jatuh cinta kepada
seseorang. Sial, aku merasa kikuk sendiri di antara ratusan
orang, padahal mereka tidak sedang memerhatikanku.
Aku memutuskan membuka aplikasi notes di smartphone
milikku. Rasa ini harus tumpah pada tempat yang tepat.
Kepada nurani,
Inikah tujuan dari semua langkah?
Mengantarkan aku pada rasa yang megah?
Membukakan aku sebuah pintu yang penuh berkah?
Apa kamu sedang mengejekku dengan senyummu yang
merekah?
Sial kamu nurani,
berani-beraninya mempermainkanku.
Tapi, apa daya. Aku pun dibuatnya malu dan terpaku.
Dan, akhirnya yang hanya bisa aku lakukan hanya mengaku.
Bahwa kamu telah memberiku pemahaman yang sangat
membahagiakan aku.
30
Biar saja semua orang melirikku dengan curiga.
Tentang senyum yang sedari tadi sombong ingin terus
bersinar.
Tentang degup yang tak ingin berhenti menggelar perayaan
dalam dada.
Kukatakan dengan lantang dalam diam.
Aku memang sedang jatuh cinta.
Tapi, bukan pada seseorang.
Biar saja mereka mereka-reka.
Rasa ini milikku,
takkan kubagi kepada siapa pun yang tak pantas.
Kedatangan kereta yang akan membawaku pulang telah
meneriakkan semangatnya dari jauh. Aku bergegas berdiri
dan bergerak menuju titik tunggu. Bersama para penumpang
yang ingin segera pulang, atau ingin segera sampai, atau
hanya ingin segera pergi. Kereta api Malabar tujuan Bandung
akhirnya tiba di depan kami. Semua penumpang dengan
teratur memasuki pintu masuk. Jogja, terima kasih untuk
kejutannya, rindu ini akan aku tanggung sendirian.
“Lara, sampai tiba-tiba bertemu lagi ya,” ucapku dalam hati.
31
Bandung masih selalu cerah sejak kepulanganku.
Mungkin karena seirama dengan suasana hatiku. Meski
begitu, sudah beberapa hari aku bermalas-malasan dulu.
Menghabiskan rasa bahagia yang masih bersisa. Rasa yang
mengganggu mood untuk mulai kembali bekerja. Maksudku,
untuk membuka email. Karena aku bisa tahu ada pekerjaan
design dari notifikasi email yang ada di smartphone milikku.
Sengaja aku biarkan, sekali aja aku ingin bermalas-
malasan. Ya, sesekali setelah liburanku selesai. Badanku
lesu karena terlalu banyak tertidur dan menonton TV
kabel. Sesuatu tiba-tiba muncul dalam kepalaku. Aku ingin
berolahraga. Hal yang cukup aneh memang bagiku, tapi
entah dari mana datangnya keinginan itu. Apakah Lara
mengirim doa agar aku mulai mau hidup sehat?
Entah, tapi sepertinya aku ingin. Entah hanya ingin
atau memang ingatan tentang Lara yang dulu sering
mencerewetiku perihal kesehatan, membuatku ingin
memiliki pola hidup yang lebih baik. Aku teringat ada
tempat fitness dekat rumahku. Seketika aku bersiap dan
setelah menikmati sarapan seadanya di dapur, lalu pergi
untuk mendaftarkan diri sebagai anggota. Mulailah aku
berolahraga.
Ternyata, olahraga cukup membuatku, bahagia. Badanku
terasa segar dan lelah di saat yang sama. Sesampainya
di rumah aku berniat untuk membuka email yang sejak
beberapa hari kemarin aku abaikan. Namun sayang, lelah ini
32
membawa kantuk yang sangat menggoda hingga tak terasa
aku terlelap.
Drrrtt...dddrrttt...
Kepalaku masih pusing. Sepertinya, aku baru terlelap
beberapa detik saja. Getar pesan di ponsel membangunkanku.
“Man, cek email bisa kali. Sekalian jangan lupa
gue tunggu di kantor buat brief desainnya.”
Salah satu temanku mengirimi pesan. Ah ya, aku lupa
akan membuka email yang sudah menungguku, berserta janji
untuk bertemu rekanku di kantornya. Pesan temanku itu
belum sempat aku balas.
Aku terbangun dan mulai membuka email. Setelah
membuka inbox email di layar laptop, aku tiba-tiba merasa
lapar. Entah karena olahraga yang ternyata menguras
tenaga, atau isi email yang ternyata cukup banyak. Badanku
mulai terasa pegal-pegal.
Aku seketika mengutuki diri sendiri kenapa bisa-bisanya
ingin berolahraga.
“Badan segar ternyata hanya ilusi!” Aku merutuk dalam
hati.
Tak lama aku segera mandi dan bersiap untuk pergi ke
kantor temanku.
“Udah enak males-malesannya, Kasep? Ganteng?”
Suara dari ruang tengah tiba-tiba menyapaku saat aku baru
33
menuruni tangga.
“Lah, Mamah, kirain kerja.”
“lya, Mamah ngambil libur dulu lagi enggak enak badan,”
jawab ibuku santai. Meski begitu, ibuku masih saja sibuk
dengan laptop untuk mengerjakan pekerjaannya.
Aku menangguhkan kepergianku, berjalan ke arah dapur
dan membuatkannya teh panas. Bisa-bisanya aku tidak
mengetahui jika ibuku sedang sakit.
“Nih, santai dulu atuh Mah, kerja mulu. Udah makan?”
Aku bertanya seraya duduk di sebelahnya.
“Eh, nuhun bageur. Udah udah makan kok tadi. Istirahat
teh bikin makin lemes, Mamah mah enggak suka. Mending
sambil ngerjain sesuatu biar istirahatnya produktif,” jawab
ibuku sembari meneguk teh panas dariku.
“Eh, Saka, kamu teh udah umur segini, enggak kepikiran
apa pengen nikah?” Ibuku tiba-tiba saja berhenti melakukan
pekerjaannya dan bertanya. Seolah pertanyaannya adalah
pertanyaan, biasa. Seolah apa yang aku dengar, biasa saja.
“Emm... Mamah kepikiran pengen punya mantu?” Aku
berbalik bertanya karena belum mendapatkan jawaban yang
baik untuk didengar ibuku. Aku masih sibuk terkejut dengan
pertanyaannya.
“Lah, dari dulu atuh kepikiran pengen punya mantu
mah. Mamah teh suka penasaran, Mamah bakal punya mantu
kaya gimana. Ya, habis anak Mamah kerjaannya sering pergi-
pergian. Sering di rumah cuma buat istirahat atau ngerjain
34
kerjaan.” Ibuku terdengar sedang mengerjaiku.
“Emm... Saka juga penasaran Mamah teh kepengen punya
mantu kayak gimana?” Aku masih saja menjawab dengan
pertanyaan.
“Mamah mah, yang penting kamu sayang dan enggak
bikin kepaksa. Enggak kepaksa karena Mamah nanyain kamu
kapan nikah. Enggak kepaksa karena kamu enggak tahu lagi
mau sama siapa. Enggak kepaksa kalau, amit-amit, kamu
udah ngebet banget pengen nikah. Pokoknya, jangan kalau
bikin kamu kepaksa.”
Ibuku meneguk lagi teh panasnya. Kali ini lalu
menyimpan laptop di pangkuan dan meletakkannya di meja.
Arah duduk ibuku kini menghadapku, seolah perbincangan
semakin seru. Aku semakin gemetar.
“Terus, Saka tahu kalau itu enggak kepaksa itu gimana?”
Lagi-lagi tanyaku pelan.
“Yang enggak kepaksa itu, yang bikin kamu sehat. Bikin
ibadah kamu sehat. Bikin diri kamu sehat. Bukan hanya
badan kamu sehat, tapi yang bikin pikiran kamu juga sehat.”
Ibuku menjelaskan.
Aku diam. Mataku menatap layar televisi yang
menampilkan seseorang berbaju seksi tengah membicarakan
kehidupan orang lain. Isi kepala ini bertengkar, ingin
mengeluh kenapa ibuku menonton acara seperti ini, atau
membahas apa yang sedang ibuku coba bicarakan.
“Mamah enggak kepikiran nikah lagi?” Tiba-tiba per-
35
tanyaan itu melayang dari bibirku. Aku hanya berharap, per-
tanyaan itu akan mengalihkan pembicaraan tentang diriku.
Ingin sekali aku menariknya kembali, namun kata-kata
itu kini sudah hinggap di kepala ibuku. Giliran ibuku yang
kini diam. Cukup untuk membuatku mengerti bahwa ada
yang sedang dipikirkan olehnya.
“Mamah tuh takut, Saka...” Ibuku menarik napas, “Takut
kalau anak-anak Mamah ada yang enggak setuju. Kalian pasti
enggak rela kalau posisi almarhum Bapak ada yang gantikan
di hidup kalian.” Ibuku menyelesaikan kalimatnya.
Kalimat itu menghujam dadaku, mengobrak-abrik
perasaanku, membuat degup kebingungan berdetak. Aku tak
tahu pernyataan itu akan keluar dari bibir ibuku.
Ada hal yang sedang membuat sesak dan menyeruak
dalam dadaku. Ibuku harus takut terhadap anak-anaknya.
Harus mengekang keinginannya menemukan orang yang
baru untuk menemaninya. Dan, seolah aku dan adik-
adikku mengekang dirinya. Hal lainnya, kalimat ibuku jelas
menyampaikan kesepiannya.
Air mata merajuk ingin tumpah. Semua sel darah dalam
diri aku paksa untuk menahannya agar tak sedikit pun berani
untuk menggenang di kelopak mataku. Tak aku sangka,
ternyata aku memang masih tak rela jika ibuku harus bersama
seseorang yang tidak aku kenali. Aku tidak menginginkan
ada orang asing berada dalam rumahku. Kini aku hanya ingin
menjadi egois, dengan menyesali pertanyaanku yang tidak
36
bisa aku terima jawabannya.
“Mamah emang pengen nikah lagi?” Aku beranikan
untuk bertanya. Lebih bersiap untuk mendengar apa
kata beliau daripada menjawab pertanyaan ibuku perihal
keinginanku untuk menikah.
“Mamah enggak ingin mengeluh kesepian karena kamu
dan adik-adik kamu sibuk sama kegiatannya masing-masing.
Adik kamu paling gede, Sinar, udah kerja. Permata, lagi
giat-giatnya kuliah dan cari beasiswa sana-sini. Si bungsu,
Putri, seneng sama ekskul debat di SMP-nya. Mamah seneng,
kalian tuh sibuk buat ngejar cita-cita kalian. Seneng enggak
ada dari kalian yang sering di rumah cuma males-malesan.
Meskipun Mamah enggak bisa perhatiin kalian semua, tapi
dengan tahu kalian sibuk untuk hal positif, Mamah lega.
Mamah rela kesepian.” Ibuku meneguk teh yang sepertinya
kian menghangat, bersiap melanjutkan perkataannya.
“Tapi, Mamah juga pengen ada temen ngobrol. Mamah
enggak pengen minta waktu kalian terus-terusan kalau lagi
pengen ngobrol. Mamah cuma pengen minta izin kalian
kalau Mamah ingin punya ayah baru untuk kalian. Mamah
berani ngomongin ini sama kamu, karena kamu anak paling
gede. Kamu yang gantiin Bapak untuk bertanggung jawab
sama Mamah. Untuk ngasih izin sama Mamah.” Ibuku
menyelesaikan kalimat yang selama ini sepertinya menunggu
untuk diutarakan.
Hal yang kukira akan tentangku, ternyata sebenarnya
37
menyoal ibuku. Kini aku merasakan sebuah beban yang
selama ini dipendam oleh ibuku. Sebuah rindu yang lama
ibuku sembunyikan. Rindu akan seseorang yang dapat
mengayomi selayaknya saat Bapak masih hidup. Aku dan
adik-adikku bukan hanya sibuk untuk cita-cita kami. Kami
sibuk membiarkan ibuku menelan kesepiannya sendirian.
Ddrrttt...ddrrrttt....
Notifikasi pesan baru sampai di ponselku.
"Udah di mana lu? Jangan telat yak!
Bos gue lagi rewel.”
Temanku bertanya lagi. Aku hampir lupa bahwa aku
harus pergi. Tapi, aku tak mungkin meninggalkan obrolan
dengan ibuku menggantung.
“Sok, kalau kamu harus ngerjain kerjaan. Pergi aja dulu ya.
Mamah juga mau ngerjain kerjaan lagi. Eh, nanti pulangnya
Mamah minta tolong nitip beliin madu hitam ya. Punya
Mamah udah habis.” Ibuku mengerti bahwa aku harus pergi.
Sungguh tidak adil bagaimana ibuku yang harus selalu
mengerti akan kesibukan anak-anaknya.
“Nanti, kita ngobrol lagi ya, Mah. Nanti Saka coba ngobrol
juga sama yang lain. Saka pergi, dulu. Assalamualaikum.” Aku
pamit dan mencium punggung tangan ibuku. Meninggalkan
pernyataan yang setidaknya bisa menenangkan ibuku. Tidak
menggantung dengan perasaan yang mungkin membuatnya
38
tak keruan karena telah mengatakan hal-hal yang membuatku
tidak nyaman.
“Walaikumsalam,” ibuku menjawab. Betapa ironis dan
egois, pekerjaan yang menunggu harus mengorbankan ibuku
sendiri. Seketika aku merasa menjadi anak yang durhaka.
Perasaan tak nyaman ini menaungi diriku. Namun, aku yakin
ibuku tidak marah dan tidak merasa ditinggalkan.
“Ya elah, gue kira lu lagi ngapain. Itu kursor
kedip-kedip mulu, capek kali dianggurin.”
Ucapan dan tepukan halus Rani sukses mem-
buatku terperanjat. Aku yang sedari tadi hanya menatap
kosong ke layar monitor sambil bertopang dagu, kemudian
menoleh sambil tersenyum menatap wanita berkacamata itu.
“Kenapa lu bengong aja? Biasanya jam segini kalau enggak
lagi nulis atau ngedit, lu blogwalking. Ini kenapa kayak orang
kesambet gitu?” Rani kembali mengajukan pertanyaannya
kepadaku usai meneguk air dari gelas yang tadi dibawanya.
Rani adalah editor di tempatku bekerja saat ini. Kiranya
aku bisa menyebut dia sebagai Kanaya kedua. Sifatnya mirip
sekali dengan Kanaya. Hanya saja Rani belum sedekat itu
denganku. Percakapan kami pun tidak pernah menyinggung
masalah pribadi. Hanya berkutat soal pekerjaan dan
39
gosip-gosip yang memang sedang marak dibicarakan oleh
kebanyakan orang.
“Enggak tahu nih, enggak ada ide. Males juga ngerjain
yang lain. Kalau belum deadline kayaknya kurang berasa
dikejar.”
“Dikejar banget, Ra? Lagian tumben amat enggak ada ide
tulisan. Hidup lu lagi kurang sedih sama kurang patah hati
tuh kayaknya,” ucap Rani seraya terkekeh sambil kembali
mengamati kertas-kertas di hadapannya.
Aku tak menimpali ucapannya sama sekali, justru
sibuk memikirkan ucapan Rani tadi. Aku kembali diam dan
mengingat-ingat kapan terakhir kali menulis dengan lancar
bahkan bekerja dengan teramat sibuk sampai lupa waktu
untuk sejenak menjeda.
“Mungkin karena ini di Jogja,” pikirku.
Hawa santainya membuatku jauh lebih rileks dalam
melakukan kegiatan. Tak seperti sedang dikejar waktu,
pun tidak seperti sedang mengejar sesuatu. Atmosfernya
memang teramat berbeda ketika aku berada di Jakarta.
Hingga akhirnya aku tak sempat lagi merasakan kesedihan,
karena cukup sibuk menjadi bahagia dengan kehidupanku
sekarang.
Atau, mungkin juga benar seperti kata Rani tadi. Aku
kurang patah hati. Bahkan aku lupa kapan terakhir kali aku
merasakannya, sampai akhirnya mataku menemukan sebuah
tulisan di arsip blogku. Seketika aku terpaku pada akhir
40
kalimat dalam tulisan itu. Tulisan yang sudah cukup lama
aku unggah.
-
Kamu, awal tanpa akhir dan akhir yang tak
membutuhkan awalan:
=
Seketika itu juga pikiranku kembali saat aku dan Saka
akhirnya kembali bertemu, tidak dalam kondisi yang salah
apalagi bertengkar. Malah pertemuan itu terjadi dalam
kondisi yang teramat tepat untuk kemudian membuatku
dengannya bisa menyelesaikan apa yang masih mengganjal.
Seulas senyum tiba-tiba saja tersungging di bibirku hanya
dengan mengingat momen itu. Bahkan aku juga teringat
momen saat aku dan Saka lagi-lagi tidak sengaja bertemu di
coffee shop, sehari sesudah camping itu berlalu.
Mungkin memang benar apa yang tadi Rani katakan,
hidupku saat ini kurang mengalami kesedihan pun patah
hati tak sedang kurasakan. Hubunganku dengan Saka yang
sudah kandas, kukira akan menyisakan namanya dalam
barisan tulisanku hingga bertahun-tahun lamanya. Tapi
ternyata, sesudah percakapan di pantai itu, aku bisa selega ini
melepasnya. Tak merasakan sesak, justru perasaan bahagia
tengah menguasaiku dengan terang-terangan.
Saka, dia saat ini memanglah bukan siapa-siapa lagi di
hidupku. Bukan seseorang yang memiliki status khusus
bahkan istimewa untuk membuatku dan dia terikat. Tapi,
41
tanpa status itu sekalipun, kehadirannya di hidupku ternyata
membuat segalanya lebih dari sekadar cukup. Hubungan
kami bahkan sudah lebih dari sekadar kata baik.
“Ra, beneran kesambet lu lama-lama! Tadi bengong,
sekarang mesem-mesem. Gih, kerjain itu naskah yang
barusan gue email. Dimarahin sama Rio baru tahu rasa lu!”
Rani kembali menyadarkanku.
“Serba salah mulu gue kayak Raisa hahaha,” aku
kemudian tertawa menanggapi ucapan Rani, seraya mulai
mengecek inbox.
Aku sendiri tak habis pikir dengan apa yang ada di hati
dan pikiranku saat ini. Sebuah perasaan yang baru kali ini
aku miliki ternyata mampu membuatku kehabisan kata-kata
untuk menggambarkannya. Mungkin memang benar kata
orang-orang, lebih mudah menuliskan kesedihan daripada
kebahagiaan.
“Saka, apa kabar?” tanyaku lirih di dalam hati.
a
“Loh Lara, kamu enggak makan siang?”
Aku yang sedang asyik membaca naskah dari Rani
mendadak dikagetkan oleh suara lelaki yang kini tengah
memandangiku dengan lekat. Rio, dia adalah pemimpin
redaksi di kantor. Saat pertama kali datang ke sini aku jarang
42
bersinggungan dengannya, karena dia baru cuti. Tapi, lain
halnya untuk saat ini. Aku bahkan bisa melihatnya berada
di kantor setiap hari, pun ketika ada rapat redaksi di tiap
Minggu.
“Eh iya Pak, ini nanggung, hehe.” Aku menjawab
pertanyaannya sembari menggaruk leher yang tidak gatal
untuk menutupi kecanggungan yang tiba-tiba saja merebak
di sekitarku.
“Deadline?” tanyanya sembari menautkan kedua alis.
“Belum sih Pak, emang lagi asyik aja.”
“Kerjaannya kan bisa ditunda dan enggak ngaruh apa-
apa juga. Tapi, kalau makan siang ditunda bisa kena maag
kamu.”
Aku sedikit tersentil mendengar kalimat itu. Aku ingat
sering menasihati Saka seperti ini saat aku masih berpacaran
dengannya. Jika dulu aku terbiasa mengingatkan, sekarang
justru aku yang perlu diingatkan oleh hal-hal yang sudah aku
tahu betul konsekuensinya.
“Eh, iya sih. Bentar lagi deh Pak, 5 menit lagi.”
“Berapa kali dibilangin sih kalau enggak usah manggil
Pak? Panggil nama aja kayak yang lain. Atau, kalau alesanmu
biar sopan, ya udah panggil Mas aja.”
Umurku dengan Rio memang tak jauh berbeda, hanya
terpaut 2 tahun lebih dewasa dia daripada aku. Sejak pertama
bertemu dengannya, Rio memang menyuruhku untuk
memanggilnya dengan nama saja. Atau, bisa juga dengan
43
embel-embel mas, seperti karyawan lain memanggilnya.
Tapi, entah kenapa ketika berpapasan dengannya aku selalu
lekat dengan sapaan pak.
Mungkin karena pembawaan Rio yang sangat dewasa dan
penampilannya yang karismatik, sehingga membuatku segan
kepadanya. Padahal cara berpakaiannya tidak menyiratkan
kedewasaan umurnya sama sekali. Bahkan cenderung jauh
dari umurnya. Mirip dengan Saka, hanya saja ini dalam versi
yang lebih rapi. Sepatu new balance cokelat tua dan sweter
abu-abu yang sering dikenakannya membuat Rio seperti
Jelaki yang baru saja lulus bangku perkuliahan.
“Ya, udah buruan beresin kerjaannya, kita makan siang
bareng abis itu.”
Ucapannya tidak terdengar seperti pertanyaan, justru
seperti sebuah perintah. Sejak kapan pula dia menawariku
untuk makan siang bersama, dan aku menyetujui ajakannya.
Seusai mengatakan hal itu Rio justru segera melangkah
ke luar, membuat aku hanya terdiam sambil menatap
punggungnya dengan keheranan.
Belum usai menelaah apa yang tadi Rio ucapkan,
suaranya kembali terdengar. Namun, kali ini setengah
berteriak, “Buruan Ra, aku tunggu di mobil ya!”
Aku segera menyimpan naskah yang tadi kubaca
kemudian mematikan komputer. Buru-buru mengambil
gawaiku setelah sebelumnya memasukkan dua lembar uang
pecahan lima puluh ribu pada case belakangnya.
44
Jika hanya ke luar untuk makan siang seperti ini, aku
memang tak suka membawa banyak barang apalagi tas.
Karena, bagiku waktu makan siang bukanlah saat yang
tepat untuk disibukkan dengan kegiatan lain yang justru
membuatku tidak bisa menikmati hidangan yang tersaji.
“Loh Ra, kamu enggak bawa tas?” Rio memandangku
yang baru saja masuk ke dalam mobilnya dengan tatapan
penuh keheranan.
“Enggak,” aku menoleh sembari menggeleng, lalu
memasang seatbelt, “cuma mau makan siang, kan?”
“Tya sih, tapi biasanya cewek tuh mau ke mana aja selalu
bawa tas,” ucapnya sambil mulai melajukan mobil.
“Ya, itu kan cewek biasanya, Pak. Eh, Mas. Nah, aku
kan cewek yang enggak seperti biasanya.” Aku kemudian
tersenyum memamerkan sederet gigiku kepada Rio. Rasanya
baru kali ini aku berbicara sepercaya diri itu kepada seseorang
yang masih dibilang cukup baru di hidupku.
Rio tertawa mendengar gurauanku, “Haha, ya, ya, ya.
Aku tahu itu sejak pertama kali liat kamu.”
“Ha? Gimana, gimana?” Aku tersedak mendengar
jawabannya.
“Enggak, itu tadi ada kucing lewat. Eh, ini mau makan di
mana?”
Aku menyatukan alis sembari menatapnya heran.
Gurauan lelaki itu justru tak lucu sama sekali. Aku tahu
ucapannya hanyalah untuk mengalihkan topik saja.
45
Sebetulnya ingin mencari tahu maksud dari perkataan Rio,
tapi sudahlah aku terlalu malas untuk sekadar bertanya.
“Dih lucu dia mah, segala bawa-bawa kucing. Makan di
mana aja, terserah.”
“Kalau aku kasih kamu pilihan buat turun sekarang di
tengah jalan atau turun di tempat sepi enggak ada angkutan
umum, jawabanmu juga terserah?”
“Eh, ya itu mah kalau Masnya tega.”
Rio melirikku sekilas kemudian menggelengkan kepala.
“Ra, Ra, hidup itu selalu ngasih pilihan ke kita. Terserah itu
bukan jawaban. Terserah itu milik mereka yang enggak tahu
mau dibawa ke mana hidupnya.”
Aku tersenyum melihat Rio. Menarik juga pikirku.
“Salah, Mas. Terserah itu lebih luas tahu artinya. Gini,
ketika kita ngasih jawaban terserah berarti ada hal yang
melatarbelakangi itu. Pertama, karena emang seikhlas itu
nerima mau diajak ke mana aja dan emang udah sepercaya
itu dengan pilihan si pemberi pertanyaan. Kedua, karena
emang sedang enggak ada rencana mau milih apa. Ketiga,
karena enggak mau sampe melukai keinginan dari si pemberi
pertanyaan untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau.”
“Gimana, gimana, Ra? Coba jelasin, coba.” Rio bertanya,
tampak tertarik dengan jawabanku.
“lya, gini. Tadi kan yang ngajak makan tuh Mas Rio. Ya,
manalah aku tahu kalau sebenernya Mas Rio tuh mau makan
miayam misalnya. Terus, ketika aku jawab mau sop ayam kan
46
jadi enggak cocok. Mematahkan keinginan Mas sebelumnya.
Padahal siapa tahu tadi Mas udah ngebayangin enaknya mi
ayam pake ceker dengan kecap dan sambel yang pedes. lya,
enggak?”
Rio terlihat sejenak berpikir sebelum kemudian
mengangguk dan bersuara. “Oh, I see. Menarik dan cukup
masuk akal sih. Tapi, tetep aja sih, Ra. Kalau kita udah dikasih
pertanyaan gitu dan bebas nentuin pilihan, berarti si penanya
emang udah seikhlas itu untuk ngasih pilihan dan keputusan
ke yang dia tanya. Kedewasaan seseorang bisa juga diukur
dari dia yang bisa menentukan pilihan loh.”
Kini giliran aku yang memikirkan perkataan Rio. “Iya sih,
tapi itu juga enggak bisa dijadikan tolok ukur kedewasaan,
Mas. Itu malah...”
Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Rio sudah
memotongnya, “Ya, udah ya, bahasannya udah dulu. Tuh, di
depan ada tongseng, makan itu aja mau?” Rio mengarahkan
jari telunjuk pada sebuah warung makan di pinggir jalan.
“Mm...
“Jawab iya atau enggak, jangan terserah lagi.”
“Tya mau,” ucapku sambil memberikan senyuman tipis
kepadanya.
“Good girl!” Rio tersenyum seraya mulai menepikan
a”
mobil.
47
48
Memiliki
Kita pada akhirnya kembali semesta pertemukan,
dengan rencananya yang selalu mencengangkan.
Kita pada akhirnya mampu menerima segala hal,
dengan lebih terbuka tanpa menyimpan sedikit pun sesal
serta amarah.
Kita pada akhirnya bisa tersenyum dan saling mendamaikan,
usai seluruh perdebatan yang dulu begitu kita kutuk sebagai
kesalahan.
Kita pada akhirnya sampai pada sebuah pemahaman,
yang terbentuk dari sebuah perenungan ketika jarak
berkuasa.
Kita telah sampai pada titik itu.
Kita sampai meski dengan tertatih bahkan sesekali merintih.
Untuk kamu yang kembali hadir membawa serta seluruh
kenyamanan dan menyingkirkan ketakutan, terima kasih
telah memberi banyak pelajaran.
Untuk kamu yang kembali datang membawa ribuan
pemahaman dengan penerimaan yang tidak pernah aku
sangka sebelumnya, terima kasih karena sudah berani untuk
menyelesaikan.
Dan terima kasih, untuk kamu yang akhirnya membiarkanku
kembali memilikimu, sebagai apa pun kamu di hidupku.
-L-
Aku baru saja mem-posting sebuah tulisan baru di Blog
ketika teleponku berdering. Mama calling.
“Assalamualaikum. lya Ma, ada apa?”
“Waalaikumsalam. Yeee, kamu mah, Mamanya baru nelepon
udah ditanya ada apa.”
“Hehe, Lara lagi engga konsen tadi, Ma. Jadinya langsung
to the point deh.”
“Kamu tuh ya, enggak kangen emang sama Mama?”
Sebuah pertanyaan terdengar dari seberang telepon
dan aku hanya tersipu mendengarnya. Entah, rasanya
selalu seperti ini ketika beliau menanyakan kerinduanku
kepadanya.
“Bilang aja Mama yang kangen, haha. Mau dibawain apa?
Minggu ini Lara balik kok, Ma.”
Aku tersenyum di ujung telepon sambil menutup laptop.
“Bakpia telo ungu ya, tiga. Kejunya dua,” pinta ibuku.
“th, banyak banget! Emang Mama sanggup ngabisinnya?”
tanyaku lagi.
49
“Ya, kan buat disimpen-simpen. Nanti kalau Mama mau lagi,
tinggal makan aja. Enggak usah nungguin kamu balik. Kalau
nungguin kamu balik tuh bisa keburu udahan kepinginnya.”
Sebuah sindiran halus kini terdengar dan membuatku
keki. Tapi, aku tak kehabisan akal, justru sekarang balik
menggoda dengan sebuah permintaan yang terselubung.
“Makanya, kalau Mama mau bisa makan itu kapan aja,
ikut pindah ke Jogja, yuk! Temenin Lara di sini, biar kita
engga LDR-an lagi. Hehehe.”
“LDR-an banget, Nak? Dulu sama yang kemarin aja betah buat
LDR, nyamperin mulu lagi. Ini LDR-an sama Mamanya, malah
jarang nyamperin.”
Aku dibuat mematung oleh ucapan ibuku barusan. Tiba-
tiba saja kembali teringat kebiasaanku untuk berkunjung
ke Bandung bila akhir pekan datang. Sudah lama rasanya
tidak bertemu Saka. Terakhir kali, itu pun pertemuan tidak
sengaja di coffee shop di Jogja. Setelah itu perjanjianku
dengannya sebelumnya tetap berlaku. Kami tidak akan
saling menghubungi jika aku tidak lebih dulu berkunjung
ke kotanya, atau kami kembali dipertemukan secara tidak
sengaja.
Aku tersenyum mengingat-ingat hal itu hingga suara
ibuku di ujung telepon kembali terdengar.
50
“udahan ngelamunnya? Ini Mamamu masih nelepon loh.”
“Hahaha, enggak ada yang ngelamun, Ma. Ya, udah nanti
Lara beliin pesenan Mama. Ada yang mau dititip lagi?”
“Titip bawain calon mantu ya, Nak. Assalamualaikum.”
Belum sempat aku protes mengenai omongan ibuku,
beliau sudah mematikan sambungan telepon. Meninggalkan
aku yang hanya bisa tersenyum menggeleng sambil berucap
lirih.
“Waalaikumsalam.”
Sebetulnya topik itu menjadi salah satu hal yang
membuat aku malas bolak-balik ke Jakarta dan berlama-lama
ada di rumah. Meski aku senang dengan sifat jahil ibuku dan
sering merasakan rindu akan sifatnya itu, tapi tetap saja, aku
merasa malas jika beliau sudah mulai merambah ke ranah
jodoh dan semacamnya.
Ya, aku memang hidup di tengah keluarga yang bisa
dibilang cukup kuno. Bila seorang wanita belum menikah
di umur twenty something, maka akan banyak pertanyaan
‘kapan’ yang akan hadir.
Tak hanya berhenti sampai di situ, pertanyaan kapan
adalah momok terbesar di setiap acara keluarga yang
kuhadiri. Bila belum juga membawa pasangan maka
pertanyaan yang mampir adalah, kapan menikah? Bila sudah
menikah dan belum jua dikarunia anak, pertanyaannya
51
akan berganti dengan, kapan punya momongan? Bila sudah
menikah dan punya anak, pertanyaannya akan semakin
bervariatif dengan, kapan nih dikasih adik? Kasihan masa
sendirian aja anaknya?
Menarik sebetulnya. Banyak sekali yang lebih peduli
dengan kekurangan hidup orang lain dibandingkan dengan
kekurangan hidupnya. Sibuk menambal sulam kekurangan
dirinya dan memamerkan kesempurnaan semata di depan
khalayak umum.
Masih dirasa belum cukup, mereka juga menerapkan
standar definisi bahagianya kepada orang lain. Dengan kata
lain, bila seseorang yang dia kenal itu belum seperti apa
yang ada di bayangan mereka, maka orang itu memang tidak
bahagia.
Aku memijat kedua pelipis dengan ujung jari telunjuk
dan ibu jari. Menyandarkan kepalaku di kursi sambil
memejamkan mata. Berusaha menghentikan isi kepalaku
yang terasa semakin melelahkan jika terus-menerus kuberi-
kan pemikiran seperti tadi. Mendadak aku dihadiahi semesta
sebuah perasaan rindu. Rindu untuk berkisah dan berbagi,
setidaknya kepada sahabatku, Kanaya.
a
52
Aku mulai kembali pada rutinitas pekerjaan
freelance-ku. Karena hampir setiap hari pulang
malam, belum sempat lagi aku dan ibuku melanjut-
kan perbincangan kami. Belum sempat juga aku mengajak
ngobrol adik-adikku perihal apa yang disampaikan ibuku.
Meski kadang aku mengerjakan pekerjaan di rumah,
ibu dan adik-adikku pasti sudah berangkat untuk bekerja
dan sekolah saat aku terbangun. Lalu, tak lama bosan akan
datang dan membuatku ingin mendatangi beberapa coffee
shop untuk mencari inspirasi dan melanjutkan pekerjaanku.
Tidak hanya bergelut dengan rutinitas, aku mulai
membeli beberapa buku untuk aku baca. Aku juga semakin
aktif untuk menulis di Blog pribadiku. Hal lain yang
membuatku tetap merasa hidup dan tidak kesepian. Hal lain
juga yang menggantikan hobiku berkutat dengan kamera,
karena sudah jarang mengikuti kegiatan komunitas fotografi.
Di suatu weekend, aku memutuskan berkumpul dengan
beberapa rekan komunitas menulis di salah satu coffee shop
di Bandung. Ajakan dari salah satu teman.
“Mas Saka kemarin abis dari Jogja katanya ya? Ketemu
sama anak-anak nulis di sana?” tanya Nina, salah seorang
anggota di komunitas menulis.
“Tya. Hehe. Sebenernya enggak sengaja ketemu. Ternyata
temenku ada yang ikutan komunitas nulis juga. Hehe.” Aku
menjawab sambil asyik menatap layar laptop karena sedang
memikirkan tulisan yang akan aku buat.
53
“Ketemu Mbak Lara lagi dong ya? Gimana rasanya,
Mas? CLBK enggak? Hahaha,” goda Asri, salah satu anggota
lainnya.
“Hah? Hehe.” Aku kikuk dan terperangah setengah mati.
Bagaimana mereka bisa tahu perihal aku dan Lara? Seketika
diriku merasa tak nyaman ada di sekitar mereka.
“Hehe, aja nih. Ciyeee...” goda yang lain.
Aku hanya bisa tertawa menutupi ketidaknyamananku.
Aku tidak pernah suka urusanku dicampuri. Entah sejak
kapan, entah bagaimana. Aku hanya tidak suka. Aku yang
terbiasa tertutup, membuat hal seperti ini menjadi seperti
serangan. Padahal sepatutnya aku bisa biasa saja. Namanya
juga komunitas, kabar bisa beredar di antara para anggota.
Tapi, aku tidak pernah suka hal itu. Tidak pernah.
Ingin sekali aku bercerita kepada Lara. Keadaanku
dengannya sudah baik dalam hal apa pun. Ya, kami baik.
Perasaanku kepada Lara masih ada, tapi tidak lagi ada ambisi
untuk memenangkannya kembali. Entah karena memang
benar aku sudah rela, atau aku yang memaksa diri ini untuk
rela.
Tapi, aku lebih suka seperti ini. Memiliki perasaan
kepadanya yang tidak membuatku kelimpungan, tidak
membuatku khawatir akan apa pun. Aku bebas. Kami merasa
bebas. Tapi, di saat yang sama seolah aku memiliki dirinya,
sebagai apa pun dia untukku.
“Eh, katanya Mbak Ratih lagi siapin buku yang kedua
54
ya?” Anto, seorang perbankan yang juga anggota komunitas
bertanya.
“Hehe. lya nih, doakan ya.” Ratih mengangguk sungkan.
Ratih adalah salah satu anggota yang diseniorkan. Jam
terbang menulisnya sudah tinggi. Dia sudah menulis sejak
2010. Butuh waktu enam tahun hingga bisa dilirik oleh salah
satu penerbit yang tak sengaja blogwalking di laman miliknya.
Ia kemudian ditawari membuat buku, dan ternyata memiliki
pembaca yang cukup banyak.
“Gilak, gilak, belum juga ada lima bulan udah bikin buku
lagi aja, Mbak. Kapan ya aku juga bisa bikin buku? Hehe,”
ucap Rudi, anggota komunitas juga.
“Eh, kalian juga bisa tahu. Cuma ya yang konsisten aja
kalau nulis. Aku aja enggak pernah kepikiran pengen bikin
buku. Aku nulis karena suka. Cuma pengen curahin isi kepala
sama hati aja. Tapi, rezeki siapa yang tahu. Setelah bertahun
nulis ada yang nawarin buat dibikin buku. Eh, sekarang
malah ketagihan. Hahaha. ” Ratih tertawa.
Fyi, Ratih adalah seorang guru honorer di salah satu SD
di Bandung. Di antara padatnya jadwal untuk mengurusi
pelajaran dan nilai-nilai anak didiknya, ia masih bisa
menyisakan waktu untuk menulis.
“Enam tahun ya, Mbak? Aku masih harus nunggu lima
tahun lagi dong biar bisa nerbitin buku. Haha,” canda Rudi.
“Waktu akan rezeki orang kan beda-beda. Siapa tahu
kalau kamu konsisten bisa lebih cepet. Yang penting, kamu
55
coba pelajarin pembaca. Kamu mungkin awalnya nulis cuma
nyampah, cuma curhat. Tapi di stase berikutnya, saat sadar
ternyata tulisan kamu banyak yang baca, kamu akan mulai
memperhatikan pembaca. Kamu mulai peduli apa yang
ingin pembaca dapatkan dari tulisan kamu.” Ratih coba
menjelaskan.
“Kalau gitu, kita harus ngikutin mau pembaca dong?”
Nina bertanya.
“Kalau itu menurut aku tergantung pemahaman masing-
masing. Tergantung tujuan menulis masing-masing orang.
Gimana pun itu, kalau kamu nyaman ya kerjain. Tapi yang
harus diperhatikan, gimana pun pembaca adalah salah
satu jalan rezeki kita juga. Mereka yang setia baca tulisan
kita, yang ngebantu kita untuk bisa terus berkarya.” Ratih
menjawab.
“Tumben-tumbenan obrolan kita ada faedah nih,”
celetuk Anto, dan membuat kami tertawa mendengarnya.
“Bikin apa nih sekarang, Mbak? Masih prosa?” tanya
Asri.
“lya, masih buku prosa atau senandika aja.” Ratih
menjawab.
“Apa itu senandika, Mbak,” tanya seseorang di sudut
meja.
“Bentar, gue buka KBBI. Eng... senandika itu wacana
seorang tokoh dalam karya sastra dengan dirinya sendiri di
dalam drama yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan,
56
firasat, konflik batin yang paling dalam dari tokoh tersebut,”
papar Asri dengan baik hatinya menjelaskan.
“Eh, enggak coba bikin novel non fiksi, Mbak?” Anto ikut
bertanya.
“Hmm, nah ini aku tuh pengen bahas. Kalau kalian
sendiri tuh lebih seneng baca prosa-prosa gitu atau baca
novel sih?” Ratih balik bertanya.
Pertanyaan Ratih itu bisa jadi terpicu dengan sebuah
keanehan yang terjadi dalam komunitasnya. Semua teman
dari Blog menerbitkan buku yang serupa. Kalau enggak prosa
ya novel. Aku yang belum tahu banyak tentang tulis-menulis
hanya bisa menikmati obrolan mereka. Sebuah pengalihan
yang baik daripada membahas hubungan seseorang.
“Emmm, aku sih lebih seneng prosa. Enggak panjang-
panjang, dan langsung ke inti. Jadi, lebih kaya makna tapi
tanpa harus baca keseluruhan cerita. Sama kayak quote-quote
gitu,” Nina berpendapat.
“Aku lebih suka novel. Kalau baca novel itu bisa ngebawa
kita sama ceritanya. Jadi, kayak kita cuma perlu duduk, tapi
diajak jalan-jalan.” Asri berpendapat. “Tapi, aku juga suka
prosa kalau bagus mah. Hehe,” Asri menambahkan.
Aku menikmati obrolan ini. Tak pernah terpikirkan juga
jika tulisanku akhirnya dibuat buku. Mimpi yang tak pernah
berani aku semogakan. Bukan perihal kepandaian dalam
menulis, ini tentang diriku yang memang tak pernah berani
bermimpi.
57
Aku baru menyadari bahwa aku hidup tanpa mimpi. Aku
hanya menjalani hari sesuai inginku saja. Sesuai caraku. Saat
ada hal yang harus aku kejar, seolah itu hanya membuatku
lemah karena seringkali aku hanya merasa tak akan mampu
menggapainya.
Selesai ngumpul dengan teman-teman komunitas
menulis, aku beranjak pulang, Pembahasan tentang menulis
terus terngiang di kepalaku selama aku mengemudikan
motor matic milikku.
Betapa kesuksesan seseorang bisa terdengar begitu
menggoda, seolah kita bisa melakukan hal yang sama. Saat
seperti ini, nurani dan nalar seolah akur. Cerita tadi seperti
sihir yang dapat membuat keduanya tunduk.
Aku tersadar tengah berada di satu kemacetan dalam
perjalanan pulang. Suara musik terdengar dari sebuah
bangunan yang di lahan parkirnya terlihat penuh oleh
kendaraan. Aktivitas yang akhirnya mengakibatkan sedikit
kemacetan.
Pada suatu hari nanti
Suaraku tak terdengar lagi
Terdengar sayup sebuah nyanyian dari bangunan itu,
menyanyikan sebuah puisi yang sepertinya aku kenali.
Tapi di antara larik-larik sajak ini
Kamu akan tetap kusiasati
58
Sapardi! Ya, itu puisi Sapardi! Seketika aku mem-
berhentikan motor di pelataran parkir. Terlihat orang begitu
penuh di dalamnya tengah menikmati alunan musikalisasi
puisi yang tengah dimainkan. RUANG PUTIH, tertulis di
tembok bagian depan, dekat tangga kecil yang dijadikan
tempat masuk. Sepertinya nama dari tempat ini.
Pada suatu hari nanti
Impianku pun tak dikenal lagi
Namun di sela-sela huruf sajak ini
Kamu takkan letih-letihnya kucari
Alunan musik ditutup oleh tepuk tangan yang meriah.
Tak terasa aku pun dibuat merinding mendengarkan
alunannya. Mendengarkan tepuk tangan yang berteriak atas
jiwa-jiwa yang dibuat puas.
Terlalu lama diam di rumah dan mengungkung diri
dari kehidupan sosial membuatku kehilangan pengetahuan
untuk hal-hal seperti ini. Musikalisasi puisi yang dibawakan
Ari Reda itu sanggup menghidupkan sesuatu yang sepertinya
telah lama mati dalam diriku. Mimpi.
Setelah Ari Reda, giliran pengisi acara lain yang
menampilkan musiknya. Aku berkeliling sebentar dan
memutuskan untuk memesan kopi sambil mengamati
sekitar. Tempat ini seperti sebuah portal khusus yang mem-
bawa penikmat musik mana pun bisa berada pada satu titik
59
nyaman. Titik yang tidak bisa didapat dalam keadaan biasa.
Cukup menarik bagiku. Sebuah area terbuka di bagian
tengah yang dikelilingi oleh satu bar coffee shop, satu buah
galeri, satu barber shop, dan dua kedai makanan. Bahkan
setelah aku mengecek sosial media Ruang Putih, aku
mendapati sebuah hal menarik. Ternyata di tempat ini
memang sering diadakan acara musik. Hampir setiap bulan
bahkan. Jazz, folk, blues, dan musik lainnya. Aku yang berniat
untuk pulang cepat mau tak mau mengurungkan niatku. Ada
hal yang lebih menggoda untuk aku nikmati di sini.
“Cappuccino panas satu?” Baru saja aku akan memesan
kopi, barista di depanku mendahului. Aku hanya mengangguk
sambil tersenyum.
“Cappuccino panas terus pesennya, Mas? Mau coba yang
seger-seger enggak? Ini ada kopi campur susu juga kok,”
tawar sang barista.
“Oh ya, apa tuh yang nyegerin?” aku bertanya penasaran.
“Es Kopi Susu Kioton,” ucapnya sambil tersenyum.
Setelah itu sang barista segera membuatkan pesananku
setelah aku mengiyakan tawarannya. Sejak acara musik di
Ruang putih waktu itu, hampir setiap hari saat aku sedang
bosan mengerjakan pekerjaan desain di rumah, aku selalu
60
datang kemari.
Tempat ini ternyata sangat cocok untukku. Tempat yang
terbuka membuat angin siang bisa dengan bebas menghibur
pengunjung yang ada di sini. Dengan sentuhan tumbuhan-
tumbuhan morning vibes; tumbuhan berdaun lebar, seperti
monstera, kuping gajah, talas; kaktus-kaktus lucu; dan
tumbuhan lainnya membuat Ruang Putih terasa sangat hijau
dan sejuk. Tambahan lain, satu buah kedai kopi bernama
Kyotown Coffee selalu bisa memenuhi kebutuhan kafeinku
dengan kopinya yang nikmat.
“Es kopi susu Kiotonnya Mas, silakan.”
Aku menggumamkan ucapan terima kasih. Sofa yang aku
duduki membuatku sedikit malas. Terlalu nyaman hingga
aku hanya ingin melamun lalu menuliskannya.
Aku sering begitu lelah.
Mendengar suara yang terdengar merusak.
Semua percakapan terasa egois, dan ingin benar sendiri.
Di antara sering itu, aku lebih banyak mendengar.
Sepi.
Menurutku, sepi adalah sebuah percakapan paling jujur.
Aku dapat mendengar lebih banyak kebenaran, ketimbang di
keramaian.
61
Bahkan, saat di antara ramai aku seperti kehilangan diriku.
Dalam sepi aku dapat menemukan sebenar-benarnya diriku.
Dalam sepi, aku bercakap dengan Tuhan, saat ramai tak
memberiku ruang bagiku untuk hal itu.
Dalam sepi, Tuhan memintaku untuk mendengar, apa yang
tak tersampaikan.
Mengerti, apa yang tak terdengar.
Hingga akhirnya, giliranku yang ingin berbicara.
Aku ingin menangkap sebuah gambar.
Cerita yang sepi, namun dapat memberi banyak makna dan
mengundang banyak paradigma.
Untuk menyampaikan pesan tanpa paksaan.
Untuk bercerita tanpa harus meminta orang untuk
mendengar.
Dari sebuah gambar yang ditangkap oleh mata lensa.
Semoga mereka, dapat menangkap banyak makna dengan
mata hati.
Dari sebuah gambar, kuberi mereka sebuah ruang sepi.
Agar lebih banyak mendengar, yang hati mereka ceritakan
pada dirinya.
‘Klik. Aku memposting tulisan di laman pribadiku, lalu
mengeluarkan kamera mirrorless milikku untuk mengambil
62
beberapa gambar dari tempat ini. Aku menemukan beberapa
foto diriku sendiri di kamera. Tiba-tiba pikiranku teringat
pada kali terakhir aku menghabiskan waktu dengan Lara di
salah satu coffee shop di Jogja.
Aku tersenyum rindu. Apa yang sedang dilakukan Lara
sekarang? Ah, ingin sekali aku menghubunginya. Tapi, kami
telah berjanji untuk tidak bertukar kabar hingga bertemu
lagi secara tak sengaja, atau setidaknya jika Lara datang ke
kota ini.
Aku kembali membuka Blog lalu menjelajahi tulisan-
tulisan orang lain. Membaca tulisan semua orang seolah
tengah mendengar keluh kesah mereka. Mendengar rahasia-
rahasia yang tak sempat didengar oleh siapa pun, atau
bahkan tak punya tempat di telinga orang-orang.
Seandainya semua tulisan yang ada di media sosial seperti
ini. Tidak hanya berisi hak-hak yang tengah diperjuangkan
namun di saat yang sama menyakiti hak orang lain. Tidak
melulu berisi cacian yang hanya tentang kebencian. Seolah
berramai-ramai mengajak pembaca untuk ikut membenci.
Namun aku sadar, mungkin mereka juga telah lama
diam. Telah lama menyuarakan keresahan mereka, tapi tak
ada satu pun yang mendengar dan mengerti. Seolah aku pun
tak ada bedanya dengan mereka. Tengah memperjuangkan
sesuatu.
Tiba-tiba sebuah pesan masuk di Blog milikku. Tertulis
nama akun, Eleftheriana.
63
“Aku suka semua tulisanmu. Rasanya, semua kata
seperti sedang menari di kepalaku :)"
Aku tersenyum dan sedikit penasaran. Aku mengunjungi
laman Blog miliknya. Ketika kembali membuka tulisan-
tulisanku, setelah aku perhatikan ternyata dia selalu
meninggalkan sebuah pesan pada kolom komentar. Ia
membuat pesan berupa prosa yang seolah-olah tengah
membalas tulisanku.
Perasaan lucu hadir dalam diriku. Aku tak pernah
memerhatikan kolom komentar. Aku pikir, tulisanku
tidak ada yang membaca, pun kalau ada ya sudah. Tapi,
saat ada sebuah apresiasi yang disampaikan, sampai saat
aku mengetahuinya, ada rasa senang yang tak terduga
mendatangiku.
“Terima kasih. Mungkin suatu saat kita bisa menari
bersama :)”
Balasan aku kirimkan. Beberapa detik kemudian aku
ingin sekali menjitak kepalaku sendiri. Untuk apa aku
membalas segombal itu. Sial! Namun, pesan sudah terlanjur
terkirim. Aku hanya bisa menertawakan dan memarahi
diriku sendiri dalam waktu yang bersamaan.
Aku mulai melihat satu demi satu tulisan yang dia
tinggalkan di kolom komentar dari setiap tulisanku.
64
Membawaku pada sebuah imajinasi tentang dirinya. Meski
avatar miliknya hanya sebuah gambar siluet seorang
gadis, tetapi pikiranku membentuk sendiri setiap lekukan
wajahnya. Bagaimana mata dan bibir, hidung dan telinganya.
Seperti ada kesenangan sendiri dalam salah satu aspek
harapan ketika terjadi kontak dengan seseorang yang tidak
kita ketahui.
Di Sepertiga Malam
Pernah ada seseorang berkata,
teruslah menulis sebab karenamu aku tahu bagaimana
mengungkap rasa.
Pernah ada seseorang berkata,
teruslah berani mengutarakan rasa melalui tulisanmu,
sebab karenanya aku menjadi mampu memikirkan apa yang
sebelumnya tak pernah kurenungkan.
Aku tersenyum sekaligus tertawa dalam hati.
Selama ini, tidak pernah ada yang menganggap apa yang
kuukir berarti.
Selama ini, tidak pernah ada yang berkata aku berhak atas
suara yang kuingin perdengarkan.
Lucunya, kata-kata itu hanya mampir di beranda dunia
mayaku saja.
65
Aku tak mengenalnya dengan terlalu.
Aku bahkan sama sekali tidak dekat dengannya.
Namun, sedikit kata-katanya membuatku merasa pantas
untuk kemudian berjuang.
Setidaknya, perjuangan untuk merasa hidup.
Perjuangan untuk merasa bahagia.
Perjuangan yang aku tahu adalah jawaban dari doa-doa yang
kerap kupanjatkan di sepertiga malam.
Perjuangan dari mereka yang juga pernah mendoakanku dan
membiarkan aku tetap menumbuhkan mimpi.
Ada rasa yang lucu menggerayangi diriku, hingga ke pipi
yang sepertinya kini tengah mengembang.
“Gimana Mas, es kopi susunya?” Seorang barista tiba-tiba
mendatangiku.
“Enak, kok.” Aku refleks menjawab, diikuti tanganku
yang mengambil gelas es kopi susu dan meneguknya untuk
semakin memastikan. Aku baru menyadari bahwa minuman
di tanganku ini benar-benar enak.
“Masnya tahu Kyotown Coffee dari mana nih kalau boleh
tahu? Belakangan seneng banget ke sini kayaknya ya. Hehe.”
Barista itu sudah duduk di sofa depanku.
“Kebetulan waktu itu ada acara musik gitu kan di sini,
terus saya lagi kejebak macet di depan. Penasaran ada rame-
rame kayaknya dari sini, terus mampir deh. Eh, ketagihan
66
nongkrong di sini, haha.” Aku menjelaskan.
Kami alu kami berbincang lebih jauh tentang kegiatanku,
tentang Kyotown Coffee, tentang Ruang Putih yang sering
mengadakan acara musik, hingga tentang kopi.
“Es kopi susu emang lagi tren banget ya sekarang, Mas?”
aku bertanya.
Meski aku tidak terlalu tahu bagaimana perkembangan
dunia kopi dan meski hanya sebentar belajar menjadi
seorang barista, tetapi aku cukup aware bahwa es kopi susu
menjadi sebuah fenomena menarik. Fenomena yang sedang
terjadi hampir di setiap kedai kopi.
“Yah, kayaknya gitu, Mas. Emang lucu sama pasar tuh,
bisa-bisanya sesuatu yang baru mengubah budaya.” Timpal
sang barista.
“Lucunya gimana emang, Mas?” Aku penasaran.
“Kayak, katakanlah setiap kedai kopi berusaha menjaga
kualitas kopi yang baik demi rasa yang enak di lidah pasar.
Rasa kopi juga jadi hal yang idealis bagi setiap orang yang
berkecimpung di dunia kopi. Tapi, mereka akhirnya harus
mengakui bahwa kopi enggak melulu tentang rasa. Mereka
harus berhenti untuk merasa seperti Tuhan yang selalu tahu
tentang kopi yang enak dan baik bagi pasar. Karena akhirnya,
pasar yang menentukan. Ada hal lain yang akhirnya membuat
pasar beralih. Es kopi susu misalnya, jadi fenomena yang
luar biasa di dunia kopi, karena sekarang menu yang satu itu
udah kaya lifestyle.” Barista di depanku terlihat bersemangat
67
menjelaskan.
“Menurut Mas sendiri, dengan mengikuti tren yang
lagi happening kayak sekarang ini, merasa mati di tangan
idealisme sendiri enggak sih?” Aku bertanya. Agak riskan
memang jika harus membahas idealisme.
“Untuk beberapa orang, saya rasa sih iya, Mas. Cuma
gimana, kita hidup dari pasar. Kita hanya pelayan yang mau
enggak mau harus manut sama tren yang lagi berlangsung.
Meski untuk beberapa kedai kopi atau coffee shop besar,
es kopi susu atau kopi bukan pemasukan terbesar, tetapi
dilihat dari demand yang tinggi terhadap es kopi susu, kedai-
kedai kopi kayak kita harus mau ikut hanyut.” Barista itu
menjelaskan.
Kami beranjak dari perbincangan mengenai kopi yang
sedang tren hingga persiapan dan apa yang dibutuhkan bagi
orang-orang yang ingin membuat kedai kopi. Ada sesuatu
dalam diriku yang sepertinya sangat tertarik perihal kopi.
Bukan hanya untuk sekadar ikut-ikutan tren di dunia kopi
yang membuat semakin banyaknya kedai kopi. Lebih besar
dari sekadar itu. Dunia kopi seperti hidup itu sendiri. Banyak
hal yang selalu diperbincangkan tapi tak pernah menemukan
titik temu untuk dijadikan jalan keluar. Terlebih, aku selalu
suka bagaimana seorang barista selalu memperhitungkan
rasa. Sama seperti apa yang pernah aku alami.
68
Bagaimana Jika
Bagaimana jika sebuah perkenalan pada akhirnya memang
akan berakhir dengan perpisahan?
Apakah kamu masih akan semangat untuk menunggu sebuah
pertemuan?
Bagaimana jika sebuah perjumpaan hanyalah awal untuk
kemudian saling meninggalkan?
Apakah kamu lantas akan percaya kepada mereka yang
mendekat?
Menariknya aku masih saja tetap menunggu.
Menariknya aku masih saja tetap percaya.
Pada siapa katamu?
Pada duka setelah kehilangan, aku masih menunggu suka.
Pada luka setelah kepergian, aku masih percaya selalu akan
ada yang menetap.
--L--
69
“Besok ikut liat sunrise di Mangunan bareng
kan, Ra?”
A Aku yang sedang asyik mendengarkan lagu
sambil membuat tulisan di Blog terperanjat akan kehadiran
Rio di sampingku. Senyumnya merekah ketika bertanya
kepadaku. Siang ini dia mengenakan kemeja lengan panjang
berwarna abu-abu dengan vest rajut tak berlengan warna
hitam. Heran, lelaki ini sepertinya memang selalu senang
mengenakan baju berlapis-lapis.
“Hmmm... enggak, Mas. Aku enggak bisa ikut hehe.”
“Loh, kenapa?” ucapnya sambil mengambil kursi di
sampingku, lalu membuka toples berisi keripik yang ada di
meja.
“Harus pulang ke Jakarta. Soalnya, udah dua minggu
belum pulang.” Aku mengambil segelas air putih, sembari
menutup Blog, dan kembali fokus dengan naskah yang baru
saja di-print dan sudah siap untuk aku baca ulang.
“Homesick terus ya? Sampe bolak-balik mulu,” tanyanya
lagi.
“Haha, enggak juga sih. Cuma kan Mama di sana
sendirian, jadi enggak enak aja kalau enggak pulang.”
“Oh, Mamamu tinggal sendiri? Lalu, Ayahmu?”
Aku meliriknya sekilas. Menatap manik mata itu lalu
mempertimbangkan apakah harus memberitahu tentang
keluargaku. Mungkin sudah bukan saatnya aku terus-
menerus mengelak untuk menjawab pertanyaan seperti ini.
70
Pun sudah bukan waktunya aku menjawab pertanyaan itu
dengan kebohongan. Lagipula aku semestinya sudah harus
mulai terbuka kepada orang lain. Bukankah untuk menjadi
diterima, aku harus lebih dulu menerima diriku sendiri?
“Divorce, udah lama,” ucapku tenang sambil memberikan
senyuman kepadanya.
Rio menatapku kikuk. Sebuah perasaan bersalah hadir di
wajahnya. Aku yang tidak terkejut akan hal itujustru kembali
bersuara sebelum dia mengucapkan kata maaf.
“Santai, Mas. Toh, perceraian itu pilihan terbaik jika
udah enggak ada kenyamanan lagi di suatu hubungan rumah
tangga, kan? Dan, enggak semua anak-anak dari keluarga
broken home akan salah kaprah kok. You can see me, right? I’m
a good girl, I guess.”
“Percaya Ra, percaya. Cuma aku enggak enak aja jadinya
pake nyinggung tentang orang tuamu. Lagian, orang kayak
kamu mah weekend aja kerjaannya pasti cuma diem baca
buku, dengerin musik, kalau enggak ya nyari foto. lya, kan?”
“th, sok tahu!”
Aku kemudian tertawa mendengar ucapan Rio yang
memang benar adanya. Selama di Jogja, jika tidak sedang
bertolak ke Jakarta, aku hanya menghabiskan waktu
di kamar. Tak jarang, sesekali aku ke luar hanya untuk
memotret sudut-sudut indah di Jogja, menghabiskan senja di
pelataran parkir Abu Bakar Ali, atau menyusuri jalanan Jogja
di malam hari.
71
“Ye, bukan sok tahu. Tapi, itu berbicara fakta. Kalau
enggak kayak gitu ngapain tiap hari isi tasmu kalau bukan
buku ya kamera. Well, isi tas itu mencerminkan kebiasaan
orang yang memilikinya, Ra.”
“Ya, ya, ya, analisa yang menarik. Hehe.” Aku meng-
anggukkan kepala sambil menjawabnya.
Sekilas aku melihat Rio kini sedang sibuk menggerakkan
jemarinya pada gawai yang dipegang. Melihatnya yang
sudah kembali sibuk, mau tak mau aku kembali menatap
naskah di tanganku sambil membubuhkan beberapa catatan
di sampingnya.
“Kalau gitu kita flight Jumat malem ya, Ra?”
Aku mengernyitkan kening ketika mendengarnya
kembali berbicara. “Flight? Jumat? Kita? Apaan sih, Mas? Kok,
aku gagal paham.”
“Iya, kita. Aku sama kamu berangkat ke Jakarta hari
Jumat malem, penerbangan terakhir. Cek email deh, aku
udah kirim ke kamu bukti booking-nya.”
Aku yang masih kesulitan menelaah ucapan barusan
hanya mengedikkan bahu sambil menggelengkan kepala
menatapnya. Rio yang tahu aku masih membutuhkan pen-
jelasan cuma tersenyum, kemudian mengambil napas dan
melanjutkan perkataannya.
“Gini ya Lara, hari Jumat malem, aku bakal temenin kamu
untuk balik ke Jakarta. Enggak usah ge-er aku mau anterin
kamu doang. Kebetulan sepupuku juga ada yang tinggal di
72
Jakarta. Udah lama dia minta aku dateng buat dikenalin
ke calonnya. Nah, karena aku enggak tahu jalanan Jakarta
terus kebetulan kamu asli sana, lumayan kan aku bisa minta
dianterin sama kamu kalau suntuk di tempat saudaraku.
Hehe.”
“Ha? Kan, ada ojek online kali, Mas. Maps juga ada. Mau ke
mana aja kamu engga akan ilang, ih. Lagian ya, aku biasanya
ke Jakarta naik kereta tahu.”
“Kalau ojek online mana bisa diajak ke tempat-tempat
menarik, terus dijelasin kenapa tempat itu bagus. Kalau pake
maps juga ribet. Jalanan Jakarta kan enggak pernah sepi.
Nanti yang ada aku cuma buang-buang waktu di jalan aja
untuk muter kalau ternyata salah arah. Ayolah, sekali-sekali
jadi tour guide masa enggak mau? Perkara pesawat, tenang
aku enggak akan minta ganti kok.”
Rio membujukku dengan memberikan tatapan memelas.
Aku yang melihat kelakuannya itu hanya tertawa sambil
menggelengkan kepala tak percaya.
“Alesannya ih, ada aja. Aku enggak janji, ya. Karena,
biasanya kalau balik Jakarta akan sibuk nganterin Mama.
Lagian ya Mas, siapa juga yang mau gantiin tiket pesawatnya?
Kan, aku enggak minta dibeliin. Kalau pun aku akhirnya
nolak dan tiket itu hangus, itu salah Mas Rio sendiri. Kenapa
pula beli enggak bilang-bilang?”
Rio tertawa sambil mengusap tengkuk. “Kalau aku
bilang-bilang juga emangnya kamu udah pasti mau? Lagian
73
ya Ra, banyak hal di dunia ini yang kalau berkaitan dengan
kebaikan tuh enggak usah diumbar-umbar. Aku beliin kamu
tiket pesawat kan artinya aku sedang berbuat kebaikan, jadi
enggak usah disebarluaskan toh?”
“Pantes jadi Pemred, ngelesnya pinter. Alesanmu itu loh
Mas, maksa banget. Terserah wes, terserahhhhhh....”
Aku dan Rio kemudian tertawa. Sesaat setelahnya
kami kembali pada kesibukan masing-masing. Aku kembali
menekuni naskah yang harus kuselesaikan hari ini, sedang
Rio sibuk menanda tangani beberapa kertas yang baru saja
dibawakan ke hadapannya. Aku diam dan mencoba fokus.
Namun, pikiranku masih sibuk menelaah kedekatan yang
baru tercipta antara diriku dengan Rio. Semoga saja selalu
akan semenyenangkan ini untuk mengenal orang-orang
a
baru.
“Tara!”
Aku menoleh ke arah sumber suara. Mataku masih sibuk
mencari-cari hingga kemudian aku melihatnya melambaikan
tangan. Aku segera berjalan menuju ke arahnya sambil
memasukkan handphone yang sedari tadi kugenggam ke
dalam tas.
“Langsung check in aja ya, Ra.”
74
Aku mengangguk menyetujui perkataannya, yang
kemudian disambut dengan dia yang melangkah lebih dulu di
depan. Aku mengekori sambil memerhatikan punggungnya.
Terasa aneh sebetulnya. Baru kali ini aku melakukan
perjalanan dengan orang yang belum lama kukenal. Biasanya,
aku hanya bersedia bepergian dengan orang-orang yang
sudah lama kukenal, atau bahkan cukup orang-orang asing
yang kutemui selama perjalanan.
Tapi, kali ini, aku bersama dengannya. Atasanku yang
sebetulnya baru saja dekat denganku selama beberapa pekan
terakhir. Tak banyak percakapan yang terjadi di antara kami.
Tapi, ketika ada momen yang membuat kami bisa mengobrol,
maka arah percakapan itu tidak pernah tidak menyenangkan.
Aku menyukainya sejauh ini. Setidaknya aku merasa
memiliki teman saat ini. Anggap saja dia Kanaya versi lelaki,
yang bisa untuk kubagikan cerita tanpa harus memusingkan
tentang rasa.
Selesai melakukan check in, aku dan Rio sibuk dengan
kegiatan masing-masing. Aku yang baru saja mengabadikan
pesawat dengan kamera HP kemudian berbalik. Hendak
memotret suasana ruang tunggu di bandara yang cukup
ramai kali ini. Namun, ketika kamera ponselku mengarah
kepada sosoknya, aku malah tertarik untuk memotret Rio. Ia
sedang fokus berbicara dengan seseorang di telepon.
Aku baru menyadari bahwa Rio selalu terlihat rapi. Tidak
ada sedikit pun yang membuat penampilannya tak sempurna.
75
Yang menarik, dia selalu saja mengenakan outfit luar sejenis
waistcoat, puffer vest, atau sleeveless sweater yang dipasangkan
dengan kaos maupun kemejanya.
Berbeda sekali dengan Saka yang kerap berantakan
di setiap waktu. Saka seolah tak pernah peduli dengan
penampilannya. Bukan berantakan urakan. Berantakan versi
Saka itu menunjukkan kalau ia tak peduli dengan penilaian
orang lain. Bagi Saka, asalkan dirinya nyaman dengan apa
yang dia kenakan, maka pendapat orang lain tak akan berarti
apa-apa.
Tapi jangan salah, meski berantakan, penampilan Saka
selalu enak untuk dipandang. Tidak hanya olehku, tapi
juga orang lain. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang
membuatku bahkan kebanyakan orang tak bisa mengalihkan
pandangan dari dia.
Meski tak menampik kalau hal-hal berantakan itulah
yang kadang membuatku gemas dengan Saka. Ingin sekali
rasanya merapikan dirinya dari ujung rambut hingga kaki.
Setidaknya agar penampilannya bisa lebih apik dilihat oleh
ibuku.
Aku tersenyum sekilas. Membayangkan andai saja
Saka berpenampilan seperti Rio saat ini ketika nanti
bertemu dengan ibuku, mungkin beliau akan melihat Saka
dengan cara yang berbeda. Mungkin ibuku juga tidak akan
mempertanyakan perihal pekerjaan Saka, serta tak akan
khawatir dengan hubunganku dan Saka.
76
Aku buru-buru mengenyahkan pikiranku yang kembali
membuat pengandaian akan hubunganku dengan Saka. Aku
dengan Saka mungkin memang lebih baik seperti ini. Sebagai
apa pun kami bagi satu sama lain. Ya, setidaknya agar tak
saling melukai, lagi.
“Ngambil foto orang secara diem-diem tuh termasuk
perbuatan enggak baik loh, Ra. Apalagi terus-terusan diliatin
kayak gitu.”
“Ngeliatin isi HP orang lain secara diem-diem juga
termasuk menguntit dan perbuatan enggak baik, Mas.”
Aku langsung menoleh ke arahnya yang kini sudah berdiri
di belakangku. Cepat aku mematikan layar serta menarik
ponsel itu ke dadaku. Berusaha menyembunyikan apa yang
tidak sepatutnya untuk dia lihat.
Rio terkekeh. “Udah keliatan, enggak usah ditutupin juga
ih. Kalau mau foto tuh bilang-bilang, Ra. Biar bisa gaya dan
benerin penampilan dulu. Jadi, hasilnya keren.” Ia kemudian
kembali memasang senyumnya.
Aku mendengus pelan, “Kalau bilang-bilang itu namanya
bukan candid. Kalau mau yang kayak gitu mah dateng aja ke
studio foto.”
Rio kemudian mengacak-acak rambutku dan menyam-
pirkan lengannya di bahu. Aku sedikit berjengit akan
sikapnya tersebut. Tak nyaman dengan perlakuannya itu aku
kemudian buru-buru berlari.
“Mumpung belum take off, cari foto yang lain dulu ya!”
77
Tampaknya tak butuh waktu lama untuk membuat Rio
mengerti, sebab ia tak mengatakan apa-apa, pun ia tidak
berteriak memanggil namaku. Dia hanya mengangguk
perlahan sambil tersenyum seolah memahami perkataanku.
a
Aku terus memandangi gelapnya malam. Alunan lagu
Shiver yang dinyanyikan Lucy Rose mengalun indah melalui
Ipod. Secara tiba-tiba sebuah perasaan menghinggapiku.
Membuatku sedikit gusar karena beragam kata seolah
berebut keluar dari kepalaku dan memaksa dituangkan
menjadi sebuah tulisan. Aku lekas mengambil buku catatan
dan pulpen yang selalu kubawa dari dalam sling bag.
Penerimaan
Pernah ada yang berkata,
bahwa sedikit memberi jarak pada dua hati yang sempat
bersitegang itu diperlukan.
Semula aku tak setuju, tapi sekarang aku dibuatnya percaya.
Sebab bila tak ada jarak,
tentu tak ada hal yang kemudian bisa kumaknai.
Bila tak ada jarak,
78
mungkin aku masih terus menuduhmu sebagai tersangka
atas seluruh luka.
Sebab bila tak ciptakan jarak,
mungkin kita tidak akan saling terbuka untuk memaafkan
segala luka.
Bila tak ciptakan jarak,
tentu rasa yang kini hadir tidak akan lebih damai lagi.
Aku belajar pada saat kita saling berjarak,
bahwa rasa sayang semestinya tidak lantas membuat kita
merasa paling berhak memiliki.
Aku belajar pada saat kita tengah berjarak,
bahwa perasaan sayang tak selayaknya membuat kita saling
menyalahkan,
hingga masing-masing harus berkemas pergi.
Aku menyadarinya kini,
tepat setelah melihatmu kembali baik-baik saja,
setelah banyak hal yang kita lewati dan sempat membuat kita
berselisih.
Kini aku mengerti,
arti cinta tidak hanya sesempit perasaan kita yang saling
berbalas.
Bukan juga tentang kita yang tidak pernah sekalipun
bertengkar apalagi menggores luka.
79
Arti cinta juga bukan hanya perihal aku suka kamu dan
kamu menyukai aku,
lalu kita akan menua bersama.
Cinta lebih luas daripada itu.
Cinta juga termasuk menerima segala luka yang pernah
disebabkan.
Dan bagiku, cinta adalah saat di mana aku kembali berani
bersitatap denganmu.
Seperti saat ini, saat semua damai dari maaf yang tercipta di
antara kita, mampu membuat semesta cemburu.
—L--
Aku tenggelam ketika kembali membaca barisan aksara
yang kubuat. Seulas senyum seketika hadir begitu saja, kali
ini bukan dengan paksaan atau bahkan dibuat-buat. Tapi,
senyum itu datang dari kelegaan akan rasa yang sebelumnya
kukira akan bercokol lebih lama dari luka yang pernah
bersemayam.
Nyatanya, sebuah penerimaan mampu membuatku
merasa jauh lebih hidup. Nyatanya, sebuah maaf tidak
selamanya harus diucapkan, melainkan memang cukup
dengan dikomunikasikan saja alasan yang melatar-
belakanginya.
Aku masih menatap lekat ke arah jendela, menyaksikan
80
pendar lampu yang berkilauan di pekatnya malam. Jakarta.
Kota ini tak pernah tidur barang sedetik. Hingga tengah
malam pun masih saja ada yang bergulat dengan pekerjaan
pun dengan kemacetan lalu lintas.
Satu-satunya hiburan yang paling diminati hanyalah
pusat perbelanjaan. Perhatikan saja bioskop dan tempat
makan yang akan semakin ramai ketika weekend menjelang.
“Pernah ngerasa capek enggak pas tinggal di Jakarta?”
Rio yang sedari tadi asyik dengan buku bacaannya kini mulai
mengajakku berbicara.
Aku kemudian mengalihkan pandanganku menatapnya.
Tersenyum sambil memutar bola mataku mengingat-ingat
memoriku selama tinggal di Jakarta, sembari kembali
memasukkan buku catatan ke dalam sling bag.
“Capek itu manusiawi, Mas. Mau tinggal di mana aja,
kalau kita terus aktivitas pasti capek, kan?” Aku menjawab
sekaligus melemparkan pertanyaan kepadanya.
“ya, sih. Tapi, kalau di Jakarta akan berkali lipat rasa
capeknya, kan?” Rio kembali bertanya.
“Bisa iya, bisa enggak. Balik lagi kita mau mensyukuri apa
yang sedang dijalani atau enggak. Kalau enggak bersyukur
mah, capek dan keluhan bakal dateng terus. Namanya hidup,
ya kan?”
Rio mengangguk mendengar ucapanku, kemudian
kembali menambahkan. “Aku takjub sama orang-orang yang
bertahan hidup di Jakarta, Ra. Salut sama mereka, keren gitu.
81
Kemampuan adaptasi orang-orang itu ngebuat mereka bisa
bertahan di mana aja kaki melangkah. Ya, kayak kamu. Keren
bisa struggling di kota sekejam ini.”
“Wow, baru kali ini aku ketemu sama orang kayak kamu.
Yang muji kita yang tinggal di Jakarta itu keren. Kenapa
gitu?” Aku bertanya sembari mengencangkan seatbelt.
“Kenapa takjub maksudmu?” Rio menatapku lekat.
Aku mengangguk untuk memberikannya jawaban. Rio
kemudian berdeham halus, seolah sedang menyiapkan
jawaban terbaik atas pernyataannya tadi. Aku hanya diam
sambil terus menatap, memberikannya ruang untuk kembali
melanjutkan kalimat.
“Aku takjub karena enggak semua orang tahan untuk
hidup dan terus ditekan, berhari-hari, bahkan bertahun-
tahun. Kejenuhan pasti udah bersarang gitu.”
Aku kemudian mengernyit mendengarnya. Menyadari
kebingunganku, Rio mengulasi sebuah senyuman yang
menenangkan, setidaknya untukku demikian.
“Gini Ra, kalau Jogja ngajarin kamu tentang gimana
caranya ngadepin masalah dengan kepala dingin. Nah,
menurutku Jakarta ngajarin kamu untuk berpikir cepat dan
berani ngadepin masalah meski di bawah tekanan. Semua hal
dan masalah tumpah ruah di jalanan, dan penyelesaiannya
juga kadang dipikirin di jalanan. Bener enggak?”
Aku menyandarkan kepala pada sisi jendela, meletakkan
tangan kananku di dagu, tapi pandanganku masih menatap-
82
nya lekat. Jika dipikir-pikir apa yang Rio katakan memang
benar. Selama tinggal di Jakarta, semua hal rasanya memang
terkuras di jalanan. Aku terus menelaah setiap ucapan lelaki
itu kemudian mengangguk dan tersenyum sebagai jawaban
atas pertanyaannya tadi.
“Jakarta tuh... enggak tahu kenapa putaran waktunya
terasa lebih cepet. Karena, mungkin ya itu tadi waktunya
hanya dihabiskan di jalanan. Bahkan di hari Minggu aja
kalian jarang banget kan punya waktu untuk bernapas
dengan tenang di rumah atau di tempat berlibur? Mau ke mal
aja harus bermacet-macet ria atau bahkan berdesak-desakan
sama orang di halte dan stasiun.” Rio berhenti sebentar,
meneguk air mineral lalu melanjutkan perkataannya lagi.
“Ttu baru menuju aja tuh, belum lagi pas udah sampe
tempat tujuan, enggak jarang harus antri. Itu hari libur,
gimana pas hari kerja coba? Mau berangkat kerja, kalau
enggak macet ya, desak-desakan. Terus, sampe kantor tiba-
tiba kerjaan udah segunung. Mau pergi makan siang, ketemu
macet lagi. Belum lagi masih kepikiran sama kerjaan di
kantor. Mau marah, cemberut, nangis, tapi inget kalau abis
itu mau ketemu klien. See? Sekeren itu loh, bisa banget untuk
menghadapi semuanya dengan cepat.”
Mata Rio begitu berbinar ketika memberikan penjelasan.
Ia begitu bersemangat untuk mengeluarkan seluruh hal
yang kutebak selama ini hanya bercokol di kepalanya saja.
Mengendap dan seringnya dibiarkan menguap, karena tak
83
menemukan lawan bicara yang pas untuk menceritakan
segalanya.
Seulas senyum masih tergambar di raut muka Rio.
Hening selama beberapa detik sebelum ia akhirnya kembali
bersuara.
“Kalian yang tinggal di Jakarta tuh terus-menerus dapet
tekanan kayak gitu. Tapi, kalian enggak sadar telah terbiasa
untuk ngejalaninnya. Itu yang bikin aku selalu percaya,
orang-orang yang pernah ngerasain bertahan hidup di
Jakarta, bisa banget untuk kerja dan beradaptasi di mana
aja. Kamu sendiri Ra, apa yang bikin kamu betah tinggal di
Jakarta sebelum akhirnya dipindahin ke Jogja? Aku berani
taruhan, kamu enggak pernah sedikit pun punya pikiran
mau pindah kerja di Jogja, kan?”
Aku terdiam sebentar, menatap ke arah luar jendela,
kemudian mengulaskan sebuah senyum ketika melihat
deretan gedung pencakar langit yang begitu berlimpah di
kota kelahiranku ini.
“Hmmm... lya sih, aku enggak pernah ada niatan untuk
pindah kerja atau pindah tempat tinggal. Maksudku gini,
untuk liburan dan jalan-jalan aku sih selalu mau jauh dari
Jakarta. Kayak Jogja, buatku ya cocoknya hanya jadi pelepas
penat. Enggak pernah kepikiran buat jadi tempat tinggal
apalagi tempat kerja. Karena kalau sampe kerja dan tinggal
di Jogja, sewaktu-waktu aku bosen, nanti ngilangin suntuk di
mana lagi dong? Kan kalau udah ribet-ribet di Jakarta, enak
84
gitu tiba-tiba ke Jogja dan nikmatin hidup sepelan mungkin.
Enggak berasa lagi dikejar-kejar waktu.”
Aku kemudian memberikan sedikit jeda untuk sekadar
menarik napas lalu kembali berucap. “Kalau kenapa betah?
Ya, mungkin karena udah terbiasa kali. Jadinya, terbentuk
semacem zona nyaman dengan rutinitas selama di Jakarta.
Bener kata Mas Rio, kayaknya aku enggak pernah sadar akan
tekanan yang selalu dateng itu karena aku terbiasa dengan
semuanya. Bahkan tanpa sadar pola kehidupan yang seperti
itulah yang membuatku akhirnya jadi suka kalau semua
halnya well-prepared, terencana, udah disusun dari jauh-jauh
hari, dan terbiasa untuk on time. Karena, semua hal di Jakarta
enggak bisa untuk diprediksi apalagi dikira-kira.”
Aku kembali berhenti berbicara, menatap sekilas ke arah
Rio yang sedari tadi tampaknya tak mengalihkan pandangan
dariku. Dia begitu antusias untuk mendengarkan semua
ucapanku yang jika Saka sering bilang terlalu bijaksana dan
terus-menerus berpikiran positif. Padahal bisalah untuk
sesekali menciptakan hal yang berbeda agar tak selalu
terjerat aturan yang mengikat.
“Kasarnya gini Mas, sedetik aja enggak merhatiin lampu
APILL’ kita harus nunggu lagi sampe satu menit untuk
kemudian bisa nyeberang atau lewat. Atau misalnya, jalanan
yang tadinya di maps lengang, bisa mendadak macet hanya
1 Lampu APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) atau biasa disebut
lampu merah.
85
karena ada kereta lewat atau orang-orang yang belok di
sembarang tempat. Seenggak teratur itu, tapi bisa ngebuat
kita jadi manusia paling teratur untuk menyiapkan A sampe
Z. Hehe.” Aku terkekeh untuk mengakhiri ucapanku yang
tampaknya sudah terlalu panjang. Anehnya, Rio tak bosan
mendengar aku bicara. Ia justru berkali-kali mengangguk
mengiyakan setiap ucapanku.
Mengobrol dengan Rio membuatku seperti menemukan
diriku dalam wujud seorang lelaki. Bukan menemukan
sebagian diri, melainkan sepenuhnya aku. Sial, tampaknya
aku mulai nyaman untuk bertukar cerita dengannya.
Setidaknya, bersama dengan Rio aku bisa bercerita, bukan
hanya sebagai pendengar.
Perjalanan memang tidak pernah salah memerangkap
dua orang asing untuk kemudian menjadi lebih dekat
dan melabuhkan nyaman. Ada banyak hal yang tak perlu
dipaksakan untuk bisa dimengerti, tapi memang ternyata
semudah itu untuk diterima. Tak lain hanya karena cara
berpikirku dengannya yang ternyata begitu sama.
a
86
Se
CHAPTER Il
“DEKAT YANG TAK MELEKAT,
Uap aR) a
;°
Di sela-sela pekerjaanku yang telah rampung,
=<=)¥ aku mendatangi beberapa kedai kopi di Bandung
setiap hari. Belajar memerhatikan bagaimana
mereka menyuguhkan kopi, bagaimana mereka menyambut
tamu dan mengajak mengobrol. Atau, bagaimana mereka
berbagi mengenai kopi yang dibuat, serta mengenai apa yang
mereka perhitungkan.
Benar saja, beberapa tempat kopi di Bandung memiliki
menu es kopi susu. Beberapa yang tidak ada, saat aku sekadar
bertanya, ternyata mereka sedang dalam tahap persiapan
untuk menyajikan menu es kopi susu. Begitulah, begitu besar
pengaruh tren yang terjadi pada beberapa kedai kopi.
Gimana, Man? Udah lu pikirin?
Pesan masuk muncul di layar ponselku. Kevin menanya-
kan lagi perihal tawarannya.
Nanti kita ngobrol lagi ya, gue beresin kerjaan dulu.
Aku menjawab sekenanya. Saat ini aku memang tengah
membereskan pekerjaan desain yang harus aku selesaikan
dahulu.
89
“Es kopi susunya, Mas.” Barista yang mengajakku ber-
bincang saat itu datang membawakan pesananku.
Kini, setiap aku datang ke mari, es kopi susu menjadi
pesanan wajib untukku. Tidak ada lagi cappuccino yang aku
pesan, kecuali jika Bandung sedang dingin-dinginnya.
Selesai mengerjakan pesanan desain, aku bersandar
di sofa. Melamunkan semua hal yang ingin dikembarakan.
Imajinasi mulai membentuk harap. Bagaimana jika aku
menerima tawaran Kevin? Bagaimana jika aku akan bisa
sering bertemu dengan Lara? Bagaimana aku akan bertemu
orang-orang baru? Namun, tiba-tiba aku teringat ibu dan
adik-adikku.
Aku belum berani membahas lebih lanjut perihal tawaran
Kevin. Bukan tidak ingin, tapi aku tidak ingin menjanjikan
sesuatu yang belum pasti dapat aku penuhi. Harap akan
tumbuh subur dalam diri Kevin. Jika suatu saat ternyata
aku tidak bisa meninggalkan Bandung, mungkin Kevin akan
dapat memaklumi keadaanku. Tapi, tidak tentangku. Aku
akan dihantui perasaan tidak enak.
Aku tidak mungkin meninggalkan mereka, ibu dan adik-
adikku. Ada rasa ingin untuk selalu ada dengan mereka. Ada
rasa tanggung jawab yang harus aku penuhi. Sebagai anak
lelaki paling tua dan satu-satunya, serah-terima jabatan
sebagai orang yang harus menjaga dan mengayomi jatuh
kepadaku. Sebuah tanggung jawab tanpa persetujuan yang
harus aku terima.
90
Beberapa saat, aku merasa sangat ingin untuk egois lagi.
Kini, saat aku akhirnya memiliki mimpi, semua tanggung
jawab yang aku miliki seolah mengekangku, dan tidak
mengizinkanku untuk memiliki mimpi. Seandainya setiap
orang dapat memahami bahwa kita tidak bisa dengan mudah
bermimpi. Setiap orang akan tidak mudah membangun
begitu saja mimpinya di satu tempat.
MENJATUHKAN SAUH
Aku terbangun dari hujan semalam,
yang rintikknya kelelahan saat matahari berencana hadir.
Bagaimana kiranya aku bisa sampai di sini?
Aku yang memilih, atau tempat ini yang terpilih untukku?
Bagaimana aku bisa percaya,
pada semua yang dihadirkan untukku?
Padahal aku punya kuasa untuk memilih,
pada apa dan siapa sauhku akan kujatuhkan.
pada apa dan siapa aku akan menetap.
Pernahkah ada yang bertanya,
bagaimana bisa dirinya bisa ada pada suatu tempat?
Hingga pada akhirnya percaya bahwa yang ditempati adalah
yang teruntuk dirinya, selain karena tidak ada tempat lain
gi
yang bisa ditemukan, atau yang bisa ditempati.
Kiranya, kita semua begitu terbiasa pada semua hal yang
tersaji. Rasa percaya yang hadir, tumbuh bukan berdasarkan
pilihan, melainkan karena penerimaan.
Hingga akhirnya menyerah, saat percaya mulai melahirkan
kekecewaan dan memaksa kita kembali memilih.
Setia pada apa yang dihadapkan,
atau melangkah mencari yang lain,
untuk kembali menancapkan sauh.
Aku mem-posting tulisan di laman Blog pribadiku.
Menumpahkan sesuatu yang tersirat. Bagaimana pun
menulis masih menjadi hal asing yang sedang aku biasakan.
Masih sedikit malu-malu untuk sepenuhnya jujur.
Seolah mencoba berteman dengan orang baru yang
tidak aku ketahui, tapi begitu membuatku tergoda untuk
aku selami. Menulis, seperti sebuah pendekatan yang
menyenangkan. Namun, yang kudekati adalah diriku sendiri.
Lucu bukan?
Ada bagian dari diriku yang memaksa untuk jujur.
Meraung untuk menyerah pada kebohongan atau pada topeng
yang selama ini aku kenakan. Hingga akhirnya, seolah diriku
yang asli adalah diriku yang lain. Sedang, aku yang ini adalah
92
diriku yang palsu. Diriku yang telah terkontaminasi oleh
pemahaman-pemahaman yang dibentuk oleh kebutuhan
sosial.
Kepergian Lara saat itu berhasil mempertemukan aku
dengan diriku yang lain. Hal itu sepertinya yang dapat
membuatku begitu merelakan kepergian Lara. Menerima
salahku atasnya, karena membuatku akhirnya memahami
bahwa kepergiannya membawaku kepada diriku seutuhnya.
Hanya dengan kehilanganlah, aku dapat menemukan diriku
yang utuh.
Aku menyeruput es kopi susu. Manis dari gula aren
terasa menyempurnakan rasa kopi dan susu di dalamnya.
Berbeda dengan cappuccino yang biasa aku minum. Manis
buatan ini, bukan rasa yang dibuat-buat. Seperti, aku yang
kini terkejut melihat notifikasi pesan masuk di laman Blog
milikku. Muncul nama Eleftheriana, lagi.
“Menarik bukan, kita sama-sama mengirim puisi dan
prosa sebagai utusan untuk menyampaikan sapa.
Hingga sapa itu bisa jauh lebih puitis dan memiliki
irama daripada dua raga yang menulisnya, yang
mengirimnya.”
Isi pesan itu pun dibuat oleh seseorang yang masih
belum aku ketahui. Namun, rasa manis saat membacanya
tidak terasa seolah dibuat-buat olehku. Aku benar-benar
93
merasakan manis saat membacanya.
Ada rasa manis di balik ketidaktahuanku tentang seorang
Eleftheriana. Dirinya benar-benar semenyenangkan es kopi
susu yang ternyata sedari tadi masih ada di tangan kiriku.
Aku meletakkan es kopi susu di meja dan bersiap membalas
pesannya.
Jariku tak mau bergerak. Sial! Apa yang sedang terjadi
kepadaku?
“Oke, Saka kamu harus tenang. Ini adalah perasaan yang
bodoh. Kamu sangat, menyedihkan.” Aku berbicara pada diri
sendiri.
Apa benar aku semenyedihkan ini? Mudah untuk begitu
tergoda pada hadir yang begitu samar. Namun, bukankah
semua orang sangat tertarik pada hal yang membuat mereka
penasaran?
“Apakah prosa dan puisi akan tiba di titik lelah untuk
saling menyapa? Semoga saja kita tidak lelah untuk
tetap menulis rasa.”
Jariku menari seinginnya di atas keyboard. Mengetik
pesan yang ingin disampaikan oleh nurani. Nalar kali ini tak
sempat untuk mencegah atau berkomentar. Aku bingung,
apakah ini pertanda baik atau buruk? Diri ini tak semestinya
mudah untuk membuka sapa, terlebih pada nama yang tak
memiliki rupa.
94
Pesan akhirnya terkirim. Anehnya, kali ini degup sedang
kewalahan menunggu balasan. Sial, untuk apa aku menunggu
balasan? Rasa seperti ini kembali menjahiliku. Membuatku
ragu dan takut, tapi juga penasaran.
Aku menyeruput lagi es kopi susu di depanku. Rasanya
benar-benar persis seperti ini, seperti es kopi susu! Sial! Isi
kepalaku mulai kacau. Aku harus mengalihkan perhatianku,
kembali mengerjakan pekerjaan desainku.
“Aku rasa kita harus mencari tahu sendiri :)”
Pesan balasan masuk. Aku membaca perlahan, percepat,
berkali-kali, hingga tak ada arti pasti dari kalimat yang aku
baca. Hingga aku tersadar sesuatu, aku tidak merasa ragu
atau bahkan takut. Tak seperti kali terakhir dengan Lara
yang membuatku harus bertindak sangat hati-hati.
Ingatan itu membangunkan nalar yang kini mulai
mengerjaiku dengan akal-akalannya. Kali ini aku membiar-
kan nalar beraksi, membiarkan diriku dikuasainya. Aku
merasa perlu untuk benar hati-hati.
Pesan darinya tak kuindahkan, kubiarkan tanpa balasan
dariku. Aku kembali mengerjakan pekerjaanku. Hari semakin
sore, matahari terlihat mulai menghangatkan kedai kopi
ini. Beberapa orang yang sedang menongkrong memetik
gitarnya dan mulai memainkan nada serta lagu.
95
Sementara... teduhlah hatiku.
Tidak lagi jauh.
Belum saatnya kamu jatuh.
Lirik lagu Sementara milik Float berhasil menenangkan
sekaligus mengacaukan pikiranku. Rindu akan Lara masih
saja sering menghampiri. Kurasa, aku cukup paham mengapa
banyak sekali orang yang susah untuk move on.
Bagaimana tidak, rindu akan kehadiran seseorang di
masa lalu memang begitu menyesakkan. Tapi, di saat yang
sama harapan seolah sama besar dengan kemungkinan.
Rindu juga berbanding lurus dengan luka saat harap semakin
ditancapkan.
Sebuah euphoria yang kontradiksi. Sebuah rasa yang
bertabrakan namun membuat ketagihan. Tenggelam dalam
ingatan masa lalu dan hanyut dalam keadaan sekarang
merupakan rasa yang memang membuat ketagihan.
Kita memang begitu senang menyiksa diri sendiri.
Keadaan seperti itu membuatku mengerti, lebih baik terluka
dalam ingatan daripada tidak merasa apa pun sama sekali.
Ini bukan perkara ingin baik-baik saja namun perkara ingin
merasakan sesuatu.
Percayalah, hati.
Lebih dari ini, pernah kita lalui.
Jangan henti di sini.
96
“Jadi, kamu nginep di mana, Mas?” tanyaku
begitu kami sampai di depan pintu kedatangan
Bandara Soekarno Hatta.
“Di Kalibata City, saudaraku tinggal di sana. Kamu sendiri
langsung balik ke rumah?”
Aku mengangguk sambil membalas pesan yang masuk
ke telepon genggamku. Salah satunya pesan dari ibuku yang
menanyakan aku sudah berada di mana.
“Yap, langsung balik aja, udah malem juga. Kasian Mama
kelamaan nungguin aku balik.”
“Bareng aja yuk, Ra. Kebetulan aku kan dijemput
saudaraku. Masa iya kamu malem-malem gini nunggu ojek
online,” ajak Rio sambil menunjuk arah di mana saudaranya
memarkirkan kendaraan.
Aku menolak ajakannya dengan gelengan kepala ringan.
“Enggak usah, Mas. Santai aja, kalau udah balik ke kota
sendiri mau pulang semalem apa pun enggak ngerasa was-
was. Lagian aku kebetulan dijemput temen kok. Dia udah
nunggu di parkiran, jadi enggak perlu order, hehe.”
“Wuih, temen apa temen, Ra?” Kali ini pertanyaan Rio
menyiratkan keingintahuan yang cukup jelas.
“Enggak boleh kepo, nanti suka!”
o7
Aku langsung mencari menu kontak untuk menelepon
Kanaya dan menanyakan di mana keberadaannya. Sambil
menempelkan ponsel di telinga, aku segera berjalan menjauh
dan melambaikan tangan kepada Rio.
“Udah ya duluan, Mas. See you!”
“Hati-hati, Ra! Besok kabarin ya kalau bisa nemenin
keliling-keliling.”
Samar aku mendengar kalimat Rio itu, dan menjawabnya
dengan sebuah senyum simpul dan anggukan kecil. Telepon
yang dari tadi hanya terdengar nada sambung kini sudah
diangkat.
“Lu di parkiran sebelah mana?” Aku kemudian
mengedarkan pandangan mencari-cari sosok perempuan
yang sedang berbicara di telepon juga saat ini.
“Parkiran keluar motor, Ra.”
Mataku terbelalak mendengar ucapannya, kemudian
mengalihkan pandangan ke arah yang dimaksud Kanaya.
“Gilaaaa... jauh juga gue jalannya. Lagian kenapa enggak
masuk sih, bantuin gue bawa barang. Capek tahu. Kalau
enggak ikhlas jemput mah mending enggak usah, Nay.”
“Manja banget, baru juga pindah Jogja bentaran udah lembek.
Lu enggak jalan kaki sampe lima kilo kali. Udah buruan, gue
ngantuk.”
98
Kali ini Kanaya yang menggerutu di ujung telepon.
Belum sempat aku membalas perkataannya, Kanaya sudah
lebih dulu mematikan sambungan telepon. Memang sih
jarakku dengan parkiran motor tidak terlalu jauh. Tapi,
dengan sisa tenaga yang sudah habis dikuras sejak pagi tadi,
ditambah harus membawa tentengan oleh-oleh untuk ibuku
dan Kanaya, membuat langkahku terasa semakin berat.
Sebetulnya aku tidak meminta Kanaya menjemputku.
Tapi, begitu dia tahu aku akan balik ke Jakarta hari ini, ia
segera menawarkan diri untuk menjemputku.
“Sekalian nginep di rumah lu,” katanya kemarin saat aku
a
“Dari Mas Rio. Katanya, ‘Siang ini sibuk enggak? Bisa kali
jadi pemandu perjalanan. Saudaraku sibuk nganter calonnya
mengabarinya.
belanja tuh, masa tamu dianggurin. Bosen nih, Ra.
Aku yang baru keluar dari kamar mandi dibuat malas
ketika Kanaya dengan kencang membaca pesan masuk itu.
Bukan hal yang mengherankan jika Kanaya bisa membuka
passcode di ponselku. Di antara kami memang tak pernah
ada rahasia apa-apa yang disembunyikan. Kecuali... mungkin
tentang rasaku kepada Saka.
Aku hanya menghela napas pelan, tak mengindahkan
99
ucapan Kanaya barusan. Memilih untuk terus melangkahkan
kaki lalu duduk di atas tempat tidur sambil mengeringkan
rambutku yang basah dengan handuk.
“Jadi, Rio tuh siapa, Ra? Kok, gue enggak pernah denger
lu nyebut namanya,” tanya Kanaya sembari melemparkan
ponsel ke pangkuanku.
“Pemred gue, di atas gue lah pokoknya. Sebut aja doi, bos
gue,” jawabku singkat sambil mulai mengetik balasan untuk
Rio.
“Bos? Terus, lu udah sedeket apa sama doi sampe dia
minta ditemenin gitu. Lagian ya, emangnya doi di Jakarta apa
di Jogja sih?”
Usai membalas pesan Rio, aku kemudian mengambil
guling yang berada di samping Kanaya dan memeluknya erat
sembari merebahkan badan di tempat tidur.
“Lagi di Jakarta, semalem ke sini bareng gue.”
“Bareng lu? Sepesawat maksud lu? Pantes lu belagu naik
pesawat, tumben banget. Ternyata sama bos yang merangkap
calon, nih?” Kanaya mulai menggodaku kini.
“lya, dia mau ke tempat saudaranya. Terus, pas tahu gue
juga mau balik ke Jakarta ngajakin bareng deh. Siapa juga
yang nolak kalau dikasih tiket gratis?”
Sedetik kemudian Kanaya melemparkan bantal ke
wajahku. “Gaji udah gede, mental masih gratisan. Hari gini
mana ada yang gratis sih, Lara? Tiati lu sama sikap baiknya
si Rio itu. Siapa tahu doi lagi usaha deketin lu. Kalau lu nya
100
enggak mau mending ngejauh deh. Nanti anak orang keburu
ngarep. Lu dikira PHP, Ra.”
“Gini ya, kalau semua orang mikirnya kayak lu, enggak
akan ada namanya orang bisa berbuat baik deh gue rasa.
Berbuat baik dibilang ada maksud terselubung. Sekalinya tuh
orang niat beneran tulus eh, karena takut ini-itu kita malah
nolak kebaikan itu. Lu tahu enggak? Ke...”
“Enggak, gue enggak tahu, Ra.” Belum selesai aku
berbicara, Kanaya dengan iseng langsung memotong
omonganku,
“Yeee sialan, dengerin gue ngomong dulu makanya.”
Aku kemudian duduk bersandar di kepala tempat tidur.
“Kemurahan hati dan kebaikan seseorang ke kita tuh enggak
sepantesnya kita curigain dan dipikirin macem-macem.
Yang perlu kita lakuin tuh, ya udah menerima dengan ikhlas
apa yang mereka tawarkan kalau sekiranya itu enggak
memberatkan. Karena, sama aja kita udah bantuin orang itu
buat dapet pahala. Balik deh situasinya, kalau lu yang niat
baik sama orang tapi ditolak karena mikir niatnya macem-
macem, lu bakal kesel enggak?”
“Omongan lu bener juga sih, Ra. Tapi, gue berasa lagi
denger Mamah Dedeh ceramah.” Kanaya terkekeh kemudian.
“Eh, tapi ya, Ra, lu yakin itu bos lu enggak ada rasa sama lu?”
tanyanya sambil mendekatkan wajahnya ke arahku. Mencoba
melihat apakah aku berbohong atau tidak.
Melihat tingkahnya yang seperti itu aku langsung
101
mendorongnya menjauh. “Ya, kalau soal itu mah bukan
urusan gue, Nay. Biar aja itu urusan dia sama hatinya sendiri.
Lagian orang kayak dia mah mau dapet cewek model apa juga
bisa. Mukanya enggak jelek kok, manis malah. Tipikal mas-
mas Jawa yang kalau senyum manisnya kayak gula merah.
Enggak bikin sakit, tapi nagih.”
“Anjir! Lara, Lara, semenjak di Jogja kenapa bisa jadi
tukang gombal gini dah? Receh banget, sumpah.”
Aku dan Kanaya kemudian tertawa bersama. Aku
sendiri heran dengan gurauan yang baru saja kulontarkan.
Sebelumnya aku bahkan tak bisa sebebas ini. Rasanya aku
seperti sudah mulai menerima segala hal yang pernah terjadi
hingga akhirnya bisa lebih menikmati hidup, lengkap dengan
lelucon yang bisa diciptakan untuk sekadar melepas penat.
Mungkin, Saka lah yang turut ikut andil dalam semua
penerimaan yang tengah kureguk. Mungkin, Saka jugalah
yang tanpa sadar telah mengubahku untuk bisa terbuka dan
mulai lepas mengungkapkan segala rasa dan pendapat.
“Lagian elo mancing, Nay. Btw ya, mana bisa gue ngontrol
perasaan orang lain. Kalau lu tanya gue ada rasa apa enggak,
gue sih bakal dengan yakin bilang enggak ada. Eh, belum ada
deng, mana tahu besok jadi ada. Gue nanti ketulah lagi kalau
sekarang sok ngomong enggak ada.”
“Ya, iyalah mana bisa lu ada rasa ke si Rio-Rio itu,
sementara hati lu masih nyangkut di Saka. Geblek, dasar. Eh,
ngomong-ngomong ya, apa kabar tuh Saka? Masih tuh kalian
102
enggak komunikasi? Perjanjian macem apa pula sih kalian
tuh? Zaman sekarang masih aja sok-sok mengandalkan
semesta yang berkonspirasi buat mempertemukan kalian.
Lu hidup di Zaman apa sih, Ra? Lu lagi bikin kisah kayak di
novel-novel?”
Aku mendengus kesal, tidak suka jika segala hal tentang
perasaanku masih saja disangkutpautkan dengan Saka yang
saat ini bahkan sudah lebih dari kata selesai itu sendiri.
Entahlah, rasanya tidak nyaman saja jika harus kembali
mengungkit apa yang sudah terjadi. Sebab, mungkin
sebagian dari diriku juga masih berusaha untuk menerima
apa yang sebaiknya diterima, terutama ketika aku mengingat
kesalahan-kesalahanku kepada Saka.
“Berisik ah, Nay. Gue sama Saka udah enggak ada rasa
apa-apa kali, enggak usah digituin terus. Yang awalnya udah
enggak ada, malah bisa jadi ada kalau dicengin mulu.”
“Yang enggak ada bisa jadi ada sih emang. Tapi, yang
udah ada terus disangkal malah jadi makin berkembang
loh, Ra.” Kanaya masih saja mencoba menggodaku dengan
ucapannya yang selalu saja bisa untuk membuatku tak bisa
berkata apa-apa lagi. Karena, terkadang apa yang dia katakan
adalah benar adanya.
“Serah lu, serah! Lagian ya, lu mau pulang jam berapa?
Entar abis zuhur gue mau nemenin si Rio jalan-jalan,”
tanyaku berusaha mengalihkan topik.
“Gue diusir? Ih, enggak berperikemanusiaan banget sih
103
lu jadi sahabat.”
Aku menggeleng malas sambil menatap Kanaya. “Apa
deh? Siapa yang ngusir? Maksud gue nanya tuh biar nanti
keluarnya bisa bareng kalau gue tahu lu mau balik jam
berapa. Hhhh.... Heran jadi orang suudzon amat.”
“Hehe, ya maaf, Ra. Gue tidur dulu deh ya, nanti pas zuhur
bangunin. Mata gue masih sepet nih abis jemput ibunda ratu
tadi malem.”
Tanpa menunggu jawabanku, Kanaya langsung meng-
ambil selimut dan kembali melanjutkan tidurnya di sebelah-
ku. Melihat kelakuannya itu aku hanya bisa terkekeh sambil
a
“Jadi, mau ke mana kita hari ini, Bu?”
menggelengkan kepala.
Rio yang sedang sibuk memasang seatbelt di sebelahku
bertanya tentang tujuan perjalanan hari ini. Berhubung
dia tak mengerti seluk-beluk jalan di Jakarta dan enggan
menggunakan Maps, maka kemudi aku yang ambil alih.
Sepuluh menit lalu aku sudah tiba di depan apartemen
saudaranya. Menunggunya keluar sembari memikirkan akan
mengajaknya jalan-jalan ke mana hari ini.
“Mas, enggak usah ngejayus manggil ibu, ih. Enggak
usah banyak nanya juga ya, percaya aja sama aku. Insya
104
Allah enggak nyasar, tapi kalau macet mah maklumin aja ya.
Namanya juga ibukota.”
“Macet di jalanan mah biasa, Ra. Asal jalan ke hatimu
enggak usah ikutan macet aja.”
Aku yang sedari tadi fokus menatap jalanan, kini
menautkan kedua alis sambil memandang ke arahnya sekilas.
Menariknya, Rio mengucapkan hal itu dengan intonasi paling
datar yang pernah kudengar. Tidak ada nada menggoda
bahkan senyuman jahil yang biasa ditunjukkan oleh laki-laki
yang sedang berusaha menarik perhatian seorang wanita.
Bukannya mencari tahu reaksiku setelah mengatakan
hal itu, Rio justru sibuk memilih lagu yang akan dia putar.
Aku hanya tertawa lirih lalu kembali menatap lurus ke depan,
sama sekali tak mengerti dengan gurauannya.
Biarlah, mungkin lebih baik memang seperti ini. Tak
usah dilanjutkan sesuatu yang sebetulnya tak perlu terlalu
dipikirkan. Lagipula mengapa aku harus memikirkan maksud
dari perkataan Rio tadi. Atau, jangan-jangan aku penasaran.
“Ah pasti karena ucapan Kanaya nih,” ucapku lirih dalam
hati.
Aku langsung mengarahkan mobil ke arah Gambir
dengan kecepatan standar. Hari Sabtu siang di Jakarta kali ini
ternyata cukup lengang. Ya, setidaknya tak terlalu membuat
kaki pegal untuk sekadar berpindah pedal. Maklum, mobil
yang kupakai hari ini adalah mobil ibuku, bukan matic, maka
akan sedikit pegal jika aku harus berjam-jam menghadapi
105
kemacetan.
“Tahu enggak Ra, apa yang bikin Jogja tuh selalu ngebuat
kita bisa enggak merasa besar? Besar pake tanda kutip ya.
Besar karena merasa jabatan kita penting, dan besar yang
membuat kita jadi jemawa.” Lagi-lagi Rio membuka obrolan.
Bisa dipastikan sepanjang perjalanan ini seluruh percakapan
akan didominasi olehnya. Aku hanya menggeleng lemah dan
menatapnya meminta penjelasan lebih lanjut.
“Karena di Jogja tuh lebih banyak manusianya yang
bersyukur. Mungkin karena atmosfernya juga sih ya, budaya
juga. Setiap orang di Jogja tuh menghargai pekerjaannya
dengan terlalu. Sesepele apa pun pekerjaan itu bagi orang lain
yang ngeliat, tapi yang bekerja itu ngejalaninnya sepenuh
hati. Itu yang bikin manusianya satu sama lain enggak
ngerasa iri dan enggak ngerasa paling besar. Mereka bisa
sesadar itu dan nerimo dengan porsi rezeki masing-masing.”
Rio melirikku yang sedari tadi masih diam mendengar-
kannya berpendapat. “Eh, enggak bermaksud diskriminasi
ya, ini hanya pendapatku yang memang asli dan besar
di Jogja tapi beberapa kali sering plesiran ke kota lain.
Mayoritas penduduknya kayak gitu, selebihnya mah balik
lagi ke manusianya masing-masing kok.”
Aku yang sedari tadi sibuk memecah isi kepala untuk
fokus mendengarkannya dan fokus terhadap jalanan, kini
memilih untuk tak lagi diam namun menimpali. “Contohnya
kayak gimana tuh?”
106
“Nih Ra, kamu liat di depan, itu tukang parkir.”
Aku mengikuti ke mana arah telunjuk Rio bermuara.
“Dia mah asal banyak yang markir di lahannya pasti
seneng banget karena pemasukannya banyak. Enggak peduli
mau orang itu bilang makasih atau enggak. Karena, yang
penting buatnya ya, hanya uang parkirannya aja. Beda kalau
di Jogja, meski juga butuh uang tapi ada satu hal lain yang
lebih penting, yaitu ucapan terima kasih.
“Aku pernah sampe diketok kaca mobilku hanya karena
lupa bilang makasih. Padahal itu enggak sengaja, aku lagi
keasyikan ngobrol sama temenku. Terus, si bapak parkirnya
ngetok aja sambil bilang, ‘Jogja Mas, matur nuwun.’ Di situ
rasanya aku malu banget, Ra. Malu banget. Aku sampe
kepikiran kalau ucapan makasih tuh dari hari ke hari makin
terasa susah terucap. Sama kayak susah ngucapin maaf,
padahal tahu kalau dirinya salah.”
Aku dibuatnya terperangah. Sedikit terkejut dengan cara
Rio bercerita dan mengambil hikmah dari sebuah kejadian.
Aku jarang bertemu lelaki seperti Rio ini, yang mau melihat
sesuatu dengan cara dan penerimaan yang begitu berbeda.
Aku jadi penasaran dengan masa lalunya. Setidaknya pasti
ada sebuah kejadian yang membuat dirinya menjadi Rio yang
seperti ini.
Sepanjang satu jam perjalanan, percakapan didominasi
oleh Rio yang membahas tentang hal-hal yang cenderung
biasa. Namun, ketika dibicarakan olehnya justru menjadi
107
luar biasa, ya seperti percakapan tadi. Jujur saja aku
menikmatinya. Rasanya sudah cukup lama aku tidak
mengobrol sesuatu yang ringan tapi sarat makna seperti hari
ini.
Jika dulu Saka yang selalu menyuguhiku ceritanya yang
luar biasa, kehadiran Rio seolah menjadi pengobat rindu akan
kehadiran Saka. Aku buru-buru mengenyahkan kerinduanku
kepada Saka yang sepertinya masih saja sering mampir.
Usai memarkirkan mobil di Gambir, aku kemudian
mengajak Rio berjalan menuju Galeri Nasional yang letaknya
tidak jauh. Hanya perlu menyeberang dan berjalan ke sisi
kiri.
“Nah, sampe deh!” ucapku sambil merentangkan kedua
tangan bak seseorang yang sedang mempersilakan tamu
datang ke kediamannya.
Rio kemudian mengedarkan pandangannya dari ujung
ke ujung. Menatap sekeliling yang cenderung sepi. Aku
kemudian kembali bersuara sebelum ia berkomentar apa-
apa tentang mengapa aku membawanya ke sini.
“Jangan salah ya, Mas. Ini bukan sembarang galeri. Di sini
banyak hal bisa kamu dapet. Mau menikmati seni, ya di sini
tempatnya. Mau merenung? Di sini juga bisa banget. Main-
mainlah ke museum, karena banyak hal yang bisa dibawa
pulang. Ini salah satu tempat favorit aku untuk melarikan
diri, hehe. Kebetulan aku lagi pengen hunting foto, terus
kepikiran sama tempat ini. Enggak keberatan, kan kalau kita
108
ke sini? Nanti pulangnya makan es krim Ragusa deh. Oke,
oke?” rayuku sambil menangkupkan kedua tangan di depan
mukaku, seakan memohon kepadanya agar tak menolak
ajakanku kali ini.
“Selama tempat-tempat yang aku datengin beda sama di
Jogja, aku mah mau-mau aja, Ra. Enggak ada masalah. Lagian
yang penting tuh sama siapa dateng ke sininya, bukan seperti
apa indah tempatnya.”
Usai mengatakan itu dia kemudian berjalan men-
dahuluiku. Meninggalkan aku yang masih terperangah
akan ucapannya. Lagi-lagi, Rio berhasil membuatku ingin
menggaruk kepala yang tidak gatal saking dibuat bingung
oleh ucapan dan tindakannya.
Belum usai aku melamun, Rio kemudian berbalik dan
menyapaku dengan gurauannya lagi, “Mau sampe kapan
berdiri di situ? Panas loh, nanti kamu item. Yuk ah, masuk.
Jelasin ke aku mana aja tempat yang menarik di sini.”
Aku yang tersadar dari isi kepalaku, lalu setengah berlari
menyusulnya sambil mengikat satu rambutku. Membuat
angin bisa mengenai tengkuk leher dan membuatku tidak
lagi merasakan panas yang menyengat.
a”
109
CE “Sinar, sini bentar,” panggilku kepada adikku
y yang paling besar. Sinar tengah libur kerja saat
\/ itu.
“Kak Saka mau tanya. Hmm... Kamu suka mikirin
enggak sih kalau Mamah kesepian?” Aku hati-hati bertanya
kepadanya.
“Hah? Tumben nanyanya begitu? Kenapa emang?” Sinar
duduk di sebelahku di kursi ruang tamu. Sudah lama tidak
berbincang, aku hampir lupa wajah polosnya kini semakin
terlihat dewasa.
“Yah, kamu kan tahu Bapak meninggal udah belasan
tahun. Belasan tahun juga Mamah sendiri. Yang biasa dulu
ada yang rawat, ada temen ngobrol, ada yang perhatiin, ada
yang mengayomi, sekarang enggak ada. Selama sebelas tahun
kamu emang enggak pernah mikirin kebutuhan Mamah
yang kayak gitu?” Aku coba mengarahkan pernyataan untuk
membangun pemahaman Sinar dahulu. Tak ingin segera
menembaknya dengan pertanyaan inti.
“Hmm, iya, ya. Udah sebelas tahun, enggak kerasa. Tapi,
emang kita enggak cukup buat nemenin Mamah ya?” Sinar
balik bertanya.
“Yah, itu menurut kamu. Kita sama adik-adik pada
sibuk sama kegiatannya. Ramenya paling cuma malem, itu
juga masih sibuk di kamar masing-masing. Yang nongkrong
di ruang tengah paling cuma Mamah. Rame juga kalau
kebetulan kalian makan malem barengan aja kan? Waktu
110
itu, waktu Mamah lagi cuti karena enggak enak badan, Kakak
merhatiin Mamah yang lagi ngerjain kerjaannya di ruang
tengah, sendirian. Kakak tiba-tiba ngerasa khawatir sama
Mamah.” Aku masih bercerita dengan hati-hati.
“Kalau Kakak mau nanya apa Mamah boleh nikah lagi,
Insya Allah Sinar mah enggak pernah keberatan, Kak.” Sinar
menembakkan maksud yang kuajukkan.
Aku hanya tersenyum. Jawaban darinya cukup untuk aku
sedikit merasa lebih tenang tapi khawatir juga. Aku tidak
bisa membayangkan bagaimana ibuku akan bersama seorang
lelaki yang tidak kami kenali, tidak aku kenali.
Sebuah pikiran muncul di kepalaku mengenai ini. Apakah
ibuku pernah khawatir perihal wanita yang aku pilih untuk
aku jadikan istri kelak? Apakah kami memiliki kekhawatiran
yang serupa satu sama lain? Atau, mungkin hanya aku saja
yang masih tidak rela untuk hormat pada seseorang yang
tiba-tiba menjabat sebagai ayah.
Berhari-hari aku memikirkan ini sejak perbincanganku
dengan Sinar. Ingin sekali membicarakan hal ini lagi dengan
kedua adikku yang lain, Permata dan Putri, tetapi ada sesuatu
yang masih menahanku.
Meski sedikit tenang bahwa Sinar sudah menyetujui tapi
bagiku jabatan seorang ayah bukan hanya perihal sosok. Ini
lebih kepada sejarah dan cerita, yang membentuk sosok itu
sendiri. Hormat dan cinta yang kemudian hadir dibentuk
oleh cerita dan sejarah itu.
a1
Sob, doain gue besok sidaang...! Setelah itu gue
tunggu kabar dari lu. You know what | mean.
Aku sedang menikmati es kopi susu di Kyotown Coffee
Siang ini saat sebuah pesan masuk dari Kevin muncul di layar
ponsel. Aku menarik napas panjang. Belum selesai perihal
ibuku, kini masih tersimpan satu hal lain yang belum berani
aku sampaikan kepada ibuku. Tentang keinginanku untuk
tinggal di Jogja beberapa waktu yang lama. Ya, beberapa lama
sudah bukan dalam hitungan hari. Bisa beberapa minggu,
bulan, atau bahkan tahun tanpa satuan waktu yang pasti.
Yoi, mangat, Sob! Make a great shot!
Aku membalas pesan singkat Kevin lalu kembali
menikmati es kopi susu di siang yang agak terik ini. Desain
yang sedang aku kerjakan tinggal finishing. Namun, enggan
sekali aku selesaikan. Kepalaku berkecamuk. Seolah banyak
hal yang harus aku selesaikan padahal aku hanya terlalu
senang membuat perandaian dalam kepalaku.
Lagi-lagi andai, andai semua masalah bisa bekerja dan
berbanding lurus dengan perandaianku dalam kepala. Saat
aku membayangkan semua jalan keluar dari apa yang tengah
12
aku hadapi dan bisa aku selesaikan, apakah akhirnya aku bisa
untuk tenang?
Kembali pada sebuah pemahaman perihal merasa,
bahwasanya manusia adalah mahluk dinamis yang tidak
pernah rela untuk diam. Seolah diam berkebalikan dengan
makna hidup itu sendiri. Perasaan, pemikiran, kesenangan,
kesedihan, adalah sebuah ledakan supernova di angkasa
yang akan membentuk kehidupan. Namun, laiknya ledakan,
semua ledakan bermula dari ketiadaan. Dan, setiap ledakan
hanya bersifat sementara. Maka, jika ledakan berangsur-
angsur menyusut dan kembali pada sepi, setiap orang
akan mencari dan membuat gesekan apa pun yang bisa
menciptakan macam-macam ledakan. Menciptakan macam-
macam keadaan agar bisa kembali merasakan sesuatu.
Ya, setiap orang memang senang membuat-buat masalah
sendiri dalam kepala dan hidupnya. Seperti aku yang senang
membesar-besarkan semua hal dalam kepalaku.
Aku membuka browser dan blogwalking untuk mencari-
cari inspirasi. Mencari tulisan-tulisan yang bisa menstimulus
pemahamanku. Meski tak tahu pasti tulisan dan pemahaman
apa yang aku butuhkan, setidaknya, aku mencari. Diam
dengan isi kepalaku yang hanya selalu berputar di situ-situ
saja kadang hanya memperkusut pikiran saja.
113
Kadang kita tidak tahu untuk percaya pada apa dan siapa,
semua hal terlihat samar dan membuat kita nanar.
Tetapi, itu bukan perihal apa atau siapa. Mungkin doa kita
yang tidak cukup baik,
untuk membuat kita bisa percaya.
Sehingga, ragu masih menjadi teman baik yang selalu kita
jaga.
Kita saja yang terlalu nyaman dengan ragu. Karena untuk
percaya, ternyata dibutuhkan usaha yang lebih.
Tulisan itu aku temukan di salah satu Blog milik
perempuan dengan rupa yang rahasia, Eleftheriana.
Sayangnya, aku tidak bisa untuk tidak setuju. lya kan, betapa
kita sebegitu rela untuk diperbudak ragu. Aku ragu jika aku
dapat dengan rela memberi izin ibuku untuk menikah lagi
dengan seseorang. Aku ragu jika ibuku dapat memilih orang
yang tepat, yang tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk
aku dan adik-adikku. Aku ragu jika harus pergi mengejar
mimpiku membuka kedai kopi di Jogja, dan meninggalkan
ibu dan adik-adikku.
Ragu, terlalu membuatku nyaman untuk tidak percaya
pada sesuatu. Hanya membuatku terlihat egois. Seolah aku
tidak membiarkan kesalahan yang mungkin saja terjadi.
Seolah semua harus sesuai dengan inginku, dengan caraku,
114
tanpa mau memedulikan orang lain.
Lalu, aku teringat pada pesan dari pemilik akun
Eleftheriana yang belum aku balas. Aku ragu jika harus
membalas pesannya. Entah karena aku masih takut melukai
seseorang, atau karena takut aku terlalu mudah untuk mau
membalas sapa seseorang. Bisa saja dia hanya wanita kesepian
yang melakukan hal itu ke setiap orang yang tulisannya
dia sukai. Namun, memang apa salahnya jika begitu? Aku
bertanya dalam hati.
Pikiranku sejenak melayang saat pertemuanku dengan
Lara. Tentang keraguan dan ketakutan. Tentang kesempatan
dan kemungkinan. Semua yang terjadi mengarahkan aku pada
hal besar. Aku mengerti, pertemuan akan membawaku pada
banyak kemungkinan yang akan semakin mendewasakanku,
dengan semua kejutan-Nya.
Saat ini, aku tidak bisa menghitung apa yang membuatku
tertarik dengan nama samaran Eleftheriana. Hanya ada
sebuah foto siluet gadis di profilnya. Ketertarikanku tidak
memiliki asal muasal selain, tertarik. Entah pada kata-
kata yang dia tulis, entah dari sapanya, entah dari caranya
mengirim pesan kepadaku. Aku hanya, tertarik. Kemudian...
“Ya, kita harus mencari tahunya. Aku ada ide, kamu
bisa menebak?”
Kalimat itu terkirim menuju kotak masuknya.
115
I’m done doubting! ujarku dalam hati.
Aku menyeruput es kopi susu milikku. Manis dan
pahitnya menyatu menjadi pengisi daya semangatku untuk
menyelesaikan yang selama ini berkecamuk dalam hati.
Perjhal ibuku, perihal izin untuk aku pergi, dan memberi izin
kepada ibuku untuk mempersilakan dirinya menikah lagi.
Kak, lagi di mana?
Pesan masuk dari adikku, Sinar.
Di tempat ngopi, ngerjain kerjaan. Kenapa?
Balasku kemudian.
Tak lama Sinar sudah mendatangiku dari kantornya
setelah mengajakku untuk bertemu. Sekalian dia tengah
beristirahat untuk makan siang.
“Di sini cuma kopi doang, kak?” Sinar bertanya.
“Tuh, itu ada salad. Belum pernah nyobain sih, tapi
kayaknya enak.” Aku menunjuk kedai salad di ujung ruangan.
“wah, salad. Pas banget Sinar lagi diet. Hehehe.” Sinar
terkekeh dan segera memesan makanan.
“Jadi, kenapa tumbenan ngajak ketemu?” Aku langsung
menembak dengan pertanyaan.
116
Bukan kebiasaan atau bahkan hal yang normal Sinar
mengajakku bertemu di suatu tempat. Kami tidak pernah,
sekali pun menikmati waktu berdua, atau berbincang laiknya
kakak-adik.
“sinar udah ngobrol sama Mama.” Sinar menjawab pasti.
Aku sedikit terperanjat. “Hah? Kok bisa?” Aku penasaran.
“Hah? Apanya yang kok bisa? Kok, kayak yang aneh
gitu?” Sinar tidak terima dengan pertanyaanku.
“Ya itu, kok udah ngobrol aja.” Aku masih terkejut.
“Ya, bisa, lah. Tinggal ngobrol. Kok, Kak Saka aneh sih,
pake kaget segala?”
Belum sempat aku menjawab Sinar melanjutkan
ucapannya. “Ahhh... Sinar ngerti. Emangnya Kak Saka yang
sok-sokan nyari waktu yang tepat buat ngobrol kayak gitu
sama Mama. Sibuk terus sih.” Sinar menggodaku.
Memang begitu, aku selalu memperhitungkan suasana.
Obrolan seserius itu harus aku perhitungkan suasananya.
Ini perihal hati ibuku. Meski urusan hati tidak bisa
diperhitungkan, setidaknya aku mengkhawatirkan dirinya.
Semua diksi yang keluar dari bibirku, harus bisa diterima
olehnya secara nyaman.
“sinar juga udah ngobrol sama Permata, sama Putri.”
Belum selesai aku memikirkan ibuku, Sinar membuatku
lebih terkejut lagi. “Hahhhh...?” Aku tak bisa menahan
keterkejutanku. Saking lepas kendali, sepertinya tamu lain
yang sedang menongkrong ikut terkejut mendengarku yang
7
setengah berteriak.
“Heh, pelan aja kali kagetnya. Lebay, ah.” Sinar
menegurku.
“Ya, lagian kamu kok bisa udah ngobrol sama mereka.”
Seolah aku tak terima karena itu adalah tugasku.
“Udah Kak, Sinar tahu Kak Saka sibuk. Kak Saka enggak
gampang buat ngobrol sama mereka ngomongin hal ini. Itu
urusan Sinar, urusan perempuan ke perempuan. Biar lebih
bisa diterima sama mereka.” Sinar coba menenangkan.
Namun, yang aku terima hanya ketidakmampuanku untuk
berbicara dengan adik-adikku.
“Eh, jangan marah. Bukan berarti Sinar enggak percaya
Kak Saka bisa ngobrol baik-baik sama mereka. Maksud
Sinar... Ngerti kan, perasaan perempuan?”
Aku mengangguk tersenyum. Setelah pesanan Sinar
datang, kami melanjutkan obrolan perihal ibuku. Semua
ternyata menyutujui untuk memberi izin ibuku menikah
lagi. Putri, hanya sempat bertemu Bapak beberapa tahun.
Permata, adalah yag paling dekat dengan ibuku sejauh ini.
Dialah yang ingin mewujudkan keinginan ibuku agar salah
satu anaknya yang menjadi seorang guru. Permata akan
menyetujui apa pun perihal menyenangkan ibu.
Sinar, sudah jelas. Dari cara ibuku memberinya restu
dan izin untuk dekat dengan seorang lelaki di kantornya
yang beberapa kali diajak ke rumah. Dari situ Sinar sudah
berada di titik paham. Setiap orang tak terkecuali ibuku,
118
membutuhkan seseorang yang dapat menemaninya, dapat
membimbing, di luar mata rantai keluarga inti.
Semua persetujuan dari adik-adikku seolah sedang
menghakimi dan memperkosa diriku di saat yang sama.
Tinggal aku sendiri yang masih menyimpan ketidakrelaan
untuk ibuku menikah lagi. Untuk dekat dengan seseorang
yang tidak aku kenali. Yang dalam waktu sangat singkat bisa
menjadi seorang ayah bagiku.
“Kalau boleh jujur, alasan lain kenapa Kakak nanyain
persetujuan ini ke kamu adalah untuk mencari alasan yang
kuat. Biar Kakak juga bisa ngizinin Mamah untuk nikah lagi,
Sinar.” Aku mengakuinya sedikit malu.
Sinar tersenyum. Bola mata hitamnya seakan ingin
memeluk aku. Ada lega dan khawatir akan perkataanku.
“Kalau boleh jujur juga,“ Sinar menarik napas panjang
sebelum melanjutkan kalimatnya. “Sebenernya, Sinarlah
yang minta Mamah untuk ngobrol sama Kak Saka, untuk
minta ijin.” Kini bola mata tadi berubah sepenuhnya
khawatir.
Aku tidak bisa lebih terkejut dari yang sudah-sudah
dikatakan Sinar. Selama ini mereka menyembunyikan
sesuatu dari aku. Seolah aku adalah musuh utama mereka,
hambatan terbesar mereka. Dada ini mendegupkan sebuah
rasa tidak terima akan apa yang didengarnya.
“Kok, gitu sih?” Hanya itu yang bisa aku ucapkan. Aku
tak sedikit pun memiliki hak untuk marah terhadap Sinar.
119
Ada sesuatu yang aku yakini yang membuat Sinar dan ibuku
melakukan hal itu kepadaku.
“Kak... Kami enggak bermaksud nyembunyiin apa pun
dari Kak Saka meski memang terkesan seperti itu.” Sinar
membuat jeda pada ucapannya. “Sinar sama Mamah paham
banget. Dari kami semua, selain Mamah, Kak Saka yang
paling deket sama almarhum Bapak. Kak Saka yang paling
lama diasuh, dirawat sama Bapak. Kak Saka tahu itu. Semua
kebebasan yang ada di diri Kak Saka. Semua sifat, karakter
Bapak, ada di Kak Saka. Kita semua sadar itu. Mungkin Kak
Saka yang enggak menyadarinya. Liat adik-adik Kakak.
Aku, Permata, Putri, kita semua punya kecenderungan yang
sama kayak Mamah.” Sinar terdengar masih belum selesai
bercerita.
Namun, memang ada benarnya. Aku yang selama ini
tidak menyadarinya. Aku, adalah kloningan dari almarhum
bapak.
“Kerinduan Kak Saka sama Bapak, mengakar di diri
Kak Saka. Sampe Kak Saka sendiri terasa seperti Bapak.
Seorang yang independen, seorang yang tertutup, tetapi
menyembunyikan kasih sayang luar biasa. Seseorang yang
tegas sama pilihannya, tapi juga rapuh dan butuh untuk
disentuh. Yang kadang pengen manja, tapi malu karena
harus tetap kuat di sekitar orang yang disayang. Kak Saka
udah bisa ngerasain itu sekarang, bahwa almarhum Bapak
ada di diri kak Saka?” ucapan Sinar memeluk nurani.
120
Seketika, diri ini jadi sangat rapuh. Semua sel dalam raga
bergegas memojokkan air mata untuk muncul ke kelopak
mata. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk menangis. Aku
tak memberinya izin untuk tumpah di atas pipiku. Biarpun
aku menangis, biar aku menangis dalam pikiranku sendiri.
“Kak, Bapak emang enggak bakal pernah bisa digantikan
posisinya sebagai orang yang luar biasa di hidup kita, di hidup
Mamah. Mamah juga enggak berniat sama sekali melupakan
atau menggantikan posisi Bapak sama orang lain. Tapi, bagi
Sinar, ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Sebuah ibadah.
Bayangin, calon Bapak kita yang baru juga kehilangan
istrinya, punya anak-anak yang merindukan sosok ibu. Dua
keluarga yang memiliki luka-luka yang sama, bergabung
untuk saling menyembuhkan. Apakah enggak indah, Kak?”
Sinar mengakhiri ucapannya dengan senyum. Namun, ada
hal yang lagi-lagi mengejutkanku.
“Kehilangan istri? Maksud kamu? Mamah?” Aku ber-
tanya penasaran. Gelagapan.
“lya, Sinar udah sempet ketemu sama orangnya. Insya
Allah, kalau Mamah aja bisa nyaman sama orang tersebut,
Sinar juga. Pasti Kakak juga bisa nyaman dan nerima beliau.”
Sinar tersenyum.
Meskibegituterkejut, semua penjelasandariadikku Sinar,
berhasil meluluhkan perasaanku. Membuat pemahaman
yang mengindahkan tanpa sama sekali menggurui atau
membuatku terpojokkan. Terasa seperti sebuah kasih sayang
121
yang selama ini tidak aku ketahui.
“Bapak juga di sana pasti pengen ada yang bisa
jagain Mama. Kita kasih restu atau izin bukan perihal
hasil perhitungan kelayakan atas seseorang yang dipilih,
melainkan titik percaya pada kelayakan seseorang yang
memilih orang tersebut. Kita tahu bagaimana Mamah kan?”
ucap Sinar pelan.
Aku tersenyum. Kami sama-sama menyetujuinya tanpa
perdebatan. Kami sepakat. Ibuku pantas mendapatkannya.
Pantas mendapatkan kebahagiaan bahkan tanpa harus
meminta izin.
Aku tengah tertegun memandangi sebuah
lukisan karya Dede Eri Supria yang diberi judul
‘Yang Berusaha Tumbuh’, ketika sebuah tepukan
halus mampir di pundakku.
“Lara!”
Aku menoleh dan mendapatinya sudah berdiri di
belakang dengan senyuman yang masih sama seperti
sebelumnya. Aku masih terpaku menatap sosok itu hingga
kemudian ia kembali bertanya.
“Menurutmu arti lukisan ini apa?”
Aku memandangnya lekat tapi sekilas, kemudian
122
memejamkan mata sebentar. Sebuah tarikan napas yang
cukup dalam begitu kuperlukan untuk memberi oksigen pada
kepalaku. Berharap sekelebat kejadian yang terus berputar
silih berganti di kepalaku segera enyah.
Beberapa tahun lalu, hal seperti ini pernah sekali terjadi
di hidupku. Sebuah pameran yang membuatku bertemu
dengan seseorang. Bukan hanya bertemu, melainkan
memutuskan untuk terbuka agar bisa berbagi cerita, bahkan
setelahnya malah menjalin cerita bersama. Pertemuan di
pameran itu membuatku menutup sebuah luka yang telah
lama menganga. Menambalnya dengan sebuah suka cita baru
akan sebuah rasa cinta yang ternyata malah memberi luka
kembali.
Iya, sayangnya menambal luka_ bukan __berarti
menyembuhkan. Itu hanyalah upaya untuk melupakan
sejenak. Luka yang ada itu kemudian kembali karena
memang tak pernah aku terima sebagai sebuah pelajaran.
Luka itu kembali karena tak pernah aku pahami dan maknai
untuk kemudian diikhlaskan.
“Lara, are you okay?” Suara Rio kembali menarikku pada
keadaan utuh dan sadar saat ini.
“Ya, ya, aku baik-baik aja.” Aku memaksakan sebuah
senyum hadir di wajah. Berusaha membuatnyatidak bertanya-
tanya lebih lanjut. “Cuma lagi mikir mau nerjemahin maksud
tulisan ini kayak gimana ke kamu. Karena, di kepalaku
banyak banget kosakata yang berebutan mau keluar. Berisik,
123
Mas. Sampe aku bingung mau ngomong apa aja. Hehe”
Rio terkekeh mendengar ucapanku. “Hahaha. Kalem
Ra, keluarin aja satu-satu. Aku siap jadi pendengarmu kok.
Kalau kamu biasanya nulis di Blog karena enggak ada yang
bersedia menjadi telingamu bercerita, now, here I am. Aku
dengan senang hati dengerin kamu ngomong, biar kamu
enggak capek nuanginnya di tulisan. Ya, itung-itung biar
kamu enggak pusing sendiri sama isi kepalamu yang penuh
diksi dan kata-kata itu.”
Aku tidak tahu apakah ucapan Rio tersebut memang
terlontar begitu saja karena dia mengetahui hobiku menulis
di Blog, atau dia mengatakannya karena memang semudah
itu untuknya membaca dan mengenali diriku.
“Menurut Mas ini berat enggak? Hmm, I mean ketika
liat lukisan ini, Mas Rio kebayang hal-hal rumit atau bisa
nikmatin karya ini begitu aja tanpa berusaha mikir keras
maknanya apa?”
Menanggapi pertanyanku itu, Rio terlihat berpikir
sejenak sambil memerhatikan lukisan yang dimaksud dengan
saksama. Matanya menyapu lukisan itu dari keseluruhan sisi,
menelitinya sebelum akhirnya bicara. “Aku bisa nikmatin
gitu aja sih Ra, enggak ada yang buat jadi mikir. Tapi, ada
hal aneh gitu yang bikin aku pengen ngungkapin sesuatu.
But, I don’t know how to describe it,” tegasnya sambil menoleh
menatapku.
Aku yang sedari tadi memerhatikannya kini kembali
124
memandang lukisan di depan kami. Mencoba mulai
merangkai kata dan berusaha menyampaikannya kepada Rio.
“Mas, liat itu ada persemaian yang tumbuh subur?” tanyaku
sambil menunjuk ke arah lukisan yang berwarna hijau persis
seperti padi ataupun tanaman teh di daerah Puncak.
Rio mengangguk sebagai jawaban atas tanyaku itu.
Membuatku kemudian melanjutkan ucapanku. “Buatku
itu artinya kekuatan dan harapan. Tanaman atau
tumbuhan adalah salah satu kehidupan. Petani-petani yang
menanamnya menggantungkan harapan di sana, harapan
untuk menyambung hidup. Sedang, pedagang di pasar dan
kita sebagai pembeli menjadikan tumbuhan itu sebagai
harapan untuk memberi kekuatan bagi tubuh, dengan
mengonsumsinya tentu aja.”
Aku menjeda sebentar, melirik ke arah Rio yang
bergantian menatapku serta lukisan itu. Seolah sedang
menelaah semua yang sedang aku tuturkan. Aku kembali
mengarahkan pandangan pada lukisan tersebut, tersenyum
sekilas sebelum akhirnya kembali bersuara.
“Sementara gedung yang runtuh dan hancur ini,” ucapku
sambil membingkai lukisan itu dengan jemariku.
“Layaknya simbolis dari kelemahan dan keputusasaan.
Dua hal yang bertolak belakang sekali kan? Kekuatan
dan kelemahan, harapan dengan keputusasaan. Seolah
mengisyaratkan bahwa di balik harapan petani-petani itu
tersimpan sebuah keputusasaan ketika tanaman mereka
125
diserang hama dan tak ada bantuan dari Pemerintah,
misalnya. Atau, bisa juga mengisyaratkan bahwa ada pihak-
pihak yang bisa membeli tanaman itu dalam jumlah banyak
tapi membandrolnya dengan harga murah hanya agar
mendapatkan untung banyak. Si pihak pembeli itu punya
kekuatan, tapi mereka melupakan kelemahan yang juga
dimiliki si petani.”
Aku kemudian mengulas sedikit senyum, lega karena
sebagian isi kepalaku berhasil kukeluarkan dengan baik
melalui ucapan. Bukan lagi hanya lewat sederet aksara yang
terkadang menimbulkan tafsir yang berbeda-beda.
Aku mengalihkan pandangan untuk menatap Rio.
“Entah maksud sang pelukis yang sebenarnya apa, tapi aku
menangkapnya sebagai sebuah kehidupan yang haruslah
berjalan seimbang. Jika ada pihak yang kuat, maka mereka tak
boleh lalai dengan si lemah. Jika ada harapan yang merekah,
maka orang lain tak boleh lupa sewaktu-waktu putus asa
itu bisa aja dateng. Jadi, gitu deh, menurutku tentang arti
lukisan ini. Hehe.”
Aku menutup penuturanku dengan sedikit tawa ringan
agar suasana menjadi sedikit lebih rileks. “Wow, aku enggak
ngerti sama isi kepalamu, Ra. But to be honest, I adore you.”
Matanya menunjukkan binar kejujuran akan setiap kata
yang diucapkan.
Aku menunduk karena tersipu malu dibuatnya.
“Dan setelah diliat-liat, apa yang kamu bilang tadi tentang
126
lukisan ini tuh masuk akal sih. Menarik, Ra. Aku jadi enggak
hanya nikmatin lukisannya aja, tapi bisa menggabungkannya
jadi sebuah pemahaman baru setelah denger ceritamu.”
Sembari kembali berjalan meninggalkan lukisan tadi
menuju lukisan lain, aku menanggapi ucapannya barusan,
“Ya, asal enggak semua lukisan di sini harus aku jelasin aja,
Mas. Banyak banget loh ini, aku bisa berbusa-busa. Nanti yang
ada pemandu tur di tempat ini harus pindah lapak karena aku
bisa gantiin mereka,” selorohku yang disambutnya dengan
sebuah tawa renyah.
Aku menatapnya yang sedang tertawa. Caranya tertawa
membuat sebuah perasaan bahagia menyeruak di dadaku.
Aku tidak mengerti mengapa bisa, tapi ternyata bahagia
memang bisa menular hanya dengan sebuah tawa yang
dibagi. Aku masih memerhatikannya hingga kemudian
mendapati sebuah kejutan manis yang dia miliki.
“Mas, itu... kamu punya, dimple?” tanyaku sambil
menaruh telunjuk pada pipiku sendiri.
“Oh, ini?” timpalnya sambil menaruh jemarinya pada
lekukan kecil di pipi sebelah kanannya. “Iya, punya, tapi
cuma satu, yang kanan aja. Itu juga harus ketawa atau senyum
yang lebar baru keliatan. Kamu aja baru liat sekarang, kan?”
“Hehe, iya sih, baru liat. Itu juga karena kebetulan kamu
ketawa dan aku baru merhatiin, Mas.”
“Jadi, dari tadi kamu merhatiin aku nih?” Rio kemudian
menghentikan langkahnya dan berdiri tepat di hadapanku
127
dengan menatapku lekat.
Aku yang sedari tadi melangkah dibuat terkesiap oleh
perkatannya. “Apa sih, Mas? Kebetulan tadi posisiku kan
di sebelah kananmu, jadi ya keliatan,” elakku berusaha
menyangkal pernyataannya. Malu sebetulnya mengakui
bahwa sedari tadi aku memang memerhatikannya.
“lya, deh iya. Sekarang ke mana nih? Laper nih, Ra. Tadi
belum sempet makan siang udah keburu kamu jemput,”
keluhnya sambil memegangi perut.
“Lagian dandannya lama sih!” ucapku menggodanya,
“Hm, cari makan di Gambir aja deh kalau gitu. Baru abis itu
kita beli es krim Ragusa. Soalnya, kalau makan di Ragusa
nanti enggak dapet tempat duduk hari libur begini.”
a
Aku dan Rio kini tengah duduk di trotoar pinggir jalan di
depan toko-toko yang sedang tutup, sambil menikmati es
krim yang tadi sudah kami beli. Kebetulan tempat duduk di
kedai Ragusa sedang penuh. Itu sebabnya aku memilih duduk
di sini seperti beberapa pengunjung lain yang tidak kebagian
tempat.
Aku sendiri memang sengaja tak membawa mobil
ke tempat ini. Sudah lama rasanya tidak berjalan kaki di
Jakarta, menikmati sudut-sudut keramaian yang sebetulnya
128
menyimpan begitu banyak cerita jika saja kita mau untuk
sedikit saja mendengar. Sayang, kebanyakan penduduknya
lebih suka mengeluh dan mengaduh tentang rumitnya lalu
lintas dan segala pelik kehidupan lain.
“Sering ke sini, Ra?” Rio bertanya.
Aku menoleh memerhatikannya yang sedang lahap
menikmati spaghetti ice cream yang tadi dipilihnya.
“Enggak juga, kalau lagi ke Galnas aja mampir ke sini.
Sekalian jalan, nanggung kalau enggak mampir.”
Rio mengangguk kemudian menatap lurus ke depan,
menerawang selama beberapa detik. “Kenapa kamu enggak
coba nulis buku aja, Ra?”
“Buku harian maksud Mas?” Aku mencoba bercanda
menanggapi pertanyannya, yang kemudian dibalasnya
dengan mengacak rambutku.
“Ya, bukan buku harian juga, Ra. Kamu nih lama-lama
ngeselin juga yah, haha.”
Rio tertawa sejenak baru melanjutkan lagi omongannya.
“Maksudku, kamu kan udah biasa nih edit naskah. Suka nulis
juga kan kamunya, dan sejauh yang kuperhatiin tulisanmu
enak untuk dibaca. Kenapa enggak coba membukukan
tulisan-tulisanmu itu? Mencoba hal baru, Ra. Masa enggak
ada sih keinginan untuk membuat karya sendiri. Melahirkan
karya orang udah jago, melahirkan karya sendiri masa
enggak mau?”
“Bukan enggak mau Mas, tapi emang belum ngerasa
129
pantes aja untuk membuat buku sendiri. Belum sepede itu,
hehe.” Kilahku singkat.
“Yang nilai pantes enggaknya tulisanmu untuk jadi buku
emangnya hanya kamu aja? Kan enggak, Ra. Sayang aja sih,
menurutku. Kamu punya bakat untuk mengolah kata dan
menelaah sebuah peristiwa jadi satu kisah yang menarik.”
Rio menjeda dengan kembali menyuap es krim ke mulutnya.
“Atau, kamu kan suka fotografi tuh. Kenapa enggak
bikin buku yang ada fotonya aja? Kamu yang menangkap
gambarnya, dan kamu juga yang menginterpretasikan
makna dan perasaanmu ketika mengambil gambar itu.
Caramu menceritakan lukisan-lukisan tadi tuh enggak
semua orang bisa loh. Maksudku, enggak semua orang
mampu menyatukannya dengan pas. Secara foto dan tulisan
memiliki dua roh yang berbeda.”
Aku yang tengah asyik memakan es krim dibuat tersedak
oleh ucapannya barusan. “Mas, bukain botolnya dong,”
pintaku sambil menyodorinya sebotol air mineral.
“Kamu enggak bisa buka tutup botol ya?” tanyanya
sambil membuka botol tersebut lalu memberikannya kembali
padaku.
Aku hanya menggeleng lemah dan buru-buru meneguk
air mineral itu untuk melegakan kerongkongan.
Jujur saja, mendengar kata gambar dan tulisan yang
disatukan, membuatku kembali teringat pameran foto di
Bandung yang akhirnya mempertemukan aku dengan Saka.
130
Aku ingat betul setiap orang yang melihat kolaborasi yang
kami ciptakan selalu berdecak dan berkata ada semacam
roh yang membuat foto Saka dan tulisanku menjadi sangat
terkoneksi. Bahkan, sampai ada beberapa orang yang
menawar untuk membelinya.
Sepertinya, menarik untuk menciptakan buku seperti
yang Rio maksud. Sayang, aku belum merasa semahir itu
mengabadikan foto. Aku merasa masih butuh orang semacam
Saka yang lebih lihai menempatkan rasa pada sebuah gambar
yang diabadikan.
“Menarik sih, Mas. Tapi, nanti deh, tunggu aku
jago ngambil fotonya dulu. Aku belum ngerasa mampu
menyampaikan rasa melalui gambar, hehe.” Aku
menjawabnya dengan tertawa sambil berdiri hendak
membuang bungkus tempat es krim dan botol air mineral
yang sudah kosong.
“Nanti sampe kapan? Sampe azan magrib yang bentar
lagi mau berkumandang?” Rio mengikuti berdiri lalu
membuang sampah bekas makanannya juga.
Aku kemudian melihat jam tangan dan mengarahkan
pandanganku. Melihat langit yang sudah memperlihatkan
semburat oranye.
“Eh, iya udah mau magrib. Salat di Istiqlal aja yuk
sekalian, Mas. Baru abis itu aku anter kamu balik.”
a”
131
So let me know the truth
Before I dive right into you
You’re a mystery
Thave travelled the world
And there’s no other girl like you, no one
What’s your history?
Do you have a tendency to lead some people on?
Cause I heard you do
Suara Ed Sheeran mengalun memenuhi mobil.
Mengisi kekosongan yang hadir antara aku
dengan Rio. Aku yang sedari tadi fokus menyetir
tak jua membuka obrolan karena sibuk dengan pikiranku
sendiri tentang percakapan yang tadi disinggung Rio.
Sedangkan, lelaki itu sibuk melihat-lihat foto yang kuambil
dengan kameraku.
“Ra, ngeliat foto-foto kamu aku kayak diajak dengerin
cerita. Semuanya sarat makna, gimana sih caranya? Dari
dulu aku juga pengen bisa foto sesuatu kayak gini dan enggak
pernah bisa. Emang enggak bakat kali ya,” keluh Rio.
“Bukan enggak bisa, hanya belum bisa. Kalau mau belajar
mah semua orang juga bisa, Mas. Aku juga awalnya enggak
bisa foto dengan fokus, tapi sekarang udah mulai bisa tuh.
Semuanya ya karena aku membiasakan diri dan terus belajar.
Gimana mau bisa foto kalau jarang-jarang hunting?”
132
Rio mengangguk menyetujui perkataanku. “Iya, juga sih
ya. Kalau jarang-jarang pegang kamera, sampe kapan juga
tetep enggak akan bisa. Tapi Ra, feel-nya tuh beda gitu kalau
liat fotomu. Ada hal lain yang bisa diliat. Beda dari kalau
liatnya cuma pake mata aja.”
Aku kemudian teringat kembali perkataan Saka saat
ia mengajariku. “Itu sih hanya karena sudut pandang aja,
Mas. Apa yang mau aku sampein lewat foto itu akan beda
dengan jepretan tangan orang lain. Karena rasa yang dibawa
memang beda. Hmm...dulu pernah ada yang ngomong sama
aku. Dalam ngambil gambar kita hanya perlu fokus sama apa
yang ingin diliat. Cari sudut pandang yang membuat mata
kita nyaman untuk menikmati hal yang ada di depan kita itu.
Jika deket, ya seberapa deket kita nyaman. Tapi kalau jauh, ya
seberapa nyaman hal itu bisa untuk kemudian kita nikmati.”
“Menarik, Ra!” Rio kemudian mengarahkan kamera ke
jalanan melalui jendela yang tertutup dan sudah dibasahi
oleh tetesan air hujan. Aku mengira ia akan mengabadikan
hujan yang mengalir di kaca jendela, tapi ternyata malah
mengarahkan kamera itu kepadaku. Sebelum aku sempat
menolak, ia sudah membidikku.
“Kenapa jadi aku yang difoto sih, Mas? Padahal tuh ya,
kaca jendela lebih romantis buat difoto,” selorohku.
“Kalau kaca jendela yang diguyur hujan mah kapan aja
bisa diabadiin. Di Jogja juga bisa. Tapi, kalau kamu yang lagi
nyetirin aku, kapan lagi bisa diabadiin kalau bukan sekarang?
133
Lagian sekalian mau coba, seberapa deket dan nyaman yang
aku rasa kalau lagi liat kamu.”
Aku kemudian menoleh sambil tertawa lirih mendengar
ucapannya. Tak ada tatapan yang ia lontarkan kepadaku. Ia
malah sudah asyik kembali fokus pada kamera, melihat hasil
gambarnya dan berkali-kali mencoba mengambil gambar
lainnya.
Tak ada sikap lanjutan dari ucapannya barusan. Entah
sudah kali keberapa di hari ini aku dibuatnya tak mengerti
atas semua perkataannya. Ingin menganggapnya hanya
sekadar lelucon, tapi dari intonasinya saat berbicara, hal
itu tidak terdengar sebagai lelucon. Ingin menganggapnya
serius, tapi ia tak menjelaskan apa-apa juga kepadaku.
Aku kembali mengedikkan bahu dan melajukan
kendaraan lebih cepat dari sebelumnya. Berharap lekas
sampai di apartemen saudaranya agar kecanggungan yang
tiba-tiba hadir bisa segera berakhir.
a
Hari Minggu kali ini kuhabiskan dengan menemani ibuku
berbelanja kebutuhan rumah serta membeli beberapa bahan
untuk membuat kue nastar serta kastengel. Dua camilan
kesukaanku yang akan kubawa pulang ke Jogja nanti malam.
Ya, malam ini aku akan kembali bertolak ke Jogja, bersama
134
dengan Rio juga tentunya.
“Ma, yang waktu itu Lara pernah bilang udah Mama coba
pikirin belum?” Aku mengetuk-ngetukkan tanganku pada
kemudi sambil sesekali melihat angka penghitung mundur
yang menunjukkan detik lampu berwarna hijau akan segera
hadir.
“Yang mana ya? Oh, Mama tahu nih, yang pindah ke
Jogja itu ya?”
“Yap!” Aku mengangguk dan kemudian segera melajukan
kendaraan karena pusing dengan bunyi klakson di belakang.
“Gimana ya Ra, masalahnya tuh pindah bukan cuma
perkara beralih ke tempat baru dan memulai segalanya di
lingkungan baru aja. Tapi, banyak hal yang harus diselesaiin
dulu sebelum akhirnya memutuskan pindah. Mama udah
terlalu kerasan di sini. Mama enggak tahu di Jogja nanti bisa
betah atau enggak. Lagian kamunya kan juga sibuk kerja. Apa
bedanya coba sama Mama yang tinggal di Jakarta?”
“Ttu teh kode mah? Kode biar Lara di rumah aja nemenin
Mama? lyah, gitu?”
Ibuku kemudian menepuk lenganku pelan, sementara
aku hanya terkekeh karena berhasil menggodanya.
“Hemmm... gini deh. Gimana kalau Mama nyoba dulu
tinggal di Jogja sama Lara selama sebulan dua bulan. Kalau
emang enggak betah, Mama mau balik lagi juga enggak
apa-apa. Sekalian nanti Lara cari kerja baru aja di Jakarta,
biar enggak jauh-jauh lagi sama Mama. Biar Mama enggak
135
kebanyakan kangennya sama Lara,” lanjutku.
“th, kamu mah! Mama enggak kangen kok, cuma
kesepian aja sendirian mulu di rumah. Kalau pagi sih enak,
ada karyawan di toko kue yang nemenin. Lah, kalau malem?
Sama Bibi aja di rumah. Kamu sih, makanya buruan nikah,
terus kasih Mama cucu biar ada temennya di rumah.”
Aku menelan ludah mendengar ucapan ibuku. Nalarku
sedang bersiteru. Ada sedikit rasa mencelos karena ibuku
berkata bahwa beliau kesepian. Namun, di satu sisi aku resah
jika sudah mulai disenggol perihal pasangan. Ah, lagi-lagi
ajakan untuk pindah malah menjadi bumerang untuk diriku
sendiri.
Sebetulnya aku malas untuk menanggapi ucapan itu,
tapi di benakku justru terlintas ide untuk kembali menggoda.
“Tuh, di kamar Lara ada boneka yang Mama pernah beliin.
Peluk aja Ma biar enggak kesepian. Lumayan loh bisa bikin
Mama ada temen tidur.”
“Th, kamu ya. Bener-bener deh. Mama sendiri malah
diisengin.” Ibuku kemudian menjewer telingaku pelan sambill
tetap mengomel, sedang aku hanya terbahak melihatnya.
Tak lama tangannya kemudian mengelus rambutku. Bila
sudah seperti ini, aku tahu ada sesuatu yang ingin beliau
sampaikan.
“Ra, Mama udah pernah pesen ke kamu kan ya, kalau
Mama enggak mau kamu berhenti kerja kalau nanti udah
nikah? Bukan apa ya Nak, Mama cuma enggak mau kamu
136
sepenuhnya bergantung sama suamimu aja. Seenggaknya
kamu tetep punya uang tabunganmu sendiri. Atau, ya kamu
bisa usaha apa gitu di rumah. Pokoknya, jangan sampe kamu
enggak ada pemasukan sendiri. Belajar dari pengalaman
Mama ya, Ra.”
Aku tersenyum sambil menggenggam tangannya yang
sedari tadi mengelus rambutku. Menyalurkan kekuatan yang
kupunya dan memberinya sedikit ketenangan. Rasanya di
mataku saat ini sudah ada air mata yang ingin tumpah. Aku
mencegahnya sekuat yang aku mampu. Aku menghela napas
pelan.
“Tya Ma, tenang aja. Lara inget kok pesen Mama. Doain
aja semoga Lara dapet suami yang bertanggung jawab dan
sayang sama kita.”
Ibuku kemudian mengambil tangannya yang tadi sempat
aku cium dan mulai menoyor pipiku pelan. Kebiasaan yang
sering dilakukan oleh ibuku bila mulai tak suka dengan
perlakuanku yang terlalu manis.
Mungkin benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Hal itu juga yang membuatku akan mudah jengah dengan
lelaki yang baru berkenalan tapi sudah berusaha menarik
perhatian dengan seribu jurus gombalan dan rayuan. Bukan
berarti aku tak suka diperlakukan romantis, hanya saja
aku tak suka diperlakukan terlalu manis secara kontinyu.
Roman picisan bagi perempuan seumurku rasanya sudah
tak lagi diperlukan. Aku justru lebih tertarik dengan cara
137
Saka mendekatiku. Pun, dengan cara Rio yang membuatku
merasa nyaman berada di dekatnya. Sial, ada apa lagi dengan
kepalaku yang sudah mulai menilai dan membandingkan
Saka dengan Rio. Tanpa sadar seulas senyum terbentuk
ketika aku memikirkan hal tersebut.
“Kamu kenapa senyum-senyum gitu? Eh, kamu beneran
udahan sama Saka? Terus, di Jogja nemu mas-mas Jawa yang
manis enggak?”
“Apa, Ma? Nemu? Manusia loh Ma, masa bahasanya
nemu sih. Emangnya barang yang ilang apa?” Aku hanya
menggeleng-gelengkan kepala tanpa sedikit pun menjawab
pertanyaan beliau tentang Saka. Ibuku kali ini hanya tertawa
mendengar perkataanku. Lupa dengan pertanyaannya yang
tak sempat aku jawab.
Mungkin aku sudah menerima hubunganku dengan Saka
yang tak lagi bersama kini. Mungkin aku bisa menerima
dengan ikhlas seluruh luka yang sempat dia torehkan,
bahkan aku juga torehkan kepadanya.
Namun, ketika membahasnya dengan ibuku, rasanya
masih selalu ada kesempatan untuk aku merasa bersalah dan
bersedih dengan kandasnya hubungan itu. Hubungan yang
kupikir akan berakhir dengan indah meski beberapa kali tak
diyakini oleh ibuku.
Mengenai kandasnya hubunganku dengan Saka juga
sebetulnya tak pernah secara gamblang kuceritakan kepada
ibuku. Jangankan bercerita tentang alasannya, berkata kapan
138
semua berakhir saja aku tak pernah.
Tapi, mungkin begitulah kepekaan orang tua terhadap
anaknya. Beliau justru yang bertanya kepadaku. Kenapa kok
udah enggak sama Saka lagi? Pertanyaan itu terlontar sehari
sesudah aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya
dengan Saka.
Aku sempat menanyakan kepadanya bagaimana ibuku
bisa mengetahui hal itu. Aku sendiri tak menunjukkan
gelagat aneh dan tak berbicara apa pun terkait putusnya
hubunganku dengan Saka. Namun, jawaban yang diberikan
hanya, “Mama cuma liat kamu gelisah aja. Enggak kayak biasanya
yang seneng terus dan senyum mulu. Dari situ Mama tahu kamu
udah enggak sama Saka lagi.”
Semua rentetan kejadian menari-nari di benakku,
seolah sedang terpasang proyektor besar di depan wajahku.
Membiarkanakuterusterpekur dan terjebak dalam kenangan.
Beruntungnya, ibuku kembali memecah lamunanku dengan
sebuah pertanyaan yang menyalakan semangat di hatiku.
“Bulan depan deh ya Mama ke Jogja. Sebulan aja tapi,
kalau betah ya pindah. Tapi, kalau enggak kamu yang harus
pindah lagi ke Jakarta.”
“Nah, gitu kek daritadi, Ma. Yey! Bulan depan Lara bisa
makan enak lagi di rumah.” Aku kemudian tersenyum lebar
sambil mengepalkan tangan.
“Ye, dasar maunya tuh biar enggak capek.”
“Lah, kan emang gitu niatnya, Ma. Hehehe.”
139
Gelak tawa kemudian menghiasi suasana pagi kami
kali ini. Ya, ini yang membuatku selalu senang berkendara
dengan ibuku. Selalu ada hal yang bisa dibicarakan dengan
lebih personal, dan membuatku selalu bisa merasa dekat
dengan ibuku.
“Mama masakin. Tenang aja. Asal kamu bawa aja calonmu
ke rumah.”
Kali ini ucapan ibuku itu membuat keningku kembali
berkerut. “Calon apaan sih, ma? Masih aja bahas gituan, heran
deh. Mendadak Lara jadi pusing,” jelasku sambil memijat
pelipis, seolah-olah aku memang sedang pening karenanya.
“th, kamu ya, udah berani main rahasia-rahasiaan.
Mama enggak akan ngomong gitu kalau Mama enggak lewat
kamarmu kemarin siang, pas ada Kanaya. Kamu pikir Mama
enggak denger waktu Kanaya sebut-sebut nama cowok?
Kamu juga sempet kan teleponan pas udah sampe rumah
kemarin malem.”
Aku kemudian mengingat-ingat semuanya, dan menepuk
jidatku setelah menyadari bahwa Kanaya memang sempat
berteriak ketika menyebut nama Rio waktu itu. Bahkan
waktu menerima telepon dari Rio, aku memang baru sampai
di rumah dan akan naik ke dalam kamar. Sementara, ibuku
saat itu ada di ruang tengah.
“Apa? Mau ngelak lagi kamunya?”
“Enggak, Ma. Lagian kalau yang itu tuh bukan siapa-siapa,
ih. Dia atasan aku di Jogja. Kebetulan dia juga lagi ke Jakarta.
140
Nanti malem berangkat ke Jogja sama aku juga. Bukan siapa-
siapa, serius deh,” ucapku dengan nada meyakinkan.
“Loh, jadi kamu pulangnya bareng dia? Kalau gitu nanti
Mama yang anter kamu. Mama mau tahu orangnya kayak
gimana.”
“Tapi Ma, nanti tuh....”
“Enggak ada penolakan. Sekali Mama bilang Mama
mau anter, ya pokoknya Mama.” Belum sempat aku
menyelesaikan ucapanku, beliau sudah memotong dengan
memberi pernyataan yang tak bisa untuk dibantah.
Aku akhirnya mengangguk pasrah. Tampaknya salah-
ku untuk berkata jujur mengenai keberadaan Rio dan
kepulanganku dengannya.
“Iya, iya. Ya, udah nanti Lara bilang Kanaya biar enggak
usah jemput sama anter Lara.”
a”
141
Se
CHAPTER III
lt. 1C] OY ey VOM EEG TA\CLOn
MENUJU SATU TITIK PERCAYA"
;°
Kevin telah berhasil membuat dosen penguji
bangga atas tesisnya. Kini mimpi lainnya bisa
terpenuhi hanya dari sebuah kata iya dariku.
Selain itu, proposal Narni juga sudah berhasil diterima dosen,
tinggal meneruskan penelitian untuk skripsinya. Sebuah
kabar yang membawa pesan kebahagiaan. Saat seseorang
yang kita pedulikan berhasil melalui salah satu chapter
menantang dalam hidupnya.
“Lu mulai siapin semua aja. Bisa atau enggaknya,
pokoknya I’m in!” Aku berbicara di telepon. Kevin di
ujung telepon sana langsung terdengar kegirangan dan
bersemangat. Bahkan suara yang bersemangat itu berhasil
membuatku bergelora juga.
Rumah tengah sepi. Semua orang di tengah bekerja dan
sekolah. Hari ini aku memutuskan untuk mulai mengerjakan
semua to do list untuk beberapa minggu ke depan. Pekerjaan
dari beberapa klien dan teman harus aku selesaikan. Lalu
memberikan kabar kepada mereka bahwa aku tidak bisa
menerima pekerjaan desain untuk beberapa bulan ke depan.
Mengerjakan semua hal yang harus aku selesaikan di
Bandung ini agar dapat dengan mudah pergi ke Jogja untuk
beberapa lama. Beberapa lama yang kumaksud kali ini
kujanjikan dari satu hingga tiga bulan. Ibuku sedikit terkejut
awalnya. Tapi, setelah menceritakan rencanaku, ibuku
akhirnya paham dan mengizinkan aku untuk pergi. Untuk
sementara waktu tidak di rumah.
145
“Meni lama gening sampe tiga bulan?” tanya ibuku untuk
memastikan.
“Ttu tergantung, Mah. Kalau emang kafe yang dibuka
di sana mengharuskan Saka untuk tinggal beberapa bulan.
Atau, kalau Saka juga betah di sana. Hehe.” Aku mencoba
menenangkan. Masih ada raut kekhawatiran meski akhirnya
ibuku mengizinkan aku untuk bekerja dan membuka kedai
kopi di Jogja.
Ada ragu yang menyeruak dalam diriku. Tapi, bagaimana
pun aku sekarang merasa tenang. Setelah perbincangan
dalam dengan derasnya air mata dari ibuku saat aku
menyampaikan kunci yang dirinya tunggu-tunggu. Sebuah
pernyataan bahwa dirinya sangat dipersilakan untuk
menikah. Untuk mendapat perhatian lebih dari orang lain.
Untuk mendapat seseorang yang bisa diajak berbincang dan
berkeluh kesah kapan pun ibuku membutuhkan.
Tangis itu akhirnya tumpah sebagai jelmaan rasa syukur
yang selama ini dipendamnya. Sebuah kelegaan yang tak
bisa dibayar dengan hal lain kecuali tangis. Setiap rintik
airmatanya, memuja Tuhan, memuji aku dan adik-adikku.
Menjadi sebuah jatuh yang paling dinanti oleh ibuku. Aku
dihadiahi peluk yang akhirnya hanya membuatku kikuk.
Membuat air mataku pun ingin ikut-ikutan jatuh. Meski
akhirnya hanya jatuh dalam pikiranku sendiri.
Senyum dariku, dan tangan yang mengusap punggung
ibuku kurasa cukup untuk membuatnya bahagia saat
146
itu. Sejak kejadian itu juga kelegaan terpapar jelas dari
senyumku. Ibuku pun berani untuk memperkenalkan
aku dengan seseorang yang memang telah layak untuk
dikenalkan kepadaku.
Seseorang yang tidak lagi bisa membuatku ragu atas
pilihan ibuku. Satu titik percaya tentang ibuku, cukup untuk
mengerti bahwa ibuku tidak akan memilih seseorang yang
tidak pantas bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk
anak-anaknya. Bahkan, titik pantas baginya, adalah paham
betul bahwal lelaki itu baik untuk anak-anaknya.
Hingga kemudian aku berani untuk mengutarakan
mimpiku kepadanya. Mengutarakan ingin dan maksudku
atas kepergianku ke Jogja kelak. Meminta izinnya untuk
sebuah mimpi yang ingin aku kejar. Tapi, ternyata sebuah
izin tetap saja membuatku tak kuasa untuk benar-benar
pergi dari rumah selama beberapa lama. Lebih lama dari
waktu yang biasanya aku pakai untuk berlibur.
Ada tanggung jawab atas ibuku dan adik-adikku. Meski
kini aku yakin ada yang mulai bisa menjaga mereka. Ada
yang bisa membuat mereka merasa aman meski tanpa aku
di sekitar. Adalah sebuah rasa tidak rela akan diriku sendiri
yang harus tidak ada di sekitar mereka.
“Bener, Mamah mah Insya Allah lega. Lega karena kamu
akhirnya tahu apa yang ingin kamu kejar buat hidup kamu.
Mamah akhirnya tahu kamu punya mimpi. Kamu juga tahu
bagaimana caranya merealisasikannya. Kamu udah dikasih
147
jalan. Jangan sampe Mamah dan adik-adik kamu malah
jadi penghalang buat kamu.” Ibuku meyakinkanku, dengan
suaranya yang selalu ramah dan merdu, sambil memegang
pundakku.
“Berkah yang besar memang ada di keluarga. Banyak
orang yang justru susah untuk bisa terus-terusan berkumpul
sama keluarga. Tapi, bukan di situ aja intinya. Berkah itu
hadir dari keikhlasan dan kerelaan keluarga. Kepergian kamu
untuk menggapai hal yang bisa membanggakan bukan diri
kamu aja, tapi juga keluarga. Tentunya dengan seizin Mama,
adik-adik kamu. Semoga jadi berkah buat kamu, Saka.” Ibuku
masih melanjutkan.
Perbincangan seperti inilah yang selalu aku tunggu
dengan ibuku. Perbincangan sepi tanpa adik-adikku di
rumah. Tanpa satu pun yang mendengar. Sebegitu masih
malunya aku untuk hal seperti ini. Seolah masih tak rela
sisi-sisi sentimental diriku diketahui orang lain bahkan adik-
adikku sendiri.
Aku yang terbiasa terlihat cuek dan misterius, padahal
menutup diri agar tak terlihat lemah. Yah, egois memang
saat aku berada dirumah. Hanya mampu menyayangi mereka
sembunyi-sembunyi.
Sejak perbincangan dengan ibuku, mimpi seolah hanya
selangkah dari tempatku berdiri. Namun untuk membuat
langkah, perlu keyakinan luar biasa agar aku bisa bergerak
dan menapak hingga pasti di titik itu.
148
Di suatu pelayaran tanpa angin, aku menengadah ke langit.
Tempat beribu tanya menguap,
menjadi kebingungan-kebingungan yang mendung.
Aku sering mengutuk kehilangan.
Bukan perkara ditinggalkan,
namun sekedar merasa, kehilangan.
Aku bahkan bertanya lebih dalam,
kapan aku merasa memiliki, hingga harus merasa
kehilangan.
Apakah aku juga tak bisa memlih,
perihal apa saja yang dapat membuatku merasa memiliki dan
kehilangan?
Sebuah pesan masuk di inbox laman blog pribadiku.
Eleftheriana, mengirimkan sebuah tulisan yang meminta
untuk aku sambung atau aku balas. Ya, sejak mengirimkan
pesan terakhir kali kepadanya, aku akhirnya mengajukkan
sebuah ide perihal apa yang bisa kita lakukan selain saling
memuji tulisan. Aku mengajaknya untuk menulis bersama,
dan dia menyetujuinya.
Meski kami hanya sepasang orang asing yang bertemu
melalui laman maya, tapi aku merasa ada yang berbeda.
Bukan sekadar pesan yang memuji, atau pesan yang mencari
149
perhatian belaka. Bahwa, setiap pesan memiliki roh sendiri
yang dikirim oleh penulisnya.
Perihal sampai, diterima atau dibalas, itu urusan
kecocokan jiwa. Karena aku meyakini, masing-masing
manusia saling mengirim gelombang, saling mengundang dan
menarik. Entah dalam cara apa pun, entah dalam singgungan
ke berapa. Semua hal, semua orang yang memiliki kedekatan
atau kesamaan gelombang, akan saling mengarahkan pada
satu titik jumpa.
Dan, perjumpaanku dengan seorang yang memiliki nama
akun Eleftheriana adalah hasil dari tarik-menarik kami
melalui lempengan kosmos yang tak kasat mata. Menembus
lembaran-lembaran gelombang lain yang berdesakan dan
saling bersinggungan.
Karena tak ada batas jelas,
kapan dan bagaimana tepatnya,
rasa tersebut hadir dalam diriku.
Hingga jawaban tak kunjung jatuh dari langit,
cemas membawaku pada gerah yang membuat pikiranku
berpeluh.
Terik di lautan bimbang, dengan semilir resah,
membawaku pada daratan penuh pertanyaan lainnya.
150
Salah satunya, haruskah aku berhenti bertanya?
Atau haruskah aku berhenti mencari jawaban?
Selesai aku menuliskan prosa balasan, segera aku kirim.
Tulisan miliknya kemudian aku padukan dengan tulisanku,
dan aku post di laman Blog pribadiku beserta namaku dan
Eleftheriana di catatan kakinya. Tak lama, pesan balasan
muncul.
ay
Sebuah senyum. Apa artinya itu? Dia senang? Ya, tentu
saja. Tapi, apa? Hanya senang? Aku kelimpungan menebak
dan mencari arti senyum agar lebih banyak penjelasan yang
lebih memuaskan.
Tapi, akhirnya aku berhenti menebak apa artinya
itu. Karena, seharusnya emoticon senyum itu sudah cukup
menjelaskan arti pesan balasan itu sendiri. Cukup, setelah
aku mengunjungi laman Blog miliknya dan sudah ter-posting
hasil tulisan kami berdua.
Aku melanjutkan pekerjaanku. Mengecek semua to do
list apakah sudah sesuai. Aku kemudian mencatat beberapa
‘keinginan’ dalam sebuah notebook yang baru aku beli
beberapa waktu lalu. Ya, aku mulai mencatat keinginan-
keinginanku. Memiliki mimpi yang semakin melebar dari
151
hasil kalkulasi harap dalam kepalaku, hanya membuatku
kewalahan saat memikirkannya.
Sepertinya, sudah banyak orang menceritakan perihal
mimpi-mimpi yang mereka catat dalam sebuah buku, atau
melalui apa pun. Hingga suatu saat mimpi itu bisa terjadi.
Bagiku hal itu lebih besar dari sekadar tabungan mimpi
yang disimpan dalam sebuah catatan. Melainkan sebuah
daftar untuk dilakukan, untuk mengingatkan, serta untuk
memindahkan data mimpi itu agar tidak memberatkan
kepalaku.
Laiknya sebuah komputer, kepalaku akan terasa berat
dan bekerja lamban jika semua data disimpan di dalamnya.
Aku perlu menyimpannya di hardisk external dalam bentuk
buku catatan.
Membuka coffee shop, menjadi seorang barista, menjelajahi
beberapa kepulauan di Indonesia lalu beberapa negara dunia
karena aku senang berpetualang, hingga menjadi orang
yang berguna entah sebagai apa. Semua aku tuliskan dalam
bentuk mind mapping. Membuat sebuah urutan kejadian dari
satu mimpi ke mimpi selanjutnya.
Namun, aku merasa mimpiku terasa terlalu sedikit.
Meski aku tak tahu aku akan mati pada umur berapa, tetapi
sepatutnya hal yang telah kutuliskan tadi bisa saja terjadi
dalam beberapa tahun jika aku memang_benar-benar
mengejarnya. Aku perlu mimpi yang lain, entah mimpi yang
lebih besar, atau mimpi yang lebih, mimpi. Lebih tidak logis,
152
lebih tidak dapat diperhitungkan oleh kemungkinan yang
dapat aku bayangkan.
Lalu pada saat aku ingin menulis mimpi yang lain,
tanganku menolak untuk bergerak. Meski isi kepalaku punya
mimpi lain yang lebih liar, tanganku tidak menyetujuinya.
Karena ternyata, sebagian dari otakku tidak bisa mencari
perhitungan logis dari mimpi itu. Tidak menemukan titik-
titik, urutan kejadian untuk bisa sampai pada mimpi itu.
Pada cerita Alice in wonderland, tokohnya pernah
berkata bahwa kita semua begitu menginginkan sesuatu
terjadi secara magis, secara ajaib, yang bisa memukau kita.
Tapi di saat yang sama, kita tidak percaya pada keajaiban.
Sialnya, aku sedang merasa seperti itu. Aku sandarkan kursi,
sedikit melamun perihal mimpi.
“Kehilangan apa yang paling menakutkan bagimu?”
Pesan masuk datang lagi, Eleftheriana. Sebuah per-
tanyaan random dilayangkan kepadaku. Menarik. Aku
tegakkan badan di kursi. Mencoba memikirkan segala jenis
kehilangan yang pernah terjadi kepadaku. Kehilangan bapak,
adalah hal paling menyedihkan bagiku saat itu. Namun,
manusia memang sudah sepatutnya akan selalu kehilangan
manusia lainnya. Sebuah ketakutan yang pasti dan tidak
terelakkan. Begitupun kita, akan menjadi kehilangan bagi
orang lainnya.
153
Aku memikirkan hal lain, sebuah kehilangan yang paling
tidak pasti. Sesuatu yang selalu kita perjuangkan, tetapi tak
terasa tengah kita perjuangkan. Hingga pada satu titik, hal
itu hilang, hancur, melebur, dan menguap entah menjadi
apa.
“Keyakinan.”
Ya, keyakinan. Menjadi sebuah kehilangan yang tak
pernah dihiraukan banyak orang. Seolah bukan sesuatu hal
yang sangat berharga. Satu-satunya hal yang tak pernah
semua orang bayangkan akan bisa, hilang.
Eleftheriana membalas pesanku, melanjutkan per-
bincangan. Seolah kami memang sedang berbincang
berhadapan. Dia ada di depanku secara pararel bukan virtual
dan hanya dipisahkan oleh dimensi jarak.
Eleftheriana: Menarik, aku tak menduga jawaban
seperti itu yang akan sampai di kotak pesanku.
Aku: Menarik, saat kamu justru harus bersiap pada
jawaban yang sudah kamu duga.
Eleftheriana: Menarik, bukan? Bahwa jawaban yang
datang, harus membuatku semakin bersiap pada hal
mengejutkan lainnya.
Aku: Jadi, sekarang kamu akan berhenti menduga?
154
Eleftheriana: Kita tidak akan pernah berhenti men-
duga-duga. Seperti kamu, yang kini tengah membuat
dugaan perihal apa yang akan aku tanyakan
selanjutnya :).
Aku: Aku ingin membiarkan dugaanmu_benar,
tapi sayang pertanyaan selanjutnya akan datang
dariku. Apa yang paling membuatmu lebih sedih?
Meninggalkan? Atau, ditinggalkan?
Pesan terakhir yang aku kirim berakhir dengan jeda.
Dugaanku, dia sedang mencoba memberikan jawaban
yang akan membuatku terpukau. Oh, aku yakin ini akan
membutuhkan waktu yang cukup lama. Lebih lama dari
dirinya saat menunggu jawabanku.
Eleftheriana: Tentu saja_ ditinggalkan. Aku_ ini
perempuan!
Ya, tak bisa kupungkiri, aku cukup terpukau karena
ternyata dirinya tidak membutuhkan waktu lama untuk
menjawab.
Aku: Waw! Kau hebat!
Eleftheriana: Satu, kamu satu-satunya orang yang
tidak menertawakan, mengejek, atau mengasihani
aku karena ditinggalkan. Kedua, apanya yang hebat?
155
perlombaan siapa yang lebih terluka. Dirinya benar, aku
tidak perlu mengajaknya membuktikan bahwa ditinggalkan
Karena jumlah luka yang aku simpan?
Aku: Bukan, kamu hebat karena kamu tidak pernah
meninggalkan seseorang.
Eleftheriana: Memang untuk apa meninggalkan
seseorang yang kamu cintai?
Aku: Kalau begitu tunggu sampai kamu _ingin
meninggalkan seseorang.
Eleftheriana: Untuk apa? Untuk =membuktikan
bahwa meninggalkan lebih menyakitkan daripada
ditinggalkan? Apa tidak ada hal lain yang lebih bodoh
yang bisa aku dengar? Kamu memang benar-benar,
mengejutkan :).
Sial, langkahku terbaca. Meski begitu, ini bukan perihal
tidak ada apa-apa dibanding meninggalkan seseorang.
156
Aku: Tidak, lupakan. Hehe.
Eleftheriana: Apa semua lelaki seperti itu?
Aku: Seperti apa?
Eleftheriana: Meminta | perempuan melupakan
semudah itu?!
Aku kelimpungan, kewalahan, dan tertawa terbahak di
saat yang sama. Wanita ini, sungguh, gila. Aku berkali-kali
tersenyum.
Aku: Hahahahahahhahahaha.
Eleftheriana: Lucu bukan? Tapi, pertanyaanku serius.
Apa kamu memang seperti itu? Hahaha.
Aku: Hmm. Entahlah, tapi buatku meninggalkan lebih
menyedihkan daripada ditinggalkan. Kamu paham
jawabannya?
Eleftheriana: Sebuah kata “tidak” yang panjang dan
rumit ya. Hehe.
Aku: Agar kamu tidak hanya mendengar jawabanya
dariku, tapi juga dari hasil olah pikiranmu :).
Eleftheriana: Menarik. Anw, aku harus pergi. Jangan
lupa tulisan selanjutnya, giliranmu memulai. Kirimkan
kapan pun kamu selesai menulisnya. See you!”
Aku: K!
Eleftheriana: Wanita tidak pernah suka balasan
seperti itu. Sekali lagi kamu membalas pesan seperti
itu, kamu akan tahu bahwa ditinggalkan lebih
menyakitkan daripada meninggalkan!
Aku: Hahahahaha. /'l/ see you soonest!
157
Aku tersenyum, lama sekali.
“Oh Eleftheriana. Mari kita bertemu. Kamu terasa seperti aku
yang lain,” ucapku dalam hati.
Perkenalan dengan Eleftheriana, membuatku selalu
menunggu percakapan selanjutnya. Caranya berbicara
kepadaku seolah kami sudah mengenal lama. Seolah dia
adalah sisi lain aku yang tidak ingin menjadi rahasia, yang
hanya aku sembunyikan dari siapa pun.
Mendapat teman berbincang seperti ini seperti kado
rahasia yang dikirim malaikat, seperti keajaiban yang tidak
pernah aku percayai. Sama seperti mimpi yang tidak berani
aku buat dalam kepalaku. Hingga keajaiban itu datang,
hingga membuatku ingin mengejek diriku sendiri karena
tidak mempercayainya.
Hampir setiap hari kami berbincang, membahas tulisan
yang aku dan dia buat.
Pernahkah ada yang berencana menyakiti?
Seingatku, aku hanya pernah berencana tinggal,
hingga menetap jadi salah satu harapanku.
Namun, perihal dikecewakan,
entah siapa yang pertama mengaku.
Atau bahkan, berebut menjadi yang pertama.
158
Saat harus ada yang mengaku,
siapa yang mengecewakan, tak satu pun berani,
mengangkat keberanian dan menurunkan ego.
masing-masing bersembunyi, di balik keangkuhan dan rasa
yang benar.
Haruskah selalu aku, yang mengalah untuk dihakimi?
Haruskah selalu aku, yang rela menjadi penyebab luka?
Aku mengirimkan tulisan yang aku buat. Tak berapa
lama Eleftheriana membalas pesanku dengan tulisan darinya
untuk melengkapi.
Tidak ada keadilan dalam perpisahan,
pergi dengan duka,
atau menetap penuh luka.
Biar aku saja yang menyembunyikan kelelahan,
aku saja yang menyisakan keraguan.
karena aku mungkin memang pantas,
untuk disalahkan. Atau, untuk terluka
Harapku,
pada perjalanan selanjutnya.
agar semesta menutup semua pintu kesempatan,
untuk aku dilukai
Tolong, pertemukan aku dengan apa pun, kecuali penyesalan.
159
Aku gabungkan tulisannya dengan milikku, dan segera
aku unggah di laman Blog pribadiku.
Eleftheriana: Sungguh, apa kamu_benar-benar
semenyedihkan itu karena telah meninggalkan
seseorang?
Aku: Hei, aku tidak bisa menjelaskan seberapa
hancurnya aku saat pergi. Itu bukan hal yang
ingin didengar banyak orang. Kamu pun tidak
memercayainya sejak awal.
Eleftheriana: Aku bukan tidak memercayainya, aku
tidak tahu bagaimana rasanya karena aku tidak
pernah meninggalkan. Jika kamu ingin aku mengerti,
kerahkan hati dan pikiranmu. Cobalah membuat
aku mengerti. Setidaknya, agar aku tahu apa yang
dipikirkan mereka saat meninggalkanku selain rasa
yang menyerah akan aku. Juga, agar aku tidak perlu
mengutuk mereka diam-diam yang memutuskan
pergi.
Aku menyandarkan badan ke sofa kedai kopi yang
menjadi tepatku mengerjakan sebagian pekerjaanku hari
ini. Kali ini dengan cappuccino panas. Bandung hari ini
tengah dingin. Sedingin kepalaku yang sedikit sulit untuk
memikirkan jawaban untuk Eleftheriana.
160
Eleftheriana: Dan juga, agar ada yang bisa mengerti
akan kepergian-kepergian yang kamu lakukan :).
Saat ini, benteng yang aku pertahankan seolah tengah
diobrak-abrik dengan pertanyaan yang menggelitik. Sebuah
serangan yang lembut, mampu melemahkanku seketika.
Aku: Biarkan aku tahu namamu, baru akan aku jawab.
Eleftheriana: Akan ada saatnya kamu tahu namaku,
sekarang cepat jawab pertanyaanku.
Aku: Oh tidak akan :).
Eleftheriana: Dengar Anak Muda, kamu mungkin
tengah merasa akan memenangkan negosisasi ini.
Tapi, sebetulnya tidak. Tidak sama sekali.
Wow, mengejutkan. Dia sama sekali tidak terlihat
terdesak, memohon, atau bahkan melakukan negosisasi
ulang.
Aku: Well, itu harga yang harus kamu bayar demi
mengetahui sedikit tentang, diriku.
Eleftheriana: Sekarang kamu tampak semakin rapuh.
Aku: Apa maksudmu?
161
Eleftheriana: Dengar, kebutuhan kamu untuk men-
jelaskan sesuatu yang tengah kamu pendam lama
agar ada orang yang dapat mengerti lebih besar
daripada kebutuhan kamu mengetahui namaku.
Semakin kamu mencoba jual mahal, semakin terlihat
bahwa apa yang kamu coba jaga itu adalah sesuatu
yang sangat rapuh.
Aku terbelalak membaca pesan itu. Sebuah bumerang
yang aku lemparkan baru saja menghantam kepalaku
sendiri. Dia benar, saat ini kebutuhan akan pengertian itu
muncul. Kehadiran dirinya ke permukaan hidupku, membuat
kebutuhanku untuk dimengerti dan didengar mulai naik.
Aku menghela napas dalam. Coba memahami dan
memikirkan bagaimana aku akan membalas pertanyaannya.
Tapi, pikiranku masih semrawut. Masih kalang-kabut karena
pernyataan darinya. Apa aku harus menjawab pertanyaan
utamanya atau bersikeras melakukan negosisasi? Tapi,
akhirnya pikiranku mengalami kebuntuan. Ada sebuah
keyakinan yang hebat bahwa jika aku tetap bersikeras akan
negosiasi, aku hanya akan kehilangan keadaan ini.
Sebuah keadaan dengan yang tepat aku bisa men-
ceritakan sesuatu yang aku pendam. Karena, jika aku
menolak keadaan ini, suatu saat akan meledak juga. Usahaku
akan lebih besar. Ya, aku akan melawan egoku sendiri karena
bagaimanapun suatu saat nanti aku yang membutuhkannya
untuk mendengarkan ceritaku. Baiklah...
162
Aku: Apa kamu pernah merasa bahwa kamulah yang
membuat semua orang dalam hidupmu pergi?
Aku melayangkan satu pertanyaan pembuka.
Eleftheriana: Hah? Apa?
Aku: Ya, selama kamu mengutuk kepergian orang-
orang yang katanya kamu cintai itu, apa pernah kamu
mengutuk dirimu sendiri karena membuat mereka
pergi?
Eleftheriana: Hmm.... Tidak pernah rasanya.
Aku: Waw, kamu benar-benar hebat.
Eleftheriana: Benarkah?
Aku: Kamu tahu, semua yang pergi menyimpan
rahasia yang sengaja tidak pernah mereka ungkap
kepadamu. Bahwa kamulah yang membuat mereka
semua pergi. Namun, hal itu tidak akan mudah
dikeluarkan dalam kalimat yang bisa didengar
langsung. Pengakuan seperti itu, hanya akan berakhir
di atas sebuah kertas atau di dalam sebuah prosa dan
puisi, dalam draf pesan, atau notes, atau Blog mereka.
Lalu, mereka menyembunyikan rapat-rapat. Karena,
rahasia itu tidak ingin didengar oleh siapa pun, tidak
ingin didengar olehmu, hingga akhirnya rahasia
itu sendiri malu untuk diketahui orang lain. Semua
163
164
rahasia itu hanya berakhir menjadi barisan kata yang
bahkan tak ingin tertuliskan.
Selain itu, ada satu hal lainnya yang akan
melukai dirinya yang memutuskan pergi. Rasa
bersalah dan rasa dihakimi. Rasa bersalah yang
menyebabkan seseorang yang ditinggalkan terluka
atas keputusannya. Dan, rasa dihakimi karena
meninggalkan seseorang yang mencintainya. Kamu
pernah ada di sana? Menjadi yang rela mengambil
keputusan untuk dihakimi? Tanpa ada satu pun pohon
yang bahkan mau memberinya teduh?
Bersyukurlah jika mereka tak pernah mengungkap-
kannya kepadamu, luka yang membuat mereka pergi.
Karena artinya, mereka sangat menyayangimu. Dan
kamu, terlalu menyayangi dirimu sendiri.
Don't be late! Enggak apa-apa, aku check in bareng
kamu aja. Aku tunggu di pintu kedatangan ya, Ra.
Sebuah notifikasi muncul dari ponselku saat baru
saja mematikan kendaraan di area parkir bandara.
Padahal aku sudah sengaja datang hampir telat
dan menyuruh Rio check in lebih dulu agar ia tak bertemu
dengan ibuku.
Tapi, semesta sedang tak ingin berkonspirasi denganku
untuk tak mempertemukan mereka. Justru saat ini dengan
terang-terangan kenyataan meneriakiku bahwa ibuku akan
segera bertemu dengan atasanku itu. Dapat dipastikan beliau
akan terus-menerus membahas tentang Rio setelah hari ini.
“Ayo Ra, udah mau telat kamu tuh. Kenapa masih santai
sih ini anak? Ini Mama malah yang panik. Kalau kamu
ketinggalan pesawat gimana? Sini barangnya Mama aja yang
bawain.”
“Enggak usah Ma, Lara bisa kok bawanya. Lagian kalau
ketinggalan pesawat mah tinggal beli tiket lagi atuh,”
jawabku asal, sambil mulai mengunci mobil dan berjalan
mendekatinya.
“Ini anak kalau ngomong suka asal deh.” Ibuku kemudian
memukul lenganku pelan. Yang sedetik setelahnya aku
sambut dengan sebuah tawa untuk menenangkan perasaanku
sendiri yang sedari tadi dirundung gelisah.
“Ra, bos kamu itu yang mana?”
Pertanyaan yang enggan untuk kudengar itu akhirnya
meluncur dari mulut ibuku. Baru saja aku ingin menjawab
bahwa Rio sudah menanti di ruang tunggu, tiba-tiba saja
sebuah suara menyerukan namaku dengan lantang.
“Lara!”
Sontak aku dan ibuku segera mengalihkan pandangan
165
menuju sumber suara itu. Tak ada omongan apa-apa yang
keluar dari mulutku pun dari ibuku. Kami sama-sama sibuk
dengan pikiran masing-masing sambil tetap melangkah
menuju laki-laki yang mengenakan kaus lengan panjang
berwarna abu-abu lengkap dengan puffer vest warna biru
dongkernya. Lelaki yang sedari tadi ingin aku lenyapkan tapi
justru memanggilku.
Saat kami sudah saling berhadapan, aku mengalah untuk
membuka suara lebih dulu. “Hmm, kenalin Mas ini ibuku.”
Rio kemudian segera mencium tangan ibuku seraya
memperkenalkan namanya. “Rio, Bu.”
Seulas senyum merekah dari bibir ibuku, entah pertanda
baik atau justru akan menjadi bumerang untukku nantinya.
“Oh ini toh yang namanya Rio. Lara kerjanya gimana?
Bagus enggak? Kalau enggak bagus mah marahin aja. Anaknya
suka ngeyel kalau dibilangin.”
Aku hanya geleng-geleng kepala mendengar ucapan
ibuku, sementara Rio justru terang-terangan senang dengan
respon hangat yang diberikan oleh ibuku itu.
“Ah, enggak kok, Bu. Lara anaknya workaholic banget.
Bahkan sering lembur kalau udah keasyikan kerja.”
Selama dua menit keduanya terlibat percakapan basa-
basi yang cukup membuatku kesulitan bernapas. Bukan
kenapa, hanya saja bosan melihat hal-hal semacam ini.
Ya, ibuku memang selalu seperti itu. Cepat akrab dengan
siapa pun teman yang kuperkenalkan kepadanya. Tapi,
166
tidak dengan Saka, karena memang aku belum sempat
mempertemukan mereka berdua.
Tidak hanya lekas akrab pada siapa saja, beliau bisa
menganggap mereka seperti anak sendiri. Tak jarang teman-
temanku yang pada akhirnya bisa bercerita tentang apa
saja dengan beliau. Meski aku sedang tak berada di antara
keduanya. Sebut saja Kanaya yang bahkan bisa menginap di
rumahku, meski aku sedang berada di Jogja.
“Hemm... langsung masuk aja yuk, Mas. Udah hampir
telat kan ya, hehe.” Aku buru-buru menghentikan perkenalan
dan percakapan yang tampaknya sudah mulai asyik itu.
Rio kemudian menatap arlojinya, mengangguk dan
segera berpamitan dengan ibuku. “Rio pamit dulu ya, Bu.
Nanti Ibu hati-hati pulangnya.”
Ibuku balas menepuk punggungnya seraya tersenyum.
“Oh iya Nak, hati-hati juga kamunya. Titip Lara ya. Marahin
aja kalau bandel.”
“Cmon Mom, Lara udah gede ih. Udah ya, Lara pamit, Ma.
Jaga kesehatan Mama. Bulan depan Lara dateng sekalian
jemput ya.”
Aku mencium tangan kemudian memeluknyaerat. Sedikit
berat hati sebetulnya bila lagi-lagi harus meninggalkan ibuku
sendirian di Jakarta. Namun apa mau dikata, beliau masih tak
ingin pindah, pun aku tak bisa begitu saja mengundurkan
diri dan berganti profesi.
Aku masih tak jua melepaskan pelukan itu hingga sebuah
167
pernyataan terdengar di telingaku. Meski hanya sebuah
bisikan tapi mampu membuatku sedikit terkejut.
“Ra, kalau kamu sama yang ini Mama kayaknya langsung
setuju deh.”
Akhirnya, aku melepaskan pelukan itu sambil meng-
geleng. Berusaha membuat ibuku mengerti bahwa aku masih
belum ingin menjalin hubungan apa pun dengan lawan jenis
apalagi itu urusan asmara.
a
Aku dan Rio tidak terlalu banyak berbicara selama berada
di dalam pesawat. Mungkin terlalu lelah dengan aktivitas
seharian, atau mungkin juga sibuk dengan isi kepala yang
terlalu berisik. Ah sial, itu sih isi kepalaku sendiri tampaknya.
Aku kembali sibuk dengan buku catatanku setelah sempat
melirik Rio yang sudah fokus dengan buku yang sedang
dibacanya. Satu hal yang kembali mengejutkanku, ternyata
Rio mengenakan kacamata. Tapi, kenapa tak pernah dipakai
jika sedang bekerja? Bukankah dengan tidak mengenakan
kacamata justru akan membuatnya bertambah parah?
Aku masih sibuk menerka-nerka alasannya hingga
sebuah pertanyaan terlontar begitu saja dari mulutku,
padahal sedari tadi coba kusimpan sendirian.
“Kamu pake kacamata, Mas?”
168
“Tya, Ra. Cuma jarang aku pake aja kalau lagi enggak baca
buku. Males, bikin sakit di hidung.”
“Padahal bagusan pake loh.” Sial, aku lagi-lagi kelepasan.
“Eh, maksudku bukannya bagusan kalau dipake ya? Soalnya,
kalau enggak dipake katanya malah bikin minusnya nambah.”
Imbuhku coba membuatnya tak berpikiran macam-macam
tentang pendapatku tadi.
“Iya, sih Ra, tapi so far kalau aku rajin makan yang sehat
dan rajin nambah asupan vitamin A, terus enggak terlalu
sering baca di gelap atau sambil tidur, enggak ada masalah
sih.”
“Ohhh... gitu,” Aku menanggapi seadanya. Seolah
kehabisan kata-kata untuk melanjutkan obrolan.
“Tapi Ra, kalau menurutmu bagusan aku pake kacamata,
ya udah mulai besok aku pake terus.”
Damn, jadi tadi dia ngeh? Aku hanya menunduk malu
tak membalas perkataannya sama sekali. Kemudian, beralih
melihat ke jendela sampai dia kembali membuka obrolan dan
menutup bukunya.
“Mamamu emang kayak gitu ke semua orang ya, Ra?”
tanya Rio yang kemudian hanya aku balas dengan sebuah
tatapan penuh tanda tanya. “Nggg, I mean selalu bisa akrab
ke siapa aja. Asyik gitu soalnya.” Rio menjelaskan.
“Oh iya, hampir semua temen yang aku kenalin selalu
kayak gitu sambutan Mama. Kenapa? Kaget ya, Mas? Maafin
ya, hehe,” ucapku sambil memasang senyum.
169
“No, aku justru seneng banget bisa disambut segitu
baiknya, Ra. Enggak nyangka aja.”
Aku mengernyit, “Enggak nyangkanya kenapa?”
“Karena, ternyata enggak sesusah ngedapetin hati
anaknya.”
Deg. Aku tak dapat berkata apa-apa, sebab isi kepalaku
terlalu sibuk menelaah ucapannya yang tidak ada kelanjutan
sama sekali. Alih-alih akan ada penjelasan lagi, Rio
justru kembali larut dalam buku yang dibacanya, tanpa
menunjukkan ekspresi apa-apa. Hal itu sukses membuat
keheningan kembali tercipta di antara kami.
Sebetulnya aku masih ingin bertanya tentang semua
ucapannya yang kerap menggantung. Tapi, melihatnya yang
seolah tak lagi peduli dengan apa yang dia katakan, aku
kemudian memilih untuk kembali sibuk pada buku catatanku
dan menuliskan keresahan di sana.
Aku tidak tahu seperti apa aku untukmu.
Namun yang aku mengerti,
ada hal-hal pada dirimu yang membuatku merasa nyaman
berada di dekat.
Aku tidak mengerti sebagai apa aku di hidupmu.
170
Namun yang aku pahami,
selalu ada tanya pada setiap pernyataan yang kamu
lontarkan.
Dan aku, masih tidak mengerti akan semuanya itu.
a
Kita yang Sudah Berakhir
:untuk kita yang sudah berakhir
Berhentilah mencari alasan, berhentilah menyalahkan,
berhentilah melihat ke belakang, dan berhentilah untuk
membawa serta luka dan duka. Karena sekarang, segalanya
telah berhenti.
Di tengah ribuan pilihan, di antara ratusan pemikiran, pada
puluhan pengharapan, serta pada banyaknya kenangan. Kita
pada akhirnya memutuskan untuk menyudahi segalanya.
Untuk beberapa alasan, kita mungkin akan terus menerus
merasa bersalah. Hingga kita lupa bahwa setiap langkah
yang kita pilih adalah bagian dari perjalanan.
Kita lupa bahwa setiap hal yang terjadi pada akhirnya akan
berlalu dan memberikan banyak pesan. Untuk membuat kita
171
semakin kuat, untuk memberitahukan siapa kita sebenarnya,
dan untuk membuat kita selalu mampu bertahan.
Oleh karenanya, berhentilah menyalahkan diri masing-
masing bahkan menyalahkan orang lain. Kita terbentuk dari
masa lalu yang mungkin menyakitkan, tapi kita dibentuk
untuk menjadi lebih berarti kemudian.
-L-
Aku sedang asyik berselancar, dan memperbarui laman
Blog dengan sebuah tulisan baru hingga tak menyadari
kehadirannya dibelakangku. Akubahkan baru tahudia sedang
memandangiku ketika Rani hendak keluar untuk makan
siang, dan memberikan isyarat kepadaku untuk menoleh
dengan gerakan dagunya. Sedetik dua detik aku masih tak
paham dengan maksud Rani tersebut, hingga kemudian aku
mendengar suara ketukan sepatu dari belakang.
“Eh Mas, udah lama di situ?” Aku dibuat terperanjat
akan kehadirannya yang selalu saja tiba-tiba.
Dia hanya membalasnya dengan senyuman. Meneguk
minuman dari gelas yang dipegangnya. “Enggak selama
nungguin kamu mau untuk buka hati sih, Ra,” imbuhnya
datar lalu berlalu begitu saja.
“Jangan lupa makan siang, Rara!” teriaknya sesaat
sebelum kemudian menghilang dari pandanganku.
172
Menyisakan aku yang kemudian bertanya-tanya tentang
kenapa dia mengubah namaku. Tentang apa yang sedang
terjadi di antara kami. Tentang kegamangan hatiku akan
seluruh sikapnya yang sangat mampu membuatku kembali
terjebak oleh perasaan.
Sekembalinya dari Jakarta memang segalanya terlihat
berbeda. Aku dengan Rio menjadi semakin akrab. Katakan-
lah, sekarang aku sudah terbiasa untuk bertukar cerita
dengannya. Perihal urusan pekerjaan atau bahkan hal-hal
remeh-temeh yang bisa memicu tawa pun sebuah sudut
pandang baru yang terbentuk.
Aku menghela napas dengan berat. Ada sesuatu yang
mengganjal dan membuatku merasa jengah dengan hal-hal
yang aku tahu apa, tapi aku tak ingin untuk menjadi tahu
akan hal itu. Aku akhirnya memutuskan membeli makanan
dari sebuah restoran cepat saji dan memakannya di kantor.
Di saat seperti ini, enggan rasanya harus berhadapan
dengan orang lain. Memasang mimik muka penuh bahagia
serta senyum yang bisa saja hanya sebuah kepalsuan,
mengingat isi kepalaku memang sedang tidak baik.
a
173
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (537)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (345)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (589)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (842)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5807)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1091)
- Venus Audyte Pustaka - The Potter BoxDocument3 pagesVenus Audyte Pustaka - The Potter BoxVENUS AUDYTE PUSTAKA100% (1)
- Etika & Kepribadian PRDocument5 pagesEtika & Kepribadian PRVENUS AUDYTE PUSTAKANo ratings yet
- Etika Dan Kepribadian Humas PDFDocument45 pagesEtika Dan Kepribadian Humas PDFVENUS AUDYTE PUSTAKA100% (1)
- 3942 - Filsafat 3Document10 pages3942 - Filsafat 3VENUS AUDYTE PUSTAKANo ratings yet
- Artikel - PERGERAKAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF PARTISIPASI POLITIK - PARTISIPASI OTONOM ATAU MOBILISASI PDFDocument10 pagesArtikel - PERGERAKAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF PARTISIPASI POLITIK - PARTISIPASI OTONOM ATAU MOBILISASI PDFVENUS AUDYTE PUSTAKANo ratings yet
- Perspektif Kritis Di Ilmu Komunikasi PDFDocument9 pagesPerspektif Kritis Di Ilmu Komunikasi PDFVENUS AUDYTE PUSTAKANo ratings yet
- Essay Tema PergerakanDocument2 pagesEssay Tema PergerakanVENUS AUDYTE PUSTAKANo ratings yet