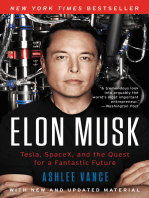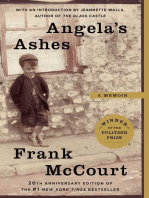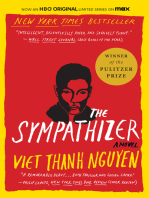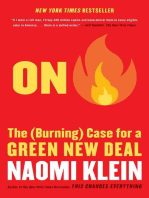Professional Documents
Culture Documents
(Belia Writing Marathon) Feli Surya - Rival PDF
(Belia Writing Marathon) Feli Surya - Rival PDF
Uploaded by
Dicky Alex0 ratings0% found this document useful (0 votes)
24 views289 pagesOriginal Title
(Belia Writing Marathon) Feli Surya - Rival.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
24 views289 pages(Belia Writing Marathon) Feli Surya - Rival PDF
(Belia Writing Marathon) Feli Surya - Rival PDF
Uploaded by
Dicky AlexCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 289
| (BEM
fami
WEL fo) iM
ery
Lo dan gue bersaing,
demj merebut hati satu sama lain
Tesfimoni untne Rival
“Rival banyak memberi pelajaran akan kehidupan yang pastinya
disajikan dengan menarik. Sangat. Ceritanya anti-mainstream,
karena tidak hanya kisah cinta dua remaja yang kita dapat ambil,
tapi juga banyak pesan moral yang bisa kita dapatkan. Kalian bakal
jatuh cinta. PASTI!”
—excinacinolak, pembaca Rival di Wattpad
“Rekomendasi banget buat baca Rival! Novel teen fiction yang nggak
muluk-muluk dan nggak alay. Amanatnya kena banget, tokoh-
tokohnya bikin ngakak dan hidup di kepala. Tema yang sederhana,
tapi dibungkus dengan sangat apik dan gokil. Excited banget sama
karya ini!”
—@haricahayabulan, pembaca Rival di Wattpad
“Rival, tuh, lengkap banget, deh, udah termasuk komplet. Ngakaknya
dapet, pengetahuan juga ada dijelasin secara perinci, konfliknya
menegangkan, sedihnya juga kerasa gitu. Come on, this is one of the
books you must buy! Dijamin nggak nyesel karena habis baca pasti
pengetahuannya nambah!”
—@sarahghdh, pembaca Rival di Wattpad
“Rival itu ibarat es campur di tengah musim kemarau. Tema cerita
yang diangkat, sih, khas anak muda, tapi bumbunya agak beda.
Formulanya beneran seger. Bikin agak dag dig dug tebak-tebak buah
manggis. Dan ... muanis, cocok banget buat seleraku yang nggak
muluk-muluk.”
—@ahnRi24, pembaca Rival di Wattpad
“Aku suka cerita Rival karena beda dari yang lain. Masalah yang
diangkat nggak cuma sekadar cerita yang benci jadi cinta. Tapi,
ada masalah besar yang tersembunyi, yang bikin cerita ini tambah
gereget. Saya suka cara penulis yang ngupas satu per satu masalah
keduanya, dan nyelesaiin pelan-pelan masalah mereka sampai
ending. Tiap di akhir part-nya juga selalu bikin penasaran, bikin
nggak sabar nunggu part selanjutnya.”
—@wulandarilmaniar, pembaca Rival di Wattpad
rival
Hak cipta dilindungi undang-undang,
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
rival
Rival
Karya Feli Surya
Cetakan Pertama, April 2018
Penyunting: Hutami Suryaningtyas, Dila Maretihaqsari
Perancang & ilustrasi sampul: Nocturvis.
Tlustrasi isi: Penelovy
Pemeriksa aksara: Achmad Muchtar, Rani Nura
Penata aksara: Anik, Petrus Sonny
Digitalisasi: FHekmatyar
Diterbitkan oleh Penerbit Bentang Belia
(PT Bentang Pustaka)
Anggota Ikapi
Jin, Plemburan No. 1 Pogung Lor, RT 11 RW 48 SIA XV, Sleman, Yogyakarta 55284
Telp. (0274) 889248 - Faks. (0274) 883753
Surel: infoebentangpustaka.com
Surel redaksi: redaksiebentangpustaka.com
http://www.bentangpustaka.com
Feli Surya
Rival/Feli Surya; penyunting, Hutami Suryaningtyas, Dila Maretihaqsari.—Yogyakarta:
Bentang Belia, 2018.
xii + 276 him; 20,8 om
ISBN 978-602-430-276-4
E-book ini didistribusikan oleh:
Mizan Digital Publishing
Ji. Jagakarsa Raya No. 40
Jakarta Selatan - 12620
Telp.: +62-21-7864547 (Hunting)
Faks.: +62-21-7864272
Surel: mizandigitalpublishingemizan.com
Untuk abang saya,
sekarang Lo tahu gue ngumpetin apa
di balie password Microsoft Word ;).
[si Cerda
Prolog - |
|: Salah Ngornong - 6
2: Sevatus Jutal - (2
3: Rencana Pevtarna - 4
4: Tentang Eda - 25
5: lim (Not) Okay - 30
6: Lets (S)Tae!- 4
7: Intrudey Alert! - 40
8: Penasavane? - 47
4; Dirvead Doangal - $2
(0: Eda Kenapa, sin - SB
It Rencana Baru - 4
[2 Rahasia Dipa - 64
1B: Pahlawan Dadatan - 75
(4: Ternyata Elo .. - 81
15: Permbelaan Dipa - So
lo: Havi Bersarmanuya - 42
17: Fix You - %%
‘8: Rencana Dadatan - 103
1% Kejutan ~ 104
20: Kvitevia Lo, Girnana? - IIS
Zk Penasavan - I2|
22 Kecewa - (2o
2: Yang Dinanti - (33
24; Havi H Lorniba - 138
25: Pevcakapan di Toilet - U4
20: Babak Teva hi - 147
77: Bolen? Boleh! - 15|
28: Yang Tak Tevsarnpaitan - |5&
24: Davi Hati - 105
30: Ketiea Dipa Tahu - (71
3k Sesuatu untuk Dipa - (lo
3: Tangis - \64
3: Every Teav Has Its Reason - \84
34; Pesan davi Dio - 147
95: A Box of You and Me - 203
3: Dia Nenghilang - 204
37. Sekali Lagi, N\aaF ... - 215
38: Continuum - 720
34, Sosok dalam Foto - 220
40: Pevjalanan Ke N\asa Lalu - 230
4; The Road Not Taken - 240
42: Sesal yang Belun (Tevlalu) Tevlannbat - 243
43; Hadiah davi Canney - 248
U4. Nohon Restu - 253
Up: Seperti Bintang - 257
Yo: Lelain davi Kata - 261
Epilog - 208
xi
CAP BADAK
gen
Profog
Ketika takdir memutuskan
untuk mempertemukan, tak akan ada
manusia yang bisa melawan.
ss
« D* lo beneran nggak tahu Eda?”
“Siapa, sih?!”
Cowok bernama Dipa yang sedang sibuk menghitung uang di
meja mulai risi dengan Dio, teman yang sedari tadi merecokinya soal
satu nama: Eda.
Siapa pula anak yang namanya Eda itu? Dipa tidak peduli.
Dia sibuk menghitung receh seribuan dan lembaran dua ribuan
yang ada di hadapannya.
“Itu, Dip, Dwenda Sastiana, murid cewek kelas XII IPA 2,
panggilannya Eda. Yang suka jualan catatan itu, Iho. Anaknya pinter
banget.”
“Hmmm... iya,” gumam Dipa asal.
Dia tak lagi memperhatikan apa yang tengah diucapkan Dio.
Otaknya sibuk menghitung.
Kok, kurang lima ribu, sih?! Apa iya jatah gue dikorupsi Bang Faisal
lagi? Dipa membatin. Duh, tega banget korupsi uang anak yatim piatu!
“Jadi, gue butuh uang dua puluh ribu, Dip.”
Mata Dipa memelotot. Dari sekian banyak ocehan Dio, yang
tertangkap di telinganya hanya: Dio butuh dua puluh ribu.
“Yo, hidup gue udah pas-pasan gini, lo masih mau minjem dua
puluh ribu dari gue?” sahut Dipa.
“Iya. Ayolah, Dip, please. Lo nggak kasihan sama gue? Gue udah
cekak, nih. Uang jajan gue udah habis semua.”
“Minta lagilah sama nyokap lo.”
“Lo gila?! Mau lihat temen lo besok udah jadi tempe bongkrek?”
Dipa menghela napas. Buatnya, dua puluh ribu itu besar, tidak
seperti murid-murid SMA Harapan yang lain.
Dipa menimbang-nimbang sejenak. Gara-gara razia seragam
hari Senin kemarin, dia lumayan untung.
Ya sudahlah, Dio barangkali lebih membutuhkan. Dari wajahnya,
Dio tampak begitu memelas.
“Nih.” Dipa menyodorkan dua lembar sepuluh ribuan kumal
kepada Dio. “Tapi, balikin, ya, nanti?”
“Iya, iya. Nanti pake bunga. Gue traktir lo makan, deh. Tapi,
bulan depan, ya? Begitu dana cair dari nyokap gue. Makasih, Dip!”
Dio menerima uang yang disodorkan Dipa dengan wajah
semringah, lalu beranjak.
“Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong, buat apa tadi lo bilang?”
tanya Dipa.
“Buat beli catatan Biologi dari Eda.”
“Beli catatan Biologi?” Dipa mengernyit.
“Iya. Tadi, kan, gue bilang, lusa gue remedial lagi, tapi lo tahulah
catatan gue gimana. Eda, kan, jualan catatan. Ya udah, gue beli aja
punya dia.”
“Beli catatan? Jadi, lo ngutang dua puluh ribu buat beli catatan?”
“Iya. Mahal banget habisnya, Dip. Seratus ribu! Duit gue kurang.
Ya udah, ya?”
Darah Dipa perlahan naik ke kepala.
Orang tua Dio adalah orang yang mapan. Namun, uang jajan Dio
sering habis sebelum waktunya hanya untuk nongkrong. Sekarang,
Dio meminjam uang kepada Dipa yang keuangannya selalu seret
untuk membeli catatan Biologi karena dia ada remedial?!
“Woi, Dio! Balikin duit gue!” teriak Dipa. Buru-buru dia
mengumpulkan semua uangnya ke dalam kantong plastik dan
menyusul Dio. “Dio!”
“[dih, Dip! Barang yang udah diberi nggak boleh diminta lagi.
Pamali!” Dio mempercepat langkahnya.
“Gue minjemin, bukan memberi, Dio!”
Dio mulai berlari. Dipa mengejar di belakangnya. Lalu, tercipta
adegan kejar-kejaran ala tarian India.
“Dio! Makanya kalo otak lo kurang mampu, nggak usah sok-
sokan sering bolos kelas!” omel Dipa sambil mengejar Dio.
“Ya udah, sih, Dip! Dua puluh ribu doang! Gue balikin bulan
depan!” Dio masih berusaha kabur.
“Dua puluh ribu doang gigi lo ngetril! Tiap rupiah bermakna
buat gue! Dio! Balikin duit gue!”
BRUK!
Dipa jatuh tersungkur ketika Dio tiba-tiba berhenti di depannya.
“Ini, Da. Dua puluh ribu, kan, kurangnya?”
Dipa menatap dengan horor ketika Dio, yang tersengal,
menyodorkan dua lembar sepuluh ribuan kumalnya kepada sosok
murid cewek yang ada di hadapan mereka.
“Oke. Nih.”
Murid itu Eda, si tukang jualan catatan di SMA Harapan. Eda
menyodorkan lembaran fotokopian kepada Dio.
“Makasih, Da!”
“Makasih juga. Senang berbisnis dengan lo. Lain kali lagi, ya.”
Eda membalikkan badan dan meneruskan langkahnya. Dipa
cepat-cepat berdiri dan mengadangnya.
“Tunggu, tunggu. Itu tadi duit gue. Tolong balikin.” Dipa
menjulurkan tangannya.
“Balikin?” Eda mengernyit. “Yang ngasih duit ini ke gue temen
lo. Kok, balikinnya ke lo?”
“Tapi, itu duit gue.”
“Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau
dikembalikan.”
Dipa menghela napas. “Gue minta baik-baik. Tolong balikin duit
gue. Dio itu minjem dan gue berubah pikiran untuk minjemin dia.”
“Apa urusannya sama gue?” balas Eda judes.
Eda melangkah lagi, tetapi Dipa kembali mencegatnya.
“Balikin!”
Eda mendecak. Dia hendak mengomel, tetapi tiba-tiba sadar
akan sesuatu. “Oh ... lo Dipa, kan? Si tukang sewa atribut sekolah?”
Dipa terdiam. Ternyata Eda tahu tentangnya.
“Iya,” jawab Dipa. “Kalo lo ke sekolah lupa dasi, topi, ikat
pinggang, atau atribut sekolah lainnya, kunjungi warungnya Bang
Faisal. Di situ lo bisa sewa. Dasi dua rib—”
“Dip.” Eda memelankan suaranya, “Jangan ribut-ribut, oke? Lo,
kan, pedagang ilegal di sekolah kayak gue, lo tahulah bahwa kita
harus fair dalam berdagang. Dio beli catatan dari gue, gue nggak
peduli itu uang dari mana atau dari siapa. Jangan menarik perhatian
minta-minta duit di koridor kayak gini. Lo tahu, kan, dagangan kita
nggak boleh diketahui guru apalagi kepala sekolah? Jadi, ya udah,
ya?”
Dipa menghela napas sekali lagi. “Oke, gini. Siapa tadi nama
lo? Eda? Gini, Da. Gue tahu kita nggak saling kenal. Tapi, sebagai
sesama pedagang, tolonglah lo maklumi gue yang omzetnya lebih
kecil dari lo ini. Lo sekali jualan seratus ribu, nggak pake modal pula.
Sementara gue udah harus modal, untungnya lebih kecil—”
“Untung apa yang lebih kecil?”
“Ampun, Pak.”
Bulu kuduk Dipa dan Eda sontak berdiri mendengar suara yang
sangat ngebas itu. Refleks mereka langsung meminta ampun.
Tak perlu menoleh untuk melihat wajahnya, Dipa dan Eda
sudah tahu bahwa kepala sekolah mereka—Pak Budi—tengah
berdiri di belakang mereka. Itu sebabnya juga koridor mendadak
sepi meskipun jam istirahat belum selesai.
“Kalian berdua, ikut saya ke kantor. Ada yang menanti kalian
berdua.”
Pak Budi meletakkan tangannya di bahu Dipa dan Eda. Keduanya
langsung lemas seketila.
“Ada yang menanti kami?” cicit Eda. “Siapa, tuh, Pak?”
“Hukuman.”
Baik Eda maupun Dipa sama-sama benci dengan yang namanya
hukuman, terlebih Eda. Dia memiliki riwayat yang begitu bersih di
sekolah. Eda dikenal sebagai anak yang pintar, rajin, penurut, tidak
pernah melanggar peraturan sekolah, dan tak pernah satu kali pun
dihukum.
Mati, deh, gue. Sekalinya bikin dosa yang berat pula. Jangan sampe
Mama dipanggil, batin Eda cemas. Bakal dihukum apa pula sama Pak
Budi?!
CAP BADAK
230
CHAPTER 1:
ee
OS
Kata-kata adalah senjata manusia
yang paling berbahaya sebab luka
yang dibuatnya tak akan ada obatnya.
ak Budi sibuk menceramahi Dipa dan Eda sejak mereka masuk
ruang kantornya. Pertama, tindakan mereka berjualan di area
sekolah melanggar peraturan. Kedua, barang dagangan mereka
melanggar etika pelajar. Ketiga, kegiatan berjualan mereka merusak
moral dan disiplin murid-murid sekolah.
“Gara-gara kalian ini, anak-anak jadi nggak disiplin dan malas.
‘Ah, bolos aja, nanti juga bisa beli catatan dari Eda’. ‘Ah, ketinggalan
seragam juga nggak apa-apa, nanti bisa sewa dari Dipa’.
“Kalian sekarang berpikir hal-hal seperti masuk kelas, mencatat
pelajaran, pakai atribut sekolah itu nggak penting. Tapi, tunggu
sampai lima-sepuluh tahun lagi saat kalian bekerja. Boleh, nggak,
coba kalau kalian ngantor, lalu bilang, ‘Waduh, Pak, saya malas
meeting, nanti pinjam protokolnya aja, ya?’ atau, ‘Waduh, Bu,
datanya ketinggalan di rumah. Saya sewa aja, ya?” Ya mana bisa!”
Dipa hanya diam. Dia tak mencemaskan soal hukuman
yang nantinya akan dia hadapi. Dia lebih cemas soal sumber
penghasilannya yang kini hilang. Dipa memutar otak, bagaimana
cara dia bisa mendapatkan uang tambahan setelah bisnisnya kena
razia?
Mungkin dia bisa minta pekerjaan dari Bu Weda, salah satu
pedagang kantin yang berjualan siomay Bandung. Ya, anaknya Bu
Weda, Sapto, sebentar lagi masuk SMP. Jam sekolahnya akan lebih
panjang dan tidak bisa membantu Bu Weda berjualan lagi.
“Dipal”
Dipa tersentak mendengar namanya dihardik Pak Budi.
“Iya, Pak!”
“Kamu ini kalau orang ngomong didengerin, dong! Malah
bengong!” Pak Budi mendengkus kesal.
“Siap, Pak! Maaf, Pak!”
“Saya tadi tanya, kalian berdua kenapa bukannya fokus belajar,
malah berjualan di sekolah?”
Dipa menoleh menatap Eda. Sejak tadi, Eda juga hanya diam
dan menunduk.
“Saya jawab duluan, Pak?” celetuk Dipa. Matanya melebar
dengan pandangan polos.
“Ya, siapa aja terserah! Yang penting jawab.”
“Gimana kalau Eda duluan aja, Pak?” Dipa membuka telapak
tangannya dan mengarahkannya kepada Eda, seolah mempersilakan.
Akan tetapi, Eda tetap membisu dengan kepala tertunduk.
“Eda? Kenapa kamu sampai seperti ini?” tanya Pak Budi. “Kamu,
kan, murid teladan sejak kelas X. Saya betul-betul kecewa sama
kamu.”
Eda masih diam dan tertunduk.
“Nggak mau jawab?” cecar Pak Budi. “Nggak mau ada pembelaan?
Pasrah aja dihukum?”
Kepala Eda perlahan mengangguk. Pak Budi melepas kacamata
dan memijat batang hidungnya.
Pak Budi kemudian menuding Dipa. “Kalau kamu kenapa, Dipa?”
“Saya jualan karena butuh uang, Pak,” jawab Dipa cepat.
“Hadehhh ... itu juga saya tahu! Kenapa pelajar seperti kamu
butuh ang segitunya sampai harus jualan?”
Dipa terdiam sejenak. Dia bicara lagi dengan suara pelan. “Jadi
... Bapak tahu, kan, saya yatim piatu?”
“lya”
“Ya, karena itu, Pak. Saya sampai sekarang tinggal di panti. Saya
satu-satunya yang tertua di sana. Saya cuma mau sedikit bantu-
bantu saja.”
Tatapan mata Pak Budi melunak. Dia menarik napas dalam-
dalam.
“Dipa, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Tapi, kamu harus
berpikir sebaliknya. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh dan fokus
belajar, itu malah memberatkan pengurus dan adik-adik kamu di
panti. Kamu sekarang sekolah yang benar, supaya suatu hari bisa
membantu mereka.”
“ya, Pak”
“Pelajar itu tugasnya belajar. Hal-hal lain biarlah jadi tanggung
jawab orang dewasa.”
“Baik, Pak.” Dipa mengangguk. Raut wajahnya dipasang
sedemikian rupa supaya menunjukkan penyesalan. “Jadi, saya nggak
dihukum, kan, Pak?”
“Bnak aja. Kamu tetap dihukum. Eda juga.”
Dipa hanya bisa mengangguk. Ya sudah. Dihukum tidak apa-
apa. Biar menjadi pelajaran baginya.
“Hukumannya jangan yang berat-berat, ya, Pak?” tawar Dipa.
“Malah nawar! Bukannya menyesal, introspeksi diri!”
“Maaf, Pak.”
Pak Budi hanya geleng-geleng kepala. “Dipa dan Eda, saya
hukum kalian berdua pulang sekolah membelanjakan kebutuhan
ruang guru di pasar. Setelah itu kalian harus menyikat WC.”
“Pulang sekolah, Pak?” Dipa memelotot. “Saya denger setelah
jam sekolah, gedung ini angker, Iho, Pak. Katanya suka ada yang
jalan-jalan gitu
“Yang jalan-jalan, ya, manusia! Angker dari mana? Saya bekerja
di sini sudah tiga puluh tahun, nggak ada, tuh, ngalamin aneh-aneh.
Lagi pula, saya dan beberapa guru ada rapat hari ini sampai sore.
Jadi, jangan banyak alasan!”
Dipa menelan ludah dan mengangguk lagi. “Siap, Pak.”
“Kamu mau protes juga, Eda? Apa mau beralasan?”
Eda menggeleng. “Nggak, Pak. Saya menyesal. Nanti saya jalani
hukumannya.”
“Bagus.”
“Saya cuma mau minta tolong satu hal ... boleh, Pak?”
“Apa itu?”
“Tolong jangan bilang ibu saya soal ini, ya, Pak,” pinta Eda
dengan memelas.
Pak Budi terlihat menimbang-nimbang sejenak apa yang harus
dia ucapkan.
Dipa melirik Eda. Kepala Eda kembali tertunduk. Wajahnya
begitu sendu. Cih, pintar sekali dia berakting supaya dikasihani?!
“Ya sudah. Saya nggak akan bilang ibumu,” kata Pak Budi
akhirnya. “Tapi janji, jangan bikin onar lagi, jangan diulangi lagi
kesalahanmu, dan fokus belajar. Kalian ini, kan, sudah kelas XII.”
“Baik, Pak. Terima kasih,” balas Eda.
“Ya sudah. Sekarang kembali ke kelas masing-masing. Daftar
belanjaan nanti sepulang sekolah minta kepada Bu Aam di ruang
guru, ya?”
“ya, Pak”
Setelahnya, Dipa dan Eda keluar dari ruangan Pak Budi. Dipa
memandang Eda sambil menaikkan alis.
“Jangan bilang ibu saya, Pak.” Dipa meledek Eda, meniru
ucapannya tadi. “Cih. Boleh juga akting lo.”
Eda takmenyahut. Dia hanya terus berjalan tanpamenghiraukan
Dipa.
“Takut dimarahin Mami, ya? Takut nggak disayang lagi sama
Mami, ya? Aduh, Eda ... anak Mami yang paling Mami sayang, kenapa
jadi nakal, sih?”
Dipa tertawa. Dia geli sendiri dengan suaranya yang pura-pura
menirukan ibu Eda.
Tiba-tiba Eda menghentikan langkahnya. Dia melempar Dipa
dengan pandangan tajam. “Jangan bicara seperti itu tentang nyokap
gue,” ucap Eda tegas.
Dipa sedikit terkejut, tapi dia buru-buru menguasai diri. “Ya,
maaf. Gue cuma bercanda. Nggak usah serius gitu, lah.”
“Kalo gue bercanda soal orang tua lo, apa lo masih bisa ketawa
juga?” sergah Eda dengan nada dingin.
Dipa terdiam. Kali ini dia tak lagi berani menyahut Eda. Dipa
hanya membiarkan Eda melangkah menjauh, mendahuluinya
kembali ke kelas.
Sementara itu, Dipa sendiri masih berdiri tertegun di koridor
sekolah yang sepi.
Nggak tahu, deh, Da, ucap Dipa dalam hati. Gue, kan, nggak
pernah kenal orang tua gue.
CAP BADAK
230
CHAPTER 2:
Serciliis dutal
Memperebutkan keberuntungan
hanya akan berujung kecewa
sebab setiap manusia sudah memiliki
sendiri-sendiri garis hidupnya.
ee
OS
¢{ Jah, belum? Lama amat!” Dipa menggerutu.
Hampir pukul 3.00 sore dan sinar matahari sangat terik
menyengat, membuat baju seragam Dipa basah oleh keringat yang
sedari tadi tak berhenti mengalir.
Dipa berdiri di depan kios kecil sambil menenteng belanjaan.
Ada satu kantong penuh berisi spidol, buku kosong, beberapa lusin
pena, beberapa kotak teh, dan sekaleng biskuit.
Ia bersama Eda yang baru saja keluar dari kios kecil dekat
tempat Dipa berdiri. Sama seperti Dipa, wajah Eda juga dibasahi
oleh peluh. Di tangan Eda ada secarik kertas. Keningnya berkerut.
Sudah setengah jam Eda dan Dipa keliling pasar untuk membeli
barang belanjaan mereka yang terakhir: satu stoples kopi.
Eda takut kalau belanjaannya salah, Pak Budi malah makin
marah. Nanti Pak Budi malah mengadukan Eda ke Mama. Aduh ...
mudah-mudahan Pak Budi menepati janjinya.
Bukan karena Eda takut dimarahi Mama, justru sebaliknya. Eda
tahu Mama tidak akan marah, tapi Mama akan kecewa. Melihat
Mama kecewa itu lebih menyakitkan bagi Eda. Bukan hanya itu, Eda
tidak mau menambah beban pikiran Mama. Tidak pada saat seperti
ini.
“Kenapa mesti kopi merek itu, sih? Yang lain aja, kenapa?” Dipa
masih terus menggerutu.
“Disuruhnya, kan, merek ini, Dip,” balas Eda.
“Aduh ... kopi, mah, semuanya sama aja. Udah, deh, beli aja yang
ada.”
“Bnak aja! Emang rasanya sama? Beda!”
“Sok tahu lo.”
“Lo yang sok tahu.”
“Lo tahu dari mana? Emangnya lo ngopi?”
“Nyokap gue koki, menurut lo?”
Balasan Eda membuat Dipa mengunci mulutnya. Dipa hanya
mengangkat bahu.
Dia mengekor di belakang Eda, yang masih pantang menyerah
mencari merek kopi seperti yang tertulis di daftar belanjaan mereka.
“Coba gue tanya ke toko itu.” Eda menuding sebuah toko
sembako yang ada di ujung jalan.
Dipa mengerang. “Udah, ya? Itu yang terakhir, ya? Kalo nggak
ada juga, beli aja yang ada, deh. Kita ini udah ada di penghujung
pasar, lho.”
“lya, iya. Tanya dulu. Lo tunggu di bawah pohon itu aja, tuh,
adem.”
“Bukan masalah panasnya juga. Ini udah jam berapa? Belum
balik ke sekolah, terus nyikat WC,” dumel Dipa.
“Kenapa, sih, buru-buru banget? Emangnya lo ada urusan?”
“Pokoknya gue harus udah balik dan duduk manis di panti jam
7.00 malam.”
“Dip, ini bahkan belum jam 3.00 sore. Tenang aja, deh.”
Dipa menggumam tak jelas. Alih-alih menunggu di bawah
pohon seperti yang disarankan Eda, dia malah mengikuti langkah
Eda masuk toko kelontong.
“Permisi, Mas. Jual Kopi Cap Talang, nggak?” tanya Eda.
“Talang? Nggak ada, Neng,” jawab pelayan toko. “Talang di
mana-mana lagi kosong! Susah dapet barangnya.”
“Oh ...,” sahut Eda kecewa. Eda menatap Dipa. “Jadi gimana,
nih?”
“Udah, beli aja yang ada. Tuh, tuh. Itu kopi apa, tuh? Banyak
stoknya,” Dipa menunjuk tumpukan stoples kopi dengan hiasan-
hiasan cerah di dekat pintu masuk toko.
“Itu Kopi Cap Badak, Dik. Enak juga. Malah lebih laku itu
daripada Kopi Cap Talang,” celetuk pelayan toko.
“Nah, tuh. Udah, beli itu aja, Da.”
Eda sedikit ragu, tetapi akhirnya mengambil sebuah stoples
Kopi Cap Badak dan membayar.
“Udah, ya? Balik ke sekolah, kan?”
“ya”
Dipa dan Eda keluar dari pasar menuju jalan raya. Di sana
mereka menunggu mikrolet untuk kembali ke sekolah. Untungnya
tak butuh waktu lama hingga mikrolet yang ditunggu datang.
Ketika sudah duduk di dalam, stoples kopi yang dibeli mereka
berdua tiba-tiba menggelinding keluar dari kantong belanjaan.
“Dip! Hati-hati, dong!” tegur Eda, buru-buru menangkap stoples
kopi tersebut. “Untung nggak pecah.”
“Sori, sori. Penuh banget, sih, kantongnya.” Dipa meringis. “Eh,
Da. Sebentar.”
Dipa mengambil stoples kopi itu dari tangan Eda. Dipa
mengernyit membaca label yang tertempel di stoples itu.
“Ada apa, Dip?”
“Ada undian kopi, Iho,” gumam Dipa. Jarinya menelusuri tulisan
yang tertera di stoples.
“Temukan kode keberuntungan di balik stoples dan menangkan
bermacam hadiah dengan hadiah utama seratus juta rupiah.” Eda
membacanya.
Dipa dan Eda saling pandang sejenak. Keduanya menelan ludah.
“Nggak mungkin, deh, punya kita.” Dipa tertawa.
“Iya. Mana mungkin.” Eda ikut tertawa.
“Tapi, coba aja.”
“Bener juga, ya, coba aja.”
Eda mengelap tangannya yang basah oleh keringat ke rok
seragamnya. Dia membuka segel stoples kopi
tersebut.
Entah kenapa napasnya menjadi cepat.
Eda melirik Dipa. Dia terlihat sama
Selamat!
Anda memenangkan
seratus jut
Jvta wupich!
Kode! Drzarby,
antusias dan tegangnya seperti Eda.
Eda merasa begitu bodoh, seperti
anak kecil. Mana mungkin stoples
yang dibelinya bersama Dipa adalah
stoples keberuntungan.
“Lihat, kosong, kan?” Eda
membuka tutup stoples dan segera
menunjukkan sisi dalamnya kepada
Dipa.
Mata Dipa membelalak. Diputarnya tutup stoples itu hingga
mengarah kepada Eda. Mata Eda ikutan membelalak. Selamat! Anda
telah memenangkan seratus juta rupiah! Kode: EXZ678Y.
Mendadak tangan Eda gemetar. Dipa meraih tangan Eda yang
masih memegang tutup stoples dan menutup kembali toples itu
rapat-rapat.
“Tenang,” gumam Dipa. “Tenang,”
“Tenang,” gumam Eda balik.
“Jangan sampai ada yang tahu.” Dipa berbisik di telinga Eda.
Eda mengangguk. “Simpan baik-baik.”
Gantian Dipa yang mengangguk. “Gue pangku aja, takut
gelinding lagi. Nggak lucu kalo ngegelinding keluar mikrolet.”
“Oke,” bisik Eda.
Dipa meletakkan stoples kopi itu di atas pangkuannya.
Tangannya mencengkeram erat bagian atas stoples tersebut.
Sementara itu, tangan Eda ikut mencengkeram erat stoples kopi
itu dari sisi samping. Baik Dipa maupun Eda hanya diam sepanjang
jalan.
Setengah mati mereka menahan diri untuk tidak berteriak
kegirangan. Ketika akhirnya mikrolet berhenti di depan sekolah,
Dipa dan Eda cepat-cepat turun.
“Dip, coba buka lagi, Dip. Beneran, nggak? Apa gue cuma
berhalusinasi?” Eda menarik lengan kemeja Dipa ketika mereka
masuk halaman sekolah.
“Mana mungkin yang berhalusinasi sampe dua orang, Da?”
balas Dipa.
“Ya, siapa tahu? Barangkali karena kita udah kelamaan kejemur,
jadi otaknya kering”
Mereka berdua berjalan hingga tiba di depan ruang guru. Dipa
meletakkan kantong belanjaan mereka di lantai. Dia membuka
tutup stoples kopi tersebut perlahan sambil menyipitkan mata.
Selamat! Anda telah memenangkan seratus juta rupiah! Kode:
EXZ678Y.
Dia kembali melihat tulisan itu. Dia tidak berhalusinasi!
“Da, beneran, Da!” Dipa mengguncang-guncang bahu Eda
dengan semangat.
“Selamat! Anda telah memenangkan seratus juta rupiah! Kode:
EXZ678Y.” Eda membaca tulisan yang ada di balik stoples. “Beneran,
Dip! Beneran!”
“AAA!!! GUE MENANG SERATUS JUTA!”
Dipa dan Eda berteriak kegirangan. Namun, rasa gembira
mereka tak bertahan lama. Mereka berdua saling pandang. Kening
keduanya berkerut.
“Tunggu, tunggu,” sergah Eda. “Lo menang seratus juta? Gue,
kali.”
“Lo2?? Gue, Da. Gue. Gue yang suruh lo beli Kopi Cap Badak ini.”
“Dan, gue yang ngambil stoples ini.”
“Lo nggak mungkin ngambil stoples ini kalo nggak gue suruh
beli Kopi Cap Badak, kan?”
“Lo nggak mungkin menang undian kalo nggak ngambil stoples
ini, kan?”
Dipa menghela napas. “Da, ini hak gue. Oke? Jangan kayak anak
kecil.”
“Dipa, balikin tutup stoples gue. Ini hak gue. Oke?” Eda berusaha
meraih tutup stoples itu.
Dipa menjauhkan tutup stoples tersebut dari Eda. “Enak aja.
Barang yang sudah diambil tidak bisa diberikan kembali.”
“Dipa, balikin tutup stoples gue sebelum gue bertindak macam-
macam ke lo,” ancam Eda.
“Seperti?”
“Seperti ini!”
“AAAAAAOOOWWW!”
Dipa menjerit keras saat Eda menendang tulang keringnya kuat-
kuat. Tutup stoples itu terlepas dari tangan Dipa dan jatuh ke lantai.
Eda segera memungutnya dari lantai. Dipa yang masih meringis
menjulurkan tangannya dan menjambak rambut Eda.
“AAAAAAAAAAAA"”
Eda ikut menjerit kencang. Tutup stoples itu kembali terjatuh.
Ketika Dipa membungkuk hendak mengambil, tiba-tiba terdengar
suara menggelegar yang familier di telinganya dan Eda.
“HEI! APA-APAAN INI?!”
Seolah waktu terhenti mendengar suara itu, Dipa dan Eda
langsung terpaku pada posisi masing-masing. Eda mengusap
kepalanya sehabis dijambak dan Dipa setengah membungkuk untuk
mengambil tutup stoples di lantai.
Siapa lagi kalau bukan Pak Budi!
CAP BADAK
gen
CHAPTER 3:
Rencana
Perfama
Ide tak terduga sering muncul ketika manusia
tengah di ambang putus asa.
« i. hadir di hadapan Anda, bersama saya Laras Sjahrir,
ose lengan serangkaian informasi yang telah dihimpun oleh tim
redaksi kami, antara lain ....”
“Mas! Mas Dipa! Mas!”
Dipa sedang di toilet ketika mendengar namanya dipanggil-
panggil.
“Mas Dipa!”
Tak lama, bukan hanya namanya yang dipanggil, melainkan juga
pintu toilet digedor-gedor.
“Sabar!” balas Dipa, setengah berteriak dari balik pintu. “Lagi
boker! Kenapa, sih?”
“Udah mulai, Mas!”
“Hah?! Emang udah jam 7.00?”
“Udah, Mas!”
“Sial.”
Cepat-cepat Dipa menyelesaikan buang hajatnya. Setelah itu dia
tergesa-gesa keluar dari toilet dan bergabung dengan Vito, salah satu
adiknya di panti yang tadi memanggil-manggil namanya, duduk di
lantai menonton TV.
“Yah, Mas Dipa telat. Lara Sjahrir udah muncul tadi,” celetuk
Vito.
“Laras Sjahrir,” ralat Dipa.
“Tya, Lara Sjahrir”
“Vit, dengerin Mas Dipa, nih. LaraSSSSSS Sjahrir. Laras. Bukan
Lara.”
“Oh.”
Vito tak peduli apakah nama pembaca berita yang ada di layar
TV adalah Lara Sjahrir ataukah Laras Sjahrir.
Akan tetapi, bagi Dipa itu penting.
Setiap hari Dipa tak pernah absen duduk di depan layar TV
menonton Laras membawakan berita. Itu sebabnya pengetahuan
umum Dipa sangat luas.
Malam itu, Dipa melewatkan bagian favoritnya dari acara
berita pukul 7.00 malam, yaitu saat Laras menyapa pemirsa dan
menyebutkan namanya.
Itu semua karena Dipa menghabiskan terlalu banyak waktu
di toilet. Mengapa Dipa mendekam begitu lama di toilet? Karena
pikirannya sibuk melayang ke mana-mana!
Tepatnya ke kejadian tadi siang. Lantaran dimarahi Pak Budi
karena terlalu berisik di depan ruang guru, akhirnya Dipa dan Eda
20
terpaksa menjelaskan perihal undian Kopi Cap Badak yang mereka
menangkan.
“Ya udah, kenapa ribut? Bagi dua aja hadiahnya, gampang, toh?”
“Nggak bisa, Pak,” sela Eda. “Saya yang ngambil stoples itu. Jadi,
saya berhak mendapatkan seratus juta itu sepenuhnya.”
“Jadi begini, Pak. Seandainya saya nggak minta Eda untuk beli
Kopi Cap Badak, apakah menurut Bapak mungkin Eda mengambil
stoples itu?” timpal Dipa.
Pak Budi mengernyit. Kepalanya pening direcok kedua muridnya
yang berseteru itu. “Kalian udah sikat WC, belum?”
“Belum, Pak.”
“Sikat dulu WC itu, baru bicara!” semprot Pak Budi. “Saya sita
stoples ini sampai kalian selesai!”
“Siap, Pak!”
Dengan segera Dipa dan Eda berlari menuju toilet, menyambar
alat-alat pembersih, menyiramnya, dan membersihkan sekuat
tenaga.
“Dip, lo nggak malu, ya, ngaku-ngaku hadiah itu adalah hak
10?” celetuk Eda, sambil dengan agresif menuang cairan pembersih
hingga dia terbatuk mencium baunya.
“Kenapa mesti malu? Itu hak gue. Lo, kali, yang mestinya malu!”
sahut Dipa, menyikat kencang-kencang hingga air memercik.
Dipa dan Eda tak bicara banyak sambil membersihkan WC.
Mereka berdua ingin cepat-cepat selesai dan mengambil hadiah
mereka.
Keduanya sampai berlari-lari, berusaha saling mendahului saat
kembali mendatangi Pak Budi.
“Sudah selesai, Pak!” seru Dipa dan Eda serempak.
“Bagus.” Pak Budi tersenyum. “Kalian ingat dihukum karena
apa?”
u
“Jualan di sekolah!”
“Apakah kalian berjanji nggak akan mengulanginya lagi?”
“Janji!”
“Sudah ada kesepakatan mengenai pembagian hadiah kalian
ini?” tanya Pak Budi.
“Pak, dengan segala hormat saya sampaikan bahwa hadiah itu
sepenuhnya milik saya,” ucap Dipa buru-buru.
Eda mendelik. “Pak, saya nggak bermaksud kurang ajar sama
Bapak, tapi ucapan Dipa itu salah besar. Hadiah itu milik saya.”
“Aduh.....” Pak Budi geleng-geleng kepala. “Kalian ini nggak malu,
ya? Udah umur segini, masih aja nggak ngerti caranya berbagi?”
“Masalahnya, saya lebih butuh uang itu daripada Eda, Pak.”
“Pak, sebetulnya saya yang lebih butuh uang itu.”
“Baiklah. Kalian berdua sama-sama butuh uang seratus juta ini.
Ini jumlah yang banyak, lho. Buat apa? Saya mau tahu.”
Baik Dipa maupun Eda segera terdiam. Tak ada satu pun dari
mereka yang berani menjawab Pak Budi.
“Buat apa? Ayo, jawab.”
Dipa dan Eda masih terdiam.
“Jangan-jangan buat maksiat, ya?”
“Astaga, Pak! Jangan suuzan,” ucap Dipa cepat-cepat, menepuk
dadanya. “Mana mungkin! Apa kata adik-adik saya di panti nanti?
Apa kata pengurus-pengurus panti?”
“Nggak usah lebay, deh.” Eda mendengkus. “Nggak, Pak. Uang
itu bukan untuk hal-hal maksiat. Uang itu untuk hal penting.”
“Hal penting apa?” Pak Budi masih mencecar mereka.
Dipa dan Eda kembali bungkam. Pak Budi menunggu mereka
untuk beberapa saat. Keduanya masih belum berubah pikiran dan
memberi tahu Pak Budi untuk apa mereka membutuhkan uang
sebanyak itu.
Uw
“Baiklah. Selama kalian nggak mau bicara, selama kalian nggak
ada kesepakatan, stoples kopi ini saya sita. Sudah, pulang kalian
sekarang”
“Oke, oke, Pak, uangnya kita bagi dua aja sesuai saran Bapak.”
Dipa buru-buru memohon.
“Iya, Pak. Saya mohon jangan disita,” pinta Eda.
Pak Budi menggeleng. “Kopi ini dibeli dengan uang sekolah. Lagi
pula, kalau sekolah nggak nyuruh kalian ke pasar dan beli kopi hari
ini, kalian nggak mungkin menemukan stoples ini, kan? Jadi, ini
hak siapa? Hak sekolah, kan?”
Kaki Dipa dan Eda langsung lemas mendengarnya. Dengan
lunglai keduanya keluar dari ruangan Pak Budi.
Dipa dan Eda menyeret langkah mereka bersamaan dengan
matahari yang mulai tenggelam. Warna oranye kemerahan yang
indah di langit sangat kontras dengan wajah mereka yang suram.
“Gue beneran butuh uang itu, Dip,” ucap Eda lirih.
“Gue juga, Da,” balas Dipa, tak kalah memelas.
Dipa dan Eda berjalan keluar gerbang sekolah dengan lunglai.
“Gimana caranya dapetin stoples itu lagi?” Eda bertanya.
“Tahu, deh. Nyolong, kali, dari ruangan Pak Budi.” Eda
mengangkat bahv. “Itu pun kalo bisa. Ruangan Pak Budi, kan, selalu
dikunci.”
Tiba-tiba mata Eda melebar. Dia menjentikkan jari. “Gue tahu
gimana caranya, Dip.”
“Gimana?” sahut Dipa malas-malasan.
“Kita harus membuat situasi kacau biar Pak Budi meninggalkan
ruangannya dan kita bisa menyelinap ke sana.”
“Oke. Situasi kacau macam apa yang lo pikirkan?”
“Bikin alarm kebakaran bunyi.”
Dipa terperangah mendengar ide Eda. Mulutnya menganga
sambil mengangguk-angguk. “Wow ... lo memang genius, Da.”
B
Eda tersenyum puas dan menaikkan alisnya. “Besok saat
jam pelajaran keempat, gue bakal izin ke toilet dan bunyiin
alarm kebakaran. Nah, kan, situasi kacau, tuh, semua pasti pada
mengevakuasi diri. Saat itulah kita menyelinap masuk ke ruangan
Pak Budi.”
“Setuju, setuju.” Dipa mengangguk-angguk. “Jam_pelajaran
keempat, ya?”
“lya. Lo siap-siap aja. Begitu denger bunyi alarm, jangan lari ke
halaman sekolah, tapi ke mana?”
“Ruang Pak Budi.”
“Pinter.”
Sepanjang sore itu hingga pulang ke panti, Dipa mengulang-
ulang kembali rencana mereka di kepalanya.
Alarm bunyi, ke ruangan Pak Budi. Alarm bunyi, ke ruangan Pak
Budi. Alarm bunyi, ke ruangan Pak Budi. Alarm bunyi....
“.. saya Laras Sjahrir, sampai jumpa.”
... ke ruangan Pak Budi.
a
CAP BADAK
20)
CHAPTER 4:
Tenfang fda
"Nggak usah menyesali hal yang nggak bisa
kita kendalikan atau nggak bisa kita ubah lagi."
‘da sedang mematangkan rencana untuk merebut kembali stoples
Kopi dari ruangan Pak Budi ketika mendengar suara pintu
rumahnya terbuka. Eda segera memasang telinga. Dia melirik jam
yang menunjukkan pukul 12.30 malam.
Dari suara langkah kakinya, Eda yakin itu adalah Mama yang
baru saja pulang. Eda melipat kertas buram, tempat rencananya
tersusun, dan menyelipkan ke dalam tas sekolah. Setelah itu dia
keluar dari kamarnya.
“Ma,” sapa Eda.
“Da?” Mama menoleh mendengar suara Eda. “Kamu, kok, belum.
tidur?”
“Iya, habis belajar,” balas Eda, berbohong.
“Jangan tidur terlalu malam. Besok, kan, kamu sekolah.”
Eda hanya mengangguk. “Mama mau teh? Aku bikinin, ya?”
“Nggak usah, Sayang. Makasih. Mama mau langsung tidur aja.
Kamu juga, gih.” Mama mengulurkan tangannya dan menyentuh
pipi Eda.
“Aku mau tidur sama Mama malam ini. Boleh?”
Mama tersenyum tipis. “Iya.”
Sejak Papa dan Dira, adik Eda, meninggal, Eda memang sering
meminta untuk tidur di kamar Mama. Terutama saat Eda sedang
sedih karena kangen Papa dan Dira. Sering kali juga karena Eda
hanya ingin menemani Mama. Eda belajar bahwa berbagi kesedihan
berdua lebih meringankan daripada menanggung sendiri masing-
masing.
“Eda, gimana di sekolah hari ini? Lancar?” tanya Mama, saat
dirinya dan Eda sudah berbaring di ranjang.
“Lancar.” Eda tersenyum kecil. Lagi-lagi dia berbohong.
Barangkali hari ini adalah hari paling tidak lancar dalam hidupnya
sebagai pelajar. “Mama gimana di restoran? Lancar?”
Mama ikut tersenyum tipis dan mengangguk.
“Ma...”
“ya, Sayang?”
“Aku udah mikir-mikir, setelah lulus SMA, aku nggak mau kuliah
Kedokteran.”
Mama mengernyit. “Lho, kenapa? Kamu, kan, dari dulu maunya
jadi dokter?”
“Nggak, ah. Kalau dipikir-pikir, aku males juga. Kuliahnya lama.”
Eda tahu, dari tatapannya, Mama tak percaya begitu saja pada
ucapan Eda.
“Lagian, jadi dokter kayaknya nggak cocok buatku, deh, Ma. Jadi
dokter itu, kan, mesti teliti, sabar, dan penuh dengan logika.”
Uo
“Da, kamu belajar yang rajin aja, ya, seperti yang selalu kamu
lakukan. Hal-hal lainnya biar Mama yang urus.”
Eda memejamkan mata saat tangan Mama mengusap kepalanya.
“Iya, Ma,” bisiknya.
Setelah itu Eda pura-pura terlelap. Eda tahu, Mama juga pura-
pura terlelap. Keduanya saling memunggungi satu sama lain. Diam-
diam air mata Eda mengalir. Dia tahu, Mama pasti juga diam-diam
menangis. Eda sering melihatnya.
Seandainya Papa masih hidup, tentu tidak akan seperti ini
keadaannya. Banyak hal berubah sejak Papa pergi. Mama jadi lebih
sibuk bekerja. Mama yang cantik kini wajahnya selalu lelah. Mama
sangat sibuk sehingga Eda jarang melihat senyumnya yang ceria
seperti dahulu. Eda jarang membawa bekal ke sekolah karena Mama
tidak punya waktu lagi untuk memasak pada pagi hari.
Eda juga banyak berubah. Eda juga tak lagi seceria dahulu.
Kalau dahulu yang memenuhi pikirannya hanyalah seputar sekolah,
mendapat nilai bagus, dan masuk jurusan Kedokteran, sekarang Eda
hanya ingin Mama kembali semangat lagi. Eda tidak ingin menjadi
beban bagi mamanya.
Pada saat pemakaman Papa dan Dira baru saja selesai, Eda
pernah bertanya kepada Mama sambil menangis. “Kenapa, sih,
Ma, hal-hal buruk menimpa orang baik? Kita orang baik, kan, Ma?
Memangnya kita salah apa?”
“Nggak tahu, Da,” jawab Mama lirih. “Nggak usah menyesali hal
yang nggak bisa kita kendalikan atau nggak bisa kita ubah lagi.”
Eda tidak puas dengan jawaban Mama. Di matanya selama ini,
Mama adalah orang yang tahu tentang segala hal. Selepas Papa dan
Dira pergi, Mama menjadi orang yang tidak punya lagi jawaban
untuk setiap pertanyaan Eda. Ada masanya Eda sempat membenci
Mama setelah Papa dan Dira meninggal. Eda merasa Mama tidak
peduli dengannya seperti dahulu.
a
Mama seolah menjauh. Mama tidak punya waktu lagi untuk
bercengkerama dengan Eda atau sekadar menemaninya belajar.
Eda merasa, Mama bahkan tidak peduli pada apa yang Eda rasakan:
bahwa dia masih belum bisa menerima kematian papa dan adiknya.
Eda masih belum bisa berhenti menangis setiap malamnya dan
masih belum bisa berhenti bertanya-tanya mengapa dia harus
mengalami musibah seperti itu.
Eda masih ingat, suatu hari, kemarahan Eda meledak begitu
saja. “Aku benci sama Mama! Sejak Papa meninggal, Mama nggak
peduli lagi sama aku. Kenapa, Ma? Karena aku cuma anak tiri?!”
Kata-kata itu keluar dari mulutnya tanpa bisa dia kendalikan.
Eda tahu dia sudah menyakiti perasaan Mama lewat ucapannya. Eda
sendiri masuk ke kamar dan menangis sehabis mengucapkannya.
Dia takut untuk bertemu Mama setelahnya. Bukan karena takut
dimarahi, melainkan karena takut jika harus melihat Mama terluka
karena ucapannya.
Dugaan Eda benar. Dia melihat Mama menangis di kamarnya
setelah Eda melontarkan kalimat tadi. Mama menangis hingga
kelelahan dan tertidur. Eda merasa sangat bersalah. Sepanjang
hidupnya, Eda sama sekali tak pernah bertengkar dengan Mama.
Bagi Eda, Mama adalah sahabat baiknya. Eda menepis semua
prasangka orang tentang ibu tiri.
“Maafin aku, ya, Ma?” bisik Eda saat itu, sambil menyelimuti
Mama. Kemudian, Eda membungkukkan badan untuk mencium
pipi Mama. Saat itu air matanya jatuh.
Mama mengerjapkan matanya dan terbangun. “Eda ...,”
panggilnya.
Mama menggenggam tangan Eda, menahannya supaya tidak
pergi. Perlahan Mama bangun dan duduk di atas ranjang. “Sini, Da.
Mama mau bicara.”
18
Eda duduk.
“Da,” ucap Mama, masih memegang tangan Eda. “Mama nggak
tahu kamu merasa seperti itu. Mama yang seharusnya minta maaf.
Mama terlalu sibuk mikirin diri sendiri, sedih sendiri, berusaha
menghibur diri sendiri, sampai nggak sadar kalau kamu juga butuh
berbagi kesedihan, butuh dihibur, butuh ditemani. Eda, maafin
Mama, ya?”
“Mama jangan ninggalin aku.” Eda mulai terisak.
“Nggak, Sayang. Mama nggak akan pernah ninggalin kamu.”
“Aku nggak bermaksud ngomong jahat ke Mama.”
“Iya. Mama percaya, Eda nggak mungkin bermaksud ngomong
seperti itu ke Mama. Maafin Mama, ya, Da?”
Dari kepergian Papa dan Dira, Eda juga belajar bahwa, bahkan
orang dewasa seperti Mama, yang selalu dia anggap kuat, ternyata
juga seorang manusia biasa. Ada kalanya Mama bersedih dan ingin
sendiri. Ada kalanya Mama bingung, tetapi tidak ingin terlihat
tersesat di mata Eda.
Akan tetapi, yang Eda yakini sekarang, Mama tidak akan pernah
meninggalkannya. Yang Eda yakini, selamanya mereka akan selalu
saling menjaga dan menyemangati satu sama lain.
“Ma,” panggil Eda, setelah lamunan tentang masa lalunya buyar.
“Iya, Sayang?”
“Mama jangan khawatir soal aku lagi. Aku baik-baik aja, kok.
Aku akan selalu cari cara supaya aku baik-baik aja. Supaya kita baik-
baik aja.”
4
CAP BADAK
7)
2830 CHAPTER 5:
1g
Jika seseorang tak pernah terdengar mengeluh,
bukan berarti dia tak pernah menangis.
atahari mulai menampakkan wujudnya saat Eda tiba di depan
batu nisan bertuliskan nama Papa dan Dira.
“Pagi, Pa. Pagi, Dira,” sapa Eda. Tak lupa Eda tersenyum, seolah
betul-betul sedang berhadapan dengan papa dan adiknya.
Eda belum pernah datang lagi ke sini sejak pemakaman mereka.
Banyak hal yang Eda takutkan jika dia datang. Dia takut menjadi
sedih lagi. Dia takut menangis lagi. Dia takut kangen lagi.
“Gimana kabar Papa dan Dira? Gimana di surga? Semuanya
indah, kan?” Eda menelan ludah, menahan diri agar air matanya tak
tumpah. “Kata Mama, doa itu seperti peta untuk ke surga bagi orang
yang udah meninggal. Papa sama Dira udah nyampe surga, kan?”
Tentu saja tak ada jawaban. Eda hanya merasakan cahaya
matahari yang perlahan menyentuh bahunya.
“Pa ... Papa tahu, nggak, sejak Papa pergi, sekarang Mama jadi
lebih sibuk.” Eda mulai bercerita. “Mama sekarang pegang shift
malam juga. Jadi, sekarang Mama selalu pulang tengah malam.
Kadang, aku udah tidur saat Mama pulang, dan Mama masih
tidur saat aku berangkat ke sekolah. Jadi, aku harus mengerjakan
semuanya sendirian, Pa. Bikin PR sendiri, belajar sendiri, bersih-
bersih rumah sendiri. Tapi, aku nggak keberatan. Aku juga udah
gede sekarang. Tapi, Papa tahu apa yang paling berat? Saat aku
pulang ke rumah yang sunyi dan sepi. Saat aku makan malam dan
sarapan sendirian ....”
Eda menyeka matanya.
“Dan, saat aku tahu, Mama sekarang kerja mati-matian seperti
ini juga buatku.”
Kedua tangan Eda menutup wajahnya. Eda tak tahan lagi. Dia
mulai terisak dan menangis.
Aku berusaha untuk bantu Mama sebisaku, batin Eda. Walau aku
tahu, yang aku lakukan salah, tapi aku cuma mau meringankan beban
Mama. Aku mau berhenti jadi beban bagi Mama.
Jadi, aku mulai jualan catatan. Idenya datang begitu aja,
ketika banyak temanku yang minjem catatanku untuk difotokopi.
Sebetulnya, sedikit demi sedikit hasil jualan catatan itu lumayan,
Pa. Tapi, aku masih butuh lebih banyak uang lagi. Kuliah Kedokteran
itu mahal biayanya. Aku sempat berpikir, mungkin lebih baik aku
nggak usah jadi dokter aja. Bahkan, kalau perlu, aku nggak usah
kuliah aja.
Tapi, aku ingat Eyang. Aku ingat kenapa aku ingin jadi dokter
dari dulu. Aku ingat ketika Eyang nggak ditangani dengan baik saat
sakit. Aku ingat wajah Papa yang penuh penyesalan, tapi nggak bisa
berbuat apa-apa. Lalu, aku juga ingat bahwa aku ingin jadi dokter
supaya aku bisa menolong eyang-eyang yang lain.
Masalahnya, Pa, kemarin aku ketangkep Kepala Sekolah karena
jualan. Aku jadi nggak boleh jualan lagi. Tapi anehnya, pada hari
yang sama, aku menang undian seratus juta!
Masalahnya lagi, Pa, karena ada makhluk nyebelin dan nggak
jelas bernama Dipa, hadiahku itu jadi disita Pak Budi. Nah, hari
ini rencananya aku mau merebut kembali hadiah itu. Doakan aku
supaya berhasil, ya, Pa! Dira, doakan aku juga, ya! Supaya aku tetap
bisa berusaha mewujudkan cita-citaku dari dulu.
Aku betul-betul butuh uang itu. Aku nggak tahu Dipa nyebelin
itu mau buat apa butuh uang sebanyak itu. Dia nggak cerita, aku
juga males tanya. Biarlah itu menjadi urusannya. Tapi, yang jelas
aku benar-benar butuh uang itu.
Tapi, harus kuakui, ya, Pa, anak itu betul-betul punya semangat
yang tinggi. Dipa ini anak yatim piatu, tinggal di panti asuhan.
Dia nggak tahu siapa orang tuanya, masih hidup atau nggak. Dia
juga nggak taku gimana nasibnya setelah lulus SMA, tapi dia
tetap semangat setiap hari datang ke sekolah, belajar. Dia bahkan
sempet-sempetnya jualan! Kalo aku jadi dia ... nggak tahu, deh, Pa.
32
Aku rasa aku nggak mungkin akan tetap punya semangat hidup yang
tinggi seperti dia.
Duh, kok, jadi ngomongin Dipa? Ya udah, deh, aku harus ke sekolah
sekarang. Papa dan Dira baik-baik, ya. Tolong doakan dan jaga aku sama
Mama dari surga sana, ya.
Eda memejamkan matanya sejenak. Dia memanjatkan doa dan
menyentuh batu nisan di hadapannya, sebelum beranjak melangkah
dengan hati yang lebih ringan.
“Every day we pray for you.
Till the day we meet again.
In my heart is where I'll keep you.”
—P. Diddy - “I'll Be Missing You”
33
CAP BADAK
230
CHAPTER 6:
Rasa penasaran itu menyebalkan,
seperti sebuah beban tak berkesudahan.
ik tik tik! Tik tik! Klik!
Dipa melirik ke kiri dan ke kanan. Dilaboratorium komputer
siang itu, Dipa hanya bisa mendengar suara jemari-jemari yang
beradu dengan keyboard dan mouse, serta suara pendingin ruangan
yang begitu keras.
Dio sudah pernah memberi peringatan kepada Dipa agar tidak
duduk dekat AC itu. AC tersebut sudah tua dan bisa saja sewaktu-
waktu jatuh menimpa orang yang ada di bawahnya.
Akan tetapi, Dipa mengabaikan peringatan Dio. Dia tetap duduk
di tempat favoritnya, sebuah sudut yang dekat dengan pendingin
ruangan. Tak ada yang mau duduk di kiri-kanan Dipa. Alasannya
sama seperti kata Dio, takut tertimpa AC. Buat Dipa tak masalah,
justru lebih bagus.
Pak Dugi, guru komputer mereka, akan sulit melihat layar
monitor Dipa dari jarak jauh. Pasalnya, di sudut inilah dia bisa
diam-diam browsing sambil mengerjakan tugas. Seperti sekarang,
Dipa sedang mengerjakan soal ulangan pelajaran komputer sambil
browsing.
“Waktunya tiga puluh menit lagi,” kata Pak Dugi.
Dipa melihat soal terakhir yang belum dikerjakannya. Ah, ini
gampang, ucapnya dalam hati. Diliriknya sekali lagi teman-temannya
yang masih sibuk mengerjakan soal.
Dipa membuka aplikasi browser di komputernya dan mengetik.
L-A-R-A-S Sjahrir.
Hasil pencarian di internet memuat profil seorang wanita muda
yang cantik dengan rambut ikal seleher.
Banyak fotonya yang menunjukkan latar belakang nama salah
satu stasiun televisi di Indonesia. Dipa menelan ludah.
Terlalu banyak foto dan informasi yang bisa dipilihnya. Akhirnya,
Dipa memutuskan untuk mengeklik laman Wikipedia.
Laras Sjahrir (lahir di Stockholm, 13 Januari 1980; umur 37 tahun)
adalah pembaca berita dalam program News Highlight di INC TV.
Ayahnya adalah seorang diplomat, membuat Laras sedari kecil
tinggal di berbagai negara, antara lain Belanda, Thailand, dan Jepang,
sebelum akhirnya kembali ke Jakarta saat SMA. Laras kemudian
melanjutkan kuliah di Amerika Serikat.
Setelah menyelesaikan pendidikannya, Laras sempat bergabung
dengan majalah ekonomi Bloomberg Businessweek di New York. Dari
situ, dia mulai meniti dunia jurnalisme. Pada tahun 2007, Laras kembali
ke Indonesia dan bergabung dengan stasiun INC TV sebagai jurnalis
hingga saat ini.
35
Kening Dipa berkerut membacanya. Dia begitu menghayati
seolah sedang membaca karya sastra saja. Jadi, Laras ini
menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di luar negeri. Sudah
lama menetap di Amerika Serikat, mendapat pekerjaan yang mapan,
lantas mengapa Laras kembali ke Indonesia?
“Dipa, kenapa malah browsing?”
DEG!
Jantung Dipa seolah berhenti mendengar suara di telinganya.
Dipa memberanikan diri untuk menoleh. Dia melihat Pak Dugi
sudah berdiri di belakangnya.
“Laras Sjahrir.”
Dipa makin gelagapan saat Pak Dugi membaca judul pada laman
yang sedang dibaca Dipa. Buru-buru Dipa menggerakkan mouse
untuk menutup laman tersebut. Namun, tangan Pak Dugi lekas
menahannya.
“Siapa Laras Sjahrir?” Pak Dugi menudingkan dagunya ke arah
Dipa.
Dipa menelan ludah. “Aaa ....” Suara yang keluar dari mulutnya
terdengar serak. Seluruh mata kini tertuju kepadanya, kecuali
beberapa murid yang memanfaatkan momen tersebut untuk saling
bertukar jawaban. “Pembaca berita, Pak, kata Wikipedia.”
“Hmmm.” Pak Dugi mengelus dagunya sambil menatap layar
monitor. “News Highlight di INC TV. Mungkin saya pernah lihat
waktu nonton berita.”
“Mungkin, Pak.” Dipa berusaha tersenyum.
“Ya sudah. Kamu keluar sekarang. Ulanganmu saya kasih nol.
Ikut rombongan remedial aja nanti, ya.”
“P-Pak, jangan, Pak. Saya minta maaf, Pak!” Dipa memohon.
Pak Dugi hanya mengangkat bahu. Dirampasnya kertas buram
dengan nama Dipa dari meja dan dia menuliskan nilai nol. Pak Dugi
juga sempat menulis: Browsing saat ulangan. Anak zaman sekarang.
30
“Keluar. Tunggu di luar sampai teman-temanmu selesai. Awas,
jangan jalan-jalan, ya!”
Dengan lemas Dipa menyeret langkahnya keluar. Dia mengacak
rambutnya seraya mengambil posisi untuk berdiri di depan pintu
laboratorium komputer. Entah mengapa sisa waktu lima belas
menit jam pelajaran komputer terasa begitu lamban bagi Dipa.
Ketika akhirnya bel tanda istirahat pertama berbunyi, Dipa menarik
napas lega.
“Dip! Lo gila, ya? Browsing pas lagi ulangan?!” Dio menepuk
bahu Dipa saat bubaran.
“Gue, tuh, udah mau kelar, Yo,” sahut Dipa. “Lagi sial aja gue!”
“Browsing apa, sih, sampe nggak bisa nunggu setelah ulangan?
Penting banget, apa?!”
“Yo, lo inget, nggak, pembaca berita yang gue ceritain ke lo
kemarin. Laras Sjahrir.”
“Kenapa dia?” sahut Dio acuh tak acuh.
“Gue, kan, tadi baca tentang dia di Wikipedia. Ternyata dia
besar di luar negeri karena bokapnya diplomat. Terus, dia kuliah di
Amerika juga, bahkan udah kerja di sana. Lo tahu, nggak, dia kerja
di mana?”
“Hmm?”
“Businessweek-nya Bloomberg!”
“Apaan, tuh?”
“Oh ... oh, iya, gue lupa. Lo, kan, cuma baca kertas bungkus
gorengan,” ledek Dipa. “Anyway, kenapa Laras pulang ke Indonesia,
ya?”
Dio memutar bola matanya. “Mana gue tahu? Emang gue
emaknya? Ngefan sama orang juga nggak segitunya, kali, Dip,
sampe dianalisis. Eh, ngomongin gorengan, gue jadi kepingin, nih.
Jajan, yuk!”
37
“Nggg ... lo aja, deh. Gue mau ke perpus.”
“KE PERPUS?!” Dio memekik. “Oh. Ya udah.”
“Apaan, sih. Gue cuma
mau ngelanjutin browsing!”
Dipa geleng-geleng kepala
Laras Sjahriv
News Broadcast
Noosas26
(
sambil tertawa. Dia geli
sendiri melihat reaksi Dio
yang sempat berlebihan,
lalu kembali datar.
Dipa membalikkan badan, _melangkah
berlawanan arah dengan Dio. Dia mengeluarkan
sebuah tanda pengenal dengan tali berwarna biru
tua dan bertuliskan INC TV.
Sambil melangkah, Dipa menatap tanda pengenal itu lekat-
lekat. Ada foto seorang wanita muda yang cantik dengan rambut
ikal seleher dan informasi pemilik tanda pengenal itu.
Laras Sjahrir. News Broadcast. NO069526.
BRUK!
“Aduh!”
Tanda pengenal di tangan Dipa meluncur dari tangannya dan
jatuh, bersamaan dengan buku dan tempat pensil yang menghambur
ke lantai. Isi tempat pensil itu bertebaran keluar.
“Duh! Makanya kalo jalan jangan sambil mainan handphone!”
omel suara murid cewek di hadapannya.
“Sori, sori,” ucap Dipa. “Gue nggak lagi mainan handphone, kok.”
Dipa buru-buru mengambil tanda pengenal Laras Sjahrir yang
terjatuh dan menyimpannya di saku seragam.
“Lah? Lo, Da?”
Ketika Dipa hendak membantu membereskan barang-barang
yang jatuh, dia tersadar bahwa murid cewek itu adalah Eda.
38
“Nggak usah. Gue aja,” gumam Eda.
Dipa menaikkan alisnya. Masih aja jutek, nih cewek?! Apa dia
nggak nyadar kalau kita punya misi bareng? Ramah sedikit sama
rekanan, kenapa?!
“Oh. Oke. Sekali lagi, maaf, ya.”
Alih-alih mengomel, hanya itu yang akhirnya diucapkan Dipa.
Eda hanya menggumam.
“Oh, ya, nanti jadi, kan?” bisik Dipa, mencondongkan tubuh dan
mendekati telinga Eda.
Eda mendecak, mengusap telinganya dengan kasar, geli karena
bisikan Dipa.
“Jadi!” desis Eda. “Udah, sana! Jangan sampai lo kelihatan dekat
sama gue, nanti mencurigakan!”
“Iya, iya. Aduh, santai, Non!”
Dipa berdiri dan cepat-cepat melanjutkan langkahnya menuju
perpustakaan, sebelum Eda merepet lagi.
“Bdal Lo ngapain?” celetuk Hanum, teman Eda yang
menunggunya di ujung koridor. “Lo kenal sama Dipa? Si tukang
sewaatribut sekolah itu, kan? Yang dagangnya di lapak Bang Faisal?”
“Iya,” gumam Eda.
“Kok, bisa kenal, Da? Th, gue mau juga, dong, dikenalin! Dia
lumayan populer, Iho. Cewek-cewek pada pengin deket sama dia,
tapi takut.”
“Takut kenapa?”
“Takut meleleh. Dipa, kan, so hooottt ....”
Eda memutar bola matanya. “Geli banget, sih?! Udah, buruan ke
kantin, gue udah laper!”
34
CAP BADAK
230
CHAPTER 7:
Apa yang seharusnya menjadi milikmu,
akan datang dengan sendirinya kepadamu.
Jangan memaksa untuk menjemputnya.
« Lz Sjahrir lagi. Lo terobsesi banget sama dia, sih?” celetuk
Dio, mengintip ponsel Dipa dari balik bahunya.
Saking kagetnya, ponsel yang dia pegang hampir terlempar.
“Apaan, sih? Ngagetin aja!” dumel Dipa. “Namanya Laras Sjahrir.
LaraSSSSSS. Pake S. Bukan Lara.”
Dio hanya melambaikan tangan dan tertawa. Tampaknya dia
tidak tertarik dengan penjelasan Dipa. Dipa pun beranjak dari kursi.
Masih ada waktu kira-kira dua menit sebelum bel masuk berbunyi.
Dipa membuka aplikasi Instagram di ponselnya. Anak yatim piatu
punya smartphone? Mungkin orang bingung. Dipa sendiri juga
bingung ketika ada sekotak smartphone baru terselip di antara
setumpuk buku pelajaran saat dia masuk SMA.
Buat Pradipta.
Di atas kotak ponsel tersebut tertera selembar kertas memo.
Hanya pesan sederhana itu yang tertulis. Sejak saat itu Dipa merawat
ponsel itu baik-baik. Jangan sampai jatuh, jangan sampai rusak.
Setelah aplikasi Instagram terbuka, Dipa mengarahkan
kamera ponselnya ke arah pintu gerbang sekolah. Murid-murid
SMA Harapan sedang ramai-ramainya melangkah masuk. Dipa
merekamnya untuk Instagram Story miliknya. Ditulisnya caption:
Nunggu bel masuk.....
Hanya sebuah video singkat sederhana yang tak menarik, tetapi
tak butuh waktu lama hingga pengikut-pengikut Dipa di Instagram
melihatnya. Setiap hari Dipa memuat foto atau video di Instagram.
Isinya sederhana saja dan sering kali tidak penting, seperti video
tadi.
“Lo sering banget, sih, upload yang nggak penting? Caper, Dip?”
celetuk Dio suatu hari.
Caper? Bukan caper, tapi apa, ya? Dipa ingin seseorang di luar
sana tahu tentang kegiatan sehari-harinya, syukur-syukur kalau
dikomentari. Instagram Dipa terbuka untuk umum, kok.
Lagi naksir siapa, sih, Dip? Belakangan aktif banget di Instagram,
komentar salah seorang temannya lewat direct message.
Lagi di depan kelas, ya, Dip? komentar temannya yang lain.
Nggak main basket, Dip?
Dipa katanya dirazia? Jadi, dagang lagi, nggak?
Ah ... di antara semua pesan yang mengomentari, tak ada
pesan yang Dipa tunggu. Dia menghela napas, lalu bernavigasi ke
4
halaman lain di Instagram. Laras Sjahrir. Akun itu terkunci. Tertera
keterangan bahwa Dipa sudah mengajukan request untuk follow, tapi
masih belum di-approve Laras.
“Aduh!”
Bulu kuduk Dipa merinding. Refleks, dia menggeliat saat
ada tangan yang mencolek pinggangnya. Dipa menoleh dan
mendengkus. Eda lagi, Eda lagi! Males banget, sih? Pada satu jam
istirahat saja sudah dua kali dia bertemu Eda!
“Lo manggil orang bisa, nggak, sih, yang bener? Jangan colek-
colekan kayak gitu? Lo kira gue sabun?!” omel Dipa ketika sosok Eda
mendekat.
“Gue panggilin dari tadi, lo nggak nyahut.” Eda membela diri.
“Jam pelajaran keempat, ya?”
“Iyeee!!! Buset, dah, lo juga tadi yang bilang kita jangan deket-
deket, takut dicurigain! Ngapain juga lo ke sini?” Dipa mendengkus.
“Cari perhatian, ya, sama gue?”
“Najis!” Eda berjengit.
“Ngomong-ngomong, lo nggak di-approve mungkin gara-gara
muka lo mesum,” celetuk Eda.
Gantian Dipa yang matanya membelalak. “Ngapain, sih, lo
ngintip-ngintip handphone gue?!”
Eda tergelak sambil berlalu.
Bel pun berbunyi. Jam istirahat telah selesai. Sekarang, saatnya
jam pelajaran keempat dimulai. Jantung Dipa mendadak berdebar
kencang. Dipa tersadar, betapa gila dirinya. Dia hendak menjalankan
aksi yang gila dengan orang yang baru saja dikenalnya kemarin, Eda.
Kemarin, saat hendak pulang dan melihat wajah Eda yang
memelas, Dipa langsung yakin bahwa Eda memang bisa dipercaya.
Eda memang butuh uang itu, tapi dia juga takkan menjebak Dipa.
Entahlah, pokoknya hati kecil Dipa berkata dia bisa memercayai Eda
42
untuk bekerja sama. Mudah-mudahan Eda memang tidak sedang
menjebaknya.
Tak lama, Pak Sutikno, Guru Fisika, masuk ke ruang kelas.
Kapan Eda akan membunyikan alarm kebakaran?
Pak Sutikno mulai mengajar. Dipa semakin resah. Tangannya
berkeringat. Dia berkali-kali menelan ludah. Belum lagi perutnya
mulas, seperti mau menceret.
“Jadi, lambda sama dengan h dibagi p, di mana lambda adalah
panjang gelombang artikel, p adalah—”
TUIT ...! TUIT ...! TUIT...!
Dipa nyaris pingsan mendengarnya. Ternyata alarm kebakaran
sekolah ini sangat dahsyat bunyinya. Pak Sutikno berhenti bicara.
Semua menatap lampu yang berkedip-kedip merah di langit-langit.
“Kebakaran, ya, Pak?” celetuk Dipa.
“lya, kok, alarm kebakarannya bunyi, ya?” Pak Sutikno
mengernyit.
“Ya, berarti ada kebakaran, Pak!” Dipa segera berdiri. “Berarti
kita harus mengevakuasi diri!”
Seisi kelas langsung heboh. Mereka ikut-ikutan berdiri seperti
Dipa.
“Tenang, tenang.” Sambil berusaha menenangkan, Pak Sutikno
keluar kelas untuk memantau situasi. Dia melihat guru-guru yang
sedang mengajar di kelas-kelas sebelah ikut keluar.
“Kebakaran, ya, Pak?”
“Kebakarannya di mana?”
“Ini anak-anak harus dievakuasi.”
Sementara itu, guru-guru masih kebingungan, Dipa sudah
menggerakkan teman-temannya untuk meninggalkan kelas.
“Ke lapangan, ya! Evakuasi ke lapangan!” Dipa berseru dengan
suara lantang.
43
Sementara itu, koridor mulai dipenuhi murid-murid yang
berjalan menuju lapangan, Dipa menyelinap menuju Ruang Kepala
Sekolah.
TUIT...! TUIT...! TUIT....!
Koridor tersebut sudah sepi. Dipa melihat Eda sudah menunggu
di dekat pintu.
“Lama banget, sih?” dumel Eda.
“Pak Sutikno, sih, pake acara kebingungan, jadi lama, deh,”
gerutu Dipa.
Eda mengibaskan tangannya, pertanda dia tak tertarik dengan
alasan Dipa. “Sekarang, gimana kita buka pintu ruangan kepala
sekolah ini?”
“Da, ngomong-ngomong alarmnya kapan berhentinya? Masa
sepanjang hari berisik begini?”
Eda mengangkat bahu. “Yang penting sekarang, gimana kita
buka pintu ini, Dip?”
“Lah, rencana lo kemarin, gimana? Kan, lo yang ngusulin, Dipa
jadi bingung.
“Gue nggak nyangka ruangannya akan dikunci. Gue pikir Pak
Budi pasti panik, dong, buru-buru keluar tanpa ngunci.”
Dipa melongo mendengarnya. “Da, lo udah heboh bikin alarm
kebakaran bunyi dan bikin seantero sekolah terevakuasi. Terus,
sekarang lo bilang ke gue kalau lo nggak tahu caranya buka ruangan
Pak Budi???!”
Eda menggigit bibir.
“Aduuuh Edaaa!!! Makanya, jangan kebanyakan makan micin!”
semprot Dipa. Dia sewot bukan main.
“Tenang, jangan marah-marah dulu.” Eda mengetuk-ngetuk
dagunya.
“Makanya, bego, tuh, jangan dipiara, Da. Nggak ada faedahnya.”
44
“Bener juga, ya, Dip. Sama kayak ngomong sama lo, nggak ada
faedahnya.”
Eda kesal bukan main dengan Dipa yang malah mengangkat
bahu mendengar sindirannya. Bukannya membantu, malah bikin
orang tambah stres!
“Lo jangan nyap-nyap doang, dong!” sembur Eda. “Bantu cari
solusi, kek!”
Dipa menghela napas. Dia mengamati ruangan Pak Budi dan
sekitarnya. Dipa menunjuk sebuah jendela kecil di atas ruangan.
“Tuh, badan lo, kan, kecil. Lo bisa masuk dari situ.”
“Dip, lo kata gue kucing? Itu celah kecil banget!”
“Ya udah, buka pake peniti kek, jepitan kek. Punya, nggak, lo?”
Eda menjentikkan jari. “Bener juga.” Eda menarik jepit rambut
dari kepalanya. “Gue cari dulu di YouTube gimana caranya.”
“Ya udah, buruan.”
Eda mengeluarkan ponselnya. Sedetik, dua detik, tiga detik
berlalu, layar ponselnya tak berubah juga. Eda mendesah. “Dip,
kayaknya kuota gue habis.”
“Hadeeeh
melihat layarnya, Dipa terkesiap. Laras Sjahrir has accepted your
Dipa segera mengeluarkan ponselnya. Saat
follow request. Laras Sjahrir started following you.
“Dip?” tegur Eda. “Kuota lo habis juga?”
“Nggak, Da.” Dengan wajah yang tiba-tiba semringah Dipa
menatap Eda. “Kuota gue banyak sekali. Sebanyak garam di laut”
“Ya udah, buruan cari gimana caranya buka pintu pakai
jepit rambut,” ucap Eda. “Terus, muka lo boleh agak santai dikit?
Mendadak kayak kucing kesurupan, gue jadi takut.”
“Entar, entar ....” Dipa memegang dadanya sambil bersandar
pada tembok. “Gue napas dulu.”
4s
“Dipa! Yang serius, dong!” Eda yang kesal merebut ponsel Dipa
dari tangan pemiliknya. Eda ikut membaca notifikasi yang masuk
dari Instagram. Laras Sjahrir has accepted your follow request. Laras
Sjahrir started following you. Eda mendengkus. Segera dibukanya
internet browser dan Eda mulai mengetik. How to open door with
“Kalian ngapain di sini?!”
Seketika jantung Eda serasa mencelus, dan Dipa terlonjak.
Yo
CAP BADAK
gen
CHAPTER 8:
Penasaran?
"It's okay if you're late.
Knock on my heart again like before."
—Lee Seung Chul - "Darling"
« Ke ngapain di sini?!”
Eda kaget bukan main mendengar suara lantang itu,
sampai-sampai ponsel Dipa yang tengah digenggamnya terlepas
dan jatuh. Dipa ikut tersentak. Antara terkejut ditegur dan melihat
ponsel kesayangannya jatuh, mata Dipa membelalak.
“Alarm kenceng begini kalian masih nggak denger juga?!”
Ternyata petugas pemadam kebakaran yang menegur mereka. Ada
dua orang petugas yang mendekat ke arah mereka.
“Tkut saya ke jalur evakuasi!” Petugas pemadam yang lain
memberi isyarat supaya Eda dan Dipa mengikutinya.
Eda mengusap wajahnya. Baik dirinya maupun Dipa tak berani
membantah. Mereka berjalan cepat menuju lapangan tempat
seantero sekolah dievakuasi. Eda melirik Dipa. Wajah Dipa begitu
kaku. Eda sampai takut sendiri, Dipa pasti kesal bukan main karena
rencana mereka berantakan. Harus Eda akui, memang salah dirinya
yang tidak memperhitungkan cara membuka pintu ruangan Pak
Budi. Eda sungguh kesal pada dirinya sendiri. Kok, bisa, sih, dia
sebodoh itu?!
Eda dan Dipa berdiri bersebelahan di salah satu sudut lapangan.
Bersama murid-murid dan para tenaga pengajar, mereka menunggu
hingga gedung sekolah selesai disisir oleh petugas pemadam
kebakaran. Dipa masih berdiri dengan ekspresi seperti patung.
“Setelah disisir, kami memastikan tidak ada kebakaran, Pak,”
kata komando pemadam kebakaran kepada Pak Budi, setelah mereka
selesai melakukan penyisiran. “Mungkin alarmnya mengalami
korsleting atau ada yang iseng membunyikannya.”
Pak Budi tidak terlalu senang mendengarnya. Ada yang iseng
membunyikannya? Murid-murid langsung berbisik-bisik. Siapa yang
nekat begitu?
“Dio! Lo, ya?” tuduh teman-teman sekelas Dipa.
“Astaga! Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, Man!”
Dio cepat-cepat menangkis tuduhan tersebut.
“Mumpung kalian semua sudah berkumpul di sini, baris
semuanya sesuai kelas masing-masing. Baris!” Tiba-tiba Pak Budi
memberi perintah. Murid-murid langsung kocar-kacir berusaha
membentuk barisan. Suasana lapangan menjadi sangat gaduh.
Setelah semua barisan tersusun, Pak Budi segera maju ke dekat
tiang bendera.
“Siapa dari kalian yang menyalakan alarm kebakaran? Mengaku
sekarang!” seru Pak Budi.
48
Deg! Jantung Eda seolah berhenti sejenak. Diam-diam Eda
melirik Dipa di barisannya. Matilah dia kalau Dipa membuka
rahasia. Bukannya tidak mungkin jika Dipa membongkar rencana
mereka yang gagal itu lantaran kesal. Eda memohon-mohon dalam
hati. Dipa, please, apa pun yang terjadi, jangan sekali-sekali lo ngaduin
gue ke Pak Budi. Please, please, please, please ....
“Tidak ada yang mau mengaku?!”
Eda menelan ludah. Sekali lagi dia melirik Dipa. Dipa masih
berdiri seperti patung. Tidak ada tanda-tanda dia akan membuka
suara. Hening. Tentunya tak ada satu pun yang mengacungkan
tangan untuk mengaku.
“Mungkin memang korsleting, Pak.”
Eda yang berdiri di barisan depan bisa mendengar suara Bu Aam
yang berbisik ke Pak Budi. Beberapa murid lain yang mendengar,
menggigit bibir, menahan tawa. Eda juga mungkin akan menahan
tawa bila pikirannya tidak sedang kalut. Sekarang dia kehabisan ide
bagaimana bisa mendapatkan kembali stoples kopi keberuntungan
tersebut.
“Ya sudah, kalian boleh bubar dan kembali ke kelas masing-
masing.”
Pak Budi akhirnya menyerah. Saat barisan bubar, Eda cepat-
cepat menyelip di antara keramaian dan mendekati Dipa.
“Dip,” panggil Eda dalam gumaman. “Lo marah, ya?”
Dipa hanya mengangkat bahu.
“Maaf, maaf. Kali ini salah gue. Gue akan berusaha memikirkan.
rencana lain yang lebih matang. Tapi, lo juga bantu mikir, dong”
“Nanti, deh.”
Hanya itu sahutan Dipa. Dipa lalu bergegas menaiki tangga. Eda
mengernyit. Buru-buru Eda menyusulnya.
“Gue tahu lo kesal, Dip. Tapi, semestinya lo juga bantuin gue,
dong, dalam menyusun rencana.” Eda mengadang Dipa.
44
Langkah Dipa terhenti. “Gue bukan marah gara-gara itu.”
“Jadi?”
“Gue marah karena lo seenaknya ngambil handphone gue, terus
ngejatuhin handphone gue segala.”
“Hah?” Eda mengernyit. Dia tidak habis pikir. Ternyata itu
alasan kenapa wajah Dipa kaku layaknya Patung Moai?! “Lo kesel
gara-gara itu? Yang bener aja, Dip? Kayak anak SMP aja!”
Dipa tak membalas tawa Eda. Dia melanjutkan langkahnya
melewati Eda.
“Dipa, Dip!” Eda kembali menjajari langkah Dipa. “Sori, deh, kalo
lo jadi kesal gara-gara itu. Tapi asli, gue nggak ngelihat apa-apa di
layar handphone lo. Cuma notifikasi lo di-approve dan di-folbek sama
. Siapa itu yang tadi pagi lo kepoin Instagram-nya? Udah, itu aja.
Dan, maaf banget kalo handphone lo jadi jatuh. Tadi gue kaget pas
tiba-tiba muncul petugas pemadam kebakaran. Lagian lo tenang aja,
handphone, tuh, nggak mungkin rusak cuma gara-gara sekali jatuh.”
Dipa menghela napas. “Iya. Ya udah, ya?”
“Ya udah ... maksudnya?”
“Ya udah, jangan ganggu gue lagi!” ujar Dipa dengan nada ketus.
Eda tercengang dengan sikap Dipa. Dia hanya berdiri terpaku di
anak tangga. Dipa itu sungguh seperti anak kecil! Masa ponselnya
diambil langsung bete? Masa ponselnya jatuh langsung ngambek?
Ditambah lagi, Eda, kan, sudah minta izin, dia mau mencari
tahu cara membuka pintu dengan jepit rambut. Plus, salah Dipa
sendiri, disuruh mencari, mengapa malah tidak sigap? Mereka,
kan, seharusnya menjadi partner dalam memperebutkan kembali
stoples kopi sitaan! Sekarang Eda jadi ikutan kesal. Pada rencana
berikutnya, Eda tak mau lagi mengikutsertakan Dipa.
Akan tetapi, di antara kesalnya, Eda teringat akan Dipa yang
tak mengadukan dirinya ke Pak Budi. Mungkin Dipa memang
50
menyebalkan, tapi ternyata dia bukan orang yang suka sesumbar.
Padahal, bisa saja Dipa cari muka di depan Pak Budi dan berkhianat
kepada Eda.
“Eh, eh, Dipa mungkin ikutan korsleting kayak alarm kebakaran,
ya? Instagram Story-nya mendadak romantis gitu.”
“Apa, apa?”
“Nih. Dipa nulis: It’s okay if you're late, knock on my heart again
like before.”
“Kyaaaaaa ...! Itu buat siapa, ya, kira-kira?”
“Kirana, kali. Anak IPS 3.”
“Idih, emang Dipa kenal?”
“Ya, kan, cantik. Orang ganteng naksirnya sama orang cantik,
lah.”
“Atau, Eda? Yang jualan catatan itu.”
“Oh, yang kemarin dihukum bareng dia? Bisa jadi, tuh.”
Deg! Saat sedang makan di kantin sewaktu jam istirahat kedua,
Eda mendengar namanya disebut di antara percakapan tentang
Dipa. Kenapa, sih, orang-orang heboh sekali soal Dipa? Kenapa
namanya dibawa-bawa pula?
Da, please, deh, jangan kege-eran! dumel Eda dalam hati. Mana
mungkin?! Dipa, kan, galak begitu sama lo!
“My darling of my dreams, hurry and run to me.
It’s okay if you're late.
Knock on my heart again like before.”
—Lee Seung Chul - “Darling”
sl
CAP BADAK
oz
230 CHAPTER 9:
1g
Doang?|
Hidup itu seperti roller coaster,
kadang kamu di atas, kadang kamu di bawah.
Dan, itulah yang membuat hidup jadi seru.
« D® handphone nggak mungkin sekali jatuh langsung rusak.
Santai aja. Lagian ini merek oke, kok,” kata Dio. “Yang penting
layarnya nggak gores atau pecah, kan?”
“Nggak, sh.”
Sepulang sekolah, Dipa memberi tahu Dio perihal ponselnya
yang jatuh. Tentu saja tanpa ada embel-embel Eda. Maklum, Dipa
tidak punya banyak pengalaman soal ponsel. Ini ponsel pertamanya.
Sebagai anak yang tinggal di panti asuhan, bagi Dipa ponsel adalah
kebutuhan yang berada di urutan kesekian.
“Ngomong-ngomong, donatur yang ngasih lo handphone baik,
ya. Ini handphone bagus, lho,” celetuk Dio.
Dipa termangu. “Iya. Gue juga penasaran. Gue pengin berterima
kasih aja. Kayaknya itu adalah orang yang sama seperti yang
ngirimin buku pelajaran dan seragam tiap tahun.”
“Thu Panti juga nggak tahu siapa?”
“Nggak. Katanya cuma sopir yang datang anter barang-barang
buat gue.”
“Mungkin kalo lo masuk kuliah nanti, lo dikasih handphone
baru, Dip!”
Dipa hanya tersenyum kecut. Kuliah? Rasanya tidak mungkin
untuknya. Dipa mau langsung bekerja saja, supaya bisa membantu
adik-adiknya di panti.
“Gue nggak perlu handphone baru lagi, kok. Udah seneng sama
yang ini,” ucap Dipa.
Tiba-tiba dia jadi teringat Eda. Mungkin tadi Dipa terlalu ketus
terhadap Eda. Dipa menyadari, dirinya memang berlebihan.
“Eh, Yo, lo tahu nomor handphone Eda, nggak?”
“Eda? Eda tukang jualan catatan?”
“ya”
“Tahu, sih. Kenapa, Dip?”
“Bagi nomornya, dong, Yo.”
“Lo mau beli catatan?”
“Bukan. Ada urusan.”
Dio memicingkan mata. Tiba-tiba dia menyeringai. “Jangan-
jangan ... cewek yang bikin lo penasaran itu Eda, ya?”
“Najis!” seru Dipa. “Ya bukanlah!”
“Kalo iya juga nggak apa-apa. Kayaknya kalian cocok juga, Dip.”
“Yo, buruan nomornya berapa?”
Masih senyum-senyum, Dio memberikan nomor ponsel Eda
kepada Dipa. Dipa cuek saja dengan Dio yang terus menggodanya.
Toh, memang Instagram Story yang diunggahnya bukan untuk Eda!
53
Dipa tak menyangka unggahannya itu menuai banyak reaksi.
Tapi tentu saja, reaksi yang muncul tak satu pun datang dari orang
yang diharapkannya.
“Serius, deh. Siapa yang bikin lo penasaran, sih, Dip?” Dio masih
belum menyerah.
“Ada, lah,” jawab Dipa sekenanya.
“Temen sekelas kita? Satu sekolah? Anak mana?”
“Mmm... anak mana, ya? Anak ibu dan bapaknya, deh.”
Dipa tergelak melihat reaksi Dio yang terlihat kesal.
“Oke, deh. Kalo gitu kasih tahu gue kenapa lo penasaran sama
dia. Karena apa? Cantik? Pinter? Super baik? Atau, jangan-jangan
karena dia wangi melati? Kakinya nggak napak?”
“Hus! Jangan ngomong sembarangan!” hardik Dipa. “Ya
napaklah kakinya! Lo kira kuntilanak?!”
“Ya, kan, mana tahu lo kenalan di bawah pohon beringin nan
rindang ...””
“Idih, amit-amit!”
Gantian Dio yang terkekeh.
“Gue penasaran karena ... susah dijelasinlah, Yo. Terlalu ribet.”
Dio hendak protes, tetapi saat itu angkot jurusan Dipa muncul.
“Eh, itu angkot gue. Udah, yal”
Dipa melambaikan tangan kepada sopir angkot dan segera
menaikinya sebelum Dio sempat berbicara lagi. Di dalam angkot,
Dipa mengeluarkan ponselnya. Dia menatap nama Eda cukup lama
sebelum memutuskan untuk mengirim pesan WhatsApp kepadanya.
Dipa: Da ....
Dipa mengirim pesan pertama. Ketika Dipa sedang mengetik
lanjutannya, status Eda yang kosong berganti menjadi online.
SH
Dipa lanjut mengetik.
Dipa: Tadi kayaknya gue lebay, sih, kesel sama lo sampe segitunya. Gue
norak, soalnya itu handphone pertama gue, sumbangan pula dari
orang yang gue nggak tahu siapa. Jadi, gue beneran takut rusak.
Sebab, kalo rusak gue nggak mampu beli lagi. Belum tentu gue
dapet lagi. Maaf, ya, Da?
Satu per satu tanda centang di sebelah pesan Dipa berubah
warna menjadi biru. Tandanya Eda sudah membacanya. Status Eda
pun masih tetap bertuliskan online.
Dipa menunggu balasan dari Eda. Semenit, dua menit, status
online Eda lenyap. Dipa mengerjapkan matanya. Di-read doang, nih?
Dipa kembali menunggu. Namun, hingga Dipa turun dari
angkot, kembali ke panti, mandi, makan, bahkan hingga Laras
Sjahrir muncul di TV dan mengucapkan, “Saya Laras Sjahrir, sampai
jumpa’, Eda masih belum juga membalas Dipa.
Sebelum tidur, Dipa yang tidak habis pikir itu kembali menatap
layar ponselnya. Dia tidak bisa tahu kapan Eda terakhir aktif di
WhatsApp. Eda tak mengaktifkan fitur itu. Namun, tidak menjawab
pesan yang sudah dibaca berjam-jam menurut Dipa itu sudah
keterlaluan. Terlebih pesan itu permintaan maaf. Bayangkan, Dipa
sudah berbesar hati melunturkan gengsinya, tapi malah dicuekin
Eda?!
Tiba-tiba Dipa jadi panik. Bagaimana kalau Eda sesumbar ke
teman-temannya soal Dipa yang mengirimi pesan? Lalu, teman-
teman Eda tadi sesumbar ke teman-temannya yang lain? Lalu,
seantero sekolah tahu bahwa Dipa diabaikan Eda?
“Lo tahu, nggak, Dipa?”
“Dipa siapa?”
9S
“Pradipta anak IPA 5. Yang dulu suka nyewain atribut, tapi
dagangannya udah gulung tiker itu.”
“Oh, tahu. Yang dikacangin Eda, kan?”
“Iya! Tengsin banget, nggak, sih, dikacangin Eda?”
“Hahahaha!”
Oh tidaaaaaak ...! Dipa menjerit dalam hati ketika
membayangkan obrolan macam itu akan segera menyebar. Dia
buru-buru memejamkan mata, tak ingin memutar skenario buruk
lain di benaknya. Pokoknya, besok kalau bertemu dengan Eda, dia
akan segera bicara langsung dengan makhluk satu itu. Kalimat apa
yang sebaiknya dia gunakan untuk membuka percakapan, ya?
“Da! Lo kenapa nggak bales pesan gue?”
Cih. Kesannya jadi Dipa yang ngejar-ngejar Eda.
“Da, kemarin terima pesan gue, nggak?”
Lah, itu lebih aneh lagi. Jelas-jelas tertera bahwa pesan Dipa
sudah dibaca. Memangnya WhatsApp bisa bohong?
“Da, jadi soal kemarin, gue mau minta maaf.”
Aduh, formal banget, sih? Ini, kan, cuma Eda doang gitu.
“Da
“Aduuuh, nggak tahu, ah!” Dipa dengan kesal membalikkan
badan dan memeluk guling. Kalimat-kalimat dalam pikirannya
berhamburan tanpa bisa dia rangkai.
Dipa pun pergi tidur. Dipa tak tahu, sepanjang dia terlelap,
ada hal-hal yang akan membuatnya memekik kegirangan saat dia
bangun. Seperti Instagram Story-nya yang dilihat oleh Laras Sjahrir
dan pesan WhatsApp yang muncul dari Eda pukul 3.00 dini hari.
Lucu, ya? Kadang, dalam suatu hari, kita merasa hari kita itu
berjalan dengan tidak sempurna, tetapi saat kita bangun keesokan
harinya, tiba-tiba keadaan berubah. Seperti roller coaster, kadang
5b
kamu di atas, kadang di bawah. Dan, itulah yang membuat hidup
jadi seru.
3?
CAP BADAK
2§S0
CHAPTER 10:
fda henapa,
sina
Penasaran adalah rasa yang paling berpotensi
berevolusi menjadi cinta.
OS
(Ch, Yo ... itu, apa ... Eda kelas berapa, sih?”
Dio yang baru duduk di kursinya langsung ditanya oleh
Dipa perihal Eda. Wajah Dio yang tadinya melongo berubah. Dia
tersenyum-senyum menjijikkan.
“th ... nanyain Eda lagi. Beneran naksir ceritanya?”
Dipa mendecak. “Jangan ngegosip lo. Gue ada urusan sama dia.”
“Kemarin, kan, udah gue kasih nomor handphone-nya?”
“Justru itu. Urusan tak terselesaikan di handphone. Gue mau
datengin ke kelasnya.”
“Dia anak IPA 2, Dip. Sukses, ya! Gue harap lo nggak lagi menjadi
jomlo orok. Yeay! Semangat! Ummmph!”
Dio berusaha membebaskan diri dari Dipa yang membekap
mulutnya. “Dibilangin jangan ngegosip!”
Setelah Dio minta ampun di balik tangan Dipa dengan suara
melengking seperti tikus kejepit, barulah Dipa melepaskan
tangannya sambil terkekeh. Dipa keluar kelas dan berjalan menuju
kelas XII IPA 2.
“Permisi ....” Dipa menjejakkan kakinya ke kelas itu. Entah
kenapa, setiap kali mengunjungi kelas orang, Dipa merasa kelas itu
lebih bagus daripada kelasnya sendiri. Mungkin memang rumput
tetangga selalu lebih hijau, ya? Beberapa murid yang tengah duduk
bercengkerama menoleh mendengar suara Dipa.
“Bda ada, nggak?” tanya Dipa.
Murid-murid itu cuma menatap Dipa dengan mulut menganga.
Tidak ada satu pun yang menjawab. Dipa jadi salah tingkah. Ternyata
walau kelasnya lebih bagus, sepertinya anak-anak IPA 2 ini lebih
bolot daripada IPA 5.
“Lo pada tahu, nggak, Eda di mana?” Dipa mengulang
pertanyaannya.
“Eda hari ini nggak masuk.” Seorang murid perempuan berambut
keriting tiba-tiba berdiri. Dia adalah Hanum. “Lo Dipa, kan? Ada
perlu apa? Nanti gue sampein.”
“Nggak masuk?” Dipa mengernyit. “Oh. Kenapa?”
“Nggak tahu, deh. Gue tanya belum dibalas lagi. Katanya dia
udah izin ke wali kelas.”
“Oh, gitu.”
“Nanti gue sampein kalau ada perlu,” ulang Hanum.
“Nggak apa-apa. Nanti aja kalau dia udah masuk. Makasih, ya.”
Dipa mengangguk sekilas, lalu pergi.
94
Aneh. Kenapa Eda tidak masuk sekolah, ya? Padahal, Eda sempat
membalas pesan WhatsApp Dipa pukul 3.00 dini hari tadi.
Ketika itu, Dipa bangun, ponselnya menghujani Dipa dengan
hal-hal yang membuatnya segera berjoget di ranjang. Pertama, saat
Dipa mengecek Instagram Story-nya yang terakhir, dia melihat
nama Laras Sjahrir tertera sebagai salah satu pengikut akunnya yang
melihat Instagram Story tersebut. Kedua, Eda akhirnya membalas
pesan Dipa sehingga dia tak perlu kehilangan muka.
Pesan Eda pun sangat memuaskan hati Dipa.
Eda: lya, nggak apa-apa, Dip. Gue juga minta maaf, ya, arena rencananya
gagal dan gue seenaknya aja ngerebut handphone lo.
Tadinya dia mau ikutan Eda, membiarkan pesan yang sudah
terbaca selama dua belas jam sebelum membalasnya. Namun, Dipa
tidak tahan. Selesai mandi, dia menjawab pesan Eda.
Dipa: lya, Da. Saling memaafkan. Nanti jam istirahat pertama lo ngapain?
Gue ada ide baru buat ngambil stoples kopi itu dari Pak Budi.
Akan tetapi, pesan Dipa tersebut tak kunjung dibaca Eda,
bahkan hingga Dipa tiba di sekolah. Itulah yang membuat Dipa
memutuskan untuk mendatangi Eda di kelasnya dan mengajak
bicara langsung. Sayangnya, Eda tidak masuk sekolah. Kenapa, ya?
Apa Eda sakit?
Bisa jadi Eda sakit. Diamembalas pesan Dipa pada jam yang tidak
lazim. Pukul 3.00 pagi? Mungkin Eda terbangun tengah malam.
Atau, jangan-jangan tuduhan Pak Budi benar? Jangan-jangan Eda
ikut anggota geng, atau pengikut dunia maksiat? Makanya, dia
masih terjaga pukul 3.00 pagi. Makanya, Eda butuh uang. Makanya,
60
Eda tidak segera menyangkal seperti Dipa saat Pak Budi menuduh
mereka butuh uang untuk maksiat? Hiiiy ...!
Akan tetapi, masa iya Eda yang anak teladan di sekolahituaslinya
berandalan? Lagi pula, tampang Eda tidak seperti itu. Namun juga,
pergaulan anak zaman sekarang, kan, begitu liar. Mana ada yang
tahu? Makanya, Eda memohon supaya Pak Budi tidak memberi
tahu ibunya. Ibu mana yang tidak akan terkejut kalau tahu anaknya
terjerumus pergaulan sesat?
Dipa menepuk-nepuk pipinya. Jangan berprasangka buruk, Dip,
jangan! Boleh jadi Dipa anak yatim piatu. Boleh jadi Dipa tak pernah
kenal didikan orang tua sendiri. Namun, bukan berarti Dipa anak
yang tidak punya moral. Dia selalu dididik di panti untuk tidak
memiliki prasangka buruk terhadap orang lain.
Kriiing!
Bel tanda masuk berbunyi. Bersama murid-murid yang lain,
Dipa segera masuk kelas.
“Contoh di buku teks ini adalah paragraf deduktif. Apa cit
paragraf deduktif? Coba baca yang benar kalimat-kalimat di paragraf
iri
ini. Kalimat pertama....”
Pelajaran pertama adalah pelajaran Bahasa Indonesia dan Dipa
sama sekali tidak bisa berkonsentrasi. Asli, dia betul-betul penasaran
dengan Eda. Apa yang terjadi pada dirinya, ya? Diam-diam Dipa
mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Dengan pandangan mata
masih menatap Pak Sutan yang mengajar di depan, Dipa mengetik.
Dipa: ;) da, lo kdnapa hafi jnj ga nasik?
Dipa menatap layar ponselnya dengan pandangan horor. Apa
pula yang barusan diketik dan dikirimnya ke Eda?!
ol
3)??? Kdnapa??? Hafi??? Jnj??? Nasik???
Yang paling membuat Dipa risi adalah emoticon ‘;)’ tersebut.
Sungguh, dia tidak bermaksud menggoda Eda!
Dipa meletakkan ponselnya di atas meja. Dia buru-buru
mengetik lagi. “Da, tadi gue ngetik nggak lihat layar. Sori. Maksud
gue, lo kenapa hari ini nggak masuk?”
“Pradiptal”
Dipa tersentak mendengar namanya dipanggil. Barusan Pak
Sutan menegurnya. Dipa celingukan. Semua mata tertuju kepadanya
sekarang.
“Coba kamu kasih tahu saya, dari tiga paragraf tadi, yang mana
yang termasuk paragraf deduktif?”
Dipa menelan ludah. Yang mana? Waduh....
“Nggg ... tiga paragraf yang mana, ya, Pak?” cicit Dipa.
“Makanya, kalau lagi pelajaran itu didengarkan! Jangan malah
mainan handphone!” omel Pak Sutan, segera berjalan menghampiri
Dipa.
Sesuai ketakutan Dipa, Pak Sutan menyita ponselnya. “Anu, Pak
.. nggg ... hati-hati, ya, sama ponselnya?” Dipa meringis.
Pak Sutan hanya memelotot, kemudian lanjut mengajar. Dipa
menarik napas dalam-dalam. Gara-gara pengin tahu soal Eda, sih!
Makanya, Dip, jadi orang nggak usah kepo! Dipa memarahi dirinya
sendiri dalam hati.
Sialnya, karena ponsel disita, Dipa justru jadi makin resah.
Dia semakin penasaran apa yang terjadi pada Eda. Siapa tahu Eda
membalas pesannya. Siapa tahu Laras Sjahrir menge-like salah
satu fotonya. Lho, kok, nggak nyambung, ya? Ah, bodo! ucap Dipa
dalam hati. Setiap kali dia jauh dari ponsel, biasanya kemudian dia
mendapat kejutan baik. Siapa tahu kali ini juga begitu.
62
Hmmm .... Eda kenapa, sih? Dipa bicara sendiri dalam hati.
Nggak, bukannya khawatir. Penasaran aja. Nggak penasaran juga, deng.
Pengen tahu aja. Sebenernya juga nggak pengin tahu banget, tapi ... ya,
pokoknya gitu, deh!
63
CAP BADAK
2360
CHAPTER 11:
Satu tujuan adalah pangkal dari satu hati.
Hanum: Da, tadi Dipa nyariin lo, tuh, ke kelas. Ada apa, sih, antara lo
sama Dipa? Dia lagi PDKT sama lo?
da langsung mengernyit membaca pesan dari Hanum. Baru
bangun sudah dihadapkan dengan pesan aneh macam itu.
Eda: Apaan, sih, lo? Nggaklah! Ngapain Dipa nyari gue?
Setelah menjawab Hanum, Eda baru sadar bahwa ada pesan-
pesan masuk dari Dipa. Terus terang, Eda terkejut saat Dipa
mengiriminya pesan berisi permintaan maaf kemarin. Eda sungguh
tidak menyangka. Gara-gara itu, Eda jadi sedikit luluh. Mungkin
Dipa tidak semenyebalkan yang dia sangka.
Eda tersenyum geli membaca pesan Dipa yang salah tik tersebut.
Eda pun membalas.
Eda: Sori, gue baru lihat handphone, Dip. Nyokap gue masuk rumah
sakit, gue nungguin dari semalam. Rencana apa yang lo punya?
Jam menunjukkan pukul 11.00. Semestinya masih jam istirahat,
mungkin sebentar lagi Dipa akan membalas. Eda cukup penasaran
apa rencana Dipa. Terutama, karena kejadian semalam, Eda semakin
menggebu untuk mendapatkan uang hasil menang undian tersebut.
Eda menatap Mama yang terbaring lemah di ranjang. Ada
kantung hitam di bawah kedua matanya. Eda kaget bukan main
semalam saat dia mendapat telepon dari restoran tempat Mama
bekerja. Mereka mengabarkan bahwa Mama pingsan dan dibawa ke
rumah sakit.
“Sebelum tak sadarkan diri, ibumu mengeluh perutnya sakit,
Da,” kata salah seorang rekan kerja Mama.
Tengah malam, Eda sendirian naik taksi ke rumah sakit. Dokter
bilang Mama terkena batu empedu dan langsung segera dioperasi.
Sekarang keadaannya sudah stabil, tapi masih harus banyak
istirahat. Sampai sekarang Mama masih tertidur.
Eda meraih tangan Mama dan memeluknya. Dia sungguh
ketakutan semalam. Bukan kali pertamanya Eda mendapat kabar
buruk yang membuat geger seperti kemarin. Belum sampai setahun
yang lalu dia mengalami hal serupa. Eda juga sedang duduk di meja
belajar, mengulang pelajaran, saat mendapat telepon dari rumah
sakit yang mengabarkan bahwa ayah dan adiknya menjadi korban
tabrak lari.
oS
“Kondisi keduanya kritis saat ditemukan warga. Tolong ke sini
secepatnya, ya.”
Tak pernah Eda sekhawatir itu sepanjang hidupnya. Namun,
ketika itu keadaannya berbeda. Ada Mama yang menemaninya ke
rumah sakit. Dalam pelukan Mama, Eda masih bisa merasa tenang
di antara cemasnya. Namun, semalam berbeda. Eda hanya sendirian
menanggung cemas dan dia pun dirundung trauma. Eda takut
kejadian itu terulang lagi. Kala itu, ketika dia tiba di rumah sakit,
ayah dan adiknya telah tiada. Eda sungguh takut kali ini dia juga
akan kehilangan Mama.
“Mama jangan kecapekan lagi ...,” bisik Eda lirih. “Kalo Mama
juga pergi, nanti aku sama siapa?”
Air mata Eda meleleh. Buru-buru dia menyekanya. Dia harus
terlihat tegar, kalau tidak, nanti Mama akan semakin cemas dan
Eda malah menjadi beban baginya. Eda menghela napas. Tak
terbayangkan baginya bagaimana menjadi Dipa yang tak punya
orang tua.
Dipa hebat, masih bisa tertawa, masih rajin sekolah, dan masih
punya semangat. Jika Eda bernasib sepertinya, Eda tak tahu apakah
dia masih punya keinginan untuk melakukan apa pun. Lama Eda
menunggu hingga kembali mendapat balasan dari Dipa.
Dipa: Sori, Da. handphone gue disita Pak Sutan tadi. Gue ketahuan
mainan handphone pas pelajarannya. Gue dihukum pula. Disuruh
analisis puisi “Pembaringan’. Semoga atas kekejaman beliau,
Pak Sutan diampuni oleh Yang Maha Kuasa dan diperhambat
pertumbuhan kumisnya. Amin.
Membaca pesan Dipa membuat Eda mau tak mau tersenyum
geli menahan tawa.
oo
Dipa: Nyokap lo kenapa? Semoga cepet sembuh, ya. Jadi gini rencana
gue, kita beli lagi Kopi Cap Badak yang baru, lalu kita nyelinap ke
sekolah malam-malam, kan, nggak ada orang. Kita bisa dengan
leluasa mendongkrak pintu ruangan Pak Budi dan menukar tutup
stoples. Dengan begitu, Pak Budi nggak tahu kalo kita ngambil
tutup stoples itu dan kita tetap dapat uangnya.
“Hmmm...” Eda mengelus dagunya. “Pintar juga Dipa ini,”
gumamnya pelan.
Eda: Ide lo bagus, Dip, gue setuju. Tapi, besok siang setelah pulang
sekolah gue baru bisa beli kopinya. Nggak apa-apa, ya?
Dipa: Nggak usah, Da. Kan, lo lagi jagain nyokap lo, biar gue aja yang
beli nanti.
Eda tersenyum kecil. Entah mengapa dia sedikit tersentuh
membaca pesan Dipa.
Eda: Oke. Jadi besok malam, ya, kita ngejalanin aksinya?
Dipa: Tunggu sampe nyokap lo sembuh aja, Da. Nggak apa-apa.
Eda: Besok aja, Dip. Gue butuh uangnya. Lagi pula, kalo udah malem,
jam besuk udah selesai. Gue nggak boleh nungguin Nyokap lagi.
Semalam cuma pengecualian aja.
Dipa: Oke. Besok lo sekolah?
Eda: Besok gue masih izin.
Dipa: Kalo gitu, kita ketemu di depan minimarket dekat sekolah aja, ya,
jam sembilan? Nanti gue jemput lo di situ. Jangan jalan sendirian
malam-malam.
Eda: Oke. Sampai besok, Dip.
Dipa membalas kembali dengan emoticon jempol. Eda jadi
kembali bersemangat setelah mendengar rencana Dipa. Ya, rencana
kali ini pasti berhasil! Untuk mempersiapkan diri, Eda sampai
menonton video-video di YouTube bagaimana cara membuka
pintu yang terkunci dengan jepit rambut. Bahkan, Eda mencoba
mempraktikkannya di toilet rumah sakit!
Yang dilakukannya adalah tindak kriminal bukan, sih? Iyalah!
kata hati kecilnya. Lo nyelinap masuk ruangan yang dikunci. Tahu,
nggak, kenapa ruangan itu dikunci? Berarti orang yang nggak berhak
nggak boleh masuk, dan lo nggak berhak! Kalo ketahuan, lo bisa
dikeluarin dari sekolah. Apa nggak jadi runyam?!
Eda menelan ludah. Tapi lo melakukannya bukan karena niat
buruk, Da. Lo cuma mau mengklaim apa yang menjadi hak lo. Kan, lo
yang menemukan stoples kopi keberuntungan itu. Lagi pula uangnya
mau lo pakai bukan untuk hal-hal maksiat, hal-hal berdosa. Niat lo baik,
kok! Sisi lain hati Eda berargumen.
“Alamak!” Eda memijat keningnya.
Sekali ini aja, deh. Sekali ini aja gue bertindak kriminal. Mungkin
kalau bareng Dipa, dosanya jadi kebagi dua.
Eda menatap wajah mamanya dengan sendu. Dia memejamkan
matanya sejenak. Maafin aku, ya, Pa? Setelah ini aku janji jadi anak
baik. Aku cuma nggak mau nyusahin Mama.
68
CHAPTER 12:
Rahasia Dipa
"Every single person has a story
that will break your heart."
—Brené Brown
« p=, Da, sini!”
Eda terperanjat ketika melihat ada sosok putih yang
menghampirinya dan berbisik. Dia hampir saja berteriak kalau saja
tak menyadari bahwa itu adalah Dipa!
“Ini gue, Da. Lo ngapain, sih, kaget gitu?” Dipa mendengkus.
Eda menghela napas lega. “Lo, kok, pake baju kayak pocong gitu,
sih?!”
“Idih, amit-amit! Apanya yang kayak pocong, sih? Ini jaket biasa,
tahu.”
“Warnanya putih, plus hoodie-nya yang makin bikin kayak
pocong!” gerutu Eda.
Dipa terkekeh. “Iya juga, ya. Tenang aja. Untung bukan malam
Jumat Kliwon.”
Eda mendengkus. Tawa Dipa menjadi-jadi.
“Kenapa, Da? Lo takut, ya? Kata orang, sekolah kita banyak
hantunya, lho.”
“Nggak, gue nggak takut,” sergah Eda. “Udah siap, kan?”
“Beres. Ini tutup stoplesnya.” Dipa mengeluarkan tutup
berwarna hijau dari tasnya. “Gue juga udah latihan cara buka pintu
pake peniti dan jepit rambut. Bahkan, gue sampe bawa peniti, jarum,
dan jepit rambut, nih. Kalau-kalau lo lupa atau ketinggalan.”
“Lo bawa jepit rambut? Di rumah suka jepit-jepitan, ya?”
“Enak aja. Gue minta dari salah satu adik gue di panti.” Dipa
buru-buru menyangkal.
Eda cekikikan.
“Da, jangan cekikikan gitu. Gue takut nggak bisa bedain antara
lo sama Mbak Kunti.”
Eda sengaja. Dia malah cekikikan semakin keras.
“Eda ....”
“Hahahaha! Kenapa, sih, Dip? Ternyata lo, ya, yang penakut?”
Dipa hanya bungkam. Eda mencolek lengan Dipa. “Takut, Dip?
Beneran takut?”
Dipa mendecak. “Udah, jangan colek-colek. Genit banget, sih,
lo.”
“Najis!” Eda segera menarik tangannya menjauh dari Dipa.
“Emangnya lo sama sekali nggak takut, Da?” celetuk Dipa.
“Nggak,” sahut Eda. “Ngapain takut?”
‘Ya ... siapa tahu ada yang diganggu atau apa.”
10
“Nggak bakal ada yang berani ganggu gue.” Eda tersenyum tipis.
“Bokap dan adik gue nanti kasih tahu mereka supaya gue nggak
digangguin. Bokap dan adik gue akan ngejagain gue.”
“Maksud lo? Bokap sama adik lo dukun gitu?”
“Bukan. Maksudnya, mereka juga udah meninggal.”
Dipa terkesiap. “Sori, Da. Gue nggak tahu. Sori kalau gue salah
ngomong,” ucapnya.
“Nggak apa-apa. Lo nggak salah ngomong, kok,” balas Eda. “Lo
juga nggak semestinya takut lagi, Dip. Kedua orang tua lo pasti
jagain lo dari sana.”
Dipa hanya diam saja.
“Lo nggak percaya?” Eda menatap Dipa.
“Bukan begitu ...,” gumam Dipa.
Dipa tak tahu harus percaya atau tidak. Dia hanya mempercepat
langkahnya supaya mereka bisa menyelesaikan rencana mereka
sebelum malam semakin larut.
Gedung sekolah di malam hari memang terlihat begitu
mencekam. Koridor terlihat kosong dalam kegelapan. Kaca-kaca
ruang kelas juga tak memantulkan cahaya apa pun. Dipa menelan
ludah. Dia menggosokkan kedua telapak tangannya.
“Tunggu, Da!” Dipa mengejar Eda yang terlebih dahulu berusaha
memanjat pagar sekolah.
“Hup!” Eda dengan sukses turun di balik pagar sementara Dipa
masih kesulitan. “Dip, bisa, nggak?”
Dipa malu bukan main karena jatuh tersungkur saat turun dari
pagar. Dilihatnya Eda tertawa. Masa dia kalah oleh Eda?!
“Bangun, Dip.” Eda mengulurkan tangannya untuk membantu
Dipa berdiri. Dipa menyambutnya. Tangan Eda hangat. Jantung
Dipa berdebar seketika. Setelah berdiri, Dipa buru-buru melepaskan
tangannya dari genggaman Eda. Eda menyadari, Dipa sepertinya
canggung ketika menyentuh tangan Eda. Keduanya jadi salah
tingkah. Mereka diam sepanjang jalan menuju Ruang Kepala
Sekolah.
Eda menarik napas dalam-dalam ketika mereka sudah ada di
depan pintu. “So, this is it.”
Dipa mengangguk. “Inget, ya, Da, pokoknya hadiah dibagi dua.
Sesuai kesepakatan.”
“Iya”
“Salaman dulu?”
“Oke.”
Darah Dipa kembali berdesir saat berjabat tangan dengan Eda.
Eda tampak menyadari hal itu sebab Eda segera menarik tangannya
kembali. Eda melepas jepit rambut dari kepalanya.
“Lo atau gue?”
“Gue aja.” Dipa mengambil jepit rambut itu dari tangan Eda. “Lo
senterin, ya.”
Eda mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya. Belum sempat
menyalakan senter, Eda mengernyit. “Eh, sebentar, Dip.”
“Kenapa?” Dipa mendadak panik. Dikiranya Eda melihat sosok
lain.
“Nggak. Gue cuma penasaran aja. Sebenernya lo butuh uang itu
untuk apa, sih?” tanya Eda.
Dipa mendengkus sambil mengelus dadanya. “Gue kira ada
apaan. Lo ngagetin aja, deh!”
“Gue pengin tahu aja,” ujar Eda. “Lima puluh juta itu, kan,
banyak.”
“Nah, lo sendiri, buat apa butuh uang sebanyak itu? Jangan-
jangan lo anak geng, ya?”
“Enak aja. Kalo gue, jujur gue butuh banget uang itu untuk biaya
masuk kuliah, Dip,” ujar Eda. “Sejak Papa meninggal, Mama harus
kerja keras ekstra untuk biaya kuliah gue nanti, Dip. Gue nggak tega
aja. Terlebih, Mama sampe jatuh sakit kemarin ini. Gue lebih butuh
biaya lagi.”
Dipa terperangah. Dari semua alasan yang diduganya, Dipa tak
pernah mengira itulah mengapa Eda sangat menginginkan uang
hadiah undian tersebut.
Eda tersenyum kecil sambil menatap Dipa. “Ya, itulah alasan
gue. Supaya lo tahu aja, kenapa gue mati-matian berusaha dapetin
uang itu. Kenapa juga gue jualan catatan. Gue tahu yang gue lakukan
salah, tapi semoga suatu hari gue bisa dimaafin. Sebab, gue nggak
berniat jahat.”
Eda menyalakan senter dan mengarahkannya ke pintu ruangan
Pak Budi. Tiba-tiba saja Dipa perlahan menurunkan tangan Eda.
“Da, pokoknya malam ini kita harus berhasil, ya?”
Eda mengangguk.
“Lo tahu, nggak, gue pernah baca quote yang bagus banget, deh.
Every single person has a story that will break your heart. Ternyata itu
bener.”
Eda mengangguk lagi.
“Lo udah membagi cerita lo ke gue. Sekarang lo juga berhak tahu
kenapa gue pengin banget uang itu. Tapi, dibandingkan dengan
alasan lo, gue yakin alasan gue pasti terdengar lebih bodoh.....” Dipa
tersenyum getir.
“Nggak ada masalah yang lebih bodoh daripada yang lainnya,
Dip,” sahut Eda. “Semua orang punya bebannya sendiri-sendiri.”
Dipa termangu.
“Jadi, kenapa lo mati-matian nyari uang? Sampe harus nyewain
atribut sekolah segala. Untuk kuliah juga?”
“Bukan.” Dipa menelan ludah. “Gue butuh pengacara.”
ve)
Eda mengernyit. “Pengacara? Pengacara dalam arti profesi
hukum?”
Dipa mengangguk. “Iyalah. Masa pengangguran banyak acara?”
“Tapi, buat apa, Dip?”
CAP BADAK
gen
CHAPTER 13:
Pahfawan
Dadatan
Di balik kegagalan, ada hikmah tersembunyi
yang bisa menyunggingkan senyum.
Carilah.
ipa menggigit bibir. Dia merasa alasannya begitu konyol jika
dibandingkan dengan Eda. Namun, dia melihat Eda begitu
penasaran menunggu jawabannya.
“Se-sebenernya ... buat nyokap—”
BRAK!
“Aduh!”
Belum sempat Dipa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba dia
terpelanting karena pintu ruangan Pak Budi mendadak membuka!
Wajah Eda langsung berubah pucat dan mulutnya menganga
manakala dia melihat sosok bertopeng hitam lewat sekilas di
hadapan mereka.
“MA ....” Eda hendak berteriak “maling”, tetapi tiba-tiba saja
otaknya seolah korsleting. Dia memastikan dahulu bahwa sosok
yang kini tengah berlari itu nyata dan kakinya menapak tanah. “...
ling. MALING!”
Refleks, Eda langsung mengejarnya. Maling yang panik karena
dikejar Eda sontak mengeluarkan pisau dari saku dan mengayun-
ayunkannya sambil berlari.
“Aduduh ... Mas, santai, Mas!” Eda segera menghentikan
langkahnya.
“Eda!”
Dipa berlari menyusul Eda. Dipa menatap pemandangan di
hadapannya dengan ngeri. Maling tersebut masih mengayun-
ayunkan pisaunya ke arah Eda dan Dipa, mengancam mereka untuk
mundur.
“Mas, Mas, kalo boleh tahu, barusan apa yang Mas curi, ya?”
celetuk Dipa.
“Grrrl! Pergi lo!” teriak si Maling, mengayunkan pisaunya lebih
ganas lagi.
“Oh, iya, iya. Maaf, Mas, maaf. Maaf,’ ucap Eda buru-buru.
Perlahan-lahan Eda mundur. Dia menarik tangan Dipa untuk juga
pergi dari hadapan si Maling.
“Mas nggak nyolong kopi, kan?” Dipa masih saja tanpa takut
melontarkan pertanyaan kepada si Maling.
Maling itu terlihat bingung dengan pertanyaan Dipa. Ayunan
pisaunya melambat.
“Mas, Mas tadi nggak ngambil kopi, kan, dari ruangan?” Dipa
mengulang pertanyaannya. Eda meringis. Mau apa, sih, Dipa ini?!
Lagi genting masih bisa-bisanya menanyakan perihal stoples kopi!
“Kopi apaan?!” bentak si Maling dengan suara lantang.
“Kopi, Mas. Kopi buat minum,” sahut Dipa. “Sebab, kalo Mas
ngambil kopi itu, saya NGGAK AKAN KASIH AMPUN! HIYAAA!!!”
Klontang!
“WAAA"”
“KYAAA!”
Baik Eda maupun si Maling sama-sama memekik ketika tiba-
tiba saja Dipa melompat dan memiting si Maling ke lantai! Eda
terkesiap dan menutup mulutnya. Dia terkejut bukan main dengan
pemandangan yang disuguhkan ke hadapannya. Napas Eda seakan
terhenti dan jantungnya berdegup cepat.
“Ambil pisaunya di lantai, Da! Buruan!” teriak Dipa.
Eda cepat-cepat berlutut dan meraba-raba lantai. Ini dial
Tangannya memegang lempengan besi dingin. Eda buru-buru
memungutnya dan memegangnya erat-erat.
“Telepon polisi, Da! Cepetan!” perintah Dipa.
Masih dengan tangan gemetar, Eda merogoh saku celananya
dan mengeluarkan ponsel. Polisi. Polisi nomornya berapa?
“Polisi nomornya berapa, Dip?” cicit Eda.
“Aduh, Edaaaa ... makanya nonton beritaaa!” gerutu Dipa. “110!”
“Aaaaaauwww .... Mas, ampun, Mas. Sakit tangannyal” jerit si
Maling.
“Pake 021, nggak?” tanya Eda.
“Nggak! Buruan!”
“Oke, oke.”
“Aaaaaauuuwww! Ampun, Mas!”
“Ampun, ampun ... diem lo!” bentak Dipa kepada si Maling. Dia
mempererat cengkeramannya pada kedua tangan si Maling.
“Halo ... Pak Polisi? Saya Dwenda, murid sekolah SMA Harapan.
‘Ada maling di sekolah, Pak. Sekarang sedang diamankan seorang
diri oleh teman saya. Tolong segera datang, Pak.”
“Aduh, Mas ... ampun, Mas!”
“Kenapa, Pak? Oh, nggak. Itu malingnya yang jerit-jerit. Nggak
ada korban. Tapi, tolong datang secepatnya, ya, Pak. Nggak tahu
sampe kapan temen saya bisa bertahan. Maling ini juga bawa pisau.
Tapi, pisaunya udah kami ambil. Iya. Makasih, Pak.”
“Diem, dong! Jangan gerak-gerak!” Dipa kembali membentak si
Maling. Kemudian, Dipa menatap Eda. “Udah?”
“Udah. Polisinya lagi dateng ke sini,” jawab Eda. “Gue bisa bantu
apa, nih?”
“Lo dudukin aja, tuh, pergelangan kakinya, biar Mas Maling
nggak bisa kabur sama sekali.” Dipa menuding kaki si Maling.
“Aduuuh ... ampun, Mas!”
Dipa mendecak. “Jangan berisik, deh. Mas nggak takut nanti
ngeganggu penunggu-penunggu sekolah ini?!”
Si Maling langsung terdiam. Si Maling sekali lagi memekik saat
Eda menduduki kedua kakinya. Tiba-tiba Eda meringis.
“Kenapa, Da?” tanya Dipa.
“Tangan gue perih, deh. Kenapa, ya?” Eda mengeluarkan ponsel
dari saku celananya dan menyinari telapak tangannya. “Ternyata
kegores, Dip. Kayaknya tadi pas ngambil pisau, karena nggak
kelihatan jadi kegores.”
“Ya ampun ... sakit?”
“Ya, perih-perih dikit. Nggak apa-apa.”
“Yakin?”
“ya”
Untungnya tak butuh waktu lama hingga polisi datang sebab
baik Dipa maupun Eda sudah pegal menahan si Maling agar tidak
kabur. Begitu melihat Pak Polisi, Eda segera melompat bangun. Dia
juga langsung menyerahkan pisau si Maling.
“Kalian memang anak-anak yang berani. Tapi, lain kali jangan
begitu lagi. Tindakan kalian itu sangat berbahaya. Apalagi, maling
itu punya senjata,” ucap Pak Polisi.
“Iya, Pak.”
“Ngomong-ngomong, ngapain kalian malam-malam disekolah?”
Deg! Jantung Eda seolah berhenti mendadak.
“Adu nyali, Pak.”
Untungnya Dipa dengan sigap menjawab, meskipun jawabannya
terdengar absurd dan asal. Pak Polisi menaikkan alisnya.
“Adu nyali? Aduh, ada-ada aja kalian ini. Ayo, saya antar pulang”
“Nggak usah, Pak. Rumah kami dekat,” sergah Eda. “Kami
pulang sendiri aja.”
“Langsung pulang, ya? Jangan pacaran!”
“Iya, Pak. Terima kasih”
Sementara itu, polisi masih berkeliaran di lingkungan sekolah,
Dipa dan Eda sudah melangkah keluar dari gerbang. Keduanya
menghela napas berat. Rasanya lelah bukan main. Dipa melihat jam
menunjukkan hampir pukul setengah 11.00 malam.
“Lo pulang naik apa, Da?” tanya Dipa.
"Jam segini udah nggak ada angkot. Naik bajaj aja, deh.” Eda
menjawab.
“Gue anterin.”
Mata Eda melebar. “Emangnya lo searah sama gue?”
“Nggak apa-apa. Gue anterin aja. Udah malem.”
“Nggak usah. Gue sendiri aja.”
“Udah malem, Da. Jangan sendirian.”
Dipa benar, hari memang sudah malam. Eda sendiri sejujurnya
agak takut pulang sendirian. Maka, akhirnya Eda mengangguk.
Sepanjang perjalanan dari sekolah menuju rumahnya, Eda salah
tingkah dengan keberadaan Dipa. Mereka hanya diam. Untung
rumah Eda dekat dari sekolah.
“Makasih, ya, Dip. Udah dianterin,” ucap Eda, saat bajaj yang
mereka tumpangi berhenti persis di depan rumah Eda.
“Sama-sama, Da.”
“Tya. Lo juga.”
“Nggg ... oh ya, tangan lo gimana?”
“Nggak apa-apa, kok. Darahnya udah kering”
“Coba lihat.”
Dipa mengulurkan telapak tangannya yang membuka,
menunggu hingga Eda meletakkan tangan di atasnya. Mendadak
jantung Eda berdebar kencang dan cepat. Eda menelan ludah.
Perlahan-lahan dia mengulurkan tangan dan diletakkannya di atas
telapak tangan Dipa. Jantung Eda makin berdebar tidak karuan saat
Dipa meraih dan menggenggam tangannya. Dipa memeriksa luka di
tangan Eda.
“Hmmm ... kayaknya, sih, lukanya nggak dalam. Tapi, nanti
bersihin pakai alkohol, ya. Takutnya infeksi. Kita, kan, nggak tahu
pisaunya berkarat atau nggak,” kata Dipa.
“ya,” gumam Eda.
“Ya udah. Met malam, Da.”
“Met malam, Dip”
Dipa kembali menaiki bajaj untuk pulang ke panti. Ketika Dipa
sudah duduk, tiba-tiba Eda memanggilnya.
“Dipal”
“lya?”
“Hati-hati di jalan, ya.”
Dipa mengangguk dan tersenyum. Eda berdiri di depan pintu,
menunggu Dipa dan bajajnya hingga tak terlihat lagi. Eda menarik
napas dalam-dalam. Dia masuk ke dalam rumah dan mengunci
pintu. Senyumnya perlahan mengembang.
80
CAP BADAK
gen
CHAPTER 14:
Ternyala Jo ...
"Mungkinkah kau pun juga begitu?
Kutahu kau masih malu.”
—Maliq © d'Essentials - "Terdiam"
She di panti, Dipa segera berganti baju dan naik ke ranjang.
Rasanya lelah sekali, tetapi Dipa tak bisa berhenti tersenyum
sejak tadi. Kenapa, ya? Padahal, rencana mereka untuk mendapatkan
kembali stoples kopi keberuntungan lagi-lagi gagal. Entahlah.
Mungkin karena dia bangga sudah berani dan berhasil menangkap
maling. Mungkin juga karena Instagram Story-nya lagi-lagi dilihat
oleh Laras Sjahrir.
Saat dalam perjalanan pulang dari rumah Eda tadi, Dipa iseng
mengunggah video dirinya naik bajaj. Dipa menyoroti pinggir jalan
yang terang benderang oleh pedagang makanan kaki lima, lalu
menyoroti wajahnya sendiri sambil mengacungkan jempol. Seperti
biasa, Instagram Story itu menuai banyak respons.
“Lagi di mana, Dip?”
“Lo naik bajaj, ya, Dip?”
“Nongkrong weekend, Dip? Sama siapa?”
Video Instagram Story yang menunjukkan sepuluh detik Dipa
mengendarai bajaj dalam kualitas buruk tersebut tak luput dari
lirikan Laras Sjahrir. Ini Instagram Story ketiganya yang dilihat oleh
Laras. Itu sebabnya Dipa pergi tidur dengan perasaan senang bukan
main.
Atau ... bisa jadi juga kegembiraannya yang meluap-luap adalah
karena tadi dia beberapa kali memegang tangan Eda. Dipa meraih
ponselnya di meja sebelah ranjang. Jam menunjukkan pukul 11.30
malam. Untung besok libur. Saat itu Dipa menyadari, ternyata ada
pesan masuk dari Eda sejak lima belas menit yang lalu.
Eda: Dip, udah nyampe rumah?
Senyum Dipa perlahan mengembang.
Dipa: Udah. Lo baik-baik aja, kan?
Eda: lya. Besok ngapain?
Deg ... deg ... deg. Napasnya menjadi cepat melihat pertanyaan
Eda. Besok ngapain? Eda ingin tahu kegiatan Dipa selain pergi ke
sekolah?
Dipa: Nggak ngapa-ngapain. Paling bantu jaga adik-adik di panti, bantu
bersih-bersih, sama paling bikin PR. Lo?
Eda: Sama. Nemenin Mama aja di rumah sakit. Pulangnya beres-beres
rumah.
82
Dipa menelan ludah. Tiba-tiba saja saat itu dia masih ingin terus
mengobrol dengan Eda walau hari sudah larut. Dipa segera memutar
otak. Dia berusaha mencari bahan pembicaraan, supaya Eda tidak
segera menutupnya dengan, “Ya udah, gue tidur, ya”. Kursor di layar
Dipa masih berkedip-kedip ketika muncul satu pesan baru dari Eda.
Eda: Lo ternyata anaknya beda dari yang gue kira, Dip. Sebelum kenal lo,
gue pikir lo anak nakal. Ada rumor kalau lo suka malak, padahal lo
“berdagang’ dengan nyewain atribut sekolah.
Dipa: Buset ... siapa yang nyebarin rumor kayak gitu? Boro-boro malak,
yang ada gue suka rugi karena diutangin. Kadang ada yang nggak
bayar utang pula.
Eda: Ya, anak-anak pada nyebarin rumor. Nggak tahu siapa tepatnya.
Oh, iya, ada lagi, gosipnya nilai lo hancur, padahal gue baru tahu,
ternyata lo masuk ranking lima besar terus di kelas.
Dipa: Hehehe ... lo udah berhasil stalk gue sampe mana, nih?
Eda: Ya, nggak gitu juga. Ge-er lo.
Dipa: Bercanda, deh, hehehe. Terus, lo denger apa lagi tentang gue?
Eda: Mmm ... yang gue denger lagi, lo hobinya nongkrong. Padahal, lo
hari Sabtu aja kerjanya ngejagain adik-adik lo dan ngurusin panti.
Tega banget, ya, yang ngegosipin lo?
Dipa tak kuasa lagi menahan senyumnya.
Dipa: Makanya, jangan percaya rumor, gosip, apalagi hoaks.
Eda: Barangkali orang-orang ngira lo bandel karena lo temenan sama
Dio, Dip. Dio, kan, reputasinya rada-rada hancur di sekolah. Kayak
mukanya. Hihihi ....
Dipa: Astaga... jahat banget lo, Da! :D.
Dipamenambahkan emoticon wajah tertawa di akhir kalimatnya.
Dia pun benar-benar tertawa saat membaca pesan Eda tadi.
83
Dipa: Bisa jadi, ya, orang mikir gue nakal karena gue temenan sama Dio.
Ya, dia emang nakal, sih. Tapi, masih wajar, kok. Gue nyambung
ngomong sama dia, tapi gue nggak suka aja ikutan gaya hidupnya.
Eda: Itu juga yang bikin lo beda dari anak-anak lain, Dip. Lo kayaknya
nggak gampang kebawa arus.
Dipa tertawa kecil. Eda sukses membuatnya kege-eran malam
itu.
Dipa: Ternyata lo juga beda, Da.
Eda: Bedanya apa, tun?
Dipa: Waktu tahu lo jualan catatan, gue pikir lo anak pinter berlagu
yang cuma mau malakin orang untuk uang jajan lebih. Gue nggak
pernah nyangka lo nyari uang untuk bantu nyokap lo. ;).
Lagi-lagi Dipa menyisipkan sebuah emoticon di penghujung
kalimatnya. Emoticon orang mengedipkan mata. Kali ini Dipa
sungguh-sungguh bermaksud mengirimkannya kepada Eda.
Eda: Berarti kita sama-sama beda dari yang lain, ya?
Dipa: lya. Dan, sama-sama udah berprasangka buruk juga terhadap satu
sama lain. Maaf ya, Da?
Eda: Maaf juga, Dip.
Dipa: Oh, ya, sayang, ya, rencana hari ini gagal lagi. Gue jadi merasa
bersalah sama lo sekarang.
Eda: Nggak apa-apa, santai aja. Bisa kita coba lagi minggu depan. Batas
ngeklaim hasil undiannya juga masih lama, kok.
Dipa: Bener juga. Kita bisa coba lagi minggu depan. Siapa tahu,
semingguan ini Pak Budi tiba-tiba jadi baik dan nyerahin hadiahnya
ke kita.
Eda: Wadub ... kalo itu terjadi kayaknya bisa hujan duit, tuh. Alias nggak
mungkin!
84
Dipa: Hahaha ... kalo hujan duit lebih bagus lagi, deh, gue tampung satu
gentong!
Eda: Ya, kali, Dip. Hehehe. Ya udah, gue tidur dulu, ya. Met malam.
Dipa: Oke, Da. Gue juga mau tidur. Eh, btw, udah diobatin luka di tangan
10?
Eda: Udah. Nggak berdarah lagi, kok.
Dipa: Bagus, deh. Kalo gitu, met malam, ya. Met istirahat.
Eda: Lo juga, Dip. ©.
Di ekor kalimat, Eda menggantungkan sebuah emoticon
tersenyum, sama seperti wajah Dipa saat membacanya. Dipa
meletakkan ponselnya kembali ke atas meja. Dia menatap langit-
langit. Dipa tidak tahu apakah dia masih bisa tidur malam ini
Jantaran begitu gembiranya.
Ah! Dipa teringat akan sesuatu. Dia kembali mengambil
ponselnya dan membuka aplikasi Instagram. Dipa membuat
Instagram Story yang baru. Di layar yang keseluruhannya hitam,
Dipa mengetik sebuah kalimat.
“Mungkinkah kau pun juga begitu? Kutahu kau masih malu.”
—Maliq & d’Essentials - “Terdiam”
85
CAP BADAK
230
CHAPTER 15:
Pembefaan
Dipa
ee
OS
“Beda dengan anak-anak, orang dewasa itu
entah kenapa bawaannya curigaan
dan nggak percayaan.”
He ini Mama sudah boleh kembali ke rumah. Tadinya Eda mau
bolos sehari lagi untuk menemani Mama pulang dari rumah
sakit, tapi Mama melarang. Itu sebabnya, pada pagi hari yang terik
ini Eda berdiri dengan malas bersama murid-murid yang lain.
“Lo tahu, nggak, Da, sejak kecil gue punya cita-cita,” bisik Hanum
yang berdiri di belakangnya, saat mereka sedang berdiri dalam posisi
istirahat. Pak Budi sedang berpidato, entah tentang apa.
“Apaan?” Eda balas berbisik.
“Gue punya cita-cita, suatu hari saat ada upacara bendera, tiba-
tiba turun hujan deras yang membuat kita semua bubar. Dua belas
tahun gue sekolah, Da, bahkan menjelang lulus SMA sekarang ini
pun cita-cita gue itu masih belum tercapai.”
Eda melongo mendengarnya. Kirain apaan!
“Itu, mah, namanya bukan cita-cital” desis Eda.
“... dan Dwenda dari kelas XII IPA 2.”
Eda tersentak. Sepertinya barusan namanya disebut oleh Pak
Budi. Ada apa lagi, nih?! Eda masih berdiri terpaku. Dia melihat
sosok Dipa tiba-tiba keluar dari barisan dan maju.
“Dwenda alias Eda, kamu hadir, nggak, hari ini?”
Ah! Benar. Itu namanya yang barusan dipanggil Pak Budi.
“Ha-hadir, Pak!” Eda mengangkat tangannya.
“Coba ke depan.”
Eda menelan ludah. Aduh, kenapa kali ini dia disuruh maju? Eda
melangkah dengan ragu. Diliriknya Dipa yang tersenyum sekilas saat
mata mereka bertemu. Kalau Dipa saja bisa tersenyum, mungkin tak
seharusnya Eda panik seperti ini.
“Jadi, saya dapat kabar bahwa hari Jumat malam sekolah kita
kemalingan,” ucap Pak Budi. “Maling itu berusaha membawa kabur
laptop dan sejumlah uang kas, tapi berhasil digagalkan oleh dua
anak pemberani ini, Dipa dan Eda.”
Eda mengerjapkan matanya. Dia seolah tak percaya baru saja
Pak Budi tersenyum kepadanya sambil bertepuk tangan. Guru-guru
dan murid-murid lain ikut bertepuk tangan.
“Untuk keberanian mereka, pihak sekolah akan memberikan
mereka hadiah,” lanjut Pak Budi.
Wajah Eda langsung menegang. Hadiah? Tutup stoples kopi
keberuntungankah?!
“Hadiah tersebut berupa piagam penghargaan dan voucher
makan di Space Burger.”
87
Eda langsung lemas seketika. Piagam penghargaan dan voucher
makan? Kirain tutup stoples!
“Baiklah, Dipa, Eda, silakan kembali ke barisan. Selesai upacara
langsung ke ruangan saya, ya.”
Dengan lunglai Eda menyeret langkahnya. Dipa sempat
diam-diam mengacungkan dua jempol kepada Eda, membuat Eda
tersenyum kecut. Setelah upacara, mereka membebaskan diri dari
barisan masing-masing dan bertemu di bawah ring basket.
“Gue kira Pak Budi mau ngasih tutup stoplesnya,” dumel Eda.
“Piagam penghargaan dan voucher makan not bad juga, kan?”
balas Dipa. “Toh, tutup stoples itu akan kita ambil Jumat ini.”
“Rencana kita harus lebih matang, Dip,” ucap Eda. “Termasuk di
dalamnya gimana caranya tetap nuker tutup stoples meskipun ada
maling kek, setan kek, apa kek.”
“Siap, Bos!” Dipa memberi hormat. Eda jadi geli sendiri.
“Eh, tangan lo udah nggak apa-apa?” tanya Dipa.
“Nggak. Nib.” Eda menunjukkannya kepada Dipa. Malu
mengakuinya, tapi Eda berharap Dipa meraih tangannya lagi seperti
malam itu. Namun, Dipa hanya mengangguk.
“Oh, iya. Udah kering, tuh, lukanya. Cepet, ya.”
“Mmm...” Eda menggumam, sedikit kecewa Dipa hanya sekilas
menatap tangannya.
Ketika sudah masuk ruangan Pak Budi, Dipa dan Eda duduk.
Mata mereka terpaku pada satu titik: rak di belakang kursi Pak Budi,
tempat stoples kopi keberuntungan itu bertengger.
“Kalian berdua sudah menangkap maling, kalian sungguh
berani. Saya atas nama pihak sekolah sangat berterima kasih kepada
kalian,” ujar Pak Budi dengan senyuman, sambil menyodorkan dua
buah amplop cokelat besar. “Ini piagam kalian beserta voucher di
dalamnya.”
88
“Terima kasih, Pak.”
“Ngomong-ngomong, setelah menangkap maling, kalian nggak
kepikiran mau jadi polisi?” tanya Pak Budi.
“Nggak, Pak,” jawab Dipa. “Saya sepertinya kurang memiliki
kualifikasi untuk jadi polisi. Nggak tahu kalau Eda.”
“Saya juga nggak, Pak,” timpal Eda.
Pak Budi mengangguk-angguk. “Tentu saja kalian nggak punya
kualifikasi untuk jadi polisi, mental kalian aja mental maling!”
Bulu kuduk Dipa dan Eda berdiri seketika saat melihat senyum.
Pak Budi terhapus dari wajahnya. Rasanya seperti saat menonton
film horor dan ketika suasana sedang tenang-tenangnya, tahu-tahu
setannya muncul!
“Ngaku, kalian berdua, ngapain hari Jumat malam-malam
berkeliaran di sekolah?!” bentak Pak Budi.
“A-adu nyali, Pak,” cicit Dipa, melontarkan kebohongan yang
sama seperti kepada Pak Polisi.
“Adu nyali? Yakin? Bukannya mau nyolong stoples ini?” Pak Budi
mengambil stoples kopi dan meletakkannya di hadapan mereka.
Dipa dan Eda terdiam. Terus terang, Eda tak suka dengan sikap
Pak Budi. Menurutnya, dari awal dia dan Dipa berhak atas hadiah
dari undian kopi tersebut. Lagi pula, tak seharusnya Pak Budi
menyebut mereka maling.
“Pak,” ucap Eda. “Tolong izinkan kami mengambil kembali
stoples kopi itu.”
“Tuh, benar, kan? Kalian mengendap-endap untuk ngambil
stoples ini?”
“Iya benar,” sahut Eda. “Karena kami merasa hak kami dirampas,
Pak!”
Dipa terkejut. Dia menatap Eda. Dipa tak menyangka Eda akan
berani bicara seperti itu. Dipa melihat kilatan marah di mata Eda.
84
Pak Budi sendiri pun sepertinya kaget dengan ucapan Eda. Pak Budi
menghela napas.
“Kamu butuh uang itu. Untuk apa?”
“Untuk saya kuliah, Pak.” Eda menjawab dengan nada tegas.
“Ayah saya meninggal belum setahun yang lalu. Ibu saya harus
setengah mati kerja keras membiayai saya. Saya cuma mau bantu
ibu saya!”
Dipa tak menyangka Eda akan seberani itu. Dia lebih
tak menyangka lagi, Eda yang selama ini diam saja akhirnya
mengutarakan alasan mengapa dia menginginkan uang tersebut.
Hening menaungi mereka bertiga untuk beberapa saat.
“Sejujurnya, saya nggak tahu apakah saya masih bisa percaya
dengan kalian, setelah kalian sudah melanggar peraturan sekolah,”
kata Pak Budi akhirnya, memecahkan keheningan. “Nakalnya kalian
itu bukan nakal biasa.”
Eda lemas mendengarnya. Dia cuma bisa menggigit bibir,
menahan air matanya agar tidak jatuh. Dipa menelan ludah.
“Kalau begitu kasih kami kesempatan, Pak, untuk melakukan
sesuatu. Kalau kami berhasil, kami berhak mendapatkan stoples itu
kembali,” ujar Dipa.
Pak Budi terdiam sejenak sambil mengelus dagunya. “Ya, nanti
saya pikirkan dan beri tahu kalian. Sekarang kalian kembali ke kelas
dulu.”
Dipa beranjak. Dia menepuk bahu Eda, memberi isyarat supaya
Eda juga berdiri.
“Permisi, Pak.” Dipa mengangguk. “Oh, ya. Bapak mau tahu
kenapa saya dan Eda dari awal nggak mau jujur sama Bapak, kenapa
kami butuh uang itu? Karena ini, Pak. Kami takut Bapak nggak
percaya begitu aja, meskipun kami jujur. Tapi, sebetulnya justru
saya kasihan dengan orang-orang dewasa. Beda dengan anak-anak,
40
orang dewasa itu entah kenapa bawaannya curiga terus dan tidak
mudah percaya. Semoga saat kami berdua tumbuh dewasa nanti,
kami nggak jadi orang dewasa seperti itu, seperti Bapak.”
Dipa meletakkan tangan di bahu Eda dan menggiringnya untuk
keluar ruangan Pak Budi, meninggalkan kepala sekolah mereka
sendirian dan termangu.
4l
CAP BADAK
230
CHAPTER 16:
Havi
Bersamanya
ee
OS
“Lo mau tahu supaya bisa terus semangat?
Selalu bersyukur dan berserah.”
Sauron Eda betul-betul sudah lupa kapan dia terakhir bahagia
seperti sekarang. Yang jelas, belum pernah ada hari saat dia
sebahagia ini semenjak Papa dan Dira meninggal. Pagi tadi, setelah
dari ruangan Pak Budi, entah apa yang merasuki Eda, tiba-tiba dia
merasa begitu putus asa.
“Ini nggak adil, Dip,” bisik Eda lirih. “Kenapa yang gue alami
semuanya nggak adil?”
Kemudian, tangis Eda pecah. Dia setengah mati menahan air
matanya. Dia tidak mau menangis di depan Dipa, tapi tidak bisa.
Eda berharap Dipa memarahinya saat itu, menghardiknya sambil
berkata, “Aduh! Cengeng amat, sih? Ya udahlah, berikutnya kita
usaha lagi.”
Akan tetapi, Dipa tidak memarahi Eda. Dipa malah merogoh
saku celananya dan mengusap pipi Eda dengan saputangan.
Harum. Eda jadi teringat ayahnya. Dahulu, ke mana-mana Papa
juga selalu membawa saputangan. Kalau mereka sedang berjalan
kaki dan melewati banyak kendaraan, Papa selalu menyodorkan
saputangannya kepada Eda.
“Pakai, Da. Tutup hidungnya.”
“Terus, Papa gimana?”
“Papa, mah, gampang. Hidung Papa banyak filternya. Hehehe.”
Bukannya berhenti, tangis Eda malah menjadi-jadi ketika
dihujani sorot mata lembut Dipa dan kata-kata yang menghibur.
“Nggak apa-apa, Da. Menangislah kalo itu bikin lo lega,” kata
Dipa. “Menangis itu wajar. Lo boleh menangis, asal jangan berputus
asa.’
3
Di sela isak tangisnya, Eda hanya bisa mengangguk. Dengan
sabar, Dipa menunggu hingga tangis Eda reda.
“Khusus hari ini, buat menghibur diri dan melepas penat gara-
gara Pak Budi, gue punya sesuatu buat lo.”
“Apa?”
Ternyata “sesuatu” yang diberikan Dipa itu adalah ajakan
untuk bolos dan pergi ke bioskop bersama. Awalnya Eda ragu, tapi
mengingat betapa kesalnya dia hari itu, Eda pun setuju. Eda dan
Dipa berhasil naik angkot menuju mal. Dipa memberikan jaketnya
untuk menyembunyikan seragam Eda. Sementara itu, Dipa sendiri
melepas seragamnya dan memakai kaus.
“Beneran, nih, Dip, lo traktir gue?” tanya Eda, saat Dipa
membayar dua tiket bioskop.
“Iya. Bang Faisal habis ngembaliin uang gue yang dikorupsi
sama dia.” Dipa cengar-cengir. “Lagian hari ini, kan, nomat—nonton
hemat. Kalo hari biasa, sih, bayar sendirilah, ya.”
Eda tertawa. “Makasih, ya, Dip”
Dipa mengangguk dan tersenyum. Selesai menonton, Dipa dan
Eda makan bersama menggunakan voucher yang diberikan Pak Budi
sebagai hadiah menangkap maling.
“Gue anter pulang, ya, Da?” celetuk Dipa, saat mereka selesai
makan dan mengobrol. “Ternyata rumah lo, tuh, searah sama panti.”
Eda tersenyum dan mengangguk. Kali ini dia tidak menolak lagi.
Walau hanya duduk di dalam angkot, dia senang bisa menghabiskan
lebih banyak waktu bersama Dipa.
“Tapi, Dip, mampir sebentar ke tukang bubur, ya? Mau beliin
buat Mama.”
Dipa mengiakan. Sepulang dari mal, Dipa menemani Eda
membeli bubur sebelum mengantarnya pulang. Ketika Eda sedang
menunggu pesanan bubur, Dipa izin pergi sejenak. Ternyata Dipa
44
pergi ke toko bunga. Eda tak memungkiri bahwa perasaannya
bercampur aduk saat itu. Mungkinkah Dipa membeli bunga
untuknya?
“Da...” panggil Dipa, ketika mereka berdua sedang berjalan kaki
menuju rumah Eda.
“Hmmm?”
“Gue tahu pertanyaan gue aneh, tapi, gimana, sih, rasanya
punya ibu?”
Eda terenyuh mendengar pertanyaan Dipa. Bagaimana rasanya?
Wajah Eda perlahan menyunggingkan senyum. “Rasanya bahagia,
Dip. Oh, ya, lo tahu, nggak, kalau Mama sebetulnya bukan ibu
kandung gue?”
“Oh, ya?” Dipa terkejut mendengarnya.
“Iya. Gue juga sempat hidup tanpa ibu. Ibu kandung gue
meninggal waktu umur gue dua tahun, jadi gue udah lupa. Lalu, gue
baru kenal Mama saat gue masuk SD. Gue dulu, lho, yang kenalan
sama Mama. Habis itu, baru, deh, Papa kenalan sama Mama.”
“Gimana caranya?”
“Gara-gara gue hilang di mal.” Eda tertawa. “Gue inget, orang-
orang cuma ngelihatin gue yang nangis di tengah-tengah mal.
Mungkin mereka takut itu modus penipuan, kali, ya? Pokoknya
hanya Mama yang berani deketin gue dan nolong gue. Gue inget,
saat itu Mama meluk gue supaya gue berhenti nangis. Rasanya
damai. Gue langsung suka.”
Dipa menangkap wajah Eda yang begitu cerah saat bercerita
tentang ibunya. Ada sedikit rasa sendu menyelip dalam relung hati
Dipa. Dia juga ingin memiliki sosok ibu seperti Eda memiliki ibunya.
Sejak kecil, Dipa sering kali bertanya-tanya, bagaimana rasanya, ya?
Kalau ibu tiri saja bisa menyayangi begitu dalamnya, apalagi ibu
kandung?
95
“Oke, deh, Dip. Makasih banyak, ya, untuk hari ini,” ucap Eda
saat mereka telah tiba di depan gerbang rumah Eda.
“Sama-sama, Da. Gue juga makasih sama lo,” balas Dipa.
“Oh, ya, lo buru-buru, nggak? Jam 7.00 udah harus di panti
lagi?”
“Mmm... kenapa emangnya?”
“Mau masuk sebentar? Gue kenalin sama Mama.”
“Boleh.”
Eda tak menyangka Dipa menyanggupi ajakannya. Anak-anak
seusia mereka biasanya segan jika diajak bertemu orang tua. Eda
lebih tak menyangka lagi ketika Dipa yang selesai memperkenalkan
diri kepada Mama tiba-tiba mengeluarkan sekuntum bunga peony
dari dalam tasnya.
“Maaf, Tante, saya nggak bisa lama-lama,” ucap Dipa. “Ini buat
Tante. Semoga cepat sembuh, ya.”
Bahkan, Mama pun terlihat takjub dibuat Dipa. “Makasih, ya,
Dipa. Hati-hati di jalan,” sahut Mama sambil tersenyum.
Eda mengantarkan Dipa hingga ke pintu gerbang. Tiba-tiba Eda
tertawa kecil.
“Kenapa ketawa-tawa, Da?” tanya Dipa heran.
“Nggak. Gue nggak nyangka aja lo beliin Mama bunga,” jawab
Eda.
“Bunga peony itu artinya semoga lekas sembuh. Semoga nyokap
lo cepet sembuth, ya, Da, biar lo nggak murung lagi.”
Eda tersenyum kecil. Dia pikir Dipa membeli bunga untuknya,
ternyata untuk Mama. Itu membuat Eda lebih senang lagi daripada
seandainya dia yang menerima bunga.
“Dadah, Dipa. Sampe besok, ya.”
“Sampe besok, Da.”
Dipa membalikkan badan dan melangkah dengan ringan.
Namun, baru melewati dua rumah, Dipa kembali.
40
“Eda!”
Eda yang baru hendak masuk rumah menoleh. “Ada apa, Dip?
‘Ada yang ketinggalan?”
“Iya,” balas Dipa. “Ketinggalan mau ngasih tahu lo sesuatu.”
Eda menaikkan alisnya. “Ngasih tahu apa, Dip?”
“Lo mau tahu supaya bisa terus semangat?”
“Apa, tuh?”
“Selalu bersyukur dan berserah.” Wajah Dipa yang dibayangi sinar
matahari terbenam tersenyum lebar. Hati Eda luluh mendengarnya.
Di mata Eda, Dipa yang ada di hadapannya sungguh berbeda dari
Dipa yang kali pertama dia kenal.
“Itu quote dari Instagram-nya Laras Sjahrir, by the way,” lanjut
Dipa.
Eda tertawa. “Pantesan bagus. Lo ngefan banget, ya, sama Laras
Sjahrir ini?”
Dipa masih tersenyum.
“Nanti gue nonton dia siaran, ah.”
“Ya, lo harus nonton.” Dipa mengangguk. “Oke, deh, Da. Tetap
semangat, ya! Jangan pernah putus asa.”
Seiring senja yang berlalu, sorot mata Eda menghantar Dipa
hingga tak kelihatan lagi. Saat itu Eda sadar bahwa dalam diri Dipa
yang dikiranya adalah musubh, ternyata Eda bisa menemukan banyak
kebahagiaan.
“Barely even friends, then somebody bends, unexpectedly.”
—“Beauty and the Beast”
41
CAP BADAK
7)
2830 CHAPTER 17:
OS Ji You
Ada banyak hal
yang memang lebih mudah diucapkan
ketimbang dilakukan.
«€ f\ as Dipa!”
M Dipa tersentak ketika Vito menepuk lengannya. Vito
menyodorkan remote TV kepada Dipa.
“Udah mulai dari tadi, tuh, beritanya. Mas Dipa, kok, bengong
aja, sih?” celetuk Vito.
Dipa mengerjapkan matanya. Di layar TV dia melihat Laras
Sjahrir tersenyum. Hari ini dia memakai terusan batik. Cantik sekali.
Bukan hanya cantik, Laras juga punya sorot mata yang cerdas, tetapi
lembut.
“Bersama saya, Laras Sjahrir, inilah News Highlight.”
Plop!
Dipa malah mematikan TV. Vito mengernyit heran. “Kok, malah
dimatiin, Mas?”
“Mas Dipa mau tidur,” gumam Dipa, beranjak dari tikar.
“Kan, baru jam 7.00, Mas!”
Dipa tak menyahut. Dia hanya terus berjalan dan masuk
kamarnya. Dia sedang tidak ingin menonton Laras Sjahrir hari ini.
Hati Dipa sedang terbagi menjadi dua perasaan. Dia sangat senang
bisa menghabiskan waktu bersama Eda dan berkenalan dengan
ibunya. Namun, di sisi lain, melihat keakraban Eda dengan ibunya,
Dipa jadi sedih.
Bersyukur dan berserah. Ada banyak hal yang memang lebih
mudah diucapkan ketimbang dilakukan. Dia memberi nasihat
kepada Eda untuk bersyukur dan berserah. Tapi, dia sendiri
terkadang masih belum bisa menerima, kenapa dia tidak dilahirkan
dalam keluarga yang hangat seperti kebanyakan teman-temannya?
Bzzzt!
Ponsel Dipa bergetar. Dia melihat nama Dio muncul di layarnya.
Dipa menjawabnya. “Halo?”
“Halo, Dip!” sapa Dio. “Lagi di mana lo?”
“Di rumah. Kenapa emangnya?”
“Kenapa? Ke mana aja lo seharian? Lo, tuh, jadi buronan di sekolah,
tahu, nggak?”
Dipa tersenyum kecut. “Dicarii
siapa gue?”
“Semualah! Pak Budi juga. Siap-siap aja besok pas dateng langsung
diciduk,” ucap Dio.
“Hmmm”
“Lo kenapa? Suaranya, kok, nggak semangat gitu?”
“Nggak apa-apa.”
“Mikirin duit, ya? Sori, deh, Dip. Gue usahain bayar, deh, lusa.
Beneran.”
49
Dipa tertawa kecil. “Nggak. Bukan karena itu. Gue cuma
mendadak galau aja. Lupakanlah.”
“Galau kenapa?”
“Jadi, tadi, kan, gue pergi sama Eda—”
“Tunggu, tunggu,” sela Dio. “Tadi pergi sama Eda? Jadi, Eda bolos
bareng lo?”
“Iya”
“Hah?! Sumpe lo?”
“Iya! Duh, dengerin gue dulu, dong”
“Tunggu, tunggu. Gue ambil pisang goreng dulu. Kayaknya bakal
seru, nih.”
Dipa memutar bola matanya. Dia mendengar suara ponsel
beradu dengan meja. Ternyata, Dio sungguhan pergi mengambil
pisang goreng!
“Halo?”
“Woi!” semprot Dipa. “Lo beneran ngambil pisang goreng dulu,
ya?”
“Iya. Lah, kan, tadi gue udah bilang.”
“Gila lo! Lo kira ini apaan? Acara gosip?!”
“Gimana, gimana? Lo bolos barengan Eda?!” Dio tak menghiraukan
protes Dipa. “Lo pacaran sama Eda sekarang?!”
“Nggak!” Dipa buru-buru menyangkal. Namun, dia merasakan
wajahnya memanas. Dipa berdeham. “Kita, tuh, lagi suntuk. Terus,
kan, dapet voucher makan dari Pak Budi. Ya udah, sekali-sekali cabut.
Anyway, pulang makan, gue nganter Eda ke rumahnya dan kenalan
sama nyokap dia.
“Gue lihat Eda deket banget, deh, sama nyokapnya. Nyokapnya,
tuh, sayang banget sama dia. Entah kenapa gue jadi galau
ngelihatnya, Yo.”
100
“Lo nge-date sama Eda, nganterin dia pulang, terus kenalan sama
nyokapnya?!” pekik Dio. “Kapan resepsi pernikahan kalian digelar, Dip?
Gue sumbang acara, deh.”
Dipa mendengkus. “Gila, kali, lo? Sumbang acara apaan lagi,
dah?! Topeng monyet? Lo yang pakai topengnya. Dio pergi ke pasar.
Dung dung tak dung dung. Huahahaha ....”
“Yeee ... serius gue! Lo sama Eda apa statusnya, sih? Kok, jadi deket
gitu tiba-tiba?”
Dekat? Dipa mengulum senyum. Kalau benar dia dan Eda
menjadi dekat ... Dipa tak keberatan.
“Ah, maleslah gue ngomong sama lo. Yang gue omongin apa,
yang lo sahutin apa.” Dipa pura-pura kesal. “Udah, ya? Daaah
“Eh, Dip, Dip! Tunggu, bercanda doang, kali, gue. Ya ampun,” ucap
Dio cepat-cepat. Terdengar suara Dio menghela napas. “Udah, jangan
galau. Mungkin gue nggak pernah bisa ngerti perasaan lo karena gue
nggak pernah ngalamin apa yang lo alamin.
“Tapi, lo harus tetap semangat, Dip. Selalu bersyukur. Walau lo
nggak punya orang tua, lo punya pengurus panti, saudara-saudara panti,
semuanya sayang dan ngerawat lo dari kecil. Lo nggak tidur di jalanan,
bisa makan cukup, bisa sekolah, tiap tahun dikirimin buku pelajaran,
dikasih handphone bagus ....”
Dipa termangu. “lya, sih, Yo.”
“Makanya. Nggak usah galau, lah! Oke?”
“Hmmm... iya. Eh, Yo, ada PR apa nggak?”
“Nggg ... nggak ada, sih.”
“Nggak ada, apa lo nggak tahu?”
“Nggg ... nggak tahu, sih. Hahaha... Yaelah, gue, kan, nggak pernah
nyimak di kelas. Ada PR juga gue biasanya nggak bikin. Hehehe.”
Dipa mendengkus.
101
“Ya udah, gue telepon cuma mau ngecek doang, apakah lo baik-baik
aja atau nggak,” ujar Dio. “Kaget gue pas lo tiba-tiba ngilang. Gue kira
udah jadi siluman kucing. Hihihi ....”
Dipa hanya mengumpat. Namun, saat selesai bercakap-
cakap dengan Dio di telepon, dia bisa tersenyum lagi. Karena Dio
mengasumsi tidak ada PR, Dipa pun bersantai.
Dipa sempat membuka aplikasi Instagram dan membuat
Instagram Story di akunnya. Isinya adalah foto langit dari jendela
kamarnya. Malam itu sebetulnya bulan bersinar terang andai kata
tak tertutup kabut polusi Kota Jakarta. Dipa menyertakan caption
lirik lagu Coldplay.
“Lights will guide you home and ignite your bones, and Iwill try...”
Dipa tersenyum kecil. Eda mungkin tak tahu, tapi lagu
itu untuknya. Dipa meletakkan ponselnya di atas meja dan
menghabiskan waktu dengan membaca sebelum terlelap.
Dipa tak tahu, tak lama setelahnya Laras Sjahrir juga membuat
Instagram Story berupa foto langit Kota Jakarta yang berkabut
dari kaca jendela mobilnya. Cahaya bulan susah payah berusaha
menyembul dari lapisan kabut tipis. Laras menyertai sebuah tulisan
di fotonya, “... to fix you.”
“Lights will guide you home and ignite your bones.
And I will try to fix you.”
—Coldplay - “Fix You”
102
CAP BADAK
gen
CHAPTER 18:
Rencana
Dadakan
“Manusia nggak pernah ada yang tahu,
akan ada kejutan apa dalam hidupnya.”
Eda: Dip, kata Bu Aam, sore ini ada rapat guru lagi. Istirahat pertama
bisa ketemu? Di belakang lab bahasa aja. Gue mau bahas rencana
nuker tutup stoples.
(¢ Daca dulu soalnya baik-baik. Jika tiga gram senyawa nonelektrolit
dalam dua ratus lima puluh gram air mempunyai penurunan
titik beku ....”
Konsentrasi Dipa yang sedang mencatat penjelasan soal Kimia
yang tengah dibahas Pak Ridho langsung buyar ketika cahaya layar
ponselnya berpendar. Dia melihat notifikasi pesan masuk dari Eda.
“... maka masa molekul relatif zat nonelektrolit tersebut ....”
Dipa_perlahan menundukkan kepalanya, _ pura-pura
berkonsentrasi pada tulisannya. Padahal, dia sedang membalas
pesan dari Eda.
Dipa: Oke.
Dipa menggigit bibir, menahan diri agar senyumnya tidak lepas.
Dipa tak lagi bisa membedakan apakah dia gembira karena Eda
mengiriminya pesan, atau karena mereka punya kesempatan lagi
untuk menukar tutup stoples. Atau, mungkin, karena dua-duanya.
Yang jelas, Dipa selalu membawa tutup stoples itu ke mana-mana
untuk berjaga-jaga.
“Pradipta Syailendra?”
“Mmm?” sahut Dipa. “Iya, Pak?”
“Kamu kenapa mukanya kayak gitu? Mau ke belakang?”
“Nggak, Pak.” Dipa meringis. “Muka saya kenapa emangnya?”
“Kayak nahan gejolak dalam perut.”
Seisi kelas tertawa. Pak Ridho memang mengajar pelajaran yang
sulit, tapi dia senang bercanda supaya suasana kelas tidak terlalu
kaku. Itu sebabnya, buat Dipa, Pak Ridho adalah salah satu guru
favoritnya.
“Ngomong-ngomong, mana teman kamu Dio?”
“Dio ... sakit katanya, Pak.”
“Sakit apa?”
“Sakit hati, katanya.”
Seisi kelas tertawa lagi. Pak Ridho cuma geleng-geleng kepala
sambil menahan senyum.
“Simpan itu handphone kamu. Jangan mainan handphone terus.
Saya ngedikte nanti kamu ketinggalan.”
104
Wajah Dipa memerah. Buru-buru dia menyimpan ponselnya
kembali ke dalam saku celana. Dipa tak sabar hingga jam istirahat
pertama tiba. Ketika bel berbunyi, Dipa cepat-cepat berjalan menuju
bagian belakang sekolah, di belakang lab bahasa.
Suatu hari, Dio pernah bertanya kepadanya. “Kenapa, sih, lab
bahasa letaknya di pojok gitu?”
“Nggak tahu. Biar kalo teriak-teriak nggak ngeganggu, kali,” jawab
Dipa asal. “Mereka, kan, harus latihan teriak-teriak AAAA UUUU itu,
lho.”
Dio menaikkan sebelah alisnya. “Itu, mah, teater, kali? Lagian
kayaknya nggak aaa uuuu kayak Tarzan begitu.”
Meskipun terlihat seperti dianaktirikan, tetapi keadaan lab bahasa
yang terasingkan justru menguntungkan menurut Dipa. Pasalnya, anak-
anak bahasa bisa nongkrong di belakang sekolah dengan leluasa tanpa
harus sempit-sempitan dengan anak-anak lain.
“Dipal”
Ketika Dipa tiba, Eda sudah ada di sana. Dipa suka bingung. Eda
gesit banget, sih? Tahu-tahu saja sudah tiba lebih dahulu.
“Cepet banget lo, Da? Terbang, ya?” celetuk Dipa.
“Nggak, gue menggelinding dari atas,” balas Eda, tak kalah asal.
Dipa tertawa. Mau tak mau Eda ikutan.
“Jadi gini, Dip. Tadi Bu Aam bilang sore nanti habis bubaran
sekolah bakal ada rapat guru sama Pak Budi. Nah, biasanya rapatnya,
kan, lama. Jadi, pas guru-guru pada rapat, kita bisa nyelinap ke
ruangan Pak Budi dan menukar tutup stoples,” kata Eda.
Dipa mengangguk-angguk. “Semestinya nggak butuh waktu
lama buat membobol ruangan Pak Budi dan nuker tutup stoples itu.
Oke, Da. Kita kerjakan aja rencana itu nanti sore.”
“Sip. Biar kita dijauhkan dari segala rintangan, gimana kalo kita
selametan dulu dengan makan siomay?” ajak Eda.
los
Tiba-tiba Dipa cengar-cengir jail. “Bilang aja pengin makan
berdua sama gue.”
Wajah Eda segera bersemu. Dia mendengkus, berusaha
menyembunyikan semburat merah di wajahnya.
“Gue juga pengin makan berdua sama lo, kok, Da.” Dipa
menambahkan. “Yuk.”
“Gue yang traktir, Dip.”
“Tya, gue tahu, kok, lo mau nraktir.”
Eda melongo. Dia kehabisan kata-kata untuk membalas Dipa,
tetapi kali ini dia tidak kesal. Justru Eda malah tertawa kecil. Murid-
murid lain sedang sibuk makan ketika Dipa dan Eda duduk di kantin
sehingga tak ada yang memperhatikan bahwa mereka sedang
berdua.
"Dip?
“Hmmm?”
“Boleh tanya, nggak?”
“Apa, Da?”
“Kehidupan di panti, tuh, kayak gimana, sih?” tanya Eda sambil
membelah siomaynya. “Boleh, nggak, kapan-kapan gue main ke
sana?”
“Bolehlah. Terbuka untuk umum, kok. Yang penting izin sama
pengurus panti,” jawab Dipa. “Nanti gue izinin. Kehidupan di panti
itu ... yang jelas rame, banyak anak-anak dari segala usia. Namanya
anak-anak, kadang berantem, kadang akur, mungkin sama seperti
sebuah keluarga, tapi bedanya banyak aja anak-anaknya.”
“Lo dari bayi di panti itu?”
Dipa mengangguk. “Tapi, rencananya habis lulus SMA ini gue
mau mandiri, Da. Jadi, nggak mau ngebebani panti lagi. Kalo bisa,
sih, gue malah bantu ngebiayain adik-adik gue di sana.”
“Lo ... pernah penasaran, nggak, sih, Dip, tentang orang tua lo?”
l0o
Dipa terdiam. Kunyahannya melamban. Dia menerawang jauh
sejenak. Eda dengan sabar menunggu jawaban Dipa, sambil was-was
kalau-kalau dia menyinggung Dipa.
“Pertanyaan gue salah, ya? Maaf, ya, Dip?”
“Nggak, nggak.” Dipa menggeleng. “Gue cuma bingung aja
gimana jawabnya. Penasaran, jelas. Tapi ... entahlah, Da. Gue nggak
tahu gimana ngejelasinnya sekarang.”
Eda mengangguk-angguk.
“Kalo lo? Hampir setahun bokap dan adik lo meninggal, lo udah
bisa ngerelain mereka?”
Eda menghela napas. “Ngerelain, sih, udah. Cuma, gue masih
suka bertanya-tanya kenapa musibah seperti itu menimpa keluarga
gue. Tapi, seperti yang lo bilang ke gue, Dip, hidup itu harus
bersyukur dan berserah.”
“Nah, harus lo akui omongan gue ternyata berfaedah juga, kan?”
Dipa menggoda Eda.
“Kapan gue bilang omongan lo nggak berfaedah?” Eda tertawa.
“Yaelah ... dia lupa. Pas kita lagi stres karena nggak tahu gimana
cara ngebobol ruangan Pak Budi, Da. Sewaktu lo diam-diam nyalain
alarm kebakaran.”
“Oh, iya!”
Dipa dan Eda larut lebih jauh lagi dalam tawa.
“Dip...”
“Tya?”
“Gue harap, sekalipun misi kita udah berhasil, sekalipun
kita udah dapet uang hasil undian itu, kita tetep temenan kayak
sekarang, ya?” ucap Eda.
“Pasti, Da.” Dipa meyakinkan. “Lucu, ya? Kita yang tadinya
musuhan karena punya tujuan yang sama, sekarang malah jadi
temenan.”
07
“Manusia nggak pernah ada yang tahu akan ada kejutan apa
dalam hidupnya, Dip.”
Dipa dan Eda menghabiskan sisa makanan mereka dalam
diam. Meskipun demikian, keduanya menikmati kesunyian di
antara mereka. Bukan lagi canggung yang mereka berdua rasakan,
melainkan damai.
“Two less lonely people in the world, and it’s gonna be fine ....”
—Air Supply - “Two Less Lonely People in the World”
108
CAP BADAK
gen
CHAPTER 19:
hepato
Berhasil memenangi hati lawan
adalah trofi yang paling membanggakan.
anusia memang tidak pernah tahu kejutan apa yang akan
datang dalam hidupnya. Baru saja Eda mengucapkan kalimat
itu kepada Dipa ketika jam istirahat, mereka berdua mengalaminya
sendiri pada sore hari.
Ketika bel bubar sekolah berbunyi, murid-murid langsung
berebutan untuk menghambur keluar kelas. Dipa yang memimpin
paling depan. Baru saja dia hendak melewati kusen pintu, langkah
Dipa tertahan lantaran ada yang menarik tasnya dari belakang.
“Tunggu, Dip!”
Dipa menoleh. Begitu melihat sosok yang menahan langkahnya,
Dipa langsung memutar bola matanya dan menghela napas.
“Apaan?!” bentak Dipa.
Aulia tersentak. Dia mengerjapkan matanya. Dipa sedikit
merasa bersalah karena sudah membentak Aulia, tetapi dia tidak
tahan lagi dengannya. Dipa tahu maksud Aulia. Ini sudah kali ketiga
dalam sehari Aulia menawarkannya.
“Dip, lo udah pikir-pikir lagi, belum? Mau, ya, ikut IKom?”
“NGGAKI” seru Dipa. “Udah, deh, jangan maksa-maksa gue
kayak bisnis MLM! Gue sibuk!”
“Tapi, Dip—”
Dipa mengabaikan Aulia. Dia bahkan menyeruak mendorong
beberapa temannya dan segera berlari menuruni tangga. Dipa
mempercepat langkahnya menuju bagian belakang lab bahasa,
tempat dia janjian dengan Eda. Eda belum muncul! Dipa tersenyum
puas ketika dia melihat Eda melangkah dari kejauhan.
“Nah!” Dipa mengagetkan Eda, membuat Eda_terlonjak.
“Alchirnya, gue duluan yang nyampe.”
Eda menggerutu. “Apa-apaan, sih?! Ngagetin aja!”
Dipa cengar-cengir. “Gue cepet-cepet lari-lari supaya nyampe
duluan dari lo, Da.”
Eda hanya memutar bola matanya. “Gimana? Udah siap?”
“Siap”
Dipa dan Eda menunggu sejenak, sekitar sepuluh-lima belas
menit, hingga sekolah mulai sepi. Kemudian, mereka mengendap-
endap menuju ruangan Pak Budi. Koridor saat itu terlihat kosong.
Mereka berdua memberi isyarat melalui anggukan di depan pintu,
kemudian Eda melepas jepit rambutnya.
JEGREK!
Eda sedang hati-hati berusaha memasukkan jepit rambutnya
ke lubang kunci pintu ruangan Pak Budi ketika pintu itu terbuka.
10
Saking kagetnya, tangan Eda sampai serasa tersetrum dan jepitan
itu terlepas. Dipa refleks menutup mulut untuk tidak berteriak.
“Kalian lagi.” Pak Budi menghela napas.
Dipa dan Eda yang jantungnya masih berdebar-debar karena
kaget segera menyiapkan diri untuk kembali dimarahi Pak Budi.
“Ngapain kalian di sini?” tanya Pak Budi dengan nada dingin.
“Nggg ... ehm.” Dipa berdeham, mengulur waktu untuk mencari
alasan. “Mau izin, Pak.”
“Tzin? Izin apa?”
“Izin ikut lomba Kom.”
Mulut Eda menganga mendengarnya. Izin ikut lomba Kom?!
Lomba yang dipromosikan ke mana-mana, tapi tidak ada yang mau
ikut itu?
“Oh ... lomba IKom yang pengetahuan umum itu, kan?” Raut
wajah Pak Budi mendadak melunak. “Disuruh siapa kamu?”
“Aulia,” cicit Dipa.
“Kalian berdua jadinya memutuskan untuk ikut?”
Dipa mengangguk. Eda yang masih tercengang tak mampu
berkata-kata.
“Bagus, bagus.” Pak Budi tersenyum. “Tentulah saya izinkan.
Ayo, masuk dulu.”
Eda mengerutkan keningnya. Matanya mendelik menatap Dipa,
meminta penjelasan. Dipa hanya mengangkat bahu.
“Pasti Aulia sudah menjelaskan, ya, perihal lombanya,” kata Pak
Budi. “Ya, saya izinkan kalian untuk ikut lomba itu. Minggu depan,
kan? Aulia nyaris mau mengundurkan diri. Saya bilang, Jangan,
Aulia. Bapak yakin pasti Aulia akan menemukan siswa atau siswi
yang berminat ikut’ Ternyata kalian. Saya senang sekali. Apalagi
kalian berdua termasuk pelajar yang cerdas.”
Dipa dan Eda hanya meringis.
tl
“Baiklah.” Pak Budi melihat jam tangannya. “Saya ada rapat
guru. Kalian persiapkan diri baik-baik, ya.”
“Iya, Pak.” Dengan lunglai Dipa dan Eda mengangguk.
“Oh, ya, semoga kalian menang, ya? Kalau kalian menang ...
hadiah undian itu saya serahkan buat kalian.”
Mata Dipa dan Eda memelotot. Nggak salah dengar?!
“Ya udah, keluar. Saya mau kunci pintunya.”
Selepas Pak Budi pergi, Dipa dan Eda yang masih tertegun saling
pandang.
“Tu ... nggak salah Pak Budi bilang apa?” celetuk Eda yang masih
terkejut.
“Kayaknya nggak,” sahut Dipa, tak kalah tercengang. Dipa
menjentikkan jari. “Kita harus cepetan cari Aulia sekarang!”
Dipa menarik tangan Eda, membuat Eda terkejut. Meskipun
demikian, Eda membiarkan tangannya dalam genggaman Dipa. Dia
tak berusaha melepaskannya. Dia hanya mengikuti langkah Dipa
hingga mereka tiba di perpustakaan.
“Aulia pasti di sini. Dia bilang, tiap pulang sekolah, dia belajar
sama Sultan buat persiapan lomba!” seru Dipa penuh semangat.
Eda hanya mengangguk. Jantung Eda masih berdetak tak karuan
setelah Dipa melepaskan genggaman tangannya. Dipa mendorong
pintu perpustakaan sepelan mungkin. Sebelum melangkah lebih
jauh, matanya menjelajah ke setiap sudut perpustakaan. Setelah dia
menemukan sosok Aulia, barulah Dipa melangkah.
“Pssst! Au!” panggil Dipa sambil berbisik.
Aulia yang tengah sibuk mencatat di meja bundar mengangkat
kepalanya. “Dipa?”
“Iya, ini gue.” Dipa perlahan menarik kursi dan mempersilakan
Eda duduk. Setelah itu barulah Dipa duduk di kursi sebelah Eda.
“Kenalin, ini Eda. Anak kelas IPA 2.”
Iz
“Hai,” sapa Eda.
“Halo.” Aulia menyapa balik. “Gue tahu, kok, Eda. Yang tukang
jualan catatan itu, kan?”
“Iya, dulu. Tapi, sekarang udah gulung tikar,” balas Eda.
“Bh, Eda. Lo mau, nggak, ikut—”
“Mau,” sela Dipa. “Mau, dia mau ikut IKom bareng gue. Kita
mesti ngapain?”
Mulut Aulia menganga. “Ini beneran?”
“Iya, beneran.”
“Apa yang membuat lo akhirnya insaf, Dip? Lo, kan, udah nolak
gue berkali-kali.”
“Bapak lo yang bikin gue insaf. Buruan, mesti ngapain kita?”
desak Dipa.
“Oh... nggak ngapa-ngapain. Pendaftaran biar gue yang urus. Lo
belajar aja tiap pulang sekolah. Banyak nonton berita. Banyak baca
koran. Mmm... apalagi, ya?”
“Oh, ya udah. Gampang. Kapan kompetisinya?”
“Minggu depan, hari Kamis. Hari itu kita diizinin bolos. Terus,
dapet makan siang juga di tempat lombanya.”
“Dipa.” Sultan, satu-satunya partner Aulia yang setia ikut
nimbrung. “Sama satu lagi, kalo menang, tuh, juara satu dapet lima
juta, juara dua dapet tiga juta, juara tiga dapet satu juta. Hadiahnya
kita bagi lima, Dip. Gue, Aulia, lo, Eda, sama sekolah.”
“Iya, iya.” Dipa hanya mengangguk-angguk. “Ya udah, ya? Kita
capcus dulu.”
“Eh ... lo nggak mau belajar bareng?”
“Nggak usah. Udah tahu. Yuk, Da.”
“Lho ... Dip? Apa maksudnya udah tahu? Pengetahuan umum
tuh luas, lho.”
13
Dipa tak menghiraukan Aulia. Melihat Dipa beranjak, Eda pun
mengekor. Setelah keluar dari perpustakaan, Dipa menarik napas
lega.
“Lo yakin nggak mau belajar bareng mereka, Dip?” Eda
menaikkan alisnya.
“Kita belajar sendiri aja, Da. Ngeri gue lama-lama sama Aulia.”
Dipa bergidik.
“Lho, ngeri kenapa?”
Dipa menggigit bibir. “Bilang, nggak, ya?”
“Ada apa, sih?”
“Kalo gue cerita, lo swear jangan cerita ke siapa-siapa, ya?”
“Iya. Kenapa, sih?”
“Aulia naksir gue dari SMP. Udah nembak gue lima kali. Kelima-
limanya gue tolak.”
“Haaah?!” Eda menutup mulut, menahan tawa.
“Ngeri gue sama dia. Agresif banget! Udah kayak maksa ikutan
sekte, tahu, nggak? Atau, maksa ikutan MLM gitu.”
Eda tak tahan lagi. Tawanya pecah. Dipa, Dipa. Ah ... entah sejak
kapan Dipa memang sudah memenangi hati Eda.
14
CAP BADAK
gen
CHAPTER 20:
hrileria Jo.
Gimana?
“Kriteria gue?
Yang penting manusia, deh!”
He itu sepulang sekolah Dipa dan Eda duduk bersama di kantin
yang sudah sepi. Pedagang-pedagang kantin sudah menutup
lapak mereka sebab sebagian besar murid-murid sudah pulang.
“Gue agak merasa bersalah, nih, sama Aulia dan Sultan.
Kesannya, kok, kita satu tim, tapi berlagu banget, nggak mau belajar
bareng mereka?”
Dipa mendecak mendengar ucapan Eda. “Aduh, jangan dipikirin,
deh, Da. Lo tega sama gue? Gue males, ah, sama Aulia.”
Eda ngakak.
“Jangan ngakak aja, Da. Nih, jawab pertanyaan gue. Berapa
jumlah tangan ayam?”
“Dua. Eh?! Haaaaaah?!”
Melihat wajah Eda yang kebingungan, gantian Dipa yang ngakak.
“tu, mah, ceker, keleeeeusss ...,” ucap Dipa di sela-sela tawanya.
“Jawabannya: ayam tidak punya tangan!”
“Pertanyaan apaan, sih? Aneh banget.”
“Ini, ada di kumpulan soal pengetahuan umum.”
“Yang serius, dong, Dip, pertanyaannya. Yang kayak gituan,
mah, nggak bakalan ditanya.”
“Oke, oke. Yang serius. Coba lo tanya gue. Ehm.”
Eda mulai melontarkan pertanyaan demi pertanyaan kepada
Dipa.
“Juara Piala Eropa 2016?”
“Portugal.”
“Theodore Roosevelt adalah presiden Amerika Serikat yang ke
“Nggg ... bentar. Dua puluh enam.”
“Pelat nomor kendaraan K berasal dari keresidenan ...?”
“Waduh! Pati?”
“ASEAN berdiri pada tanggal ..
“Delapan Agustus ... tahunnya ... 1967!”
“Hari Perdamaian Dunia diperingati setiap tanggal ...?”
“Setiap 21 September.”
“Pemenang kategori Best New Artist untuk Grammy Awards
tahun 2015 dimenangkan oleh ...?”
“Sam Smith!”
“Lagu ‘When I See You Smile’ tahun 1989 dinyanyikan oleh ...?”
“Bad English.”
“Wow.”
Eda mendecak kagum. Semua pertanyaan yang dilontarkannya
kepada Dipa berhasil dijawab tanpa kesalahan. Dipa betul-betul
memiliki wawasan yang luas.
lo
“Kok, bisa, sih, lo ngejawab semua dengan benar?” tanya Eda
heran
‘isa, dong. Gue, kan, selalu nonton berita. Hehehe.”
“Thanks to Laras Sjahrir idola lo itu, ya.”
Dipa hanya tersenyum tipis. Eda membuka tasnya dan
mengeluarkan kotak bekal. Dia juga mengeluarkan dua buah sendok
dan menyodorkan salah satunya kepada Dipa.
“Dimakan, Dip. Tadi pagi gue dibawain bekal sama Mama.”
Eda mendorong kotak bekalnya ke tengah, di antara dia dan Dipa.
“Mama sengaja bikin banyakan, katanya sekalian buat Dipa.”
Dipa menatap makanan di depannya. Walau sudah dingin, nasi
goreng sederhana yang ada di hadapannya itu terlihat menggoda.
Namun, lebih dari itu, Dipa juga tersentuh bahwa mama Eda
ternyata ingat dengannya.
“Makasih, Da. Bilang ke nyokap lo, makasih, ya,” ucap Dipa.
“Gimana keadaannya sekarang?”
7
“Udah baik, kok. Udah kembali kerja.” Eda mulai menyendok.
“Nyokap lo masih inget sama gue?”
“Inget, lah. Lo satu-satunya cowok yang pernah ke rumah.
Dateng bawa bunga pula buat nyokap gue.” Eda tertawa kecil.
Dipa tersenyum. Dia mengambil sesendok nasi goreng dan
dikunyahnya. Enak! Memang beda, deh, kalau koki sungguhan yang
masak. Nasi goreng sederhana pun rasanya bisa meledak-ledak di
mulut.
“Hmmm ... enak banget, nih!” Dipa mengangguk-angguk.
“Suka?”
“Suka banget! Gue bisa, nih, makan ini tiap hari.”
“Lebay!”
“Th, beneran.” Dipa menyendok sesuap lagi. “Ngomong-
ngomong ... tadi apa lo bilang? Gue satu-satunya cowok yang pernah
ke rumah lo?”
“lya.”
“Masa, sih? Gue nggak percaya, deh.” Dipa menaikkan sebelah
alisnya.
“Beneran.”
“Cewek kayak lo gini ... nggak pernah didatengin cowok ke
rumah???” Dipa menuding Eda dengan tangannya.
“Bmang cewek kayak gue, kenapa?”
Dipa tertegun dengan mulut penuh. Dia buru-buru
menunduk, pura-pura sibuk dengan nasi goreng bagiannya untuk
menyembunyikan wajah yang bersemu merah. Dipa cepat-cepat
mengunyah dan menelan.
“Nggak apa-apa. Berarti, lo nggak pernah punya pacar gitu?”
celetuk Dipa.
Eda hanya mengangguk-angguk. Gengsi banget untuk terang-
terangan mengaku! Pasti Dipa akan meledeknya culun lah, nggak
laku lah.
“Gue juga belum pernah pacaran,” ujar Dipa.
itt
Eda menatapnya dengan tidak percaya.
“Kenapa? Kok, heran gitu?”
“Lo? Mana mungkin lo belum pernah punya pacar?”
“Emangnya kenapa?”
Gantian Eda yang tertegun. Ya ... kalau Eda mendengar
percakapan menjijikkan antara teman-teman cewek di kelas, sih,
semestinya Dipa sudah punya pacar. Eda pernah mendengar ada
yang berkata, “Gue takut, ah, deket-deket Dipa. Takut meleleh. Soalnya
dia so hoooooottt ....” Rasanya Eda mau muntah mendengarnya,
meskipun harus dia akui memang benar juga.
“Makanya, Dip. Aulia lo tolak, sih.” Eda berusaha bercanda,
mencairkan suasana ketika mereka sudah mulai saling pandang.
Dipa mendengkus. Melihat ekspresi Dipa, tawa Eda pecah.
“Lo kenapa, sih, nolak Aulia?” tanya Eda. “Dia kan not bad, lah.
Anaknya nggak macem-macem, pinter pula.”
“Ya, bukan berarti gue mesti naksir, kan?” sahut Dipa. “Atau,
jangan-jangan, buat lo, semua cowok yang baik lo pacarin, lagi?”
“Enak aja!” Eda mencibir. “Tuh, aki-aki tukang sayur yang lewat
di depan rumah gue juga baik. Masa gue pacarin?”
Gantian Dipa yang tertawa. “Jadi, cowok yang bakal lo pacarin
adalah ...?”
“Yang memenuhi kriteria gue, lah.”
“Dan, yang memenuhi kriteria lo adalah ...?”
Eda membuang pandangan. Dari sudut mata dia tahu Dipa
menatapnya tak berkedip. Dipa menunggu jawaban Eda. Duh,
kenapa jadi grogi, sih? gerutu Eda dalam hati. Kriterianya? Apa, ya?
Standarlah! Seperti kriteria-kriteria yang diinginkan setiap cewek dari
seorang cowok. Baik, nggak suka bohong, sopan, nggak macam-macam
... gimana, sih, Dipa? Masa jawaban standar gini aja nggak tahu.
Yang tahu Eda lagi bete dan berusaha menghibur. Yang tahu Eda
sebetulnya takut pulang malam dan mau nganterin. Yang tahu orang
14
tuanya sakit dan berinisiatif jenguk. Yang nggak pernah berusaha
kelihatan keren, tapi diam-diam sebetulnya gentleman. Yang apa
adanya, seperti Dipa.
“Kriteria gue?” senyum Eda perlahan tersungging. Dipa
mengerjapkan matanya, semakin penasaran dengan jawaban Eda.
“Yang ... yang penting manusia, deh!”
Dipa memutar bola matanya. Eda hanya tertawa ringan.
“Ya udah, lanjut belajarnya sambil makan.” Dipa menyentuh
layar ponselnya yang sudah meredup.
“Kalo lo ... kriteria lo gimana, Dip?” tanya Eda takut-takut.
“Kriteria gue? Yang ... yang penting manusia juga, deh,” jawab
Dipa asal.
“Jangan ikut-ikutan!”
“Nggak ada kriteria-kriteriaan,” ucap Dipa.
“Yang kayak Aulia?”
“Da, kalo sampe ada satu jiwa lain di sekolah yang tahu soal
Aulia selain lo dan Aulia-nya sendiri, gue tahu rahasia itu bocor dari
mulut siapa”
Eda kembali tertawa. Dipa hanya geleng-geleng kepala.
“Gue tahu, deh, kriteria lo kayak gimana,” kata Eda. “Pasti yang
kayak Laras Sjahrir.”
Dipa mengangkat bahu.
“Pastilah, Dip. Dia, kan, idola lo. Tapi, memang wajar, sih, lo
ngefan sama dia. Gue aja tiap hari jadi nonton berita gara-gara dia.
Enak gitu bawain beritanya, nggak kaku, orangnya cantik, gaya
ngomongnya tenang, cerdas.”
“Gue nggak ngefan sama dia, Da. Dia bukan idola gue. Orang-
orang aja mikirnya kayak gitu.”
“Ya, ya, ya. Dia memang bukan idola lo, tapi inspirasi lo, panutan
lo, pedoman—”
“Da ... Laras Sjahrir itu ibu gue.”
120
CAP BADAK
gen
CHAPTER 21:
Penagaran
“Could this be that real love I’ve been missing ...
before I’ve met you?”
—Afgan - “Knock Me out”
da tersentak mendengar ucapan Dipa. Laras Sjahrir adalah
ibunya?! Eda dan Dipa saling tatap tanpa berkedip untuk
beberapa detik, sebelum tiba-tiba tawa Dipa pecah.
“Hahaha!” Dipa tergelak. “Lo percaya, Da?! Gue bercanda, lah!”
Seharusnya Eda misuh-misuh saat Dipa tertawa, tapi Eda hanya
menggumam, “Oh...”
“Yuk, lanjut belajar lagi. Udah kebanyakan main, nih, kita.”
Eda tak bisa lagi berkonsentrasi. Di kepalanya terus terngiang
kalimat Dipa. “Da ... Laras Sjahrir itu ibu gue.” Bahkan, sampai Eda
tiba di rumah pun, momen tersebut masih menghantuinya.
Firasat Eda mengatakan, Dipa tidak bercanda. Eda bisa melihat
sorot sendu dari kedua mata Dipa saat dia menyebut bahwa Laras
adalah ibunya. Lagi pula, masa iya Dipa bercanda tentang hal
seserius itu? Namun, mengingat tawa Dipa, Eda jadi ragu....
Eda menghela napas. Saat duduk di hadapan meja belajar, Eda
mengetuk-ngetuk dagunya sambil melirik ponsel yang tergeletak di
atas meja. Dia bukan pegiat media sosial. Dia tidak eksis di sana sini
seperti kebanyakan teman-teman sekolahnya.
Akan tetapi, sekali itu dia betul-betul penasaran. Akhirnya,
Eda mengambil ponselnya. Dia mengunduh aplikasi Instagram. Dia
membuat sebuah akun baru. Setelahnya dia langsung mencari nama
Laras Sjahrir. Tentu saja dikunci! Itu sebabnya Dipa harap-harap
cemas menunggu di-approve oleh Laras.
Eda terdiam sejenak. Dia hanya memandangi layar ponselnya
untuk beberapa saat sebelum memutuskan ke laman Google dan
mencari: how to view locked Instagram.
Just request to follow.
Eda memutar bola matanya ketika mendapat jawaban pertama.
Dia belum mau menjadi pengikut Laras Sjahrir di Instagram
sekarang. Eda melanjutkan pencariannya.
Just speak to the person.
Eda mengernyit. Speak to the person. Perlahan, Eda membuka
menu yang ada di pojok kanan atas profil Laras Sjahrir. Send message.
Inikah? Eda menyentuhnya. Ya, sepertinya benar. Memang bicara
langsung adalah jalan tercepat untuk menjawab rasa penasarannya.
Sejenak Eda merasa gengsi. Kok, tiba-tiba dia jadi kepo dengan
Dipa seperti ini?! Lucu sekali hidup manusia itu. Seminggu yang lalu
masih belum kenal, seminggu setelahnya sudah demikian penasaran.
Eda mengusap-usap kedua telapak tangannya dan menyentuh layar
ponsel lagi.
(22
Eda: Halo Mbak Laras. Saya Dwenda, kelas XII dari SMA Harapan.
Saya punya teman satu angkatan yang namanya Dipa, Pradipta
Syailendra. Apa mungkin Mbak Laras kenal?
Eda mengetikkan pesan melalui direct message Instagram Laras
Sjahrir.
Send.
Eda menghela napas lagi. Dia pesimis Laras akan membalas
pesannya, tapi dicoba dahulu saja. Siapa tahu. Setelahnya, Eda
kembali ke navigasi pencarian. Tadinya dia mau langsung menutup
aplikasi tersebut dan tidur, tapi ada godaan begitu besar dalam hati.
Eda menelan ludah. Dia menyentuh keyboard di layar ponselnya. P,
ketik Eda. P-R-A-D-I-P-T-A spasi Syailendra. Deg... deg... deg.... Duh!
Kenapa Eda jadi deg-degan begini mencari akun Instagram Dipa?!
Tidak ada hasil.
Baiklah, dicoba lagi. Kali ini apa, ya? Mungkin ... D, ketik Eda
lagi. I-P-A spasi Syailendra. Ada! Eda menjadi lebih deg-degan lagi
ketika dia melihat wajah Dipa di hasil pencariannya. Eda menyentuh
wajah tersebut. Betulan Dipa!
Eda hampir berteriak saking girangnya. Eda menarik dan
membuang napas dalam-dalam. Tenang, Da, tenang, ucapnya pada
diri sendiri. Nggak usah norak, ini cuma Dipa!
Dipa tidak narsis. Foto-foto yang diunggah jarang memuat
wajahnya sendiri. Malahan foto-foto itu lebih banyak menunjukkan
random stuffs Kota Jakarta. Seperti bajaj yang mengangkut sayur
hingga ke atapnya. Atau, motor yang membawa kandang-kandang
ayam hingga sopirnya terkubur di balik kandang-kandang tersebut.
Ada foto Dipa sedang naik bajaj, yang membuat Eda segera
tertawa. Dia mengenalinya. Foto itu diambil setelah Dipa
mengantarkan Eda pulang. Di sampingitu, Dipabanyakmengunggah
foto makanan.
(23
Eda mengenali sepiring siomay dan taplak meja yang menjadi
latar belakangnya. Itu adalah siomay kantin sekolah. Eda juga
mengenali sepiring burger dan kentang goreng serta segelas
minuman bersoda di sebelahnya. Itu adalah makanan gratis yang
mereka peroleh dari voucher Pak Budi. Senyum Eda mendadak
menjadi sangat lebar.
Dipa juga banyak memuat foto-foto kegiatan di panti. Ada
fotonya bersama anak-anak yang lebih muda. Mereka sedang
menyapu halaman dengan sapu lidi. Ada juga fotonya memakai
celemek dengan latar belakang dapur. Dipa tersenyum lebar di foto
itu, memegang sepiring makanan yang terlihat seperti oseng tahu
tempe sambil mengacungkan jempol.
“Hahaha ...” Eda geleng-geleng kepala sambil tertawa. Dia
tak pernah tahu ada orang semenarik Dipa di sekolahnya. Dia tak
pernah menyangka, Dipa adalah pribadi yang unik!
Setelah puas menyisir satu per satu foto-foto yang diunggah
Dipa, Eda menyentuh layar ponselnya di bagian Instagram Story.
Sepertinya ini yang suka dihebohkan anak-anak perihal Dipa.
Ketika Instagram Story Dipa membuka, Eda melihat layar hitam
dengan emoji pengeras suara. Ternyata ada cuplikan lagu di dalam
Instagram Story tersebut:
“T'lah kutemukan sebuah cinta yang kunantikan. Ternyata engkau
yang s'lalu kutunggu ... hiasi hatiku.”
Deg ... deg ... deg! Lagi-lagi jantung Eda berdebar-debar ketika
mendengar cuplikan lagu tersebut. Dia tahu lagu ini. Darah Eda
lebih berdesir lagi saat membaca potongan lirik lagu tersebut yang
dituliskan Dipa di Instagram Story-nya. Cepat-cepat Eda menutup
aplikasi itu dan meletakkan ponselnya kembali ke atas meja.
124
Eda mengempaskan diri ke ranjang dan menindih kedua
tangannya di belakang kepala. Dia menatap langit-langit kamarnya.
Kosong. Hanya plafon polos berwarna putih dengan lampu bulat
yang menempel. Namun, entah kenapa bagi Eda malam itu dia
seperti melihat ribuan bintang di langit.
“Could this be that real love I've been missing ... before I've met you?”
—Afgan - “Knock Me Out”.
(es
CAP BADAK
7)
2830 CHAPTER 22:
OS
hecewa
“Kalau cewek tiba-tiba kabur kayak gitu,
berarti dia punya hal yang lebih penting:
gebetannya atau pacarnya.”
alau ada yang tahu bahwa pada hari Sabtu yang panas terik ini,
Eda sedang berkebun di panti bersama dengan Dipa dan Vito,
mereka pasti akan menjadi bahan gosip.
“Mbak Eda! Tanahnya diginiin.” Vito memberi contoh.
“Ini udah”
“Kurang”
“Oke.”
Dipa tersenyum-senyum sendiri menyaksikan pemandangan
di depannya. Dipa sendiri masih tidak percaya Eda mau diajak ke
panti. Entah apa yang merasuki Dipa, tiba-tiba saja semalam dia
mengirim pesan kepada Eda. Sudah cukup malam pula, pukul 11.00!
Dipa: Da... lo, kan, pernah tanya, ya, tinggal di panti itu kayak gimana.
Besok ada acara, nggak? Mau main ke panti? Kami besok sekitar
jam 9.00 rencananya mau berkebun. Baru dapet bibit baru, terus
beberapa pohon udah berbuah juga. Ada jeruk limau, srikaya,
jambu, kalo nggak salah ada satu lagi, tapi gue lupa. Nanti lo bisa
bawa pulang juga buat dimakan di rumah, buat nyokap lo juga.
Itu pesan yang Dipa kirim ke Eda semalam. Tiga detik setelah
pesan Dipa terkirim, Dipa menyesalinya. Saking gemas dengan
dirinya sendiri, Dipa sampai mengepalkan tangan dan meninju-
ninju udara di atas ranjang. Dipa tak habis pikir mengapa dia begitu
bodoh.
Pertama, sudah pukul 11.00 malam. Mana mungkin Eda masih
melek?! Ya, mungkin saja, sih, karena besok hari Sabtu, tapi rasanya
tidak etis mengirim pesan selarut itu. Kedua, mengundang Eda ke
panti?! Memangnya tidak ada tempat lain? Pergi makan kek, nonton
kek, masa ke panti?! Ketiga, buat apa Dipa menawarkan buah-
buahan hasil kebun panti kepada Eda?! Bukan cuma ditawarkan
kepada Eda, tapi juga kepada ibunya. Gila, kali?
Dia sungguh merasa seperti si Paman dalam lagu “Paman
Datang”. Pamanku dari desa ... dibawakannya rambutan, pisang,
dan sayur mayur... DIAAAAM!!! Dipa menjerit dalam hati sambil
mengacak rambutnya.
Dipa menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya.
Tenang, Dip, ucap Dipa dalam hati. Ngapain panik? Ini cuma Eda. Eda
yang berebutan seratus juta dengan lo. Eda si Jutek. Eda yang sebetulnya
kalo dilihat-lihat, tuh, manis banget, apalagi waktu lagi serius nyimak
(2?
layar bioskop. Eda yang awalnya sekilas kurang ajar, tapi ternyata nggak
pernah lupa ngucapin terima kasih tiap ditemenin pulang. Eda yang...
Senyum Dipa tiba-tiba saja mengembang di wajahnya saat
benaknya melayang-layang memikirkan Eda.
BZZZT!
Dipa tersentak saat ponselnya bergetar. Jantungnya berdegup
kencang, cemas dengan jawaban yang diberikan Eda.
“Hiiih!” dumel Dipa, kesal bukan main saat tahu ponselnya
ternyata bergetar karena ada SMS masuk dari nomor tak dikenal
yang meminta pulsa!
Saking kesalnya, Dipa sampai berniat membalas SMS tersebut.
Minta... pulsa... jangan ... sama... gue... lo kira... gue ....
BZZZT!
Sekali lagi ponselnya bergetar. Dipa mengerjapkan matanya.
Ada satu notifikasi masuk dari Eda. Dipa segera melupakan SMS tak
jelas itu dan membuka pesan dari Eda.
Eda: Boleh, Dip. Alamatnya di mana? Besok gue ke sana.
Ingin sekali Dipa berteriak saat itu saking girangnya. Jari-jarinya
sampai terpeleset berkali-kali ketika mengetik alamat panti di atas
layar. Saking girangnya juga, semalaman Dipa sampai tak bisa tidur!
“Kenapa mata lo item gitu, Dip?” tanya Eda, saat mereka
bertemu keesokan paginya.
“Hah ... item? Oh, nggg ... kena tanah, kali!” jawab Dipa asal.
“Haaah?!” Eda mengernyit, lalu geleng-geleng kepala. “Eh,
beneran, nih, gue nggak apa-apa dateng ke sini?”
“Nggak, kok. Sama sekali nggak. Anak-anak seneng gitu kalo
ada yang berkunjung.”
Dipa mengenalkan Eda kepada Bu Isma, Kepala Panti, dan juga
pengurus-pengurus lainnya. Setelah itu, Dipa mengajak Eda keliling
(28
panti. Seperti yang Dipa ucapkan, adik-adiknya di panti senang
sekali kedatangan tamu. Mereka sibuk membuntuti Eda ke mana-
mana dan minta dikenalkan dengan Eda. Eda juga tak canggung
mengajak bicara anak-anak itu.
“Gue nggak nyangka lo bisa ngomong sama anak kecil juga,”
gumam Dipa, mengelus dagunya. “Gue kira wajah jutek kayak lo ini
nggak suka anak-anak.”
“Gue, kan, punya adik, Dip,” balas Eda. “Ya ... pernah punya adik.
Adik gue udah meninggal. Oh, lo udah tahu, kan?”
Dipa mengangguk. Dia tak ingin Eda jadi sedih mengingat
adiknya. Buru-buru Dipa mengajak Eda ke kebun dan menunjukkan
koleksi pepohonan panti.
“Ttu udah pada mateng jambunya. Kalo srikaya kayaknya yang
di pohon itu sama itu udah, yang ini belum.” Dipa sibuk menunjuk-
nunjuk. “Eh, Bay! Bayu! Turun! Jangan dipetikin itu jambunya! Buat
Mbak Eda.”
“Nggak apa-apa.” Eda tertawa. “Buat kamu aja, Bayu!”
“Bayu!” seru Dipa lagi kepada Bayu, salah satu adiknya di panti.
“Bay! Kalo gitu mumpung kamu udah manjat, petikin sekalian buat
Mas Dipa sama Mbak Eda!”
“[diith! Mas Dipa petik sendiri!” sahut Bayu.
“Bayu ....” Dipa memelotot. Ditunjukkannya wajah galak yang
membuat Bayu langsung segan.
“Iya ... Mas Dipa mau berapa?” sahut Bayu lagi, nadanya
melunak.
“Sebanyak yang bisa kamu petik, asal mateng dan nggak banyak
ulatnya. Makasih, ya!”
Eda tertawa lagi.
“Kenapa ketawa?” tanya Dipa.
(24
“Geli aja. Kenapa lo ditakutin banget di panti, sih? Ehm.” Eda
berdeham.
“Karena gue yang paling tua,” ujar Dipa. “Nggak ada lagi yang
lebih tua dari gue. Dan, gue yang paling lama. Ya iyalah, kalo gue
paling tua, gue pasti paling lama. Walau kadang yang paling lama
nggak mesti juga yang paling tua. Ada beberapa anak yang cuma
sebentar, habis itu udah diadopsi. Ya, gue rasa nasib tiap-tiap anak
berbeda.”
Eda menatap Dipa dengan perasaan bercampur aduk. Bagaimana
rasanya menjadi Dipa, ya? Ketika teman-teman lainnya di sekolah
punya orang tua sementara dia tidak. Ketika saudara-saudaranya di
panti kemudian diadopsi oleh keluarga baru sementara dia tetap di
sana hingga dewasa.
“Tapi gue senang di sini.” Cepat-cepat Dipa menambahkan. Dipa
menyadari Eda menatapnya dengan pandangan kasihan. Dipa tak
mau dikasihani. Dia juga tak merasa ada hal dari dirinya yang patut
dikasihani. “Rame, banyak adik-adik, banyak pengurus panti. Setiap
hari selalu seru.”
Eda tersenyum kecil. “Iya. Pasti seru, ya, kalo setiap hari rame
kayak gini.”
“Makanya, disyukuri aja, Da.” Dipa balas tersenyum. “Eh,
ngomong-ngomong, kayaknya makan siang udah mateng, nih. Udah
kecium wangi-wangi masakan. Makan, yuk!”
“Oh!” sela Eda. “Nggg ... gue mesti balik sekarang, Dip. Udah jam
12.00, kan?”
“Lho, kenapa?” tanya Dipa. Nadanya kecewa. “Cepet banget
udah mau balik? Makan dulu aja, Da.”
“Makasih, Dip. Tapi ... gue ada janji lagi.”
“Sama nyokap?”
“Nggak ....” Eda menelan ludah. “Sama ... ada orang”
130
sOha
“Bu Isma sama pengurus panti yang lain di mana, ya? Gue pamit
dulu.”
“Oh, mereka kayaknya lagi sibuk di dalem, ngurusin makan
anak-anak. Nanti gue salamin.”
“Kalo gitu gue balik dulu, ya? Makasih, Dip. Hari ini gue seneng
bisa ke sini.”
Dipa tersenyum. “Sama-sama, Da. Hati-hati di jalan, ya? Salam
buat nyokap lo. Semoga jambu sama srikayanya enak.”
Eda mengangguk sambil tersenyum sekilas. Dipa masih terus
berdiri di dekat pagar, menunggu Eda hingga tak terlihat lagi. Dipa
menghela napas. Eda ada janji dengan orang lain? Siapa? Dipa
penasaran. Padahal, Dipa senang sekali mendapat kunjungan dari
Eda.
Eda juga tidak memberi tahu Dipa siapa orang itu. Mungkin
seseorang yang tak dikenal Dipa? Atau, mungkin seseorang yang
dikenal Dipa, tapi Eda tidak mau Dipa tahu bahwa dia menemui
orang itu? Kenapa?
Apa Eda sebetulnya sudah punya pacar? Apa Eda pergi dengan
pacarnya? Kalau bukan pacarnya, lantas siapa? Gebetannya?
“Coba gue ulang pertanyaan lo ... misalnya lo lagi sama cewek, terus
tiba-tiba cewek itu izin pulang karena ada janji sama orang lain. Cewek
itu nggak bilang siapa orang lain tersebut. Pertanyaan lo adalah, kira-
Kira siapa orang lain itu? Bener, nggak?”
Saking penasarannya karena Eda yang tiba-tiba pulang, Dipa
sampai tak tahan lagi dan menelepon Dio untuk bercerita. Tentu
saja dia tidak menyebut perempuan itu adalah Eda.
“Iya. Kira-kira begitu pertanyaannya,” sahut Dipa.
“Hmmm... kok, gue merasa lo kayak lagi ngomongin gue sama Gita,
sih?”
BI
“Lo sama Gita? Apa hubungannya?”
“Iya. Gue, kan, lagi jalan sama Gita waktu itu, gue minta dia
temenin gue nyari kado buat kakak gue yang mau ulang tahun. Kakak
gue, kan, suka gambar-gambar gitu, tuh, kayak Gita, jadi gue pura-pura
aja minta pendapat dia. Kalau beli buku sketsa sama alat gambar yang
mana. Modus gitulah ceritanya. Habis itu, kan, setelah beli kado, gue
mau ngajak Gita makan, dong, eh, malah ditolak. Dia bilang, dia harus
pulang, ada urusan, ada janji sama orang lain. Ternyata dia pergi sama
Rama, gebetannya. Males banget, kan? Eh! Lo bukannya udah tahu
cerita ini?!”
Dipa tertawa. “Yeee ... itu, mah, emang Gita aja males sama lo
dan udah punya gebetan!”
Tepat setelah Dipa mengucapkan kalimat tersebut, dia terkesiap.
Bukankah itu yang terjadi pada dirinya?! Dipa merasa seolah
menjadi Dio dan Eda menjadi Gita! Berarti, Eda meninggalkan Dipa
tadi siang karena ingin pergi dengan gebetan atau pacarnya!
“Ya makanya, kalo cewek tiba-tiba kabur kayak gitu, mah, berarti
dia ada yang lebih penting. Gebetan atau pacarnya. Cuma, dia nggak
mau bilang aja, karena nggak enak sama cowok yang awalnya pergi sama
dia itu. Kayak Gita nggak enak gitu bilang ke gue kalo dia ninggalin gue
gara-gara mau ketemu sama Rama.”
“Oh... iya, sih.”
Dipa langsung lunglai. Hhh ... ya, tentu saja, perempuan seperti
Eda pasti sudah punya pacar. Mungkin baru jadian sebab belum
lama ini Eda bilang dia belum pernah pacaran. Atau, mungkin
juga gebetannya. Yang jelas, siapa pun itu orangnya, lebih penting
daripada Dipa di mata Eda ....
132
CAP BADAK
2§30
CHAPTER 23:
Youg Dinanté
OS
“Jangan bilang dia kalau kamu kontak saya, ya.
Kemungkinan dia kurang senang mendengarnya.”
Laras Sjahrir: Hai Eda, kamu kenal dekat dengan Pradipta?
De bunyi pesan balasan untuk Eda dari Laras di aplikasi
Instagram. Laras Sjahrir menjawab pesannya! Eda terkesiap. Dia
sampai membekap mulutnya dengan tidak percaya.
Awalnya, Eda sempat curiga apakah Laras betul-betul adalah
ibu dari Dipa. Rasa penasaran itulah yang mendorong Eda untuk
begitu nekat menghubungi Laras lewat Instagram. Eda sungguh tak
menyangka Laras akan membalas pesannya.
Eda: Saya temannya, Mbak. Belum lama kenal, tapi belakangan saya
sering main sama Dipa. Apa Mbak Laras kenal dengan Dipa?
Eda membalas pesan Laras dan kembali mengulang
pertanyaannya. Balasan dari Laras lagi-lagi mengejutkan Eda.
Laras Sjahrir: Saya tahu Pradipta. Sudah lama sekali. Gimana kabarnya?
Oh, ya, jangan bilang dia kalau kamu kontak saya, ya. Kemungkinan
dia akan kurang senang mendengarnya.
Pesan balasan yang aneh, membuat Eda semakin penasaran.
Eda pun lanjut membalas pesan tersebut.
Eda: Dipa baik, Mbak. lya, saya nggak bilang Dipa. Tapi, kenapa dia
kurang senang kalau tahu saya Kontak Mbak Laras?
Kemudian, datanglah balasan yang semakin membuat Eda
tercengang. Laras tak menjawab pertanyaan Eda. Dia malah
mengajak bertemu.
Laras Sjahrir: Eda, Sabtu ini kamu ada waktu? Kalau iya, boleh kita
ketemuan jam 1.00 siang? Di Quaker Café, lokasinya di lobi
gedung INC TV.
Eda menyanggupi pertemuan tersebut. Dia sedang bertandang
ke panti asuhan Dipa ketika menyadari jam sudah menunjukkan
pukul 12.00 siang. Eda ingin sekali menghabiskan waktu lebih lama
lagi dengan Dipa, tetapi sudah saatnya untuk pergi dan menemui
Laras.
Eda begitu gugup. Dia memang sudah sering melihat Laras
di televisi, tetapi tetap saja telapak tangannya berkeringat dingin
seiring dengan langkah yang kian mendekati Quaker Café.
4
Saat mendorong pintu kafe, Eda menangkap sosok perempuan
yang duduk di dekat jendela. Satu tangannya menopang dagu,
memandang ke arah luar jendela. Tangan yang lain mengaduk-aduk
isi cangkir di hadapannya dengan gerakan sangat lambat.
Eda menarik napas dalam-dalam. Sosok itu adalah Laras. Dia
mengenalinya. Berpakaian lebih santai dari yang terlihat di televisi.
Laras mengenakan kaus lengan panjang putih dan celana jins biru.
Rambut sebahunya yang sedikit bergelombang dibiarkan jatuh
menutupi sebagian wajah. Jantung Eda berdegup cepat.
“Pe-permisi,” sapa Eda. “Mbak Laras?”
Sosok itu menoleh mendengar namanya dipanggil. Memang,
dia adalah Laras. Senyum Laras mengembang. Detik itu juga Eda
teringat Dipa. Apa jadinya kalau Dipa ada di sana saat itu? Mungkin
sudah pingsan saking terpesonanya.
“Hai,” sapa Laras. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya
untuk bersalaman. “Eda, ya? Saya Laras. Silakan duduk.”
Eda begitu tersihir. Perempuan ini sangat sopan, ramah, cantik,
dan memiliki pembawaan yang menyenangkan. Laras terkesan
begitu sempurna, membuat Eda semakin gugup.
“Makasih, ya, udah mau meluangkan waktumu untuk saya hari
ini,” ucap Laras.
“Sa-sama ... sama-sama,” balas Eda, terbata-bata.
“Kamu mau pesan apa, Eda?”
“A-apa aja, Mbak.”
“Pollo picante di sini enak. Mau coba?”
Eda hanya mengangguk. Dia terlalu gugup untuk berpikir.
Laras memesankan makanan untuk mereka berdua. Saat sedang
menunggu pesanan, Eda memberanikan diri untuk bertanya.
“Mbak Laras ... maaf, sa-saya cuma penasaran aja, Mbak Laras
gimana bisa kenal Dipa?”
Bs
Laras tersenyum, lalu menyeruput minumannya. Dari aromanya,
Eda yakin isi cangkir itu adalah kopi yang cukup kuat rasanya.
“Panjanglah ceritanya,” jawab Laras. “Tapi, udah lama banget.”
“Lalu ... Mbak Laras kenapa mau ketemu saya?”
“Penasaran aja gimana kabar Dipa. Kamu sendiri, kenapa
menghubungi saya?”
“Pe-penasaran juga aja ... Dipa ngefan banget sama Mbak
Laras. Dan ....” Eda menelan ludah. Sesaat dia ragu, haruskah dia
menceritakan semuanya kepada Laras?
“Dan?” Laras menaikkan alisnya.
“Dan ... tiba-tiba baru-baru ini Dipa bilang kalo Mbak Laras itu
ibunya.”
Kedua mata Laras melebar.
“Tapi, habis itu dia bilang cuma bercanda.” Eda buru-buru
menambahkan. “Tapi ... tapi, saya jadi penasaran. Sa-saya tahu, saya
lancang. Maaf.”
Laras tertawa kecil. “Boleh saya tebak sesuatu?”
“Liya?”
“Kamu naksir Pradipta, ya?”
Wajah Eda memerah. Dia sontak membuang pandangan dari
Laras. Ekspresi Eda malah membuat Laras tertawa sekcali lagi.
“Kamu kelihatannya peduli banget sama dia.”
“Bu-bukan begitu, Mbak!”
“Nggak apa-apa. Pradipta anak yang baik, kan?”
“Liya.”
“Di sekolah, pintar?”
“Sa-saya nggak sekelas sama dia. Tapi ... tapi, kata temen-temen,
sih, dia lumayan pintar.”
Laras menyeruput kopinya lagi. “Pradipta senang di sekolah?”
Eda sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Senang? Sepertinya
iya. Dia selalu terlihat energik, gembira, dan penuh semangat.
Bo
“Iya,” jawab Eda. “Anaknya rame, berisik, ceria terus.”
Laras mengangguk. Kembali dia menyeruput kopinya. Saat
itu ponsel Laras yang ada di atas meja bergetar. Dia meliriknya,
kemudian menghela napas.
“Eda, maaf banget, ya? Saya harus pergi sekarang, dipanggil
redaksi. Kamu makan sendiri nggak apa-apa, ya? Pesanan saya buat
kamu aja, bawa pulang”
“Oh...”
“Sabtu depan kamu ada waktu? Malam, sekitar jam 7.00, kita
makan bareng, gimana?”
Laras menyebut nama sebuah restoran yang ada di salah satu
mal papan atas.
“Boleh, Mbak,” sahut Eda.
Laras tersenyum. Dia memanggil salah seorang pelayan. “Mbak,
meja ini open bill, ya, charge ke saya aja seperti biasa. Laras Sjahrir.”
Laras menunjukkan kartu tanda pengenal yang melingkar di
lehernya. Pelayan itu men;
n, Laras beranjak dari kursinya.
“Saya masih mau ngobrol dengan kamu, tapi maaf banget,
Eda, saya betul-betul harus ninggalin kamu sekarang,” ucap Laras.
“Sampai Sabtu depan, ya?”
“L-iya, Mbak. Nggak apa-apa.”
“Senang berkenalan dengan kamu.”
“Sama-sama, Mbak.”
“Oh, ya. Jangan bilang Pradipta soal pertemuan kita, ya, Eda?”
Laras tersenyum, lalu mengangguk pertanda pamit. Eda hanya
tertegun menatap Laras yang pergi meninggalkannya.
37
OS
CHAPTER 24:
Hari H Jomba
Semangat dari kawan
bukan hanya menjadi alasan untuk bertahan,
melainkan juga untuk terus berjalan.
+¢
¢ Cori, sori! Lo tahu, nggak, apa yang terjadi? Masa tadi gue naik
mikrolet, mikroletnya berhenti mendadak di tengah jalanan,
gara-gara ada penumpang yang mendadak mau melahirkan!”
Dipa, Aulia, dan Sultan serempak menarik napas lega ketika
melihat Eda akhirnya muncul pada detik-detik terakhir, lima menit
sebelum lomba dimulai. Rambut Eda berantakan tak karuan.
Napasnya tersengal-sengal. Dia segera menarik kursi di sebelah
Dipa.
“Da, kirain lo nggak dateng.” Aulia mengusap wajahnya.
“Ya jelas gue dateng, Au. Gue udah bangun jam 5.00, jalan jam
6.00, nggak tahunya—”
“Selamat pagi!”
Cerita Eda terpotong oleh sapaan yang terdengar lewat pengeras
suara. Dipa memberi isyarat kepada Eda agar menyimpan ceritanya
untuk nanti saja.
“Selamat datang di Lomba Pengetahuan Umum IKom yang
diselenggarakan setiap tahunnya. Juara bertahan kita tahun lalu
adalah SMA Harapan.”
Aulia terlihat gelisah. Wajahnya terlihat seperti antara menahan
senyum dan menahan hajat.
“Tahun lalu kakaknya Aulia yang ikut,” bisik Sultan. “Sama
kakak gue”
Dipa mengangguk-angguk, sebetulnya tak peduli. Yang
dipedulikan Dipa hanya satu: mereka harus menang dan harus
berhasil mendapatkan kembali tutup stoples keberuntungan yang
disita Pak Budi! Dipa sungguh sudah tak sabar untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan. Kata-kata sambutan panitia terdengar di
telinganya hanya seperti bla bla bla saja.
“Dip,” bisik Eda. Dia mencondongkan tubuhnya ke Dipa. “Inget,
ya, kesepakatan kita. Bagi dua!”
Dipa mengangguk.
“Salaman dulu!”
Bunyi deg ... deg ... deg ... saat telapak tangan Dipa bersentuhan.
dengan telapak tangan Eda, jantungnya berdebar keras. Fokus, Dip,
fokus!
“Kita mulai soal pertama. Kategori Olahraga. Pada tanggal
berapakah pasangan ganda campuran Indonesia Liliyana Natsir dan
Tontowi Ahmad berhasil masuk ke babak final Olimpiade tahun
2016?”
TET!
Dipa langsung memencet bel, bahkan sebelum Eda, Aulia,
ataupun Sultan sempat berpikir. Eda sampai terlonjak dibuatnya.
134
“Tanggal 16 Agustus!”
“Benar. Sepuluh poin untuk SMA Harapan.”
Dipa mengepalkan tangannya penuh semangat. Awal yang
bagus, sungguh awal yang bagus.
“Pertanyaan berikutnya. Kategori Seni. Sebutkan tokoh-tokoh
utama dalam film Indonesia berjudul Tabula—”
TET!
“Hans, Emak, Parmanto, dan Natsir!”
“Benar. Sepuluh poin untuk SMA Harapan.”
Senyum Dipa merekah. Dia memandang berkeliling, menikmati
pandangan takjub dari peserta-peserta lain dan juga anggota timnya
sendiri.
“Pertanyaan selanjutnya. Kategori Sains. Apa nama fungi yang
digunakan untuk produksi tempe?”
Satu detik ... dua detik ....
TET!
“Rhizopus oligosporus!”
“Benar. Sepuluh poin untuk SMA Bakti Siswa.”
Dipa mengusap wajahnya. Kalau pertanyaannya ilmiah seperti
itu, dia tidak mungkin bisa menjawabnya. Aulia terlihat menggigit
bibir dengan tegang. Eda menelan ludah. Sultan meremas-remas
jarinya.
“Pertanyaan berikutnya ....”
“Tenang, Dip,” bisik Eda, sambil menepuk punggung tangan
Dipa.
Tarik napas. Dipa mengangguk mantap.
“Geografi. Sebutkan enam negara yang berbatasan langsung
dengan Laut Hitam!”
TET!
“Ukraina, Rusia, Georgia, Turki ....” Jari-jari Dipa membuka di
telapak tangannya, menghitung jumlah negara yang disebutkan.
140
“Rumania, Bulgaria!” Eda menyambung.
“Benar. Sepuluh poin untuk SMA Harapan.”
“Yes!”
Dipa dan Eda saling melempar tos, juga dengan Aulia dan Sultan.
“Perolehan skor sementara, SMA Harapan mendominasi
dengan tiga puluh poin. SMA Bakti Siswa ada di urutan kedua
dengan sepuluh poin. Ayo yang lainnya semangat, masih banyak
kesempatan untuk mengejar ketertinggalan.”
Tim SMA Harapan seolah mendapat angin. Betul-betul
permulaan yang baik. Dipa dan Eda sangat optimistis mereka bisa
menang. Namun, mereka tidak ingin terlena dengan keberhasilan
mereka pada awal perlombaan.
Persaingan semakin ketat ketika mereka maju ke babak-babak
berikutnya. Setiap kali Dipa tidak mampu menjawab sebuah
pertanyaan, Dipa bersyukur sebab teman-teman yang lain bisa
menutupi kekurangannya.
“Babak berikutnya adalah Rapid Fire. Satu perwakilan dari tiap
tim menjawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dalam waktu satu
menit. Kalian kami beri waktu satu menit untuk merundingkan
siapa wakil dari tim kalian masing-masing.”
Dipa, Eda, Aulia, dan Sultan langsung duduk merapat.
“Dipa aja, mendingan Dipa,” usul Sultan.
“Tapi, mendingan jangan Dipa,” balas Aulia. “Dipa ditaruh paling
akhir aja, buat final. Lo aja gimana, Da?”
Eda menelan ludah. Semua mata teman-temannya tertuju
kepadanya. Kalau dia tidak bisa memenangi babak ini maka
timnya tidak bisa maju ke final. Selama ini Dipa yang paling
banyak berkontribusi terhadap tim. Dia bisa berpikir dengan cepat
dan menjawab dengan tepat. Eda tak yakin apakah dia punya
kemampuan seperti Dipa.
(4
“Lo pastibisa, Da.” Dipa menggenggam erat tangan Eda. “Anggap
aja ini seperti saat kita belajar. Lo pasti bisa. Lakukan ini buat tim
kita, buat gue, buat nyokap lo, buat diri lo sendiri.”
Eda mengangguk-angguk. “Oke.”
“Perwakilan dari tim SMA Harapan?”
“Saya.” Eda beranjak sambil mengacungkan tangannya.
“Baik. Kita masuk ke babak berikutnya, babak Rapid Fire,
dimulai dari tim dengan skor terendah, SMA Bethesda ....”
Eda berusaha mengatur napasnya. Dipa benar. Ini semua seperti
saat dia belajar bersama dengan Dipa saja. Yang penting tidak panik
dan fokus. Hadiah undian kopi tersebut hanya tinggal selangkah
lagi.
“SMA Harapan, siap?”
“Siap”
“Sebutkan nama kabinet pemerintahan yang dipimpin
almarhum Presiden Abdurrahman Wahid!”
“Kabinet Persatuan Nasional!”
“Sebutkan kota terbesar ketiga di Indonesia!”
“Ban ... nggg ... MEDAN!”
“Bagaimana cara memainkan alat musik serunai?”
“Ditiup!”
“Pada tahun berapakah Ratu Elizabeth II naik takhta?”
“1952!”
“Apa nama virus yang menyerang pergantian milenium tahun
2000?”
“Y2K!”
“Siapa penerima Nobel Perdamaian pertama?”
“Henry Dunant!”
“Negara manakah yang memenangi Piala Dunia tahun 2006?”
“Jerman?”
142
“Salah! Di manakah lokasi—”
Pip.... pip... pip
“Ya, waktunya habis. Tim SMA Harapan berhasil menjawab
enam pertanyaan dengan benar.”
Eda melirik papan skor. Di bawah nama SMA Harapan muncul
skor tambahan yang diperolehnya dari babak Rapid Fire tadi. Eda
menghela napas lega saat mengetahui timnya juga memimpin di
babak tersebut!
“Bagus, Da! Bagus!” Teman-temannya menepuk-nepuk bahunya.
“SMA Harapan masih memimpin dengan perolehan skor
tertinggi dan berhasil masuk ke final bersama SMA Bakti Siswa dan
SMAN X!”
“YES! YES!”
“Kita akan jeda sejenak. Silakan kembali ke ruang perlombaan.
lima belas menit dari sekarang”
Satu per satu peserta lomba mulai meninggalkan ruangan.
143,
CAP BADAK
oz
230 CHAPTER 25:
1g
OS
Percakapon
di Toile”
Dia yang hatinya terbuat dari emas
justru tak pernah memamerkannya.
lash!
Eda membasuh wajahnya dan melihat pantulan Aulia di
cermin. Baru saja Aulia keluar dari bilik toilet di belakangnya.
Aulia menghampiri wastafel di sebelah Eda dan mencuci tangan.
“Kenapa, Da? Lo ngantuk?” celetuk Aulia.
Eda tersenyum kecut. “Lagi tegang gini mana bisa ngantuk?
Cuci muka biar lebih seger aja, Au.”
“Emang ngelihat yang di dalem belum seger, tuh?” goda Aulia.
“Di dalem mana? Siapa?” Eda malah celingukan ke bilik-bilik
kosong di belakang mereka berdua.
“Bukan di WC, Da, diruanglomba.” Aulia buru-buru menjelaskan.
“Dipa maksudnya.”
“Oh.”
Eda menelan ludah. Entah kenapa dia membasuh wajahnya lagi.
Dia berharap barangkali dengan begitu semu merah di wajah Eda
bisa segera pudar sebelum Aulia menyadarinya.
“Emang menurut lo, Dipa nggak ganteng, Da?” tanya Aulia.
“Mmm... ya, bolehlah,” jawab Eda canggung.
“Dia tidak cuma ganteng, tapi juga baik banget.”
“Oh, ya? Baiknya gimana?” pancing Eda.
“Kalian bukannya deket, ya?”
“De-deket? Kata siapa?”
“Ya, kelihatannya gitu. Gue juga beberapa kali ngelihat kalian
berdua di sekolah.”
Eda menggigit bibir, menahan supaya senyumnya tak lepas
begitu saja. Bukan main ge-er dia ketika orang lain mengira dirinya
dekat dengan Dipa.
“Ya, Dipa baik banget gitu anaknya, dari zaman SD.”
“Lo kenal Dipa dari SD?”
“Iya. Kita bahkan sekelas terus, lho.” Aulia tersenyum
mengenang masa lalu. “Gue inget, deh, waktu itu gue kelas V SD.
Pagi-pagi pas lagi jalan ke sekolah, gue dipalak di dekat gang menuju
sekolah. Uang jajan gue diambil sama anak-anak SMP sekolah lain.
Terus, Dipa nemuin gue lagi nangis di halte. Dia tanya kenapa, ya
udah, gue cerita. Eh, dia malah ngeluarin kotak bekalnya dan ngasih
ke gue, Iho!”
Mata Eda melebar, antusias mendengar cerita Aulia.
“Terus, gue bilang, kan, nanti Dipa makan apa kalau makanannya
dikasih ke gue? Lo tahu, nggak, dia bilang apa? ‘Nggak apa-apa.
Nanti katanya mau ada mobil susu gratis dateng buat bagi-bagi
susu, minum itu aja juga gue kenyang, kok’”
(4s
Eda tertawa. Hatinya meleleh mendengar cerita Dipa kecil.
Pantas saja Aulia naksir berat dengan Dipa. Kalau jadi Aulia, Eda
juga pasti langsung jatuh cinta seketika itu juga!
“Terus, terus, apa lagi?” Eda ketagihan mendengar kisah Dipa.
“Banyak, deh. Dia sayang banget sama adik-adiknya di panti.
Kalau weekend diajakin pergi gitu jarang banget mau. Dia lebih
senang bantu bersih-bersih di panti, bantuin adik-adiknya belajar.
Anak rumahan banget, deh.”
Eda senyum-senyum sendiri mendengar cerita Aulia. Ya, Eda
percaya. Dia melihat sendiri ketika berkunjung ke panti.
“Kasihan anak itu yatim piatu. Padahal, kalau orang tuanya
tahu, mereka pasti bangga punya anak kayak Dipa.” Aulia menghela
napas. “Eh, kayaknya kita udah mesti balik, deh. Babak selanjutnya
udah mau dimulai.”
Eda mengangguk. Ya, seandainya orang tua Dipa tahu, mereka
pasti bangga. Eda jadi teringat ucapan Laras kemarin ini. Jangan
bilang Pradipta soal pertemuan kita. Kenapa? Apa Laras tahu sesuatu
tentang Dipa yang tak diketahui siapa pun?
Apa benar, ternyata Laras adalah ibunya Dipa? Kalau iya,
mengapa dia menelantarkan Dipa di panti? Kalau iya, mengapa dia
masih punya nyali untuk mengajak Eda bertemu lagi? Kalau iya,
mengapa dia tega membiarkan Dipa hidup sebatang kara sambil
merindukan sosoknya?
(Ho
CAP BADAK
gen
CHAPTER 26:
Babak
Terakhir
Niat yang baik
akan berujung pada hasil yang baik pula.
gee kembali berkumpul di luar, Dipa, Eda, Aulia dan Sultan
segera duduk di salah satu pojokan, menyusun strategi.
“Kita harus tenang” Aulia kembali mengingatkan. “Skor kita
beda tipis dengan SMAN X. Kita juga harus hati-hati. Jadi, kita
sepakat, ya, Dipa yang wakilin kita?”
Eda dan Sultan mengangguk.
“Dipa, lo bersedia?”
Dipa juga mengangguk dengan sangat mantap.
“Kiat dari kakak gue, kalau nggak yakin sama jawabannya,
mending jangan jawab, karena di babak ini jawaban yang salah bisa
mengurangi skor.”
Dipa mengangguk lagi. Mereka berempat minum dan berdoa
sejenak sebelum kembali ke ruang perlombaan. Babak final ini
adalah babak yang paling mengintimidasi.
Babak final terdiri atas tiga bagian. Pertama, bagian saat
jawaban yang salah akan mengurangi skor. Kedua, bagian saat
kategori pertanyaan dipilihkan oleh tim lawan. Ketiga, bagian saat
pertanyaan yang dilontarkan adalah pertanyaan yang dibuat sendiri
oleh tim lawan dan sebelumnya sudah melalui persetujuan panitia
perlombaan.
Dipa meregangkan lehernya dan berkali-kali menarik napas
dalam-dalam. Dia harus membawa timnya menang. Harus! Ini bukan
sekadar mempertahankan gelar juara bagi sekolahnya. Ini bukan
juga sekadar merebut kembali uang seratus juta yang merupakan
hadiah undian yang disita. Dipa punya rencana lain, keinginan yang
lain.
“Pertanyaan untuk SMA Harapan. Pada tahun berapakah tokoh
perdamaian, Mahatma Gandhi, menjadi Person of the Year dari
majalah Time?”
Dipa menelan ludah. “19 ... 30.”
“Benar. Mahatma Gandhi menjadi Person of the Year dari
majalah Time pada tahun 1930 atas gerakannya memimpin Pawai
Garam atau Satyagraha Garam sepanjang 240 mil, atau kira-kira
390 kilometer, untuk menentang pajak dan monopoli garam oleh
pemerintah kolonial.”
Dipa menghela napas lega. Dia melihat teman-temannya ikut
tegang menonton. Meskipun demikian, tatapan mereka kepada
Dipa begitu membara penuh semangat. Dipa menjadi lebih percaya
diri, Dipa tak memusingkan perolehan skor tim lain. Dia hanya
menunggu gilirannya kembali dengan tenang.
(48
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5807)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1091)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (842)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (537)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)