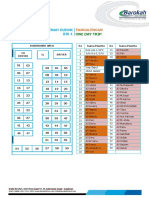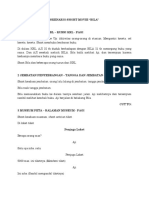Professional Documents
Culture Documents
A00 Mar 2
A00 Mar 2
Uploaded by
Siti Rahayu Salsabila0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views99 pagesOriginal Title
A00mar2
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views99 pagesA00 Mar 2
A00 Mar 2
Uploaded by
Siti Rahayu SalsabilaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 99
A/ see
3.800
00%? ANALISIS JENDER
DALAM KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN
(Kasus Balai Informasi dan Penyulahan Pertanian
Kabupaten Daerah Tingkat If Karawang, Propinsi Jawa Barat)
Oleh
MARYUNANI
A 09495041
JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2000
“ Janganiah kamu irihati terhadap pemberian Allah kepada sebahagian lebik
banyak dari yang lain. Laki-taki berate bagian dari usakanya, dan orang-orang
perempuan beroteh baglan pula dari usahanya ; Mintalah kepada Allah
kurniaNya; sesungeuknya Allah ite menyaksikan segala sesuatie “
(An nisaa’ : 32)
“ Kapersembahkan karya kecttkae ini
‘kepada Papa dan Mama terenta, yang
getar bibirnya adalah doa senyum dan
tangisnya adalak harapan, langkak kaki
dan. ayunannya adalak juang, bagi anak-
anak yong dikasthinya. Juga buat
a’iyus, Dina, De'Vira, Melly, Deddy, Kiki,
A’Yudi dan Mas Suryo yang Insya Allah
akan mendampingi hidupka.”
(idaryunani )
RINGKASAN
MARYUNANIL. Analisis Jender Dalam Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Kasus
Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat 1 Karawang,
Propinsi Jawa Barat. (Dibawah bimbingan SITI SUGIAH MUGNIESYAH).
Kehadiran SKB Mendagri-Mentan No, 54 Tahun 1996 dan No. 301/Kpts/L.P,
120/4/96 merupakan suatu perubahan besar terhadap kelembagaan penyuluhan
pertanian, Dengan adanya kelembagsan baru penyuluhan pertanian maka perlu
ditelaah kinerja BIPP termasuk di dalamnya BPP dengan menggunakan analisis,
jender, Masalah jender dalam kelembagaan penyuluhan menjadi penting mengingat
pembangunan pertanian paradigma lama yang bias jender kurang menghasilkan
pertanian yang berkelanjutan, Sehubungan itu akan dilihat bagaimana pembagian
kerja (kualitatif), curahan waktu (kuantitatif) serta beban kerja dalam kegiatan
produktif ? Sejauh mana akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan yang
berkenaan dengan kegiatan produktif'? Bagaimana sumberdaya pribadi dan keluarga
mempengaruhi profil aktifitas, akses dan kontrol penyuluh pria dan wanita dalam
kegiatan produktif ?
Penelitian ini bertujuan untuk © (1) mempelajari profil BIPP, (2) mekanisme
kerja BIPP dengan dinas instansi daerah tingkat II lingkup pertanian. (3) profil
aktivitas, khususnya pembagian kerja dan curshan waktu serta beban kerja antara
penyulub pertanian pria dan wanita dalam kegiatan produktif di BPP dan BIPP, (4)
akses dan kontrol penyuluh pertanian pria dan wanita dalam kegiatan produktif. (5)
hubungan sumber daya pribadi dan keluerga terhadap profil aktivitas, akses dan
kontrol penyuluh pertanian pria dan wanita
Unit analisis yang dipakei adalah individu dan lembaga. Responden terditi
alas penyuluh pertanian pria dan wanita, di BIPP 15 responden dan di BPP 25
responden, Data primer diperoleh dari wawancara dan pengamatan dengan
menggunakan metode survey. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen
dinas lingkup pertanian, PEMDA Karawang, BAPEDAL, BIPP dan BPP. Data yang
diperoleh dianalisis secara kuantitatif’ dan diperkuat dengan data kualitatif yang
diperoleh melalui wawancara mendalam
BIPP sebagai kelembagaan baru mempunyai 15 fungsi yang terbagi dalam
Jima urusan pelayanan, Namun mengingat umur BIPP baru memasuki tahun kedua
diketahui dari semua fungsi belum semua terealisir, hanya sebagian saja yang
terrealisasi yaitu. penyusunan program, bimbingan penyusunan dan rencana kerja
penyuluh, penyelenggaraan latihan (Kursus) dan pelaksanaan urusan tata usaha,
Hubungan dan mekanisme kerja BIPP dengan Dinas Sub Sektor bersifat
koordinatif, namun ketiadaan kebijakan yang mengatur hubungan dan pembagian
kerja antara dinas sub sektor dengan BIPP menyebabkan tugas penyuluh pertanian
tumpang tindih, ditambah sikap dinas yang belum mampu melepaskan penyuluh
pertanian kepada BIPP menyebabkan dualisme kepemimpinan, Adanya dualisme
kepemimpinan ini menyebabkan kinerja penyuluh pertanian kurang efektif sehingga
disarankan agar dualisme kepemimpinan yang terjadi antara BIPP dengan dines perlu
segera dibenahi untuk menghindari ketidak jelasan status penyuluh pertanian dengan
cara menyatwkan kontrol terhadap penyuluh pertanian dengan cara semua urusan
yang menyangkut kepegawaian penyuluh pertanian dilimpahkan kepada BIPP.
Selain sarana dan prasarana yang kurang memadai, sumberdaya pribadi juga
menentukan kualitas kerja penyuluh pertanian, Tingkat pendidikan penyuluh wanita
yang lebih rendah dibandingkan pria menyebabkan wanita kurang mampu
melaksqnakan kegiatan teknis yang selalu mengikuti perkembangan ilmu dan
teknologi dibidang pertanian, Namun motivasi wanita yang bersifat pengabdian bagi
negara memacu untuk bekerja dengan sebaik mungkin, berbeda dengan pria yang
bermotivasi pribadi lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan keluarga
dibandingkan pengabdian terhadap pekerjaannya
Selain motivasi yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian, sumberdaya
keluarga juga sangat mendukung. Hal tersebut terlihat dari dukungan kepemilikan
lahan dan temnak terhadap pekerjaan pria yang bersifat teknis, sedangkan wanita lebih
akses terhadap pemilikan benda berharga yang berkaitan dengan penggunaan
teknologi modern sebagai alat bantu melaksanakan kegiatan reproduktif sehingga
dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas pokoknya.
Pembagian kerja dan curahan waktu penyuluh pertanian pria dan wanita
dalam melaksanakan tugas dan pokok sebagai penyuluh pertanian berbeda, Penyuluh
pria lebih memilih pekerjaaan yang bersifat teknis sedangkan wanita lebih bersifat
administrasi. Dalam mengumpulkan angka kredit, penyulub pria tidak memerlukan
curahan waktu yang tinggi mengingat angka kredit untuk kegiatan yang bersifat
teknis jauh lebih besar dibandingkan kegiatan administrasi.
Akses penyuluh pria dalam kegiatan produktif di BIPP maupun BPP rendah
mengingat sebagian besar waktu yang seharusnya digunakan melaksanakan kegiatan
di wilayab tugasnya dicurahkan untuk pekerjaan sampingan. Sedangkan akses wanita
tethadap bidang tugasnya tinggi mengingat pekerjaan wanita yang bersifat
administrasi-mengharusken ia untuk akses pada setiap kegiatan yang memerlukan
evaluasi atau laporan akhir
Kontrol penyuluh pertanian pria rendah mengingat aksesnyapun rendah,
sedangkan kontrol penyuluh wanita yang seharusnya tinggi mengingat aksesnya
tinggi tidak terjadi. Hal ini disebabkan kontrol atau pengambilan keputusan dalam
setiap kegiatan diserahkan kepada penyuluh pertanian yang berpendidikan tinggi dan
mempunyai keahlian dibidangnya.
Stereotipi yang menyatakan pria lebih baik ditempatkan dalam pekerjaan
yang berhubungan dengan kegiatan teknis sedangkan penyuluh wanita lebih baik
ditempatkan dalam kegiatan administrasi menyebabkan terjadi kecenderungan
tertentu dalam pembagian kerja dan penentuan petuges. Bias jender yang terjadi
tampak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh baik di BIPP maupun BPP
Bias jender masih mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian menyebabkan
adanya ketimpangand alam curahan waktu, akses dan kontrol dalam kegiatan
produktif, sehingga perlu penyadaran jender dalam kelebagaan penyuluhan. Untuk
meningkatkan kedudukan dan peran wanita dalam kelembagaan diperlukan kebijakan
yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan jender.
ANALISIS JENDER
DALAM KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN
( Kasus Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian
Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Propinsi Jawa Barat )
Oleh :
MARYUNANI
A 09495041
SKRIPSL
Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Untuk Memperolch G
SARJANA PERTANIAN
Pada
JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2000
JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Dengan ini kami menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh
‘Nama ‘Maryunani
NRP A09495041
Program Studi : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
Judul ANALISIS JENDER DALAM KELEMBAGAAN
PENYULUHAN — PERTANIAN (Kasus_ Balai
Informasi dan Penyuluban Pertanian Kabupaten Daerah
Tingkat If Karawang, Propinsi Jawa Barat)
Dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian
pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Menyetujui,
Dosen Pembimbing
Ir. Siti Sugiah Mugniesyah,
NIP, 130779 504
Mengetahui,
[mu Sosial Ekonomi Pertanian
Tanggal Kelulusan : 29 Februari 2000
PERNYATAAN
‘Dengan ini saya menyatalan bahwa skripsi ini adaleh bener-bener hasil kerja.
sondiri dan bolum pernah diajukan sebagai ckripsi di perguruan tinggi lain dan
Jembaga manapun.
Bogor, 29 Februsri 2000
MARYUNANI
KATA PENGANTAR
Poji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaiken.
Adapun skripsi yang berjudul “Analisis Jender Dalam Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian (Kasus Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten
Daerah tingkat If Karawang Propinsi Jawa Barat)” ini merupakan salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana pertanian, pada Program Studi Penyuluban dan
Komunikesi Pertanian, Jurusan Umu-llmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas
Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada :
1. Ibu Ir. Siti Sugish M. Mugniesyah, MS selaku dosen pembimbing yang telah
momberikan saran, bimbingan serta bantuannya baik materiil maupun moril.
2. Dengan tulus penulis mengucepkan terima kasih kepada Bapak Ir. Dwi Sadono,
‘MSi selaku Dosen Penguji Utama dan Ibu Ir. Nuraini W. Prasodjo, MS selaku
Dosen Penguji Komisi Pendidikan jurusan Sosial Ekonomi Pertanian.
3. Bapak Ir, Sodikun, MS seleku kepala BIPP serta Bapak dan Ibu Penyuluh
Pertanian baik di BIPP maupun di BPP yang tidak dapat disebut orang-perorang,
alas segala bantuan dan kerjasamanya solama menjadi responden.
4, Seluruh Staf Pusat Studi Wanita (PSW) IPB dibawah pimpinan Ir. Siti Sugiah M.
‘Mugnisyah, MS atas kesabaran dan bantuannya,
5. Keluarga Bapak H. Ir. Machfuud, MS, Kak Pipit dan De’Alvi, terima kasih atas
segalanya,
6, Keluarga Bapak M. Yusuf, Papa, Mama, A’Iyus, Dina, De’Alvira, Melly, Dedi,
Kiki, A’Yudi dan Mas Suryo Rahmadhani atas bantuan doa, moril dan materi.
7. Teman-teman PKP khususnya Pitsi, Upi, Wardah, Heryab, Mba’ Gina, Mas Tata,
Budi, dan Daniel, atas kerjasamanya.
8, Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tak mungkin
disebutkan satu persatu, sekali lagi terima kasih.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, karena itu tulisen ini
ferbuka untuk kritik yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan serta harapan
enulis hasil penelitian ini dapat bermanfuat bagi semua pihak yang memerlukannya.
Bogor, 29 Februari 2000
MARYUNANI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI ..
DAFTAR TABEL
DAETAR GAMBAR_
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.
1.2.Permasalahan
1.3.Tyjuan Penelitian
1.4.Kegunaan Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1-Penyuluhan Pertanian
2.2.Program Penyelenggaraan Penyuluban Pertanian
2.3. Programa Penyuluhan Pertanian
2.4,Rencana Kerja Penyuluh Pertanian
2.5.Kelembagaan Penyuluhan
2.6 Penyuluh Pertanian..
2.7. Motivesi
2.8.Status dan Peranan
BAB Il METODOLOGIPENELITIAN
3.1, Pendekatan Teoritis
3.2.Definisi Operasional
3.3.Pendekatan di Lapangan
BAB IV. PROFIL KELEMBAGAAN PERYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN KARAWANG
4.1 Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian
4.2.Balai Penyaluhan Pertanian
BAB V. PROFIL PENYULUH PERTANIAN
5.1. Sumberdaya Pribadi
$.2.Sumberdaya Keluarga/Rumeh Tangga
5.3.Sumberdaya Lingkungan
BAB VL KINERJA PENYULUHAN PERTANIAN
6.1. Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Satu Bulan
6.2.Akses dan Kontrol Terhadsp Beragam Sumberdaya
BAB VIL VARIABEL YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENYULUH
PERTANIAN
7.1. Hubungan Antara SumberdayaPribad dengan Curahan Waktu dalam Kegistan
Produldif 65
7.2-Hubungan Antara Sunberdaya Keluarga dengan Co Curahan Waktu dalam
Kegiatan Produktif ”
7.3.Hubungan Antara: Sumbordaya Pibai dengan Akses dan Kontrol dalam
Kegiatan Produktif .. . 72
7.4.Hubungan Antara Sumberdaya Keluarga dengan Akses dan Kontrol dalam
Kegiatan Produktif
7
BAB VIL KESIMPULAN DAN SARAN
8.1. Kesimpulan
8.2.Saran
DAETAR PUSTAKA
vill
10.
i
oo
13.
DAFTAR TABEL
Teks
Halaman
Persentase Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Tingkat
Pendidikan, Tahun 1999
Distribusi Curahan Waktu Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin,
Tahun 1999 i
Distribusi Pasangan Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan ‘Fingat
Pendidikan, Tahun 1999
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Golongan
Kepangkatan, Tahun 1999 feats
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Masa Keri,
Tahun 1999
Distribusi Penyulh Pe Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Motivasi, Tatun
1999 aaectiae Spinteerentrscetnnr tetany
Distribusi Penyuluh pertanian Menurut Persepsi Responden Terhadap
Lingkangan Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun 1999
Distribusi Penyuluh pertanian menurut Jenis Kelamin dan s Patspa dalam
Berbagai Kelembagasn, Tahun 1999 :
Distribusi Pasangan Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Jenis
Pekerjaan, Tahun 1999 eine i
Distibusi Ponyuluh Pertanian menurut Jenis Kelemin, Relasi dengan
Pasangan dan Jenis Pekerjann, Tahun 1999
Distribusi Anggota Rumah Tangga Penyuluh Pertanian menurut Jenis
Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 1999
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Kepemilikan
Lahan, Tahun 1999
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Pendapatan
Dalam Sebulan, Tahun 1999 ra
39
41
42
42
43
45
46
a7
4B
48
49
4
15.
16.
17.
18.
19.
20,
an
22.
23.
25,
26.
21.
28.
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Reta-Rata
Pemilikan Ternak, Tahun 1999 : eee +
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Pemilikan Benda
Berharga, Tahun 1999 it
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Keadaan Unum
Rumah Tangga, Tahun 1999 i
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Curahan Waktu
dafam Pelaksanaan Tugas BIPP 30 Hari Terakhir, Tahun 1999
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Curahan Waktu
dalam Pelaksanaan Tugas BPP 30 Hari Terakhir, Tahun 1999 we
Persentase Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Akses dalam
Pelakeanaan Tugas BIPP Selama 30 Hari Terakhir, Tahun 1999
Persentase Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Kontrol dalam
Pelaksanaan Tugas BIPP Selama 30 Hari Terakhir, Tahun 1999...
Persentase Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Akses dalam
Kegiatan BPP Selama 30 Hari Terakhir , Tahun 1999 :
Persentase Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Kontrol dalam
Kegiatan BPP Selama 30 Heri Terakhir , Tahun 1999 to
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan
dan Curahan Waktu ”
DisribosiPenyuluh Pertanian menurat Jenis Kelamin, Golongan
Kepangkatan dan Curahan Waktu i
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelsmin, Masa Kerja dan
‘Curahan Waktu a
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Motivesi dan
‘Curahan Waktu a
Distribusi Penyaluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Kepemilikan Ternak
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Kepemilikan Lahan
dan Curahan Waktu a
49
50
Sst
35
38
61
63
65
66
67
68
69
70
30.
31.
2
uM
35.
36,
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Kepomilikan Benda
Berharga dan Curahan Waktu ...... -
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Tingicat Pendiikan
Akses dan Kontrol dalam Kegiatan Produktif..
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Golongm
Kepangketan, Akses dan Kontrol
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Masa Kerja, Akses
dan Kontrol dalam Kegiatan Produktif ..
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Motivasi, Akses dan
Kontrol dalam Kegiatan Produktif ...... i
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Kepemilikan Tema,
‘Akses dan Kontrol dalam Kegiatan Produltif .
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jonis Kelamin, Kepeiikan {ahan,
Akses dan Kontrol dalam Kegiatan Produktif.
Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Kepemilikan Benda
Berharga, Akses dan Kontrol dalam Kegiatan Produktif.... ae
n
B
4
1S
6
nn
9
80
No
DAFTAR GAMBAR
Deks
Hubungan Antar Faktor dan Variabel dalam Analisis Jender dalam
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pasca SKB Mendagri-Mentan 1996
Lampiran
18
‘Struktur Organisasi Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian core)
Kabupaten Daerah Tingkat I Kerawang
Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten
Karawang
Susunan Organisesi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
‘Karawang Tahun 1999
‘Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Karawang Tahun 1999
‘Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Karawang Tahun 1999
Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Karawang Tahun 1999
Hubungan Kerjasama Antara Balai Informasi dan Ponyuluhan Pe Pertanian
Dengan Dinas/Instansi Lain : ae
Peta Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 1998
90
90
1
92
93
95
96
BABI
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan di Indonesia yang saat ini sedang memasuki Pembangunan
Jangka Panjang II meliputi pembangunan di segala seltor, termasuk sektor pertanian,
Pembangunan pertanian paradigma lama, baik itu berupa Revolusi Hijan atau juga
disebut dengan pembangunan pertanian yang konvensional didukung ofch penelitian
den penyuluhan pertanian yang diciriken oleh sntara Iain : (a) Menekankan pada
komoditi tunggal (misalnya padi), (b) Mengabailan sumberdaya Iahan kering dan
lokal, (c) Bias jender, (d) Mengabaikan pengetahuan dan teknologi petani lokal, (e)
Monekankan pada penelitian yang berbasis pada pusat-pusat penelitian bukan pada
usahatani petani, serta tidek berpusat pada sumberdaya manusia itm sendiri dan
‘mengabaikan kelembagaan-kelembagaan lokal (Reintjes dkk,1992; Chambers,1993,
Uphoff,1993 dalam Mugniesyah, 1999). Pendekatan ini kurang berbuah baik dalam
arti kurang atau tidak menghasilkan pertanian yang berkelanjutan, kerenanya perlu
dikoreksi menjadi paradigma baru, yakni menj
berkelanjutan,
Keberhasilan pembangunan pertanian antara lain ditentukan oleh faktor
manusia dan kelembagasnnya yang merupakan pelaku dalam Kegiatan pembangunan
pertanian. Kelembagaan yang terkait dalam pembangunan pertanian meliputi
pembangunan pertanian
Kelembagaan aparatur, kelembagann tani, termasuk pranata sosial, dan kelembagaan
sosial ekonomi. Masalah kelembagaan dalam sektor pertanian dapat di tinjau dari
dinamika perkembangan kelembagaan penyuluhan pertanian,
Sejak Orde tama dirasakan perkembangan penyuluhan pertanian selalu
mengalami perbaikan melalui berbegai Keputusan presiden, Surat Keputusan
Bersama antar Menteri, Surat Keputusan Menteri, Surat Edaran Menteri serta
keputusan-keputusan ditingkat daerah, Hal ini membuktikan suatu lembaga
penyuluhan pertanian yang bersifat dinamis. Kebijaksanaan terakhir dari pemerintah
pusat adalah ditetapkannya keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam
Negeri No. 54 tahun 1996 tonfang pedoman penyelenggaraan penyuluban pertanian
menggantikan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam
‘Negeri yang sama No. 539/Kpts/LP.120/7/1991.Adanya SKB Mendagri-Mentan 1996
menyebabkan pengalihan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan satuan
administarasi pangkal penyuluh pertanian dari dinas lingkup pertanian kepada Balai
Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP). Dengan adanya kelembagean baru
Penyulthan pertanian maka perln ditelaah kinerja BIPP dan BPP Pasca SKB 1996,
dan secara khusus menyoroti masalah jender. idasaisin jender dalam kelembagaan
Penyuluban menjadi penting mengingat pombangunan pertanian paradigma lama
yang bias jender kurang menghasifkan pertanian yang berkolanjutan,
Kinerja kelembagaan penyuluhan ditentukan oleh beberapa faktor, dalam hal
ini diduga sumberdaya manusia (penyuluh pertanian) merupakan faktor yang sangat
menentukan dimana dalam kelembagaan penyuluhan bekerja sumberdaya manusia
(@enyuluh Pertanian). Adapun jumlah penyuluh Indonesia tahun 1991 diketahui
sebanyak 29.350 orang (Hubeis,1991), jika dilihat berdasarkan jenis kelamin
cenderung lebih banyak penyuluh pria dibandingkan wanita, seperti data di Jawa
Barat dimana jumlah penyuluh pertanian pria dan wanita berturut-turut sebanyal
3.250 orang (86,4 persen) dan 510 orang (13,6 persen) (Rekspitulasi Data
Doptan, 1998).
Selama ini terdapat stereotipi bahwa wanita dominan bekerja dalam kegiatan
domestik, dimana kegiatan domestik ini turut mewarnai kinerja wanita dalan
kegistan produktif dan sosial. Kenyataan menunjukan bahwa penyuluh pertanian juga
mencakup pria dan wanita, demilian juga sasaran penyuluhan pertanian juga
mencakup anggota rumsh tangga pria dan wanita,
Studi-studi selama ini lebih memfokuskan pada tingkat rumah tangga petani,
belum ada studi yang secara khusus menelaah kelembagaan penyuluban pertanian
dengan perspeltif jender. Ini menjadi eangat penting mengingat walaupun dalam
jumlah penyuluh pertanian wanita lebih rendah dari pria, namun apakah kinerjanya
juga menjadi berbeda?
1,2, Perumusan Masalah
Adanya SKB Mendagri-Mentan 1996 menyebabkan pengaiihan pengelolaan
Balai Penyuluhan Pertanian dan satuan administarasi pangkal (satminkal) ponyuluh
pertanian dari dinas lingkup pertanian kepada Balai Informasi dan Penyuluban
Pertanian (BIPP). Dengan adanya kelembagoan baru penyuluhan pertanian maka
perlu ditelash bagaimana profil kelembagaan penyuluban pertanian Pasca SKB
Mendagri-Mentan 1996 dalam hal keduduken, tugas pokok, fungsi, unsur-unsur
organisasi, struktur organisasi, fasilitas, sarang, preserane, Sumberdaya Manusia yang
tersedia? Bagaimana hubungan dan mekanisme kerja kelembagaan penyuluhan pasca
SKB mendagri-Mentan 1996 dengan Dinas/instansi Daerah Tingkat I lingkup
pertanian?
Kinerja kelembagan penyuluhan pertanian ditentukan oleh beberapa faktor,
diduga faktor yang sangat menentukan adalah kinerja sumberdaya manusia (penyuluh
pertanian). Penyuluh pertanian baik pria maupun wanita selain bekerja dilingkungan
BIPP dan BPP mereka juga anggota unit sistem sosial lainaya yaitu keluarga/rumah
tanga dan masyarakat dimana mereka berdomisili. Sehubungan dengan itu akan
dilihat bagaimana pembagaian kerja (kualitatif) dan curahan waktu (kuantitatif) serta
beban kerja antara penyuluh pertanian pria dan penyuluh pertanian wanita dalam
kegiatan produktif ? sejauhmana akses dan kontrol penyuluh pertanian pria dan
wanita dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kegiatan produktif?
Bagaimana sumberdaya pribadi dan keluarga mempengaruhi profil aktivites, akses
dan kontrol penyuluh pertanian pria dan wanita?
1.3. Tujuan Peneiitian
Berdasarkan perumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan
mempelajari:
1) Profi! Balai Informasi Dan Penyuluhan Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian
dalam hal kedudukan, tugas pokok, fungsi, unsur-unsur organisasi, struktur
organisasi, fasilitas, sarana dan prasarana,
2) Hubungan dan mekanisme kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian dengan
Dinas /instansi Daerah Tingkat Il lingkup pertanian,
3) Profil aktivitas khususnya pembagian kerja dan curahan waktu serta beban kerja
antara penyuluh pertanian pri dan wanita dalam kegiatan produktif di BIPP dan
BPP.
4) Akses dan kontrol penyuluh pertanian pria dan wanita dalam mengikuti pelatihan
dan kegiatan produktif.
5) Hubungan sumberdaya pribadi dan keluarga terhadap profil aktivitas, akses dan
kontrol penyuluh pertanian pria dan wanita.
Kegunaan Pen
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi penyuluh pertanian untuk
mengetahui keadaan dirinya sendiri sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja,
Bagi Pemerinvah, penelitian ini bisa dijadikan landasan kebijakan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, serta memberi masukan kepada
Pemerintah Daerah Tingkat I Karawang khususnya Balai Informasi dan Penyuluhan
Pertanian sebagai Satuan Administrasi Pangkal penyuluh pertanian agar dapat lebih
efektif dan efisien dalam pelaksanaan 15 fungsinya. Bagi pevelir, penelitian ini
‘menambah pengalaman dan pengetahuan dibidang penyuluhan pertanian khususnya
jender dalam kelembagean penyuluhan, Bagi sesama peneliti, penelitian ini dapat
digunakan sebagai informasi awal yang bisa menjadi asupan pengetahuan, juga
merupakan dasar bagi penelitian Janjutan mengenai efektifitas hasil penyuluhan
pertanian dengan latar belakang yang sama
BABIT
TINJAUAN PUSTAKA
2.1, Penyuluhan Pertanian
Penyuluhan pertanian menurut SKB Mendagri-Mentan 1996, didefinisikan
sebagai sistem pendidikan Inar sekolah dibidang pertanian untuk petani-nelayan dan
‘olnarganya serta angola masyarskat pertanian, agar dinamika dan kemampuannya
dalam memperbaiki kehid Penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat
berkembang, schingga dapat meningkatken peranan dan peran sertanya dalam
pembangunan pertanian.
Menyimak pengertian ini tampak jelas bshwa penyuluhan pertanian
membawa misi pendidikan bagi petani-nelayan dan keluarganya untuk mampu
membangua dinamika, berswadaya dan mandiri dalam memperbaiki kebidupan dan
penghidupannya sohinggn mampu berkiprah dalam pembangunan
2.2, Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri-Mentan 1996 menjelaskan
Pengertian Program Penyuluhan Pertanian sebagai suatu rencana kegiatan
Pendayagunaan segala sumberdaya penyuluhan pertanian di berbagei tingkat
berdasarkan prinsip kerjasama yang serasi, selaras dan terpadu antara masyarakat
Petani nelayan dengan pemerintah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah
Pusat dalam rangka mewujudkan kondisi yang sebaik-baiknya bagi keberhasilan
Program pembangunan pertanisn (Anonimous, 1996).
Penyusunan program menurut Wiriaatmaja (1986) peru momporbatiken
azas-azas berdasarkan analisa falta-falkta situasi, masalah dan kebutuhan yang
dirasakon petani, pencapaien tyjuan, fleksibel, seimbang, mempunyai rencana Kerja
yang jelas, kontinyu, proses pengajaran dan pembimbingan, koordinasi, dan dapat
dievaluasi.
2.3, Programa Penyuluhan Pertanian
Programa penyuluhan pertanian adalah rencana kegistan penyuluban
pertanian (ahunan yang dijadiken acuan kerja para penyuluh pertanian. Mengawali
Penelusuran akan pengertian programa ponyuluhan pertanian dalam era Revitalisesi
ini, maka yang menjadi landasan hukumnya ialah SKB Mendagri-Mentan nomor 56
abun 1996 dan Nomor 301/Kpts/LP.126/4/96 tentang pedoman penyelenggaraan
penyuluban pertanian. Programa Penyuluhan Pertanian diattikan sebagai rencana
istan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani-nelayan dan
masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian
yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalch-mesalah
dan altematif pemecabannya serta cara mencapai tujuan yang disusun secara
partisipatis, sistematis dan tertulis setiap tahun (Anonimous, 1996).
2.4, Rencana Kerja Penyuluh Pertanian
Rencana kerja adalah suatu acara kegiatan-kegiatan yang disusun sedemikian
mupa sehingga memungkinkan pelaksanaan program secara efisien, menyangkut soal-
soal bagaimans, kapan, dimana dan oleh sigpa pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang
ditetapkan dalam program itu (Wiriaatmaja .1986).
Berdasarkan SKB Mendagri-Mentan 1996 rencana kerja penyuluhan pertanian
adalah jadwel kegiatan yang disusun oleh para penyuluh pertanian berdasorken
Programa penyuluhan pertanian setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu
disiapkan dalam berinteraksi dengan petani-nelayan (Anonimous, 1996).
Keberbasilan Penyuluhan Pertanian difentukan oleh unsur-unsur penyuluhan
Pertanian yang tidak dapat dipisahkan karena semua tunjang menunjang dalam satu
aktivitas. Unsur-unsur tersebut adalah: (1) Penyuluh pertanian (sumber). (2) Saseran
penyuluhan pertanian. (3) Metode penyuluban pertanian. (4) Media penyuluhan
pertanian. (5) Materi penyuluhan pertanian. (6) Waktu penyuluhan pertanian. (7)
‘Tempat penyuluhan pertanian (Kartasapoetra. 1951).
2,5. Kelembagaan Penyuluhan
Apabila penyuluhan pertanian kita artikan sebagai istilah yang berarti sistem,
program atau perangkat instrumental (piranti) untuk menyelenggarakan karya
pembaharuan pertanian, make pengertiannya dapat ditinjau dari sudut pandang
kelembagazn maupun perorangan. Dari sudut kelembagaan penyuluhan pertanian
adalah organisasi dan pranata atau wadah pengelolaan interaksi pembelajaran yang
melibatkan petani dengan agen pembaharu untuk menghasilkan pembaharuan
pertanian . Dari sudut pandang perorangan penyuluhan pertanian berarti profesi atau
jabatan dalam mengelola proses pembaharuan yang berporos kepada pembentukan
tekad, keberdayaaa, kemandirian serta pengetahuan dan keterampitan petani melalui
proses belajar dengan melakukan (“learning by doing”). Dalam dunia penyuluban
pertanian, jargon pembaharuan itu berarti perubahan perilaku dari individu, keluarga,
kelompok masyarakat dan komunitas (Adjid. 1998).
Balai Informasi Penyuluban Pertanian merupakan lembaga baru penyuluban
pertanian di Indonesia sejak diberlakukannya SKB Mendagri-Mentan 1996. Mengacu
pada pendapat Koentjaraningrat (1974) bahwa lembaga kemasyarakatan atau lembaga
sosial merupakan serangkaian kegiatan tertentu, berpusat pada suatu kelakuan berpola
yang mantap, bersama-sama dengan sistem norma dan tata kelekuan serta peralatan
fisikeya yang dipakai juga orang-orang yang melakukannya,
Gillin dan Gillin dalam Sockanto (1990) melihat lembaga kemasyarakatan
bahwa lembaga kemasyarakatan adalah organisasi
pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas
kemasyarakatan dan hasil-hasilaya, mompunyai satu tingkat kekekalan tertentu,
mempunyai beberapa tujuan, mempunyai alat-alat perlengkapan untuk mencepai
berdasarkan ciri yang dimil
tujuan, mempunyai lambang-lambang dan mempunyai tradisi tertulis maupun tidak
tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dam lain-lain.
Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan satu
Kesatuan fungsional (Soekanto, 1990). Sebagai sarana untuk mencapai tujuan
organisasi mempunyai tiga ciri pokok yaitu : Pembagian pekerjaan (tugas), pusat ata
Pusat-pusat kegiatan dan penggantian petugas (Etzioni dalam Anonimous (1993)),
Dengan demikian segenap pekerjaan yang harus di lakukan oleh seluruh pendukung
organisasi untuk mencapai tujuannya dibagikan kepada semua unit dan personalia
yang ada. Agar tujuan dapat dicapai dengan tepat maka unit organisasi dan petugas
harus menyesuaikan diri terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dengan
kata Jain, organisasi menjadi efektif jika acuan tugas dijadikan kriteria untuk
menentukan petugas pelaksananya Dalam pada itu organisasi mempunyai pusat dan
pusat-pusat kendali yang berfungsi sebagai pengambil keputusan, pengawas dan
Penilai polsksanaan tugas-tugas organisasi, efektifitas pengendalian tersebut
dihasilkan oleh distribusi kewenangan organisasi diantara pusat-pusat kendali yang
disusun secara hierarkhis disekitar pusat kendali utama Kesinambungan dan
Pembaharuan organisasi dalam rangka tujuannya ditentukan pula oleh mobilitas
tenaga atar petugas didalamnya, artinya, diantara tenaga-tenaga yang ada
Gilaksanskan pergantian tugas berdasarkan kebutuhan dan kecocokan tugas dengan
petugasnya Mobilitas diartikan pula sebagai pergantian petugas lama dengan
petugas yang didatangkan kedalam organisasi . Dengan demikian bekerjanya
organisasi ditentukan oleh tiga tiga cirinya yaitu ; Pembagian tugas, struktur
kewenangannya dan mobilites tenaga. sedangakan keberhasilan organisasi ditentukan
oleh daya tanggap (respon) terhadap lingkungannya disatu pihak dan dipihak lainnya
ditentukan oleh efektifitas kerja organisasi tersebut (Anonimous, 1993).
2.6. Penyuluh pertanian
Berdasarkan SKB Mendagri-Mentan 1996, penyuluh pertanian adalah
pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluban
pertanian secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup
pertanian (Anonimous, 1996).
2.6.1. Kedudukan dan Tugas Pokok
Penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelakeana teknis fungsional
penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.
Penyuluh pertanian yang dimaksud hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah
berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Tugas pokok penyulub pertanian adalah
~ menyiapkan, molaksanakan dan melaporkan kegiatan penyuluhan_ pertanian.
(Anonimous, 1999), Berdasarkan fungsi dan tugasnya itu, Kartasapoetra (1994)
membedakan penyuluh pertanian menjadi Penyuluh yang langsung berhubungan
dengan para petani dan Penyuluh yang tidak langsung berhubungan dengan para
petani.
2.6.2. Jenjang Jabatan Dan Pangkat
Berdasarkan jabatan fungsional, penyuluh pertanian dibagi menjadi dua yaitu
penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli. Penyuluh pertanian trampil
adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian keterampilan yang dalam pelaksanaan
pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu sedangkan penyuluh
pertanian abli adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian keablian yang dalam
pelaksanaan pekerjaamya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan
teknik analisis tertentu, Jabatan fungsional penyuluh pertenian, jenjang pamgkat dan
Golongan dari yang terendah sampai dengan tertinggi terdiri atas (Anonimous, 1999):
1. Penyuluh Pertanian Trampil :
1.1-Penyuluh Pertanian Pelaksana terdiri deri : (a) Pengatur Muda Tingkat I
(Golongan ruang Tb). (b) Pengatur ( Golongan ruang Ic). (c) Pengatur
‘Tingkat I ( Golongan ruang I/d).
1.2-Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan terdiri dari : (2) Penata Muda
(Golongan ruang TV/a). (b) Penata Muda Tingkat I (Golongan ruang I/b).
1.3 Penyuluh Pertanian Penyelia terdiri dari : (a) Penata (Golongan ruang IV/c)
(b) Penata Tingkat I (Golongan Ruang IIV/d)
2. Penyuluh Pertanian Abli
2.1.Penyuluh Pertanian Pertama terdiri dari : (a) Penata muda (Golongan ruang
IlV/a). (b) Penata Muda Tingkat I (Golongan ruang IVb).
2.2.Penyuluh Pertanian Muda terdiri dari : (a) Penata (Golongan ruang TIV/c). (b)
Ponata Tingkat I ( Golongan Ruang IIV/d)
2.3,Penyuluh Pertanian madya terdiri dari -(a) Pembina (Golongan ruang VV/a).
(b) Pembina Tingkat ( Golongan Ruang IV/b), (c) Pembina Utama muda
(Golongan ruang IV/c).
2.4.Penyuluh Pertanian Utama tordiri dari’: (a) Pembina Utama Madya (Golongan
Ruang IV/d). (b) Pembina Utama (Golongan Ruang IV/e).
2.6.3. Rincian Kegiatan Dan Unsur Yang Dinilai Dalam Memberikan
Anghka Kredit
Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari Unsur
Utama dan Unsur Penunjang Unsur Utama adalah kegiatan yang merupakan
pelaksanaan tugas pokok penyuluhan pertanian, terdiri atas (Anonimous, 1999):
. Pendidikan, meliputi ; (a) Pendidikan sekolah dan memperoleh Tjazab/gelar.
(b)Pendidikan dan Pelatihan kedinasan dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
Persiapan Penyuluhan Pertanian, meliputi: (a) Identifikasi potensi wilayah dan
agrosistem, serta kebutuhan teknologi pertanian. (b) Penyusunan Programa
x
Penyuluhan pertanian, (c) Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian.
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, meliputi : (a) Penyusunan materi
penyuluhan pertanian. (b) Penerapan metode penyuluhan pertanian. (c)
Pengembangan swadaya dan swakerya petani-nelayan
=
Evaluasi dan Pelaporan, meliputi : (a) Evaluasi dan peleporan hasil pelaksanaan
penyuluban pertanian. (b) Evaluasi dampak penyuluben pertanian.
. Pengembangan Penynluhan Pertanian, meliputi : (a) Penyusunan pedoman/
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan pertanian. (b)Perumusan kajian
arah Kebijakeanaan pengembangan penuyuluhan pertanian, (c)Pengembangan
metode / sistem kerja penyuluhan pertanian.
Pengembangan Profesi, moliputi: (a) Kegiatan karya tulis/karya ilmish dibidang
penyuluhan pertanian, (b)Penerjemahan/penyaduran buku-buku dan bahan-bahan
lain dibidang penyuluhan pertanian. (c)Bimbingan bagi penyuluh pertanian
dibawah jenjang jabatannya,
Unsur Penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok
Penyuluh Pertanian yang meliputi : (1) Seminar/lokakarya dibidang pertanian,
2) Keanggotaan Tim penilai jabatan fingsional penyuluh pertanian;
(3) Penghargaan/tanda jasa; (4) Pangajaran/pelatihan pada diklat; (5) Keanggotaan
Organisasi profesi; (6) Gelar kesarjanaan lainnya.
2.6.4. Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
Untuk dapat diangkat dalam jabatan penyuluh pertanian terampil atau
ponyuluh pertanian abli, seorang pegawai negeri sipit haruy memenuhi angka kredit
kcumulatif'minimal yang ditentukan.
Pogawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan
penyuluban pertanian Trampil harus memenuhi syarat sebagai berileut:
1. Berijazah serendah-rendahnye Diploma IMI dibidang pertanian;
2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang I/b.
3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dibidang penyuluhan
pertanian dan memperoleh sertifikat tanda lulus; dan
4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangaya
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakkir.
Pogawai negeri sipil yang diangkat periama kali dalam jabstan penyuluh
pertanian ahli, harus memenuhi eyarat sebagai berikut :
1. Berijazah serendatr-rendahaya Sarjana/ Diploma IV dibidang pertanian.
2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Mude, golongan ruang Il/a
3. Toleh mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kedinasan dibidang penyuluhan
pertanian dan memperolch sertifikat tanda lulus; dan
4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjam dalam DP3 sekurang-kurangnya
borniali baik dalam 1 (satu) tahun terakbir,
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam jabatan
penyuluh pertanian Trampil atax Penyuluh Pertanian Ali dapat dipertimbangkan
dengan ketentuan bahwa disamping harus memenuhi syarst diatas, diharusken pula
memenubi syarat sebagai berikut : (a) Memiliki pengalaman dalam kegiatan
penyuluhan pertanian sekurang-kurangnya 2 tahun; (b) Berusia sotinggi-tingginya 5
ima) tahun sobelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang
didudukinya; (c) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-
‘urangaya bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ( Anonimous, 1999),
2.7. Motivasi
‘Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat dan dorongan kerja
dimana tinggi rendahnya motivasi kerja sescorang akan menentukan besar keciluya
Prestasi ker
itu sendiri, Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi
seseorang, yaitu kemampuan individy dan pemahaman tentang perilaku untuk
mencapai prestasi yang maksimal, disebut persepsi peranan. Dimana antara motivasi,
kemampuan dan persepsi peranan merupakan satu kesafuan yang saling berinteraksi.
‘Tidak ada organisasi yang dapat berhasi! tanpa tingkat komitmen dan usaha
tertentu dari para anggotanya. Porter dan Miles dalam Stoner (1994) berpendapat
bahwa Pandangan Sistem mengenai motivasi sangat bermanfaat bagi para manajer.
Yang mereka maksudken dengan suatu pandangan sistem adalah selurub rangkaian,
atau sistem, kekuatan yang beroperasi pada karyawan harus dipertimbangkan
sebelum motivasi dan perilaku karyawan dipahami secara memadai. Sistem terdiri
dari 3 perangkat variabel yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi yaitu :
1. Karakteristik individu adalsh minat, sikap dan kebutuhan yang dibawa seseorang
kedalam situasi kerja.
2. Karatteristik Pekerjaan adalah sifat dari tugas keryawan dan meliputi jumlah
tanggung jawab, macam tugas, dan tingkat kepuasan yang orang peroleh dari
karakteristik pekerjaan itu sendiri.
3. Karakteristik Situasi Kerja adalah faktor-faktor dalam lingkungan kerja seseorang.
Terdiri dari dua kategori : tindakan, kebijakan, serta kultur organisasi sebagai
keseluruhannya dan lingkungan kerja terdekat.
12
2.8. Status Dan Peranan
Untuk melihat relasi individu dengan lembaga, Soelaeman (1992)
mengartikan lembaga sebagai norma-norma yang berinteraki disekitar suatu fongsi
maxyarakat yang penting Dengan demikian, ada segi kultural berupa norma-norma
ddan juga ada segi strukturalnya berupa berbagai peranan sosial. Posisi dan peranan
induividu dalam lembaga sosial sudah dibakukan berdasarkan moral, adat atau hukum
yang berlaku, Individualitasnya ditanggung dalam struktur hubungan kelembagaan.
Individe bertingkah laku spesifik, berbeda dengan !ainnya.
2.8.1 Kedudukan (Status)
Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu
kelompok sosial. Masyarakat pada umumnya mongembangken dua macam
kedudukan yaitu (Soekanto,1990) : (a) Ascribed-Status, yaitu kedudukan seseorang
dalam masyarakat tanpa memperhstikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan
kemampuan. Kedudukan tersebut diperolch karena kelahiran; (b) Achived Status,
adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja;
(©) Assigned-Status yang merupakan kedudukan yang diberikan (Polak dalam
Soekanto, 1990).
2.8.2.Peranan (Role)
Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi, Peranan (role) merupakan aspek dinamis
kedudukan (Status). Apabila seseorang molaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
dengan kedudukennya maka dia menjalankan suatu peranan (Soekanto,1990).
Menurut Edholm, Harris dan Young (1977); Beneria (1979); dalam
‘Mugniesyah (1995 (a)) peranan sescorang dapat dilihat dalam kegiatan produksi dan
reproduksi (domestik). Kegiatan reproduksi mencakup reproduksi sosial, reproduksi
tenaga kerja dan reproduksi biologis. Reproduksi sosial adalah keadaan-keadaan
untuk mempertahankan suatu sistem sosial. Reproduksi tenaga kerja maksudnya
adalah proses dimana anggota rumah tangga menjadi tenaga kerja yang mencakup
pada kegiatan perawatan sehari-hari pekerja dan calon tenaga kerja serta juga alokasi
pelaku-pelaku kedalam berbagai posisi didalam proses pekerjaannya. Berbeda dari
kedua jenis kegiatan reproduksi itu, reproduksi biologis menunjuk pada proses
perkembangan fisik umat manusia. Kegiatan produktif’ mencakup semua kegiatan
yang berhubungan dengan pencaharian nafkah yang sering disebut sebagai kegiatan
bekerja yang menghasilkan, baik berupa natura (barang-barang), wang tunai (cash)
maupun stafus sosial.
2.9, Jender Dan Analisis Jender
Konsep jender diartikan sebagai perbedann-perbedaan (dikotomi) sifat wanita
dan pria yang tidak mendasarkan perbedasn biologis semata akan tetapi lebih pada
sistem nilai budaya dan etruktur sosial yang menentukan peranan dan status wanita
dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara (Instraw dalam
‘Mugniesyah ,1995 (b)). Disadari atau tidak, nilai jender yang terinternalisasi dalam
kehidupan keseharian kita selama ini telah memfusilitasi terciptanya
ketidakadilan/ketimpangan jender, yang secaralangsung — menyebebkan
ketidaksamaan antara pria dan wanita atau diskriminasi terhadap wanita dalam
berbagai dimensi kebidupan.
Dalam sejarah perkembangan hubungan antsra pria dan wanits, perbedaan
Jjender tefsh menciptakan suatu hubungan yang tidak adil, menindas serta
mendominasi antara kedua jenis kelamin tersebut. Bentuk manifestasi dalam berbagai
bentuk yaitu : (2) Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi. (b) Subordinasi
‘atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik. (c) Stereotyping dan
diskriminasi atau pelabelan negatif. (4) Kekerasan (violence). (0) Bekerja lebih
panjang dan lebih banyak (double burden). (£) Sosialisasi ideologi nilai peran jender.
‘Manifestasi ketidakadilan jender tersebut masing-masing tidak bisa dipisablan, saling
berkaifon dan mempengaruhi secare dielektika (Fakih,1998).
Sehubungan dengan itu perlu dilakukan analisis jender. Analisis jender
adalah pengujuian secara sistematis terhadap peranan-peranan dan proses-proses yang,
memusatkan perhatian pada ketidakseimbangan kekuasaan, kesejahteraan dan beban
kerja antara pria dan wanita disemua masyarakat. Dalam monganalisis jender,
terdapat beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan seperti disarankan “Borgen
Conference On Gender ‘Training And Development Planning’, 1991 dalam
‘Mugniesyah (1995 ) yaitu:
1. Profil Aktivitas, yang mencerminkan siapa melakukan apa ? Pertanyaan ini
dityjukan untuk mempelajari pembagian kerja (lcualitaif) dan curahan waktu
(kuantitatif) serta beban kerja.
2. Profil Akses dan Kontrol yang berkenaan dengan siapa yang mempunyai akses
dan kontrol terhadap Sumberdaya dan manfaat ? Pertanyaan ini uaak
mempelajari sejauh mana akses pria dan wanita terhadap kekayaan, benda-benda
berharga, informasi, kredit, teknologi serta hak-hak dalam pengambilan keputusan
yang berkenaan dengan sumberdaya pribadi dan publik.
3. Analisis faktor-faktor yang mempengarubi aktifitas akses dan kontrol, atau faktor-
faktor apa yang mempengaruhi pengaturan jender tersebut ? Pertanyaan ini
ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor budaya, hukum, kebijaksanaan
ekonomi dan politik yang mempengaruhi konstruksi jender dan bagaimana hal-hal
tersebut bisa berubah serta mana yang dapat dimanipulasi
4. Bagaimana sumberdaya pribadi dan publik didistribusiken dan siapa yang
memperoleh apa dati pendistribusian tersebut ? Pertanyaan ini memusatkan
perhatian untuk memperoleh informasi struktur-struktur kelembagaan yang
digunakan, tingkat efisiensi dan keadilanya serta bagaimana membuat
kelembagaan tersebut lebih responsif terhadap wanita dan pria.
BAB DIL
METODOLOGI PENELITIAN
3.1, Pendekatan Teoritis
‘Terdapat 5 variabel utama dalam mewujudkan pembangunan, yaitu daya
duling sumberdaya alam, teknologi, modal, tenaga kerja dan kelembagaan (Hidayat
dalam Anonimous, 1996). Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era
globalisasi dan agribienis harus dihadapi oleh penyluh pertanian sebagai ujung
tombak pembangunan pertanien dengan cara meningkatkan dan mengembangkan
kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan sifat, arah dan tujuan penyuluhan
pertanian sorta tuntutan kebutuhan belajar-mengajar para petani-nelayan dalam
pengembangan usahanya. Kedua hal pokok yang dijadikan pertimbangan kelahiran
kebijakan pemerintah berupa SKB Mendagri-Mentan 1996 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ini dijabarkan lebih lanjut dalam Program
Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
Perubahan kelembagaan penyuluhan pertanian, menyebabkan pula perubahan
terhadap jalur birokrasi, struktur organisasi dan tugas pokok penyuluh pertanian.
Perubahan jalur birokrasi akan dilihat dari hubungan kerjasama antara kelembagaan
penyuluhan baru (BIPP) dengan pemerintah daerah tingkat IT dan instansi daerah
lingkup pertanian khususnya dengan dinas subsektor. Perubahan struktur organisasi
penyuluhan pertanian digambarkan dalam profil kelembagaan penyuluhan pertanian
secara deskriptif dengan mengacu pada data sekunder dan primer terbaru. Dalam
kaitannya dengan tugas pokok penyuluh pertanian akan dilihat pengaruh perubahan
tugas penyuluh pertanian yang dulunya monovalen menjadi polivalen terhadap
kinerja penyuluh pertanian.
Dalam meleksanakan tugas pokoknya, penyuluh pertanian harus mempunyai
faktor pendukung yaitu sumberdaya pribadi dan sumberdaya keluarga. Mengingat
sumberdaya manusia (penyulub pertanian) terdiri dari pria dan wanita, maka kedua
faktor pendukung tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai jender. Untuk melihat sejauh
mana nilai jender mompengaruhi kinerje penyuluhan pertanian digunakan analisis
ender. Ditingkat kelembagaan anslisis jender menyoroti (a) Pembagian kerja,
curalan waltu serta beban kerja antara penyuluk pertanian pria dan penyuluh
Pertanian wanita dalam kegiatan produltif pada beragam kegiatan dalam 1 bulan
terakhir. dan (b) akses dan kontrol penyuluh pertanion pria dan wanita yang
mencakup peluang mengikuti pelaksanaan tugas dan fingsinya,
‘Untuk mengidentifikasi faltor-faktor yang mempengaruhi pengaturan jender
fersebut akan dilibat dari hubungan antara sumberdaya manusia dan sumberdaya
Keluarga dengan profil aktivitas, akses dan kontrol dalam kegiatan produltif
mompengaruhi kinerja penyuluh pertanian dan selanjutaya mempengaruhi kinerja
kelembagaan penyuluhan pertanian,
Dengan mengacu pada berbagai pendekatan diatas maka hubungan antar
faktor dan variabel dalam studi Analisis Sender Dalam Kelembagaan Penyulukan
Pertanian ini digambarkan seperti Bagan 1.
ae Piseintai Dac Kerawang
Karawang bcted
KELEMBAGAAN PENYULUBAN PERTANIAN
Berdasarkan SKB Mendagrt-Mentan No. 54 Tahun 1996 dan No. 301/KptvLP.A204/96
Balai Informasi Dan Penyuluban Pertanian:
(Sasori Fein]
Kinerja Penyuluh Pertanian
1. Profil Aktivitas
a) Pembagian Kerja dalam kegiatan produktif
b) Curahan Waktu dalam kegiatan produktif
2. Profil Akses Dan Kontrol
a) Pengambilan keputusan dalam kegiatan produktif!
‘Sumberdaya Pribadi
1. Tingkat Pondidikan
2. Masa Kerja
i. Gotongan Kepangkatan
4. Motivasi
Keterangan
= Analisa Kuantitatif
Bagan 1. Hubungan Antar Faktor Dan Variabel Dalam Analisis Jender Dalam
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pasca SKB Mendagri-Mentan 1996
18
3.2, Definisi Operasional
1. Tingkat Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai
responden, dikelompokan dalam Tingkat Pendidikan rendah (SMA/sederajat) dan
Tingkat Pendidikan tinggi (Diploma 3, Sarjana, dan Pasca-sarjana).
2. Motivasi adalah sesvatu yang menimbulkan semangat dan dorongan kerja dimana
tinggi rondahnya motivasi kerja seseormg akan menentukan besar kecilnya
prestasi kerja itu sondiri. Dalam hal ini motivasi dibagi meniadi motivasi untuk
mengamalkan ilmu, Berbakti pada negara, mencari uang, pengembanan Karier, dan
kombinasi dari keempatnya. Dalam hal ini motivasi dikelompokan dalam motivasi
rendah (Motivasi untuk diri sendiri) dan motivasi tinggi (motivasi untuk negara
dan kombinasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakaUnegara).
3. Masa Kerja adalah lama responden bekerja pada penyelenggaraan penyuluhan
pertanian yang dikelompokan menjadi mase kerja rendah(bekerja kurang dari 20
tahun) dan masa kerja tinggi (bekerja lebih atau sama dengan 20 tahun).
4. Golongan kepangkstan adalah jabstan yang membedakan pekerjaan dan gaji
seseorang, yang dikelompokan menjadi golongan kepangkatan rendah (honorer
dan golongan I) dan golongan kepangkatan tinggi (golongan II).
5. Partisipasi dalam beragam kelembagaan adalah akses penyuluh pertanian
dalam beragam kelembagaan baik formal manpun informal. Partisipasi penyuluh
pertanian digolongkan rendah apabila mengikuti berbagai kelembagaan Kurang
dari SO persen, dan tinggi jika lebih atau sama dengan SO persen
6. Kepemilikan Iahan adalah Iuasan tanah yang dimiliki dan digunakan sebagai
usabatani yang golongkan kedalam rendah apabila luas Ishan yang dimiliki kurang
dari 1000 m? dari luas rata-rata dan tinggi apabila sama dengan atau lebih dari
1000 m” dari luas rata-rata.
19
3.2, Definisi Operasional
1. Tingkat Pendidikan adaleh jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai
responden, dikelompokan dalam Tingkat Pendidikan rendah (SMA/sederajat) dan
‘Tingkat Pendidikan tinggi (Diploma 3, Sarjana, dan Pasca-sarjana),
2. Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat dan dorongan kerja dimana
tinggi rendahnya motivasi kerja seseorang akan menentukan besar kecilnya
prestasi kerja itu sendiri. Dalam hal ini motivasi dibagi menjadi motivasi untuk
mengamalkan ilmu, Berbakti pada negara, mencari uang, pengembanan karier, dan
kombinasi dari keempatnya. Dalam hal ini motivasi dikelompokan dalam motivasi
rendah (Motivasi untuk diri sendiri) dan motivasi tinggi (motivasi untuk negara
dan kombinasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat/negara).
3. Masa Kerja adalah lama responden bekerja pada penyelenggaraan penyuluban
pertanian yang dikelompokan menjadi masa kerja rendah(bekerja kurang dari 20
tahun) dan masa kerja tinggi (bekerja Jebih atau sama dengan 20 tahun).
4. Golongan kepangkatan adalah jabatan yang membedaken pekerjaan dan paji
seseorang, yang dikelompokan menjadi golongan kepangkatan rendah (houorer
dan golongan II) dan golongan kepangkatan tinggi (golongan II).
S. Partisipasi dalam beragam kelembagaan adalah akses penyuluh pertanian
dalam beragam kelembagaan baik formal maupun informal. Pertisipasi penyuluh
pertanian digolongkan rendah apabila mengikuti berbagai kelembagaan kurang
dari 50 persen, dan tinggi jika lebih atau sama dengan 50 persen
6. Kepemilikan laban adalah Iuasan tanah yang dimiliki dan digunakan sebagai
usahatani yang golongkan kedalam rendah apabila luas lahan yang dimiliki kurang
dari 1000 m? dari luas rata-rata dan tinggi apabila sama dengan atau lebih dari
1000 m? dari Iuas rata-rata
19
7. Kepemilikan ternak adaish jumlah ternak yang dimiliki saat ini, yang golongkan
kedalam rendah apabila harga temak yang dimiliki kurang dari 50 point dan tinggi
apabila sama dengan atau lebih dari 50 point.
8. Kepemilikan benda-henda herharga adalah jumlah sumberdaya fisik yang
dimitiki saat ini yang terdiri dari benda-benda produktif (usahatani) dan benda
rumah tanga. yang golongkan kedalam rendah apabila memiliki kurang dari SO
point dan tinggi apabila sama dengan atan lebih dari 50 point.
9. Pembagian kerja (kualitatif) dalam kegiatan produktif. Dominasi terhadap
suatu kegiatan yang diukur berdasarkan persentase terbesar_antara penyuluh pria
dongan penyuluh wanita
10,Curahan waktu (kuantitatif) serta beban kerja dalam kegiatan produktif
yang dihitung dalam jam kerja terhadap kegiatan 30 hari terakhir. Curahan waktu
digolongkan tinggi bila jam kerja yang dikeluarkan lebih atau sama dengan 70 Jam
Kerja (JK) dan rendah bila kurang dari 70 Jam Kerja (JK)
LLAkses, adalah peluang yang bisa diperoleh wanita dan pria untuk melakukan
sesuatu. kegiatan produktif untuk mendapatkan angka kredit dalam kegiatan
produktif selama 30 hari terakhir. Akses dibedakan menjadi akses terhadap tugas
pokoknya yang dikategorikan tinggi jika mencapai lebih atan sama dengan 50
persen dan rendah kurang dari 50 persen, dan diluar tugas pokoknya yang --
dikategorikan tinggi jika mencapai lebih atan sama dengan SO persen dan rendah
kurang dari 50 porsen terhadap total tugas dan fungsinya
12.Kontrol, menyangkut sejauh mana wanita dan pria mempunyai kekuasaan atau
kemampuan dalam proses pengambilan keputusan dalam —merenomakaan.
Melakukan kegistan produktif selama 30 hari torakhir. kontrol dibedakan menjadi
kontrol terhadap fugas pokoknya yang dikalegorikan tinggi jika mencapai lebih
atau sama dengan $0 persen dan rendah kurang dari 50 persen, dan diluar tugas
pokoknya yang dikategorikan tinggi
‘a mencapai lebih atau sama dengan 50
persen dan rendah karang dari 50 persen ferhadap total tagas dan fingsinya.
Informasi yang akan diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan kuisioner dan hasil
observasi/pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh pertenian di
BIPP dan di BPP, yang mencakup sistem kerja penyuluh pertanian di BIPP dan BPP ,
status dan peranan penyuluh pertanian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, profil
aldifitas penyuluh pertanian (pembagian kerja dan curehan waktu) dalam kegiatan
produktif, Profil Akses dalam memperoleh angka kredit dan Kontrol dalam hak-hak
pengambilan keputusan kegiatan produktif' sclama 30 hari terakhir, Sumberdaya
Pribadi (tingkat pendidikan, masa kerja, motivasi, , golongan kepangkatan dan
partisipasi dalam beragam kelembagasn), Sumberdaya keluarga. (kepemilikan laban
usahatani, pemilikan benda berharga, dan pemilikan ternak), dan hubungan kerjasama
antara BIPP, BPP, PEMDA Tingkat II Karawang, Dinas Subsektor dan
instansi/lembaga lain.
Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan Dinas
lingkup pertanian, PEMDA. Tingkat 1 Karawang, Badan Perencana Pembangunan
PEMDA Tingkat II Karawang, BIPP dan BPP.
Pengolahan dan analisis data akan dilekukan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Mengedit (editing) untuk memeriksa atau menilai kesempurnam data, apakah
semua data yang dikumpulkan sudsh sesuai dengan apa yang direncanakan
semuta, sehingga bila ada penyimpangan dari yang telah ditetapkan dapat segera.
diperbaiki.
2. Pengolahan data dilakuken dengan cara tabulasi sederhana yaitu proses
pemindahan data dari kuesioner lembar data sementara, yang selanjutnya
disajikan dalam kerangka tabel yang dipersiapkan.
3. Data kualitatif yang terkumpul melalui wawancara mendalam dianalisis secara
deskriptif sementara data yang dikumpulkan dalam survey diolah dengan
menggunakan program microsoft exel kedalam tabel frekuensi dan tabel silang,
untuk kemudian dianalisis dengan menghubungkannya dengan analisis jender.
BAB IV
PROFIL BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN
DAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN KARAWANG
Pedoman Penyelenggerann Penyuluhan Pertanian yang diatur dalam
Keputusan Bersama Mendagri-Mentan No, 65 tahun 1991 dan No,
S39/Kpts/LP.120/7/1991 sudah tidak sesnai lagi dengan perkembangan penyuluhan
pertanian Penyuluh pertanien yang bekerja secara Monovalen tidak akan bisa
terlepas dari persoalan di luar sektor kerjanya, demikian pula dengan administrasi
pangkal periyuluh pertanian yang berada di tiap Dinas-Dinas Sub Sektor menjadikan
penyuluh pertanian terkotak-kotak dan ditambah lagi dengan pekerjaan ganda yang
ditangeung penyuluh pertanian membust penyuluban pertanian tidak optimal dan
mengelami stagnansi (lampiran 3,4,5 dan 6). Kelembagaan penyvluhan yang sangat
berperan dalam menyebarluaskan informasi pertanian yaitu Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP) juga mengalami stagnansi karena sedikit sekali aktivitas penyuluhan
yang terkonsentrasi disana.
Dalam rangka menumbuh kembangkan swadaya dan peran serta petani-
nelayan dalam kegiatan usaha dan pembangunan pertanian pemerintal mengeluarkast
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 tahun 1996
dan Nomor 301/Kpts/p/120/4/96 tertanggal 10 April 1996 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Penyuluban Pertanian dan Petunjuk Pelaksanaannya yang
membawa perubahan bagi penyuluhan pertanian dimana urusan penyuluhan pertanian
diserahkan menjadi urusan rumah tangga dgerah dan meny: kembali penyuhih
pertanian yang dulunya terkotak-kotak didinas-dinas sub sektor dengan cara
membentuk Bulai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) sebagai Satuan
Administrasi Pangkal Penyufuh pertanian yang dalam melaksanakan tugas dibantu
olch Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Instalasi/sarana kegiatan penyuluhan
pertanian di Kecarmatan.
a3
4.1, Balai Informasi Dan Penyuluhan Pertanian
4.11. Kedudukan
Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Karawang dibentuk
berdasarkan keputusan Bupati Daerah Tingkat If Karawang No. 2 tahua 1997
tertanggal 20 Maret 1997 yang dilegitimasi dengan Keputusan Mendagri No. 35
Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Balai
Informasi dan Penyuluhan Pertanian , namun secara operasional baru berjalan pada
tanggal 4 Agustus 1997. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah unit kerja
organik penyuluh sebagai pelaksana teknik operasional Pemerintah Daerah Tingkat IT
dibidang penyutuhan pertanian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati Kepala Daerah melalui pejabat yang ditunjuk olehnya.
4.12, Tugas Pokok dan Fungsi
‘Tugas pokok BIPP adalah menyelenggarakan penyuluban pertanian diwilayah
kerjanya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepala
daerab. Dalam melaksanakan tuges pokoknya, BIPP mempunyai fungsi-fungsi :
(1) Menyusun Program penyelenggaraan penyuluhan pertanian, (2) Bimbingan
penyusunan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian, (3) Penyediaan,
penyebaran dan pelayanan informasi pertanian, (4) Pembinaan pengelolaan BPP,
(5) Pelaksanaan kordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, (6) Pemantauan
dan Evaluasi, (7) Sentra komunikasi pembangunan pertanian di Kabupaten,
(8) Penyelenggaraan latihar/kursns bagi penyuluh dan petani-nelayan, (9) Melakukan
penumbuhan dan pengembangan petani-nelayan, (10) Bimbingan penggunaan sarana
usaha pertanian-nelayan, (11) Penyelenggarasn percontohsn, (12) Pengelolaan
perpustakaan, (13) Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian,
(14) Pemberian pelayanan teknis atau penyuluban, (15) Pelaksanaan tata usaha.
Mengingat umur BIPP baru memasuki tahun kedua, diketahui bahwa dari
semua fungsi diatas belum semua dapat terealisir. Diakui oleh kepala BIPP Karawang
bahwa di Kabupaten Karawang yang dirasekan sudah dapat dilakukan dengan baik
24
hanya beberspa fungsi yaitu fimgsi penyusunan programa ponyelenggaraan
penyuluban pertanian, bimbingan penyusunan dan rencana kerja penyuluh pertanian,
Penyelenggaraan lotihan/kursus bagi penyuluh pertanian dan petani-nelayan dan
pelaksanaan urusan tata usaha.
4.13. Organisasi
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dati I Karawang No. 2 tahun 1997
‘ertanggal 20 Maret 1997, Balai Informasi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Dati, UI
Karawang terdiri dari uasur-uasur organisasi seperti terlihat pada Lampiran 1 yang
tersusun dan mempunyai tugas sebagai berikut :
4.1.3.1, Pimpinan (Kepala BIPP)
Balai Informasi dan Penyuluhan pertanian dipimpin oleh seorang kepala yang
‘memenubi persyaratan unum untuk menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, diangkat dan dibethentiken oleh Gubermur kepala Daeth Tingkat I atas usul
Bupati Kepala Daerah. Pimpinan (Kepala BIPP) mempunyai tugas :
1. Membantu bupati Kepala Daerah didalam melaksanakan tugasnya dibidang
penyuluban pertanian baik dalam perencanaan maupun delam perumusan
kebijaksanaan teknis,
2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan-kegiatan balai,
3. Mongatur pelaksanaan tugas pera penyuluh pertanien di BIPP untuk
melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai urusannya diwilayah kerjanya,
4, Momberikan informasi mengenai penyuluhan pertenian seta saran dan
pertimbangan kepada Bupati kepala daerah sebagai bahan untuk menerapkan
kebijaksonaannya,
5. Menyusua program kerja penyuluhan pertanian untuk pelaksanaan tugas,
6. Menyelenggarakan pengelolaen -kepegawaian, keuangan dan perlengkepan
dilingkungan balai,
7. Mengadakan hubungan kerja dengan dinas lingkup pertanian, instansi pemerintah
‘maupun lembaga terkait dalam rangka kegiston penyuluhen pertanian,
25
8. Mempertanggung jawabkan tugas balai kepala bupafi kepala daerah melalui
pejabat yang ditunjuknya
4.1.3.2. Pembantu pimpinan (Kepala sub bagian tata Usaha).
Kepala sub bagian tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab kepada kepala balai dalam hal :
1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum
dilingkungan balai,
2. Menyiapkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan balai,
3. Menyelenggarakan urusan rumah tangga balai,
4, Memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi
ingkungan balai,
5. Bersama kelompok pejabat fungsional melakukan penyusunan rencana, program
supervisi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan statistik serta pembinaan organisasi
dan tata laksana,
6, Melakukan pengelolaan keungan dan pembendaharaan,
7. Melakukan urusan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat,
kearsipan, kehumasan dan protokol,
8. Membimbing pengelolaan rumshtangga BPP.
Dalam melakeanakan tugasnya, Kepala Tata Usaha dibantu oleh Sub-sub
Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian, Urusan
Perlengkapan, Urusan Umum/arsip, masing-masing dilimpahkan kepada seorang
kepala urusen yang barada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Tata
Usaha.
Selain seorang kepala urusan dalam setiap sub-sub bagian tata usaha,
pelaksanaan tugas tata usaba juga dilaksanakan oleh staf tala ussha yang bertanggung,
jawab kepada kepala urusan yang terdiri dari seorang staf umum, seorang stsf
Keuangan dan dua orang staf kepegawaian, Kedua orang staf kepegawaian bukenlah
penyuluh pertanian, melainkan pejabat struktural/ pegawai negeri sipil Kantor wilayah
Departemen Pertanian yang diperbantukan.
26
4.1.3.3, Peaksana (Kelompok Jabatan Fungsional)
Kelompok jabatan fiungsional dilingkungan balai bertugas menunjang tugas
pokok yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan fungsional
ini dipimpin oleh pejabat fungsional sebagai ketua kelompok yang bertanggung
Jjawab kepada kepala balai. sesuai kebutuhan, kelompok jabaian fungsional dapat
dibagi kedatam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang
pejabat fimgsional, Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban ‘ugas. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sub-sub kelompok jabaton
fungsional dilingkungan balai terdiri dari beberapa urusan yang membantu dan
bertanggung jawab kepada ketua kelompok jabatan flngsional sebagtai berileut :
4.1.3.3.1. Urusan Program
‘Urusan Program mempunyai tugas :
1, Menyusun perumusan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat
Kabupaten.
. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan penyusunan program penyuluhan
pertanian tingkat BPP.
3. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan penyusunan rencana kerja PPL.
4, Membimbing pelaksanaan program BPP dan rencana kerja PPL.
x
5. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program BPP dan program
penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan,
Dalam menjalankan tugasnya seorang Kepala Penyuluh Pertanian Urusan
(KPPU) Program dibantu oleh dua orang Penyuluh Pertanian Urusan (PPU) Program.
Pembuaian program maupun rencana kerja penyuluhan pertanien baik di tingkat
Kabupaten atanpun BPP dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu pada bulan April,
sehingga perumusan, bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap program maupun
rencana kerja dilakukan sejak 3 bulan sebelum pembuatn program dan rencana kerja.
2
4.1.3.3.2, Urusan Pelayanan Teknologi dan Sumberdaya
Urusan Pelayanan Teknologi dan Sumberdaya mempunyai tugas :
1. Melakukan kaji terap teknologi baru pertanian.
2. Melakukan bimbingan pelaksanaan kaji terap teknologi yang dilakukan oleh
tingkat BPP/WEPP.
3. Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak poneliti
Melakukan pengkajian tentang hasil kaji terap/percobaan teknologi.
‘Merumusken rekomendasi teknologi yang lebih menguntungkan.
Moelaksanakan evaluasi.
‘Melakukan penilaian tingkat penerapan teknologi oleh petani/kelompok tani.
‘Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan,
Pengamatan dilapang selama 1 bulan efektif di BIPP, tampak sekali tugas
Urusan pelayanan teknologi sumberdaya (Teknosda) terpusat pada KPPU Teknosda
sedangkan seorang PPU Teknosda hanya membantu dalam pembuatan laporan
kegiatan, Kedua pelaksana urusan Teknosda merasa kesulitan dalam melaksanakan
tugas, ini dikarenakan kurangnya sumberdaya dan fasilitas sehingga kualitas dan
kuantitasnyapun keurang baik.
ge
eae
4.1,3.3.3. Urasan Manajemen Informasi dan Penyuluhan
Urusen Manajemen Informesi dan Penyuluhan mempunyai tugas :
1. Mempersiapkan manajemen sistem informasi..
Melakukan penjabaran program penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat
BIPP kedalam teknis pelaksanaan.
Merumusken metode pilihan untuk pelaksansan kegiatan program.
Mempersiapkan kegiatan penyuluban dan menyampaikan informasi pertanian,
‘Membantu pelaksanaan kegiatan penyuluban ditingkat BPP/WKPP.
‘Mempersiapkan dan membuat alat bantu pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
‘Mempersispkan dan menyusun materi penyuluhan pertanian.
Monitoring dan mengevaluasi teknis kegiatan penyuluhan diberbagei tingkatan.
Mengelola perpustakaan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
Swe N Aw hw
Berbeda dengan urusan pelayanan lainaya, urusan pelayanan manajemen
informasi dan penyuluhan (MIP) dikepalai oleh seorang wanita yang dibantu oleh dua
orang PPU pria. Tugas yang rutin dilaksanakan adalah pemberian informasi terbaru
kepada penyuluh pertanien di BPP yang pelaksanaannya bersamaan dengan
pertemuan penyuluh pertanian di BPP. Seperti halnya urusan pelayanan Teknosda,
pelaksanaan tugas urusan MIP juga terpuset pada KPPU.
4.1.3.3.4. Urusan Pendidikan dan Latihan
‘Urusan Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas:
‘Melakukan identifikasi materi kebutuhan lafihan.
‘Merumuskan dan menentukan skala prioritas materi pelatihan.
‘Menyusun jadwal pelatihan.
‘Merumuskar/menentukan pelatihan sesuai dengan materi yang dibutubkan.
Morumusken dan penyusunan jadual supervisi scoring dan non scoring.
Perumuskan dan menyusun instramen kegiatan supervisi.
‘Mengolah dan menganalisa serta mengevaluasi hasil kegiatan supervisi.
‘Melakukan bimbingan bagi penyvluh dalam pelaksanaan kegiatan.
Menyusun rangking hasil kegiatan supervisi.
Dalam hai pelaksanaan pelafihan, telah dilaksanakan berdasarken Rencana
Peleksanaan Setahun yang diorganisasikan kedalam program triwulanan. Prioritas
materi sangat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, kebijaksanaan dinas terkait,
lokal spesifik, serta kebutuhan. Namun demikian dari pelatihan yang dilaksanekan
haya 25 persen yang dapst mencapai kebutuban yang diajukan PPL karena
terbatasnya personal serta waltu penyelengaraan yang seringkali bersamaan dengan
penyelenggaraan kegiatan Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Pembangunan
(RAKORBANG). Selain itu. dirasakan kemampuan pelatih di BIPP yang notabene
adalah mantan PPL tidak lebih tinggi dibanding PPL yang menjadi peserta pelatihan,
sehingga dirasakan bahwa sebaiknya struktur BIPP seharusnya mengikuti struktur
‘SPBB (Satuan pelaksana Harian Bimas) dimana pihak pelatih di BIPP mendapatkan
pelatihan dan binaan dari Penyuluh Pertanian Spesialis di tingkat propinsi.
een aya yn
29
4.1.3.3.5. Urusan Pelayanan Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Tani
Urusan Pelayanan Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Tani mempunyai
tugas :
1. Mengidentifikasi kemampuan wilayah dan pasar bersama petani-nelayan dan
pensliti dalam pengembangan agribisnis, agroindustri dan agrowisata dalam suatu
satan wilayah kawasan pertumbuhan (SWKP).
2. Membuat rancangan pengembangan usaha agribisnis, agroindustri dan agrowisata
sesuai dengan potensi wilayah.
3. Mengembangkan dan melayani masuken yang dibutuhkan usaha kelomok tani-
nelayan diwilayah kerjanya.
4. Mengembangkan dan melayani masukan yang dibutuhkan oleh pengusaha
(BUMN, BUMS dan Koperasi) untuk pengembangan usahanya
5. Menggerakan sektor swaste/BUMN, koperasi dan unit kerja faimya untuk
menumbuhkan kemitraan usaha datam membangun satuan wilayah ekonomi .
6. Memberikan pelatihan terhadep petugas maupun petani-nelayan dalam rangka
pengembangan agribisnis, agroindestri dan agrowisata.
7. Menyusun strategi pembinaan terhadap petani/kelompok tani-nelayan.
8. Melakukan inventarisasi petani/kelompok tani-nelayan.
9. Melaksanakan penilaian tingkat kemampuan kelompok tani.
10, Pembinaan peran dan fungsi KTNA diberbagai tingkatan,
LL. Membantu petani/kelomopok tani dalam kerjasama dengan perusahaan
pombimbing.
12. Merumuskan dan menyusun jadual supervisi.
13. Melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi serta melaporkan hasil kegiatan,
Pelaksanaan tugas urusan pembinaan usaha dan kelembagaan tani belum
semua dapat dilaksanakan, hel ini dapat dimaklumi mengingat umur kelembagaan
BIPP baru 2 tabun, Tugas yang sudah dapat dileksanakan adalah pembinaan dax pola
kemitraan antara PPL, Kelompok ‘Teni-Nelayan Andalan (KI'NA) dengan
kelembagaan Iain, namun kendala yang dirasakan cukup berat saat ini adalah adanya
porkembangan Karena pembangunan industri yang mengakibatkan adanya alih profesi
dikalangan petani-nelayan dan keluargannya termasuk dikalangan KTNA. Hal ini
menycbabkan sulitnya mendapatkan KTNA yang dapat bekerjasama dan menjadi
partner PPL secara berkelanjutan.
4.1.4, Tata hubungan Kerja
Sepert terlihat pada Lampiran 7, hubungan kerja antara BIPP dengan dinas-
dinas daerah tingkat II lingkup pertanian adalsh bubungan koordinatif, dalam hal
pembinaan teknis operasionalnya dilakulsan oleh Bupati Kepala Daerah yang sebsri-
hari dilakukan oleh PEKD/Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Daerah fingkat IL Sedangkan pembinaan teknis administrasi ditalukan
oleh assisten administrasi Pembangunan setwilda tingkat II Karawang.
Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya, BIPP mendapat bimbingan teknis
dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian yang meliputi penyampaian
kebijakan penyuluban pertanian, penyampaia pedoman, petunjuk pelaksanaan,
petunjuk toknis pelaksanaan penyuluban pertanian, mengkoordinasikan kebutuban
lotihon bagi penyuluh pertanian, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
penyuluhan pertanian, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinye, BIPP mempuinyai
hubungan koordinatif dengan Dinas-Dinas Daerah Tingkat II lingkup pertanian antara
Jain melalui pertemuan-pertemuan mengenai :
1. Penyusunan program penyelenggaraan dan program penyuluban pertanian.
2. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian,
3, Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan Tingkat Kecamatan.
4. Penyelenggeraan Pelatihan/kursus bagi penyuluh pertanian dan petani-nelayan.
Kerjasama BIPP dengan instansi/lembaga lain diantaranya dengan :
1. Pusat Studi Mahasiswa (PSM) Dati. Il Karawang yaitu penyelenggaraan
pemberian kulish program D TI Pertanian bagi penyuluh pertanian yang telah
mendaftar untuk mengikuti perkulishan
2. Balei Pengkajien Teknologi Pertanian (BPTP) Dati. II Karawang, Serpong dan
Lembang, melaksanakan pengujian-pengujian teknotogi pertanian yang, diileti
31
oleh beberapa penyuluh pertanian yang dipilih olch kepala BIPP disesuailcan
antara materi dengan satminkal penyuluh pertanian sebelum adanya BIPP.
3. PT. Pindodeli, melaksanakan pengujian limbah padat. Diikuti oleh personil
urusan pelayanan Teknosda untuk kemudian disebarkan kepada penyuluh
pertanian di BIPP maupun di BPP sebagai tambahan pengetahuan.
4. PT. MMS melaksanaken pengembangan kedealai dan P.T. OECF Jepang
melaksanakan model farm dan UPJA yang dihadiri oleh hampir seluruh penyuluh
Pertanian karena merepakan bagian dari tugas yang diberikan kepala BIPP kepada
penyuluh pertanian di BIPP dan BPP, Pertemuan dalam bentuk pelatihan ini
bertujuan untuk mengembangkan kedelai dengan pola kemitraan dengan
Pengusaha -
4.1.5. Sarana Dan Prasarana
Usia BIPP saat ini sudah mencapai 2 tahun, namun gedung sebagai sarana
penunjang belum memadai, Kantor BIPP pertama berada di SPMA, sebuah gedung
milik Pemda, namun kerena akan di renovasi make kantor BIPP pada bulan mei 1999
dipindah ke Salah Satu Ruangan Rapat di gedung Bappeda yang juga milik Pemda.
Sebenamya sudah ada paket bantuan dari SPL mengenai dana bantuan
bangunan dengan Iuas 2 Ha, namun dana tersebut belum cair dan Pemda sendiri bars
menyediakan lehan seluas 1 Ha dari 2 Ha lahan yang dijanjikan. Ketiadaan Ruangan
atau kantor yang memadai menyebabkan suasana bekerja tidak nyaman, ruangan dan
sarana lain seperti Meja, Kursi dan Perlengkapa Rumah tangga Balai yang masih
meminjam dari Bappeda menyebabkab Staf yang bekerja di BIPP seperti
“menumpang”, sehingga tidak ada perasaan memiliki dan punya kekuatan untuk
molakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi balai.
Berdasarkan data inventarie bangunan BIPP tahun 1998, BIPP mempunyai 11
BPP, Kebun percontohan yang terdiri dari lahan sawah seluas 43.793 M? pekarangan
seluas 17.923 M? dan Kolam percontohan seluas 3.832 M? . Peralatan kantor yang
ada di BIPP saat ini terdiri satu set komputer, 1 buah stabilisator dan 3 buah mesin
kotik yang semuanya dalam keadaan baik dan merupakan bantuan dari Bantuan
32.
Khusus Operasional Penyulukan Pertanian (BKOPP). Alat bantu penyuluban yang
‘ersedia saat ini terdri dari 1 buah wireles dan 1 buah over head projector yang juga
merupakan bantuan dari BKOPP.
4.1.6. Pembiayaan
Dalam hal pengenggaran berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan BIPP,
pembiayaan BIPP disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sorta
Subsidi atau bantuan Pemorintah Daerah Tingkat I Jawa Barat maupun Pemerintah
Pusat dan lembaga
Sejak berdirinya BIPP (fahun 1997), anggaran biaya yang diterima dari PPKD
Departemen pertanian oleh BIPP sebesar Rp. 15,100.000,00, berasal dari Inpres Dati
T sebesar Rp. 952.210,00 dan Dana Operasional Program sebesar Rp. 480.000,00,
Dengan perkataan lain anggaran dari Kabupaten Dati I Belum ada Hal inj
Gisebabkan belum adanya PERDA (Peraturan Daerah) yang mengatur anggaran
BIPP, ini membuktikan belum adanya otonomi penuh bagi BIPP karena belum
adanya PERDA menyulitkan BIPP dalam membuat Anggaran Rumah Tangganya.
in diluar pemerintah dengan cara yaug sah.
4.17, Tenaga Penyuluk Pertanian
Penyuluh pertanian yang ditempatkan di Unit Kerja Pertanian Pusat atau
Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pertanian, Penyuluh pertanian
yang ditempatkan di Unit kerja pertanian Daerah tingkat II satuan administrasi
Pangkalnya berada di BIPP dan merupakan pegawai negeri sipil pusat diperbsintukan.
Jumlah Penyuluh Pertanian yang berada di BIPP sebanyak 21 orang dan 2
orang staf yang berasal dari kanwil Departemen Pertanian. Keseluruhan _pervonil
yang ada di BIPP dipilih dan disahkan olch Bupati berdasarken Surat Keputusan
Bupati, bukan kemavan dari penyuluh itu sendiri, Hal ini diakui Kepala BIPP
menyebabkan sikap dan kinerja sebagian penyuluh yang ade di BIPP dirasakan masih
fourang baik, namun dewasa ini rasa memiliki (self of belonging) penyuluh pertanian
tethadap BIPP dirasakan meningkat. Dilingkungan BIPP terdapat harapan bahwa
untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan sikap Penyuluh Pertanian maka semua
33
uwrusan yang menyangkut kepegawaian penyuluh pertanian sebaiknya dilimpahkan
Pada BIPP. Sementara itm dipihak Dinas dirasakan bahwa PPL bagaimanapun
“dibesarkan” oleh Dinas dan bahwa yang mempunyai program adalah “Dinas”,
sehingga PPL diharapkan masih berumah di Dinas masing-masing. Selain itu, dalam
hal kepegawaian pihak Dinas masih merasa perlu dilibatkan dalam penilaian konduite
Penyuluh pertanian, karena pihak Dinas merasa bahwa merekalah yang mengenal
betul perilaku dan prestasi PPL. Dualisme “Kepemimpinan” bagi kalangan PPL ini
perlu segora dibenahi, untuk menghindari ketidakjelasan status PPL dan moncegah
PL yang kurang disiplin, serta menyatu padukan kontrol terhadap PPL.
Jumlah penyuluh pertanian yang berada di BIPP menurut pendidikan adalah
sebagai berikut: empat orang berpendidikan SLTA, ompat orang Diploma 3 atau
sarjana Muda, sebelas orang Sarjana dan sebanyak dua orang berpendidikan Pasca
Sarjana. Jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan penyuluh pertanian di BIPP
dengan penyuluh pertanian di BPP akan tampak bahwa tingkat pendidikan penyuluh
pertanian di BIPP jauh lebih tinggi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat personil di
BIPP bertugas mengkordinir penyuluh pertanian di BPP.
4.2. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
Berdasarkan SKB Mendagri-Mentan No. 223/Kpts/Unv4/1976 dan No. 76
tahun 1976 dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang bercikal bakal dari
Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD), Setelah dibentuknya BIPP terdapat
perubahan, dibawah ini dikemukakan BPP pasca BIPP.
4.2.4, Kedudukan
Dalam meloksanakan tugas dan fungsinya BIPP menggunakan Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai instalasi/sarana kegiatan penyuluhan pertanian
di Kecamatan. Balai penyuluhan Pertanian (BPP) diarehkan untuk dikelola oleh
kelompok tani nelayan yang dibimbing oleh seorang penyuluh pertanian senior, yang
ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat I atas usul kepala BIPP.
34
4.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Balai Penyuluhan Pertanian yang dibentuk disetiap Kecamatan dengan
wilayah Kerja satu wilayah administrasi kecamatan atau kelipatan desa dalam safu
wilayah administrasi Kecamatan yang ditetepkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat
1 Berfungsi sebagai :
1. ‘Tempat penyusunan Program Penyuluhan Pertanian,
2, Tempat penyebarluasan informasi pertanian,
3. Tempat lafihan para PPL yaag toratur sehinggr kemampuannya akan selalu
meningkat, baik pengetahuan maupun keterampilannya.
4, Tempat pemberian rekomendasi pertanian yang lebih menguntungkan,
‘Tempat mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik kepada
petani.
Jika dilihat fungsi-fimgsi BPP diatas, maka jelas pula bahwa di BPP tidakleh
cukup hanya diselenggarakan kegiatan-kegiatan Klasikal eaja, molainkan harus
terdapat berbagai jenis dan bentuk kegiatan di lapangan, yang dalam hal ini di
kompleks BPP. Kegiatan lapangan terutama dityjukan bagi segi-segi pendidikan, baik
bagi para PPL maupun bagi para petani, dengan demikian maka kompleks BPP
tidaklah hanya bermanfaat bagi pelaksanean rapat-rapat saja, melainkan juga bagi
kegiatan belojar-mengajar, pelaksanaan diskusi yang menyangkut bidang pertanian,
penyampaian informasi secara timbal balik (Two way traffic communication),
mengenalisa dan mengevaluasi hel-hal yang berasel dari dan diperuntukan bagi
tingkat lapang,
4.2.3. Organisasi
Balai Informasi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Dati, It Karawang terdiri
dari uasur-unsur organisasi yang tersusun dan mempinyai tugas sebagai berilut :
4.2.3.1. Kepala (Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian)
‘Tugas pokok pimpinan BPP adalah menyusun program penyuluhan pertanian
untuk dilaksanakan diwilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP) yang dapat
diperinei sebagai berikut :
35
1. Menyusun program penyuluh portanian seluruh sub sektor portanian secara
musiman dengan bimbingan penyuluh pertanian yang berada di Kabupaten .
2. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan kegialan penyuluban pestanian,
3. ‘Menyelenggarakan latihan untuk penyuluhan secara teratur dan berkelanjutan.
4. Menyampaikan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dipecahkan
setempat kepada forum koordinasi penyuluhan pertanian tingkat II (FKPP 11).
5. Menyelenggarakan koordinasi penyuluban pertanian dengan penyuluh seluruh sub
sektor, dan instansi lain yang ada kaitannya dengan kegiatan penyuluhan,
6. Mengadakan pertemuan dengan kontak tani secara priodik.
42.3.2. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Wilayah Kerja
Penyuluh Pertanian (WKPP)
‘Tugas pokok PPL di WKPP dapat diperinci sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan kunjungan teratur, pasti dan berkelanjutan kepada kelompok
tani, nelayan sesuai dengan sistem kerja latihan dan kunjungan (Iaku).
2 Menyelenggarakan penyuluhan pertanian dengan materi yang terpada
mendinamisasikan kelompok tani dengan pendekatan kelompok.
3. Memanfaatkan metode penyuluhan pertanian untuk memantapkan sistem kerja
Latihan dan Kunjungan.
4. Menyusun program penyuluban pertanian dan menyelenggarakan kegiatan
penyuluhan pertanian yang mengikutsertakan pemuka masyarakat.
‘Melakeanakan tugas yang dibebankan oleh badan pelaksana BIMAS Kecamatan,
‘Melakukan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani-nelayan,
Bimbingan penggunaan sarana usaha petani-nelayan.
Penyelenggaraan percontohan.
‘Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian.
Pengelolaan BPP dilakukan oleh Koordinator penyuluh pertanian bersama-
em ND
sama dengan kelompok tani-nelayan Pengelolaan BPP antara lain mencakup
pengamanan komplek BPP, membantu pengelolaan Iahan percontohan, memelihara
kebersihan serta kenyamanan kerja kantor BPP.
36
4.2.4, Tata hubungan Kerja
‘Hubungan kerja antara BIPP dengan BPP bersifat koordinatif, dimana BIPP
memberikan bimbingan teknis maupun non teknis kepada penyuluh pertanian di BPP
melalui Pelatiban yang waktunya bersamaan dengan pertemuan yang dilakukan di
BPP yaitu 2 minggu sekali, namun jadwal kegiatan yang sudah terjadwal baik di BPP
maupun di BIPP hanya sebagian kecil saja dapat dilaksanalm, hal ini dikarenakan
jarak yang cukup janh dengan sarana dan prasarana yang terbalas, Waktu yang
bersamaan serta ada beberapa staf dari BIPP yang terkadang enggan pergi kelapang,
i whan Penyuluh pertanian di BPP dikarenakan sedikitnya frekuensi
pertemuan Penyuluh pertanian BIPP dengan Penyuluh pertanian BPP mengakibatkan
informasi tentang pertanian juga sedikit.
ini meni
4.2.5, Sarana Dan Prasarana
Kabupaten Dati. Il Karawang mempunyai 18 Kecamatan, empat perwakilan
kecamatan/kemantren dan 303 desa/ kelurahan. Dalam penyelonggaraan penyuluhan
pertanian Kabupaten Dati. II Karawang memiliki 22 BPP, 143 WKPP (wilayah kerja
penyuluh pertanian ) dan 2054 wilayah Kelompok toni-nelayan.
Balai penyuluban pertanian yang ada hanya 12 yang memilki bangunan
sedangkan 10 bangunan lainnya merupakan pinjamawKontrak, Jumlah BPP yang
mempunyai !ahan percontohan terdiri dari 9 BPP dengan luas Iahan seluruhnya 10,4
Ha. Untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan, 20 buah BPP mempunyai 42
buah motor dengan keadaan jalan 26 buah, rusak 12 buah dan rusak berat 4 buah,
Kepemilikan Kendaraan Bermotor ini Sebagian besar diberikan kepada Penyuluh
Pertanian Spesialis ketika berada di Dinas, setelah perpindahan Satuan Administrasi
pangkal dari Dinas ke BIPP menyebabkan Dinas tidak bertanggung jawab lagi
terhadap biaya ekeplorasi dan perbaikan kendaraan bermotor sedangkan di BIPP
sendiri belum dapat mengajukan biaya eksplorasi inventaris kendaraan bermotor yang
Perda schingga tidak bisa mengajukan
37
4.2.6. Pembiayaan
‘Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian secara
bersama mengatur pembiayaan BIPP, BPP dan penyuluh pertanian, Pemberian dana
bagi penyelenggaraan penyuluhan disesuaikan dengan anggaran yang diajukan oleh
penyuluh pertanian melalui Rencana Kerja dan Programa penyuluhan pertanian yang
i buat secara priodik 1 kali setiap tahunnya yang diserahkan kepada BIPP untuk
disetujui oleh kepala BIPP sesuai dengan prosedur yang berlalcu.
Adanya Bantuan Khusus Operasional Penyuluh Pertanian (BKOPP) dalam
Inpres Bantuan Pembangunan Dacrah Tingkat 1 adalah salah satu upaya untuk
‘memperkuat pembiayaan kegiatan penyuluban pertanian didaerah tingkat IL Bantuan
Khusus Operasional Penyuluh Pertanian (BKOPP) dalam Inpres Dati II bukan untuk
menghilangkan pembiayaan yang bereumber dari dasrah. Porsi pendanaan dari
pemerintah Pusat akan semakin kecil sebaliknya, porsi pendanaan dari pemerintah
Daerah akan semakin besar.
Dengan diterbitkannya SKB Mendagri-Mentan 1996, penyediaan biaya
penyuluhan pertanian yang selama ini ada di APBD Tingkat I atau APBD tingkat II
fetap dilakukan berdasarkan mekanisme penyusunan anggaran pembangunan
schingga pembiayaan penyuluhan pertanian tetap dijamin sesuai dengan kebutuhan,
4.2.7, Tenaga Penyuluh Pertanian
Penyuluh Pertanian yang berada di BPP berjumlah 157 orang, terdiri atas 14
orang Wanita dan 143 orang pria, Pendidikan terakhir Penyuluh pertanian di BPP
terdiri dari 2 orang Sarjana (S1), 10 orang Diploma 3 (D3) dan sisanya 145 orang
adalah Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA).
Sumberdaya penyuluh pertanian yang = mayoritas _berpendidikan
SMA/sederajat, rendahnya dana operasional, monotonnya kegiatan yang dilaksanakan
penyuluh pertanian di BPP serta adanya perubahan dalam perkembangan struktur
demografi keluarga penyuluh pertanian di BPP menyebabkan perhatian penyuluh
pertanian di BPP terhadap fungsi yang herus dilakeanakannya sangat heterogen
bahkan diantaranya ada yang menurun,
38
BAB V
PROFIL PENYULUH PERTANIAN
5.1, Sumberdaya Pribadi
Sumberdaya pribadi terpenting yang menentukan kuualitas seorang penyuluh
pertanian adalah tingkat pendidikan, Pada Tabel 1 dikemukakan data tingkat pendidikan
Penyuluh Pertanian. Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara umumn tingkat
pendidikan wanita dan pria mayoritas berpendidikan Sekolah Pertanian Menengah Atas
(SPMA). Gejala tersebut terjadi kerena pegawai negeri sipit yang diangkat untuk
pertama kali dalam jabatan penyuluhan pertanian harus memenuhi syarat berijazah
serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas dibidang pertanian
Tabol 1. Persentase Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan,
‘Tahun 1999
Tingkat Pria Wanita
Pendidikan A B A B
‘SPMA a3 | 679 92 92
Diploma 3 71 4 0 0
Sarjana 3 36 [L178 0 0
‘Pasca Sarjana 0 I 0 8 8
Keterangia : A= Sebelum menjadi penyuluh peranian
‘B= Sesadch menjadi penyuluh pertenian
Hal tersebut dimungkinkan mengingat setelah menikah akses penyuluh wanita
untuk memperoleh pendidikan terrhambat oleh beban kerja reproduktif . Dalam
kegiatan reprodultif curahan waktu peuyuluh wanita lebih banyak dibandingkan pria,
seperti terlihat pada tabel 2, Curahan waktu wanita dalam kegiatan reprocultif yang
menyita 20 persen waktu dalam sehari menyebabkan wanita sulit menyisihkan waltu
untuk meningkatkan pendidikan formalnya.
Hal tersebut dimungkinkan mengingat setelah menikah akses penyuluh wanita
‘untuk memperoleh pendidikan terrhambat oleh beban kerja reproduktif . Dalam
kkegiatan reprodultif curaban waktu penyuluh wanita lebih banyak dibandingkan pria,
seperti dapat dilihat pada tabel 2. Curahan wakty wanita dalam kegiatan reproduldif
yang menyita 20 persen waktu dalam sehari menyebabkan wanita sulit menyisibkan
‘walu untuk meningkatkan pendidikan formalnya.
‘Tabel 2. Diistribusi Curahan Wakt Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Tahun
1999
No Tenis Kegiatan PRIA (n=28) | WANITA (n=12)
3K _[Persen | JK | Persen
1_| Kegiotan Reproduktif Domestik) |
2._| Masak oo [ 00 | 18 77
'b. | Meneuel 00 [0.0 [07 [30
c._| Mengasub Anak o3 | a1 [10 4d
4.| Membersihkan /merapikan Rumah o4 | as [10 40 |
e. | Kegiatan Leinnya 03 | 13 [03 13
Subtotal [09 [38 [48 | 200
2 | Repiatan Produktif cs |
a__| Dings Luar 38 42 | 173 |
b._[ Dinas Dalam [19 17 69 |
¢._| Rapat/Pertermuan li o1 [03 |
d._| Perjalanan Kerja 06 4 18
e._| Apel a ol 05)
£_| Kegiotan Cainnya 14 58
= ‘SubTotal | 78 | 32.7
3 | Regiatan Sosial dan Organisasi
a._| Sosiabisast 03 13
b._| Tolong Menofong a 00 Ou
c._| Pendidikan - 0.0 0.0)
SubTotal 03 14
4 _| Kegiatan Waktu Luany eee
Olah Raga o2 oo
buran/kesenian, 08 35_|
stirahat a 5 2.0
iH Sub Tod | 29 [a2 | 1s 63
3__| Kebutuban Desar [eat
a_| Keplatan agama is | 63 |" 20 i
b._| Tidur 66 | 276 | 65 | 274
c._{ Maken dan Minum o9 | 36 | 06 27
d._| Membersihkan Diti [o6 | 24 | 04 17
SubTotal | 9.5 | 398 | 9.5 | 396
Total| 24 | 100 | 24 100
Keterangan : JK = Jam Kerja
40
Selain beban kerja dalam kegiatan reproduktif, hambatan lain yang
menyebabkan wanita tidak akses terhadap pendidikan datang dari pasangannya. Dari
‘Tabol 3 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan suamisisteri penyuluh pria dan wanita
mayoritas berada pada (ingkat pendidikan SMA/sederajat. Data yang didapat
memperkuat fakta yang ada, dimana penyuluh wanita tidalviurang akses terhadap
pendidikan, Hal tersebut terjadi karena suami umumnya tidal rela pendidikan isterinya
lebih tinggi dibandingkan dirinya. Berbeda dengan penyuluh wanita, penyuluh pria
lebih banyak mendapatkan dulamgan isteri dalam mencapai jenjang pendidikan yang
lebih tinggi. Hal tersebut terungkap dari wawancara terhadap tiga pasangan yang
keduanya adalah penyuluh pertanian .
Tabel 3. Distribusi Pasangan Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Tingkat
Pendidikan, Tahun 1999
Tingkat Pendidikan Pria (n=27) Wanita (n=12)
jumlah | Persen | Jumlah | Persen
Tak Sekolah 3 i 0 0.0.
SD 3 m1 0 0.0,
SMTP 8 29.6 0 0.9
‘SMTA 10 37.0 6 50.0
[3 3 it 4 33.3
st 0 0.0. 1 83
32 0 0.0) 1 83
Kemampuan wanita untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi yang
terhambat tidak mengakibatkan kemampuan wanita untuk menempati golongan/jenjang
kepangkatan yang lebihh tinggipun terhambat. Golongan kepangkatan seseorang antara
Jain menentukan pendapatanigaji dan tugas/pekerjaan penyuluh pertanian. Sika
diperbandingkan secara umum mayoritas golongan kepangkatan penyuluh pertanian pria
sama dengen wanita, dimana golongan kepangkatan penyuluh pertanian pria dan wanita
terbesar tersebar pada golongan HT, seperti dapat dilihat pada Tabel 4.
a
Tabel 4. Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Goiongan
‘Kepangkatan, Tahun 1999
Golongan Pria Wanita
Kepangkatan _[~ Jumlah Persen Jumlah Persen
‘Honorer & I 5 179 1 83
ot 3B 321 | i 91,7
Golongan kepangkatan pada penyuluh pertanian sebagai pegawai negeri sipil
(NS) didasarkan pada pengumpulan angka kredit yang secara koicitif diberikan setiap
3 tahun sekali. Salah satu faktor yang dilihat dalam mencapai golongan kepangkatan,
fertentu adalah angka Kredit, semakin lama seseorang bekerja maka semakin besar
‘angka kredit yang dikumpulkannya.
‘Masa kerja seseorang menggambarkan pengalamaniya dalam melaksanakar
‘tugas pokok dan fimgsinya. Masa kerja penyuluh pertanian pria menduduki persentase
terbesar pada masa kerja lebih dari 20 tahun yaitu 54 persen sedangkan wanita SO
persen mempunyai masa kerja kurang dari 20 tahun dan 50 persen masa kerja
ebilv/sama dengan 20 tahun,
‘abel 5. Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Masa Kerja, Tahun
1999
Masa Kerja Pria ‘Wanita
Jumlah_|Persen | Jumlah | Persen
‘Kurang dari 10 tahun 3 0 0
10 sampai 20 tahun 10 36 3 25
Lebih dari 20 tahun as [54 3 25
‘Tabel 5 juga memberiican gambaran dimana selama 10 tahun terakhir tidak ada
penerimaan pegawai/penyuluh pertanian wanita dalam kelembagaan penyuluhan
pertanian, Hal fersebut membuktikan masih berlakunya penerimaan penyuluh pertanian
yang lebih mengutamakan calon penyuluh pria dibandingkan wanita dan masih
kurengnya minat remaja putri untok belajar di sekolah pertanian menengah atas yang
42
selanjuinya akan menjadi penyuluh pertanian. Berdasarkan hesil seminar yang diadakan
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertanian, Pemda TK. I
Karawang dan BIPP dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang penyuluh
pertanian yang bait dibutuhkan motivasi yang tinggi terhadap bidang pekerjaannya,
Motivasi adalah seswatu yang menimbulkan semangat dan dorongan kerja
dimana tinggi rendahnya motivasi kerja seseorang akan menentukan besar kecilnya
prestasi kerja itu sendiri. Motivasi kepentingan pribadi pada penyuluh pertanian pria
{28,6 persen) sedikit lebih besar dibandingkan wanita (25 persen) dikarenakan
penyuluh pria mempunyai beban lebih besar dibandingkan penyuluh wanita dalam
‘memenuhi kebutuhan rumah tangga/kelarganya.
Tabel 6.Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Motivasi, Tahun
1999
Pria Wanita
Jumlah | Persen |" Jumlah_ | Persen
3 | 286 3 25
-Kepentingan masyarakat 20 TA 9 75
Aspek motivasi kerja ini berkaitan dengan sikap dan pandangan responden terhadap
bidang pekerjaannya, Persepsi penyuluh pertanian pria dan wanita yang menganggap
kesempatan pengembangan karier dan kualitas keragaan antara penyuluh pertanian pria
dan wanita sama (Tabel 7), menjadikan motivasi penyuluh pertanian pria dan wanita
Jebih terpusat pada kepentingan bagi masyarakat.
Motivasi penyuluh pertanian yang cenderung untuk kepentingan masyarakat
berhubungan dengan peranan sosialnya, Status penyuluh pertanian sebagai fasilitator
menyebabkan penyuluh harus lebih mengutamakan kepentingan petani/masyarakal,
Dalam melaksanaken tugas dan fimgsinya sebagai fasilitator penyuluh pertanian
membutubkan wadaby/tempat. Salah satu cara yang dinilai cukup efektif adalah dengan
berpartisipasi dalam beragam kelembagaan baik formal maupun informal
43
abel 7.Distribusi Penyuluh pertanian Menurut Persepsi Responden Terhadap
Lingkungan Kerja Dan Jenis Kelamin, Tahun 1999
iv] Persepsi Responden PRIA WANITA
‘Terhadap Lingkungan Kerja ___| Jamiah [Persen] Jumian | Persen
1 |Kesempatan Pengembangan Karier
[Pria dan Wanita Mempunyai Kesempatan sama 2s [100] 1 92.
[Kescmpatan Pria Lebih Besar dibanding wanita oO cu 1 8
2{Kualitas Koragaan Penyuluh Pertanian
[Wanita lebih Berkualitas dibanding pria 0 0 1 8
[Pria lebih berkualitas dibanding wanita 7 [3s 4 3
[Kualitas pria dan wanita sama 2 | 75 7 38
Partisipasi penyuluh pertanian pria sedikit lebih tinggi dibandingkan wanita
esa (KUD). Dalam
kegiatan karang taruna umumnya penyuluh pria lebih mampu berinteraksi dengan
pemuda-pemudi di lingkungan rumahnya, sedangkan dalam KUD — umumnya
dikarenakan keanggotaan koperasi diberikan kepada kepala rumah tangga
dalam berpartisipasi pada karang taruna dan Koperasi Unit
Dalam kelembagaan Keluarga Berencana (KB) penyuluh wanita jauh lebih
tinggi dibanding pria, hal ini dimungkinkan mengingat penyuluh wanita selain sebagai
akseptor KB juga pemberi penyuluhan mengenai KB. Program keluarga berencana
(KB) lebih dipercayakan kepada penyuluh pertanian wanita mengingat peran wanita
sebagai ibu rumah tangga yang berkaitan langsung dengan kegiatan reproduktif’ biologis
( Melahirkan dan merawat anak). Penyuluh pria yang berpartisipasi dalam program
keluarga berencana yaitu. menjadi akseptor KB dan tidak memberikan penyuluban
kepada masyarakat mengenai program KB tersebut
Partisipasi penyuluh pria lebih besar dibandingken penyuluh wanita dalam
kelembagaan dibidang portanian menggambarkan pria lebih akses lerhadap
kelembagaan penyuluban dan kegiatan-kegiatan dibidang pertanian dimana kegiatan
tersebut selain menambsh nilai Kredit juga mendatangkan penghasilan tambahan.
Seperti dapat dilihat pada tabel 8 dimana penyuluh wanita sama sckali tidak akses
dalam kegiatan P4K yang merupakan proyek pemerintah dalam mengembangkan petani
44
kecil dimana kegiatan tersebut selain diperhitungkan dalam pengumpulan angka kredit
juga memberikan tambahan pendapatan.
‘abel 8. Distribusi Penyuluh pertanian menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Dalan
Berbagai Kelembagaan, Tahun 1999
No Jenis ‘Wanita
Kelembagaan Jumlah Persen
1. Lingkungan Pemerintahan
‘a_| Karang Taruna 6 214 2 167
> [xB 2 Head 10 $33
¢_| Korpri 2 736 | 10 83,3
@ | KuD i ara 2 16.7
2. Pertanian
a__[ HKTI 7 25 4 33,3
b__[ANST 1 3.6 0 0
¢_| PERHIPTANT 25 89,3 10 83,3
@ [Pekan Tani 1 3.6 1 83
| Pak __6 21.4 0 0
3. Informal zs H 7
2_| Pengajian 16 S71 iH 31
>| Arisan 8 [28.57 12
¢ | Gotong Royong io | 35.7 6 |
d_| Selamatan’ 6 j 35,7 | fee }
Partisipasi penyuluh pertanian dalam kelembagaan pertanian terkait dengan
wilayah kerjanya, begitu pula dalam pelakeanaan program dibidang pertanian. Dalam
kasus pelaksanaan program pertanian di Kabupaten Karawang, seperti yang dijelaskan
oleh Seksi Bina Program Dan Penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
pelaksanaan program lebih dipercayakan kepeda penyulub pertanian pria mengingat
terbatasnya dana dan fasilitas sedangkan jangkanan program yang cukup luas sehingga
‘membutubkan kekuaten fisik yang lebih prima.
Dalam kegiatan pengelolaan masyarakat/informal partisipasi penyuluh wanita
cenderung lebih tinggi dibanding pria, mengingat wanita lebih banyak menghabiskan
‘waktu di lingkungan tempat tinggalnya dengan cara berinteraksi dengan masyarakat di
Tingkungannya.
45
5.2. Sumberdaya Keluarga/Rumah Tangga
Penyuluh pertanian baik pria dan wanita selain bekerja di lingkungen BIPP dan
BEP mereka juga anggota unit sistem sosial laimya yaitn keluarga/rumah tangga.
Stereotipi yang menyatakan peranan wanita hanya sebagai ibu rumah tanga,
pendamping suami, ibu anak-anaknya, anggota rumah tangga dan pencari nafkah
tambahan, tidak seluruhnya benar.
Hal tersebut tampak dari banyaknya isteri dan penyuluh wanita berstatus
pegawai negeri dimana kontribusi pendapatan rumah tangga yang diberikan sama
banyainya dengan suami, begitu pula dengan status dan peranannya sebagai pegawai
negeri sipil yang tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin,
Tabel 9 menggambarkan pasangan suami-isteri penyuluh pertanian sebagian
besar mempunyai profesi yang sama yaitu pegawai negeri sipil, mamun cukup besar
persentase isteri-isteri penyuluh pertanian yang hanya menjadi ibu rumah tanga, hal ini
{erjadi pada isteri-isteri yang berpendidikan dibawah SMA/sederajat,
‘abel 9. Distribusi Pasangan Penyuluh pertanian menurut Jenis Kelamin dan Jenis
Pekerjaan, Tahun 1999
Jenis Pekerjaan Utama Pria (n=27) Wanita (n=12)
jumiah | Persen | Jumlah | Persen
PNS 6 22.2 & 66.7
Petan 2 7A 0 0.0
Buruh Tani 1 37 ° 0.0
Pedagan 3 il 1 83
industii RT 2 74 3 25.0
[ou Rumah Tangga B 48.1 6 0.0
Jenis pekerjaan yang sama menyebabkan penyuluh pertanian baik pria maupun
wanita sering mendiskusikan masa depan karier kepada pasangannya, namun jika
menyangkut pekerjaannya penyuluh pria Kurang suka mendiskusikennya dengan
pasagannya Karena selain berbeda ilmu dan pandangan terhadap topik yang
dibicarakan, hanya sesekali saja mereka akan menceritakan/berdiskusi_mengenai
46
pekerjaannya Berbeda dengan penyuluh pertanian pria, penyuluh pertanian wanita
sering mendiskusikan pekerjaanya dengan suami.
Tabel 10. Distribusi Penyuluh pertanian menurut Jenis Kelamin, Relasi Dengan
Pasangan dan Jenis Pekerjaan, Tahun 1999
No Relasi Dengan PRIA.(n=28) | WANITA(n=12)
Pasangan jumlah [Persen| Jumlah | Persen
1 [Persetujuan Bekerja 28 | 100 2 100
[Dukungan Karier
alTidak Mendukany 4 14 0 0
[Mendukung, 23 [852 [2 100
3 [Diskusi Masa Depan Karier
idak Pemah 1 37 0 0
i 26 [963 | 12 100
(4 [Diskusi Pekerjoan
[alidak Pemah 1 3.57 0 0
b[Kadang-kadang 14 [53.57[ 2 16.7
dsetata 10 37 10 83,3
[5 |Bangga Terhadap Profest
alantara bangea dan tidak 4 is] 2 167
clBangga 23 85,2 | 10 #33
'7__|Menanyakan Pendapat tt
a[Kadang-kadang Baa o |
b|Serin i (556 {12 100
Nilai jender yang masih metekat kuat menyebabkan wanita mempunyai peran
‘ganda yaitu selain sebagai pencari nafkah, beban kerja reproduktif’ wanita juga lebih
besar dibanding pria. Dari
‘Tabel 11 dapat dilihat bahwa walapun jumlah Balita
lebih banyak pada penyeluh pria, namun curalan waktu dalam Kegiatan reproduktif,
khususnya mengasuh anak, lebih banyak diberikun oleh wanita, sehingga dapat
disimpulkan bahwa wanita bertanggung jabab dan mempunyai beban yang lebih besar
dalam kegiatan reprodukif dibandingkan pria (Tabel 2). Selain ita penyuluh wanita
‘juga mempunyai tanggung jawab untuk mengurus/merawat orang tuanya. sedangkan
penyuluh pria tidak:
47
Tabel 11. Distribusi Anggota Rumah Tanga Penyuluh Pertanian menurut Jenis
Kelamin dan Kelompok Umur, Tehun 1999
Kelompak: Pria Wanita
Umor jumlah | Persen | Jumlah | Persen
Balita (0-4 talum) 15 194 4 108
Sekolah (5-14 tahun) 33 42.9 13, 35,1
Produktif (15-59 tahun) 29 37,66 19 S14
Manula (lebih dari 60 tabun) 0 0 1 27
Jumloh rata-rata anggota rumah tangga baik pada penyuluh pria dan wanita yang,
sama yaite lima orang, dengan gaji yang tidak terlalu besar, menyebabkan penguasaan
Johan penyuluh pertanian untuk usaha tani tidak Inas. Rata-rata luas penguasaan lahan
baik lahan kering maupun lahan sawah terlihat pada tabel 12, lebih banyak penyuluh
pertanian pria yang menguasai lahan dibanding penyuluh wanita. Banyalnya penyuluh
pria yang menguasai lahan membuat penyuluh pria lebih menguasai praktek penyuluhan
pertanian dibanding penyuluh wanita.
‘Tabel 12. Distribusi Penyuluh pertanian menurut Jonis Kelamin dan Kepemilikan
Lahan, Tatnun 1999
Lathan (m”) Pria Wanita
Sumiah | Persen | Luaerate-reta | Jurlah,
[ Sawah [29 15333, 3
Ladan; 0 0 2380. 1
Pekarangan 23 | 824 2633 8
3 10,7 2
Kolm 3 10,7 @
| Kamdany, 1 1
Gudang, 2 or
Penguasaan Jahan yang tidak begitu luas mengakibatkan tidak banyale penyuluh
yang berusahatani, hal tersebut dapat dipahami mengingat pendapatan/gaji penyuluh
pertanian yang hanya cukup untuk membeli Iahan yang tidak begitu luas sebagai usaha
tani seperti dapat dilibat pada Tabel 13 dimana ponyuluh pertanian pria mempunyai
48
pendapatan/gaiji yang lebih tinggi dibandingkan ponyuluh wanita sehingga lebih mampu
menguasai lahan usahatani
‘Tabel 13. Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Pendapatan Dalam
1 Bulan, Takun 1999
No | Pendapatan Pria, Wanita,
1 Bulan Tumlah Persen Jumlah Persen
1_| SPMA SSPMA__|>SPMA
‘Aksos
<50 Porson 7 5 3 7
(259) 7s) (25,0) (83)
250 Persen 2 4 6 0
(429) (43) (500) (00)
Kontrol
<50Persen 3 T a 7
(17,9) (36 (33,3) (0,0)
> 50 Persen 6 ° 7 1
(21a) (oo (383) (83)
Keterangan + Angka dalam () Merupakan Persertase
Dari Tabel 30, diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok
penyulub pertanian tidak dilaksanakan secara maksimal. Hal ini akon menyebabkan
menurunya kualitas dan luantitas produksi pertanian mengingat penyuiuh pertanian
merupakan ujung tombak pembangunan pertanian dan fasilitetor antara pemerintah,
pengusaha, peneliti dan petani.
7.3.2.Hubungan Golongan Kepangkatan dengan Akses dan Kontrol
dalam Kegiatan Produkiif
Dari Tabel 31 dapat dilihat perbedaan yang cukup nyata antara akses dengan
golongan kepangkatan dan kontrol dengan golongan kepangkatan pada peayuluh pria.
‘Akses lebih dari 50 persen pada penyuluh pria berada pada golongan honorer dan II
sebesar 14,3 persen dan golongan Il dan IV sebesar 42,9 persen, sedangkan kontrol
lebih dari 50 person berada pada golongan honorer dan II (10,7 persen) dan golongan
‘Dl dan IV sebesar 46,4 persen.
Tidak berhubungannya skees dan kontrol denga: golongan kepangkatan
penyuluh pertanian pria membuktikan tidak adanya sistem senioritas yang, diterapkan
dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan kegiatan produldif penyuluh pertanian.
Hal ini terjadi karena tidak adanya pembedaan golongan dalam melaksanakan tugas
yang sama.
3
Tabel 31. Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Golongan
Kepangkatan, Akses dan Kontrol dalam Kegiatan Produktif
20Taun [<20 Tan | >20Tabun
Aksos
<50 Persen 5 7 hd 7
7,9) (259) (333) 63)
250 Persen 7 7 7 z
(25,0) (33,1) 6,7) 333)
Kontrol,
<50 Persen 6 6 1 3
(21) cig (33) (259)
250 Persen 6 10 es 2
(ia (35) (ay 25,0)
‘Keterangan = Angka dalam () Meropakan Peraentase
Dari Tabel 32 juga dapat dilihat kontrol penyuluh pria dan wanita yang
dibubungakan dengan masa kerja. Pada penyuluh pria kontrol kurang dari 50 persen
tersebar dan sama besar berada pada masa kerja kurang dari 20 tahun dan masa kerja
lebih atan sama dengan 20 tahun (21,4 persen), sedangkan kontrol lebih atay sama
dengan 50 persen berada pada masa kerja kurang dari 20 tahun (21,4 persen). Berbeda
dengan hubungan antara kontrol pria dengan masa kerja, pada penyuluh wanita kontrot
Tebih atau sama dengan 50 persen tersebar pada masa kerja kurang dari 20 talnm (41,7
persen) dan masa Kerja lebih ata sama dengan 20 tahun (25,0 persen), sedangkan
kontrol kurang 50 persen berada pada masa kerja kurang dari 20 tahun (25,0 persen).
Penyebaran yang cukup merata antara masa kerja kedalam kontrol dalam
kegialan produktif pada peayuluh pria maupun wanita terkait dengan pelimpaban
wewenang dan pembagian kerja yang merata baik di BIPP mpun di BPP tanpa
membedakan senioritas
7.3.4, Hubungnn
Produktif
‘Motivasi sescorang berkaitan dengan sikap dan pandangan responden terhadap
bidang pekerjaannya. Salah sofu yang menjadi ukuran adalah akses responden terbadap
bidang tugesnya, Pada Tabel 33 dapat dilihat pada penyuluh pria akses kurang dari 50
JMotivasi dengan Akses dan Kontrol dalam Kegiatan
15
persen berada pada penyuluh bermotivasi pribadi (14,3 persen) sedangkan akses lebih
atau sama dengan 50 persen berada pada penyuluh dengan motivasi pribadi (14,3
persen) dan negara (42,9 persen). Hal ini terkait dengan motivasi penyuluh pria yang
dominan bermotivasi pribadi yong berhubungan dengan pemenuban kebutuban keluarga
karena pria merupakan kepala rumah tanga yang harus memenuhi kebutuhan
keluarganya.
Pada ponyuluh wanita akses kurang dari 50 persen berada pada penyuluh
dengan motivasi pribadi (25 persen) dan akses lebih dari 50 persen berada pada
penyuluh yang mempunyai motivasi negara (50 persen), Hubungan positif yang terjadi
smenggambarkan tinggi rendabnya kuantitas penyuluh pertanian dimana penyuluh dengan
motivasi pribadi menyebabkan akeosnya rendah, sedangian motivasi bagi negara
menyebabkan aksesnya tinggi.
‘Tabel 33. Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Motivasi, Akees dan
Kontrol dalam Kegiatan Produltif’
Mofivasi
Akses dan Kontrol Pria ‘Wanita
Pribadi_[ Negara Pribadi ‘Negara
Alses
<50 Persen 4 s 3 3
43) (286) (250) 25,0)
2 50 Persen 4 12 @ é
43) 42,9) (oo) (509)
Kontrol |
50 Persen 3 o @ a
107) (21) (00) (333)
250 Persen 3 y 3 3
79) (39,3) (25,0) (41,7)
‘Keterangen : Anake dalam () Meropaken Persentase
‘Hal menarik yong dapat dilihat dari Tabel 33 adalah adanya porsamaan antara
kontrol penyuluh pria dan wanita. Pada penyuluh pria kontrol iebih dari 50 persen
berada pada penyuluh dengan motivasi pribadi (17,9 persen) dan negara (39,3 persen),
sedangkan pada penyuluh wanita kontrol lebih dari 50 persen berada pada penyuluh
dengan motivasi pribadi (25,0 persen) dan negara (41,7 porsen).
16
‘Tidak bertubungamya motivasi dengan kontrol baik pada ponyaluh pria dan
wanita dapat difhami mengingat beban tanggung jawab tidak diberikan berdasarian
motivasi, namun kechliavkemampuan dalam molaksanakan dan mengambil keputusan
tersebut.
7.4. Hubungan Sumberdaya Keluarga Dengan Akses Dan Kontrol
Dalam Kegiatan Produktif
74.1. Hubungan Kepemilikan ternak dengan Akses dan Kontrol dalam
Kegiatan Produktif
Pada Tabel 34 dapat dilibat hubungan antara kepemilikan ternak dengan akses
dan kontrol penyuluh pertanian. Pada penyuluh pria akses lebih alan sama dengan 50
person berada pada penyuluh yang momiliki temnak kurang dari SO point (32,1 person)
dan lebih atau sama dengan 50 point (25 persen). Sama halnya dengan akses, kontrol
lebih dari 50 persen pada penyuluh pria juga tersebar pada penyuluh yang memiliki
ternek kurang dari 50 point (32,1) dan lebih atau sama dengan 50 point (25 persen).
‘Tabel 34, Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Kepemilikan Ternak,
Akses dan Kontrol dalam Kegiatan Produktif
‘Kepemilikan Ternak
Akses dan Kontrol Pria ‘Wanita
< 50 Point 2 50 Point <50 Point = 50 Point
Akses:
-<50 Porsen 7 3 3 1
(25,0) (17,9) 41,7) (83)
9 7 8 3
ee cay (250 (500) 00)
Kontrol
<50 Persen 7 3 4 7
t (25,0) 7,9) (33,3) (583) 4
9 7 0 it
250 Persen (25) (oo) (83)
(32,1)
‘Keterangan | Angka dalam () Merupakan Persentase
‘Tidak berhubungannya kepemilikan termak dengan akses maupun kontrol pada
ponyuluh pertanian pria lebih disebabkan tugas pria yang bersifat teknis dan
berkubingan dengan usahatani (termak) monyebebkan skses dan kontrol pria terhadap
bidang tugasnya tinggi.
Pada penyuluh wanita, akses lebih atau sama dengan 50 persen berada pada
penyuluh yang memiliki temak kureng dari 50 point (50,0 persen) dan akses kurang dari
‘50 persen berada pada penyuluh yang memiliki ternak lebih atan sama dengan 50 point
(8,3 persen), sedangkan kontrol kurang dari 50 persen penyuluh pertanian wanita
tersebar pada penyuluh yang momiliki ternak Kurang dari 50 point (33,3 persen) dan
penyuluh yang memiliki ternak lebih stan sama dengan 50 point (58,3 persen).
Hubungan negatif yang terjadi pada hubungan antara akses wanita dengan
kepemilikan ternak menggambarkan bahwa usaha teak yang kurang dari 50 point
menyebabkan wanita mampu akses terhadap kegiatan produktif, sedangkan ponyuluh
wanita yang mempunyai teak lebih atan sama dengan SO point tidak mampu lebih
akses terhadap kegiatan produktif mengingat tidak adanya bantuan tonaga kerja keluarga
menyebabkan wanita tidak mampu membagi waktunya dengan baik.
7.4.2.Hubungan Kepemilikan Lahan dengan Akses dan Kontrol dalam
Kegiatan Produktif
Pada Tabel 35 dapat dilihat hubungan aksos dengan kepemilikan ternak antara
penyulub pertanian pria dan wenita mempunyai pola yang sama Pada penyuluh pria,
akses lebih ata sama dengan 50 persen berada pada penyuluh yang memiliki laban
Kurang dari 1000 M? (39,3 persen) dan akses kurang dari 50 persen berada pada
penyuluh yang memiliki lahan lebih atau sama dengan 1000 M? (25,0 persen),
sedangkan pada penyuluh wanita, okses lebih atau sama dengan 50 persen berada pada
penyuluh yang memiliki aan kurang dari 1000 M? (33,3 persen) dan akses kurang dari
50 persen berada pada penyuluh yang memiliki lahan lebih atan sama dengan 1000 iM”
(25,0 persen),
Hubungan negatif yang terjadi bik pada penyuluh pria maupun wanita
disebabkan pembagian waktu yang kurang baik, dimana disatu sisi ia harus bekerja
sebagai penyuluh pertanian hingga mampu lebih akses, namun disetu sisi ia harus
dekerja untuk mengelola Iahanya. Pengelolaan lahan yang cukup menyita wakts
rT
menyebabkan berkurangnya jam kerja sebagai penyuluh pertanian, schingga aksesnya
terhadap kegiatan dan pelakeanaan penyuluhan pertanian tidak optimal.
‘Tabel 35. Distribusi Penyulub Pertanian menurut Jenis Kelamin, Kepemilikan Laban,
Akses dan Kontrol dalam Kegiatan Produktif
Kepemilikan Laban
Aksos dan Kontrol Pria Wanita
<1000M [ >1000mM' | <1000M [ >1000M
‘Akses
<30 Person 5 7 3 3
(17,9) (25,0 (25,0) (25,0)
> 50 Persen VW 3 2 2
(393) 79) (333) 67)
Kontrol
<30 Persen 6 6 3 4
(21,4) (214) (25,0) (33,
250 Persen 10 a 1 :
(35,7) (21,4) (8,3 (33,3)
‘Keterangan : Angka dalam () Merupakan Persentase
Hubungan antara kontro! dengan kepemilikan lahan juga dapat dilihat pada Tabel
35. Pada penyuluh pria kontrol lebih atau sama dengan 50 persen tersebar pada
penyuluh yang memiliki tahan kurang dari 1000 M? (35,7 persen) dan Jahan lebih atau
sama dengan 1000 M? (21,4 persen), sedangkan kontrol! kurang dari 50 persen berada
pada penyuluh yang memiliki lahan lebih atau sama dengan 1000 M? (21,4 persen). Hal
ini disebabkan pekerjaan teknis pria yang membutuhken Jahan sebagai pemunjang
pelaksanaan tages, sehingga kontrol yang diberiken padanyapun tinggi mengingat
pongalaman dilapang eudah cukup baik.
Pada penyoluh wanita kontrol kurang 50 persen tersebar pada penyuluh yang
memiliki Jahan kurang dari 1000 M? (25,0 persen) dan lahan lebih atau sama dengan
1000 M? (33,3 persen), sedangkan kontrol kurang dari 50 persen berada pada penyuluh
yang memiliki Iahan lebih atau sama dengan 1000 M? (33,3 persen). Hal ini terjadi
Karena tugas yang bersifat administrasi tidak mengharusken wanita memiliki fahan
sebagai penunjang tugas, Selain itu pekerjaan penyuluh pertanian yang lebih bersifat
teknia lebih dipereayakan kepada penyuluh pertanian pria dibandingkan pada penyaluh
wanita,
9
7.4.3. Hubungan Kepemilikan Benda Berharga dengan Akses dan
Kontrol dalam Kegiatan Produktif
Dari Tabel 36 dapat dilihat pada penyuluh pria akses lebih atau sama dengan
'50 persen tersebar pada penyuluh yang memiliki benda berharga kurang dari 50 point
(42,9 persen) dan Jebih atan sama dengan 50 point (14,3 person), begitu pula
Kontrolaya dimana kontrol lebih atau sama dengan 50 persen tersebar pada penyuluh
yang memiliki benda berharga kurang dari SO point (42,9 persen) dan lebih atau sama
dengan 50 point (14,3 persen). Penyebaran yang merata pada akses dan kontrol yang
tinggi terhadap kepemilikan benda berharga pada pria membuldilkan benda berharga
merupakan penunjang pekerjaan pria yang bersifat teknis.
abel 36, Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jonis Kelamin, Kepemilikan Benda
‘Berharga, Akses dan Kontrol dalam Kegiatan Produktif
Kepemilikan Benda Berharga
Akses dan Kontrol Pria, ‘Wanita
=50Point [ =50Point |
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Laporan Praktikum DPK Kelompok 5Document7 pagesLaporan Praktikum DPK Kelompok 5Siti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Denah Duduk SiswaDocument3 pagesDenah Duduk SiswaSiti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Cover PROPOSALDocument1 pageCover PROPOSALSiti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Modul PBHP2Document10 pagesModul PBHP2Siti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Green and Dark Gray Creative Illustrated Cooking Class PresentationDocument35 pagesGreen and Dark Gray Creative Illustrated Cooking Class PresentationSiti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Penangananan BHP - Pre TreatmentDocument28 pagesPenangananan BHP - Pre TreatmentSiti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Panduan PraktikumDocument8 pagesPanduan PraktikumSiti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Denah Raport 2122 GanjilDocument5 pagesDenah Raport 2122 GanjilSiti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Soal Dan Jawaban PAT B Indonesia Kelas XDocument14 pagesSoal Dan Jawaban PAT B Indonesia Kelas XSiti Rahayu Salsabila100% (1)
- Untitled DesignDocument30 pagesUntitled DesignSiti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Jadwal Ukk Kedelai - 12 A7Document2 pagesJadwal Ukk Kedelai - 12 A7Siti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- KPT Apr2004Document5 pagesKPT Apr2004Siti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Jiptummpp GDL Ahmadkrist 50086 3 Bab2Document16 pagesJiptummpp GDL Ahmadkrist 50086 3 Bab2Siti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Skripsi Tanpa Bab PembahasanDocument57 pagesSkripsi Tanpa Bab PembahasanSiti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- 2016 JadDocument103 pages2016 JadSiti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Surat Peminjaman BemDocument2 pagesSurat Peminjaman BemSiti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Keracunan AlDocument7 pagesKeracunan AlSiti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Tugas Paper - Pak SusiloDocument22 pagesTugas Paper - Pak SusiloSiti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Skenario Short Movie (Historical of Place)Document2 pagesSkenario Short Movie (Historical of Place)Siti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Makalah Kemitraan Kelompok 1 (1c)Document19 pagesMakalah Kemitraan Kelompok 1 (1c)Siti Rahayu SalsabilaNo ratings yet
- Nata de CocoDocument10 pagesNata de CocoSiti Rahayu SalsabilaNo ratings yet