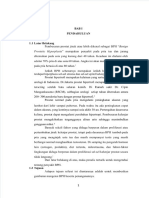Professional Documents
Culture Documents
4
4
Uploaded by
dafir firdaus0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views8 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views8 pages4
4
Uploaded by
dafir firdausCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 8
BEBERAPA ASPEK DIAGNOGKS KLIS DEMAH BERDARAH DENGUE
. Sutaryo
Jurusan fimu Kedokteran Medik
Fakuitas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yooyakarta
Pendahuluan
Demam berdarah dengue (DBD) atau Dengue Haemorrhagic Fever (OHF)
sejak tahun 1953 menjadi salah satu penyebab sakit dan kematian pada
anak yang utama di Asia Tenggara. Epidemi telah ter jadi di Burma,”
Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysja, Filipina Singapura, Thailand, dan
Vietnam. Di Cina, India, Sri Lanka dan Cuba juga ter jadi waban yang
serupa. Dari negara-negara tersebut telah dilaporkan 750.000 pasien
dirawat di rumahsakit dalam 25 tahun terakhir dengan 20,000 kematian
(WHO, 1985),
Di Indonesia DBD mulai dikenal pada tahun 1968 di Jakarta dan Sura~
baya (Kho et a/., 1969; Partana and Partana, 1970). Setelah itu penya~
kit tersebut menyebar Ke seluruh pelosok tanah air. Jumiah kasus pada
tahun 1983 sebanyak 13.668, tahun 1984 sebanyak 12.710 dan tahun 1965
sebanyak 13.588, Angka kematian pada masing masing tahun tersebut ada-
lah 491, 362 dan 185. Satu-satunya propinsi yang belum melaporkan
adanya Kasus DBD adalah Timor Timur (Sureso and Bang, 1986).
Sebelum tahun 1975 penyakit tersebut hanya terdapat di perkotaan.
Tetapi setelah itu juga terdapat dipelosok desa (Suroso, 1983). Keja-
dian tersebut akan membawa puskesmas sebagai penemu awat pasien DBD.
Dokter praktek pribadi dan poiiklinik juga merupakan institusi pertama
yang akan dikunjungi pasien DBD.
Permasalahan yang timbul adalah bagaimana cara menegakkan diagnosis
yang awal dan tepat sebelum terjadi penyulit yang berat yaitu syok dan
atau perdarahan. Karena tidak semua pasien DBD harus dirujuk untuk
Perawatan maka timbul masalah dalam hal pemisahan pasien yang dapat
berobat jalan dan pasien yang harus dirawat. Dalam tulisan berikut
akan dibahas beberapa aspek diagnosis Klinis, kesulitan serta pemeca-
han masalah untuk menetapkan diagnosis secara awal dan tepat DBD bak
di poliklinik, praktek dokter swasta maupun puskesmas untuk dikelola
sebagamana mestinya, sehingga dapat menurunkan angka Kematian.
Kriteria Diagnosis
Patokan WHO(1975) untuk membuet diagnosis DBD ditetapkan sebagai
berikut:
Serita Kedokteran Masyarakat [W:1
cen N2eR_407% .k1 AW No. ft Januari 1988
12 Berita Kedokteran Masyarakat IV:t
Klinik:
1. Demam tinggi yang mendadak dan terus menerus selama 2-7 hari.
2. Manifestasi perdarahan,termasuk setidak tidaknya uji tourniquet po-
sitif dan salah satu bentuk perdarahan yang lain misainya: petekie,
Purpura, ekimosis, epistaksis, perdaranan gusi, hematemesis atau
melena,
3. Pembesaran hati.
4, Syok yang ditandai oleh nadi cepat dan lemah, tekanan nadi yang me~
fhurun (menjadi 20 mmHg atau kurang), tekanan darah sistolik sampai
60 mmig atau Kurang disertai Kulit teraba dingin dan lembab teruta-
Mma Pada ujung jari tangan dan Kaki, penderita menjadi getisah, dan
timbul sianosis disekitar mulut. .
Laboratorium:
4, Trombositopeni, 100.000 per mm kubik atau Kurang,
2. Hemakonsentrasi yang dapat dilihat dari Kenaikan hematokrit seba-
yak 20% atau lebih dibandingkan dengan aoitai hematokrit pada masa
penyembuhan, .
Oitemukan dua atau tiga patokan kiinis pertama disertai trombosito-
penia dan hemokonsentrasi sudah cukup untuk secara Klinis dibuat
diagnosis DBD, Selanjutnya WHO (1985) membagi derajat 080 sebagai
berikut:
_ Derajat Deskripsi
' Demam disertai gejala tidak knas dan satu satunya manifes-
tasi perdarahan yang ada adalah uji tourniquet positif.
a, Deréjat | disertai manifestasi perdarahan spontan.
ih Kegagalan sirkuiasi yang ditunjukkan oleh nadi yang cepat
dan lemah, penurunan tekanan nadi (20 mmHg [2.7 kPa) atau
Kurang) atau hipotensi.
Vv profound shock dengan adi dan tensj tidak terukur.
Pemeriksaan virologi dan serologi (HI, CFT, NT) merupakan diagnosis
pasti. Ketepatan kriteria Klinis WHO (1975) di atas berkisar antara
64%-80%. Kriteria tersebut sangat berguna karena hasil virologi yang
sukar diharapkan positif dan serologi yang datangnya sangat terlambat.
Sehingga untuk penanganan segera kriteria tersebut harus digunakan.
Ada beberapa kesulitan di dalam penerapan kriteria diagnosis klinis
WHO (1975),
Sutaryo, 1988 Beberapa Aspek Diagnosis Kiinis 13
1. Uji tourniquet.
Uji tourniquet atau tes Rumple Leede dikerjakan sebagai berikut:
- Tetapkan tekanan darah dengan memasang manset pada lengan atas. Man-
set harus menutup 3/4 iengan atas, jangan teriaiu lebar atau sempit.
- Berikan tekanan dj antara sistolik dan diastolik pada alat pengukur.
Tekanan diberikan selama 5 menit.
~ Lepaskan tekanan tersebut
- Perhatikan timbuinya petekia pada kulit lengan bawah bagian medial
sepertiga bagian proksimal.
- Uji dinyatakan positif apabila pada satu inci persegi (2,8 cm x 2,8
cm) didapat lebih dari 20 petekie. ,
Hambatan dan kesalahan yang sering ter jadi pada uji tourniquet ada~
jah sebagai berikut:
@- Tensimeter yang tidak baik, Kebocoran tensimeter akan menyebabkan
tekanan yang diberikan selama 5 menit tidak memenuhi sasaran, se-
hingga hasilnya negatif. Tindakan yang salah dan sering terjadi un-,
tuk mengatasi kejadian tersebut adalah mengadakan pengikatan dengan
karet gétang,
Manset terlalu lebar. Pada umumnya di ruang periksa hanya ada satu
macam manset dewasa sehingga untuk lengan anak terlalu lebar. Kesa—
Jahan umum yang dikerjakan adalah terus menggunakan manset itu atau
dengan melipat manset yang tentu hasilnya sulit dipercaya.
. Anak yang sedang mendapat periakuan tes tourniquet rewel sekali ka-
rena merasa kesakitan sehingga pemeriksa enggan melakukan atau me-
ngurangi waktu tes, dengan demikian hasilnya tidak seperti yang
seharusnya ter j
d. Timbuinya petekie tidak segera setelah manset dilepas, sehingga
perlu ditunggu 2 sampai 5 menit.
@. Penilaian yang salah. Petekie di fossa kubiti dihitung.
. Penilaian jumlah lebih dari 20 petekia per inci persegi tidak di-
patuhi. Sehingga asal ada titik petekie dianggap positif.
g. Uji tourniquet diker jakan pada lengan yang masih ada sisa petekie
hasil uji yang telah lalu sehingga menimbulkan jumiah petekie yang
Jebih banyak,
Uji tourniquet akan negatif kalau pasien dalam keadaan syok, Uji
harus diulang setelah tensi dan nadi terukur dengan baik,
Pada dokter yang terlal banyak pasien enggan melakukan ui ini ka-
rena memakan waktu yang lama, minimal 5-10 menit.
b,
h
2. Perdarahan spontan
Perdarahan spontan pada awal penyakit sering tidak ada. Melena, he-
matemesis, perdarahan yang berat ter jadi setelah syok. Petekie yang
terjadi tidak selalu di bagian tubuh yang terbuka, sehingga perlu di-
4 Berita Kedokteran Masyarakat (V:1
teliti seluruh Kulit. Hal tersebut jarang dilakukan karena keengganan.
Kesulitan jain akan timbul kalau kamar periksa Kurang terang atau
praktek di waktu sore atau matam hari.
3. Hepatomegali
Kisaran penemuan hepatomegali sangat besar. Di Thailand dengan dasar
Kriteria WHO (1975) didapatkan 95%, di Filipina hampir tidak ada, di
Bantul 18,9 % (Eram, 1979), Penyebab perbedaan tersebut kemungkinan
besar ada tiga hal:
2. Ketidaksamaan mengenai kriteria hepatomegal. Ada yang menggunakan
kriteria Blanknart, ada yang mengambil Kriteria 2 cm di bawah arkus
kostarum pada linea aksilaris media, ada yang menggunakan pembesa-
ran hepar adalah pembesaran yang dibanding hari yang telah lalu
atau pada masa penyembuhan.
. Pembesatan hepar pada DBD merupakan proses yang ber jalan,Sejak hari
ketiga akan nampak jelas pembesarannya sampai hari ke enam, lalau
mengecil lagi. Jadi kalau hanya sekali memeriksa sangat sulit men-
dapatkan proses pembesaran hepar.
Kriteria hepar yang normal belum ada kesepakatan antar ahli ter—
utama yang menyangkut umur dan daerah. Pada daerah PCM tentunya
pembesaran hepar merupakan keadaan yang sering terdapat.
c,
Tindakan yang harus -diker jakan untuk menjaring adanya hepatomegali
adalah mengusahakan pasien supaya Kontro} setiap hari, sambi) menandai
besarnya hepar. Hal ini sukar dikerjakan tanpa pendekatan yang baik
dengan orangtua.
4, Syok
Tidak semua pasien DBD akan jatuh ke dalam syok (derajat il dan IV
atau Dengue Shock $yndrome, DSS). Kisaran yang syok pada pasien yang
di rumahsakit sekitar 10-30% dari seluruh pasien DBD yang dirawat.
Gradasi syoK sangat bervariasi Sejak dari yang ringan sampai yang
berat. Untuk bisa mengetahui gradasi tersebut dokter narus banyak
pengalaman sehingga mempunyai pandangan Klinik yang tajam.
5. Trombositopenia
Cara pemeriksaan trombosit dengan fase kontras sulit dikerjakan di
daerah bernubung dengan fasilitas dan ketrampilan yang terbatas. Peng~
hitungan trombosit dengan menggunakan bilik hitung dan digabung dengan
penghitungan tak langsung dari preparat darah tepi merupakan pilihan
yang bisa diterima. Kesulitan pemakaian kriteria ini selain masalah
kKetrampilan penghitungan trombosit juga pada kasus yarig positif DBD
secara Virologi atau serologi belum tentu menunjukkan trombositopenia.
Sumarmo et a/. (14983) menemukan trombositopenia pada 81,34 Kasus de-
Sutaryo, 1988 Beberapa Aspek Diagnosis Kiinis 15
ngan virologi positip. Itu berarti satu di antara lima pasien tidak
menderita trombositopenia. Trombositopenia juga merupakan proses yang
berjalan. Pada hari pertama sampai Ketiga praktis tidak akan dijumpai
trombositopenia. Trombositopenia baru terjadi pada hari ke empat dan
bertahan sampai hari keenam atau ketujuh (Sutaryo et al., 1982). Jadi
tidak bisa menetapkan trombositopenia hanya dengan seKali periksa.
Kembali problem di sini adalah mengharapkan pasien mau kontrol setiap
hari terutama pada hari keempat sampai keenam.
6, Hemokonsentrasi
Istilah hemokonsentrasi sering disalah artikan dengan hematokrit
Tebin dari 40%, Padahal kriteria WHO (1975) menuntut kenaikan hemato-
krit lebih dari 20% dibanding dengan masa penyembuhan. Kesulitan tim-
bul kalau pada saat pertama menerima pasien dengan hematokrit misainya
45%. Apakah nilai tersebut termasuk hemokonsentrasi atau tidak? Kalau
pada masa penyembuhan hematokrit 35 % berarti angka tersebut menunjuk—
kan hemokonsentrasi. Tetapi kalau hematokrit masa penyembuhan 42% maka |
tidak termasuk hemokonsentrasiKarena harus menunggu hasil pada masa
penyembuhan maka timbul Kesulitan pada waktu mengadakan diagnosis
kerja waktu pasien datang pertama kali. Apakah betut pasien yang dina-
dapi sesuai dengan kriteria WHO?
Hambatan lain adalah tidak selalu tersedia alat mikrosentrifuge un-
tuk pemeriksaan mikrohematokrit, Kesulitan itu bisa diatasi dengan
pemeriksaan hemoglobin. Tetapi cara pemeriksaan hemoglobin cara Sahli
mempunyai resiko kesalahan besar, Paling baik adalah memeriksa hemo—
globin cara sianmethemogiobin dengan spektrofotometer. Tetapi alat. ini
pun serupa dengan mikrocentrifuge yang belum tentu ada di setiap dae-
rah endemik. Cara Sahli sebaiknya dikerjakan oleh satu orang dengan
memperhatikan cara pemeriksaan secara cermat. Hubungan antara hemo-
globin dan hematokrit ditunjukkan oleh Sumarmo (1983).(Gambar 1).
Kesulitan lain yang didapat dalam menetapkan hemokonsentrasi adalah
kapan pasien mengalami perdarahan. Dalam Keadaan perdarahan yang ba-
nyak maka hemokonsentrasi sulit ditemukan. Pemberian cairan dan plasma
akan menurunkan hematokrit. Transfusi darah yang diberikan juga akan
memberikan kadar hematokrit pada masa penyembuhan lebih tinggi daripa-
da kalau tidak ditransfusi. Kenaikan hematokrit pada saat penyembuhan
akan mengurangi Kemungkinan penetapan hemokonsentrasi,
Dengan menggunakan Kriteria.diagnosis Klinis WHO (1975) di antara
499 penderita yang dirawat, 356 penderita (71,7%) disokong oleh hasi}
pemeriksaan serologis dan atau virologis (Sumarmo, 1963), Berdasar ke-
terbatasan tepatnya diagnosis Kriteria WHO (1975) tersebut, maka akan
Sangat berkurang lagi ketepatan diagnosis DBD kalau hanya mengambil
satu atau dua gejala saja. Conton yang paling populer adalah panas dan
uji tourniquet yang positif sudah dianggap DBD.
16 Berita Kedokteran Masyarakat [V:1
19
o se ——Xx
‘ 8 10 i 4 16 18 He GAD
Gambar 4. Korelasi antara Hb dan Ht pada 200 orang penderita DBD pada
masa akut dan penyembunan (keseturuhan terdapat. 400 hasil
pemeriksaan), (Sumber; Sumarmo Sunaryo Poorwo Soedarmo,
- Demam Berdarah (Dengue) pada Anak, Ul-Press 1983)
Kesalahan diagnosis tersebut akan mempunyai dampak yang twas, antara
lain:
\. Kerugian tenaga, waktu , obat dan dana untuk pengelolaan pasien
yang sebetulnya tidak perlu.
2, Menmbulkan efek kecemasan pada keluarga pasien dan masyarakat.
3, Diagnosis yang salah itu digunakan untuk laporan ke Departemen Ke-
sehatan, sehingga menyebabkan kesalahan pelaporan, penilaian serta
Pengambilan kKeputusan dan kebijakan karena kesalanan analisis.
4, Kalau di tempat tinggai pasien dan sekitarnya dilakukan pemberanta~
san nyamuk dengan pengasapan malathion dan abatisasi berarti pro-
gram tersebut salah sasaran.
Ada beberapa penyakit dengan gejala panas dan uji tourniquet posi-
tip, di antaranya: morbili, tifus, difteri,trombositopeni purpura,
leukemia, sepsis (Erwin Santosa et a/, 1961), Yogyakarta adalah daerah
endemik demam berdarah dengue dan tifus. Bila panas tinggi menginjak
hari ke empat atau kelima disertai uji Rumple Leede positif, maka se-
ring merupakan persoalan bagi dokter yang pertama kali menerima.
Sutaryo et al. (4986) membedakan kedua penyakit tersebut (Tabel 1).
Sutaryo, 1986 Beberapa Aspek Diagnosis Klinis 47
Tabel diagnosis banding demam dengue berdarah dan demam tifoid.
Pengamatan Demam Dengue Berdarah Demam Tifoid
Panas tinggi ada ada
Kesadaran menurun ada ada
Keluhan perut ada ada
Syok ada pada DSS ada pada Syok
septik
Uji Rumpte Leede _—positif dapat positif
Hepatomegali ada, cepat ada
Hematokrit meningkat normat
Leukopenia ada ada
Trombositopenia ada Jarang
Limfosit Plasma Biru lebih dari 5% Kurang dari 5%
Eosinofil timbul hari ke 5 atau 6 belum timbul
(Sumber: Sutaryo, 1986)
Sepsis dengan syok sangat sulit dipisahkan dari OSS. Karena kesuli-
tan tersebut, banyak yang segera memberikan antibiotika untuk keadaan
DSS, disamping alasan pada syok sangat lemah dan banyak tindakan mani~
pulasi, Kultur darah sangat menentukan pemisahan tersebut. Klinisi
tentunya akan mengamati gambaran perjalanan Klinis yang berbeda,
leukositosis atau leukopeni, toksik granulasi pada segmen netrofil,
persentase bentuk batang dan segmen. Asites dan efusi pleura disertai
udem lebih cepat ter jadi pada DSS. Chikungunya mempunyai gejala yang
mirip dengan 08D. Perbedaan yang nyata ialah pada penyakit yang
disebabkan oleh virus Chikungunya tersebut tidak menimbulkan perdara—
han, syok dan Kematian (Kandun, 1985).
Kesimpulan
DBD termasuk penyebab utama sakit dan Kematian pada anak di Asia
Tenggara. Penyakit ini dikenal di Indonesia sejak tahun 1969 di Sura—
baya dan Jakarta, kemudian menyebar ke daerah perkotaan. Sejak tahun
4975 penyakit ini juga menyerang daerah pedesaan, sehingga membawa
konsekuensi Puskesmas dan dokter praktek swasta harus bisa mendeteksi
awal adanya penyakit DBD/DSS, Kriteria diagnosis menurut patokan WHO
(1975) banyak dipakai untuk menegakkan diagnosis. Didalam tulisan ini
telah dibahas pelbagai’ aspek Kesulitan penggunaan eria tersebut
dan cara pemecahannya. Karena kriteria tersebut nilai diagnostiknya
terbatas maka apabila kriteria tersebut tidak digunakan secara benar
6 Gerita Kedokteran Masyarakat Wit
akan mengakibatkan banyak Kesalahan diagnosis. Kesalahan diagnosis
‘tersebut akan mempunyai dampak yang las dan tidak menguntungkan baik
bagi pasien, dokter, perawat, rumah sakit, masyarakat dan negara.
Untuk itu periu peningkatan penghayatan dalam menggunakan kriteria WHO
secara baik dengan meningkatkan ketrampilan klinis dan laboratoris.
Daftar Pustaka “
Eram, S., Setyabudhi, Y., Sadono, TA et af. 1979 Epidemic Dengue
Hemorrhagic Fever in Rural indonesia li, Clinical Studies, Am. U.
Trop. Med. Hyg, 28:7-7%.
Santosa, E. Sutaryo, Asparin, dan Triatmojo 1984 Prevalensi Uji
Tourniquet pada Anak Sakit, Kongres Nominal limu Kesehatan Anak
(KONIKA) VI, Denpasar.
Kandun, LN. 1985 Demam Chikungunya dan Beberapa Kejadian Luar
Biasa di Indonesia, Naskah Lengkap Pendidikan Tambahan Berkala limu
Kesehatan Anak, hal, 6-22, Jakarta. :
tho, LK. Wuiur, H., Karsono, A. dan Thaib, $. 1969 Haemorrhagic
Fever in Ojakarta, Majalah Kedokteran indonesia 19:41T~425,
Partana, L. and Partana, J.S. 1970 Haemorrhagic Fever Shock Syndrome
in Surabaya, Indonesia, Kobe J. Med. Sci. 16:189.
Sumarmo, 1983 Demam Berdarah (Dengue) pada Anak hai, 155 Penerbit
Universitas Indonesia, Jakarta.
Sumarmo, Wuryadi, $. and Gubler D.J. 1986 Clinical observations on
hospitalized patients with virologically confirmed dengue hemorrha—
gic fever in Jakarta, indonesia 1975-1983, Pediat. Indon 26:37.
Songco, RS, Hayes, C.G, Lens, C.D. and Hanaloto, C.0.R, 1987 Dengue
Fever/Dengue Hemorrhagic Fever in Filipina, Children Ciinical Expe-
riece During the 1983~1964, Epidemic Southeast Asian, J. Trop. Med.
Pub, Health 18:284-290,
Suroso, T. and Bang, Y.H. 1985 Control and Prevention of Dengue Hae~
morrhagic Fever in indonesia: Strategy and Thrust. Dengue Newsletter
1147-23
Sutaryo, Hariati, R., dan Suwasono, B. 1986 Pengobatan dan Pengelolaan
‘Demam Two pada Anak, Peningkatan Berkaja limu Kesehatan Anak ke
2, hal. 46, Semarang.
WHO, 1975 Technical Guides for Diagnosis, Treatment, Surveillance,
Prevention and Control of Dengue Haemorrhagic Fever, Technical and
Advisory Committee on Dengue Hemorrhagic Fever for The South-East
Asian dan Western Pasific Region.
WHO, 1985 Viral Haemorrhagic Fevers, Report of a WHO Expert Committee,
Technical Report Series 72t.
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- Referat BPH 56168764c735dDocument41 pagesReferat BPH 56168764c735dIin Sakinah DewiNo ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- LAPSUS Hemoroid DR - SakinahDocument24 pagesLAPSUS Hemoroid DR - Sakinahiin sakinah dewiNo ratings yet
- Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan IklimDocument24 pagesPerspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan IklimIin Sakinah DewiNo ratings yet
- Assesment GeriatriDocument27 pagesAssesment GeriatriIin Sakinah DewiNo ratings yet
- Pidi Angkatan 1ii 2023 10 AgustusDocument69 pagesPidi Angkatan 1ii 2023 10 AgustusIin Sakinah DewiNo ratings yet
- JURNAL 2.en - IdDocument3 pagesJURNAL 2.en - IdIin Sakinah DewiNo ratings yet
- Assesment GeriatriDocument34 pagesAssesment GeriatriIin Sakinah DewiNo ratings yet
- Guideline Urologi Pediatrik Indonesia 4edDocument268 pagesGuideline Urologi Pediatrik Indonesia 4edUrology RSKMNo ratings yet
- Emerg 5 E66Document5 pagesEmerg 5 E66Iin Sakinah DewiNo ratings yet
- Obsos 2Document13 pagesObsos 2Iin Sakinah DewiNo ratings yet
- Obsos 3Document9 pagesObsos 3Iin Sakinah DewiNo ratings yet
- Occupational Rhinitis Due To Steel Welding Fumes: SS 2014 Wiley Periodicals, IncDocument4 pagesOccupational Rhinitis Due To Steel Welding Fumes: SS 2014 Wiley Periodicals, IncIin Sakinah DewiNo ratings yet
- Penanganan Air LimbahDocument78 pagesPenanganan Air LimbahIin Sakinah DewiNo ratings yet
- Praktikum ToksikologiDocument3 pagesPraktikum ToksikologiIin Sakinah DewiNo ratings yet
- Oke 3cejph - cjp-201404-0008.sk - IdDocument5 pagesOke 3cejph - cjp-201404-0008.sk - IdIin Sakinah DewiNo ratings yet
- 29-Article Text-155-1-10-20200212Document14 pages29-Article Text-155-1-10-20200212Iin Sakinah DewiNo ratings yet
- Engagement of Occupational Safety and Health at Mahkamah's Welding Worker MedanDocument6 pagesEngagement of Occupational Safety and Health at Mahkamah's Welding Worker MedanIin Sakinah DewiNo ratings yet