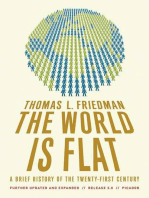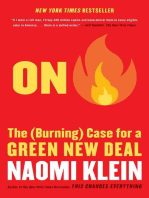Professional Documents
Culture Documents
Amor Fati
Amor Fati
Uploaded by
Bryan Prazetio0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views442 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views442 pagesAmor Fati
Amor Fati
Uploaded by
Bryan PrazetioCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 442
¢
ig \\ 16-1 -1m a
CeO}
SYAHID MUHAMMAD
(ELEFTHERIAWORDS)
AMOR FATI
KITA ADALAH SEPASANG SALAH
YANG MENOLAK PASRAH
Tentang KALA. Tentang proses, romansa. Ya hidup. Dengan
penyampaian yang.. ah, baca saja. Semoga tenggelam.
~ @ghumaydha
Novel yang sungguh puitis, bahkan untuk orang-orang yang
menyukai puisi dan terlalu manis untuk dilewatkan mereka yang
tidak menyukai puisi. Novel ini untuk semua orang yang sempat
kehilangan sesuatu dalam dirinya, dan tetap percaya bahwa kelak
nanti akan menemukannya kembali.
~ Tia Setiawati (Penulis Buku Perempuan Penggenggam Rindu)
Kisah cinta yang lahir dari kolaborasi 2 penulis muda berbakat. Diksi
yang indah dari 2 sudut pandang yang berbeda dikemas dengan
alur yang menarik membuat pembaca tidak sulit untuk memahami
karakter Saka dan Lara. Bacalah, maka kau akan tau bagaimana
indahnya menginterpretasikan gambar ke dalam aksara.
~ Hani (bookstagrammer)
Satu kisah romansa dari dua penulis muda berbakat yang bisa
dikategorikan unik, dengan pemilihan diksi yang tidak umum
digunakan oleh penulis-penulis muda zaman sekarang. Alur kisah
yang manis, diceritakan dalam sudut pandang masing-masing (Saka
dan Lara).
~ F. Annisa (bookstagramer, guru)
Sebuah kisah sederhana yang mencerminkan kehidupan sehari-
hari, tetapi dengan pemilihan kata yang luar biasa indah. Kisah
yang ingin terkubur, namun dia akan selalu menemukan celah untuk
muncul dalam memorimu. Sebab Saka dan Lara adalah kau dan dia.
~ Elmaria (Master Student in Acturial Science, Kent University)
Novel ini recomended banget bagi kalian yang suka bacaan berbau-
bau sastra puisi dan yang gagal move on dalam percintaan.
~ Amberr
Untuk para penikmat sastra, buku ini bisa menjadi salah satu pilihan
untuk dibaca untuk mengisi waktu senggang, dan untuk awam
yang baru atau ingin belajar memahami sastra, buku ini merupakan
pilihan yang tepat.
~ alineafajr
Untuk pecinta genre romance buku ini sangat romantis. Saya
membaca buku ini layaknya orang gila, senyum-senyum sendiri.
Diksi dalam cerita ini amat sangat pas bikin baper. Covernya lucu
hitam manis gimana gitu.
~ Syabillaptr
Aku masih begitu terpukau dengan deretan kalimatnya. Menambah
perbendaharaan kataku juga seperti: entitas, enigma, nisbi, dsb.
Banyak kata-kata baru yang berseliweran, senang aku mendapatkan
pengetahuan lebih. Sekali lagi, tidak picisan.
~ @ra.juwita
Cocok buat yang suka novel yang agak puisi-puisi gitu, setelah
kamu baca halaman pertama, aku yakin kamu gakan bisa berhenti
sampai halaman terakhir.
~ @putridinaryr
Kisah cinta dengan akhir yang lucu. Aku pun mau punya ending
kaya dibuku ini. Semesta yang tidak mau meninggalkan sepasang
manusia yang terluka.
~ irhammaladi (http://www.penar.org)
AMOR FATI
KITA ADALAH SEPASANG SALAH
YANG MENOLAK PASRAH
STEFANI BELLA
{HUJANMIMPI)
SYAHID MUHAMMAD
({ELEFTHERIAWORDS)
€
GRADIEN MEDIATAMA
AMOR FATI
Penulis:
Stefani Bella & Syahid Muhammad
ISBN: 978-602-208-161-6
Penyunting:
flo
Penyelaras Aksara:
Tri Prasetyo
Desain Sampul dan Tata Letak:
eleftheriawords, Techno
Penerbit:
Gradien Mediatama
Redak:
Jl. Wora-Wari A-74 Baciro,
Yogyakarta 55225
Telp/Faks: (0274) 583 421
E-mail: redaksi@gradienmediatama.com
Web: www.gradienmediatama.com
Distributor Tunggal:
TransMedia Pustaka
Jin, Moh, Kahfi 2 No.13-14 Cipedak,
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
: (021) 7888 1000 Fax: (021) 7888 2000
emasaran@distributortransmedia.com
Cetakan Pertama, November 2017
Cetakan Kedua, Januari 2018
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apa pun tanpa izin dari penerbit
Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Stefani Bella & Syahid Muhammad
AMOR FATI /Penulis, Stefani Bella & Syahid Muhammad —
Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2017.
440 him. ; 13 x 19. cm
ISBN 978-602-208-161-6
1. AMOR FATI 1, Judul
I. flo
895
“Dalam sebuah KALA tempat kita bermula,
pada sebuah percaya kita ingin bermuara.”
Thanks To
\\
AMOR FATI tak pernah direncanakan sebelumnya.
Setelah kelahiran KALA, Tuhan dengan rencana-rencananya
membawa kami pada kesempatan yang tidak pernah kami
semogakan. Dengan Keromantisan Tuhan, hinggaplah kami
pada masa yang siap untuk akhirnya AMOR FATI dapat
terlahir dari dua pasang jari-jari kami.
Oleh karena itu, kembali kami ingin memanjatkan syukur
yang tiada henti tercurah. Izinkan kami mengucapkan terima
kasih untuk setiap hal yang sempat bersinggungan di hidup
kami.
Terima kasih kepada Allah SWT, atas segala kesempatan
lainnya, kekuatan, dan seluruh hal yang diberikan kepada
kami hingga detik ini. Sebab, jika bukan karena izin-Nya
karya ini tidak akan bisa lahir.
Kepada keluarga kami, terima kasih atas doa, kasih
sayang, dan support yang tidak pernah ada habisnya.
Kepada editor kami, Mbak Aning, terima kasih sudah
menemukan dan memberikan kesempatan kepada kami
untuk menjadikan kolaborasi ini nyata. Dan, tentunya kepada
seluruh tim Penerbit Gradien Mediatama yang terlibat—Mas
Tepe, Mas Tikno, dan mereka-mereka yang belum kami kenal
namanya—terima kasih. Sebab, tanpa kerja keras mereka
buku ini tidak akan hadir.
Kepada semua pembaca KALA dan tulisan kami lainnya,
kalianlah yang sesungguhnya membuat AMOR FATI punya
kesempatan untuk hidup di hati kalian.
Kepada Fadil dan rekan-rekan di The Point Coffee & Drama
di Jogja, terima kasih telah memberikan kami izin untuk
menggunakan nama tempat coffee shop-nya. Juga, kepada
Kyotown Coffee di Bandung yang menjadi tempat penulis
untuk bisa meramu AMOR FATI.
Dan, kepada Andry Bem Mandariana terima kasih untuk
dukungannya yang tiada henti terhadap kami, juga terhadap
KALA. Terima kasih atas kreativitas dan karyanya karena
telah dengan luar biasa membuatkan sebuah lagu tentang
SAKA dan LARA.
Last but not least, kepada seluruh sahabat, teman, dan
orang-orang yang mengenal kami—baik yang hanya singgah
dan masih bertahan hingga sekarang—terima kasih sudah
hadir dan memberikan banyak pelajaran akan kehidupan.
Darl Kami with Camu
\\
Hai, selamat berjumpa lagi! Bagaimana, sudah
bosan dengan kisahku? Atau, justru semakin
penasaran dengan ceritaku dengannya? Sebab,
menurut kabar yang kudengar, kamu bahkan teman-
temanmu cukup gemas dengan akhir yang katanya
menggantung.
Padahal siapa bilang itu menggantung? Menurutku,
yang kemarin itu adalah akhir terbaik yang bisa aku
ceritakan. Kamu tahu kan, meminta lebih terkadang justru
tak akan berakhir baik? Bagaimana jika nanti pada apa
yang kuceritakan ini, malah akan kamu temui hal-hal yang
mengecewakan? Jangan protes! Ingat, ini juga maumu kan?
Maka, saat ini aku putuskan untuk kembali,
menyelesaikan apa-apa yang belum selesai. Ya, aku kembali,
pada rangkaian kisah yang belum jua usai. Aku kembali,
pada potongan-potongan kejadian yang membawaku untuk
mengurai kembali segalanya agar lebih jelas. Bila pada kisah
Jalu katamu aku terlalu egois dan menuntut, maka kali ini
mungkin saja masih akan atau malah berubah. Entah aku tak
tahu juga.
Sudahlah, aku tahu kamu tak ingin berlama-lama
membaca ini. Justru kamu mungkin lebih tertarik untuk
membalik halamannya. Maka, segeralah balik halamannya
Jalu lanjutkan cerita yang kemarin sempat tertunda. Tapi
ingat, tak usah gemas sendiri. Ajak saja temanmu untuk ikut
serta merasakannya.
Sebab, kisahku ini bukan hanya tentang perjalanan
melainkan juga tentang pelajaran. Sebab, kisahku ini bukan
hanya perihal kisah cinta yang manis atau penuh kemelut, tapi
juga tentang sebuah penerimaan akan hidup. Tenggelamlah
bersama barisan aksaranya, tapi jangan sampai hanyut,
karena pagi masih menantimu untuk kembali.
Oh ya, jangan selalu berharap akhir dari kisahku ini
akan penuh kebahagiaan. Sebab mungkin, definisi bahagiaku
denganmu memang tak pernah sama.
Salam rindu,
Lara
10
\\
=, Kudengar banyak yang sebal denganku pada kisah
= Bd sebelumnya? Ayolah, jangan egois. Aku ini lelaki.
Aku yang harusnya egois, bukan?
Sebetulnya kisah yang lalu sudah selesai, bahkan
menurutku tidak menggantung. Karena di sini, perjalananku
berbeda. Tidak akan seperti yang kalian harapkan. Oh
tentu, kini aku sudah berteman baik dengan semesta untuk
mengacaukan harapan kalian. Hanya untuk kalian yang mau
untuk menerjemahkan makna di balik semua yang akan aku
persembahkan, yang dapat memahaminya.
Aku tidak berpikir aku akan berhenti menyebalkan pada
kisah ini. Karena, jika beberapa orang terlihat baik, mungkin
mereka cukup pandai menyembunyikan keburukannya. Jadi,
jika aku terlihat menyebalkan di mata kalian, sempurnakan
pandangan kalian. Mubazir rasanya memiliki sepasang mata
sempurna nan indah tapi hanya digunakan memandang
dengan sebelah mata.
Semesta, masih akan mengajak kalian berjelajah.
Cerita kami hanya sebuah portal pengingat perihal takdir
a
yang menuju diri kalian masing-masing. Apakah semua
yang terjadi memang sepatutnya demi kebaikan kalian?
Atau, justru adalah sebuah tantangan? Bahwa, kalian perlu
melakukan hal yang lebih. Karena, hanya kalian yang dapat
memahami, kapan kiranya sebuah cukup akhirnya bisa
disepakati.
Salam syahdu,
Saka
12
DAFTAR ISI
Thanks to
Dari Kami untuk Kamu
Semesta
CHAPTER |
“Kelak Setiap Kenangan Hanya
Akan Berakhir Pada Ingatan"
CHAPTER Il
“Dekat yang Tak Melekat,
Tetapi Hanya Memberi Sekat"
CHAPTER III
“Pergi, dari Satu Titik Ragu
Menuju Satu Titik Percaya”
CHAPTER IV
“Hingga Kemudian Kembali Meragu,
Pada Satu Titik yang Berujung Temu"
15
21
87
143
217
13
CHAPTER V 265
“Masing-Masing Kita Membawa Rahasia,
yang Menanti untuk Diungkap"
CHAPTER VI 319
“Pada Jarak yang Sempat Tercipta,
Sebuah Renung Seharusnya Berkuasa”
CHAPTER VII 375
“Pada Sebuah Kembali yang Seutuhnya,
Ada Sebuah Penerimaan yang Sepenuhnya"
Tentang Penulis 437
14
SEMESTA
“Mas, iced chocolate satu, ya.” pesan seorang wanita yang
baru datang. Ia duduk di kursi bar sambil tersenyum.
“Siap, Mbak. Gulanya mau manis aja apa manis banget?”
tanya seorang barista sedikit menggoda untuk mencairkan
dan mengakrabkan suasana. Terlebih, perempuan itu
sepertinya bukan salah satu tamu reguler yang sering datang
ke coffee shop tersebut.
“Manisnya yang cukup aja, asal nyaman.” Si perempuan
balik menggoda.
Sambil tersenyum, barista tadi dengan sigap menyiapkan
gelas untuk membuat pesanan perempuan itu. Tidak butuh
waktu lama, segelas iced chocolate pun ready.
“Silakan Mbak, iced chocolate-nya. Gulanya sengaja saya
pisahin aja. Saya enggak punya hak untuk nentuin seberapa
manisnya Mbak. Eh, seberapa manis minumannya buat
Mbak.”
15
Perempuan itu kemudian tertawa mendengar kelakar si
barista.
“Eh, Kev. Gue cabut ya.” Barista itu mendadak pamit
seraya melepaskan vest berwarna biru tuanya.
“Lah, tumben balik cepet lu.” Lelaki yang bernama Kevin
itu menjawab keheranan.
“Yoi, ada janji gue,” ucap barista itu sambil memamerkan
senyuman yang menyiratkan tanda tanya bagi yang melihat.
“Mas Saka pasti mau ketemu cewek sih ini. Enggak pernah
kayaknya Mas Saka pamit pulang on time,” timpal seorang
perempuan bernama Narni dari salah satu kursi yang tidak
jauh dari bar. Di mejanya tampak segelas Americano dingin di
samping buku dan tumpukan diktat.
“Serius lu? Ajegilee... akhirnya, pergi sama cewek lagi
doi,” goda Kevin.
“Ah, kalian enggak bisa apa liat temennya seneng? Udah
ya, gue cabut dulu.” Saka meninggalkan teman-temannya
setelah sebelumnya sempat kembali menyapa barista yang
lain.
“Eh, Gil, cabut duluan ya!”
Yang disapa kemudian ikut tersenyum sambil menggoda
Saka, “Mas Saka, sukses ya! Lain kali diajak ke sini toh temen
perempuannya.”
“lya, diajak Mas. Jangan disembunyiin lagi, terus tiba-
tiba cerita udah putus aja.” Narni masih menggoda.
Saka tersenyum namun tak mengindahkan godaan
16
teman-temannya. Ia hanya melambaikan satu tangannya
sebagai tanda pamit.
YO.
“Siaaal...! Kok, ilustrasinya enggak kayak yang diharepin
sih,” gerutu seorang perempuan dari balik mejanya.
Mata perempuan itu terus menatap kertas-kertas yang
menampilkan sederet gambar. Ia acuh saja meski jam di
dinding sudah menunjukkan hari semakin malam.
“Kenapa, Ra? Enggak sesuai lagi? Udah dibilang kalau
buat ilustrasi buku romance tuh mending sama yang freelancer
satunya lagi aja.” Temannya kemudian menasihati.
“Ya, masalahnya kemarin tuh udah ditanya sanggup apa
enggak? Doi jawab sanggup. Ya, udah aja kasih ke dia. Lagian
juga, gue pikir enggak ada salahnya ngasih kesempatan
buat orang lain biar bisa berkembang. Eh, enggak tahunya,
hasilnya bikin naik darah gini. Mampus, deh!”
Perempuan itu terlihat kesal. Ia membanting kertas-
kertas yang ada di mejanya, “Kalau dia belum paham konsep-
nya tuh harusnya bilang, elah. Mana deadline besok lagi.
Minggu depan harus udah up buat cetak. Sekarang, kalau
begini jadinya, kan kacau semua.”
Si perempuan lalu menghempaskan diri ke kursi sambil
memijat pelipisnya.
17
“Coba lu tanyain sama ilustrator satu lagi, keburu enggak
kira-kira kalau dia yang handle?”
“Raniiii... ini bukan masalah keburu enggaknya. Tapi, gue
telanjur deal sama yang ini. Kalau harus gue tolak padahal
udah bolak-balik revisi, kan kasian juga. Lagian, kalau
sekarang gue hubungin ilustrator yang itu, bisa kena mahal
kali bayarannya. Ya, lu pikir aja, semalem harus selesain
sekian ilustrasi, dikira lagi bikin candi?”
“Lara, gini deh mending nolak karena enggak sesuai sama
konsep. Atau, diterima tapi setengah hati? Ngejalanin yang
setengah hati tuh enggak enak loh.” Perempuan bernama
Rani itu kembali mengomentari kemarahan si perempuan,
Lara, dengan menggodanya.
“Lah, kenapa malah curhat? Haha,” Lara kemudian
tertawa sambil melirik ke jam tangannya. “Sial, udah hampir
telat. Gue cabut duluan deh ya. Ntar malem di rumah aja baru
gue pikirin lagi enaknya gimana. Atau, kalau enggak besok
lagi baru gue kerjain.” Lara berpamitan seraya membereskan
meja kerjanya.
“Lah, mau ke mana lu? Tumben amat. Ntaran lagi, Ra.
Gue masih nanggung nih. Masa lu tega, gue lembur sendirian
sekarang.”
“Gue ada janji makan malem. Lupa gue,” ucap Lara sambil
meringis memamerkan deretan giginya.
Rani sontak menghentikan kegiatannya sambil mem-
belalakkan mata menatap Lara.
18
“DEMI APA? Been centuries, akhirnya lu punya janjimakan
malem sama cowok?”
“Enggak usah lebay dih. Lagian siapa yang bilang, gue
janjiannya sama cowok?”
“Alah, udah santai kali. Muka lu enggak usah merah kalau
emang bukan sama cowok. Lagian, kalau emang iya sama
cowok juga enggak apa-apa. Gue malah seneng dengernya.”
“Hmm... Ya, udah ah, gue cabut ya. Sampe ketemu besok,
Sayang.” Lara kemudian mencium pipi teman kerjanya lalu
bergegas pergi.
~”
19
20
Semoga separuh aku yang kamu bawa dapat menemanimu.
Karena kamu pergi membawa doa-doa yang aku titipkan.
Semoga, doa-doa itu akan selalu bisa menemanimu,
bukan hanya saat kamu kesepian.
Namun, juga saat kamu bersama seseorang meski tetap
merasa sepi.
Kupastikan, aku tak kehilangan apa pun kecuali
kehadiranmu.
Percayalah, kini aku telah menerima kehilanganmu,
menerima luka yang tersisa dari kepergianmu.
Tak ada yang lebih menenangkan dari sebuah penerimaan.
Karena tak ada yang lebih menyiksa dari mempertahankan
kebencian.
Melangkahlah dengan tegap,
tak perlu lagi kamu pikirkan bagaimana aku tanpamu.
Nikmatilah kamu yang kini tanpaku.
se
CHAPTER I.
“KELAK SETIAP KENANGAN HANYA
AAU laa a CA
;°
“Thad it all figured out. So I cut out a little early, who cares? Its
probably a good thing. Life sucks, anyway. But I met you and it
got weird. And, you were so... Amazing. And I?”
“What? What?”
“I just wanted a little more time. So all in all, I'd say you’re the
worst thing that’s ever happened to me. Goodbye partner.”
“I’m staying with you until you leave. I don’t care how much
time we have! Give up you stupid jerk.”
“th, Mas Saka nangis yaaaa...?” celetuk Narni.
“Anjriiiiit... sialan, Narniiii...!” Aku yang tengah
“ menikmati scene goodbye dari film Keith harus
terganggu oleh celetukan Narni yang tiba-tiba.
“Hahahahahahahahahahahahahaha....
terbahak-bahak.
“Anjrit, mata lu kok juga basah gitu, Nyet? Hahahaha.”
Kevin tertawa
Giliran aku menggoda Kevin.
“ya, apa? Masa sih?” Kevin segera mengelap genangan
di kedua matanya.
“Duh, kalian nih ya, cowok-cowok lembut. Bisa banget
nangis nonton film drama gini.” Narni masih saja menggoda.
“Kita enggak nangis, Narni! Enggak sempet nangis
karena udah keburu kamu ganggu duluan!” Aku protes
sembari diam-diam menyeka mataku.
23
“Lagian kamu bisa-bisanya lagi nonton malah merhatiin
orang sih?” Kevin protes dan berdiri dari tempatnya duduk.
Ja menuju dapur, mungkin mau mengambil minum.
“Ya, gimana mau merhatiin, Mas? Udah kalian berdua
nonton paling depan, berisik bener sama idung. Kukira
ingusan, ternyata lagi siap-siap mau nangis. Gimana aku mau
konsen coba?” canda Narni.
Film yang seharusnya membuatku tergugah, puas akan
aksi kedua tokoh dari Natalie dan Keith, harus berakhir
mengesalkan karena Narni. Kami masih saja_berisik
menyalahkan Narni. Namun, gadis itu sama sekali tidak
merasa berdosa. Dia malah asyik menggoda kami terus. Dia
yang perempuan seharusnya lebih terharu menonton film
drama bukan?
Ini malam terakhirku di Jogja. Sebelum pulang, kami
ngumpul di rumah Narni. Dia yang memaksaku, karena
setelah sekian lama saling kenal tak pernah sempat
mengunjungi rumahnya.
“Rame juga tapi ya filmnya. Narni nanti nonton sendiri
aja ah, biar enggak ada yang ledekin kalau nangis. Hehehe.”
Narni berdiri dari ranjang tempatnya duduk.
“Ah, sialan Narni. Harusnya aku pulang ke Bandung
dalam keadaan bahagia nih. Udah bisa terharu nonton film.
Lah, malah jadi mentah gini deh.” Aku kembali protes, lalu
segera berdiri menyiapkan barang-barangku.
“Lu bawa laptop bukan? Lu nonton aja di kereta
24
ntar. Download dulu aja, bentaran juga kelar pasti.” Kevin
menyarankan.
“Yakali Sob, terus gimana ntar kalau gue di kereta
terenyuh mau nangis gara-gara filmnya? Bayangin
penumpang lain harus nahan ketawa ngeliat gue yang
gondrong gini, tapi matanya berair nonton drama. Enggak
keren lagi gue.” Aku menjawab.
“Mas Saka, lakik yang berani nangis tuh keren!
Yang enggak keren tuh lakik yang bikin nangis.” Narni
membalasku.
“Hahaaaaaaaaaa.... Kenaa lu, Nyet. Kena lu! Skak mat!
Hahahahaha....” Kevin tak bisa menahan tawa mendengar
ucapan Narni.
“Eh, Narni salah ngomong ya?” Narni belagak polos.
“Enggak, Narni. Kamu... bener.. banget....” Aku menjawab
pelan dengan wajah yang tak keruan.
Aku teringat Lara. Teringat apa yang pernah membuatnya
menangis. Sebuah penyesalan yang tidak bisa aku bayar.
Namun, kini setidaknya keadaan kami sudah cukup untuk
membuatku sedikit tenang dari rasa bersalah yang bisa saja
masih menghantuiku.
“Udah tenang, Sob. Lu sama Lara kan udah baikan.
Udah saling merelakan dan saling nerima lagi.” Kevin coba
menenangkan. Dia sepertinya bisa membaca pikiranku.
“Saling nerima lagi sebagai teman ya, Mas Saka.” Narni
masih saja menggodaku dengan ucapannya.
25
“Duh, kok gue dengernya nyelekit gitu ya.”
“Man, gue baik-baik aja. Kata-kata lu yang bikin seolah
itu nyelekit. Jangan gitu dong. Stop saying like I’m not okay. You
guys who make me not okay!”
Aku mengeluh sebal sembari mengecek perlengkapanku.
Memastikan tidak ada barang yang tertinggal.
“Eh, sori-sori, Sob. Gue enggak maksud, sumpah!
Keceplosan gue. Sori!” Kevin meminta maaf.
“Mas Kevin tuh, dijaga coba omongannya sama sahabat
sendiri.” Narni menyalahkan Kevin.
Aku hanya diam dan mengacuhkan permintaan maaf
Kevin.
“Heh! Kamu juga tuh, Narni. Mentang-mentang cewek
bisanya nyalahin doang. Hih,” jawab Kevin ketus.
Sementara mereka berseteru, aku masih sibuk dengan
barang-barangku untuk menyembunyikan wajahku, dan
mencoba memastikan apa aku benar baik-baik saja, atau
sebetulnya tidak. Meski sebenarnya tidak apa jika memang
aku masih menyimpan sisa-sisa luka. Tidak apa jika aku
memang tidak baik-baik saja. Tapi, jika aku harus berpura-
pura saat ini, aku memilih untuk berpura-pura baik-baik
saja. Ya, dari pada berpura-pura tidak baik-baik saja.
“Udah napa, pada berisik mulu. Just please stop making
fun of it. Gue tuh enggak kenapa-napa. Lu pada boleh
becandain hal itu, tapi please jangan ngomong apa pun yang
menyudutkan gue, atau seolah gue nyesek dan enggak baik-
26
baik aja. Becandanya enggak usah nyampah, please.” Aku
memberi nada tegas, meski sedikit tidak enak. Tapi, mereka
perlu tahu bahwa tidak semua orang bisa menerima gurauan.
“Siap, Pak Bos! Maafkan kami!” seru Narni dan Kevin
bersamaan.
Meski kadang menyebalkan atau kadang ada perkataan
dan gurauan mereka yang menyinggung, yang membuatku
senang adalah mereka begitu bisa menerima teguran dariku.
Bukan teman yang hanya akan lebih menyudutkanku jika
aku marah, atau tidak terima atas gurauan mereka.
Setelah selesai bersiap, kami melaju menuju Stasiun
Tugu untuk mengantarkanku pulang. Jalanan Jogja di tengah
malam selalu melambaikan kerinduan. Mengejekku dengan
riang, seolah aku akan pulang dengan berat. Aku terhibur
saat memandang lampu-lampu jalan yang seolah tersenyum
mengantarkan kepulanganku.
“Gue balik dulu ya!”
Aku pamit setelah menukarkan boarding pass di stasiun
Tugu. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kereta
yang akan membawaku pulang ke Bandung akan berangkat
30 menit lagi.
“Mas Saka, ini Narni tadi dibawain nasi kucing sama
Mama. Buat Mas Saka kalau laper di jalan. Kucingnya udah
Narni pisahin kok. Sama ini juga semangka buat makanan
penutupnya. Atau, kalau enggak mau repot, makan
semangkanya pake nasi aja biar sekalian telan.” Narni
27
tersenyum polos.
“Kapan kamu bawa semangka? Kok, enggak ketahuan?
Anyway, terima kasih Narni.” Aku berkata dengan gemas,
sedang Narni hanya tersenyum.
“Tiati, Sob. Jangan lupa bentar lagi gue lulus. Terus, yang
gue omongin kemarin dipikirin. Siapa tahu ya, siapa tahu lu
masih pengen perjuangin Lara. Kan, biar sekalian. Haha.”
Kevin memelukku.
“Hahaha... kampret! Ya, gampang lah...”
“th! Kalian ngobrolin apaan kemarin. Kok, Narni enggak
tahu sih?” Belum selesai aku menjawab, Narni langsung
memotong. Mukanya cemberut.
“Sstt.... Itu urusan lelaki, kamu jangan dulu ikut-ikutan!”
tukas Kevin.
“Lah, itu ngomongin Mbak Lara juga, berarti ada urusan
perempuannya juga dong,” balas Narni.
“th, nih anak enggak bisa dikit aja enggak bawel. Udah,
ntar juga kamu tahu. Ini masih rencana, belum bisa dikasih
tahu siapa-siapa. Nanti kalau enggak jadi kan malah malu,”
jelas Kevin berharap Narni bisa diam.
“Yo Mas, mumpung masih rencana siapa tahu aku bisa
bantu. Aku nih lagi dilanda tekanan proposal skripsi, sedang
teraniaya. Amin dariku tuh bakal didenger ribuan malaikat
Joh. Bisa bikin rencana yang kalian obrolin jadi diijabah sama
Tuhan.” Narni bersikeras ingin tahu.
Aku hanya bisa tertawa terbahak mendengar debat
28
mereka.
“Heh, Narni. Itu enggak ada apa-apanya dibanding aku
yang bentar lagi mau sidang tesis. Deg-deganku lebih kenceng
daripada kamu. Aku nih lebih teraniaya. Amin dariku bisa
bikin isi surga ikut ngaminin! Sstt, udah diem!” Kevin kali ini
benar-benar gemas.
“Emm, penghuni surga sama malaikat banyakan mana
ya, Mas?” Narni bertanya polos.
Kevin mengelap wajah dengan kedua tangan, tanda tak
lagi bisa menahan gemas. Aku masih tertawa melihat mereka
berdua. Pulang memang selalu menjadi hal terberat. Harus
membawa rindu yang tak bisa aku bawa sendirian. Aku yakin
rindu yang aku bawa akan cukup membuatku sendu dalam
beberapa hari ke depan. Sejak nanti aku kembali tiba di
Bandung.
Tidak lama, kami benar-benar berpisah. Aku melangkah
masuk ke ruang tunggu penumpang. Terlihat para
penumpang yang sedang beristirahat. Entah untuk pulang
atau melanjutkan perjalanan.
“Bu, air mineralnya satu,” pintaku kepada ibu-ibu di
kantin stasiun.
Aku lalu melongok isi bungkusan yang diberikan Narni
kepadaku. Nasi kucing dan potongan buah semangka. Aku
tertawa kecil. Sungguh ada-ada saja kelakuan gadis itu.
Langkahku gontai mencari tempat duduk yang menurutku
nyaman. Lalu, tak bisa kutolak pikiranku menyapa ingatan
29
tentang Lara.
Bahagia dan rindu sedang berpesta dalam diriku.
Perutku dibuat geli karena kupu-kupu baru saja keluar dari
kepompong. Saat seperti ini, sulit sekali menahan bibirku
untuk tidak keras kepala tersenyum. Orang-orang di stasiun
bisa menganggapku sedang jatuh cinta. Memang iya. Tapi,
mereka tidak tahu bahwa aku tidak jatuh cinta kepada
seseorang. Sial, aku merasa kikuk sendiri di antara ratusan
orang, padahal mereka tidak sedang memerhatikanku.
Aku memutuskan membuka aplikasi notes di smartphone
milikku. Rasa ini harus tumpah pada tempat yang tepat.
Kepada nurani,
Inikah tujuan dari semua langkah?
Mengantarkan aku pada rasa yang megah?
Membukakan aku sebuah pintu yang penuh berkah?
Apa kamu sedang mengejekku dengan senyummu yang
merekah?
Sial kamu nurani,
berani-beraninya mempermainkanku.
Tapi, apa daya. Aku pun dibuatnya malu dan terpaku.
Dan, akhirnya yang hanya bisa aku lakukan hanya mengaku.
Bahwa kamu telah memberiku pemahaman yang sangat
membahagiakan aku.
30
Biar saja semua orang melirikku dengan curiga.
Tentang senyum yang sedari tadi sombong ingin terus
bersinar.
Tentang degup yang tak ingin berhenti menggelar perayaan
dalam dada.
Kukatakan dengan lantang dalam diam.
Aku memang sedang jatuh cinta.
Tapi, bukan pada seseorang.
Biar saja mereka mereka-reka.
Rasa ini milikku,
takkan kubagi kepada siapa pun yang tak pantas.
Kedatangan kereta yang akan membawaku pulang telah
meneriakkan semangatnya dari jauh. Aku bergegas berdiri
dan bergerak menuju titik tunggu. Bersama para penumpang
yang ingin segera pulang, atau ingin segera sampai, atau
hanya ingin segera pergi. Kereta api Malabar tujuan Bandung
akhirnya tiba di depan kami. Semua penumpang dengan
teratur memasuki pintu masuk. Jogja, terima kasih untuk
kejutannya, rindu ini akan aku tanggung sendirian.
“Lara, sampai tiba-tiba bertemu lagi ya,” ucapku dalam hati.
31
Bandung masih selalu cerah sejak kepulanganku.
Mungkin karena seirama dengan suasana hatiku. Meski
begitu, sudah beberapa hari aku bermalas-malasan dulu.
Menghabiskan rasa bahagia yang masih bersisa. Rasa yang
mengganggu mood untuk mulai kembali bekerja. Maksudku,
untuk membuka email. Karena aku bisa tahu ada pekerjaan
design dari notifikasi email yang ada di smartphone milikku.
Sengaja aku biarkan, sekali aja aku ingin bermalas-
malasan. Ya, sesekali setelah liburanku selesai. Badanku
lesu karena terlalu banyak tertidur dan menonton TV
kabel. Sesuatu tiba-tiba muncul dalam kepalaku. Aku ingin
berolahraga. Hal yang cukup aneh memang bagiku, tapi
entah dari mana datangnya keinginan itu. Apakah Lara
mengirim doa agar aku mulai mau hidup sehat?
Entah, tapi sepertinya aku ingin. Entah hanya ingin
atau memang ingatan tentang Lara yang dulu sering
mencerewetiku perihal kesehatan, membuatku ingin
memiliki pola hidup yang lebih baik. Aku teringat ada
tempat fitness dekat rumahku. Seketika aku bersiap dan
setelah menikmati sarapan seadanya di dapur, lalu pergi
untuk mendaftarkan diri sebagai anggota. Mulailah aku
berolahraga.
Ternyata, olahraga cukup membuatku, bahagia. Badanku
terasa segar dan lelah di saat yang sama. Sesampainya
di rumah aku berniat untuk membuka email yang sejak
beberapa hari kemarin aku abaikan. Namun sayang, lelah ini
32
membawa kantuk yang sangat menggoda hingga tak terasa
aku terlelap.
Drrrtt...dddrrttt...
Kepalaku masih pusing. Sepertinya, aku baru terlelap
beberapa detik saja. Getar pesan di ponsel membangunkanku.
“Man, cek email bisa kali. Sekalian jangan lupa
gue tunggu di kantor buat brief desainnya.”
Salah satu temanku mengirimi pesan. Ah ya, aku lupa
akan membuka email yang sudah menungguku, berserta janji
untuk bertemu rekanku di kantornya. Pesan temanku itu
belum sempat aku balas.
Aku terbangun dan mulai membuka email. Setelah
membuka inbox email di layar laptop, aku tiba-tiba merasa
lapar. Entah karena olahraga yang ternyata menguras
tenaga, atau isi email yang ternyata cukup banyak. Badanku
mulai terasa pegal-pegal.
Aku seketika mengutuki diri sendiri kenapa bisa-bisanya
ingin berolahraga.
“Badan segar ternyata hanya ilusi!” Aku merutuk dalam
hati.
Tak lama aku segera mandi dan bersiap untuk pergi ke
kantor temanku.
“Udah enak males-malesannya, Kasep? Ganteng?”
Suara dari ruang tengah tiba-tiba menyapaku saat aku baru
33
menuruni tangga.
“Lah, Mamah, kirain kerja.”
“lya, Mamah ngambil libur dulu lagi enggak enak badan,”
jawab ibuku santai. Meski begitu, ibuku masih saja sibuk
dengan laptop untuk mengerjakan pekerjaannya.
Aku menangguhkan kepergianku, berjalan ke arah dapur
dan membuatkannya teh panas. Bisa-bisanya aku tidak
mengetahui jika ibuku sedang sakit.
“Nih, santai dulu atuh Mah, kerja mulu. Udah makan?”
Aku bertanya seraya duduk di sebelahnya.
“Eh, nuhun bageur. Udah udah makan kok tadi. Istirahat
teh bikin makin lemes, Mamah mah enggak suka. Mending
sambil ngerjain sesuatu biar istirahatnya produktif,” jawab
ibuku sembari meneguk teh panas dariku.
“Eh, Saka, kamu teh udah umur segini, enggak kepikiran
apa pengen nikah?” Ibuku tiba-tiba saja berhenti melakukan
pekerjaannya dan bertanya. Seolah pertanyaannya adalah
pertanyaan, biasa. Seolah apa yang aku dengar, biasa saja.
“Emm... Mamah kepikiran pengen punya mantu?” Aku
berbalik bertanya karena belum mendapatkan jawaban yang
baik untuk didengar ibuku. Aku masih sibuk terkejut dengan
pertanyaannya.
“Lah, dari dulu atuh kepikiran pengen punya mantu
mah. Mamah teh suka penasaran, Mamah bakal punya mantu
kaya gimana. Ya, habis anak Mamah kerjaannya sering pergi-
pergian. Sering di rumah cuma buat istirahat atau ngerjain
34
kerjaan.” Ibuku terdengar sedang mengerjaiku.
“Emm... Saka juga penasaran Mamah teh kepengen punya
mantu kayak gimana?” Aku masih saja menjawab dengan
pertanyaan.
“Mamah mah, yang penting kamu sayang dan enggak
bikin kepaksa. Enggak kepaksa karena Mamah nanyain kamu
kapan nikah. Enggak kepaksa karena kamu enggak tahu lagi
mau sama siapa. Enggak kepaksa kalau, amit-amit, kamu
udah ngebet banget pengen nikah. Pokoknya, jangan kalau
bikin kamu kepaksa.”
Ibuku meneguk lagi teh panasnya. Kali ini lalu
menyimpan laptop di pangkuan dan meletakkannya di meja.
Arah duduk ibuku kini menghadapku, seolah perbincangan
semakin seru. Aku semakin gemetar.
“Terus, Saka tahu kalau itu enggak kepaksa itu gimana?”
Lagi-lagi tanyaku pelan.
“Yang enggak kepaksa itu, yang bikin kamu sehat. Bikin
ibadah kamu sehat. Bikin diri kamu sehat. Bukan hanya
badan kamu sehat, tapi yang bikin pikiran kamu juga sehat.”
Ibuku menjelaskan.
Aku diam. Mataku menatap layar televisi yang
menampilkan seseorang berbaju seksi tengah membicarakan
kehidupan orang lain. Isi kepala ini bertengkar, ingin
mengeluh kenapa ibuku menonton acara seperti ini, atau
membahas apa yang sedang ibuku coba bicarakan.
“Mamah enggak kepikiran nikah lagi?” Tiba-tiba per-
35
tanyaan itu melayang dari bibirku. Aku hanya berharap, per-
tanyaan itu akan mengalihkan pembicaraan tentang diriku.
Ingin sekali aku menariknya kembali, namun kata-kata
itu kini sudah hinggap di kepala ibuku. Giliran ibuku yang
kini diam. Cukup untuk membuatku mengerti bahwa ada
yang sedang dipikirkan olehnya.
“Mamah tuh takut, Saka...” Ibuku menarik napas, “Takut
kalau anak-anak Mamah ada yang enggak setuju. Kalian pasti
enggak rela kalau posisi almarhum Bapak ada yang gantikan
di hidup kalian.” Ibuku menyelesaikan kalimatnya.
Kalimat itu menghujam dadaku, mengobrak-abrik
perasaanku, membuat degup kebingungan berdetak. Aku tak
tahu pernyataan itu akan keluar dari bibir ibuku.
Ada hal yang sedang membuat sesak dan menyeruak
dalam dadaku. Ibuku harus takut terhadap anak-anaknya.
Harus mengekang keinginannya menemukan orang yang
baru untuk menemaninya. Dan, seolah aku dan adik-
adikku mengekang dirinya. Hal lainnya, kalimat ibuku jelas
menyampaikan kesepiannya.
Air mata merajuk ingin tumpah. Semua sel darah dalam
diri aku paksa untuk menahannya agar tak sedikit pun berani
untuk menggenang di kelopak mataku. Tak aku sangka,
ternyata aku memang masih tak rela jika ibuku harus bersama
seseorang yang tidak aku kenali. Aku tidak menginginkan
ada orang asing berada dalam rumahku. Kini aku hanya ingin
menjadi egois, dengan menyesali pertanyaanku yang tidak
36
bisa aku terima jawabannya.
“Mamah emang pengen nikah lagi?” Aku beranikan
untuk bertanya. Lebih bersiap untuk mendengar apa
kata beliau daripada menjawab pertanyaan ibuku perihal
keinginanku untuk menikah.
“Mamah enggak ingin mengeluh kesepian karena kamu
dan adik-adik kamu sibuk sama kegiatannya masing-masing.
Adik kamu paling gede, Sinar, udah kerja. Permata, lagi
giat-giatnya kuliah dan cari beasiswa sana-sini. Si bungsu,
Putri, seneng sama ekskul debat di SMP-nya. Mamah seneng,
kalian tuh sibuk buat ngejar cita-cita kalian. Seneng enggak
ada dari kalian yang sering di rumah cuma males-malesan.
Meskipun Mamah enggak bisa perhatiin kalian semua, tapi
dengan tahu kalian sibuk untuk hal positif, Mamah lega.
Mamah rela kesepian.” Ibuku meneguk teh yang sepertinya
kian menghangat, bersiap melanjutkan perkataannya.
“Tapi, Mamah juga pengen ada temen ngobrol. Mamah
enggak pengen minta waktu kalian terus-terusan kalau lagi
pengen ngobrol. Mamah cuma pengen minta izin kalian
kalau Mamah ingin punya ayah baru untuk kalian. Mamah
berani ngomongin ini sama kamu, karena kamu anak paling
gede. Kamu yang gantiin Bapak untuk bertanggung jawab
sama Mamah. Untuk ngasih izin sama Mamah.” Ibuku
menyelesaikan kalimat yang selama ini sepertinya menunggu
untuk diutarakan.
Hal yang kukira akan tentangku, ternyata sebenarnya
37
menyoal ibuku. Kini aku merasakan sebuah beban yang
selama ini dipendam oleh ibuku. Sebuah rindu yang lama
ibuku sembunyikan. Rindu akan seseorang yang dapat
mengayomi selayaknya saat Bapak masih hidup. Aku dan
adik-adikku bukan hanya sibuk untuk cita-cita kami. Kami
sibuk membiarkan ibuku menelan kesepiannya sendirian.
Ddrrttt...ddrrrttt....
Notifikasi pesan baru sampai di ponselku.
"Udah di mana lu? Jangan telat yak!
Bos gue lagi rewel.”
Temanku bertanya lagi. Aku hampir lupa bahwa aku
harus pergi. Tapi, aku tak mungkin meninggalkan obrolan
dengan ibuku menggantung.
“Sok, kalau kamu harus ngerjain kerjaan. Pergi aja dulu ya.
Mamah juga mau ngerjain kerjaan lagi. Eh, nanti pulangnya
Mamah minta tolong nitip beliin madu hitam ya. Punya
Mamah udah habis.” Ibuku mengerti bahwa aku harus pergi.
Sungguh tidak adil bagaimana ibuku yang harus selalu
mengerti akan kesibukan anak-anaknya.
“Nanti, kita ngobrol lagi ya, Mah. Nanti Saka coba ngobrol
juga sama yang lain. Saka pergi, dulu. Assalamualaikum.” Aku
pamit dan mencium punggung tangan ibuku. Meninggalkan
pernyataan yang setidaknya bisa menenangkan ibuku. Tidak
menggantung dengan perasaan yang mungkin membuatnya
38
tak keruan karena telah mengatakan hal-hal yang membuatku
tidak nyaman.
“Walaikumsalam,” ibuku menjawab. Betapa ironis dan
egois, pekerjaan yang menunggu harus mengorbankan ibuku
sendiri. Seketika aku merasa menjadi anak yang durhaka.
Perasaan tak nyaman ini menaungi diriku. Namun, aku yakin
ibuku tidak marah dan tidak merasa ditinggalkan.
“Ya elah, gue kira lu lagi ngapain. Itu kursor
kedip-kedip mulu, capek kali dianggurin.”
Ucapan dan tepukan halus Rani sukses mem-
buatku terperanjat. Aku yang sedari tadi hanya menatap
kosong ke layar monitor sambil bertopang dagu, kemudian
menoleh sambil tersenyum menatap wanita berkacamata itu.
“Kenapa lu bengong aja? Biasanya jam segini kalau enggak
lagi nulis atau ngedit, lu blogwalking. Ini kenapa kayak orang
kesambet gitu?” Rani kembali mengajukan pertanyaannya
kepadaku usai meneguk air dari gelas yang tadi dibawanya.
Rani adalah editor di tempatku bekerja saat ini. Kiranya
aku bisa menyebut dia sebagai Kanaya kedua. Sifatnya mirip
sekali dengan Kanaya. Hanya saja Rani belum sedekat itu
denganku. Percakapan kami pun tidak pernah menyinggung
masalah pribadi. Hanya berkutat soal pekerjaan dan
39
gosip-gosip yang memang sedang marak dibicarakan oleh
kebanyakan orang.
“Enggak tahu nih, enggak ada ide. Males juga ngerjain
yang lain. Kalau belum deadline kayaknya kurang berasa
dikejar.”
“Dikejar banget, Ra? Lagian tumben amat enggak ada ide
tulisan. Hidup lu lagi kurang sedih sama kurang patah hati
tuh kayaknya,” ucap Rani seraya terkekeh sambil kembali
mengamati kertas-kertas di hadapannya.
Aku tak menimpali ucapannya sama sekali, justru
sibuk memikirkan ucapan Rani tadi. Aku kembali diam dan
mengingat-ingat kapan terakhir kali menulis dengan lancar
bahkan bekerja dengan teramat sibuk sampai lupa waktu
untuk sejenak menjeda.
“Mungkin karena ini di Jogja,” pikirku.
Hawa santainya membuatku jauh lebih rileks dalam
melakukan kegiatan. Tak seperti sedang dikejar waktu,
pun tidak seperti sedang mengejar sesuatu. Atmosfernya
memang teramat berbeda ketika aku berada di Jakarta.
Hingga akhirnya aku tak sempat lagi merasakan kesedihan,
karena cukup sibuk menjadi bahagia dengan kehidupanku
sekarang.
Atau, mungkin juga benar seperti kata Rani tadi. Aku
kurang patah hati. Bahkan aku lupa kapan terakhir kali aku
merasakannya, sampai akhirnya mataku menemukan sebuah
tulisan di arsip blogku. Seketika aku terpaku pada akhir
40
kalimat dalam tulisan itu. Tulisan yang sudah cukup lama
aku unggah.
-
Kamu, awal tanpa akhir dan akhir yang tak
membutuhkan awalan:
=
Seketika itu juga pikiranku kembali saat aku dan Saka
akhirnya kembali bertemu, tidak dalam kondisi yang salah
apalagi bertengkar. Malah pertemuan itu terjadi dalam
kondisi yang teramat tepat untuk kemudian membuatku
dengannya bisa menyelesaikan apa yang masih mengganjal.
Seulas senyum tiba-tiba saja tersungging di bibirku hanya
dengan mengingat momen itu. Bahkan aku juga teringat
momen saat aku dan Saka lagi-lagi tidak sengaja bertemu di
coffee shop, sehari sesudah camping itu berlalu.
Mungkin memang benar apa yang tadi Rani katakan,
hidupku saat ini kurang mengalami kesedihan pun patah
hati tak sedang kurasakan. Hubunganku dengan Saka yang
sudah kandas, kukira akan menyisakan namanya dalam
barisan tulisanku hingga bertahun-tahun lamanya. Tapi
ternyata, sesudah percakapan di pantai itu, aku bisa selega ini
melepasnya. Tak merasakan sesak, justru perasaan bahagia
tengah menguasaiku dengan terang-terangan.
Saka, dia saat ini memanglah bukan siapa-siapa lagi di
hidupku. Bukan seseorang yang memiliki status khusus
bahkan istimewa untuk membuatku dan dia terikat. Tapi,
41
tanpa status itu sekalipun, kehadirannya di hidupku ternyata
membuat segalanya lebih dari sekadar cukup. Hubungan
kami bahkan sudah lebih dari sekadar kata baik.
“Ra, beneran kesambet lu lama-lama! Tadi bengong,
sekarang mesem-mesem. Gih, kerjain itu naskah yang
barusan gue email. Dimarahin sama Rio baru tahu rasa lu!”
Rani kembali menyadarkanku.
“Serba salah mulu gue kayak Raisa hahaha,” aku
kemudian tertawa menanggapi ucapan Rani, seraya mulai
mengecek inbox.
Aku sendiri tak habis pikir dengan apa yang ada di hati
dan pikiranku saat ini. Sebuah perasaan yang baru kali ini
aku miliki ternyata mampu membuatku kehabisan kata-kata
untuk menggambarkannya. Mungkin memang benar kata
orang-orang, lebih mudah menuliskan kesedihan daripada
kebahagiaan.
“Saka, apa kabar?” tanyaku lirih di dalam hati.
a
“Loh Lara, kamu enggak makan siang?”
Aku yang sedang asyik membaca naskah dari Rani
mendadak dikagetkan oleh suara lelaki yang kini tengah
memandangiku dengan lekat. Rio, dia adalah pemimpin
redaksi di kantor. Saat pertama kali datang ke sini aku jarang
42
bersinggungan dengannya, karena dia baru cuti. Tapi, lain
halnya untuk saat ini. Aku bahkan bisa melihatnya berada
di kantor setiap hari, pun ketika ada rapat redaksi di tiap
Minggu.
“Eh iya Pak, ini nanggung, hehe.” Aku menjawab
pertanyaannya sembari menggaruk leher yang tidak gatal
untuk menutupi kecanggungan yang tiba-tiba saja merebak
di sekitarku.
“Deadline?” tanyanya sembari menautkan kedua alis.
“Belum sih Pak, emang lagi asyik aja.”
“Kerjaannya kan bisa ditunda dan enggak ngaruh apa-
apa juga. Tapi, kalau makan siang ditunda bisa kena maag
kamu.”
Aku sedikit tersentil mendengar kalimat itu. Aku ingat
sering menasihati Saka seperti ini saat aku masih berpacaran
dengannya. Jika dulu aku terbiasa mengingatkan, sekarang
justru aku yang perlu diingatkan oleh hal-hal yang sudah aku
tahu betul konsekuensinya.
“Eh, iya sih. Bentar lagi deh Pak, 5 menit lagi.”
“Berapa kali dibilangin sih kalau enggak usah manggil
Pak? Panggil nama aja kayak yang lain. Atau, kalau alesanmu
biar sopan, ya udah panggil Mas aja.”
Umurku dengan Rio memang tak jauh berbeda, hanya
terpaut 2 tahun lebih dewasa dia daripada aku. Sejak pertama
bertemu dengannya, Rio memang menyuruhku untuk
memanggilnya dengan nama saja. Atau, bisa juga dengan
43
embel-embel mas, seperti karyawan lain memanggilnya.
Tapi, entah kenapa ketika berpapasan dengannya aku selalu
lekat dengan sapaan pak.
Mungkin karena pembawaan Rio yang sangat dewasa dan
penampilannya yang karismatik, sehingga membuatku segan
kepadanya. Padahal cara berpakaiannya tidak menyiratkan
kedewasaan umurnya sama sekali. Bahkan cenderung jauh
dari umurnya. Mirip dengan Saka, hanya saja ini dalam versi
yang lebih rapi. Sepatu new balance cokelat tua dan sweter
abu-abu yang sering dikenakannya membuat Rio seperti
Jelaki yang baru saja lulus bangku perkuliahan.
“Ya, udah buruan beresin kerjaannya, kita makan siang
bareng abis itu.”
Ucapannya tidak terdengar seperti pertanyaan, justru
seperti sebuah perintah. Sejak kapan pula dia menawariku
untuk makan siang bersama, dan aku menyetujui ajakannya.
Seusai mengatakan hal itu Rio justru segera melangkah
ke luar, membuat aku hanya terdiam sambil menatap
punggungnya dengan keheranan.
Belum usai menelaah apa yang tadi Rio ucapkan,
suaranya kembali terdengar. Namun, kali ini setengah
berteriak, “Buruan Ra, aku tunggu di mobil ya!”
Aku segera menyimpan naskah yang tadi kubaca
kemudian mematikan komputer. Buru-buru mengambil
gawaiku setelah sebelumnya memasukkan dua lembar uang
pecahan lima puluh ribu pada case belakangnya.
44
Jika hanya ke luar untuk makan siang seperti ini, aku
memang tak suka membawa banyak barang apalagi tas.
Karena, bagiku waktu makan siang bukanlah saat yang
tepat untuk disibukkan dengan kegiatan lain yang justru
membuatku tidak bisa menikmati hidangan yang tersaji.
“Loh Ra, kamu enggak bawa tas?” Rio memandangku
yang baru saja masuk ke dalam mobilnya dengan tatapan
penuh keheranan.
“Enggak,” aku menoleh sembari menggeleng, lalu
memasang seatbelt, “cuma mau makan siang, kan?”
“Tya sih, tapi biasanya cewek tuh mau ke mana aja selalu
bawa tas,” ucapnya sambil mulai melajukan mobil.
“Ya, itu kan cewek biasanya, Pak. Eh, Mas. Nah, aku
kan cewek yang enggak seperti biasanya.” Aku kemudian
tersenyum memamerkan sederet gigiku kepada Rio. Rasanya
baru kali ini aku berbicara sepercaya diri itu kepada seseorang
yang masih dibilang cukup baru di hidupku.
Rio tertawa mendengar gurauanku, “Haha, ya, ya, ya.
Aku tahu itu sejak pertama kali liat kamu.”
“Ha? Gimana, gimana?” Aku tersedak mendengar
jawabannya.
“Enggak, itu tadi ada kucing lewat. Eh, ini mau makan di
mana?”
Aku menyatukan alis sembari menatapnya heran.
Gurauan lelaki itu justru tak lucu sama sekali. Aku tahu
ucapannya hanyalah untuk mengalihkan topik saja.
45
Sebetulnya ingin mencari tahu maksud dari perkataan Rio,
tapi sudahlah aku terlalu malas untuk sekadar bertanya.
“Dih lucu dia mah, segala bawa-bawa kucing. Makan di
mana aja, terserah.”
“Kalau aku kasih kamu pilihan buat turun sekarang di
tengah jalan atau turun di tempat sepi enggak ada angkutan
umum, jawabanmu juga terserah?”
“Eh, ya itu mah kalau Masnya tega.”
Rio melirikku sekilas kemudian menggelengkan kepala.
“Ra, Ra, hidup itu selalu ngasih pilihan ke kita. Terserah itu
bukan jawaban. Terserah itu milik mereka yang enggak tahu
mau dibawa ke mana hidupnya.”
Aku tersenyum melihat Rio. Menarik juga pikirku.
“Salah, Mas. Terserah itu lebih luas tahu artinya. Gini,
ketika kita ngasih jawaban terserah berarti ada hal yang
melatarbelakangi itu. Pertama, karena emang seikhlas itu
nerima mau diajak ke mana aja dan emang udah sepercaya
itu dengan pilihan si pemberi pertanyaan. Kedua, karena
emang sedang enggak ada rencana mau milih apa. Ketiga,
karena enggak mau sampe melukai keinginan dari si pemberi
pertanyaan untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau.”
“Gimana, gimana, Ra? Coba jelasin, coba.” Rio bertanya,
tampak tertarik dengan jawabanku.
“lya, gini. Tadi kan yang ngajak makan tuh Mas Rio. Ya,
manalah aku tahu kalau sebenernya Mas Rio tuh mau makan
miayam misalnya. Terus, ketika aku jawab mau sop ayam kan
46
jadi enggak cocok. Mematahkan keinginan Mas sebelumnya.
Padahal siapa tahu tadi Mas udah ngebayangin enaknya mi
ayam pake ceker dengan kecap dan sambel yang pedes. lya,
enggak?”
Rio terlihat sejenak berpikir sebelum kemudian
mengangguk dan bersuara. “Oh, I see. Menarik dan cukup
masuk akal sih. Tapi, tetep aja sih, Ra. Kalau kita udah dikasih
pertanyaan gitu dan bebas nentuin pilihan, berarti si penanya
emang udah seikhlas itu untuk ngasih pilihan dan keputusan
ke yang dia tanya. Kedewasaan seseorang bisa juga diukur
dari dia yang bisa menentukan pilihan loh.”
Kini giliran aku yang memikirkan perkataan Rio. “Iya sih,
tapi itu juga enggak bisa dijadikan tolok ukur kedewasaan,
Mas. Itu malah...”
Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Rio sudah
memotongnya, “Ya, udah ya, bahasannya udah dulu. Tuh, di
depan ada tongseng, makan itu aja mau?” Rio mengarahkan
jari telunjuk pada sebuah warung makan di pinggir jalan.
“Mm...
“Jawab iya atau enggak, jangan terserah lagi.”
“Tya mau,” ucapku sambil memberikan senyuman tipis
kepadanya.
“Good girl!” Rio tersenyum seraya mulai menepikan
a”
mobil.
47
48
Memiliki
Kita pada akhirnya kembali semesta pertemukan,
dengan rencananya yang selalu mencengangkan.
Kita pada akhirnya mampu menerima segala hal,
dengan lebih terbuka tanpa menyimpan sedikit pun sesal
serta amarah.
Kita pada akhirnya bisa tersenyum dan saling mendamaikan,
usai seluruh perdebatan yang dulu begitu kita kutuk sebagai
kesalahan.
Kita pada akhirnya sampai pada sebuah pemahaman,
yang terbentuk dari sebuah perenungan ketika jarak
berkuasa.
Kita telah sampai pada titik itu.
Kita sampai meski dengan tertatih bahkan sesekali merintih.
Untuk kamu yang kembali hadir membawa serta seluruh
kenyamanan dan menyingkirkan ketakutan, terima kasih
telah memberi banyak pelajaran.
Untuk kamu yang kembali datang membawa ribuan
pemahaman dengan penerimaan yang tidak pernah aku
sangka sebelumnya, terima kasih karena sudah berani untuk
menyelesaikan.
Dan terima kasih, untuk kamu yang akhirnya membiarkanku
kembali memilikimu, sebagai apa pun kamu di hidupku.
-L-
Aku baru saja mem-posting sebuah tulisan baru di Blog
ketika teleponku berdering. Mama calling.
“Assalamualaikum. lya Ma, ada apa?”
“Waalaikumsalam. Yeee, kamu mah, Mamanya baru nelepon
udah ditanya ada apa.”
“Hehe, Lara lagi engga konsen tadi, Ma. Jadinya langsung
to the point deh.”
“Kamu tuh ya, enggak kangen emang sama Mama?”
Sebuah pertanyaan terdengar dari seberang telepon
dan aku hanya tersipu mendengarnya. Entah, rasanya
selalu seperti ini ketika beliau menanyakan kerinduanku
kepadanya.
“Bilang aja Mama yang kangen, haha. Mau dibawain apa?
Minggu ini Lara balik kok, Ma.”
Aku tersenyum di ujung telepon sambil menutup laptop.
“Bakpia telo ungu ya, tiga. Kejunya dua,” pinta ibuku.
“th, banyak banget! Emang Mama sanggup ngabisinnya?”
tanyaku lagi.
49
“Ya, kan buat disimpen-simpen. Nanti kalau Mama mau lagi,
tinggal makan aja. Enggak usah nungguin kamu balik. Kalau
nungguin kamu balik tuh bisa keburu udahan kepinginnya.”
Sebuah sindiran halus kini terdengar dan membuatku
keki. Tapi, aku tak kehabisan akal, justru sekarang balik
menggoda dengan sebuah permintaan yang terselubung.
“Makanya, kalau Mama mau bisa makan itu kapan aja,
ikut pindah ke Jogja, yuk! Temenin Lara di sini, biar kita
engga LDR-an lagi. Hehehe.”
“LDR-an banget, Nak? Dulu sama yang kemarin aja betah buat
LDR, nyamperin mulu lagi. Ini LDR-an sama Mamanya, malah
jarang nyamperin.”
Aku dibuat mematung oleh ucapan ibuku barusan. Tiba-
tiba saja kembali teringat kebiasaanku untuk berkunjung
ke Bandung bila akhir pekan datang. Sudah lama rasanya
tidak bertemu Saka. Terakhir kali, itu pun pertemuan tidak
sengaja di coffee shop di Jogja. Setelah itu perjanjianku
dengannya sebelumnya tetap berlaku. Kami tidak akan
saling menghubungi jika aku tidak lebih dulu berkunjung
ke kotanya, atau kami kembali dipertemukan secara tidak
sengaja.
Aku tersenyum mengingat-ingat hal itu hingga suara
ibuku di ujung telepon kembali terdengar.
50
“udahan ngelamunnya? Ini Mamamu masih nelepon loh.”
“Hahaha, enggak ada yang ngelamun, Ma. Ya, udah nanti
Lara beliin pesenan Mama. Ada yang mau dititip lagi?”
“Titip bawain calon mantu ya, Nak. Assalamualaikum.”
Belum sempat aku protes mengenai omongan ibuku,
beliau sudah mematikan sambungan telepon. Meninggalkan
aku yang hanya bisa tersenyum menggeleng sambil berucap
lirih.
“Waalaikumsalam.”
Sebetulnya topik itu menjadi salah satu hal yang
membuat aku malas bolak-balik ke Jakarta dan berlama-lama
ada di rumah. Meski aku senang dengan sifat jahil ibuku dan
sering merasakan rindu akan sifatnya itu, tapi tetap saja, aku
merasa malas jika beliau sudah mulai merambah ke ranah
jodoh dan semacamnya.
Ya, aku memang hidup di tengah keluarga yang bisa
dibilang cukup kuno. Bila seorang wanita belum menikah
di umur twenty something, maka akan banyak pertanyaan
‘kapan’ yang akan hadir.
Tak hanya berhenti sampai di situ, pertanyaan kapan
adalah momok terbesar di setiap acara keluarga yang
kuhadiri. Bila belum juga membawa pasangan maka
pertanyaan yang mampir adalah, kapan menikah? Bila sudah
menikah dan belum jua dikarunia anak, pertanyaannya
51
akan berganti dengan, kapan punya momongan? Bila sudah
menikah dan punya anak, pertanyaannya akan semakin
bervariatif dengan, kapan nih dikasih adik? Kasihan masa
sendirian aja anaknya?
Menarik sebetulnya. Banyak sekali yang lebih peduli
dengan kekurangan hidup orang lain dibandingkan dengan
kekurangan hidupnya. Sibuk menambal sulam kekurangan
dirinya dan memamerkan kesempurnaan semata di depan
khalayak umum.
Masih dirasa belum cukup, mereka juga menerapkan
standar definisi bahagianya kepada orang lain. Dengan kata
lain, bila seseorang yang dia kenal itu belum seperti apa
yang ada di bayangan mereka, maka orang itu memang tidak
bahagia.
Aku memijat kedua pelipis dengan ujung jari telunjuk
dan ibu jari. Menyandarkan kepalaku di kursi sambil
memejamkan mata. Berusaha menghentikan isi kepalaku
yang terasa semakin melelahkan jika terus-menerus kuberi-
kan pemikiran seperti tadi. Mendadak aku dihadiahi semesta
sebuah perasaan rindu. Rindu untuk berkisah dan berbagi,
setidaknya kepada sahabatku, Kanaya.
a
52
Aku mulai kembali pada rutinitas pekerjaan
freelance-ku. Karena hampir setiap hari pulang
malam, belum sempat lagi aku dan ibuku melanjut-
kan perbincangan kami. Belum sempat juga aku mengajak
ngobrol adik-adikku perihal apa yang disampaikan ibuku.
Meski kadang aku mengerjakan pekerjaan di rumah,
ibu dan adik-adikku pasti sudah berangkat untuk bekerja
dan sekolah saat aku terbangun. Lalu, tak lama bosan akan
datang dan membuatku ingin mendatangi beberapa coffee
shop untuk mencari inspirasi dan melanjutkan pekerjaanku.
Tidak hanya bergelut dengan rutinitas, aku mulai
membeli beberapa buku untuk aku baca. Aku juga semakin
aktif untuk menulis di Blog pribadiku. Hal lain yang
membuatku tetap merasa hidup dan tidak kesepian. Hal lain
juga yang menggantikan hobiku berkutat dengan kamera,
karena sudah jarang mengikuti kegiatan komunitas fotografi.
Di suatu weekend, aku memutuskan berkumpul dengan
beberapa rekan komunitas menulis di salah satu coffee shop
di Bandung. Ajakan dari salah satu teman.
“Mas Saka kemarin abis dari Jogja katanya ya? Ketemu
sama anak-anak nulis di sana?” tanya Nina, salah seorang
anggota di komunitas menulis.
“Tya. Hehe. Sebenernya enggak sengaja ketemu. Ternyata
temenku ada yang ikutan komunitas nulis juga. Hehe.” Aku
menjawab sambil asyik menatap layar laptop karena sedang
memikirkan tulisan yang akan aku buat.
53
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)