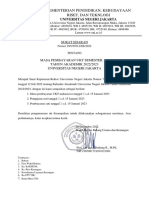Professional Documents
Culture Documents
Materi Kelompok 3 Arkeologi
Materi Kelompok 3 Arkeologi
Uploaded by
Fina Amelia0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views14 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views14 pagesMateri Kelompok 3 Arkeologi
Materi Kelompok 3 Arkeologi
Uploaded by
Fina AmeliaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 14
29
od
Menuju Arkeologi
Maritim Indonesia’
Dua hal yang menjadi pandangan pokok bagi Diskusi
Ilmiah Arkeologi XIV ini, yaitu pertama, pengembangan
Arkeologi Maritim, dan kedua, perhatian pada kawasan timur
Indonesia dan wilayah-wilayah di sebelah timurnya lagi, seluruh
kawasan Oseania yang meliputi Mikronesia, Melanesia, dan
Polinesia. Mengenai perlunya perhatian ditujukan ke kawasan
Pasifik di sebelah timur Indonesia telah pernah saya lontarkan
dalam Diskusi Imiah Arkeologi II tahun 1985. Bahkan dalam
pengembangan kurikulum di Jurusan Arkeologi Universitas
Indonesia telah dimasukkan matakuliah “Prasejarah Kepulauan
Pasifik”. Namun, kemajuan belum tampak, para ahli arkeologi
Indonesia kebanyakan masih terlalu “home bound”, kakinya
masih berat untuk melangkah ke luar daerah asalnya.
|_._'Makalah pada Diskusi Imiah Arkeologi (DIA) XIV, bertema
‘Hubungan Maritim Antara Indonesia dengan Wilayah Sebelah Timurnya”,
diselenggarakan bersama oleh: IAAI Komda Sulawesi, Maluku dan Irian;
SPSP Sulselra; Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin; Balai Arkeologi
Makassar; dan Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non-Hayati.
Makassar, 16-17 Juni 2001.
1a Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah
30 Budayt
Pengembangan arkeologi Asia-Pasifik, atau khusug
Indonesia-Pasifik, memang memerlukan pemancangan nial
yang kuat, disertai program yang terarah untuk pembinaan
kemampuan di bidang penelitian dan kerja sama antamegara, dan
juga antarlembaga. Masalah warisan bersama sejarah dan sejarah
kebudayaan yang selama ini telah mendapatkan cukup banyak
perhatian para ahli arkeologi Indonesia adalah yang berkaitan
dengan kawasan ‘Asia daratan, sampai India dan Persia di arah
arat, serta Cina di arah utara. Dalam pada itu data kebahasaan
menunjukkan adanya kekerabatan budaya antara suku-suku
bangsa di Indonesia dengan suku-suku bangsa di kawasan
Oseania. Sejumlah penelitian prasejarah pun menunjukkan
adanya hubungan-hubungan budaya tertentu, khususnya
sebagaimana ditunjukkan oleh temuan keramik tanah liatnya.
Petunjuk-petunjuk itu membawa ke arah keharusan adanya
Komunikasi dan interaksi antarwarga budaya yang berlainan
aE ae tentunya dengan melintasi sejumlah
cones , baik itu laut besar, laut kecil, teluk, ataupun
——
Selanjutnya, izinkan say
Lb 4ya me! i
ae i ape peaagkhususkan perhatian kepada
than pe 5 em
Arkeologi Maritim meliputi dua a
mempelajari dan menangani segala tin
a Penta segala sesuatu yang terkait q,
pelayaran, nam a
eee mun datanya terdapat dj ie engan kelautan
ea ae ane aspek-asp elenya, Sudah tentu
yang di dalam 9; au tin, a
Arkeologi maritim yang te mait dan juga di i
a antara lain adalah yang eae 2 dapat gi santa
pen, akan adanyapelayuren eet? den, dijumpai di
arkawasan, eo Si
gan Arkeologi Maritim.
Sarapan, yaitu pertama,
ggalan di bawah air, dan
aN si,
BaN sisa_si
nd sisa, atau
i a
: lu, seperti
=
a
misalnya ¢
prasejarav
Sebaran n
antarpula'
pulau di
kegiatan }
arkeologi
kegiatan |
pembuat
pelayaran
perlengk
mutiara, |
masa lalu
penafsira
tertulis, s
melalui p
yang ma:
yang hid
Sisa-
lebih me
tinggalan
danau. In
terdahult
lalu di da
sistem m
yang ten
disebutk:
crannog ye
Robert N
Tinggala:
i di
“Arkeologi dan Perluasannya 31
misalnya ditunjukkan oleh sebaran gerabah sekerabat yang oleh
prasejarawan disebut jenis Sahuynh-Kalanay dan Bao-Malayu.
sebaran nekara perunggu pun merujuk pada adanya pelayaran
antarpulau, serta antara daratan Asia Tenggara dengan pulau-
pulau di Indonesia. Itu adalah data tak langsung mengenai
kegiatan pelayaran di masa lalu. Adapun golongan kedua data
arkeologi maritim adalah, baik yang berkenaan langsung dengan
kegiatan kelautan manusia masa lalu, seperti yang menyangkut
pembuatan kapal dan penggunaan peralatan penunjang
pelayaran seperti untuk menentukan arah, maupun yang berupa
perlengkapan penangkapan/pencarian hasil laut seperti ikan,
mutiara, dan karang- Peralatan pelayaran dan kenelayanan dari
masa lalu itu dapat ditemukan sebagai artefak arkeologi, yang
penafsiran akan fungsinya dapat diperkuat oleh adanya data
tertulis, seperti catatan-catatan lama, ataupun analogi etnografik
melalui pengetahuan akan adat-kebiasaan dan teknologi serupa
yang masih dapat diamati pada masyarakat-masyarakat etnik
yang hidup di masa kini.
Sisa-sisa teknologi dan sistem maritim masa lalu itu sendiri
lebih mempunyai peluang untuk masih bisa diketahui melalui
tinggalan-tinggalannya yang terdampar di dasar laut, sungai, atau
danau. Ini termasuk ranah garapan pertama yang telah disebutkan
terdahulu. Arkeolog harus menyelam ke dalam air. Sisa-sisa masa
lalu di dasar Jaut itu dapat berupa sisa-sisa kapal dengan segala
sistem manajemen dan peralatannya, maupun sisa-sisa hunian
yang tenggelam ke dalam air. Suatu contoh kajian yang dapat
disebutkan adalah berkenaan dengan sisa-sisa rumah yang disebut
crannog yang ditemukan di perairan Skotlandia dan Irlandia (periksa
wer Munro, 1882, Ancient ‘Scottish Lake Dwellings or Crannogs)
ggalan crannog di dalam air itu, berkat efek pengawetan dari
i Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah
Budaya
: Jain dapat melestarikan sisa-sisa Mentega g
cate ungkin bertahan di atas tangy
ang sistematis dan komprehensif mengep
‘i V0 yang karam dapat dilihat dalam Hollangj,
nium. A Contribution to the Study of the History, Archaeology
Compe
Ceefeatnan Lsicograpy of] 150ft Dutch East ndiamen 7
St]
1750), yang disusun oleh Jerzy Gawronski, Bast Kist, dan Od
Stokvisvan Boetzelaer (Rijksmuseum Amsterdam & Elser
1992). Struktur kapal, beserta tata peralatan dan tata penemp a ih
muatan kapal dibahas dengan teliti, diklasifikasikan, dan disertai
gambar-gambar detail.
Pengembangan penelitian arkeologi bawah-air sesungguh-
nyalah memerlukan taruhan besar dalam hal peralatan penelitian
serta pelatihan fisik dan mental bagi para penelitinya. Itu
semua memerlukan modal besar, dan juga keberanian besat-
Bagsimanapun, kiranya adalah amat pantas apabila Indonesia,
ee Perairan begitu luas, juga mempunyai divist
ge nen yen a Usaha ke arah itu sudah dimulal
pelaihan di negerisnec es oH arkeologi untuk menjalani
Seri lain,
Pada kongresnya ter n. That
memuat dalam
akhir (tahan toni Atkeologi Indonesia
eKlarasinya, Ee 1999) di Yogyakarta telah pula
dikembangkan di Indonee a? Atkeologi B, :
Betbagai teknik pense Namun, usahe penv2” Air harus
. :
maupun men; Pendugaan, lum maksimal:
. » baik menge, es
genai kar ngenai
laut, adalah tekni ndungan yang terkub ‘eaeman laut
ur di
ies ng sel; 1 baw,
mikian juga teknikeet, Perla dif ae dasar
i 1 4
teknil a eni. Pemu:
ik Pendokumentasian sere Y*lamay BKatan ol
atas permukaan 2 Pengangpar, Sta j se
AN tey
air,
Bagi tem
kaan air dip
hal konserve
Diperlukan f
telah terjadi
itu, diperlul
biologi. Men
air memerlu
arkeologi itt
bahu-memb
masyarakat
Arkeologi B
Dalam |
tegas meng
atau peraire
Ini tidak be
Jalu harus ¢
tetap “pele
sebagaima
Kebudayaatr
perlindung:
Gawronski
belum ada |
penelitian
pandangan
didapat dai
ada dua pa
Pertama, m
kapal-kapa
komples d
al.
aut
sat
nu-
sSe-
nik-
Arkeologi dan Perluasannya 33
Bagi temuan-temuan yang telah diangkat ke atas permu-
kaan air diperlukan berbagai kemahiran lain, yaitu dalam
hal konservasi benda-benda sesuai dengan ragam bahannya.
Diperlukan pula kajian mengenai sebab-sebab kerusakan yang
telah terjadi atas artefak-artefak yang ditemukan itu. Untuk
itu, diperlukan keahlian dalam analisis kimia dan (mikro)
biologi. Memang harus diakui bahwa kajian arkeologi bawah-
ait memerlukan tunjangan berbagai disiplin ilmu lain di luar
arkeologi itu sendiri. Sudah matang waktunya bagi kita untuk
pahu-membahu antardisiplin, antarinstansi, antarpotensi dalam
masyarakat, untuk mewujudkan kekuatan nasional dalam
Arkeologi Bawah Air.
Dalam kaitan itu semua perlu diambil sikap bersama yang
tegas mengenai data masa Jalu yang tersimpan di dalam laut,
atau perairan apa pun, yang terpusat pada tujuan pelestarian.
Jni tidak berarti bahwa sisi komersial yang dapat dimanfaatkan
lalu harus diabaikan sama sekali. Namun, pedomannya harus
tetap “pelestarian dahulu”, baru yang lain-lain. Pelestarian,
sebagaimana dipahami dalam teks calon RUU tentang
Kebudayaan (Ditjen Kebudayaan, 1999), meliputi aspek-aspek
perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan.
Gawronski (dalam Compendium, 1992:15) mengeluhkan bahwa
belum ada kerangka umum yang disepakati bersama mengenai
penelitian arkeologi bawah air, dan adanya kesenjangan
pandangan mengenai nilai dan hakikat dari artefakartefak yang
didapat dari sisa-sisa kapal VOC yang tenggelam. Menurutnya
ada dua pandangan yang bertolak belakang mengenai hal itu.
Pertama, menganggap bahwa tinggalan arkeologi bawah-air dari
kapal-kapal karam itu merupakan sumber informasi ilmiah yang
komples dan beraneka ragam dan itu dapat digunakan untuk
esa sarah
Indonesia: Kajian Arkeologi Sets dan Sejaral
Budaya In
erekc i ia.Sementra i
si kegiatan dan tata perilaku manusia. ° i ty,
ag dua melihat artefak-artefak yang itemukan itu
pandangan yang e ian koleksi penda-benda bersejarah yang
rmempunyai harga pasaraniny® dan dengan Ce nae
upaya techadapnya adalah Penge ar ogi”. Contoh
yang sering diberi label salah sebagal arkeologi”. Conto:
pendekatan kedua yang disebutnya adalah perlakuan terhadap
peninggalan kapal Geldermalsen oleh M. Hatcher, yang bersifat
purely commercial and is not aimed at producing or even keeping a record
of archaeological information ‘murni komersial dan tidak ditujukan
untuk membuahkan, atau bahkan menyimpan (saja) catatan
sebagai informasi arkeologis’.
Pengkajian mengenai teknologi pelayaran, beserta segala
urusan i
n yang terkait dengannya, seperti teknologi perkapalan
IPA arsip-arsi tersedi
pelayaran, maupun petdagan arsip, anya
‘gan, b;
bai *
terkait dengan masa ae ‘mengenai perkapalan,
eadaan sepertinadinan Sah day; ne kadang-kadang
dan isi tu ‘a dan sae
analisis data dati sinero; Politik. Dalam
analisis data dari aWah aj Slantar;
terdapat ‘di — Sumber.si, Ngan pe *Penghimpunan
uar air’ Nghi:
arkeologi Indonesian : Bagaiman lig ihe smpunan dart
nyata dalam Arken. eS Pang PU 8 lebj
Keolog Bay Cunt, OPT ASL h banyak
ada kemauan, gj
» di si ™Mem| my -
wu ada jalan Saya bere, bent Nida ahli
1 mana
(E.B..
Tempe
EJ.Bri
oleh ar
van de |
“Ontw
Java”,
begitu
Pencap
Walaup
Masih t
Yang dit
ada keb
dimaksy
asal-uen
ali
atan
nana
35
@&
Masyarakat dan Perubahan
Gaya Seni: Ulasan atas Studi
EB. Volger'
E.B.Vogler telah membuat suatu kajian mengenai hiasan
kalamakara pada candi Jawa hampir empat puluh tahun yang lalu
(E.B.Vogler, 1949. De Monsterkop uit het Omlijstingsornament van
Tempeldoorgangen ennissen in de Hindoe-Javaanse Bouwkunst. Leiden:
EJ.Brill. Hasil studi yang berupa buku tersebut kemudian disusul
oleh artikel-artikel mengenai pokok yang sama, yaitu “De stichtingstijd
yan de tjandi’s Gunung Wukir en Badut”, BEI 108 (1952):313-50, dan
“Ontwikkeling van de gewijde bouwkunst in het Hindoeistische Midden
Java”, BKI 109 (1953):249-71.) Hasil studi sarjana ini telah
begitu sering dikutip, dan sesungguhnya merupakan salah satu
pencapaian penting dalam sejarah kajian Arkeologi Indonesia,
walaupun oleh sarjana itu sendiri telah diakui bahwa mungkin
masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam kesimpulan-kesimpulan
yang ditarik, Akan tetapi, ia juga menyatakan dengan tandas bahwa
ada kebenaran pada garis besarnya (1949: 235). Garis besa yang
dimaksudkannya dalam kutipan ini khususnya berkenaan dengan
asal-usul dari kerangka bentuk hiasan kalamakara. Namun, dari
'Makalah disajikan dalam diskusi ilmiah Arkeologi is
gi VI, diselenggarakan
ie TAAL katan Abli Arkeologi Indonesia) Komisariat Daerah Jabarta dan
jawa Barat, di Jakarta, 11-12 Februari 1988.
udaya Indonesia: Kajian Arkeolog, Sen, dan Sejarah
36
keseluruhan studi E.B.Vogler itu terbaca juga keyakinany a
kebenaran kesimpulan-kesimpulannya yang erkenaan denpay
. ip-prinsip dasar yang melandasi perkembangan kesenian}
on (petiksa khususnya Vogler 1943: (Dinsisrrai spp
Funstenkele wetten welke haar vormgeving en vormontvid ing beers
halaman 1-23, dan “Slotsbeschouwingen", halamien) 234-43), Prinsip.
prinsip dasar inilah yang dalam karangan ini akan dibahas.
Kajian Vogler itu pada dasarnya merupakan suatu kajian
mengenai vormgeving (pemberian bentuk, penciptaan bentuk)
dalam seni rupa, seni pahat batu khususnya. Kasug yang
ditelitinya adalah hiasan kalamakara pada pintu-pintu dan
relung-relung candi batu di Jawa sepanjang masa yang disebutq 1
“Hindoe—Javaans” (Jawa-Hindu). Kajian vormgeving itu diara
kan untuk mengidentifikasikan berbagai stijl (gaya) yang pad#
gilirannya dihubungkannya dengan wilayah dan rentangall
masa yang lebih sempit. Studi ini merupakan yang petta
dalam Arkeologi Indonesia yang menggunakan pendekatall
‘uantitatif meskipun tidak digarap dengan teknik kuantitatl
Yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif di sini adalall
bahwa si peneliti menghadapi
items (satuan-satuan, dalam hal ini
5 al ini masin ing hiasal
wn ; '8-masing hias:
]amakara) sebagaimana laiknya dalam survei statistik orang
menghadapi himpunan satuan-s; as
3 ati i
emudian menyelidiki hubungan-hubusge eo emetlan sampe
wubungan di ;
itu dengan menganalisisnya berdacer va salam himpunal
terdapat di dalam items terseby inset variabel
keajian Vogler ini den, :
gan kajian ED,
vita ‘pigura sulur 2
Men; i hi:
Se Belung, "8enai hiasas
besar (periksa EDK. i
candi yang lain,
sama mengenai
> me
Bosch, 194g, tu es a
* De Gouden, Jumlah yang
Ki
em: Inleiding it
de Indische Symbol
mencari hubung:
melainkan henda
kiem” (rahim em
yang dikemukakat
tertulis yang din
melandasi tema I
Vogler tidak
pemasalahan lai
pokoknya adalal
bagaimana caran
dijawabnya deng
(variabel) dari
dijumpai dan di
lebih muda dijel:
yang lebih tua.
sendiri’ dan me
seni. Dengan d
terjadi sebagai
Kesimpulan ini.
telaahnya bahw
perjalanan’, dan
Kesimpulan ini
kedua, yaitu b:
berubah). Keny
adalah bahwa se
merupakan suz
baku beserta v
digunakan seb:
Saya-gaya ters
“Arkeologi dan Perluasannya 37
de Indische Symboliek. Amsterdam/] Brussel:Elsevier). Bosch tidak
mencari hubungan antarsatuan atau antarkelompok satuan,
melainkan hendak menjelaskan makna tema tunggal “gouden
kiem” (rahim emas) yang diwujudkan dalam seluruh contoh
yang dikemukakannya itu dengan menggunakan sumber-sumber
tertulis yang dinyatakannya sebagai penjelasan konsep yang
melandasi tema hiasan candi yang dibahasnya itu.
Vogler tidak membahas makna simbolis. Ja mengajukan
pemasalahan lain sejarah kesenian. Pertanyaan-pertanyaan
pokoknya adalah: bagaimana asal-usul suatu gaya seni dan
bagaimana caranya gaya seni itu terbentuk. Pertanyaan pertama
dijawabnya dengan cara menelusuri satu per satu komponen
(variabel) dari hiasan kalamakara itu: di mana ia mula-mula
dijumpai dan di mana saja ia kemudian terdapat. Tempat yang
lebih muda dijelaskannya sebagai “mengambil alih” dari tempat
yang lebih tua. Masing-masing komponen dapat ‘berjalan
sendiri’ dan menjadi unsur yang dapat mengubah suatu gaya
seni. Dengan demikian, perubahan gaya seni pada dasarnya
terjadi sebagai suatu stijlver-menging (percampuran gaya).
Kesimpulan ini ditarik oleh Vogler karena ia menjumpai dalam
telaahnya bahwa setiap komponen mempunyai suatu ‘riwayat
perjalanan’, dan tidak pernah hanya terdapat pada satu contoh.
Kesimpulan ini berhubungan dengan penjawaban pertanyaan
kedua, yaitu bagaimana cara gaya seni itu terbentuk (atau
berubah). Kenyataan yang muncul dari data yang digarapnya
adalah bahwa setiap gaya seni yang diidentifikasikannya ternyata
merupakan suatu konfigurasi saja dari komponen-komponen
baku beserta variasi-variasinya. Latar sejarah dalam hal ini
digunakan sebagai betul-betul suatu latar untuk meletakkan
gaya-gaya tersebut. Dikotomi-dikotomi yang digunakannya
8 Budaya Indonesia: Kajian Arkeotogi, Seni, dan Sejarah
3
ntuk menggolong-golongkan Jatar tersebut adalah: “Siwaitiscy»
ul
vs budahistisc” dan “Sailendra” vs “non-Sailendra”, ditambah ula
dengan dikotomi geosrafis yaitu “Midden-Java" ¥® Oost-Javar,
Dibedakan pula “Noord Midden-Java” dengan “Zuid Midden-Jaya
yang bertumpangtindih dengan perbedaan sifat Saiwa untuk Jawa
Tengah Utara dan sifat Bauddha untuk Jawa Tengah Selatan,
Kekuasaan politik maupun keagamaan dijelaskannya sebagai
faktor yang menentukan dalam memaksakan perubahan gaya
seni (Vogler 1949:7-10). Dalam bagian yang selebihnya dari
bab pertama bukunya, Vogler menandaskan bahwa seni pahat
Jawa-Hindu itu pada dasarnya bersifat dienstbaar (terpakai) dan
gebonden (terikat). Dasar pikirannya adalah bahwa seni pahat,
yang khususnya terlihat pada bangunan-bangunan keagamaan
itu, sepenubnya diabdikan untuk memenuhi kebutuhan agama,
dijalankan dengan rasa hormat dan ketaatan pada tradisi yang
dianggap suci, dan tidak mungkin ada ruang untuk kebebasan
individual si seniman.
aan Vogler mengajukan kerangka pembabakan berdasarkan
. i a pee ‘uno yang ada padanya, kemudian didukung
1 data perkembangan gaya seni pahat yang disusunnya. la
Jawa Tengah
Ss
ase2| sa stirmasat gee engahan awa Timur
i bad ke M]
382-3 | sekiar 7% hingga +750 M
750 hing 5
Masa | 3860-3927 ys nat B60 Mas
Dinoyo,
», 7E .
Magacy OOM
se
a
Sia 271042
itokhingga ag tt dari
wa Ka Avangga;
Wasa.
S25] mundumya Kekuatan masyarakat
indy,
ingasan.
S2t-Majapahit
Kete
kembang
Jawa Ten
Jawa Ten
Jawa Tent
Jawa Ten!
Jawa Ten
(Periksa Vo
Jawe
Namun,
diperhat:
pertumb
Tengah,
sesuatu 1
1949:23;
Negeri ya
dan Utar
Laut dar
Arkeologi dan Perluasannya 39
Keterangan-keterangan pokok mengenai tahap-tahap pet-
kembangan seni pahat itu adalah:
Guatutahap perkembangan Kesenian yang hiptels, hanya
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5820)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Makasih Udah Pesan Gofood: Total DibayarDocument1 pageMakasih Udah Pesan Gofood: Total DibayarFina AmeliaNo ratings yet
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Se Pembayaran Ukt 118 2022-2023Document1 pageSe Pembayaran Ukt 118 2022-2023Fina AmeliaNo ratings yet
- Soal Uas 11 Sma/smk SejarahDocument12 pagesSoal Uas 11 Sma/smk SejarahFina AmeliaNo ratings yet
- Ypab Is HiringDocument5 pagesYpab Is HiringFina AmeliaNo ratings yet
- PocapoeeDocument1 pagePocapoeeFina AmeliaNo ratings yet
- Thanks For Ordering Gofood: Order DetailsDocument1 pageThanks For Ordering Gofood: Order DetailsFina AmeliaNo ratings yet
- Penelitian SejarahDocument25 pagesPenelitian SejarahFina AmeliaNo ratings yet
- Vereenigde Oostindische Compagnie Perusahaan Hindia Timur BelandaDocument6 pagesVereenigde Oostindische Compagnie Perusahaan Hindia Timur BelandaFina AmeliaNo ratings yet
- Perang Melawan Kolonialisme Dan ImperialismeDocument17 pagesPerang Melawan Kolonialisme Dan ImperialismeFina AmeliaNo ratings yet
- Kehidupan Awal ManusiaDocument17 pagesKehidupan Awal ManusiaFina AmeliaNo ratings yet
- Masa Pemerintahan BelandaDocument10 pagesMasa Pemerintahan BelandaFina AmeliaNo ratings yet
- Vereenigde Oostindische Compagnie Perusahaan Hindia Timur BelandaDocument6 pagesVereenigde Oostindische Compagnie Perusahaan Hindia Timur BelandaFina AmeliaNo ratings yet
- Pengajaran Bahasa Jepang UiDocument29 pagesPengajaran Bahasa Jepang UiFina AmeliaNo ratings yet