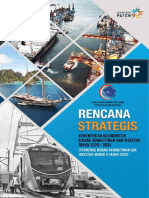Professional Documents
Culture Documents
Pidato Pengukuhan Guru Besar
Pidato Pengukuhan Guru Besar
Uploaded by
Agung Kresna Bayu0 ratings0% found this document useful (0 votes)
76 views27 pagesOriginal Title
Pidato_Pengukuhan_Guru_Besar
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
76 views27 pagesPidato Pengukuhan Guru Besar
Pidato Pengukuhan Guru Besar
Uploaded by
Agung Kresna BayuCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 27
NEGARA, UNIVERSITAS DAN BANALITAS
INTELEKTUAL:
SEBUAH REFLEKSI KRITIS DARI DALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Itmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Oleh:
Prof. Drs. Heru Nugroho, S.U., Ph.D.
NEGARA, UNIVERSITAS DAN BANALITAS
INTELEKTUAL:
SEBUAH REFLEKSI KRITIS DARI DALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
pada tanggal 14 Februari 2012
di Yogyakarta
Oleh:
Prof. Drs. Heru Nugroho, S.U., Ph.D.
Para Guru besar dan hadirin yang saya hormati,
Assalamu’alaikum Wr.Wb. dan Salam sejahtera bagi kita semua
Saya sangat merasa terhormat bisa berdiri di forum pengukuhan
guru besar ini dan saya menyadari bahwa peristiwa ini dapat terjadi
hanya karena campur tangan kekuatan Adi Kodrati Yang Maha Kuasa
dan Maha Bijaksana. Ijinkanlah saya menyampaikan pidato
pengukuhan saya sebagai Guru Besar Sosiologi pada Fisipol UGM
dengan judul:
NEGARA, UNIVERSITAS, DAN BANALITAS INTELEKTUAL:
SEBUAH REFLEKSI KRITIS DARI DALAM
Para hadirin yang saya hormati,
Ketika saya akan memilih tema pidato ini, saya mencoba
merenung dan menghitung waktu mundur, berapa lama saya sudah
bekerja dan apa yang telah saya sumbangkan untuk UGM. Dua puluh
empat tahun sudah saya bekerja sebagai dosen dan peneliti di
lembaga ini, yaitu di sebuah universitas terbesar di tanah air dan
sebuah perguruan tinggi yang menjadi salah satu barometer
perkembangan akademik di bumi Pertiwi.
Tokoh-tokoh akademik sejati telah lahir di UGM seperti Prof.
Dr. Sardjito, Prof. Dr. Johanes, Prof. Dr. T. Jacob, Prof. Dr.
Notonagoro, Prof. Dr. Koesnadi Hardjasumantri, Prof. Dr. Mubyarto,
Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Prof. Dr. Umar Kayam, Prof. Dr.
Loekman Sutrisno, dll. dengan karya akademiknya dari bidang
Kedokteran, Fisika, Filsafat, Hukum, Sosiologi, dll. Kalau kita mau
jujur nama besar yang disandang oleh UGM ini hanya ditopang oleh
beberapa gelintir akademisi dan tidak berarti semua akademisi yang
bekerja di dalamnya memberi kontribusi yang sama bagi kebesaran
nama itu. Sungguh saya sebagai dosen yang belum memiliki karya
apa-apa merasa sangat beruntung bisa mengabdi di lembaga ini.
Saya berkeinginan juga memberikan sumbangan kepada
almamater tercinta, meskipun hanya setitik upaya akademik tanpa arti.
Tema dan kaiian kritic vane akan cava kemukakan adalah hanalitas
2
intelektual yang sclama ini menggejala di perguruan linggi ini, Saya
sengaja menggunakan UGM sebagai subject matter karena cinta
saya kepada almamater. Banalitas intelektual sebetulnya merupakan
fenomena yang terjadi di hampir seluruh perguruan tinggi di tanah air,
Pilihan UGM sebagai fokus kajian dikarenakan lembaga ini
merupakan representasi dari perguruan-perguruan tinggi yang ada.
Sekaligus saya ingin melakukan refleksi kr karena saya ada di
dalam permasalahannya dan sekaligus saya men jadi bagian dari
persoalan tersebut. Pada umumnya civitas akademika dan khususnya
ilmuwan sosial, politik, atau budaya biasanya mengarahkan alat-alat
kerjanya untuk menganalisis, mengkritisi dan mencari solus problem-
problem yang ada di luar diri mereka, Namun, refleksi diri yang saya
lakukan berupaya membalik cara itu, karena alat-alat kerja akademik
yang ada di dalam disiplin Sosiologi (and beyond) diarahkan untuk
melihat perilaku “banalitas intelektual” yang sedang berlangsung di
perguruan tinggi sendiri.
Tujuannya jelas, untuk membuang stereotype ilmuwan sosial
bahwa “gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan
terlihat jelas”. Refleksi kritis dari dalam atau self-reflection
(Habermas, 1971: 228) berupaya membalik anggapan negatif tersebut
dengan cara kontemplasi subjektif/transendental dan historis/empiris
untuk membongkar borok yang ada di dalam diri sendiri kemudian
dikritisi, bertindak emansipatoris untuk mencari_ solusi agar
pendidikan tinggi kita menjadi lebih berkualitas. Atas dasar kesadaran
subjektif, saya berusaha bangun dari candu banalitas intelektual yang
me-ninabobo-kan dunia pendidikan tinggi dan mencoba menyadari,
kalau hal ini dibiarkan terus, dunia pendidikan tinggi kita cenderung
involutif (mengalami perumitan-perumitan yang tampak sibuk tetapi
sebetulnya stagnan) sehingga tinggal menungeu waktu berdentangnya
lonceng kematian universitas, Karena rasa cinta saya terhadap UGM
sebagai tempat saya berkarya dan mengabdi maka saya ingin berbuat
sesuatu yang positif untuk lembaga ini.
Para hadirin yang saya muliakan,
Setelah berkecimpung di bidang sosiologi hampir seperempat
3
sebagai sosiolog. Kadang saya merasa optimis dengan perkembangan
school of thought yang ada, namun sering saya jatuh dalam fase
pesimis, skeptis bahkan nihilis karena lingkaran setan perdebatan yang
tak berkesudahan. Skeptisme saya menguat ketika sosiologi akan saya
gunakan untuk membongkar fenomena banalitas intelektual di
perguruan tinggi sendiri, dimana fenomena ini dilingkupi relasi-relasi
kuasa antar intelektual kampus dan praktek-praktek kekuasaan rezim
akademik dimana saya menjadi bagiannya.
Ditambah lagi perdebatan tak berkesudahan dari para penganut
Klasisisme, modernisme, kritisme dan postmodernisme/post-
strukturalisme yang saling tidak pernah mencapai titik temu. Justru
yang saya tangkap dan pahami bahwa Sosiologi sebagai disiplin ilmu
pengetahuan dan sekaligus sebagai pendekatan yang digunakan untuk
menganalisis, menafsir, dan mengkritisi fenomena-fenomena sosial,
semakin hari cenderung semakin dijumpai _limitasi-limitasinya,
meskipun bantahan-bantahan akan hal itu juga muncul. Anehnya, saya
tidak pernah lari dari disiplin ini. Saya tetap setia dan tekun mengikuti
bahkan kadang merasa mengalami “ekstasi” dengan terlibat dalam
perdebatan-perdebatan itu dan sekaligus terdorong untuk tetap
melakukan riset-riset akademik. Hal ini mungkin karena menyangkut
soal “periuk” dan kapling ekonomi politik. Sosiologi dapat diibaratkan
sebagai “rumah sakit jiwa” di mana para sosiolognya saling terlibat
perdebatan dan terkesan mereka saling meyakinkan bahwa mereka
masih tinggal di rumah sakit jiwa tersebut (Berger & Kellner, 1981
dan Berger, 2011)
Sebagai contoh, kritik keras dan olok-olok telah dilontarkan dari
para sosiolog aliran kritis dan skeptis yang mendegradasikan status
keilmuan Sosiologi menjadi sekedar pseudo-science (Islam, 2008)
untuk menegaskan bahwa Sosiologi mengalami limitasi akademik.
Sosiologi yang didirikan oleh filsuf Perancis aliran positivisme,
Auguste Comte, yang memiliki spirit dan logika sebagai the queen of
social sciences telah mengalami academic distrust karena kegagalan
demi kegagalannya dalam menjelaskan, menafsir atau memecahkan
berbagai persoalan sosial sehingga status pengetahuannya tidak
ubahnya seperti kepercayaan (belief). Kondisi seperti ini oleh Thomas
Kuhn (1996) disebut sebagai fase anomalie dalam setiap revolusi ilmu
4
istilah dunia yang mrucut (Runaway World) karena konsep, teori dan
metode yang ada dalam Sosiologi cenderung selalu tertinggal dengan
fenomena yang akan dijelaskan yang selalu mengalami perubahan
terus-menerus. Dalam tradisi klasik, kondisi seperti itu melahirkan
pandangan static vs dynamic (Coser, 1977) atau Weber menegaskan
dengan dikotomi konsep charisma vs routinization dalam melihat
proses kebudayaan (Schroeder, 1992).
Kegalauan saya semakin menjadi ketika sindiran kaum kiri
menyatakan Sosiologi telah mengalami pemiskinan (the poverty of
Sociology) sebagai ilmu karena cenderung asyik terjebak dalam
ambiguitas logika Neo-Kantian (Weber, 1990), sehingga sudah cukup
puas dengan sekedar menjelaskan (Erklaeren) dan memahami/
menafsir (Verstehen). Sosiologi secara ideologis tidak berbuat apapun
terhadap subject matter yang diteliti kecuali harus menjaga sikap
“objektivitas ilmiah” yang dingin dan kaku. Misalnya, fenomena
kemiskinan, penindasan, dan marginalitas hanya sekedar cukup
dideskripsikan, dianalisis, dan ditafsir tanpa ada komitmen apapun
terhadap perubahan atas fenomena itu kecuali menjaga objektivitas
ilmiah. Kemiskinan Sosiologi ini mendapat inspirasi dari keprihatinan
Marx atas kemandegan filsafat pada waktu itu —disebut dengan
kemiskinan filsafat (The Poverty of Philosophy) — di mana bidang
filsafat hanya berkutat dengan pertanyaan apa/mengapa (ontologi) dan
bagaimana (epistemologi) tanpa berbuat apapun terhadap subjek yang
diteliti (Marx, 2001). Sosiologi harus memberanikan diri menegaskan
bukan sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang hanya sekedar
menjelaskan dan menafsir tetapi harus melakukan Kkritik untuk
mengubah keadaan dengan cara memihak sehingga terjadi
pembebasan. Konsekuensinya teori tidak bisa dipisahkan dengan
praktik, berteori adalah sekaligus praxis, maka dengan sendirinya
menolak stereotype akademisi yang berumah di angin (Hartoko,
1980).
Saya semakin tidak yakin dengan Sosiologi konvensional
apabila digunakan untuk menjelaskan dan membongkar fenomena
banalitas intelektual di perguruan tinggi sendiri yang akan saya
ungkapkan ini. Fenomena ini bersifat multifacet dan sangat kompleks
karena melibatkan kekuasaan akademisi, eksistensi, kapling ekonomi-
5
yang ada di dalamnya di mana saya sebagai akademisi sekaligus
terlibat. Salah satu kiat yang bisa ditawarkan adalah beyond sociology,
yaitu dengan cara pergi melintasi disiplin Sosiologi yang selama ini
saya imani sebagai pisau yang mujarab, untuk kemudian meminjam
alat-alat kerja ilmu-ilmu sosial atau humaniora yang lainnya agar
masalah banalitas di kampus bisa terbongkar secara kritis agar
terwujud perubahan radikal yang emansipatoris. Maka, tidak ada cara
lain kecuali menyerahkan diri pada ideologi kritik yang menjelma ke
dalam teori-teori kritik sosial. Maksudnya adalah teori-teori sosial
yang ditujukan untuk melakukan kritik dan perubahan sosial, di mana
hal ini berbeda secara diametral dengan teori tradisional yang
diarahkan hanya untuk menjelaskan dan memahami fenomena sosial
(Horkheimer, 1992). Konsekuensinya, pembagian kerja pengetahuan
dengan metodologinya yang selama ini diyakini oleh kaum Neo-
Kantian —yaitu ilmu sosial dan humaniora— tidak cukup lagi atau
dengan menggunakan istilah Giddens akan mrucut apabila digunakan
untuk membahas tema ini. Habermas (1971) dengan jitu
mengelaborasi bahwa pengetahuan kritis memiliki kepentingan
emansipatoris, yaitu mengkritisi untuk merubah keadaan, sementara
pengetahuan empiris-analitis (science) hanya memiliki kepentingan
teknis dan historis-hermeneutik (humanities) sekedar berkepentingan
praktis (memahami).
Rumitnya, teori kritik sosial tidak berperspektif tunggal. Faham
kritis dari modernisme merasa puas dengan teori kritik yang cukup
membongkar dan melakukan perubahan emansipatoris, sementara
postmodernisme melihat kepentingan dan hasrat kuasa akademisi
dalam setiap produksi pengetahuan (riset) —termasuk membongkar
fenomena banalitas —_intelektual— _—potensial = menghasilkan
ketidakstabilan makna dan krisis representasi karena menolak adanya
objektivitas (logosentrisme). Jadi, pembongkaran banalitas intelektual
di perguruan tinggi dengan dalih emansipatoris bisa juga dicurigai
sebagai ekspresi hasrat kuasa dan politisasi akademik untuk menjaga
kapling pikiran kritis dalam upaya meneguhkan realitas homo
academicus (Bourdieu, 1990). Maka adalah wajar mencurigai makna
dan kepentingan kuasa di balik tema pidato ini, atau paling tidak,
saling mencurigai di antara sudut pandang tersebut adalah positif
karena akan berakhir dengan itikat baik open ended.
Para hadirin yang saya cintai,
Setelah empat belas tahun kejatuhan rezim otoriter Orde Baru,
dunia pendidikan tinggi berbenah namun masih terlilit oleh sejumlah
persoalan. Masalah-masalah itu meliputi membengkaknya biaya
pendidikan tinggi, cengkeraman kuasa pemerintah atas sumber-
sumber daya pendidikan dan penelitian, kualitas pendidikan yang
kurang memenuhi kualitas, mutu dan karya penelitian masih minim,
ketiadaan budaya dan rendahnya etos kerja akademik, dil. Meskipun
saya tidak terlalu yakin dengan publikasi QS World University
Ranking 2010, dimana posisi UGM pada ranking 321, namun bisa jadi
posisi itu sebagai akibat dari persoalan-persoalan yang belum
terpecahkan tersebut. Maka persoalan itu menjadi tersangka sebagai
kausalitas munculnya fenomena banalitas intelektual di kampus.
Secara sederhana banalitas intelektual di universitas ditandai
dengan pendangkalan yang tidak disadari (Arendt, 1992) disestai
menurunnya kualitas akademik dan sekaligus merosotnya komitmen
terhadap bidang ilmu yang digeluti oleh para akademisi. Kualitas
akademik merujuk pada tingkat penguasaan ilmu yang menyediakan
peralatan-peralatan kerja akademik, sedang kualitas intelektual
merujuk pada komitmen akademisi terhadap ilmu sebagai bidang
pengabdian (Kleden, 1987: 112). Dengan demikian, fenomena
banalitas intelektual tersebut telah mengingkari fungsi normatif
perguruan tinggi yang ada dalam semboyan universitas magistrorum
et scholarium. Artinya, universitas bukan semata-mata merujuk pada
gedung-gedung yang megah yang berdiri di atas tanah berhektar-
hektar, yang memiliki sistem administrasi dan birokrasi canggih dan
didukung oleh peralatan teknologi komunikasi canggih tetapi juga
merujuk pada organisasi manusia yang memiliki aktivitas akademik.
Universitas merupakan tempat bertemunya para sarjana dalam
rangka mencari kebenaran akademik melalui berbagai bentuk riset dan
sekaligus sebagai tempat untuk mengembangkan kapasitas diri
melalui disiplin yang diyakini oleh masing-masing insan akademik.
Unirsis juga sebagai lembaga di mana para sarjana berkewajiban
mengajar para mahasiswa, saling bertukar ide melalui debat, diskusi,
seminar, polemik, dan publikasi sebagai konsekuensi dari hasil
penelitian yang dilakukan. Pengertian tempat bukan hanya merujuk
7
pada arti kata benda, tetapi lebih merupakan institusi di mana lembaga
universitas menjadi meeting of minds para akademisi. Jadi, universitas
bukan hanya merujuk pada tempat dalam arti fisik yang terikat oleh
dimensi ruang dan waktu, namun tempat bertemunya perbedaan
maupun persamaan ide dalam upaya mencari kebenaran ilmiah.
Tronisnya, banalitas intelektual merupakan fenomena yang
merebak dan mengingkari dunia pendidikan tinggi kita saat ini.
Karena luasnya pengertian intelektual (Nikita, 2010) maka dalam
konteks ini dibatasi pada lingkup intelektual kampus yang aktivitasnya
di perguruan tinggi. Beberapa indikator maraknya banalitas intelektual
dapat diungkap. Pertama, adalah apa yang dikenal sebagai gejala
menguatnya pengkhianatan intelektual (Benda, 2007) di kampus yang
menjelma dalam bentuk pengkhianatan akademik. Para akademisi
lebih mementingkan nilai pragmatis daripada nilai-nilai_ ilmu
pengetahuan. Aktivitas pengajaran dan penelitian yang orientasinya
meningkatkan pendapatan, atau yang populer dikenal sebagai
“proyek”, terasa lebih menonjol daripada kegiatan pengembangan
ilmu pengetahuan. Tugas utama akademisi yang seharusnya
melakukan refleksi kritis dan mempertahankan nilai-nilai abstrak pada
setiap jamannya seperti kebenaran, keadilan, dan rasio, justru terasa
semakin memudar karena lebih mengejar kepentingan-kepentingan
pragmatis. Maka tidak mengherankan jika muncul istilah “dosen
asongan’”, yaitu dosen yang kerja di luar kampus dan menjadikan kerja
kampus justru sebagai sambilan.
Misalnya, seorang dosen memiliki pekerjaan lain di luar kota
sehingga tidak punya cukup waktu lagi beraktivitas di kampus.
Macam-macam atribut dan profesi yang disandang oleh akademisi tipe
“asongan” ini misalnya menjadi staf ahli, staf khusus, konsultan,
direktur, deputi, konsultan lembaga donor internasional, dll. Tugas
utama mereka bukan menjadi intelektual kampus tetapi menggunakan
alat-alat akademik untuk kepentingan-kepentingan ekonomi politik
mereka. Intelektual tipe ini cenderung bukan memberikan eksplanasi
kritis- reflektif tetapi justru membela mati-matian secara defensif
pihak yang memberinya posisi. Contohnya, saya pernah menjadi
konsultan pembangunan baik di pemerintahan, lembaga donor
internasional maupun konsultan CSR untuk sebuah perusahaan
maupun dalam membuat rekomendasi yang saya formulasikan
terutama bila dikaitkan dengan persoalan yang sedang dialami rakyat.
Saya menjadi tidak bisa membela penuh kepentingan rakyat.
Kedua, dalam waktu sepuluh tahun terakhir, mengikuti
maraknya industri media televisi, timbul gejala intelektual kampus
yang sering muncul di TV, saya istilahkan sebagai intelektual pamer
(intellectual of the spectacle). Para intelektual ini umumnya diundang
oleh televisi sebagai narasumber untuk acara talk show, wawancara
langsung, atau sekadar obrolan ringan persoalan sosial, politik, budaya
atau ekonomi yang sedang populer. Mereka dengan instant diberi
atribut sebagai ‘pakar’ oleh televisi, bukan karena prestasi_ hasil
penelitian yang berbobot, tetapi semata-mata karena faktor
penampilan dan pencitraan lewat pamer pengetahuan di TV secara
rutin. Inilah fenomena yang oleh DeBord (1995) dikatakan sebagai
kualitas kehidupan yang dimiskinkan oleh lack of authenticity, dan
pemikiran kritis dihalangi karena semua telah terbius oleh masyarakat
pameran (spectacular society). Itu bisa terjadi karena terbenamnya
keberadaan (being) ke dalam kepemilikan (having) dan kepemilikan
ke dalam penampilan (appearing). Celakanya, akademisi ikut terbius
oleh hasrat untuk tampil, naik panggung, unjuk diri bahkan kehendak
narsistik di televisi yang memang gemar mengeksploitasi apa saja
menjadi sekedar komoditas tontonan sebagai realisasi hasrat ekonomi
politik. Maka, lahirlah intelektual instant dengan sebutan ahli atau
pakar yang merupakan produk dari dunia ci-luk-ba (Peek-a-Boo
World) bikinan televisi (Postman, 1986).
Artinya, kemampuan televisi dalam mengkonstruksikan atribut
atau citra kepakaran seorang akademisi secara instan didukung oleh
kemajuan teknologi informasi yang mementingkan kecepatan dengan
menenggelamkan ruang dan jarak, kemudian menghasilkan ruang
kecepatan (dromospheric space). Akibatnya, seolah-olah ruang
menyatu dengan dimensi transmisi (Virilio, 1986). Ruang dan waktu
melebur schingga peristiwa yang terjadi di belahan bumi manapun
dapat ditayangkan kapan pun dan dapat segera diketahui oleh pemirsa
di manapun. Contohnya, dahulu ketika saya punya job sebagai
konsultan di sebuah departemen di Jakarta, yang memaksa saya sering
tinggal di sana, saya sering diwawancarai oleh televisi nasional
sanntar macalah masolah casia fi tite enlls daw ftteuanalon soon
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- UntitledDocument314 pagesUntitledAgung Kresna BayuNo ratings yet
- KRITERIA PENENTUAN DESA MANDIRI BUDAYA (Multi Dimensi)Document19 pagesKRITERIA PENENTUAN DESA MANDIRI BUDAYA (Multi Dimensi)Agung Kresna BayuNo ratings yet
- ID Masyarakat Adat Versus Korporasi KonflikDocument20 pagesID Masyarakat Adat Versus Korporasi KonflikAgung Kresna BayuNo ratings yet
- Executive Summary Naskah Kuno Kadipaten PakualamanDocument24 pagesExecutive Summary Naskah Kuno Kadipaten PakualamanAgung Kresna BayuNo ratings yet
- Materi Tot - Padi Umkm b2cDocument19 pagesMateri Tot - Padi Umkm b2cAgung Kresna BayuNo ratings yet
- RENSTRA Marves 2020 2024 FINAL31 AgustusDocument61 pagesRENSTRA Marves 2020 2024 FINAL31 AgustusAgung Kresna BayuNo ratings yet