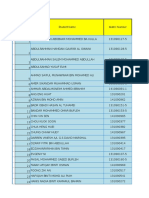Professional Documents
Culture Documents
5247 ArticleText 19249 1 10 20220131 PDF
5247 ArticleText 19249 1 10 20220131 PDF
Uploaded by
Ilham RabbaniOriginal Description:
Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
5247 ArticleText 19249 1 10 20220131 PDF
5247 ArticleText 19249 1 10 20220131 PDF
Uploaded by
Ilham RabbaniCopyright:
Available Formats
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.
net/publication/358246847
IDENTITAS TOKOH PRIBUMI DALAM CERPEN "PENUNJUK JALAN" KARYA
IKSAKA BANU: KAJIAN PASCAKOLONIAL HOMI K. BHABHA
Article · January 2022
DOI: 10.12928/mms.v3i1.5247
CITATIONS READS
0 168
2 authors, including:
Ilham Rabbani
Universitas Gadjah Mada
12 PUBLICATIONS 1 CITATION
SEE PROFILE
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
Feminisme View project
Kajian Sastra Jepang View project
All content following this page was uploaded by Ilham Rabbani on 31 January 2022.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
MIMESIS
VOL. 3. No. 1, Januari 2022
IDENTITAS TOKOH PRIBUMI DALAM CERPEN PENUNJUK JALAN
KARYA IKSAKA BANU: KAJIAN PASCAKOLONIAL HOMI K. BHABHA
Risen Dhawuh Abdullah
Alumni Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi,
Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Ringroad Selatan, Tamanan, Bantul
risen1700025044@webmail.uad.ac.id
Ilham Rabbani
Magister Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada,
Jl. Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta
ilhamrabbani@mail.ugm.ac.id
ARTICLE INFO ABSTRACT
This study aims to uncover an Indigenous character named Oentoeng in the short story “Penunjuk
Jalan”. The short story is one of Iksaka Banu's works contained in the book Semua untuk Hindia. The
Article history
identity of the character that is trying to be dismantled includes hybridity, mimicry, and ambivalence.
Received 30 November 2021 The theory used in this study is the postcolonial theory initiated by Homi K. Bhabha. The study used a
Revised 29 January 2022 qualitative descriptive method. There are three findings in this study. First, the identity of Oentoeng is
Accepted 29 January 2022 a hybrid. Oentoeng absorbs Western values continuously, namely from his upbringing, education, and
his association in the Dutch family environment. Second, mimicry as mockery by the character can be
seen from three aspects, specifically the ability to speak Dutch, possess Western medical knowledge,
and to be able to devise a strategy of rebellion that made the VOC troubles as invaders. Third,
Keywords Oentoeng's attitude of wanting to be angry and willing to provide assistance, treatment, and
Identity entertainment to the Dutch doctor and his porter who had an accident could be interpreted as a form of
Iksaka Banu ambivalence in the Indigenous character.
Hybridity
Mimicry
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Ambivalence
Postcolonial
Bhabha
INFO ARTIKEL ABSTRAK
Penelitian ini bermaksud membongkar identitas seorang tokoh Pribumi bernama Oentoeng dalam
Article history cerpen “Penunjuk Jalan”. Cerpen tersebut merupakan salah satu karya Iksaka Banu yang termaktub
dalam buku Semua untuk Hindia. Identitas tokoh yang berusaha dibongkar meliputi hibriditas,
Received 30 November 2021 mimikri, dan ambivalensi. Teori yang digunakan ialah teori pascakolonial yang dikembangkan oleh
Revised 29 Januari 2022 Homi K. Bhabha. Metode yang dipilih adalah metode kualitatif-deskriptif. Adapun temuan dari
Accepted 29 Januari 2022 penelitian ini: pertama, identitas tokoh Oentoeng berada pada posisi hibrid karena menyerap nilai-nilai
Barat secara berkontinuitas, yakni dari asuhan, didikan, dan pergaulannya di lingkungan keluarga
Belanda; kedua, mimicry as mockery yang dilakukan tokoh tersebut dapat dilihat berdasarkan tiga
aspek, yakni kemampuan berbahasa Belanda, memiliki pengetahuan medis ala Barat, dan mampu
Keywords merancang strategi pemberontakan yang membuat kerepotan VOC selaku penjajah; dan ketiga, sikap
Identitas Oentoeng yang membenci penjajah namun sekaligus berkenan memberi pertolongan, pengobatan, dan
Iksaka Banu perjamuan kepada dokter Belanda beserta portirnya yang mengalami kecelakaan, dapat dimaknai
Hibriditas sebagai bentuk ambivalensi pada diri sang tokoh Pribumi.
Mimikri
Ambivalensi
Pascakolonial This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Bhabha
VOL. 3. No. 1, Januari 2022 hlm. 10-23 10
MIMESIS
VOL. 3. No. 1, Januari 2022
PENDAHULUAN
Kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda ke
Nusantara semenjak abad XVI, tidak pelak telah menimbulkan pertemuan dua kebudayaan
besar: Timur dan Barat. Negara yang kini dikenal sebagai Indonesia pun, tanpa terkecuali,
telah bersentuhan dengan keempat negara tersebut. Rempah-rempah menjadi daya magnet
yang menarik keempatnya untuk datang. Dapat dikatakan bahwa pendudukan Malaka pada
tahun 1511 M oleh Portugis, di bawah komando Albuquerque, menandai dimulainya usaha
pendirian kerajaan kolonial besar di Asia Tenggara oleh bangsa-bangsa Eropa tersebut
(Stroomberg, 2018: 45).
Hampir seluruh wilayah kepulauan Nusantara dikuasai oleh keempatnya, dan Jawa,
termasuk di dalamnya. Sebelumnya, Pulau Jawa pun telah terbagi-bagi berdasarkan daerah
kekuasaan beberapa kerajaan besar. Dengan demikian, peradaban atau kebudayaan di pulau
tersebut, dapat dikatakan telah mapan. Kedatangan bangsa Eropa, yang diwakili empat
negara di atas, sebagai “pembawa” kebudayaan Barat, meniscayakan pertemuan kebudayaan
dengan Timur yang diwakili oleh kerajaan-kerajaan di Jawa secara khusus. Dengan demikian,
dimulailah “kelahiran” manusia-manusia hibrid di dalamnya.
Setelah suksesnya pendirian “kerajaan kolonial besar”, atau yang secara sederhana
dapat disebut sebagai fenomena penjajahan, dimulailah pula proses hegemoni kultural, yakni
pengaruh dan penguasaan—yang tertanam dengan sangat dalam—para pihak Barat selaku
penjajah atas pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku masyarakat Pribumi sebagai pihak yang-
terjajah (Ratna dalam Turama, 2017). Kondisi tersebut dapat terus berlangsung, bahkan
ketika sang penjajah telah melepaskan kekuasaannya atas wilayah geografis tersebut (Faruk,
2007: 16). Lebih jauh, efek yang tercipta ialah bersemayamnya inferioritas dalam diri
masyarakat terjajah akibat hilangnya orisinalitas dan budaya lokal mereka (Loomba dalam
Fajar, 2011).
Hal-hal demikian kemudian tercatat, dan menjadi dokumen sejarah. Peran para
sejarawan dalam hal ini tidak dapat diabaikan. Akan tetapi, selain sejarawan, para pengarang
juga tidak kurang berandil. Mereka menyajikan peristiwa-peristiwa sejarah dengan lebih
“fleksibel” dibandingkan catatan para sejarawan yang terkesan kaku dan sarat data tersebut.
Sudah jelas, bahwa fenomena yang terjadi, takkan lepas dari pengamatan para pengarang,
sebab fenomena dalam masyarakat menjadi bahan penggarapan karya yang strategis.
Objek karya sastra adalah realitas–apa pun juga yang dimaksud dengan realitas oleh
pengarang (Kuntowijoyo, 2006: 171). Secara mengerucut, sejarah juga merupakan realitas.
Mengutip pendapat (Kuntowijoyo, 2006: 171), bahwa apabila realitas itu berupa peristiwa
sejarah, maka karya sastra dapat: pertama, mencoba menerjemahkan peristiwa itu dalam
bahasa imajiner dengan maksud untuk memahami peristiwa sejarah menurut kadar
kemampuan pengarang; kedua, karya sastra dapat menjadi sarana bagi pengarangnya untuk
menyampaikan pikiran, perasaan, dan tanggapan mengenai suatu peristiwa sejarah; dan
ketiga, seperti juga karya sejarah, karya sastra dapat merupakan penciptaan kembali sebuah
peristiwa sejarah sesuai dengan pengetahuan dan daya imajinasi pengarang.
VOL. 3. No. 1, Januari 2022 hlm. 10-23 11
MIMESIS
VOL. 3. No. 1, Januari 2022
Pengarang yang mencatat peristiwa tersebut, dapat saja yang bersentuhan secara
langsung dengan peristiwa kolonial, seperti misalnya Marah Roesli, Abdoel Moeis, Sutan
Takdir Alisjahbana, dan lain-lain. Ada juga pengarang yang lahir dan bersentuhan hanya
lewat catatan-catatan sejarah mengenai kolonialisme, seperti halnya Iksaka Banu. Nama
Banu bukan lagi nama asing dalam kancah kesusastraan Indonesia mutakhir. Ia adalah
penulis ternama di Indonesia, dengan sederet prestasi mentereng di bidang sastra. Sebut saja
dua di antaranya: Pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa edisi 2014 untuk kumpulan cerpen
Semua untuk Hindia (2014) dan edisi 2019 untuk kumpulan cerpen Teh dan Pengkhianat
(2019).
Kedua karya tersebut adalah bukti konsistensi Banu menggarap karya-karya bertema
kolonialisme. Selain Semua untuk Hindia dan Teh dan Pengkhianat, satu lagi karyanya yang
juga berlatar masa kolonial ialah novel Sang Raja (2017). Heryanto (2015) menyoroti
sekaligus merangkum kecenderungan para pengulas karya Banu—khususnya Semua untuk
Hindia—yang memandang fenomena perwatakan karakter dalam prosanya sebagai suatu
keganjilan. Pandangan ganjil dari para pengamat tersebut, salah satunya mengisyaratkan
adanya pikiran bahwa pihak penjajah atau Belanda tidak sepatutnya bersinggungan dengan
sisi-sisi humanisme. Karya-karya Banu lahir untuk mematahkan hal tersebut. Ia memilih
meletakkan tokoh-tokoh sentral ciptaannya, yang dominan merupakan tokoh berdarah
Belanda, berada dalam lingkaran protagonis. Akan tetapi, salah satu cerpen yang termaktub
dalam Semua untuk Hindia, justru memberikan porsi atau ruang hampir sama bagi eksplorasi
tokoh dari Belanda dan Pribumi itu sendiri. Cerpen tersebut berjudul “Penunjuk Jalan”
(2007), yang berkisah tentang kebaikan tokoh Pribumi bernama Oentoeng—lengkapnya
adalah Untung Surapati—kepada seorang dokter dan portir yang mengalami kecelakaan
dalam perjalanan.
Bagi peneliti, eksplorasi lebih terhadap tokoh Pribumi yang dilakukan Banu dalam
karyanya merupakan hal yang menarik dan patut dikaji lebih jauh. Oleh sebab itu, dalam
penelitian ini, cerpen “Penunjuk Jalan” dalam kumpulan cerpen Semua untuk Hindia tersebut
akan coba dianalisis menggunakan teori pascakolonial yang dikembangkan oleh Homi K.
Bhabha, guna berfokus melihat identitas tokoh Pribumi bernama Oentoeng yang diciptakan
oleh Banu dalam karyanya.
Dalam cerpen “Penunjuk Jalan”, tokoh Oentoeng dapat disebut sebagai tokoh sentral
selain sang dokter Belanda (Jorijs Handlanger) yang sekaligus menjadi narator cerita (tokoh-
Aku). Alasan lain pemilihan tokoh Oentoeng adalah posisinya yang strategis: berada dalam
semacam ketegangan antara latar belakang (berdarah Pribumi namun dididik Belanda) dan
sosoknya sebagai penentang pihak Kompeni yang gigih saat itu. Dibandingkan tokoh lain
dalam cerpen, Oentoeng juga merupakan tokoh yang paling kuat merepresentasikan hibriditas
dan ambivalensi. Mimicry as mockery juga ia lakukan dalam cerpen tersebut. Oleh karena itu,
pertanyaan yang kemudian berusaha dijawab oleh penelitian ini adalah, “Bagaimana bentuk
hibriditas, mimikri, dan ambivalensi tokoh Oentoeng dalam cerpen ‘Penunjuk Jalan’ karya
Iksaka Banu?” Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
membongkar bentuk-bentuk hibriditas, mimikri, dan ambivalensi tokoh Oentoeng dalam
cerpen terkait.
VOL. 3. No. 1, Januari 2022 hlm. 10-23 12
MIMESIS
VOL. 3. No. 1, Januari 2022
Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara
lain yang ditulis oleh Khuzaini (2018), Suweleh (2020), dan Fiaji, Fitrahayunitisna, dan
Wulandari (2020). Pertama, dalam penelitiannya, Khuzaini (2018) berusaha mendeskripsikan
kepribadian dan bentuk aktualisasi diri tokoh-tokoh utama dalam kumpulan cerpen Semua
untuk Hindia. Teori yang digunakan ialah psikologi humanistik atau aktualisasi diri Abraham
Maslow. Letak perbedaan antara penelitian Khuzaini dengan penelitian ini ialah objek
formalnya. Khuzaini menggunakan perspektif psikologi sastra Maslow, sementara penelitian
ini menggunakan perspektif pascakolonial Bhabha.
Kedua, penelitian Suweleh (2020) berfokus pada pengungkapan bentuk-bentuk
keterbelahan tokoh-tokoh nativephilia dalam empat cerpen—“Selamat Tinggal Hindia”,
“Racun untuk Tuan”, “Semua untuk Hindia”, dan “Penunjuk Jalan”—yang termaktub di
dalam antologi Semua untuk Hindia, menggunakan konsep split yang ditawarkan oleh
Bhabha. Konsep tersebut mengindikasikan bahwa keterbelahan tidak hanya dialami oleh
pihak terjajah, melainkan juga pihak penjajah. Terdapat kesamaan objek material dan
perspektif pascakolonial yang digunakan oleh Suweleh dan peneliti, hanya saja perbedaannya
terdapat pada konsep yang dieksplorasi. Suweleh mengeksplorasi konsep split, sementara
penelitian ini berfokus pada hibriditas, mimikri, dan ambivalensi.
Terakhir, penelitian Fiaji, Fitrahayunitisna, dan Wulandari (2020) berupaya
membahas nilai-nilai nasionalisme yang meliputi nasionalisme religius, nasionalisme
kemanusiaan, nasionalisme berkerakyatan, dan nasionalisme berkeadilan dalam kumpulan
cerpen Semua untuk Hindia menggunakan teori pascakolonial dengan menitikberatikan
resistansi akan inferioritas kaum terjajah. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan
penelitian ini ialah perspektif pascakolonial yang digunakan: Fiaji, Fitrahayunitisna, dan
Wulandari berfokus pada resistansi kaum terjajah, sementara peneliti berfokus pada identitas
tokoh.
METODE
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Moleong (2018: 6)
menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami
fenomena tentang hal yang dialami subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Di dalam penelitian kualitatif, peneliti berposisi
sebagai instrumen kunci.
Mengabstraksi pendapat Faruk (2017: 22–26), penelitian ini memiliki langkah-
langkah sebagai berikut. Pertama, penentuan objek material dan objek formal. Objek material
dalam penelitian ini adalah cerpen “Penunjuk Jalan” (2007) yang termuat dalam buku
kumpulan cerpen Semua untuk Hindia (2014) karya Iksaka Banu, dan diterbitkan oleh
Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Sementara itu, objek formalnya ialah
identitas tokoh yang meliputi hibriditas, mimikri, dan ambivalensi berdasarkan perspektif
pascakolonial Bhabha. Kedua, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang
berfungsi menemukan data-data dalam cerpen “Penunjuk Jalan” sebagai sumber data atau
VOL. 3. No. 1, Januari 2022 hlm. 10-23 13
MIMESIS
VOL. 3. No. 1, Januari 2022
data primer, serta teks-teks sekunder yang berkaitan dengan tokoh Pribumi bernama
Oentoeng (Untung Surapati) dalam penelitian. Teknik yang dipergunakan adalah teknik
simak-catat. Ketiga, analisis data dilakukan dengan teknik content analysis, yaitu peneliti
melakukan pemaknaan terhadap data atau teks-teks yang telah diklasifikasikan dengan
kerangka teori pascakolonial yang dikembangkan oleh Bhabha.
Bagian analisis data atau pembahasan akan dibagi ke dalam empat sub: 1) analisis
hibriditas yang terjadi dalam diri tokoh Oentoeng serta ideologi tokoh-Aku (Jorijs) sebagai
representasi dari ideologi penguasa (penjajah), yang selanjutnya memicu timbulnya mimikri
dari tokoh Oentoneng—analisis ideologi sejatinya merupakan bagian dari analisis hibriditas,
namun dispesifikkan dalam bab tersendiri guna memperjelas posisi dari masing-masing tokoh
(Jorijs dan Oentoeng); 2) analisis mimicry as mockery yang dilakukan tokoh Oentoeng
sebagai efek dari kondisi hibrid-nya, serta sebagai wujud resistansi yang dilakukan terhadap
ideologi dan kebijakan-kebijakan pihak penjajah; dan 3) analisis kondisi ambivalen yang
dialami oleh Oentoeng selaku tokoh Pribumi.
PEMBAHASAN
Seperti telah disinggung pada bagian Pendahuluan, penelitian ini menggunakan teori
pascakolonial yang dikembangkan oleh Bhabha sebagai pisau analisisnya. Berikut ini
merupakan hasil analisis terhadap cerpen “Penunjuk Jalan”—yang difokuskan pada tokoh
Pribumi bernama Oentoeng—dengan menggunakan perspektif tersebut.
Hibriditas Tokoh Oentoeng dan Pandangan Tokoh Jorijs sebagai Representasi dari
Ideologi Penguasa
Hibriditas merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Bhabha dalam pemikiran
pascakolonial yang ia kembangkan. Konsep lainnya yang juga ia perkenalkan dalam
karyanya yang berjudul The Location of Culture adalah mimikri, dan ambivalensi. Menurut
Setiawan (2018: 19), penggunaan istilah analogis tersebut merupakan cara Bhabha
menggambarkan bangsa terjajah yang memanipulasi ketakberdayaan mereka menjadi
kekuatan resistansi terhadap penjajah.
Hibriditas ialah istilah yang dipakai untuk mengacu pada interaksi antara bentuk-
bentuk budaya yang berbeda, yang dapat menghasilkan pembentukan budaya dan identitas
baru dengan sejarah dan perwujudan tekstual sendiri (Day dan Foulcher, 2008: 12). Akan
tetapi, dalam kajian pascakolonial, hibriditas mengacu pada pertukaran silang budaya.
Hibriditas tidak hanya mengarahkan perhatian pada produk-produk paduan budaya itu
sendiri, tetapi lebih kepada cara produk-produk budaya tersebut dan penempatannya dalam
ruang sosial dan historis di bawah kolonialisme, menjadi bagian dari pemaksaan penolakan
hubungan kekuasaan kolonial (Day dan Foulcher, 2008: 13).
Tokoh Oentoeng sebagai orang berdarah Pribumi, selain karena pertemuan dua
kebudayaan besar (Barat dan Timur) secara meluas karena kolonialisme di Nusantara, juga
mengalami penyerapan nilai-nilai Barat secara khusus lewat tokoh bernama Cnoll dan Moor.
Oentoeng pernah tinggal dan dididik di lingkungan keluarga Belanda, tepatnya dalam
VOL. 3. No. 1, Januari 2022 hlm. 10-23 14
MIMESIS
VOL. 3. No. 1, Januari 2022
lingkungan Keluarga Cnoll (yang kemudian beralih ke Edeleer Moor), kendati tidak
dijelaskannya secara eksplisit dan panjang lebar kepada tokoh-Aku saat pertemuan pertama
mereka dalam cerpen. Pertemuan kedua tokoh terjadi dalam perjalanan, ketika sang dokter
Belanda mengalami kecelakaan dan membutuhkan pertolongan medis bagi dirinya dan sang
portir:
“Aku pernah tinggal bersama keluarga Belanda yang kerap berurusan dengan chirurgijnen.
Aku tahu benar pekerjaanmu, Tuan Dokter,” ujarnya dalam bahasa Belanda. Ya, Belanda!
(hlm. 120)
…
“Tuan!” Sang Pangeran menggeleng. “Kuhabiskan masa kecilku di Batavia. Aku melihat
semuanya. Kurasa penduduk di sana pun melihat, bahwa sejak direbut Kompeni enam puluh
tahun silam, kota itu menjelma menjadi kota terkutuk. …” (Banu, 2014: 123)
Hibriditas tokoh Oentong yang diperoleh dari pergaulannya dalam lingkungan
keluarga Belanda, dalam cerpen “Penunjuk Jalan” diungkapkan lagi menjelang ending cerita,
yakni ketika sang dokter memperhatikan sebuah lukisan karya Jacob Jansz Coeman (seorang
pelukis ternama Hindia) yang terpampang di dinding ruangan Asisten Sekretaris Dewan
Hindia bernama Vuijborn. Keberadaan sosok Oentoeng atau Pangeran (panggilan lainnya
dalam cerpen) dalam lukisan membuat tokoh-Aku terheran. Vuijborn menjelaskan kepada
tokoh dokter Belanda perihal lukisan tersebut:
“Perkenalkan: Keluarga Cnoll, dilukis oleh Jacob Jansz Coeman, pelukis termahal Hindia,”
Vuijborn memegang bingkai lukisan. “Yang bergaun hitam itu Cornelia.”
Kuamati lebih dekat. Mendadak aku tersentak. Di sana, di belakang Cornelia. Dilukis dalam
nuansa hijau kecokelatan. Seorang pemuda berambut panjang memanggul payung militer di
bahu kanan, sementara tangan kirinya dengan jenaka mengutil jeruk yang dibawa seorang
budak wanita.
“Mijn God! Tak salah! Aku nyaris histeris. Sang Pangeran.” (Banu, 2014: 127–28)
Relasi antaranggota keluarga, kendati hanya terjadi dalam konteks pemungutan dari
yang menjajah kepada yang terjajah, tetap dapat dipandang sebagai hubungan fundamental
tempat terjadinya transfer nilai-nilai kehidupan. Dibesarkan dalam keluarga Belanda,
membuat identitas Oentoeng berada pada posisi hibrid karena menyerap nilai-nilai Barat
secara berkontinuitas.
Pernyataan sang tokoh bahwa dirinya menghabiskan masa kecil di Batavia dan
“pernah melihat semuanya”, mengindikasikan bahwa dirinya menyerap berbagai hal, mulai
dari pandangan, tata krama, gaya hidup, dan hal-hal lain yang bernuansa Eropa. Situasi yang
dialami Oentoeng, setidaknya dapat dijadikan sebagai contoh kasus dari pernyataan Young
(2003: 79), bahwa hibriditas melibatkan proses interaksi yang menciptakan ruang sosial baru,
di mana makna baru diberikan, serta memungkinkan artikulasi pengalaman perubahan dalam
masyarakat yang terpecah oleh modernitas, dan mereka memfasilitasi tuntutan konsekuensi
untuk transformasi sosial. Dengan demikian, menjadi hal yang wajar apabila sang tokoh
berdarah Pribumi digambarkan memiliki wawasan luas dalam cerpen “Penunjuk Jalan”.
VOL. 3. No. 1, Januari 2022 hlm. 10-23 15
MIMESIS
VOL. 3. No. 1, Januari 2022
Berkaitan dengan kondisi tokoh Oentoeng yang menyerap berbagai hal, mulai dari
pandangan, tata krama, gaya hidup, dan hal-hal lain yang bernuansa Eropa tersebut, dapat
dikatakan bahwa sejatinya ia telah mengalami proses hegemoni oleh ideologi penguasa atau
penjajah (pihak Belanda) pada masa-masa tersebut.1 Keadaan itu pun terus bertahan dalam
dirinya sampai masa ketika terjadinya pertemuan dengan sang tokoh-Aku. Untuk melihat
bagaimana ideologi pihak penguasa bekerja sekaligus ditentang oleh tokoh Oentoeng (dalam
pembahasan mimikri), dapat dilakukan dengan mencermati cara pandang tokoh Jorijs selaku
orang Belanda totok dalam cerpen, baik lewat tuturan-tuturan (dialog) antartokoh maupun
monolog tokoh-Aku selaku narator utama. Cara pandang dan sikap tersebut, kemudian
dicermati kembali pada bagian pembahasan mimicry as mockery, untuk membuktikan bahwa
memang terdapat ideologi penguasa, baik yang ditentang maupun bertahan dalam diri tokoh
terjajah (Oentoeng).
Pertama, tokoh-Aku atau Jorijs sendiri adalah seorang Belanda totok yang diutus oleh
pemerintah Belanda di Eropa untuk membantu mengatasi permasalahan yang sedang
menimpa Batavia, yang artinya ia berada di pihak yang pro atau mendukung penjajahan
mereka atas tanah Hindia Belanda. Posisi pro tersebut ia jelaskan secara gamblang di
hadapan tokoh Oentoeng ketika mereka bercaka-cakap:
Aku baru tiba dari Rotterdam minggu lalu. Dan karena Bandar Sunda Kelapa sedang
diperbaiki, kapalku harus merapat di Banten. Perlu tiga hari perjalanan kereta pos untuk ke
Batavia. Lusa aku harus menghadap Gubernur Jenderal Speelman, membicarakan jabatan
baruku sebagai Ketua Dewan Kesehatan Batavia. (Banu, 2014: 118-119)
Lebih jauh, ia juga menjelaskan bahwa ia diminta langsung oleh Pimpinan Kompeni untuk
meneruskan pekerjaaan dokter resmi pertama di Batavia bernama Jacobus Bontius, sebab saat
itu Batavia sedang didera penyakit perut dan beri-beri parah, sementara mutu para
chirurginjen mereka semakin merosot, dan pendahulu-pendahulu mereka yang lebih terampil
bahkan turut menjadi korban penyakit-penyakit tersebut (Banu, 2014: 122-123).
Ideologi tokoh Oentoeng secara nyata berseberangan dengan yang dilakukan oleh
tokoh-Aku tersebut. Ia menegaskan dan melontarkan pernyataan kepada lawan bicaranya,
bahwa cara hidup orang-orang Belanda yang sama seperti tokoh-Aku, tidak hanya
menimbulkan kerusakan lingkungan dari segi fisik, melainkan juga dari aspek budaya berupa
hegemoni perebutan kekuasaan, gaya hidup tidak sehat, dan sebagainya yang melanda
Kerajaan Mataram (Banu, 2014: 123). Sederhananya, ia menyayangkan keadaan tersebut.
1
Definisi ideologi yang dirujuk dalam konteks ini ialah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas
pendapat (kejadian), yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, atau secara sederhana
merupakan cara pandang dan berpikir seseorang atau suatu golongan tertentu (KBBI Daring, 2021). Cabanis, de
Tracy, dkk. (dalam Althusser, 2007: 185-186) menyebut ideologi sebagai sistem ide-ide dan gambaran-
gambaran yang mendominasi pikiran seseorang atau sebuah kelompok sosial. Menurut Althusser (2007: 167-
168), ideologi sendiri didistribusikan lewat institusi-institusi seperti institusi keagamaan, pendidikan, keluarga,
hukum, politik, serikat buruh, komunikasi (pers, radio, televisi, dll.), dan kebudayaan (kesusastraan, seni,
olahraga, dll.). Baginya, manusia tidak perlu dibebaskan dari ideologi, sebab memiliki sisi baik, yakni sebagai
reaksi terhadap suatu dominasi—setiap penindasan akan menghasilkan usaha-usaha pada pihak tertindas untuk
melepaskan diri.
VOL. 3. No. 1, Januari 2022 hlm. 10-23 16
MIMESIS
VOL. 3. No. 1, Januari 2022
Kedua, sebagai orang Eropa yang dalam konteks penjajahan selalu diposisikan
sebagai yang superior, beradab, cerdas atau berpengetahuan luas, dan sebagainya—sementara
pihak terjajah atau pribumi menjadi oposisi binernya—maka tidak mengherankan ketika di
dalam narasi cerpen, ditemukan cara pandang dari tokoh-Aku yang skeptis, bahkan mengarah
ke sinis, terhadap ketulusan pertolongan yang mereka terima dan pengetahuan dari kelompok
Oentoeng sendiri:
Aku mulai cemas. Seorang kawan pernah berkisah tentang gerombolan penyamun yang
banyak berkeliaran di di hutan Jawa. Mereka gemar merampok dan membantai saudagar
Belanda atau Tionghoa yang kebetulan memintas hutan.
…
Jantungku berdebar. Inikah gerombolan penyamun itu? Belasan penunggang kuda di belakang
kedua orang itu memang cukup mewakili gambaran umum penyamun: Berkumis tebal,
berkulit legam, serta menyimpan kelewang panjang di punggung. (Banu, 2014: 119)
“Aku pernah tinggal bersama keluarga Belanda yang kerap beruruasan dengan chirurgijen.
Aku tahu benar pekerjaanmu, Tuan Dokter,” ujarnya dalam bahasa Belanda. Ya, Belanda!
“Donder er bliksem!” aku melompat mundur. “Betapa fasih. Pujianku untuk Tuan,” lanjutku.
Kali ini sepenuhnya dalam bahasa Belanda. (Banu, 2014: 120)
Pangeran melempar senyum. Kutangkap kembali sorot ganjil lewat tarikan bibir dan matanya,
seperti saat pertama melihatku tadi. Berhati-hatilah dengan bumiputra, kepala mereka penuh
muslihat. Terngiang lagi nasihat temanku. Tapi adakah tawaran yang lebih baik? … Adakah
penyamun fasih berbahasa Belanda? (Banu, 2014: 122)
Kutipan tersebut menunjukkan cara pandang dan berpikir yang khas Orientalisme: mereka
melakukan penilaian budaya serta sejarah bangsa Timur secara otoritatif. Orientalisme
menjadi perspektif pada pengetahuan Barat tentang dunia timur, yang menggambarkan timur
sebagai sesuatu yang secara negatif kontras dengan Barat (putih-hitam, kuat-lemah, beradab-
barbar, pintar-bodoh, dan oposisi biner lainnya), yang notabene keseluruhan dan
kecenderungannya selalu mengarah kepada fungsi untuk merendahkan masyarakat Timur
(Setiawan, 2018: 39).
Kentara dalam konteks cerpen tersebut, bahwa di satu sisi tokoh-Aku
mengidentifikasi dirinya selaku subjek dari Barat yang berpengetahuan dan beradab (dari segi
pilihan dan cara berbahasa, berpenampilan, bersikap, dsb.), sementara di sisi seberangnya
tokoh Oentong dan kelompoknya adalah penyamun barbar yang perlu diwaspadai.
Singkatnya, ada tindakan menggeneralisasi: seluruh orang Timur adalah mereka yang tidak
memahami bahasa masyarakat kelas atas di Hindia Belanda (bahasa Belanda), serta patut
diwaspadai karena di kepala mereka tersimpan berbagai muslihat yang dapat mengancam
subjek-subjek lain yang mereka temui, tidak terkecuali pihak Barat yang memang beroposisi
dengan mereka.
Ketiga, dari aspek medis, tokoh-Aku sebagai seorang dokter dari Eropa secara jelas
digambarkan sebagai penganut paham positivistik-empiris. Cara, proses, dan jenis obat yang
dibutuhkan dalam tindkan medis harus berdasarkan data-data empiris sebagaimana lazimnya
sains dalam pandangan mereka selaku orang-orang Barat. Oleh sebab itulah, ia digambarkan
VOL. 3. No. 1, Januari 2022 hlm. 10-23 17
MIMESIS
VOL. 3. No. 1, Januari 2022
tertantang, bahkan sempat memprotes tindakan medis yang dilakukan Kyai Ebun terhadap
tokoh Joep sebagaimana kutipan berikut.
Dalam bilik, kusaksikan Joep mengelepar seperti ayam disembelih. …
“Apa yang Tuan lakukan? Ia bisa lumpuh, kurenggut tangan si tabib seraya memaki dalam
bahasa Melayu. Kutumpahkan pula amarahku kepada Pangeran. Ia diam, tapi mendadak
jarinya mamatuk bahuku, membuat lenganku gontai.
“Tuan harus percaya kepada Kyai Ebun,” kata Pangeran. “Telah ratusan kali ia melakukan
pengobatan semacam ini. Memang sakit. Tapi lihat hasilnya.”
…
“Orang Belanda mengobati sakit dari luar. Kami membiarkan tubuh menyembuhkannya dari
dalam,” Pangeran berdiri di belakangku dengan dua gelas the panas. Diangsurkannya segelas.
… (Banu, 2014: 124–25)
Mimicry as Mockery dalam Bahasa, Pengetahuan Medis, dan Strategi Perang
Hibriditas subjek memicu timbulnya mimikri. Dijelaskan oleh Bhabha (dalam
Foulcher 2008: 105), bahwa mimikri merupakan reproduksi belang-belang subjektivitas
Eropa di lingkungan kolonial yang sudah tidak murni, yang tergeser dari asal-usulnya, dan
terkonfigurasi ulang dalam cahaya sensibilitas dan kegelisahan khusus kolonialisme.
Sebenarnya, mimikri lebih mendekati olok-olok, dalam artian berupa resistansi dengan
peniruan yang memunculkan kesan olok-olok.
Peniruan yang dilakukan pihak terjajah, dalam hal ini tidak pernah mencapai titik final
atau purna. Dengan kata lain, peniruan mereka merupakan hal buruk, terlebih jika dikaitkan
sebagai alat resistansi. Kita kemudian mengenal istilah “mimicry as mockery”. Tentang hal
ini, (Bhabha, 1994: 123) mengungkapkan bahwa, “The effect of mimicry on the authority of
colonial discourse is profound and disturbing. For in ‘normalizing’ the colonial state or
subject, the dream of post-Enlightenment civility alienates its own language of liberty and
produces another knowledge of its norms,” dan ia lanjutkan pada bagian berikutnya, “it is
from this area between mimicry and mockery, where the reforming, civilizing mission is
threatened by the displacing gaze of its disciplinary double, that my instances of
colonial imitation come.”
Setidaknya, mimikri atau peniruan yang dilakukan oleh tokoh Oentoeng terhadap
pihak penjajah, dapat dilihat berdasarkan tiga aspek: berbahasa, pengetahuan medis, dan
strategi perang. Pertama, tokoh Oentoeng digambarkan sebagai tokoh Pribumi yang fasih
berbicara dalam bahasa Belanda. Adegan tersebut digambarkan pada pertemuan pertama
antara sang dokter dengan Oentoeng juga. Oentoeng kemudian memperkenalkan dirinya, dan
menjelaskan bahwa dirinya pernah hidup di bawah asuhan orang Belanda (sebagaimana
dijelaskan dalam pembahasan hibriditas):
“Aku pernah tinggal bersama keluarga Belanda yang kerap berurusan dengan chirurgijnen.
Aku tahu benar pekerjaanmu, Tuan Dokter,” ujarnya dalam bahasa Belanda. Ya, Belanda!
“Donder en bliksem!” aku melompat mundur. “Betapa fasih. Pujianku untuk Tuan,” lanjutku.
Kali ini sepenuhnya dalam bahasa Belanda.
…
Ya, aku akan selamat. Adakah penyamun fasih berbahasa Belanda? (Banu, 2014: 120)
VOL. 3. No. 1, Januari 2022 hlm. 10-23 18
MIMESIS
VOL. 3. No. 1, Januari 2022
Kedua, meskipun tidak dijelaskan secara tersurat dalam cerpen “Penunjuk Jalan”,
penggambaran tokoh Oentoeng yang memiliki pengetahuan mengenai dunia medis ala Barat
justru dihadirkan berupa paparan mengenai sebab kecarut-marutan masalah kesehatan di
Hindia, khususnya Batavia, serta sangkalan terhadap protes sang dokter Belanda ketika
melihat seorang tabib rombongan Oentoeng beraksi. Artinya, dalam hal ini mimicry sang
tokoh Pribumi terhadap pandangan orang Belanda bergerak ke arah mockery, yakni
keberanian menjelaskan secara objektif penyebab kecarut-marutan dan sangkalan mengenai
proses pengobatan ala orang-orang Eropa. Berikut merupakan kutipan pernyataan pandangan
tokoh Oentoeng:
“Kuhabiskan masa kecilku di Batavia. Aku melihat semuanya. Kurasa penduduk di sana pun
melihat, bahwa sejak direbut Kompeni enam puluh tahun silam, kota itu menjelma menjadi
kota terkutuk. Sungai Ciliwung dicabik menjadi puluhan kanal sehingga arusnya melemah.
Lumpur mengendap di sana-sini, menciptakan dinding-dinding parit yang becek. Kalau
sedang pasang, seisi laut menerjang kota. Saat surut, bangkai ikan serta kotoran manusia
terperangkap di selokan dan parit-parit tadi. Menebarkan udara tak sehat.” (Banu, 2014: 123)
Ia berusaha melihat dan memaparkan secara objektif semua penyebab terjadinya
kekacauan dan masalah kesehatan yang melanda Batavia saat itu, yang notabene berusaha
diatasi si tokoh-Aku. Dengan pengetahuan tersebut pula, ia menyerang secara lisan pihak
Belanda (yang diwakili si tokoh-Aku) yang ia anggap sebagai biang keladi dari berbagai
permasalahan Batavia. Seperti diketahui, pemandangan itu diperoleh Oentoeng ketika masih
berada di bawah asuhan orang Belanda. Pemandangan yang dianggap lazim oleh pihak
Belanda karena alasan proyek kolonial tersebut, pada mulanya dianggap lazim juga oleh
Oentoeng selaku sosok Pribumi. Akan tetapi, karena tumbuhnya kesadaran, pandangannya
tersebut pun bergeser terhadap pembelaan Pribumi dan kondisi alam mereka yang dirusak
oleh pihak penjajah.
Dalam konteks pengobatan medis, sangkalan dalam kutipan berikut juga dapat
dimaknai sebagai mockery tokoh Oentoeng kepada sang dokter Belanda beserta pandangan
medis orang-orang Eropa:
… Seorang lelaki tua sigap mengompres dahinya dengan dedaunan yang ditumbuk halus.
Agaknya ia seorang tabib. Aku sungguh merasa tertantang. Namun ajakan pangeran untuk
berkumpul di bilik depan mengurungkan niatku meyaksikan si tabib beraksi.
…
Dalam bilik, kusaksikan Joep mengelepar seperti ayam disembelih. …
“Apa yang Tuan lakukan? Ia bisa lumpuh, kurenggut tangan si tabib seraya memaki dalam
bahasa Melayu. Kutumpahkan pula amarahku kepada Pangeran. Ia diam, tapi mendadak
jarinya mamatuk bahuku, membuat lenganku gontai.
…
“Orang Belanda mengobati sakit dari luar. Kami membiarkan tubuh menyembuhkannya dari
dalam,” Pangeran berdiri di belakangku dengan dua gelas the panas. Diangsurkannya segelas.
… (Banu, 2014: 124–25)
VOL. 3. No. 1, Januari 2022 hlm. 10-23 19
MIMESIS
VOL. 3. No. 1, Januari 2022
Sangkalan tersebut membuktikan adanya pemahaman metode pengobatan yang digunakan
oleh orang-orang Barat, yang notabene dianggap tidak lebih efektif dari cara orang-orang
Timur (Pribumi) “merangsang” kinerja tubuh dalam memperbaiki dirinya sendiri.
Pemahaman mengenai dunia medis ala Barat oleh Oentoeng, dapat dimaknai sebagai kondisi
bahwa sebelumnya ia pun pernah mengamini keefektifan metode tersebut—ia sempat
menjadi “penganut” cara pandang positivistik-empiris dari segi medis sebagaimana tokoh
Jorijs. Hal itu menandakan bahwa Oentoeng juga melakukan mimikri dalam konteks dunia
medis. Akan tetapi, sekali lagi, sangkalannya kemudian dapat dimaknai pula sebagai mockery
karena penemuan metode ala Timur yang kini ia anggap lebih alami dan efektif dalam
memperbaiki tubuh manusia.
Ketiga, telah disinggung sebelumnya dalam pembahasan tentang hibriditas tokoh
Oentoeng, bahwa sang dokter atau tokoh-Aku melihat sosok Oentoeng dengan posisi
memegang payung militer dalam lukisan karya Coeman. Artinya, dapat diasumsikan bahwa
identitasnya sebagai oposisi atau penentang orang-orang Belanda yang menjajah kaum
Pribumi—sebagaimana dinarasikan dalam cerpen—bermula dari pemahamannya terkait
kemiliteran Belanda. Tokoh Oentoeng, sebagaimana disinggung pada halaman ke-128 buku
Semua untuk Hindia, dikenal sebagai sosok yang kejam dan tidak mengenal ampun ketika
berhadapan dengan Kompeni:
Vuijborn menyorongkan wajahnya mendekati kanvas. “Kalau benar, ajaib sekali kau bisa
lolos,” gumamnya. “Ia pemimpin penyamun. Pembenci Belanda. Membunuh banyak tentara
sejak lolos dari Stadhuis. Buronan Kompeni nomor satu. Minggat dari rumah Cnoll karena tak
boleh lagi menjadi pemegang payuung oleh anak lelaki Pieter. Konon ia lalu dipelihara oleh
Edeleer Moor, dan membuat skandal cinta dengan Suzanna, anak gadis Moor.” (Banu, 2014:
128)
Dalam hal ini, perlu kiranya merujuk kepada fakta sejarah—sebab setelah titimangsa
cerpen, pengarang membubuhkan keterangan bahwa cerpen “Penunjuk Jalan” terinspirasi
dari roman Surapati (1950) karya Abdoel Moeis dan cerita perjalanan Untung Surapati,
seorang pahlawan Indonesia—bahwa Oentoeng memang dikenal sebagai sosok Pribumi yang
gigih menentang penjajahan Belanda di Tanah Nusantara. Dapat dikatakan bahwa mockery-
nya dalam hal ini berkaitan dengan perlawanan secara langsung atau perlawanan fisik
terhadap Belanda, berbekal pemahaman mumpuni mengenai strategi militer Belanda yang
pernah ia peroleh dari didikan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) sebelumnya
(Raditya, 2018). Oleh sebab itulah, Oentoeng atau Untung Surapati dalam sejarah Nusantara
dikenal sebagai sosok yang sukses membuat pihak Belanda kerepotan karena ulah dan dan
tindakan memberontaknya terhadap VOC atau Kompeni (Wijaya, dkk., 2019).
Jejak Ambivalensi dalam cerpen Penunjuk Jalan: Memusuhi Sekaligus Menolong
Penjajah
Telah diungkapkan pada bagian pembahasan mimikri, lewat kutipan dari Bhabha,
bahwa mimikri sendiri disebabkan adanya hubungan yang ambivalen antara pihak penjajah
dan pihak yang terjajah. Sikap ambivalensi ini dipicu oleh adanya kecintaan terhadap suatu
VOL. 3. No. 1, Januari 2022 hlm. 10-23 20
MIMESIS
VOL. 3. No. 1, Januari 2022
hal sekaligus membencinya. Menurut Bhabha (dalam Loomba, 2016: 229–30) ambivalensi
tidak hanya dapat dibaca sebagai petanda trauma subjek kolonial, melainkan juga sebagai ciri
cara kerja otoritas kolonial serta dinamika perlawanan. Bhabha juga mengungkapkan bahwa
kehadiran kolonial itu selalu ambivalen, terpecah antara menampilkan dirinya sebagai asli
dan otoritatif dengan artikulasinya yang menunjukkan pengulangan dan perbedaan. Dengan
kata lain, identitas kolonial itu tidak stabil, meragukan, dan selalu terpecah.
Dalam cerpen “Penunjuk Jalan”, tokoh Oentoeng digambarkan memiliki
kecenderungan ambivalensi, yakni memusuhi pihak penjajah, namun sekaligus berkenan
menolong sang dokter Belanda beserta portirnya yang mengalami kecelakaan. Tindakan
membantu tersebut memang didasari oleh situasi darurat, namun tetap dapat dimaknai
sebagai ambivalensi karena Pribumi yang membenci pihak penjajah semestinya melakukan
penumpasan terhadap musuhnya. Perilaku baik Oentoeng terhadap tokoh-Aku dalam cerpen,
digambarkan sebagai berikut.
“… Keretaku masuk jurang. Portir ini butuh bantuan kesehatan. Kami akan sangat berterima
kasih bila Tuan bersedia menunjukkan jalan ke Batavia.”
Si pemuda melepaskan tatapannya. Ketegangan mencair. (Banu, 2014: 120)
Tidak hanya penerimaan yang baik, tokoh Oentoeng bahkan berkenan membantu sang dokter
Belanda dan memberi perawatan pada portirnya yang mengalami luka parah. Ia pun berkenan
menunjukkan rute terdekat untuk sampai ke Batavia:
“… Sebaiknya Tuan ikut kami. Biarkan portir itu mendapat perawatan. Besok pagi kami
tunjukkan jalan tersingkat ke Batavia.”
“Betapa budiman,” aku membungkuk. “Joep dan aku akan selalu mengingat kebaikan Tuan.”
Pangeran melempar senyum. … (Banu, 2014: 122)
Disebabkan kebaikan perlakuan, berkali-kali tokoh-Aku memeri pujian pada
perlakuan Oentoeng terhadap “orang luar” yang membutuhkan pertolongan, padahal
notabene yang ia tolong adalah bagian dari orang Belanda dan yang sekaligus akan
ditugaskan menjalankan proyek kolonial. Ia menunjukkan ambivalensi sikap terhadap orang
Belanda yang seharusnya ia musuhi. Ambivalensi sikap tokoh pribumi ini seperti didasari
rasa kemanusiaan:
“… Nah, di balik sana kami tinggal. Tak banyak orang luar yang bisa masuk dengan mudah.
Tapi kami juga tidak bisa membiarkan teman Tuan seperti itu bukan?”
Kutoleh Joep. Masih terbaring layu.
“Pangeran sungguh berhati mulia,” aku mengangguk, lalu bergegas mengejar kudanya yang
dipacu kencang. (Banu, 2014: 124)
Perlakuan baik Oentoeng dan rombongannya terhadap pihak musuh (Belanda) tidak
hanya berhenti pada pertolongan medis, melainkan suguhan makanan dan minuman juga,
bahkan sang tokoh Pribumi memilih porsi yang lebih sedikit dibandingkan sang dokter
Belanda. Hal itu dijelaskan dalam kutipan pernyataan narator cerita:
VOL. 3. No. 1, Januari 2022 hlm. 10-23 21
MIMESIS
VOL. 3. No. 1, Januari 2022
Syukurlah sebentar kemudian disuguhkan kopi, air, dan makan malam. Aku menyantap
semuanya dengan lahap, namun segera berhenti demi menyaksikan kecilnya porsi yang
diambil Pangeran dan pengikutnya. (Banu 2014: 125)
Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa ambivalensi tokoh Oentoeng dalam
cerpen “Penunjuk Jalan” ialah berupa penerimaan, pemberian pertolongan, dan perlakuan
baik terhadap seorang dokter Belanda, yang notabene merupakan bagian dari pihak Belanda
yang sejatinya ia musuhi.
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis terhadap cerpen “Penunjuk Jalan” karya Iksaka Banu
menggunakan perspektif pascakolonial Homi K. Bhabha, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut. Pertama, karena dibesarkan dalam asuhan, didikan, dan pergaulan dengan keluarga
Belanda, membuat identitas tokoh berdarah Pribumi bernama Oentoeng berada pada posisi
hibrid karena menyerap nilai-nilai Barat secara berkontinuitas. Kedua, mimicry as mockery
yang dilakukan tokoh tersebut dapat dilihat berdasarkan tiga aspek, yakni kemampuan
berbahasa Belanda, memiliki pengetahuan medis ala Barat, dan mampu merancang strategi
pemberontakan yang membuat kerepotan VOC selaku penjajah. Terakhir, sikap Oentoeng
yang membenci penjajah namun sekaligus berkenan memberi pertolongan, pengobatan, dan
perjamuan kepada dokter Belanda beserta portirnya yang mengalami kecelakaan, dapat
dimaknai sebagai bentuk ambivalensi sang tokoh yang dapat ditemui dalam cerpen
“Penunjuk Jalan”.
DAFTAR PUSTAKA
Althusser, Louis. 2007. Filsafat sebagai Senjata Revolusi. Yogyakarta: Resist Book.
Banu, Iksaka. 2014. Semua untuk Hindia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Bhabha, Homi K. 1994. The Location of Culture. New York: Routledge Classics.
Day, Tony, and Keith Foulcher. 2008. “Bahasan Kolonial dalam Sastra Indonesia Modern:
Catatan Pendahuluan.” P. 468 in Sastra Indonesia Modern Kritik Postkolonial.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Fajar, Yusri. 2011. “Negosiasi Identitas Pribumi dan Belanda Dalam Sastra Poskolonial
Indonesia Kontemporer.” Literasi 1(2):178–86.
Faruk. 2007. Belenggu Pascakolonial: Hegemoni & Resistensi dalam Sastra Indonesia.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Faruk. 2017. Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
VOL. 3. No. 1, Januari 2022 hlm. 10-23 22
MIMESIS
VOL. 3. No. 1, Januari 2022
Fiaji, Noveria Anggraeni, Fitrahayunitisna, dan Prisca Kiki Wulandari. 2020. “Potret Nilai
Nasionalisme dalam Kumpulan Cerpen Semua untuk Hindia Karya Iksaka Banu.”
Kode 9(4).
Foulcher, Keith. 2008. “Larut di Tempat yang Belum Terbentuk Mimikri dan Ambivalensi
Dalam Sitti Noerbaja Marah Rusli.” Dalam Sastra Indonesia Modern: Kritik
Postkolonial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Heryanto, Ariel. 2015. “Indonesia dalam Indo: Menghargai Semua untuk Hindia.”
Indoprogress.Com. Retrieved June 10, 2021
(https://indoprogress.com/2015/04/indonesia-dalam-indo-menghargai-semua-untuk-
hindia/).
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. "Ideologi". Retrieved November 18, 2021
(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ideologi).
Khuzaini, A. H. 2018. “Kepribadian dan Aktualisasi Diri Tokoh Utama dalam Kumpulan
Cerpen Semua untuk Hindia Karya Iksaka Banu (Kajian Psikologi Sastra).” EDU-
KATA 5(2):115–22.
Kuntowijoyo. 2006. Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Loomba, Ania. 2016. Kolonialisme/Pascakolonialisme. Yogyakarta: Narasi.
Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya.
Raditya, Iswara N. 2018. “Untung Surapati, Bekas Budak yang Mengawini Perempuan
Belanda.” Tirto.Id. Retrieved June 12, 2021 (https://tirto.id/untung-surapati-bekas-
budak-yang-mengawini-perempuan-belanda-cFj3).
Setiawan, Rahmat. 2018. Pascakolonial: Wacana, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta:
Gambang Buku Budaya.
Stroomberg, J. 2018. Hindia Belanda 1930. Yogyakarta: IRCiSoD.
Suweleh, Fadlun. 2020. “Tokoh-tokoh Nativephilia dalam Antologi Cerpen Semua untuk
Hindia Karya Iksaka Banu: Analisis Pascakolonial Homi K. Bhabha.” Jentera
9(2):199–215.
Turama, Akhmad Rizqi. 2017. “Ambivalensi dalam Cerpen 'Anak Ini Mau Mengencingi
Jakarta?' Karya Ahmad Tohari: Kajian Poskolonialisme.” Eufoni 1(1).
Wijaya, Guntur S., Achmad Zulfikar N., Alhadisatur Rofiqoh, Dwi Rofikoh, Widayawati,
Khusnul Villah, Puji M. Arfi, and Syahrul Ramadhan W. 2019. “Peranan Untung
Surapati di Wilayah Mataram dalam Babad Trunajaya-Surapati.” Suluk 1(1):51–58.
Young, Robert J. C. 2003. Postcolonialism: a Very Short Introduction. New York: Oxford
University Press.
VOL. 3. No. 1, Januari 2022 hlm. 10-23 23
View publication stats
You might also like
- The Rastaman Vibration 2009 PDFDocument245 pagesThe Rastaman Vibration 2009 PDFDénes Kéri100% (3)
- History of India Part - 4-1877Document180 pagesHistory of India Part - 4-1877Parveen KumarNo ratings yet
- The Message of ManassehDocument75 pagesThe Message of ManassehRF / HebrewNationNo ratings yet
- Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in IndiaFrom EverandColonialism and Its Forms of Knowledge: The British in IndiaRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (3)
- Design For Discipleship 1: You're Life in ChristDocument31 pagesDesign For Discipleship 1: You're Life in ChristBen Stimpson50% (4)
- INDONESIAN lITERATUREDocument11 pagesINDONESIAN lITERATURErayhana minalang-limbonaNo ratings yet
- Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern IndiaFrom EverandCastes of Mind: Colonialism and the Making of Modern IndiaRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (3)
- Colonial Constructions of Tribe in India The CaseDocument36 pagesColonial Constructions of Tribe in India The CasePrashant KumarNo ratings yet
- Reading MattersDocument284 pagesReading MattersebisosuNo ratings yet
- List of AyushmanDocument573 pagesList of AyushmanRaghu Nathkumar Reddy100% (2)
- The Shadow of The Crescent MoonDocument4 pagesThe Shadow of The Crescent MoonHoover Gonzalez SotoNo ratings yet
- Postcolonialism and The Study of Indology in India: A Reading of Selected Works of K. K. HandiquiDocument15 pagesPostcolonialism and The Study of Indology in India: A Reading of Selected Works of K. K. HandiquiShiladitya HaldarNo ratings yet
- Habib SimplifiedDocument9 pagesHabib Simplifiedpigixih621No ratings yet
- HTTPS:/WWW Ijsr Net/archive/v9i6/SR20607091927 PDFDocument4 pagesHTTPS:/WWW Ijsr Net/archive/v9i6/SR20607091927 PDFJaisingh ChandramaniNo ratings yet
- 8 Mohan GuptaDocument3 pages8 Mohan Gupta123prayerNo ratings yet
- British IndologyDocument10 pagesBritish IndologyLalit MishraNo ratings yet
- Early Indian History and The Legacy of DD Kosambi: Romila ThaparDocument23 pagesEarly Indian History and The Legacy of DD Kosambi: Romila ThaparAbhishek HandaNo ratings yet
- Tokoh Pribumi Dalam Relasi Barat-Timur Kajian PoskDocument10 pagesTokoh Pribumi Dalam Relasi Barat-Timur Kajian Poskricardo laurenssNo ratings yet
- The Study of Arundhati Roy's The God of Small Things: History, Diaspora, Hybridity, WomenDocument12 pagesThe Study of Arundhati Roy's The God of Small Things: History, Diaspora, Hybridity, WomenshibayanNo ratings yet
- 06 - Chapter 1 PDFDocument42 pages06 - Chapter 1 PDFRikita MajumderNo ratings yet
- Hybridity and History: A Critical Reflection On Homi K. Bhabha's Post-Historical ThoughtsDocument22 pagesHybridity and History: A Critical Reflection On Homi K. Bhabha's Post-Historical Thoughtsbolontiku9No ratings yet
- Acquired Human Violence andDocument5 pagesAcquired Human Violence andGabriel BazimazikiNo ratings yet
- B. R. Ambedkar, John Dewey, and The Meaning of DemocracyDocument27 pagesB. R. Ambedkar, John Dewey, and The Meaning of Democracygnarayanswami82No ratings yet
- A Reading of The Introductions of WilliaDocument24 pagesA Reading of The Introductions of WilliaBusinessNo ratings yet
- 27 Ideological PDFDocument8 pages27 Ideological PDFIJELS Research JournalNo ratings yet
- Interpreting Early India Romila ThaparDocument16 pagesInterpreting Early India Romila ThaparArmand LyngdohNo ratings yet
- Buddhist Visions of Transculturalism: Picturing Miyazawa Kenji's 'Yamanashi' (Wild Pear)Document20 pagesBuddhist Visions of Transculturalism: Picturing Miyazawa Kenji's 'Yamanashi' (Wild Pear)BurcuNo ratings yet
- Final Essay - English For Academical Purposes PDFDocument5 pagesFinal Essay - English For Academical Purposes PDFMarilena KokkiniNo ratings yet
- Bki Article p273 - 5Document26 pagesBki Article p273 - 5Bahomious Adi SolomonNo ratings yet
- Sum Atran Politics and Poetics: Gayo History 1900-1989Document2 pagesSum Atran Politics and Poetics: Gayo History 1900-1989Hesri Rawana GayoNo ratings yet
- Theories of IndianizationDocument20 pagesTheories of IndianizationAnuj PratapNo ratings yet
- 4.1 Postcolonial NovelDocument51 pages4.1 Postcolonial NovelazharNo ratings yet
- Multicultural Values in The Indonesian Novel of Minangkabaus Local Culture Pre TDocument5 pagesMulticultural Values in The Indonesian Novel of Minangkabaus Local Culture Pre TVika YusnitaNo ratings yet
- Teks ArtikelDocument20 pagesTeks ArtikelNisa Ul KarimaNo ratings yet
- PostcolonialismDocument13 pagesPostcolonialismNasir NasirNo ratings yet
- Postcolonial ThemesDocument3 pagesPostcolonial ThemestarcisiamercadoNo ratings yet
- "Indian Historiography" "History": "Unit (1) (C) "Document32 pages"Indian Historiography" "History": "Unit (1) (C) "ArjunNo ratings yet
- Being Mizo CHP IntroDocument35 pagesBeing Mizo CHP IntroHimanshu ThakurNo ratings yet
- Monthly Multidiciplinary Research JournalDocument8 pagesMonthly Multidiciplinary Research Journalbadminton12No ratings yet
- Perspectives On India During Colonial PeriodDocument8 pagesPerspectives On India During Colonial PeriodDrYounis ShahNo ratings yet
- B C ChatterjeeDocument11 pagesB C ChatterjeekomalNo ratings yet
- Thapar On KosambiDocument23 pagesThapar On KosambiSudheer KumarNo ratings yet
- Cultural Materialism in The Selected Short StoriesDocument5 pagesCultural Materialism in The Selected Short StoriesKristian Jane ELLADORANo ratings yet
- Four Ways of Reading The Work of Nirad C. Chaudhuri. A Case Study of A Postcolonial ConservativeDocument23 pagesFour Ways of Reading The Work of Nirad C. Chaudhuri. A Case Study of A Postcolonial ConservativeAney jangra bostiNo ratings yet
- Remaking The Indian Historians CraftDocument9 pagesRemaking The Indian Historians CraftChandan BasuNo ratings yet
- Research Works of Debaprasad BandyopadhyayDocument27 pagesResearch Works of Debaprasad BandyopadhyayDebaprasad BandyopadhyayNo ratings yet
- Antonomasias Formed On The Basis of The Names of Mythological, Religious-Legendary HeroesDocument3 pagesAntonomasias Formed On The Basis of The Names of Mythological, Religious-Legendary HeroesResearch ParkNo ratings yet
- Looking Back From The Periphery Situating Indonesian ProvincialDocument30 pagesLooking Back From The Periphery Situating Indonesian ProvincialStalin TrotskyNo ratings yet
- Alphabetic Script As A Material Condition For Western PhilosophyDocument33 pagesAlphabetic Script As A Material Condition For Western PhilosophyAnonymous 8zZGf0WkNNo ratings yet
- Dodson - Contesting Translations - Orientalism and The Interpretation of The VedasDocument17 pagesDodson - Contesting Translations - Orientalism and The Interpretation of The VedasEric M GurevitchNo ratings yet
- Research Article On Art of Writing Back To The EmpireDocument12 pagesResearch Article On Art of Writing Back To The Empireirtasham ul haqNo ratings yet
- Oleh: Nang Naemah Nik DahalanDocument18 pagesOleh: Nang Naemah Nik Dahalanhanina123No ratings yet
- Sanskrit in The 18th C-KavirajDocument25 pagesSanskrit in The 18th C-KavirajtanimajnuNo ratings yet
- 21948-Article Text-78635-2-10-20160113 PDFDocument13 pages21948-Article Text-78635-2-10-20160113 PDFNudrat TahfeemNo ratings yet
- A Study of Folklore Materials in The Novel Birgwsrini Thungri by Bidyasagar NarzaryDocument10 pagesA Study of Folklore Materials in The Novel Birgwsrini Thungri by Bidyasagar NarzaryIJAR JOURNALNo ratings yet
- The Colonial Official As Ethnographer VOC Documents As ResourcesDocument25 pagesThe Colonial Official As Ethnographer VOC Documents As ResourcesyaizacasalriosNo ratings yet
- The Trilogy of Gadis Tangsi Novels by Suparto BrataDocument7 pagesThe Trilogy of Gadis Tangsi Novels by Suparto BrataTirto SuwondoNo ratings yet
- Project .Docx Layout Thahsi 3Document29 pagesProject .Docx Layout Thahsi 3Bishru SalahudheenNo ratings yet
- DR ANJALI TRIPATHY 74-79Document6 pagesDR ANJALI TRIPATHY 74-79hurunnashaNo ratings yet
- 1 PBDocument7 pages1 PBmbojo klopediaNo ratings yet
- Jurnal (Nur Sitha Afrilia 13010114120023)Document18 pagesJurnal (Nur Sitha Afrilia 13010114120023)Dian febriyaniNo ratings yet
- Analisis Poskolonial Pada Novel Tak Ada Esok Karya Mochtar LubisDocument9 pagesAnalisis Poskolonial Pada Novel Tak Ada Esok Karya Mochtar LubisJBSI FITRIYAHNo ratings yet
- Monsters, Examined Etiropean Responses To: NotesDocument3 pagesMonsters, Examined Etiropean Responses To: NotesMylena GodinhoNo ratings yet
- Thesis Haque 2013Document469 pagesThesis Haque 2013Vanshika SharmaNo ratings yet
- Indian Intellectual HistoryDocument10 pagesIndian Intellectual Historyysaeed7No ratings yet
- British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835From EverandBritish Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835No ratings yet
- 1 PFHL 121 Divine JoyDocument23 pages1 PFHL 121 Divine JoyBill StevensonNo ratings yet
- Home of Last Resort - Urban Land Conflict and The Nubians in Kibera, KenyaDocument16 pagesHome of Last Resort - Urban Land Conflict and The Nubians in Kibera, KenyaIsdomo SunaryoNo ratings yet
- Adam and Hawa - Story of Propher AdamDocument2 pagesAdam and Hawa - Story of Propher Adamabbyr nulNo ratings yet
- Cultural Communities in Visayas: Sseis Grade 4 Sped ImmbDocument2 pagesCultural Communities in Visayas: Sseis Grade 4 Sped ImmbMaam Aina BalajadiaNo ratings yet
- Hamlet Essay Template ENG4U1 Exam: MadnessDocument3 pagesHamlet Essay Template ENG4U1 Exam: Madnessameera sNo ratings yet
- Registro Electoral 2011Document25 pagesRegistro Electoral 2011Apunefm IppunefmNo ratings yet
- Repentance and FaithDocument5 pagesRepentance and FaithDennis ToomeyNo ratings yet
- Assignment MarksDocument164 pagesAssignment MarksBen AzriNo ratings yet
- Watchtower: Our Lord's Return, 1925Document68 pagesWatchtower: Our Lord's Return, 1925sirjsslutNo ratings yet
- MÃ ĐỀ 014Document2 pagesMÃ ĐỀ 014Yuki SaitoNo ratings yet
- Bio - Sci Elec SecondaryDocument7 pagesBio - Sci Elec SecondaryPrabhakar ReddyNo ratings yet
- Ethnology of India 00 CampDocument294 pagesEthnology of India 00 CampOm SatpathyNo ratings yet
- The Bible Is TrustworthyDocument6 pagesThe Bible Is TrustworthyDrew DixonNo ratings yet
- Urban Session Sites With Vaccinator 14.07.2021Document3 pagesUrban Session Sites With Vaccinator 14.07.2021Rudraksh shindeNo ratings yet
- The Basque Element in Puerto Cabello 18th Century VenezuelanDocument113 pagesThe Basque Element in Puerto Cabello 18th Century VenezuelanXabier AmezagaNo ratings yet
- Eoy History) PDFDocument6 pagesEoy History) PDFsabeehaNo ratings yet
- ReportDocument59 pagesReportDave ThreeTearsNo ratings yet
- 45 BCS Subjective MT-04-solutionDocument8 pages45 BCS Subjective MT-04-solutionMd ShuvoNo ratings yet
- Narrating Past Events Student PDFDocument34 pagesNarrating Past Events Student PDFbianca75No ratings yet
- Amitabh Bacchan's BiographyDocument2 pagesAmitabh Bacchan's BiographyMohitNo ratings yet
- HIC Shelter Data Pack 30 July 2005Document227 pagesHIC Shelter Data Pack 30 July 2005Edi SusantoNo ratings yet
- OntopatiaDocument1 pageOntopatiadddgfdgNo ratings yet
- Mary Magdalene, From A Praefica of Nenia To A Messenger of CarmentisDocument18 pagesMary Magdalene, From A Praefica of Nenia To A Messenger of CarmentisBennet Arren LawrenceNo ratings yet
- Professor Vijay Shankar Vyas Iima Director Ids Imf Rbi World Bank & Advisor PmoDocument1 pageProfessor Vijay Shankar Vyas Iima Director Ids Imf Rbi World Bank & Advisor PmoKNOWLEDGE CREATORSNo ratings yet