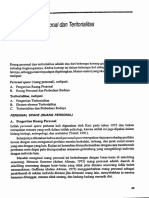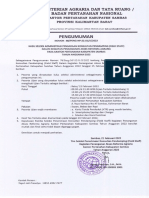Professional Documents
Culture Documents
Bab6 Privasi
Bab6 Privasi
Uploaded by
Izzai Anwar Yad0 ratings0% found this document useful (0 votes)
191 views11 pagesOriginal Title
bab6-privasi
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
191 views11 pagesBab6 Privasi
Bab6 Privasi
Uploaded by
Izzai Anwar YadCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 11
emt tt re ens RSA SEEN TRCN
Bab 6 Privasi
Privasi adalah salah satu konsep dari gejala persepsi manusia terhadap lingkungannya, di
mana konsep ini amat dekat dengan konsep ruang personal dan teritorialitas seperti yang
dibahas di muka. Materi-materi yang akan dibahas di dalamnya antara lain meliputi:
A. Pengertian Privasi
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Privasi
Faktor Personal
Faktor Situasional
Faktor Budaya
C. Pengaruh Privasi Terhadap Perilaku
A. PENGERTIAN PRIVASI
Privasi merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada
suatu kondisi atau situasi tertentu.-Tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut
keterbukaan atau ketertutupan, yaitu adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain,
atau justra ingin menghindar atau berusaha supaya sukar dicapai oleh orang lain (Dibyo
Hartono, 1986).
Beberapa definisi tentang privasi mempunyai kesamaan yang menekankan pada
kemampuan seseorang atau kelompok dalam mengontrol interaksi panca inderanya dengan
pihak lain.
Privasi merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendakioleh seseorang
pada suatu kondisi atau situasi tertentu. Tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut
keterbukaan atau ketertutupan, yaitu adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain,
atau justru ingin menghindar dengan berusaha supaya sukar dicapai oleh orang lain, dengan
cara mendekati atau menjauhinya. Lang (1987) berpendapat bahwa tingkat dari privasi
tergantung dari pola-pola perilaku dalam konteks budaya dan dalam kepribadian dan aspirasi
dari keterlibatan individu.
Rapoport (dalam Soesilo, 1988): mendefinisikan privasi sebagai suatu kemampuan
‘untuk mengor.trol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan-pilihan dan kemampuan
untuk mencapai interaksi seperti yang diinginkan, Privasi jangan dipandang hanya sebagai
penarikan diri seseorang secara fisik tethadap pihak-pihak lain dalam rangka menyepi saja.
60
sists xt A AOA EO RST TE ES,
Hal ini agak berbeda dengan yang dikatakan oleh Marshall (dalam Wright man & Deaux,
1981) dan ahli-abli lain (seperti Bates, 1964; Kira, 1966 dalam Altman, 1975) yang
mengatakan bahwa privasi menunjukkan adanya pilihan untuk menghindarkan diri dari
keterlibatan dengan orang lain dan lingkungan sosialnya.
‘Altman (1975), hampir sama dengan yang dikatakan Rapoport, mendefinisikan privasi
dalam bentuk yang lebih dinarnis, Menurutnya privasi adalah proses pengontrolan yang
selektif terhadap akses kepada diri sendiri dan akses kepada orang lain. Definisi ini
mengandung beberapa pengertian yang lebih luas. Pertama, unit sosial yang digambarkan
bisa berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dan
seterusnya, Kedua, penjelasan mengenai privasi sebagai proses dua arah; yaitu pengontrolan
input yang masuk ke individu dari luar atau output dari individu ke pihak lain. Ketiga, definisi
ini menunjukkan suatu kontrol yang selektif atau suatu proses yang aktif dan dinamis.
‘Altman (1975) menjabarkan beberapa fungsi privasi. Pertama, privasi adalah pengaturdan
pengontrol interaksi interpersonal yang berarti sejauh mana hubungan dengan orang lain
diinginkan, kapan waktunya menyendiri dan kapan waktunya bersama-sama dengan orang .
lain, Privasi dibagi menjadi dua macam, yaitu privasi rendah yang terjadi bila hubungan dengan
orang lain dikehendaki, dan privasi tinggi yang terjadi bila ingin menyendiri dan hubungan
dengan orang lain dikurangi. Fungsi privasi kedua adalah merencanakan dan membuat strategi
‘untuk berhubungan dengan orang lain, yang meliputi keintiman atau jarak dalam berhubungan
dengan orang lain. Fungsi ketiga privasi adalah memperjelas identitas diri.
Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memiliki referensi tingkat privasi yang
diinginkannya. Ada saat-saat dimana seseorang ingin berinteraksi dengan orang lain (privasi
rendah) dan ada saat-saat dimana ia ingin menyendiri dan terpisah dari orang lain (privasi
tinggi). Untuk mencapai hal itu, ia akan mengontrol dan mengatur melalui suatu mekanisme
perilaku, yang digambarkan oleh Altman sebagai berikut :
a). Perilaku verbal
Perilaku ini dilakukan dengan cara mengatakan kepada orang lain secara verbal, sejauh
mana orang lain boleh berhubungan dengannya. Misalnya “Maaf, saya tidak punya
waktu”.
b). Perilaku non verbal
Perilaku ini dilakukan dengan menunjukkan ekspresi wajah atau gerakan tubuh tertentu
sebagaitanda senang atau tidak senang, Misalnya seseorang akan menjauh dan membentuk
jarak dengan orang lain, membuang muka ataupur terus-menerus melihat waktn yang
‘menandakan bahwa dia tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Sebaliknya dengan
mendekati dan menghadapkan mnka, tertawa, menganggukkan kepala merhberikan
indikasi bahwa dirinya siap untuk berkomunikasi dengan orang lain.
c). Mekarisme kultural
Budayz mempunyaibermacam-macam adat istiadat, aturan atau norma, yang
menggambarkan keterbukaan atau ketertutupan kepada orang lain dan hal ini sudah
61
diketahui oleh banyak orang pada budaya tertentu (Altman, 1975; Altman & Chemers
dalam Dibyo Hartono, 1986).
d). Ruang personal .
Ruang personal adalah salah satu mekanisme perilaku untuk mencapai tingkat privasi
tertentu. Sommer (dalam Altman, 1975) mendefinisikan beberapa karakteristik ruang
personal. Pertama, daerah batas diri yang diperbolehkan dimasuki oleh orang lain.
Ruang personal adalah batas maya yang mengelilingi individu sehingga tidak kelihatan
oleh orang lain. Kedua, ruang personal itu tidak berupa pagar yang tampak mengelilingi
seseorang dan terletak pada satu tempat tetapi batas itu melekat pada diri dan dibawa
kemana-mana. Fisher dkk. (1984), mengatakan bahwa ruang personal adalah batas maya
yang mengelilingi individu. Ketiga, sama dengan privasi ruang personal adalah batas
kawasan yang dinamis, yang berubah-ubah besarnya sesuai dengan waktu dan situasi.
Hal ini tergantung dengan siapa seseorang itu berhubungan. Keempat, pelanggaran
Tuang personal oleh orang lain akan dirasakan sebagai ancaman sehingga daerah ini
dikontrol dengan kuat.
Kebanyakan penelitian menunjukkan bahwa individu yang mempunyai kecenderungan
berafiliasi tinggi, ekstrovert atau yang mempunyai sifat hangat dalam berhubungan
interpersonal mempunyai ruang personal yang lebih kecil daripada individu yang
introvert (Gifford, 1987).
e). Teritorialitas
Pembentukan kawasan teritorial adalah mekanisme perilaku lain untuk mencapai privasi
tertentu. Kalau mekanisme ruang personal tidak memperlihatkan dengan jelas kawasan
yang menjadi pembatas antar dirinya dengan orang lain maka pada teritorialitas batas-
batas tersebut nyata dengan tempat yang relatif tetap.
‘Menurut Holahan (1982) teritorialitas adalah suatu pola perilaku yang ada hubungannya
dengan kepemilikan atau hak seseorang atau sekelompok orang atas sebuah lokasi geografis
tertentu. Pola perilaku ini mencakup personalisasi dan pertahanan terhadap gangguan dari
luar. Altman (1975) mendefinisikan teritorialitas sebagai berikut: 1) Teritori merupakan
wilayah geografis. Daerah ini meliputi tanah dengan batas-batas alam, tempat tertentu,
gedung dan bangunan. 2) Daerah itu untuk bermacam-macam keperluan biologis dan sosial-
psikologis. 3) Ada kontrol terhadap daerah penggunaannya, misalnya dengan memberikan
tanda-tanda tertentu (pagar, bangunan, dan lain-lain). 4) Teritori dapat dikontrol oleh
perorangan ataupun kelompok. 5) Pemilik teritori berusaha mempertahankan teritori tersebut
dari penerobosan orang lain.
Altman (1975) membagi teritorialitas menjadi 3 macam. Pertama, terito:i primer
merupakan tempat yang bersifat pribadi yang mencerminkan harga diri dan identitas
pemiliknya. Misalnya ruang tidur, ruang kerja, pekarangan, dan lain-lain. Kedua, teritori
sekunder merupakan tempat yang dimiliki bersama oleh sejumlah orang yang sudah saling
mengenal atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kelompok itu misalnya
62
tangga bersama, toilet, pintu gerbang, dan lain-lain. Ketiga, teritori umum, yaitu tempat-
tempat terbuka untuk umum. Misalnya bioskop, taman umum, plaza, dan lain-lain.
Sementara itu Marshall (dalam Holahan, 1982); Sarwono (1992) berusaha membuat alat
yang berisi serangkaian pernyataan tentang privasi dalam berbagai situasi (dinamakan
Privacy Preference Scale) dan ia menemukan adanya enam jenis orientasi tentang privasi
yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu tingkah laku menarik diri
(withdrawal) dan mengontrol informasi (control of information). Tiga orientasi yang
termasuk dalam tingkah laku menarik diri adalah solitude (keinginan untuk menyendiri),
seclusion (keinginan untuk menjauh dari pandangan dan gangguan suara tetangga serta
kebisingan lalu lintas) dan intimacy (keinginan untuk dekat dengan keluargadan orang-orang
tertentu, tetapi jaul: dari semua orang lain). Tiga orientasi lain yang termasuk dalam tingkah
laku mengontrol informasi adalah anonymity (keinginan untuk merahasiakan:jati diri),
reserve (keinginan untuk tidak mengungkapkan diri terlalu banyak kepada orang.fatfi) dan
not-neighboring (keinginan untuk tidak terlibat dengan tetangga).
Hampir sama dengan Marshall, Westin (dalam Altman, 1975; Wrightman & Deaux,
1981) menjadi privasi menjadi empat macam, yaitu solitude, intimacy, anonymity dan
reserve, Dalam solitude seseorang ingin menyendiri dan bebas dari pengamatan orang lain
serta dalam kondisi privasi yang ekstrem. Intimacy ialah keadaan seseorang yang bersama
orang lain namun bebas dari pihak-pihak lain. Anonymity ialah keadaan seseorang yang tidak
menginginkan untuk dikenal oleh pihak lain, sekalipun ia berada di dalam suatu keramaian
umum. Sedang reserve ialah keadaan seseorang yang menggunakan pembatas psikologis
untuk mengontrol gangguan yang tidak dikehendaki.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka kita dapat mengatakan bahwa konsep privasi
ternyata sangat dekat dengan konsep ruang personal dan teritorialitas. Altman (1975)
membuat suatu model organisasi konseptual. Altman mempertimbangkan ruang personal,
teritorial, dan kesesakan untuk mencapai privasi.
Isolasi Sosial (Privasi yang dicapai
lebih besar dari yang diinginkan)
v
Kedudukan Privasi yang Kontrol Privasi yang Optimum (privasi
Pola-pola —®Diinginkan —>Mekanisme —® Dicapai ©—® yang diinginkan
Perilaku (ideal) Interpersonal (Keluaran) = privasi yang
dicapai)
4
Kesesakun (Privasi yang dicapai
lebih kecil dari yang diinginkan) © *—
Gambar 1.6. Model Privasi Yang Dapat Dicapai dengan Mempertimbangkan
Ruang Personal dan Teritorialitas
Sumber: Altman (1975)
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRIVASI
Terdapat faktor yang mempengaruhi privasi yaitu faktor personal, faktor situasional, dan
faktor budaya,
Faktor Personal. Marshall (dalam Gifford, 1987) mengatakan bahwa perbedaan dalam latar
belakang pribadi akan berhubungan dengan kebutuhan akan privasi. Dalam penelitiannya,
ditemukan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam suasana rumah yang sesak akan lebih
memilih keadaan yang anonim dan reserve saat ia dewasa. Sedangkan orang menghabiskan
sebagian besar waktunya di kota akan lebih memilih keadaan anonim dan intimacy.
Sementara itu Walden dan kawan-kawan (dalam Gifford, 1987) menemukan adanya
perbedaan jenis kelamin dalam privasi. Dalam sebuah penelitian pada para penghuni asrama
ditemukan bahwa antara pria dan wanita terdapat perbedaan dalam merespon perbedaan
keadaan antara ruangan yang berisi dua orang dengan ruangan yang berisi tiga orang. Dalam
hubungannya dengan privasi, subjek pria lebih memilih ruangan yang berisi dua orang,
sedangkan subjek wanita tidak mempermasalahkan keadaan dalam dua ruangan tersebut. Hal
itu menunjukkan bahwa wanita merespon lebih baik daripada pria bila dihadapkan pada
situasi dengan kepadatan yang lebih tinggi.
Faktor Situasional. Beberapa hasil penelitian tentang privasi dalam dunia kerja, secara
‘umum menyimpulkan bahwa kepuasan terhadap kebutuhan akan privasi sangat berhubungan
dengan seberapa besar lingkungan mengijinkan orang-orang di dalamnya untuk menyenditi
(Gifford, 1987).
Penelitian Marshall (dalam Gifford, 1987) tentang privasi dalam rumah tinggal,
menemukan bahwa tinggi rendahnya privasi di dalam rumah antara lain disebabkan oleh
seting rumah. Seting rumah di sini sangat berhubungan seberapa sering para penghuni
berhubungan dengan orang, jarak antar rumah dan banyaknya tetangga sekitar rumah.
Seseorang yang mempunyai rumah yang jauh dari tetangga dan tidak dapat melihat banyak
rumah lain di sekitanya dari jendela dikatakan memiliki kepuasan akan privasi yang lebih
besar.
Faktor Budaya. Penemuan dari beberapa peneliti tentang privasi dalam berbagai budaya
(seperti Patterson dan Chiswick pada suku Iban di Kalimantan, Yoors pada orang Gypsy dan
Geertz pada orang Jawa dan Bali) memandang bahwa pada tiap-tiap budaya tidak ditemukan
adanya perbedaan dalam banyaknya privasi yang diinginkan, tetapi sangat berbeda dalam
cara bagaimana mereka mendapatkan privasi (Gifford, 1987). Dua buah studi tersebut antara
Jain akan disajikan pada alinea-alinea berikut.
Tidak terdapat keraguan bahwa perbedaan masyarakat menunjukkan variasi yang besar
dalam jumlah privasi yang dimiliki anggotanya. Dalam masyarakat Arab, keluarga-keluarga
menginginkan tinggal di dalam rumah dengan dinding yang padat dan tinggi mengelilinginya
(Gifford, 1987). Hasil pengamatan Gifford (1987) di suatu desa di bagian Selatan India
menunjukkan bahwa semau keluarga memiliki rumah yang sangat dekat satu sama lain,
64
2c HR LEE IE RE
sehingga akan sangat sedikit privasi yang diperolehnya. Orang-orang desa tersebut merasa
tidak betah bila terpisah dari tetangganya. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pengamatan
yang dangkal seringkali menipu kita. Kebutuhan akan privasi barangkali adalah sama
besarnya antaza orang Arab dengan orang India.
Studi Patterson dan Chiswick (dalam Gifford, 1987) di bawah ini menggambarkan
privasi masyarakat Iban, Serawak, Kalimantan. Orang-orang Iban tinggal di rumah panjang
dengan privasi yang (diduga) kurang, dimana kesempatan untuk menyendiri atau keintiman
ada di belakang pintu-pintu yang tertutup. Apakah orang-orang Iban memiliki privasi yang
amat memprihatinkan? Atau apakah mereka tidak membutuhkan privasi? Patterson dan
Chiswick menemukan orang Iban tampaknya membutuhkan privasi kira-kira sebanyak yang
kita butuhkan, akan tetapi mereka melakukannya dengan mekanisme yang berbeda.
Mekanisme-mekanisme ini adalah suatu kesepakatan sosial. Sebagai contoh, orang Iban
memiliki cara khusus untuk berganti pakaian di daerah yang bersifat publik dengan cara yang
sederhana. Terdapat aturan-aturan bagi anak-anak untuk mengurangi hal-hal yang tidak
dinginkan dalam hubungannya dengan orang dewasa. Rumah panjang itu tertutup bagi anak-
anak dalam banyak kesempatan. Pada saat mulai pubertas, ruang tidur anak mulai dibedakan
berdasarkan jenis kelaminnya.
Geertz dalam suatu presentasi seminar seperti yang disebutkan oleh Westin pada tahun
1970 (dalam Altman, 1975) menerangkan privasi keluraga pada masyarakat Jawa dan Bali:
DiJawa, orang tinggal di rumah kecil dengan dinding dari bambu. Hampir semua
rumah terdiri dari keluarga inti tunggal, yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak yang
belummenikah... Rumah-rumah berhadapan dengan jalan dengan halaman yang bersih
didepan rumahnya. Tidak terdapat dinding atau pagar di sekeliting rumahnya, dinding-
dinding (bambu) rumahnya tipis dan dianyam secara longgar, dan umumnya bahkan
tanpa pintu. Di dalam rumah orang bebas untuk berlalu-lalang, bahkan orang luar
dapat pula bebas berlalu-lalang di dalam rumah sepanjang hari atau pada sore hari.
Singkamya, privasimenurutisilah kita adalah tentang ketidaktertutupan yang diperoleh.
‘Anda dapat berjalan bebas menuju ruang dimana pria dan wanita tidur berbaring
(dalam keadaan berpakaian tentunya). Bila anda memasuki dari belakang ataupun dari
depan rumah, maka anda akan menerima lebih banyak peringatan daripada sambutan
yang yang akan mempermalukan kehadiran anda
‘Hasilnya adalah pertahanan mereka yang lebih bersifat psikologis. Hubungan-
hubungan di dalam rumah tangga bahkan sangat terkendali: orang berbicara pelan,
menyembunyikan perasaannya, dan apabila anda menjadi bagian dari keluarga Jawa,
‘maka akan memiliki perasaan bahwa anda seperti berada di suatu alun-alun tetapi
harus berperilaku sopan-santun yung sepantasnya. Orang Jawa menutup dirinya
terhadap orang lain dengan suatu “dinding etiket” (di mana sopan-santun adalah hal
yang dijaga dengan bait), dengan emosi yang terkendali, dan umumnya dengan
kekurangterusterangan dalam kata dan tindakan, Hal ini tidak berarti bahwa orang
Jawa tidak menginginkan atau tidak memiliki nilai privasi. Akan tetapi mereka memiliki
65
er PER SP SE NRE ES
semacam mekanisme untuk mengatur penghalang secara fisik dan sosial terhadap
orang luar yang masuk secara fisik menuju rumah tangga mereka. Mereka harus
mengaturnya secara psikologis dengan cara yang berbeda.
Di Bali orang tinggal di dalam haiaman rumah yang dikelilingi oleh dinding batu
yang tinggi, di mana pintu masuknya sempit terbuat dari balok kayu yang dipotong
setengahnya. Di dalam halaman tersebut tinggal beberapa keluarga inti (atau dalam
” istilah Antropologi disebut sebagai “patrilineal extended family"). Keluarga seperti itu
bisa terdiri dari satu atau belasan keluarga inti dengan anggota-anggotanya seperti
pada keluarga Jawa, dimana para pemimpinnya adalah sanak saudara dari sistem
patrilineal seperti: ayah, dua anak laki-lakinya yang sudah menikah, dua saudara laki-
lakinya yang sudah menikah, ayahnya,
Sangat kontras keadaannya dengan Jawa, orang yang bukan sanak saudaranya
hampir tidak pernah memasuki halaman rumah. Di dalam halaman yang seperti
benteng, orang luar lebih baik tidak terdorong untuk memasukinya.
Sanak saudara lain boleh datang memasuki halaman untukmembicarakan sesuatu,
dan dalam beberapa kasus satu atau dua orang teman dekat boleh melakukan hal itu,
Kecuali dari itu bila anda berada di dalam halaman rumah anda, maka anda bebas dari
publik, Hanya keluarga dekat yang berada di sekeliling anda.
Geertz kemudian mengatakan bahwa karakter rumah Orang Bali adalah:
Sesuatu yang amat hangat, humor, dan terbuka..
Sesegera orang Bali melangkahkan kakinya ke pintu keluar menuju ke jalan, melewati
alun-alun, pasar, dan candi-candi, la menjadi lebih atau kurang seperti orang Jawa.
. PENGARUH PRIVASI TERHADAP PERILAKU
Altman (1975) menjelaskan bahwa fungsi psikologis dari perilaku yang penting adalah untuk
‘mengatur interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungan sosial. Bila seseorang
dapat mendapatkan privasi seperti yang diinginkannya maka ia akan dapat mengatur kapan
harus berhubungan dengan orang lain dan kapan harus sendiri.
Maxine Wolfe dan kawan-kawan (dalam Holahan, 1982) mencatat bahwa perigelolaan
hubungan interpersonal adalah pusat dari pengalaman tentang privasi dalam kehidupan
sehari-hari. Menurutnya, orang yang terganggu privasinya akan merasakan keadaan yang
tidak mengenakkan.
Westin (dalam Holahan, 1982) mengatakan bahwa ketertutupan terhadap informasi
personal yang selektif, memenuhi kebutuhan individu untuk membagi kepercayaan dengan
orang lain. Keterbukaan membantu individu untuk menjaga jarak psikologis yang pasdengan
orang lain dalam banyak situasi.
© Schwartz (dalam Holahan, 1982) menemukan bahwa kemampuan untuk menarik diti ke
dalam privasi (privasi tinggi) dapat membantu membuat hidup ini lebih mengenakkan saat
harus berurusan dengan orang-orang yang “sulit”. Sementara hal yang senada diungkapkan
66
exe NRA RLE, 2:8 ER ERRATA
oleh Westin bahwa saat-saat kita mendapatkan privasi seperti yang kita inginkan, kita dapat
melakukan pelepasan emosi dari akumulasi tekanan hidup sehari-hari.
Selain itu, privasi juga berfungsi mengembangkan identitas pribadi, yaitu mengenal dan
menilai diri sendiri (Altman, 1975; Sarwono, 1992; Holahan, 1982). Proses mengenal dan
menilai diri ini tergantung pada kemampuan untuk mengatur sifat dan gaya interaksi sosial
dengan orang lain. Bila kita tidak dapat mengontrol interaksi dengan orang lain, kita akan
memberikan informasi yang negatif tentang kompetensi pribadi kita (Holahan, 1982) atau
akan terjadi proses ketelanjangan sosial dan proses deindividuasi (Sarwono, 1992).
Menurut Westin (dalam Holahan, 1982) dengan privasi kita juga dapat melakukan
evaluasi diri dan membantu kita mengembangkan dan mengelola perasaan otonomi diri
(personal autonomy). Otonomi ini meliputi perasaan bebas, kesadaran memilih dan
kemerdekaan dari pengaruh orang lain.
Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil suatu rangkuman bahwa fungsi psikologis
dari privasi dapat dibagi menjadi, pertama privasi memainkan peran dalam mengelola
interaksi sosial yang kompleks di dalam kelompok sosial; kedua, privasi membantu kita
memantapkan perasaan identitas pribadi.
Menurut Fisher dkk. (1984), salah satu aspek yang sangat penting dari desain ruang
dalam ialah jumiah privasi yang disediakan. Kita kadangkala membutuhkan nya agar dapat
““pergi dari sernuanya”. Desain arsitektur dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi
kemudahan orang melakukan hal tersebut. Pada beberapa seting sulit bagi kita untuk
“menyendiri”, sementara pada seting yang lain hal ini lebih mudah. Misalnya, asrama yang
menempatkan satu mahasiswa di suatu kamar akan meningkatkan lebih banyak privasi
daripada dua orang di satu kamar. Demikian pula, pemanfaatan pembatas di sekitar daerah
kerja seseorang dapat menambah kesan privasi tempat tersebut. Tidak demikian halnya
dengan Altman (1975) yang berpendapat bahwa privasi adalah konsep sentral, yang berbeda
dengan pandangan tradisional. Sebelumnya privasi dilihat sebagai proses dari keinginan
untuk menjadi sendirian sampai keinginan untuk pergi dari orang lain (sebagaimana
pendapat Fisher dkk. di atas). Para praktisi berdasarkan pendapat tersebut seringkali
menterjemahkannya dalam rancangan pada area tersendiri di dalam rumah atau di tempat
lain, Dalam pandangan Altman, privasi memiliki pendekatan yang lebih jauh, yaitu sebagai
“perubahan dari proses pengaturan pembatas diri atau orang lain terhadap seseorang atau
kelompok, dari keinginan untuk terpisah dari orang lain pada suatu saat sampai keinginan
untuk berhubungan dengan orang lain pada saat yang lain”, Altman menggambarkan privasi
sebagai proses dialektika, dimana dihadirkan dua hal: sesuatu keinginan untuk berhubungan
dengan orang lain dan sesuatu keinginan untuk menghindari orang lain; dengan cara yang
dominan pada saat tertentu dan pada saat yang lain menjadi lebih kuat. Sebagai garnbaran
ringkasnya adalah ketika sescorang menjadi sendirian untuk jangka waktu yang terlalu lama
(isolasi) dan menjadi satu atau bersama-sama dengan orang lain dalam jangka waktu yang
terlalu Jama juga adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan.
Untuk menterjemahkan pandangan ini ke dalam desain praktis adalah hal yang tidak
mudah. Prinsip umum yang kita pakai adalah merancang suatu lingkungan yang responsif,
67
(epee om oor tena enn RR RRR A RE PEER,
yang memungkinkan kemudahan bagi keterpisahan maupun kebersamaan. Suatu ruangan
seyogyanya responsif terhadap perubahan keinginan pemakainya untuk berhubungan atau
tidak berhubungan dengan orang lain sesuai dengan kebutuhan. Lingkungan yang meriekankan
kemungkinan sedikitnya interaksi atau justru kemungkinan lebih banyak menerimainformasi
adalah lingkungan yang dianggap statis dan tidak responsif terhadap perubahan kebutuhan
privasi. Seorang perancang hendaknya mencoba menciptakan lingkungan yang memungkinkan
adanya perbedaan tingkat kendali dalam hubungannya dengan orang lain, Salah satu contoh
adalah pintu, yang merupakan ontoh sederhana dari desain yang responsif dan memungkinkan
pengaturan interaksi sosial, Terbukanya pintu berarti suatu keinginan untuk kontak sosial,
sedangkan tertutupnya pintu berarti keinginan untuk tidak berhubungan dengan orang lain
(Altman, 1975).
Pada hakikatnya, dinding-dinding dan pintu-pintu yang disediakan oleh rumah kita
besar kemungkinannya adalah mekanisme paling umum yang sesungguhnya kita gunakan
untuk mengelola privasi. Bahkan beberapa studi melaporkan bahwa terdapat hubungan
antara individu dengan privasinya melalui faktor eksterior (ruang luar), seperti ukurannya
yang besar atau jaraknya yang lebar dengan tetangga. Jika suatu rumah berukuran besar,
"maka privasi bukanlah menjadi masalah, kecuali jika karena terlalu besarnya rumah dengan
sedikitnya jumlah anggota keluarga justru akan menjadikan anggota keluarga menjadi
terisolasi dan teralinasi satu sama lain (Gifford, 1987).
Sependapat dengan Altman, Lang (1987) melihat bahwa penggunaan dinding, tirai
pembatas, jarak, ataupun pembatas teritorial secara simbolis atau nyata, merupakan mekanisme
untuk mencapai privasi dimana seorang perancang dapat mengembangkannya dalam berbagai
macam cara. Permukaan dinding dengan berbagai macam sifat seperti tembus cahaya,
tembus pandang, atau tembus suara akan dapat menghubungkan jalannya informasi dari
suatu tempat ke tempat lain, atau dari yang kurang privasinya ke yang lebih banyak
privasinya.
‘Suatu desain rumah tinggal dapat mempengaruhi perasaan privasi secara langsung ialah
dengan cara meningkatkan atau mengurangi kemungkinan melihat dan dilihat oleh orang
Jain. Ini mengacu kepada penyerapan visual, dimana kesan privasi lebih sulit dicapai ketika
orang masih bisa dilihat. Jika anda hidup di rumah kaca dan bisa melihat orang di luar atau
sebaliknya, perasaan privasi anda akan lebih kecil dibandingkan jika anda dapat
menghalanginya. Sesuai dengan hal ini, suatu penelitian menunjukkan bahwa pembatas yang
menghalangi pandangan orang lain akan mengurangi pengaruh orang tersebut sementara
pembatas yang tidak menutup pandangan (misalnya panel tembus pandang) tidak mengura-
ngi pengaruh orang lain (Fisher dkk., 1984). Tetapi apakah privasi dapat dicapai hanya
dengan pembatas fisik yang mengalangi penglihatan saja ?
Salah satu studi menarik pernah dilakukan oleh Leo Kuper (dalam Lang, 1987) terhadap
Pengembangan rumah-rumah di Inggris. Dalam studinya terhadap rumah kopel, Kuper
menemukan bahwa para penghuni mendapati kesulitan dalam mencapai privasi, karena
walaupun privasi secara visual mereka tercapai tetapi tidak demikian halnya dengan privasi
secara pendengaran. Pengaturan dinding tidak mencukupi untuk mencapai privasi, lokasi
68
pintu seperti itu membuat sulit untuk menempatkan posisi tempat tidur selain seperti yang
terlihat dalam gambar 2.6. tersebut. Para penghuni mengeluh bahwa mereka mendengar
terlalu banyak apa yang terjadi pada tetangga mereka dan agaknya kehadiran tetangga akan
menghalangi perilaku mereka sendiri.
Privasi dalam Konteks Budaya. Menurut Altman (1975) “ruang keluarga” di dalam rumah
pada rumah-rumah di daerah pinggiran Amerika Serikat umunya dijadikan tempat untuk
berinteraksi sosial dalam keluarga. Rumah-rumah di sana, menggunakan ruang-ruang
tertentu seperti ruang baca, ruang tidur, dan kamar mandi sebagai tempatuntuk meyendiri dan
tempat untuk berpikir. Dengan cara itu seseorang yang tidak memiliki cukup ruang di dalam
rumah dapat memperoleh privasi secara maksimal. Selama ini kita terpaku bahwa suatu
desain tertentu memiliki fungsi tunggal, sebagai ruang untuk berinteraksi secara terbatas atau
sebaliknya secara berlebihan, tetapi bukan untuk fungsi keduanya sekaligus. Oleh karena itu,
untuk mencapai privasi yang herbeda kita harus pergi ke suatu tempat lain, Kita tidak pernah
berpikir untuk memiliki ruang yang sama untuk beberapa fungsi serta dapat diubah sesuai
dengan kebutuhan kita. Untuk berubahnya kebutuhan, kita tidak perlu mengubah tempat.
Prinsip ini telah dipakai oleh orang Jepang, dimana di dalam rumah dinding dapat dipindah-
pindahkan ke luardan ke dalam ruangan, Satu area yang sama kemungkinan dapat difungsikan
untuk makan, tidur, dan interaksi sosial dalam waktu yang berbeda. Logikanya adalah bahwa
penggunaan lingkungan yang mudah diubah-ubah tersebut adalah cara agar lingkungan
tersebut fleksibel terhadap perubahan kebutuhan privasi.
Ruang Tidur Ruang Tidur
Ruang Tamu
Gambar 2.6, Pelanggaran dari Beberapa Persyaratan Privasi
Sumber: Kuper (dalam Lang, 1987)
69
1a SAN EERE PR EE A REE ORS NE
LATIHAN SOAL
1. Apa fungsi privasi bagi individu?
2. Apa yang terjadi jika:
a, privasi lebih besar dari yang diinginkan
b. _privasi lebih kecil dari yang diinginkan?
3. Jelaskan kaitan antara ruang personal, teritorialitas, dan kesesakan terhadap privasi?
4. Apakah konsep privasi dapat diterapkan pada masyarakat Kalimantan, Jawa, dan Bali?
Apakah mereka-mereka ini dapat mencapai privasi?
5. Bagaimana cara orang Jepang mencapai privasi?
70
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Personal/ Interpersonal SpaceDocument10 pagesPersonal/ Interpersonal SpaceIzzai Anwar YadNo ratings yet
- Bab2-Pendekatan Teori Dan Metode Penelitian Psikologi LingkunganDocument14 pagesBab2-Pendekatan Teori Dan Metode Penelitian Psikologi LingkunganIzzai Anwar YadNo ratings yet
- Bab1 Arsitekture Dan PsikologiDocument14 pagesBab1 Arsitekture Dan PsikologiIzzai Anwar YadNo ratings yet
- Bab5-Ruang Personal Dan Teritorialias PDFDocument11 pagesBab5-Ruang Personal Dan Teritorialias PDFmulia safrinaNo ratings yet
- Suplement 3Document13 pagesSuplement 3Izzai Anwar YadNo ratings yet
- Suplemen 1Document4 pagesSuplemen 1Izzai Anwar YadNo ratings yet
- Materi Kuliah 7BDocument7 pagesMateri Kuliah 7BIzzai Anwar YadNo ratings yet
- Buku PA Versi 2007Document57 pagesBuku PA Versi 2007Izzai Anwar YadNo ratings yet
- Pengumuman Seleksi Asn Sambas Tahun 2021Document50 pagesPengumuman Seleksi Asn Sambas Tahun 2021Izzai Anwar YadNo ratings yet
- FS2022Document5 pagesFS2022Izzai Anwar YadNo ratings yet
- BISMILLAHDocument71 pagesBISMILLAHIzzai Anwar YadNo ratings yet
- Rulebook DC: MLBBDocument8 pagesRulebook DC: MLBBIzzai Anwar YadNo ratings yet