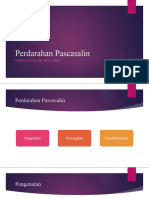Professional Documents
Culture Documents
Bahan Masalah
Bahan Masalah
Uploaded by
BIDAN KSAOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Bahan Masalah
Bahan Masalah
Uploaded by
BIDAN KSACopyright:
Available Formats
Pengentasan kemiskinan di Indonesia
A. Latar belakang
Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipungkiri
hadir di tengah-tengah masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
Berbagai upaya penanggulangannya pun telah dilakukan pemerintah melalui
berbagai kebijakan, diantaranya berupa bantuan langsung dan program
pemberdayaan yang diharapkan mampu menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat kelas bawah agar mampu mandiri baik secara ekonomi, social maupun
pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan
pemerintah yang komperenehsif dan bersinergis antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat dalam memberdayakan masyarakat
miskin tersebut. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada berbagai
faktor, diantaranya adalah pemahaman kebijakan dan masyarakat menerima
kebijakan tersebut secara sadar. Di samping itu, kebijakan yang kurang efektif dan
efisien sejatinya dapat dikaji kembali dan direvisi bila diperlukan, sehingga kebijakan
yang ada benar-benar mampu mangatasi permasalahan di masyarakat.
Menurut Dunn (2000:21) Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima
prosedur umum yaitu:
1. Perumusan Masalah (Definisi)
2. Peramalan (Prediksi)
3. Rekomendasi (Preskripsi)
4. Pemantauan (Deskripsi)
5. Evaluasi
B. Dasar Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Program
perlindungan sosial yang meliputi:
a) Program simpanan keluarga sejahtera
b) Program Indonesia Pintar
c) Program Indonesia Sehat
C. Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program perlindungan
sosial di Indonesia
Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan
sosial untuk menurunkan tingkat kemisikinan serta memperkecil kesenjangan
multideimensional. Perlindungan sosial sangat penting dalam menanggulangi
problematika kemiskinan. Hingga saat ini terdapat berbagai macam definisi
perlindungan sosial. Keragaman ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan
politik suatu negara. Berikut adalah beberapa dari sekian banyak definisi yang
digunakan oleh berbagai institusi dan negara. Perlindungan sosial didefinisikan
oleh Asian Development Bank‟s (ADB‟s, 2001) sebagai “the set of policies and
programs designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labor
markets, diminishing people’s exposure to risks, and enhancing their capacity to
protect themselves against hazards and the interruption loss of income”
(perangkat kebijakandan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan
dan kerentanan dengan mempromosikan secara pasar tenaga kerja, mengurangi
terhadap risiko masyarakat, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk
melindungi diri terhadap bahaya dan hilangnya gangguan pendapatan). ADB
membagi perlindungan sosial ke dalam 5 (lima) elemen, yaitu: (1) pasar tenaga
kerja (labor markets); (2) asuransi sosial (social insurance); (3) bantuan sosial
(social assitance); (4) skema mikro dan area-based (micro and area based
schemes) untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan (5) perlindungan
anak (child protection).
Namun, menurut Bank Dunia, konsep yang digunakan oleh ADB dalam
membagi perlindungan sosial tersebut masih tradisional. Bank Dunia
mendefinisikan perlindungan sosial sebagai: (1) jejaring pengaman; (2) investasi
pada sumberdaya manusia; (3) upaya menanggulangi pemisahan sosial; (4)
berfokus pada penyebab, bukan pada gejala; dan (5) mempertimbangkan
keadaan yang sebenarnya. Menanggapi konsep ADB dan Bank Dunia,
menyejajarkan perlindungan sosial dengan jejaring pengaman bisa berarti
menyempitkan makna perlindungan sosial itu sendiri. Sementara, menurut ILO
(2002), perlindungan sosial merupakan konsep yang luas yang juga
mencerminkan perubahan-perubahan ekonomi dan sosial pada tingkat
internasional. Konsep ini termasuk jaminan sosial (social security) dan skema-
skema swasta. Lebih jauh, dijelaskan bahwa sistem perlindungan sosial bisa
dibedakan dalam 3 (tiga) lapis. Lapis Pertama, merupakan jejaring pengaman
sosial yang didanai penuh oleh pemerintah; Lapis Kedua, merupakan skema
asuransi sosial yang didanai dari kontribusi pemberi kerja (employer) dan pekerja;
dan Lapis Ketiga, merupakan provisi suplementari yang dikelola penuh oleh
swasta. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa definisi tersebut berdasarkan
kontributor dana dalam tiap skema. Sedangkan, Conway, de Haan dan Norton
(Barrientos dan Hulme, 2008:5).
Perlindungan sosial terutama dipahami sebagai kerangka kebijakan yang
menjelaskan "tindakan publik yang diambil sebagai tanggapan terhadap tingkat
kerentanan, risiko, dan kekurangan yang dianggap tidak dapat diterima secara
sosial dalam pemerintahan atau masyarakat" Conway, Haan dan Norton (dalam
Barrientos dan Santibanez, 2009: 2) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai
„public actions taken in response to levels of vulnerability, risk and deprivation,
which are deemed socially unacceptable within a given polity and society ‟.
Selanjutnya, Conway, Haan dan Norton (Barrientos dan Santibanez, 2009:2)
menjelaskan perlindungan sosial memiliki tiga komponen utama: social insurance,
social assistance, and labour market regulation. Social insurance refers to
programmes providing protection against life course and employment hazards,
financed out of contributions from employers, workers and governments. Social
assistance includes programmes supporting those in poverty, and is largely
financed from government revenues. Labour market regulation includes protection
against unfair dismissal, and the right to voice and representation of workers.
Banyak orang memberikan penilaian bahwa perlindungan sosial yang
dilakukan negara bersifat mahal, boros dan karenanya kontradiktif dengan
pembangunan ekonomi. Buku berbasis riset yang ditulis Adam, Hauff, dan John
(2002:17) itu menunjukkan hal yang sebaliknya, “... it is often forgotten in this
context that social security can also make a positive contribution to the economic
development of an industrialized or developing nation ... Social security should
therefore always be a central component of economic development policy”.
Dengan demikian, pernyataan bahwa perlindungan sosial yang berbasis negara
tidak bermanfaat bagi pembangunan ekonomi adalah asumsi yang keliru, karena
tidak didasari landasan teori dan penelitian empiris.
Kebijakan jaminan sosial negara yang diterapkan dari negara maju dan
berkembang telah: a. Memberi kontribusi penting bagi pencapaian tujuan ideal
bangsa, seperti keadilan sosial dan kebebasan individu, dan karenanya
mendukung kedamaian dan keamanan sosial; b. Mencegah atau memberi
konvensasi terhadap dampak-dampak negatif yang timbul dari sistem produksi
ekonomi swasta, seperti perusahaan bisnis dan asuransi swasta; c. Menciptakan
modal manusia (human capital) dan pra-kondisi bagi penguatan produktivitas
ekonomi mikro dan makro, dan karenanya memberi kontribusi bagi pembangunan
ekonomi jangka berkelanjutan (Adam, Hauff, dan John, 2002:18).
Senada dengan temuan di atas, Lampert dan Althammer (2001:436) juga
menyatakan banyak kritik telah salah menilai dan mengesampingkan bukti-bukti
sejarah yang menunjukkan betapa jaminan sosial negara telah membangun dan
merealisasikan masyarakat yang humanis dan tingkat kesejahteraan sosial yang
tinggi. Abramovitz (1981:2), memberi bukti yang jelas lagi, ketika mengatakan
bahwa perluasan peran ekonomi pemerintah, termasuk dukungannya terhadap
pencapaian pendapatan minimal, perawatan kesehatan, asuransi sosial, dan
elemen-elemen lain dari sistem negara kesejahteraan, telah sampai pada satu
kesimpulan bahwa jaminan sosial negara adalah bagian dari proses produksi itu
sendiri.
Berkaitan dengan hal di atas, maka kebijakan perlindungan sosial khususnya
bagi masyarakat miskin adalah dibutuhkan. Kebijakan perlindungan sosial (social
protection policy), menurut Wiranto (2002) adalah berkaitan dengan upaya
memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, utamanya
kelompok masyarakat yang paling miskin (fakir miskin, orang jompo, anak
terlantar, cacat) kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana
alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial. Yang diarahkan melalui
mekanisme tabungan kelompok (pood funds). Kebijakan tersebut meliputi:
1) Meningkatkan penanganan jaminan sosial anak terlantar dan fakir miskin;
2) Penanganan masyarakat miskin pada kawasan terisolir dan terbelakang;
3) Peningkatan kemampuan jaringan lembaga perlindungan sosial masyarakat
pemerintah daerah dalam pengelolaan jaminan sosial khususnya pendidikan,
dan kesehatan; dan
4) Mengembangkan system jaminan social terutama pada tingkat daerah yang
mampu melindungi masyarakat dalam menangani fakir miskin, anak-
anakterlantar, orang jompo, masa pensiun, bencana alam, krisis ekonomi,
dan konflik sosial (Wiranto, 2002).
Agar efektif dan berkelanjutan, menurut Suharto (2009:55-56) kebijakan
perlindungan sosial bagi masyarakat miskin perlu mempertimbangkan beberapa
prinsip sebagai berikut:
1) Skema-skema yang dibangun mampu memberikan perlindungan yang
memadai bagi penerima pelayanan;
2) Terhindar dari penciptaan budaya ketergantungan di antara penerima
pelayanan;
3) Mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan,
implementasi, dan pengawasan program;
4) Sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial makro,
khususnya yang menyangkut kemampuan anggaran, kebijakan fiskal, dan
strategi nasional investasi sosial;
5) Diselenggarakan oleh lembaga yang tepat dan kredibel, serta ditunjang oleh
teknologi dan sumberdaya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi
tinggi;
6) Perumusan kebijakan dan program sebaiknya dilakukan pada saat situasi
sosial dan ekonomi sedang baik (normal) dan bukan saat kritis, sehingga
mampu mencegah dan mengatasi situasi yang memburuk.
Permasalahan
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui program perlindungan sosial
bagi masyarakat miskin masih menghadapi beberapa permasalahan, seperti:
1) Masih banyaknya rakyat miskin yang belum masuk dalam kepesertaan
program perlindungan sosial. Data kepesertaan masyarakat miskin belum jelas
dan valid sehingga banyak orang miskin dan tidak mampu yang tidak terdata
dengan baik yang seharusnya terdaftar dan memiliki hak untuk mendapatkan
program perlindungan sosial yaitu program simpanan keluarga sejahtera,
program Indonesia sehat dan program Indonesia pintar. Data masyarakat
miskin itu adalah dinamis, kerapkali mengalami perubahan. Orang yang
tadinya hampir miskin (near poor) bisa jatuh menjadi miskin (poor) atau
sebaliknya, yang tadinya miskin menjadi tidak miskin. Hal tersebut apabila
pemetaan (mapping) terhadap mereka tidak dilakukan secara baik, maka
mereka tidak terupdate secara jelas dan valid.
2) Jumlah anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk
pembiayaan program Perlindungan Sosial khususnya pada program Indonesia
sehat di Daerah masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah
masyarakat miskin yang ada. Eks peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan
Masyarakat) dan eks Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) seharusnya
sudah bertransformasi ke BPJS Kesehatan peserta PBI (Penerima Bantuan
Iuran) yang preminya dibayar oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah.
3) Tidak maksimalnya sosialisasi program perlindungan sosial yaitu program
simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia sehat dan program
Indonesia pintar di tingkat bawah (grass root) menyebabkan masyarakat
penerima manfaat, khususnya masyarakat miskin peserta Penerima Bantuan
kurang memahami manfaat Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program
Indonesia Sehat dan Program Indonesia Pintar.
Peramalan (Prediksi)
1) Apabila masalah pendataan dan pemetaan terhadap masyarakat miskin tidak
tidak mendapatkan formulasi yang tepat untuk penyelesaiannya dalam jangka
waktu tertentu, maka tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak
masyarakat miskin yang tidak terdata dalam kepesertaan program
Perlindungan Sosial tersebut yang imbasnya mereka tidak akan mendapatkan
manfaat dari program dimaksud. Masalah lain yang akan timbul adalah data
yang dipublikasi oleh pemerintah mengenai kemiskinan di Indonesia tidak
akan valid, karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdata oleh
pemerintah.
2) Apabila masalah Pembiayaan ini tidak segera diselesaikan, akan semakin
banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan pelayanan, khususnya
pada pelayanan kesehatan yang notabene membutuhkan anggaran yang
sangat besar. Tentu ini bukan suatu keberhasilan sebuah program
pengentasan kemiskinan, apabila masih banyak orang miskin yang tidak
mendapatkan hak-haknya.
3) Apabila sosialisasi tidak sampai pada masyarakat penerima bantuan, maka
yang akan terjadi adalah masyarakat tidak faham dengan hak apa yang akan
mereka dapatkan. Hal ini menyebabkan program pengentasan kemiskinan
tersebut tidak berjalan efektif seperti yang diharapkan.
Rekomendasi
Beberapa hal yang perlu direkomendasikan adalah sebagai berikut:
1) Membangun data base kepesertaan penerima bantuan dengan menggunakan
metodologi mapping yang tepat. Data kemiskinan semestinya dapat
mencerminkan jumlah yang lebih pasti, siapa yang miskin, di mana mereka,
dan mengapa mereka miskin. Apabila data kemiskinan yang berbasis pada
kriteria spesisfik daerah dapat diperoleh, maka strategi dan upaya-upaya untuk
mengatasi masalah kemiskinan akan menjadi jelas. Oleh karena itu, basis data
kemiskinan adalah hal yang penting untuk disusun secara lengkap, akurat, dan
akuntabel yang dapat dijadikan acuan dasar kebijakan sosial bagi masyarakat
miskin.
2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pembiayaan
kesehatan bagi Penerima bantuan untuk menjangkau kepesertaan yang lebih
luas sesuai dengan hak-hak mereka.
3) Pembentukan tim sosialisasi yang professional dan menjangkau seluruh
wilayah Indonesia. Sehingga seluruh lapisan masyarakat mengetahui akan
tujuan sebuah program yang pada akhirnya masyarakat, khususnya
masyarakat miskin tahu akan hak-hak mereka.
Pemantauan (Deskripsi)
Program Perlindungan Sosial adalah sebuah program yang diharapkan
mampu menjadi andalan pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan di Indonesia. Meskipun pada prosesnya program ini menemui
beberapa kendala, tidak serta merta membuat program ini terhenti dan sia-sia.
Cukup banyak pencapaian yang dihasilkan dari program ini, beberapa
diantaranya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Menurut
data BPS, jumlah penduduk miskin berkurang 1,18 juta jiwa dalam kurun waktu
satu tahun (dari tahun 2016-2017). Upaya peningkatan efektifitas dan penguatan
program-program perlindungan sosial juga dilakukan melalui perluasan cakupan
sasaran penerima manfaat program keluarga harapan menjadi 10 juta keluarga
dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang.
Selain itu, program Perlindungan Sosial juga mendapatkan sentimen yang
cukup positif di masyarakat. Opini masyarakat pun beragam meminta agar
Pemerintah dapat meningkatkan performa dalam menjalankan Program tersebut
agar di masa mendatang mampu menjadi jawaban atas permasalahan-
permaslahan yang ada pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah.
Evaluasi
Pada akhirnya mengenai Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang
dicanangkan oleh Pemerintah dalam bentuk Program Perlindungan Sosial yang
mencakup Kesejahteraan, Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat miskin
tidak berjalan tanpa hasil. Program tersebut memiliki potensi yang cukup besar
dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia hal ini terbukti dengan
turunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Data BPS menyebutkan, per
September 2016 terdapat 27,76 juta penduduk miskin sedangkan per September
2017, jumlah penduduk miskin turun menjadi 26,58 juta jiwa, atau berkurang 1,18
juta jiwa dalam setahun. Angka ini cukup tinggi mengingat rata-rata jumlah
penurunan penduduk miskin dalam kurun waktu 10 tahun terakhir adalah berkisar
pada 500 ribu jiwa saja.
Daftar Pustaka
Adam, E., Hauff, M. & John, M. (2002). Social Protection in Southeast and
Asia, Singapore: Friedrich Eber Stiftung
Badan Pusat Statistik. 2017. Survei Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk
20016/2017, Jakarta: BPS
Jurnal
Abramovitz, M. (1981). “Welfare Quandaries and Productivity Concerns” dalam
jurnal Abu Huraerah, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14, No. 2, Desember
2015 Penerbit Universitas Pasundan Bandung
Barrientos, A. & Santibanez, C. (2009). New Forms of Social Assistance and
the Evolution of Social Protection in Latin America dalam jurnal Abu Huraerah,
Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14, No. 2, Desember 2015 Penerbit
Universitas Pasundan Bandung
Suharto, E. (2009). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia
(Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan) dalam jurnal
Abu Huraerah, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14, No. 2, Desember 2015
Penerbit Universitas Pasundan Bandung
Peraturan Perundang – Undangan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- PI - KOICA-YONSEI Masters Degree Program in Control of Infectious Disease - FinalDocument28 pagesPI - KOICA-YONSEI Masters Degree Program in Control of Infectious Disease - FinalBIDAN KSA100% (1)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Digital Ethic 2023Document16 pagesDigital Ethic 2023BIDAN KSANo ratings yet
- AI Indikator Mutu KlinisDocument5 pagesAI Indikator Mutu KlinisBIDAN KSANo ratings yet
- Perdarahan PascasalinDocument32 pagesPerdarahan PascasalinBIDAN KSANo ratings yet
- Makalah Permasalahan Ekonomi - 114328Document37 pagesMakalah Permasalahan Ekonomi - 114328BIDAN KSANo ratings yet
- Kehamilan Resiko TinggiDocument11 pagesKehamilan Resiko TinggiBIDAN KSANo ratings yet
- Perkembangan Dan Pertumbuhan RemajaDocument14 pagesPerkembangan Dan Pertumbuhan RemajaBIDAN KSANo ratings yet
- Kota Bersih 2022Document29 pagesKota Bersih 2022BIDAN KSANo ratings yet
- Konsep Dan Teori Kebijakan Publik Merujuk Pada Pendapat para PakarDocument20 pagesKonsep Dan Teori Kebijakan Publik Merujuk Pada Pendapat para PakarBIDAN KSANo ratings yet
- SK Dirut TTG Pedoman Keselamatan Pasien RSDocument63 pagesSK Dirut TTG Pedoman Keselamatan Pasien RSBIDAN KSANo ratings yet
- Pedoman k3 Puskesmas UmbulsariDocument18 pagesPedoman k3 Puskesmas UmbulsariBIDAN KSANo ratings yet
- Makasih Udah Pesan Gofood: Total DibayarDocument1 pageMakasih Udah Pesan Gofood: Total DibayarBIDAN KSANo ratings yet