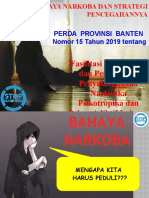Professional Documents
Culture Documents
Jurnal 1
Jurnal 1
Uploaded by
katong supriadi0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views8 pagesOriginal Title
jurnal 1
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views8 pagesJurnal 1
Jurnal 1
Uploaded by
katong supriadiCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 8
TIKEL ILWIAH
113
Metafora Politik sebagai Pendekatan Manajemen
(Sebuah Alternatif Pendekatan Manajemen)
‘SISWANTO
Pusitbang Sistom dan Kebjakan Kesehatan
‘Badan Peneltian dan Pengembangan Kesehatan, Surabaya
V ABSTRACT
‘The aim ofthis article isto present poktical metaphor as a managerial approach inorder ta provide a better understanding on
‘now to practice such a metaphor in areal management practice. The theories of managemant can be categorized ito two schools of
thought, 8. instrumental account and social action account. The analysis of insttumental account started om whe organization, winereas
the analysis of social action account started from the actors social action’. Intumertal account of organization saw organization as
‘being pro-existont and independent of people's perception and action. inthis account, managerial works were seen as boing noua,
‘predictable, rational, and tree trom manager's interests. On the contrary, social action account of organization saw crganizaton asthe
‘Product of people’s action in negotiating meanings and interests. n this account, managerial works were seen a3 partisan. not neutral,
‘Sometimes katona, and not tre from manager's interests. One of the derivatives of social action account wae poltical methapor,
‘besides cultural metaphor Poltical metaphor saw organization asa politcal entity that avery acto including managers, was trying 10
‘negotiate, bargain and compromize thei interests in every organizational event by exercising power. Evely actor, intuding manager,
‘played within the area of sulace poltics to compete thei interests. Overt interests would always be propagated and advocated to other
{actors by managers in erder to achieve manager" ntrets nthe light of politcal metaphor, an elective manager isthe one who can
‘propagate overt interests to other actors and can keep covert intrests unknown by others,
Keywords: poltical metaphor, organization, management, power
PENDAHULUAN
Meskipun hampir setiap orang menyadari bahwa dalam kehidupan organisasi terdapat ‘polltk’
tetapi tampaknya cara pandang politik tentang kehidupan organisasi ini belum banyak diperkenalkan
pada pelatinan manajemen, seperti diklatpim maupun perkuliahan di manajemen kesehatan. Untuk
sebagian orang, membicarakan polik organisasi mungkin dianggap tabu, karena diskursus politk selalu
‘mengaitkan perilaku (aksi sosial) dengan motif dan kepentingan pribadi atau kelompok. Politik tidak harus
dikaitkan dengan sesuatu yang negatif atau merusak; justru politik harus dianggap sebagai alat (means)
untuk menyatukan perbedaan kepentingan dari berbagai pihak guna menghasilkan interaksi sosial yang
produktif, sebagaimana diungkapkan oleh Aristoteles (Morgan, 1996).
Melihat aktivitas organisasi sebagai altivitas politik merupakan penyegaran tethadap pemahaman
kehidupan ‘organisasi' yang selalu didominasi oleh cara pandang normatif, yang analisisnya mengabaikan
‘motif dan kepentingan aktor yang terlibat dalam kehidupan organisasi. Memahami organisasi dengan
perspektif poltik akan mengantarkan praktisi manajemen paca pemahaman tentang sisi lain dari kehidupan
organisasi; menyadarkan manajer bahwa ia hanyalah salah satu aktor dalam permainan politk, sehingga
ia akan mampu menyusun taktik dan strategi yang tepat untuk mempertahankan keteraturan (order)
‘organisasi yang dipimpinnya.
Politic didefinisikan oleh Dahl (1991) sebagai setiap pola hubungan antarmanusia yang kokoh,
dan melibatkan, secara cukup mencolok, kendali, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan (power).
Dengan menggunakan definisi ini, maka dapat dikatakan bahwa polik tidak hanya terjadi pada sistem
pemerintahan, namun politi juga terjadi pada klub-klub pribadi, badan usaha, organisasi keagamaan,
kelompok suku primitif, marga, dan bahkan pada unit keluarga. Pusat analisis politik adalah bagaimana
‘seorang aktor dapat mempengaruhi aktor lain, sehingga aktor terakhir menuruti kernauan aktor pertama,
‘Dalam kontes saling mempengaruhi ini, maka tiap aktor akan saling beradu ‘power’ (kekuatan) untuk
"memenangkan ‘kepentingan’, dengan taktik memainkan kekuatannya masing-masing
Panclangan sederhana tentang manajemen adalah proses pengelolaan man, money, materials,
machine, method, dan market (6 M) dalam rangka mencapai tujyan organisasi. Sudah tentu, definisi ini
‘dapat saja diperdebatkan karena bagaimana orang memaknai ‘manajemen’ sangat tergantung bagaimana
ia meoginterpretasixan (memahami) entitas yang namanya ‘organisasi’ itu sendiri..Menurut tecri polit
‘organisasi tak ubahnya bagaikan gelanggang politik yang terdiri dari banyak aktor dan koalisi yang
‘saling berebut, tawar menawar dan negosiasi berbagai kepentingan untuk mendapatkan kompromi dan
‘komitmen yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun demikian, karena entitas ‘organisasi' yang bersifat
114 J. Adm. Kebijak. Kesehat., Vol. 4, No. 3, Sept-Des 2006: 113-11
Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan metafora sebagai “pemakaian kata atau kelompok
kata bukan dengan arti yang sebenamya, melainkan sebagai deskripsi persamaan atau perbandingan*
(Balai Pustaka, 1990). Morgan (1996) dan Bolman & Deal (1991) menyatakan bahwa kelahiran teori
crganisasi dan manajemen tak ubahnya dengan metafora yang mencoba mendeskripsikan atau melihat
apa itu organisasi dan apa itu manajemen dengan ‘pertimpamaannya’ sendiri-sendiri, Dari beragam.
metafora teori organisasi dan manajemen, salah-satunya adalah metafora poltik. Tulisan ini mencoba
uk memberikan pemahaman tentang bagaimana menggunakan metafora politik untuk menambah
koleksi ‘foo!' manajemen bagi praktisi manajemen, dalam rangka mengelola orgariisasi menjadi lebih
bak, Harus dipahami bahwa manajemen yang efeitf adalah penguasaan seluruh metafora, dan mampu
menggunakan setiap metafora pada ‘event’ yang tepat (contingem).
DUA CARA PANDANG TEORI MANAJEMEN
Realitas sosial yang bemama ‘organisasi’ dan ‘manajemen’ telah dimaknai oleh berbagai pengemuka
teori manajemen sesuai dengan latar belakang dari pengemuka teori. Seorang engineer akan melihat
‘organisasi sebagai mesin, behaviorist melihatnya sebagai sasana memenuhi kebutuhan manusia, biologist
melihatnya sebagai sistem organisme, mathematician melihatnya sebagai entitas matemattk, political
scientist melihatnya sebagai wahana politik, dan akhirnya anthropologist melihatnya sebagai entitas
budaya, Pemaknaan melalui perumpamaan yang berbeda-beda inilah yang disebut dengan metalora.
Dinamakan metafora karena setiap teori mencoba melihat ‘organisasi’ dan ‘manajemen’ menurut kaca
matanya masing-masing, tanpa melihat realitas prektik manajemen yang senyatanya.
Sebelum dibahas lebih mendalam tentang metafora poliik ada baiknya dijelaskan dulu taksonomi
dari keseluruhan metafora, Degeling (1997) membagi semua hirukcpikuk metafora teori organisasi dan
manajemen menjadi dua kelompok cara pandang, yakni cara pandang instrumental dan cara pandang
aksi sosial.
Dalam cara pandang instrumentel, organisasi dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan, sehingga
organisasi bersifat pre-existent (organisasi sudah ada lebih dulu sebelum aksi para anggotanya);
sementara manajemen dilhat sebagai aktivitas yang rasional, sekuensial (urut), prediktif, dan bebas deri
kepentingan aktor. Dengan kata lain, aktivitas manajemen adalah penguasaan ilmu yang bersifat ‘tekrik’.
Degeling (1997) membagi cara pandang instrumental ke dalam empat sub-kelompok teori, yakni teori
manajemen klasik (rasional), manajemen kemanusiaan, manajemen sistem organik dan manajemen
kontinjensi (contingency).
Karena titik tolak bahasan berangkat dari ‘organisasi', maka diskursus dalam cara pandang
instrumental ini mengarah kepada ‘bageimana seharusnya mendesain dan mengelola organisas', misalnya
saja, tujuan organisasi (goals), struktur organisasi (departemenisasi), tugas, wewenang, peran, fungsi,
efektvitas, efisiensi, perencanaan, penggerakan, motivasi, monitoring, evaluasi, dan sebagainya.
Sebagaimana diungkapkan oleh Weber (dalam Worsley, 1981), aksi sosial (social action) adalah
tindakan seseorang dalam konteks melekukan hubungan sosial, yang notabene tidak terlepas dari
interpretasi terhadap realitas, motif dan kepentingan individu). Analisis pada cara pandang aksi sosial
imulai dari ‘aktor yang ada dalam organisasi; dengan demikian diskursus dalam cara pandang ini adalah
membahas “apa yang dikerjakan para aktor dalam membangun interaksinya dengan aktor lain sehingga
terbentuklah organisasi (getting organized)”. Oleh karena itu, organisasi dilihatnya sebagai produk dari
aksi para aktor yang terlibat (nan pre-existent), dan perilaku para aktor bukanlah semeta-mata produk
mangjer tapi lebih kepada produk individual masing-masing aktor dalam memaknai realitas dan mengejar
kepentingannya.
Direktur sebuah organisasi adalah orang yang secara kebetulan saja mendapatkan otoritas formal
untuk memimpin organisasi. Namun demikian, dalam cara pandang aksi sosial, siapapun dapat menjadi
‘manajer’ atau /eader dalam suatu organisasi, tergantung kemampuan seseorang untuk mempengaruhi
innya, apakah ia bisa menjadi orang yang paling berpengaruh atau tidak. (Degeling, 1997; Giddens,
Karena cara pandang ini menjelaskan apa yang sebenamya dikerjakan oleh para aktor termasuk
idupan nyata organisasi, maka cara pandang ini sering disebut dengan pemikiran
iit, Hal ini berbeda dengan cara pandang instrumental yang berusaha membangun tear
kan resep kepada para mangjer, sehingga seting disebut sebagai pemikiran manajemen
.u normatit. Cara pandang aksi sosial diwakil oleh apa yang sering disebut dengan manajemen,
budaya (kultura!) dan manajemen poll. :
Perdebstan cara pandang instrumental dengan cara pandang aksi sosial dalam lima manejemen
sesungguhnya analog dengan perdebatan panjang tentang terbentuknya struktur sosial dalam sosiologl.
Pada sebagien teor|, misalnya Durkheim (dalam Worsley, 1991). menyatakan bahwa perilaku individu:
ipengaruni oleh hukum umum dari suatu struktur sosial; sementara teori lainnya, Weber misalnya,
menyatekan bahwa perilaku individu berawal dari motif-motif dan pemaknaan realitas yang berasal dari
dirinya sendiri, Dengan mencermati apa yang telah diuraikan diperoleh pemahaman yang semakin jelas,
bahwa semua teori manajemen telah menggunakan ‘metaiora’ dalam melihat apa itu organisasi dan apa
itu manajemen, yang berakibat pada pemaknaan parsial ketimbang pemaknaan yang utuh. Perbandingan
‘cara pandang instrumental dan cara pandang aksi sosial dideskripsikan pada Tabel 1
Tabel 1.
Perbandingan cara pandang instrumental dan cara pandang aksi sosial
tentang organisasi dan manajemen*
Definisi tentang
Konsep struktur
tidak tergantung dari persepsi,
pemahaman, dan kepentingan
dari aktor di dalam maupun di luar
organisasi.
Aktivitas manajemen diasumsikan neta,
peran, fungsi, perencanaan,
departemenisasi, penggerakan,
maotivasi, monitoring, evaluasi,
efektivitas, efisiensi dan sejenisnya
Struktur organisasi adalah bagan
*) Diadopsi dari Management of Organization (Degeling,1997) ~
‘METAFORA POLITIK — ‘
Metafora polit adalah salah satu metafora dalam cara pandang ‘aksi sosial di samping motafora
‘budaya_ (1996) misainya, melihat organisasi sebagai wahana atau gelartggang poltk tempat
en oleh para anggotanya. Dengan menggunakan metafora poliik, maka perilaku
bukan saja oleh arahan
Domain ‘Cara Pandang Instrumental Cara Pandang Aksi Sosial
Pendekatan’ Analisis bertolak dari “organisasi” ‘Analsis bertolak dari “aks anggota’
Analisis
Definisi tentang Organisasi adalah alat untuk mencapai_Organisasi adalah produk dari aksi
organisasi tujuan kelompok, yang keberadaannya para anggota yang terlibat melalui
negosiasi pemaknaan realitas dan
negosiasi kepentingan
Aitivitas manajemen adalah tidek
‘manajemen rasional, dapat diprogramkan, dan netral, kadang irasional, tergantung
bebas dari persepsi dan kepentingan _persepsi dan kepentingan manajer
manajer -
Diskursus Tujuan organisasi, tugas, wewenang, —_Tata nilai, norma, ritual, seremoni,
pemaknaan realitas, kepentingan,
kekuatan (power), negosiasi
kompromi, tawar menawer, dan
sejenisnya
Struktur organisasi adalah pola
organisasi organisasi yang menggambarkan hubungan perilaku antaranggota
pembagian tugas dan fungsi dari yang terlibat, yang bukan semata-
bagian-bagian orgenisasi yang mata sebagai produk manajemen tapi
diasumsikan akan membentuk lebih kepada hasil kontes pemaknaan
perilaku anggota organisasi, oleh realitas dan perebutan kepentingan
kkarenanya perilaku anggota organisasi antaraktor yang terlibat
dianggap sebagai produk manajemen
Konsep tentang —_Perilaku anggota organisasi dibentuk —_Perilaku anggota dalam organisasi
| perilaku anggota dan diarahkan oleh manajemen dalam adalah hasil dari proses negosiasi
Gi dalam bentuk aturan dan prosedur, guna kepentingan dan kontes pemaknaan
corganisasi Pencapaian tujuan organisasi realitas kehidupan antaraktor di
dalam dan di luar organisasi, manajer
dianggap sebagai salah satu peserta
saja dalam kontes pemaknaan dan
negosiasi Kepentingan antaraktor
manajemen tapi lebih dipengaruhi oleh
‘dan orientasi seseorang yang menyebabkan ia bergabung dalam
115
116
yaeg mempengarun tindakan seseorang dalam berinteraksi, meliputi tujuan, ria, Keinginan, harapan,
dan orientasi ses
Lebin jauh, Morgan (1996) membagi kepentingan ke dalam tiga kategot, yaitu kepentingan pekerjaan,
kepentingan karir dan kepentingan ekstramural. Kepentingan pekerjaan adalah kepentingan yang terkalt
dengan tugas seseorang sesuai kedudukan dan jabatan yang diembannya. Sementara, kepentingan keri
terkait dengan masa depan seseorang dalam organisasi (posisi dan jabatan yang lebih baik), yang bisa
tidak berhubungan dengan kepentingan pekerjaan. Dalam komponen kepentingan juga termasuk
ntingan ekstramural yang terdiri dari kepribadian, sikap, nilai, keyakinan dart komitmen di luar
pekerjaan, yang keseluruhannya akan membingkai pola perilaku seseorang baik menyangkut pekerjaan
maupun karit.
‘Asumsi dasar manajemen politi« adalah (1) organisasi adalah koalisi yang terdiri dari berbagai
individu: dan kelompok dengan berbagai kepentingan, (2) dalam organisasi selalu ada potensi perbedaan
menyangkut kepribadian, keyakinan, kepentingan, sikap, persepsi, dan preferences dari para anggotanya,
(3) kekuatan (power) memainkan peranan penting dalam memperebutkan sumber daya, (4) tujuan
corganisasi, pengambilan keputusan dan proses manajemen lainnya adalah hasil dari bargaining, negosiasi
dan brokering dari berbagai faksi peserta, (5) karena keteratasan sumber daya dan setiap aktor berebut
kepentingan, maka konilik adalah wajar (alamiah) dalam kehidupan organisasi (Bolman & Deal, 1991;
Degeling. 1997; Morgan, 1996).
Dalam berebut kepentingan tersebut, setiap aktor, termasuk manajer, memanfaatkan sumber-sumber
kekuatan (power) yang climilikinya untuk saling mempengeruhi aktor lainnya. Weber (1947) mendefinisikan
power sebagai “peluang seorang aktor dalam interaksi sosialnya berada di posisi memenangkan
keinginannya meski ada hambatan dari pihak fain’. Sebagai ilustrasi, ‘A’ mempunyai power terhadap
“B kalau ‘A’ dapat mempengaruhi atau memaksa ‘B’ untuk melakukan sesualu yang diinginkan oleh ‘A’
(Blau, 1965), Dengan kata lain, power adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain
untuk bertindak sesuai dengan keinginan orang pertama,
‘Sumber-sumber power yang dipakai para aktor untuk saling mempengaruhi adalah (1) otoritas
formal, (2) kendali pada sumber daya, (8) penggunaan struktur organisasi dan aturan, (4) kendall pada
pengambilan keputusan, (5) penguasaan informasi dan pengetahuan, (6) pembentukan networking dan
koalisi, (7) penanganan ketidakpastian, (8) simbolisme dan manajemen makna, dan (@) karisma (Bolman
& Deal, 1911; Morgan 1996). Mangjer yang lidak mampu mengelaborasi atau mengumpulkan kesembilan
sumber power tersebut dengan baik, ia akan kehilangan legitimasinya sebagai pemimpin, yang berakibat
pada munculnya pemimpin (leader) bayangan.
Dengan metafora politik, maka organisasi diinterpretasikan sebagai wahana perebutan kepentingan
oleh aktor yang terlibat; sementara pekerjaan manajer adalah analog dengan seorang politisi yang
berusaha untuk mempengaruhi aktor lain dengan memainkan sumiber-sumber kekuatan yang ia milk
‘Aktivitas manajer untuk mempengeruhi aktor lain dalam rangka menuju keteraturan (getting organized)
adalah mobilisasi, kooptasi, mediasi, networking, brokering, dan propagasi nilai-nilai dan aturan untuk
memenangkan kepentingannya. Aktivitas manajemen ini bersifat tidak netral dan tidak ster! dari kepentingan
mangjer, setidaknya untuk mempertahankan posisinya pada setiap kontes yang sedang terjadi.
Beberapa taktik dan strategi manajemen dalam metafora politik sebagaimana diungkapkan oleh
Degeling (1997) diantaranya adalah: 1) Membentuk koalisi dengan pihak lain untuk meningkatkan
dukungan dan sumber daya; 2) Menciptakan suasana (seremoni dan simbol) untuk membentuk persepsi
dan perilaku orang-orang sesuai dengan peran dan fungsinya; 3) Mentransformasikan kepentingan kita
adi kepentingan pihak lain dengan mengubah persepsi dan tindakan pihak lain; 4) Memperiuas
rain yang terlibat dalam sualu isu yang menjadi kepentingan kita untuk mendapatkan perhatian.
lebih luas; 5) Melaksanakan negosiasi dan tawar menawar dengan pihak lain yang bersinggungan
' fan kita untuk mendapatkan kompromi; dané) Memilih waktu yang tepat untuk setiap
nagar situasi manguntungkan kita
> taktik dan strateji tersebut harus disesuaikan dengan aturan umum, noma dan budaya
+ berada. Setiap pilihan taktk dan strategi yang dipakal manajer harus kontinjen
epenti
h posisi manajer.
STRUKTUR DALAM. KONTEKS METAFORA POLITIK
Metatora Politk sebagai Pendekatan Manajemen (Siswanto)
isusun berdasarkan fungsifungsi yang telah citetapkan sebelumnya, sehingga sering didengar aksioma:
structure follows function (struktur mengikut fungsi). Dalam konteks ini, tugas dan tungsi suatu organisasi
dapat cihat dar struktur organisasi tersebut. Setelah struktur terbentuk barulah dilakukan staffing. yakni
mengisi personalia dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari struktur
yang aken diembannya. Cara pandang sepert ini adalah cara pandang teori klasik tentang manajemen,
yang menggunakan asumsi bahwa semua hal yang terjadi di organisasi adalah produk dari aktivitas
manajemen.
Dalam metafora manajemen politi, istilah ‘struktur’ bukan diinterpretasikan sebagai bagan atau
struktur organisasi, namun ‘struktur’ diinterpretasikan sebagai ‘karakteristik pola hubungan kehidupan
corganisasional’ yang sudah mengendap dalam rutinitas kehidupan organisasi, menjadi norma dan tata
nila, sehingga setiap aktor menerima apa adanya tanpa menanyakan mengapa demikian (taken as given).
‘Struktur dalam konteks ini bersifat membingkai dan membatasi apa-apa yang boleh diperebutkan dan
dinegosiasikan oleh para aktor yang terlibat. Dalam metafora polltik kesepakatan pola interaksi antaraktor
yang sudah menjadi norma dan tata nilai ini disebut sebagai ‘structural politics’. Sementara, komponen-
komponen yang masih terbuka untuk dinegosiasikan antaraktor disebut sebagai ‘surface politics’ (Degeling,
1997). Hubungan antara structural politics dan surface politics dapat diabstraksikan di Gambar 1.
ALAT DIAGNOSIS
~ Siapa pemain dan mengapa ia
menjadi pemain?
~ Apa yang diperebutkan?
~ Siapa punya power dan mengapa?
Surface Politics:
area yang diperebutkan antar aktor melalui: ~ Taktik apa yang dipakai?
~ negosiasi ~ Siapa bakal menang dan kalah?
~ tawar menawar — Bageimana hasil kompetisi dapat
— kompromi diterima?
Structural Politics: area yang menjadi
Pemahaman bersama dan tidak diperebutkan
antaraktor:
= Apa yang dipahami bersama oleh
semua pemain?
~ Apa yang tidak perlu didiskusikan?
~ Tata nilai ~ Pemahaman = Apa boleh pamain menanyakan
~ Keyakinan ~ Rutinitas, domain ini?
~ Norma ~ Hirarki kekuasaan
—Aturan = Komitmen
Gambar 1.
Hubungan antara Structural Politics dan Surface Politics dalam Kehidupan Organisasi
(modifikasi dari Management of Organization, Degeling, 1897)
Gambar 1. menekankan bahwa para aktor dalam kehidupan organisasi hanya bermain dalam
\wilayah ‘surface politics’; dan mereka tidak bermain pada wilayah ‘structural politics’. Hal ini dikarenakan
‘stwctural politics adalah menyangkut tata nilai dan norma yang sudah mengendap menjadi budaya
Kolekti, sehingga wilayah structural politics adalah doriiain-yang tidak petlu dipertanyakan lagi cleh
para pemain (faken as given). Untuk memahami hubungan structural politics dan surface politics kita
‘dapat mengambil contoh pola interaksi antara mahasiswa dengan dosen‘pembimbing. Dalam hubungan
bimbingan tugas alhig balk skripsi,tesis ataupun disertasi, mahasiswa mengetahui area mana yang bisa
Gragesiasten tac 083) dan area mana yang harus diterima apa adanya tanpa boleh bertanya
| paitics). isi dari proposal peneltian mahasiswa mulai pendahuluan, tyjuan
‘Pengumpulan dala merupakan area yang masth dapat dinegosiasikan
Pembimbing (area surface politics). Akan tetapi, ‘proposal penelitian’,
47
118
J. Adm, Kebljak esha, Vol No 9 ept-Des 2006
“pola interaksi bimbingan’, ‘otoritas pembimbing terhadap yang dibimbing’ dan’ er proposal” siilah
area yang harus diterima apa adanya (area structural politics) :
Untuk metinat area mana sala yang termasuk surface polities, Kita dapat rena ages
pertanyaan-pertanyaan
> Siapa pemain dari mengapa ia menjadi pemain?
+ Apa yang diperebutkan? 5
> Siapa punya power dan mengapa?
> Tektik apa yang dipakai?
1 Siapa bakal menang dan kalah?
1» Bagaimana hasil kompetisi dapat diterima?
Untuk area surface politics, apabila pertanyaan-pertanyaan alat diagnosis ini diajukan, maka kita
dapat mempréliiksi atau menjawabnya dengan mudah. Bila kita mengambil contoh hubungan mahasiswa
dan dosen pembimbing, maka area surface poltics adalah jacwal bertemu dosen pembimbing, negosiasi
substansi proposal, dan jadwal ujian.
‘Sementara itu, untuk melihat area mana saja yang termasuk structural politics, kita dapat
mendiagnosisnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan:
> Apa yang dipahami bersama oleh semua pemain?
> Apa yang tidak perlu didiskusikan?
> Apa boleh pemain menanyakan domain ini?
‘Area structural politics adalah area yang menjadi ‘pemahaman bersama’, sebagai sesuatu yang
diterima apa adanya (taken as given), tanpa perlu dipertanyakan mengapa harus begitu. Bila kita
mengambil contch hubungan bimbingan antara mahasiswa dengan dosen, maka ‘penyusunen proposal’
‘ujian proposal’, ‘ujian skripsitesis’ adalah area structural politics yang harus diterima apa adanya tanpa
bisa dinegosiasikan.
MANAJEMEN MELALUI PENDEKATAN POLITIK
Dalam konteks metafora polik, manajer adalah seorang politisi yang mampu menanamkan pengarun
kepada semua aktor yang terlat. Dalam rangka menanamkan pengaruhnya, manajer memainkan sumiber-
sumber power (linat pembahasan sumber-sumber power) sesuai dengan event organisasional dan aktor
yang ja hadapi (kontinjen dengan event dan aktor). Dalam hal ini apa yang dilakukan manajer adlah
melakukan advokasi, membengun koalisi, mentransformasi kepentingan menjadi kepentingan aktor lain,
memperluas pemain, melobi dan negosiasi dengan berbagai aktor untuk mencapai agenda organisesi
(visi dan misi organisasi) yang telah ditentukan. Hubungan advokasi (komunikasi), memainkan sumber
power, aktivtas politik, dan memenangkan kepentingan dapat dilihat di Gambar 2:
‘Aktivitas politk
> Mobiisasi
7 Membangun koalsi
> Mentranstormasi kepentingan
‘menjadi kepentingan pibak lain *
> Memperluas pemain
> Nogosiasi dan tawar-menawar
2 Memiih waktu yang tepat
Memainkan
et poner
Gambar 2.
Hubungan antara Advokas, Aktivitas Polk dan Pemenangan Kepentingan
(modifikasi dari Management of Organization, Degeling,1997)
Untuk mempraktikkan manajemen dengan metafora politik, maka
yang selalu mémperluas sumber-sumber power (koleksi sumber power)
setiap ‘event’ yang tepat guna untuk membentuk perilaku aktor lain 868
‘Agar hal demikian dapat terjadi, tentunya manajer harus seorang pemimpin yang mampu menanamkan
pengaruhnya baik secara intramural (ke dalam) dan ekstramural (keluar), sehingga aktor lain mengikuti
._ kehendak dan agenda yang telah disusunaya.
_ Setiap ‘event’ organisasional, seperti Planning, Organizing, Actuating, Controlling dan Evaluating
harus dapat dipakai sebagai wahana untuk pemetaan kekuatan, penyusunan strategi memenangkan
kepentingan, negosiasi dan tawar-menawar dari agenda-agenda yang telah disusun oleh manajer. Dalam
perspektf ini, seorang manajer harus sadar bahwa dirinya hanyalah ‘salah satu pemain’ (partisan) dari
panggung politik yang bernama ‘organisasi’. Setiap aktor akan selalu berusaha memainkan power-nya
‘masing-masing untuk berebut pengaruh demi kepentingannya sendiri. Dengan demikian, seorang manajer
akan efektif apabila ia mempunyai sumber power lebih banyak dari aktor lain dan mampu memainkan
power-nya secara tepat, balk tepat event maupun tepat aktor yang dihadapi. Apabila langkah-langkah
sekuensial fungsi manajemen dikaitkan dengan praktik manajemen politi, maka dapat diabstraksikan
di Tabel 2.
Tabel 2.
Interpretasi Proses Manajemen Dikaitkan dengan Metafora Politik”?
Proses Manajemen Interpretasi dengan Metafora Politik
Perencanaan ‘Arena untuk pemetaan power dan menyelesaikan konflik
Pengambilan keputusan Kesempatan untuk meningkatkan dan memainkan power
Reorganisasi Redistribusi power dan membentuk koalisi baru
Evaluasi Kesempatan untuk memainkan power
Penyelesaian kontlik Menyelesaikan konflik dengan memainkan power melalui
advokasi, negosiasi, tawar-menawar dan pemaksaan kepada
aktor lain «
Penetapan tujuan Memberikan kesempatan kepada setiap aktor atau kelompok
menunjukkan kepentingannya
Komunikasi ‘Sebagai sarana untuk saling mempengaruhi antaraktor
Rapat (meeting) ‘Wahana kompetisi untuk memenangkan kredit (poin)
Motivasi Dilaksanakan dengan cara advokasi, koersi (pemaksaan) dan
maniputasi
*Diadopsi dan Reframing Organizations (Bolman & Deal,1991)
Interpretasi proses manajemen dengan metafora politi sebagaimana pada tabel 2 menunjukkan
bahwa mantaat setiap ‘event’ fungsi manajemen tidak dilhat dari produk akhir event tersebut dalam
perspektiftujuan organisasi. Namun, setiap event fungsi manajemen dilhatnya sebagat ‘game’ untuk saling
memenangkan kepentingan. Oleh karena itu, fokus dari metafora polik adalah bagaimana manajer mampu
‘memainkan ‘power -nya untuk memenangkan kepentingan terhadap kepentingan aktor lain, Dengan kata
lain, setiap event organisasi adalah wahana berebut kepentingan oleh setiap aktor yang terlbat, dimana
seorang manajer adalah hanya salah satu peserta (partisan) dalam setiap game yang ia ikuti
‘Agar seorang manajer dapat menanamkan pengaruhnya untuk mencapai visi dan misinya, maka
ia/harus berada di atas rata-rata dari aktor lainnya, balk menyangkut koleksi sumber power maupun care
memainkan power secara tepat. Seorang manajer efektit adalah seorang pemain elegan, yang selalu
‘mempropagasi dan mengadvokasi tujuan overt (tujuan sakral) organisasi kepada aktor intra dan ekstra
‘cxganisasi, namun ia juga cerdik menyimpan dengan rapi tujuan covert-nya (kepentingan individualnya).
Dengan begitu pengamat luar akan melihatnya sebagai seorang pemimpin elegan yang dalam setiap event
corganisasi selalu tampil mengesankan (sense making) untuk berjuang demi kepentingan organisasinya,
‘Dapat disimpulkan beberapa poin pokok dari tulisan ini: 1) Cara pandang organisasi dan manajemen
‘dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni cara pandang instrumental dan cara pandiang aksi
‘Social; 2) Cara pandang instrumental memufai analisisnya bertolak dari ‘organisusi’, sehingga melihat
‘organisasi ada terlebih dahulu sebelum aksi anggotanya (pre-existent), bebas dari persepsi dan pemaknaan
: ‘pekerjaan manajemen sebagal sesuatu yang fetal, dapat diprogram.
f. 8) Cara pandang aksi sosial memulatanalisisnya bertolak da ‘aks!
| sebagai produk dari aksi anggotanya dalam bemegosiasi makna
119
120
dan kepentingan, kemudian melihat pekerjaan manajemen sebagai sesuatu yang partisan, tidak netral
dan tidak bebas dari kepentingan manajer; 4) Metafora polltik, sebagai salah satu metafora dalam cara
pandang aksi sosial, melihat organisasi sebagai ‘game’ yang digunakan oleh aktor anggota organisasi
termasuk manajer untuk bernegosiasi kepentingan pada setiap ‘event’ organisasi; 5) Structural politics
dalam kehidupan orgenisasi mencerminkan domain mang yang harus diterima apa adanya (taken as
given), sedangxan surface politics mencerminkan domain mana yang boleh dinegosiasikan; dan 6) dengan
pendekatan metafora politit, manajer efektif adalah seorang manejer yang mampu mengembangkan
sumber power secara luas dan mampu menggunakannya secara tepat sebagai alat Untuk meyakinkan
aktor lain guna meraih kepentingannya.
DAFTAR PUSTAKA
Balai Pustaka, 1980. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia,
Biau PM. 1965. Exchange and Power in Social Life. Wiley.
Bolman LG & Deal TE. 1991. Retraming Organizations: Artistry, Choice, and Leadership. San Francisco: Jossey-Bash
Publishors
Dahi R. 1991, Analisis Politik Modern (Terjemahar). Jakarta: Bumi Aksara.
Degeling P. 1997. Management of Organization. Sydney, Australia: University of New South Wales.
Giddens A. 1981. “Agency, Institution, and Time-Space Analysis", in K. Knor-Cetina & AY. Circourel (Rds), Advances
in Social Theory and Methodology. London: Routledge & Kegan Paul.
Morgan G. 1996. Images of Organization. London: Sage Publications.
Spradley JP. 1979. The Ethnographic Interview. New York: Holt, Rinehart and Wilson,
Weber M, 1947. The Theory of Social and Economic Organization, trom Henderson AM and Parsons T. Glencoe
Press.
Worsley P. 1991. The New Modern Sociology Readings. London: Penguin Books.
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- LAMPIRAN II A Surat Pendaftaran Calon AnggotaDocument1 pageLAMPIRAN II A Surat Pendaftaran Calon Anggotakatong supriadiNo ratings yet
- Manajemen Strategik Untuk Pendidikan Yang Bermutu Strategic Management For Quality of EducationDocument12 pagesManajemen Strategik Untuk Pendidikan Yang Bermutu Strategic Management For Quality of Educationkatong supriadiNo ratings yet
- Pengembangan Aplikasi Ecommerce Dengan Metode Feature Driven DevelopmentDocument4 pagesPengembangan Aplikasi Ecommerce Dengan Metode Feature Driven Developmentkatong supriadiNo ratings yet
- Fenomena KonsumenDocument419 pagesFenomena Konsumenkatong supriadiNo ratings yet
- Sistem Informasi Penjualan Sutera Berbasis E-Commerce Pada Butik Cantika Malaka SoppengDocument8 pagesSistem Informasi Penjualan Sutera Berbasis E-Commerce Pada Butik Cantika Malaka Soppengkatong supriadiNo ratings yet
- Perda Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2019 TentangDocument17 pagesPerda Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2019 Tentangkatong supriadiNo ratings yet