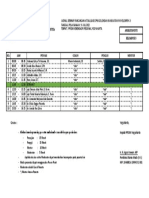Professional Documents
Culture Documents
Makalah Penanganan Sshock
Makalah Penanganan Sshock
Uploaded by
harun0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views25 pagesOriginal Title
makalah penanganan sshock
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views25 pagesMakalah Penanganan Sshock
Makalah Penanganan Sshock
Uploaded by
harunCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 25
TERAPI CAI
AN PADA PASIEN SYOK
Oleh
dr, Kadek Agus Heryana Putra, Sp.An
I Komang Gede Triana Adiputra
DALAM RANGKA ME
GIKUTI KEPANITERAAN KLINIK MADYA,
BAGIAN / SMF ILMU ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI
FK UNUD / RSUP SANGLAH DENPASAR
TAHUN 2017
BAB | PENDAHULUA!
BAB II TINJAUAN PUSTAKA........
2.1 Definisi Syok
22 Patofisiologi Syok,
2.3. Etiologi Syok
23.1 Syok Hipovolemik.
23.2 Syok Kandiogenik.
BAA — Syok Obstruktif
23.4 — Syok Distributif.....
2.4 Penatalaksanaaan Umum Syok.
2.5 Manajemen Cairan Pada Syok
25.1 Kompartemen Cairan Tubuh Manusi
25.2 Pemilihan Cairan Resusitasi
2.5.3. Pemantayan Hemodinantik ......
25.1 Terapi Cairan Pada Syok Hipovolemik....
25.2 Terapi Cuiran Pada Syok Sepsis... 19
BAB III SIMPULAN.
DAFTAR PUSTAKA...
BABI
PENDAHULUAN
Dalam kondisi normal, jumlah cairan dan elektrolit di dalam tubuh sclalu scimbang,
dimana asupaa ait dan elcktrolit akan dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Asupan air dan
elektrolit berasal dari makanan dan mimuman yang dikensumsi sehari-hani, sera didapatkan
dari hasil oksidasi di dalam tubuh, Air dikeluarkan di dalam tubuh dalam uni, tinja, dan
insensible water loss (IW1.) atau pengeluaran yang tidak disadari, seperti melalui pernapasan
dan keringat, Gangguan keseimbangan atau homeostasis air dan clektrolit horus segera
diterapi untuk mengembalikan keseimbangan air dan elcktrolit tersebut, dit
diperlukan untuk dilakukan terapi caitan. (Leksana, 2015)
ana dafam hal ini
Syok adalah sindrom klinis akibat kegagalan sirkulasi dalam meneukupi kebutuhan
oksigen jaringan tubuh. Pada Kondisi syok; terjadi gangguan hemodinamik yung
menyebabkan tidak adekuatnya hantaran oksigen dan perfusi jaringan. Gangguan
hemodinamik tersebut dapat berupa penurunan tahanan vaskuler sitemik terutama di arteri,
berkurangnys darah bolik, penurunan pengisian ventrikel dan sangat kecilnya eurah jantung,
Gangguan faktor-faktor tersebut disebabkan oleh bermacam-macam proses baik primer pada
sistem kardiovaskuler, neurologis ataupun imunologis. (Hardisman, 2013)
‘Secara umum syok digolongkan menjadi beberapa Kategori berdasarkan penyebab,
yaitu: (1) Syok hipovolemik (dari kehilangan cairan internal maupun eksteral), (2) Syok
kardiogenik (pompa jantung terganggu, contohnya pada AML, kardiomiopati, miokarditis,
dan aritmia), (3) Syok obstruktif (hambatan sirkulasi menuju jantung, contohnya puda emboli
‘paru, tamponade jantung, atau pacumothorax), dan (4) Syok distributif (vasomotor tergangeu,
-contohnya pada sepsis dan anafilaksis) (Vineent & Backer, 2013)
Syok merupakan kondist yang sering ditemui pada pasien kei
pada sepertiva pasien yang dirawat di ICU, Syok sepsis, salalr satu bentuk syok distributive,
merupakon jenis syok yang paling sering ditemui pada pusien di ICU, diikuti syok
yang mana terjadi
kardiogenik, syok hipovolemik, dan syok distributive (Vincent & Backer, 2013)
Penanginan pasien syok memerlukan kerjasama multidisiplin berbagai bidang ilmu
kedokteran dan multi sektoral. Langkah awal penatalaksanagn syok adalah mengenal
diugnosis Klinis secara (lini, olch kurena manajemen syok harus memperhatikan“The Golden
Period”, yaitu jangka waktu dimana hipoksia sel belum menycbubkan “eummulative oxygen
deficit”, Secara empiris satu jam pertama sejak onset dari syok adalah batas waktw maksimal
untuk mengembalikan sirkulasi yang adekuat kembali(Suryano, 2008)
‘Tujuan penanganan tahap awal pada pasien syok adalah untuk mengembalikan perfusi
dan oksigenasi jaringan dengan memulihkan volume sirkulasi intravaskuler, Terapi cairan
paling penting pada syok distibutif Khususnya syok sepsis dan syok hipovolemik, yang
paling sering terjadi pada wauma, perdarahan, dan luka bakar, Pemberian eairan intravena
akan memperbaiki volume sirkulasi intravaskuler, meningkatkon curah jantung dan tekanan
dara, (Leksana, 2015)
‘Terapi cairan dan elektrolit adalah salah satu terapi yang sangat_menentukan
Keberhasilan penanganan pasien kritis, Dalam langkah-langkah resusitasi, langkah D (drug
and fluid treatment) dalam bantuan hidup lanjut, merupakan langkah yang penting secara
simultan dengan langkah - langkah yang lainny. Tindakan ini seringkali merupakan langkah
life saving pada pasien yang menderita kehilangan cairan yang banyak seperti perdarahan,
dehidrasi karena muntah, diate, dan atau lainnya.(Primanand:t, 2010)
24
a
BABII
TINJAUAN PUSTAKA,
Definisi Syok
Syok merupakan gambaran klinis kegagalan sirkulasi yang mengakibatkan
penggunaan oksigen seluler inadektat. Diagnosis syok dapat ditegakkan dengan
gejala Klinis, hemodinamik, dan biokimia yang dapat dibagi menjadi tiga Komponen;
Pertama, biasanya tetjadi hipotensi arterial sistemik, namvun derajat hipotensi yang
sedang dapat ditemui pada pasien dengan hipertenst kronis, Secara umum syok pada
orang dewasa ditandai dengan tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg atau mean
arterial pressure kurang dari 70 mmilg- yang disertai dengan takikardi. Kedus,
terdapat gejala ktinis hipoperfusi jaringan yang terlihat pada tiga “window” dalam
tubuh; kulit (kulit yang dingin dan keriput akibat vasokonstriksi dan sianosis}, ginjal
¢produksi urin kurang dari 0,5 mi/kg/am), dan neurologis (perubshan status mental).
terdapat peningkatan laktat yang menunjukkan metabolisme oksigen seluler
yang abnormal. (Vincent & Backer, 2013)
Keti
Patofisiologi Syok
Syok dapat timbul akibat cmnpat mekanisme palofisiologis yang tidak selalu terpisah
satu sama lain, yaitu; (1) Hipovolemia (dari kehilangan cairan internal maupun
ceksternal), (2) Kardiogenik (¢.g AMI, kardiomiopati, miokarditis, dan aritmia), (3)
Obstruksi (c.g emboli par, tamponade jantung, atau pneumothorax), dan (4)
Distributif (e.g sepsis, anafitoksis).(Vinoent & Backer, 2013)
Karaktcristik syok cenderung berubah seiring dengan perjalanan penyakit
dengan derajat keparahan yang berbeda pada masing-masing stadiumnya, Secara
umum, syok digolongkan menjadi tiga stadium, yaitu; (1) Stadium kompensata
(compensated stage) dimana mekanisme kompensas| normal masih dapat
mengembalikan fungsi sirkulasi meskipun taspa intervensi dari luar; (2) Stadium
progresif (progressive stage) dimana syok akan cenderung memburuk dan dapat
mengakibatkan kematian jika tidak diterapi; dan (3) Stadium imeversible (irreversible
stage) dimana syok telah berkembang sedemikian rupa schingga segala terapi yang.
tersedia tidak dapat meneegah kematian,(Hall, 2006)
Pada stadium kompensata, mekanisme feedback negative tubuh masih dapit
mengembalikan: cardiac ouput dan tekanan arteri, Mekanisme feedhack tersebut
meliputi; barorecemtor reflex, reverse stress-relaxation response, respon iskemia
susunan saraf pusat, sckresi angiotensin ol¢h ginjal, sekresi vasapressin (ADH) oleh
kelenjar pituitari, Selain itu, terdapat mekanisme konapensasi untuk mengembalikan
volume intravascular seperti abserpsi air dalam jumilah besar dari salurtn cera, shift
cairan dari interstitial ke kapiler, konservasi air dan garam oleh ginjal, dan rasa haus
yang ilirasakan penderita.(Hall, 2006)
Reflek simpatik merupakan mekanisme pertama dalam pemutihan syok karena
teraktivasi sceara maksimal dalam 30 detik — 1 monit pertuma, Mekanisme
Kompensasi yang melibatkan angiotensin dan vasopressin, Serta reverse-sivess
relaxation memertukan waktu 10 menit ~ 1 jam untuk dapat merespon secara penuh;
fnamun mekanisme ini berperan besar dalam meningkatkan tekanan arteri otou /illing
pressure schingga meningkatkan cardiac output, Kemudian, mekanisme untuk
mengembalikan volume intravascular seperti absorpsi cairan dari saluran cema dan
fetensi cairan dan natrium pada ginjal memerlukan 1 — 4% jam untuk berfungsi
maksimal (Hall, 2006)
Syok yang berlanjut akan menimbulkan mekanisme feedback positifyang
menurunkan cardiac ompur sehingga menimbulkan syok progresif! (Gambar 1)
Mekanisme feedback positif tersebut meliputis
1. Cardiae depression
Pada penurunan tekanan arteri yang berat, terutama ickanan diastolic, uliran darah
coroner juga berkurang sehingga terjadi iskemia coroner. Hal ini semakin
memperlemah miokardium dan semakin meourunkan cardiac omtput
Kegagalan vasomotor
Ketika curah jantung menurun, aliran darah ke otak dan jantung umumnya
dipertahankan. Jika tekanan arteri turin cukup rendah, aliran darah ke otak mula
tergunggu dan aliran darah ke pusat vasomotor juga berkurang. Impuls yang
berkurang secara drastic dari pusat vasomotor dapat_menyebabkan semakin
{urunnya fekanap arteri dan kegagalan sirkulasi perifer yang progresif.
3. Penyumbatan pembulub darah kecil
Karena rendahaya aliran darah pada saat syok, metabolit-metabotit jaringan,
termasuk asam laktat dan karbonat tidak dapat dibersihkan dengan baik dan
konscnirasi lokalnya meningkal, Meningkatnya korisentrasi ion hydrogen dan
produk iskemik lain menyebabkan aglutinasi lokal dan pembentukan bekuan
dorah, Darah yang mengental di pembuluh-pembuluh halus ini disebut “sludge
blood”.
|. Peningkatan permeabilitas kepiler
Karena pada syok terjadi hipoksia kpiler dan kurangnya mutrient lain,
permeabilitas kapiler meningkat sehingya cairan dan protcin keluit ke jaringan.
Hal ini menyehabkan penurunan volume darah yang dapal memperparah syok
Pelepasan toksin dari jaringan iskemik,
Dalam keadaan syok, diduga terjadi pelepasan histamine, serotonin, dan enzim
jaringan yang menimbulkan penurunan fungsi sirkulast tebih Janjut. Penurunan
aliran darah ke usus juga dapat menyebabkan peningkatan pembentukan dan
absorpsi endotoxin yang. diproduksi bakteri gram negative pada usus, Toksia ini
menyebabkan peningkatan metabolisme intraseluler walaupun di saat yang sama
terjadi kekurangan nutrisi pada jaringan, Hal ini menimbulkan efek spesifik pada
tot juntung, dimana akan terjadi pesurunan curah jantung.
Gambar 2.1 Feedback positif pada syok progresif(Hall, 2006)
Jikae syok berlanjut sampai pada tahapan tertentu, transfusi ataw terapi lain
tidak mampu menyelamatkan hidup pasien; tahapan ini disebut sebagai irreversible
svok,Pada stadium inj tekanan arteri dan cardiac output dapat normal kembali untuk
beberupa waktu, namun sistem sirkulasi pada ski
iy akan terus memburuk, dan
kematian biasanya terjadi dalam beberapa menit atau jam,
Etiologi Syok
Syok Hipovolemik
Syok hipovolemik merupakan syok yang terjadi akibat berkurangnya volume plasma
di intravaskuler, Penyebab utama syok hipovelemik adalah pendarahan, dimana
pendarahan menurunkan filiiig pressure sirkulasi dan kemudian jugs menurunkan
venous return, (Hall, 2006} Penyebab syok hipovolemik lain adalah dehidrasi berat
oleh berbagai sebab seperti luka baker dan diare berat. (Hardisman, 2013)
Dalam Klasifikasi ATLS, syok hipoyolemik dibagi atas 4 derajat betdasarkan
perkiraan hilangnya darah (Estimated! Blood Loss) yang digambarkan pada Taki-laki
dewasa dengan berat badan 70 kg (Tabet 1).
‘Tabel 1. Derajat Hipovelemi Berdasarkan EBL (ACS Commitees on Trauma, 2012}
; ~=<15% EBY 30-40% EBV 40%
Kehilangan darah
ml) (750-1500 mip (1500-2000 ml) (©2000 rl)
Frokwensi nadi S100 ximenit «100-120. xmenit—120-140-x/menit > 140-x/menit
“Tekanan darahy Normal Normil Mensrun Menuran
‘Normal aiau o
‘Vekanan nad " Menunan Menurun Meniunait
‘meningkat
Frekuensi papas 14-20x/menit___20-Mix/menit 0-0 x/inewit Sal ximenit
Froduksi urin 330 cejam 20-30 cezjam S15 cofjam ‘Oligourifarairi
ii isorieat
Blanes menial (a Cemax ingcer sete: Letwreis
asi
Koreksi awal Kristaloid “Kristaloid Kristaloid + darah-Kristalold + daralt
Gejata Kebilangan volume pala perdarahan Kelas 1 eenderung minimal,
‘Takikardia minimal biasanya terjadi dengan faju napas, tckanan darah, dan tekanan
adi dalam bates normal, Pada pasien tanpa pangguan lain, kehilangan darah pada
erajat ini tidak memerlukan penggantian karena mckanisme kempensasi tubuh
6
23.2
umumnya dapat mengembalikan volume darah dalam 24 jam,(ACS Commitees on
‘Trauma, 2012)
Pada loki-laki dewasa dengan berat badan 70 kg, kebilangan darah sejumlah
750-1500 mi tergolong sebagai perdarahan kelas I. Gejala Klinis yang muncul
‘meliputi takikardi, twkipneu, dan penurunan tekanan nadi, Penurunan tekanan nadi
umumnya disebabkan peningkatan tekanan darah diastolik akibat peningkatan jumlah
kaickolamin dalam sirkulasi. Tekanan darah.sistoll
uumumnya masih normal pada
fase awal syok hemoragik; oleh karena itu, monitoring tekanan nadi Iebih penting
dibandingkan tekanan darah sistolik. Gejala lain yang dapat diternui adalah perubahan
pada sistem saraf pusat seperti ansietas dan ketakutan(ACS Commitees on Trauma,
2012)
Perdarahan kelas IT hampir selalu ditandai dengan gejala penurunan perfusi,
termasuk takikardi, tokipneu, perubahan signifikan status mental, dan pentiranan
tekanan darah sistolik. Pada kasus tanpa komplikast, perdarahan sejumlah 30% dari
EBV (Estimated Blood Volume) merapakan jumlah minimal yang dapat menyebabkan
penurunan tekanan darah sistolik, Pada perdarahan kelas 1V, tekunan daral sistolik:
turun lebih jauh dan (ekanan nadi menjadi sangat sempit atau tekanan diatolik yang
tidak dapat diukur. Produksi urin pada Kategori ini sangat minimal, dan disertai
Penurunan status mental yang nyata4ACS Commitees on Trauma, 2012)
Syok Kardiogenik
Syok kardiogenik menupakan sindrom klinis akibat penurunan curdh jantuny yang
menyebabkan hipoksia jaringan dan volume intravaseul
yang adekuat, Pada syok
kandiogenik, terjadi perubahan hemodinamik sebagai berikut: (1) Penuranan curah
jantung (<2,2 L/menitim’), (2) Hipotensi sistolik arteri (<9 mmHg), dan (3)
Peningkatan tekanan akhir-diastolik ventrikel kiri (pulmonary capillary wegde
pressure (PCWP) >18 mmHy){Hochman & Ingbar, 2012)
Syok kordiogenik dapat terjadi akibat beberapa mekusisme yang menuninkan
ccurah jantung, yaitu
Disfungsi miokardium (gagal memompa) terutana karen komplikasi infiark
miokardium akut.
233
~ Pengisian diastolik venteikel yang tidak Kuat, antara lain takiaritmia,
tamponade jantung, tension pneumothorsk, emboli paru dan infark ventrikel
kanan,
= Curah jentung yang tidak adekuat, antara lain bradiaritmia, regurgitasi mitral
‘tau ruptur septum interventrikel(Chow JL, 2004)
Gambar 2, Syok Kardiogenik{Hochman & Ingbar, 2012)
Syok kardiogenik terjadi akibat penurunan kentraktilitas miokardium yang,
menimbulkan disfungsi fungsi sistolik dan diastolik jantung. (Gambor 2) Pada
disfungsi sistolik texjadi penurunan isi Sckuncup dan cura jantung yang berdampak
Iangsung terhadap perfusi sistemik. Selain efek langsung terhadop perfusi sistemik,
Penurunan curah jantung juga menurunkan perfusi arieri coroner sebingya terjacdli
iskemia dan kerusakan miokardium yang progresif. Disfungst diastolik berdampak
pada tekanan diastolik akhir ventrikel kiri dan Kongesti paru. Kendisi edema para
akan mempercepat terjadinya hipoksemia jaringan, termasuk pada miokardium.
(Hochman & Ingbar, 2012)
Syok Obstruktif
Syok obstruktif dischabkan oleh ketidakmampuun pasien dalam menghasilkan curah
jamuny yang cukup, walaupun volume intravaskuler dan kontraktilitas: miokardium
134
normal, Keadaan ini dikarenakan aliran darah keluar dari ventrikel terobstruksi secant
mekanik, Penyebab utama obstruksi adalah tamponade pericardium. (Chow JL, 2004)
Syok Distributif
Syok distributif adalah syok yang discbabkan olch maldistribusi volume sirkulast
darah pada tubuh, Ada tiga jenis syok distributif yaitu syok anafilaktik, syok sepsis
dan syok neurogenik, (Chow JL, 2004)
1
Syok anatilaktike
Syok snafilaktik adalah kejadian akut yang berpotensi fatal di mana terjadi reaksi
sistem multiorgan yang discbabkan oleh perilisan mediator kimia dari sel mast
dan basofil, Banyak pemicu yang menycbabkan terjadinya syok anafilaktik.
Makanan adalah pemicu yang paling umum terutama kacang, Selain makanan,
tetdapat obat-abatan (antibiotik, anestesi lokal, analgesik, opiate, dekiran, dan
media kontras), produk-produk biologis (darah, venom, vaksin, ekstrak alergen),
pengawet dan zat adiktif (metabisulfite, MSG) dan lain-lain (lateks dan idiopatik)
Syok sepsis
Syok sepsis tetap menjedi penyebab utama kesakitan dan kematian dalam
berbagai kasus. Infeksi saluran pernapasan dan saluran penecmaan merupakan
tempat yang paling sering terjadi sepsis, diikuti oleh saluran kemih dan infeks!
jaringan lunak, Setiap sistem organ cenderung terinfeksi oleh patogen tertentu.
Syok sepsis disebabkan Olch beberapa hal yaitu bakteri_gram_pasitif,
bakteri gram negatif, parasit dan jamur. Namun, penycbab paling sering adalah
bukteri, Bakteri gram positif adalah organisme utama yang menyebabkan sepsis.
Lalu bakteri gram negatif' menjadi patogen penting yang, menyebabkan sepsis
berat dan syok sepsis.
Syok neurogenik
Syok neurogenik adalah jenis syok distributif dimana terjadi suatu keadaan
hilangnya tonus atonom secant tb;
iba akibat dari cedera tulang belakang,
Syok neurogenik disebabkun oleh usdanya disfungsi sistem saraf otomom dengan
ddisfungsi ganigtia simpatis paravertebral yang mengineryasi segmen
torakolumbal, dimana bagian: ini merupakan persarafan yang berfungsi untuk
mempertahankan tonus pembulul drab perifer. Syok neurogenik disebabkin
oleh adanya cedera tulang belakaing, anestesi umum atau spinal, luka, dan
"
24
kecemasan. Pasien dengan cedera tulang belakang bagian servikal lebih mungkin
untuk berkembang menjadi syok neurogenik.(Chow JL, 2004)
Penatalaksanaaan Univam Syok
Pada pasien dengan syok, dukungan hemodinamik yang dini dan adekuat sangat
penting untuk mencegah disfungsi dan kegagalan organ. Resusitasi scharusnya segera
dilakukan meskipun investigasi penyebab syok masih berjalan. Ketika kausa syok
telah diketabui, penyebab tersebut_harus dikoreksi dengan cepat (eas kontrol
petdarahan, PCI pada sindrom coroner, thrombolysis atau: emnbolektomi pada emboli
pulmonal yang massif, dan pemberian antibiotic dan kontrol sumber infeksi pada syok
sseptik), (Vincent & Backer, 2013)
Manajemen awal syok terdiri atas tiga komponen penting yaitu ventilasi,
resusitasi cairan, dan pemberian agen vasoaktif, Pemberian oksigen sebaiknya dimulai
sesegera mungkin untuk meningkatkan hantaran oksigen dan mencegah hipertensi
pulmonal, Monitoring saturasi dengan pulse oximetry scringkali tidak reliabel akibat
terjadinya ‘vasokonstriksi perifer pada syok sehingga pasien seringkali memerlukun
pemeriksaan gas darah. Intubasi endotrakeal sebaiknya dilakukan untuk memberikan
ventilasi mekanik pada pasion dengan dyspnea berat, hinoksemia, atau asidosis
persisten (pH <7,30). Kelebihan penggunaan ventlasi mekenis adalah berkurangnya
axygen demand dari otot-otot bantu pemapasan dan mengurangi ofierlaad ventrikel
kiri dengan meningkatkan tekanan intratorakal, (Vincent & Backer, 2013)
Resusitasi cairn bertujyan untuk meningkatkun aliran darah mikrovaskuler
dan meningkatkan curah jantung. Hal ini bermanfaat pada semua jenis syok termasuk
syok kardiogen
intravascular efek
‘arena edema pada syok kardiogenik dapat menurunkan eairan
£ Pemberian cairan sebaiknya dimonitor dengan ketat, karena
pemberian cairan yang berlebihan dapat berakibat pada edema dan kensekuensi
lainnya. (Vincent & Backer, 2013)
Jika hipotensi memberat atau menetap setelah dilakukan pemberian cairan,
Penggunoan vasopressor seringkalidiperlukan.Agonis adrenergic merupakan lini
pertuma vasopressor karena onsetnya yang cepat, potensi yang tinggi, dan shaifife
yang rendah schingga memudubkan penyesuaian desis. Norephineprine merupakan
pilihan pertama yasopresser pada syok.dimana pemberiannye dapat meningkatkan
MAP yong signifikan dengan sedikit peningkaton pada laju nadi dan cura jantung.
lo
25
25.1
rikan antara 0,1-2 mey/kg/menit. (Vincent & Backer,
Manajemen Cairan Pada Syok
Kompartemen Cairan Tubuh Manusia
Tubuh manusia terdiri atas dua bagian utama, yaitu agian yany padat (40% berat
badan) dan bagian yang cair (60% berat badan). Bagian yang padat terdiri atas tulang,
kuku, rambut, ott, dan jaringan yang lain. Bagian yang cair merupakan bagian
terbesar, terdiri dari : cairan intraselular (40% berat badan ) dan cairan ekstraselular
(20% berat badan), Sedangkan cairan ekstraselular terdiri dari : cairan intravaskular
(5% berat badan) dan cairan interstitial (15% berat badan) dan cutran transelular
sekitar 1-3% berat badan yang meliputi sinovial, intraokuler dan lain ~ lain, Cairan
intrasetular dan ekstrasclular dipisahkan oleh membran semipermeabel.
i.
Cairan Intraselular
Cairan yang terkandung di dalam set disebut cairan intraseluler. Pada arang
dewasa, sekitar 2/3 dari eairan tubuhnya (40% dari berat badan) terdapat di
intraselular (sekitar 27 liter rata-rata untuk dewasa laki-laki dengan berat bedan 70
kg), sebaliknya pada bayi hanya setengah dari berat badannya merupakan cairan
infraselular. Ruang intraseluler merupakan ruang terhesar (& 25 liter) dimana
kalium mcrupakan kation terbesar, Oleh karcna itu cairan yang mengandung
atrium tidak didistribusi ke intraseluler,
Cairan ekstrasetular
Cairan yang berada di Iuar sel disebut cairan ekstraseluler. Jumlah rel
cekstrasclular berkurang seiring dengan hertambahnya usta, Pada bayi baru ahi,
Sekitur setengah dari cairan tubuh terdapat di ruang ekstraselular (lebih besar dari
f cairan
intraselulur), Perbandingan ini aksn berubah sesuai dengan perkembangan tubub,
sehingga pada dewasa cairan intaselular dua Kali dari eairan ekstraselular, Setelah
vusia 1 tahun, jumlah cairan ekstraselular tenunan satnpai sekitir sepertiza dari
volume total
Caitan ekstraselular dibagi menjadi
+ Cairan Interstitial
Cairan yang mengelilingi sel atau berada di amara sel dan ruany
intravaskuler termasuk dalam catran interstitial, sekitar (10-15% dari
cairan ektraselular}. Cairan limfe termasuk dalam volume interstitial
Relatif terhadap ukuran tubuh, volumenya sekitar 2 kali lipat pada bayi
yang baru Iahir dibandingkan dengan orang dewasa. Cairan interstisial
‘memifasilitasi transpor antara sel dan ruang intravaskuler, Selain air,
reang-ruang intertisial mengandung. elektrolit: dengan predeminan
Kation natrium dengan kensentrasi yang sama dengan mang
intavaskuler,
© Cairn tntravaskular
Merupakan cairan yang terkandung dalam pembuluh darah, misalnya
volume plasma, Rata-rata volume darah orang dewasa sekitar 5-6 liter,
Dimana 3 iiteraya merupakan plasma, sisanya terdin dari sel darah
merah, sé! darah putih dan platelet Sirkulasi mentransportasikan nutrisi
dan oksigen ke scl dan mengangkut hasil metabolisme dan
karbondioksida
252 Pemilihan Cairan Resusitasi
Cairan resusitasi yang ideal digunakon adalah eairan yang menghasilkan peningkatan
cairan intravascular yang bertahan Tama dan dapat diprediksi, memiliki komposisi
yang sedekat mungkin dengan cairan ekstraseluler, dimetabolisme dan diekskrest
sepenuhnya tanpa akumulasi pada jaringan, tidak memiliki efek samping metabolic
dan sistemik, dan cost-effective dalam hal meningkatkan outcome pada pasicn, Akan
tetapi, sampai saat ini tidak ada cairan dengan kurakter seperti cairan ideal di atas
yang tersedia untuk digunekun secara klinis. (Myburgh & Mythen, 2013)
4. Cairan Kristaloid
Cairan kristaloid dapat pindah menembus membrane semipermeable secara bebus.
Kadungannya adalah air dan berbagai clektrolit yang sifatnya isotonic dengan
cairan ekstrasel. Kristaloid yang berbahan dasar satin akan terdistribusi di dalam
rongga ckstrasel, scsuai dengan lokasi terdapamya natrium, Hanya sepertizs
cairan kristaloid yang akan tinggal di dalam pembuluh darah sementara sisanya
akan masuk ke dalm rongga interstitial, (Gaol, et al., 2014)
Larutan normal salin (NaCl 0.9%) metupakan jeais kristaloid yang paling
sering digunakan di seluruh dunia, Larutan salin mengandung natrium dan klorida
dengan konsentrasi yang sama, schingga isotonis dengan cairan ekstrascluler,
in adalah nol, sehingga pemberian satin
Strong ton differenée pada \arutan sal
dalam jumlah besar dapat menychabkan asidosis metabolic hiperkloremik.
(Myburgh & Mythen, 2013)
Kristaloid: dengan komposisi kimia mendekati cairan ekstrascluler disebut
cairan garam fisiologis atau “balanced
‘merupakan heberapa contoh cairan dalam Kategori ini. Jenis cairam ini relatif lebih
hipotonis terhadup cairan ckstraseluler karena memiliki konsentrasi natrium yang
lebih rendah, Pemberian cairan garam fisiologis secara berlebihan dapat
menimbulkan hiperlaktatemia, asidesis. metabolik, dan kardiotoksik (dengan
aasetat). (Myburgh & Mythen, 2013)
Karena risiko kelebihun atrium dan Klorida pada pemberian larutan sain
ger laktwt dan ringer ssetat
dalam jumlah besar, cuiran garam fisiologislebih dirckomendasikan pada pasien
yang menjalani pembedahan, pasien dengan trauma, dan pasion dengan
‘ketoasidosis diabetic, (Myburgh & Mythen, 2013)
‘Cairan Koloid
Cairan koloid tidak thereampur menjadi larutan sei
dan tidak dapat menembus
membrane semipermeable. Koloid cenderung, menetap dalam pembuluh darah
lebih lama dibanding kristaloid karena tidak dapat disaring secara langsung oleh
ginjal, Koloid dapat meningkatkan tekanan osmotic dan menarik cairan keluar
dari rongga interstitial ke dalam pembuluh darah. Koloid digunakan secara
sementara untuk mengganti komponen plasma arena tingal selama beberapa
saat dalam sirkulasi, Lama tinggal suatu koloid dalam pembulub darah bergantung,
pada berat dun ukurar molekul koloid. Jenis cairan koloid yang tersedia antara
lain Gelofusin, Dekstran, starch (HES), dan albumin, (Gaol, et al,, 2014)
Secara umum, penggunaan koloid diindikasikan pada; (1) Resusitasi eairan
pada pasion dengan deficit cairan intravascular berat (e.g syok. hemoragik)
sebelum transfuse darah dapat dilakukan, dan (2) resusitasi cairan pada pasien
dengan hipoalbuminemia berat tau keadaan yang dihubunpkan dengan
kehilangan protein dalam jumlab besar seperti pada luka bakar, Kolvid juga sering
digunakan beramoan dengan kristaloid jika kebutuhan cairang pengganti
melebihi 3.4 L sebelum transfusi, (Butterworth, et al., 2013)
Albumin (4-5%) dalam larutan salin dianggap sebagai eairan koloid rujukan,
Albumin merupekan cairan dengan biaya produksi dan distnbust yang mabal,
schingga hanya tersedlia secara terbatas di negara-negara berkembang, Beberupa
penelition menunjukkan bahwa tidak ads perbedaan outcome yang signifikan
13
aniara resusitasi dengan albumin atau cairan kristaloid(Mybureh & Mythen,
2013) Penclitian SAFE (saline versus albumin fluid evaluation)merupakan,
blinded RCT dengan sampel 6997 pasien dewasa yang dirawat di ICU untuk
mengetalui keamanan penygunaun albumin. Penelitian imi menunjukkan bahwa
tidak ada perbedaan yang bermakna dalam hal angka kematian dalam 28 hari
aniara resusitasi dengan albumin dengan eairah kristaloid (RR 0,99; 95% CL 0,91 -
1,09; P=0,87). Namun analisis lebih lanjut pada penelitian tersebut menunjukkan
Tesusitasi dengan albumin dihubungkan dengan penurunan resiko kematian datum
28 hari pada pasien dengan sepsis berat(OR 0.71; 95% Cl, 0,52 - 0,97, P = 0.03),
Penclitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan resuscitation
endpoints seperti MAP dan laju nadi yang. signifikan pada resusitasi dengan
albumin atau salin. Perbandingan volume albumin dengan salin yang diberikan
untuk mencapai yesuscftation endpoints tersebut 1:1.4(Myburgh & Mythen,
2013)
Hydroxyethy? Starch (HES) merupakan keloid berbahan dasar pati yang
tesproteksi dari hidrolisis. oleh amilase nonspesifik pada darah, sehingga
meningkatkan durasi ckspansi intravaskuler. Akan tetapi, hal ini membuat FES
cenderung terskumulasi di jaringan retikuloendotelial seperti kulit, liver, dan
Binjal. Dosis maksimal HES yang direkomend:
pada jaringan adalah 33-50 mike BB. HE
memiliki konsentrasi yang rendah (6%) dengan berat molekul 130 kD yang
tersedia dalam berbagai jenis cairan krisialoid pembawa, Pada blivided RCT
CHEST(Crisialloid versus Hydroxyethyl Starch Trial yang melibatkan 7000
kan untuk mencegah akumulasi
yang Saat ini sering digunakan
orang dewasa yang dirawat di ICU, didapatkan hasil buhwa tidak ado perbedaan
yang bermokna dalam hal angka kematian dalam 90 hari pada pasien yang
diresusitasi dengan HES dibanding salin (relative risk 1,06; 95% Cl, 0.96 - 1.18; P
0.26); nomun penggunaan HES dihubungkun dengan peningkatan yang
signifikan dalam hal penggunaan terapi pengganti ginjal, Pada penelitian ini juga
didapatkan bakwa perbandiagan volume HES dan kristaloid yang diberikan untuk
meneapai reseucitation endpoints adalah 1:1,3.
25.3) Pemantauan Hemodinamik
Pemantauan hemodinamik penting dilakukan pada pasien syok, terutama untuk
menilai respon terhadap terapi cairan, Secara teorit/s, terapi cairan bertujaan untuk
4
mencapai curdh jantung yang independen terhadap jprefoad, vamun hal ini sulit
dievaluasi secara klinis,(Vincent & Backer, 2013)
Respon pasien terhadap terapi cairan dapat dievaluasi dari beberapa parameter
klinis, seperti tanda vital dar perfusi serta oksigenasi perifer. Kembalit
darah, tckanan nadi dan Taju nadi menandakan perfusi malai membaik, Namun tanda-
ya tekanan
tanda tersebut tidak menggambarkan perfusi pada organ. Perbaikan status mental dan
sirkulasi kulit dapat menandakan perbaiken perfusi, namun tidak dapat dikuastifikasi.
Produksi urin merupakan indicator yang spesifik untuk perfiest ginjal, produksi urin
normal umumnya menandakan aliran darah ginjal yang eukup, Oleh karena itu,
produksi urin merupakan salah satu indicator utama yang dipantau selama resusitasi,
(ACS Commitees on Trauma, 2012)
Fluid challenge merupekan salah satu cara yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi respon terhadap terapi cairan tanpa menimbulkan komplikasi yung
berarti, Terdapat empat elemen dalam fluid challenge yang barus ditentukan
sebelumnya, yaitu: (1) Jenis eairan, (2) Kecepatan pemberian eairan, (3) Parameter
respon, dan (4) Batas keamanan pemberian cairan. (Vincent & Weil, 2006)
Cairan kristaloid sebanyak 300-S00 mi umumnya diberiken dalam 20-30
menit pada fluid challenge. Cairan sebaiknya diberikan dengan cepat untuk
menimbulkan respon yang cepat pula, namun tidak terlalu cepat untuk menghidari
munculnya stress response, Peningkatan tekunan arteri sistemik, penurunan laju nadi,
dan peningkatan produksi urin dapat dinilai sebagai respon terhadam terapi cairan,
Edema pulmonal kareaa gagal jantung kongestif merupakan. komplikasi paling, serius
dari terapi cairan, hal ini dapat dinilai dengan pengukuran central venous pressure
(CVP) pada pasien. (Vincent & Weil, 2006) Fluid challenge dapat diulang.
‘bobcrapakali jika diperlukan, namun harus segera dihentikan jika pasien tidak
‘imerespon untuk mencegah kelebihan cairan, (Vincent & Backer, 2013)
‘Tabel 2.Contoh Fluid! Chaliengepada pasien dengan bipotensi (Vincent & Weil, 2006)
Thiniee mins re
purest teases rr ae
Gre tl | Ge tw ori
Tobel 2 menunjukkan contoh /Puid challenge pada pasien hipotensi dengan
MAP 65 mmbg dan CVP 12 unig. Resusitasi cairan dilakukan dengan ringer laktat
dengan kecepatan 500m1/30 menit. Respon yang diharapkan adalah MAP 75 mmHg
dan batas keamanan yang digunakan adalah CVP.15 mmHg. Pada conteh pertama
(example 1), MAP ceoderung meningkat seiring peningkatan CVP sehinggs fluid
challenge dianggap berhasil dan terepi cairan dapat dilanjutkan. Pada contoh kedua
{example 2) MAP cenderung meningkat pada 10 menit pertama namun menurun
setelah 20 menit sementara CVP terus meningkat dan mencapai batas keamanan
(eafety limit) yaitu CVP 1S mmiig, sehingga fluid challenge dianggap gagal. (Vincent
& Weil, 2006)
Pada pasien dengan ventilasi mekanik, perubaban siklikal pada tekanan
intratoraks menimbulkan perubshon pada preload ventrikel. Peningkatan tekanan
intratoraks selama inspirasi menurunkan venous return dan penurinan lebih lanjut
pada i
hemodinanik yang dipengaruhi ventilusi ini menunjukkan bahwa pulse pressure
sekuncup dan tekanan nadi, Penelitian mengenai perubahan dinamis pada
variation dan stroke volume variation merupakan indikator respon terhadap terapi
cairan yang Sensitive dan spesifik, (Douglas & Walley, 2014)
Passive leg raising (PLR) merupakan salah satu altematif untuk menilai
respon hemodinamik terhadap pemberian cairan karena dapat digunakan sebagai
“selfvohune challenge”, Pada pasien dengan ventilator mekanik yang telah
teradaplasi dengan ventilatornya, perubshan stroke volume pada PLR ditemmukan
menimbulkan respon yung setara dengan pemberian 300 ml koloid. (Monnet &
Teboul, 2008)
Pada pasien dengan posisi 45" semirekumben, PLR dapat dilakukan dengan
merotasikan bed pasien sehingga tubub pasien berada pada posisi horizontal. Metode
ini membuat PLR dapat dilakukan dengan eepat tanpa memicu fleksi pangeul dan
16
perubahan posisi Kateter femoral, Hal ini penting mengingat maneuver pada PLR
sebisa mungkin mengindari munculnya stimulasi simpatik akibat nyeri. (Monnet &
Teboul, 2008)
PLR sebaiknya dilakukan dengan pemeriksaan/pemantauan,kardiovaskular
yang bersifut real-time dan mampu merekam perubahan hemodinamnik dalam 30-90
detik. Perubahon pada tekanon nadi arterial, descending aorta blood flaw, plse-
contour derived stroke volume telah digunakan untuk menilai respon terhadap PLR.
(Monnet & Teboul, 2008)
‘Terapi Cairan Pada Syok Hipovolemik
Pada syok hipovolemik, pemberian cairan bertujuan untuk ekspansi volume
intravaskuler dan mengembalikan venous return, Cairan awal yang dapat diberikan
adaluh cairan isotonik (¢.g normal salin dan ringer laktat) yang dihangatkan sebanyak
142 L untuk orang dewasa dan 20 ml/kg untuk pasien anakeanak. Jenis caitan ini
memberikan ckspansi vaskuler sementara dan lebih lanjut menstabilkan volume
vaskuler dengan mengisi Kehilangan cairan pada ruang, interstitial dan intraselular
(ACS Commitees on Trauma, 2012)
Tujuan resusitasi pada pasien dengan syok hipovolemik adalah untuk
mengembulikan perfusi pada target organ, Hi
ini dicapai dengun penggunaan eairan
restisitusi dan produk darah untuk mengganti volume intravaskuler yang hilang,
Namun, perl diingst bahwa jika tekanan darah naik terlalu cepat sebelum perdarahan
dapat dikontrol, perdahan yang lebih parah dapat terjadi, Penyeimbangan antara
perfusi target organ dengan risike perdarahan vlang dengan menerima tekonan darah
dibawah normal dinamai “permissive ypotension” tau “Aypotensive
resuscitation"(ACS Commitees on Trauma, 2012) Target MAP. dibawah 60-75
mmHg masih dapat diterima pada pasien dengan perdarahan akut tampa gangguan
is yang nyata dengan tujuan untuk mengurangi kehilangan darah dan
koagulepati sampai perdarahan dapat dikomtrol, (Vincent & Backer, 2013)
Berdasarkan respon terhadap pemberian cairan awal, pasien digolongkan
sebagal: rapiel response, inansient response, dan imininal or no eespanse. (Tabel 2)
Pasien yang tergolong. sebagai rapid response umumnya kehilangan darah dalam
jumlalh yang minimal (<20% dari EBV) dan menespan dengan cepat terhadap
pemberian esiran awal, Pasien dalam Kategori’ int juga cenderung memiliki
W
hemodinamik yang stabil setelah terapi cairan awal dikurangi menjadi desis cumatan.
dan transfusi segera pads kategori ini, (ACS
Tidak ada indikasi bolus cairan resusita:
Commitees on Trauma, 2012)
Pasien dengan sransient response memespon terhadap pemberian eairan awal,
homun menunjukkan tanda-tanda perburukin perfusi seteloh terapi cairan dikurangs
menjadi dosis rumatan, Hal ini dapat menunjukkan resusitasi yang kairang memadai
atau proses perdarahan yang masih berlangsung. Pasien dalam katcgori ini umumnya
kehilangan darah sebanyak 20-40% dari EBV, sehinggn umumnya tranfusi darah dan
produk darah dapat diberikan. (ACS Commitees on Trauma, 2012)
‘Transfusi darah dapat dipertimbangkan pada pada pasien dengan perdarahan
yang mosih berlangsung dan kadar hemoglobin 10 mg/dL. Pasien yang teresusitast
umumnya mengalami koagulopati akibat tidak adanya faktor pembekuan pada cairan
kristaloid dan PRC yang diberikan selama resusitasi. Pemberian dini komponen darah
(FFP dan TC) dengan rasio FFP:PRC mendekati 1:1 terbukti meningkatkan survival
padapasien dengan syok hemoragik. (Maier, 2012)
Pasien dengan minimal or na response umumnyatidak merespon terhadap
pemberian cairan owal, Hal ini menunjukkon diperlukannya terapi definitive (eg
operasi atau embolisasi) untuk mengchentikan perdarshan, Pada beberapi kasus
kegagalan dalam merespon juga dapat disehabkan gangguan pada jantung. akibat
trauma tumpul jantung, tamponade jantung, dan tensian preumothorax. Syak non-
hemoragik harus dipertimbangan sebagai diagnosis banding pada pasien dalam
kategori ini, (ACS Commitees on Trauma, 2012)
‘Tabel 3. Respon Terhadap Pemberian Caitan Awal(ACS Commitecs on Trauma, 2012)
APIO RESPONSE | TRANSIENT RESPONSE MINIMAL OR WO RESPONSE
Wiad ges Fetus 19 nowmal
eran ance
‘Etimated Meo Dons Meat
tame20m)
tow oe to mode Moder 35 bide to rin
severe 5051)
Wee for mare crpatont
x eae ror
[pe tes wen | Teese
= a
eae e
‘25.2 Terapi Cairan Pada Syok Sepsis
Sepsis berat dan syok sepsis merupakan guangguan yang sering dihadapi oleh Klinisi di
ICU, Pada pasien dengan sepsis berat dan syok sepsis umumaya nengalimi
Penurunan efektivitas sirkulasi arterial akibat vasodilatasi bersamaan dengan
terjadinya gangguan cardiae oupni. Penatalsksanaan syok septik menggunakan
‘manajemen kamprehensif untuk mempeshaiki outcome, yaitu protacol EGDT (Early
Goals Directed Therapy), Penataloksanaun syok sepsis dengan resusitasi cairan dini
secara EDGT telah terbukti menurunkan angka disfungsi organ dan mortalitas rumah
‘sokit dibandingkan dengan terapi standar, Selain itu EDGT juga dikaitkan dengan
lama petawatan di rumah sakitdan biaya perawatan yang lebih minimal. Prioritas
utama pada EDGT adalah stabilisasi jalan napas dan perapasan, Protokol EGDT
dimnulai dengan bolus 20 mL/kg bb krisialoid atau koloid diberikan dalam Kurun
waktu 30 menit untuk mencapai CVP 8-12 mmHg. Jika MAP kurang dati 65 mmHg,
diberikan vasopressor, dan MAP. yang lebih dari 90 mmHg, diberikan vasodilator
sampai mencapai 90 mmHg atau kurang, Jika saturasi oksigen vena sentral (SovO2)
kurung dari 70% dan kadar hematokrit < 30%, diberikan sel darah merah yang
dimampatkan (PRC). Apabils sotelah diberikan tranfusi PRC kadar SevO2 masih <
70%, diberikan inotropic dobutamin mulai dengan dosis 2,Suwkubb per menit, Dosis
tersebut dapat dinaikkan 2,5 pgkgbb per menit setiap 30: menit sumpai SevO2
meneapai 70 persen atau lebih ataw sampai dosis maksimal 20 jug/kbb per menit.
Dosis dobutamin diturunkan ataupun dihentikan jika MAP kurang dari 63 mmHg atau
jika denyut jantung diotas 120 kali per menit, Untuk mengurangi konsumsi oksigen,
pasion dengan kondisi hemodinamik yang belum optimal diberikan ventilasi mekanik
dan sedatif. (Widyanti, é1 al., 2012)
Pemilihan cairan resusitasi pada syok septik juga masih menjadi topik yang
kontroversial, Kristaloid cenderung lebih murah, dengan cepat mengisi kompartemen
intravascular don ekstravaskular, meningkatkan perfusi target orga, dan merniliki
risiko reaksi anafilaktoid yang minimal. Sementara koloid dengan capat
menirigkatkan volume intravascular dan tekanan onkotik, dengan demikian resusitasi
dapat memerlukan waktu dan volume eairan yang tebih sedikit. Resusitasi dengan
Koloid dapat meningkatkan transport oksigen, Konraktilitas miokardium, dan curah
Jantung, Akan tetapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa HES. yang merupakan
salah satu jenis koloid meningkatkan risike kematian dan diperlukannys terapi
pengganti ginjal dibanding penggunaan kristaloid, Penggunaan albumin dibanding
kristaloid pada resusitasi di pasien ICU memiliki risiko kegagalan target organ, waktu
rawat di ICU, terapi pengganti ginjal, dan kematian yang suma. Akan tetapi, analisis
subgroup pada pasicn dengan sepsis berat menunjukkan risiko kematian yang lebih
rendah, (Douglas & Walley, 2014)
BABII
SIMPULAN
Syok adalah sindrom Klinis akibat kegagalan sirkulasi dalam mencukupi kebutuhan oksigen
Jjaringan tubuh, Pada kondisi syok, terjadi ganyguan hemedinamik yang menyebabkan tidak
edekuatnya hantaran oksigen dan perfusi jaringan, Diagnosis syok dapat ditegakkan dengan
eit ki
hemodinamik, dan biokimia yang meliputi hipotensi, takikardi, penurunan
‘perfusi pada kulit, penurunan produksi urin, perubahan status mental dan. kadar asam laktat
pada darah.
Secari umum syok digolongkan menjadi beberapa kategori berelasarkan penyebab,
itu: (1) Syok hipovolemik (dari kehilangan cuirun internal maupun ekstemal), (2) Syek
Aardiogenik (pompa jantung terganggu, contohnya pada AMI, kardiomiopati, miokarditis,
"dap aritmnia), (3) Syok obsiruktif (hambatan sirkulasi menuju jantung, contohnya pada emboli
‘pant, tomponade jantung, atau pneumothorax), dan (4) Syok distributif (vasomotor tergangeu,
-contolinya pada sepsis dan anafilaksis),
‘Terapi cairan pada syok bertujuan untuk memperbaiki aliran mikrovaskular dan
atkan curah jantung dan merupakan bagian esensial dari terapi pada semua j
Akan (ctapi, terapi cairan harus dimonitor dengan ketat, karena pemberian cairan tertalu
meningkatkan risiko edema dengan kensekuensinya yang tidak diinginkan,
DAFTAR PUSTAKA
ACS Commitees on Trauma, 2012. Advanced Trauma Life Suppart (ATES) Student Course
Manual. 9h ed, Chicago: American College of Surgcons,
Butterworth, J. F., Mackey, D.C. & Wasnick. J.D, 2013. Morgan & Mikhail's Clinical
Anesthesiology, Sth ed. New York: McGraw-Hill,
‘Chow JL, BK. a. B, L., 2004, Critica! Care Handbook of the Massachusetts General Hospital,
rd od. US: Lippincott Williams & Wilkins
“Douglas, J. J. & Walley, K. R. 2014, Fluid choices impact outcome in septic shack. Current
Opinion Critical Care, Issue 20, pp. 378-384.
‘Gaol, H.L., Tanto, C..& Pryambodho, 2014. Terapi Cainm. In: C. Tando, F. Liwang, 8. Hanifati
AE. A. Pridipta, eds. Kapita Selektu Kesdokieran. Jakiirta: Media Aesculapius, pp. 561-564.
‘Hall, J. B., 2006, Guytan's Teubook of Medicad Physialogy. | cd. Philadelpia: Elsevier.
‘Hardisman, 2013. Memahamti Patofisiologi dan Aspek Klinis Syok Hipovolemik: Update dan
svewar, diurnal Kesehatan Andatas, U3), pp. 178-182.
shnan, J. $. & Ingbar, D. H., 2012. Cardiogenie Shock and Pulmonary edema, In; D. L.
‘Longo, et al. cds. Harrison's Principle of Internal Medicine. New York: McGraw-Hill, pp. 2232-
2237.
‘Leksuna, Ery, 2015. Dehidrasi dan Syok. Cermin Dunia Kedokteran, Volume 42, Issue 5, pp
1-395
Maier, R.V., 2012. Approsch to The Patient With Shock, In: D. L. Longo, et al. ects. Harrison's
“Principles of Incernat Medicine. New York: MeGraw-Mill, pp, 2215-2222.
“Mangku, G. & Senapathi, TG. A. 2010. Bukir Afar Mma Anestesia dan Reanimasi, 1st ed,
Jakarta: Indeks,
“Monnet, X. & Teboul, J.-L, 2008, Passive Ley Raising. Jiitensive Care Medicine, Volume 34,
p> 659-663,
‘Myburgh, J. A. & Mythen, M.
i a, E., 2010, Terapi Cairan Pada Syok. Universitas Sumatera Utaru, pps 1-42.
B., 2008, Diagnosis dan Penatalaksanaan Syok Pada Dewasa. Clinica! Updates, pp. 44
2013. Resuscitation Fluids, NEJM , Issue 369, pp. 1243-1251,
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- 5 Fab 8 Ac 66 F 02 C 7099 FC 51 Eb 0Document1 page5 Fab 8 Ac 66 F 02 C 7099 FC 51 Eb 0Bima PerwirayudaNo ratings yet
- Tension Headache RevisiDocument1 pageTension Headache RevisiBima PerwirayudaNo ratings yet
- Ijazah AsliDocument1 pageIjazah AsliBima PerwirayudaNo ratings yet
- 5 Facb 1 BD 6 F 02 C 7099 FC 52048Document1 page5 Facb 1 BD 6 F 02 C 7099 FC 52048Bima PerwirayudaNo ratings yet
- FR New - For MergeDocument132 pagesFR New - For MergeBima PerwirayudaNo ratings yet
- Asyncrounus Agenda 1: Tugas 1 Selasa, 21 Juni 2022: Latsar Cpns Golongan Iii Angkatan Xvii Kelompok 4Document4 pagesAsyncrounus Agenda 1: Tugas 1 Selasa, 21 Juni 2022: Latsar Cpns Golongan Iii Angkatan Xvii Kelompok 4Bima PerwirayudaNo ratings yet
- Seminar Ra Gol III A. Xvii-3-1Document1 pageSeminar Ra Gol III A. Xvii-3-1Bima PerwirayudaNo ratings yet
- Pemberitahuan Habituasi G4Document4 pagesPemberitahuan Habituasi G4Bima PerwirayudaNo ratings yet
- Perwal 70 Tahun 2021 Uptd DinkesDocument9 pagesPerwal 70 Tahun 2021 Uptd DinkesBima PerwirayudaNo ratings yet
- Template RA New OKDocument20 pagesTemplate RA New OKBima PerwirayudaNo ratings yet
- Kartu Tanda Peserta Ujian Kartu Tanda Peserta UjianDocument1 pageKartu Tanda Peserta Ujian Kartu Tanda Peserta UjianBima PerwirayudaNo ratings yet
- Certificate: Presented ToDocument1 pageCertificate: Presented ToBima PerwirayudaNo ratings yet
- Referat Tumor Ginjal Rod FixDocument18 pagesReferat Tumor Ginjal Rod FixBima PerwirayudaNo ratings yet
- Soal TO AIPKI 7 April 2018Document95 pagesSoal TO AIPKI 7 April 2018Bima PerwirayudaNo ratings yet
- 5faa2bc56f02c709a8c4f006 PDFDocument1 page5faa2bc56f02c709a8c4f006 PDFBima PerwirayudaNo ratings yet
- Anamnesis Mata PDFDocument15 pagesAnamnesis Mata PDFBima PerwirayudaNo ratings yet