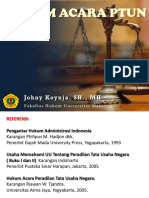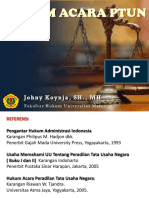Professional Documents
Culture Documents
Efektivitas Eksekusi
Uploaded by
LuthfieIbnu'AliOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Efektivitas Eksekusi
Uploaded by
LuthfieIbnu'AliCopyright:
Available Formats
EFEKTIVITAS EKSEKUSI PADA PASAL 116 UU No 5 TAHUN 1986 YANG TELAH DIUBAH MENJADI UU No 9 TAHUN 2004 TENTANG PTUN
I. PENDAHULUAN Ketika para pendiri Bangsa (The founding fathers) mendesain model Negara Indonesia setelah merdeka lebih mengedepankan perdebatan mengenai dasar Negara, bentuk Negara (kesatuan atau federal), bentuk pemerintahan (Kerajaan atau Republik) dan ide/ cita Negara (individualistik, kolektivistik, atau totalitas integralistik) yang sedikit terkait dengan Negara hukum dan pemerintahan yang demokratis konstitusional khususnya mengenai perlu tidaknya Hak Asasi Manusia (HAM) masuk dalam konstitusi, selain itu the founding fathers sebagian besar terlalu di semangati oleh obsesi sebuah bangunan Negara yang berciri khas Indonesia sehingga terlalu mengidealisasikan prinsip kekeluargaan, demokrasi desa, asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan demi politik pengintegrasian ketimbang politik pembebasan melawan absolutisme kekuasaan sebagai corak paham konstitusionalisme, yang akibatnya bangsa ini tidak pernah curiga terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan (Mukthie Fadjar, 2003: 3-4) yang oleh Lord Acton disebut sebagai hukum batu power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely (Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula). Ketidakjelasan UUD 1945 dalam
menyatakan Negara Indonesia sebagai Negara hukum juga tercermin dalam pengkaidahan prinsip- prinsip yang harus melekat dalam suatu Negara hukum, juga dalam dimensi penerapan konstitusi sebagai aturan main dalam bernegara, baik pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1967) maupun Presiden Soeharto (19671998) Indonesia telah terjebak sebagai Negara kekuasaan (machtsstaat) ketimbang Negara hukum (rechtsstaat), Interprestasi konsitusi sesuai dengan selera pribadi sehingga legitimasi kekuasaan semakin kuat dan melemahkan sendi-sendi peradilan (hukum), rezim Presiden Suharto yang berkuasa selama 32 tahun pun akhirnya harus mengakui kuasa rakyat, gerakan reformasi rakyat berkobar seiring tuntutan reformasi konstitusi, gerakan reformasi telah membawa nuansa baru dalam dinamika politik ketatanegaraan Indonesia, orde baru yang begitu mensakralkan UUD 1945 telah mengalami desakralisasi, sakralisasi UUD 1945 berakhir setelah aspirasi rakyat Indonesia (representation in ideas) kemudian dilanjutkan oleh wakil rakyat (representation in presence) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengamandemen UUD 1945. Selain itu UUD 1945 dan peraturan perundangundangan di bawahnya tidak menjamin kemandirian badan peradilan, termasuk didalamnya Peradilan Tata Usaha Negara sehingga wajar kalau lembaga judikatif seolah-olah menjadi lembaga penghukum musuh-musuh politik penguasa dan warga negara yang menjadi pembangkang dan melawan ketidakadilan penguasa dan bisa dikatakan bahwa lembaga judikatif adalah lembaga yang memberikan legitimasi hukum ketidakadilan pemerintah.
Kondisi ini merupakan suatu fakta hukum yang memprihatinkan bahwa keberadaan lembaga yudikatif, khusunya Peradilan Tata usaha Negara belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Setelah Amandemen UUD 1945, eksistensi Negara hukum tertuang jelas dalam konstitusi, salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya lembaga yudikatif yang independent and impartial judiciary, lembaga yudikatif tersebut merupakan tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum, baik dalam kerangka penyelesaian perkara pidana, perdata, tata Negara maupun tata usaha Negara, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari kekusaan kehakiman yang merdeka dan secara heirarki berada di bawah Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Indonesia sebagai negara demokrasi wajib memberdayakan rakyatnya, menghormati hak-hak rakyatnya, dan berupaya mewujudkan civil society. Salah satu elemen penting perwujudan kedaulatan rakyat dan civil society adalah adanya Pengadilan TUN yang kuat dan dapat memberikan rasa keadilan kepada rakyatnya. Melihat kenyataan ini, jelas keberadaan lembaga eksekutorial dalam PTUN beserta landasan hukumnya merupakan kebutuhan mendesak. Selama duapuluh dua tahun eksistensi PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) di Indonesia, dirasakan masih belum memenuhi harapan masyarakat
pencari keadilan. Banyaknya putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi telah menimbulkan pesimisme dan apatisme dalam masyarakat. Masalahnya adalah penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Permasalahan eksekusi putusan PTUN ini juga dapat timbul terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah, karena dengan adanya otonomi daerah seluruh pejabat kepala daerah di kabupaten/kota memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola daerahnya dan hal tersebut pasti menggunakan metode
keputusan-keputusan administratif. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis sedikit akan
mengkaji masalah tersebut dalam sebuah makalah dengan judul :
B. RUMUSAN MASALAH Dalam penulisan ini dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah efektivitas penerapan eksekusi pada pasal 116. UU No. 5 tahun 1986 yang telah diubah menjadi UU No. 9 tahun 2004? 2. Apa yang kemudian menjadi solusi kongkrit atas permasalahan yang ada? C. TINJAUAN PUSTAKA Keputusan Tata Nsaha Negara adalah : suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hokum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hokum bagi seorang atau badan hokum perdata. Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjutan dalam hal melaksanakan putusan perngadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum yang sah (in kracht). Eksekusi putusan pengadilan adalah, pelaksanaan putusan Pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah ; eksekusi putusan untuk, membayar sejumlah uang, dan menyerahkan suatu barang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sarana-sarana yang tersedia untuk melaksanakan suatu putusan yang bersifat langsung yang berupa, kuasa yang diberikan hakim untuk membatalkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan (pasal 1240 KUH Pdt), eksekusi oleh juru sita, penyitaan yang diikuti dengan pelelangan dimuka umum, suatu putusan yang
menggantikan akte atau pernyataan pihak terhukum. Bersifat langsung berupa, penyanderaan dan pembebanan uang paksa.
D. PEMBAHASAN 1. PENERAPAN EKSEKUSI PADA PASAL 116. UU No. 5 TAHUN 1986 YANG TELAH DIUBAH MENJADI UU No. 9 TAHUN 2004 Pada perundang-undangan administrtif maupun dalam praktek pemerintahan sehari-hari, disitu selalu sangat diperhatikan bagaimana caranya serta dengan sarana-sarana apa saja suatu tujuan pemerintahan disuatu bidang kehidupan masyarakat itu dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, jadi dalam hal ini segi efektifitas dan efesiensi (doelmatigheid) merupakan hal-hal yang sangat diperhatikan dalam hukum Tata Usaha Negara. (Indroharto SH. 1995: 16-17). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan pemerintah itu harus dapat menghasilkan perlindungan bagi kepentingan rakyat. Apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka kepentingan rakyat tidak semena-mena dapat dikorbankan begitu saja. Demikian juga semangat prinsip dari PTUN tersebut harus diterapkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kewenangan yang besar dan luas menimbulkan potensi
penyelewenangan seperti abuse of power dan excessive power sehingga dibutuhkan pengawasan yang serius dalam hal ini. Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari pejabat TUN. Dengan penegoran sistem hirarki seperti diatur dalam UU No. 5 tahun 1996 terbukti tidak efektif dalam pelaksaan putusan PTUN. Bahwa dalam pasal 115 UU PTUN disebutkan bahwa: Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap yang dapat dieksekusi. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hokum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hokum tidak dapat dimintakan eksekusinya(Zairin Harahap. 1997: 150) Baru-baru ini pemerintah telah sadar akan tumpulnya pelaksanaan putusan PTUN yang hanya menyandarkan pada kesadaran yang dirasa kurang efektif sehingga pemerintah mengundangkan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun perubahan yang mendasar dalam UU No. 5 tahun 1986 terletak pada Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5). Sehubungan dengan butir yang ke-empat tersebut yaitu masalah eksekusi, perlu disampaikan perkembangan baru revisi
undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 116, UU No. 5 tahun 1986 berbunyi sebagai berikut: 1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari; 2) Dalam hal empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajibannya tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut; 4) Jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya, ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan; 5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah pemberitahuan dari Ketua pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut;
6) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal in kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Pasal 116, UU No. 9 tahun 2004 berbunyi sebagai berikut: 1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari; 2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi; 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;
4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi adminsitratif; 5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Beberapa problema dalam implementasi Pasal 116 baru tersebut dapat timbul dan harus dipecahkan jalan keluarnya, meskipun adanya revisi Pasal 116 dapat dikatakan merupakan kemajuan dalam pengembangan kepastian hukum bagi pelaksanaan (eksekusi) suatu Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 116 lama, pelaksanaan putusan lebih bersifat dan mengandalkan pada paksaan oleh instansi hiekrarkis sendiri yang banyak tergantung pada tingkat kesadaran hukum tergugat. Sedangkan Pasal 116 baru mengenal 2(dua) jenis upaya paksa yang dapat diterapkan manakala pihak tergugat (baca: Pejabat Tata Usaha Negara) tidak mentaati dan melaksanakan secara suka rela putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: a) Upaya paksa berupa sanksi administrasi dan atau;
b) Upaya paksa berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) dan masih dapat diterapkan pula kemungkinan untuk adanya sanksi pengumuman (publikasi) putusan dalam media massa cetak.
adanya
penjatuhan
uang
paksa
bagi
pejabat
TUN
yang
tidak
melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif serta publikasi di media cetak diharapkan mampu membuat efek jera terhadap para pejabat TUN yang sebelomnya sulit untuk dijerat. Pemberlakuan uang paksa merupakan salah satu tekanan agar orang atau pihak yang dihukum mematuhi dan melaksanakam hukuman. Namun, dalam penerapannya pemberlakuan uang paksa (dwangsom) masih menimbulkan permasalahan antara lain jenis putusan apa yang dapat dikenakan uang paksa (dwangsom), siapa yang akan dibebankan uang paksa (dwangsom), dan sejak kapan uang paksa (dwangsom) diberlakukan. Bahwa penerapan dwangsom tidak dapat dapat diterapkan pada semua putusan PTUN. Penerapan dwangsom hanya dapat dibebankan pada putusan PTUN yang bersifat penghukuman (putusan condemnatoir). Pejabat TUN yang sedang menjalankan tugasnya dalam kedinasan dan kemudian menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat, namun tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum maka kerugian yang dialami masyarakat haruslah dibebankan kepada negara. Karena merupakan kesalahan teknis dalam menjalankan dinas. Lain halnya jika pada saat pejabat TUN tidak patuh untuk melaksanakan putusan PTUN maka pada saat tersebut pejabat TUN tidak sedang melaksanakan peran negara. Apabila terjadi hal demikian maka pertanggung
jawabannya
dibebankan
secara
pribadi
kepada
pejabat
TUN
yang
bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori kesalahan yang dikembangkan dari Yurisprudensi Counsil dEtat yang membedakan kesalahan dinas (Faute de serve) dan kesalahan pribadi (Faute de personelle). Dalam pelaksanaan penerapan uang paksa, mekanisme pembayaran uang paksa juga perlu diperhatikan, karena yang dihukum untuk melaksanakan putusan PTUN adalah pejabat TUN yang masih aktif yang masih mendapatkan gaji secara rutin. Maka akan lebih efektif jika pengenaan dwangsom diambil dari gaji bulanan pejabat TUN yang bersangkutan. Dan perintah pemotongan gaji dalam amar putusan hakim diperintahkan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Namun untuk melaksanakan pembayaran uang paksa yang dikenakan kepada pejabat TUN yang bersangkutan masih menimbulkan kendala. Kendala yang pertama adalah apabila dalam pelaksanaan eksekusi ternyata pejabat TUN yang bersangkutan dipindah tugaskan ke tempat wilayah kerja KPKN yang berbeda. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala pertama adalah dengan adanya koordinasi antara PTUN yang satu dengan PTUN yang lain, dan antara PTUN dengan Pengadilan Negeri jika ternyata pejabat TUN bersangkutan pindah ditempat yang tidak ada PTUN. Kendala selanjutnya adalah apabila gaji pejabat yang bersangkutan tidak mencukupi untuk membayar uang paksa. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hal ini adalah dengan cara pejabat bersangkutan dapat
mengangsur setiap bulan dengan mempertimbangkan sisa gaji yang layak untuk biaya hidup. Lalu satu lagi sanksi yang dapat dikenakan pada pejabat TUN yang membandel adalah sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat diberikan berdasarkan PP No. 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, pembebasan dari Jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi administratif berupa pembebasan dari jabatan adalah paling tepat karena pada saat ia tidak mematuhi putusan PTUN maka pada saat itu ia tidak mau menggunakan kewenangan jabatannya. Perintah penjatuhan sanksi administratif ditujukan kepada pejabat yang berwenang untuk menghukum pejabat TUN tersebut. Namun, dalam hal apabila pejabat TUN adalah gubernur dan bupati karena sesuai dengan UU Otonomi Daerah secara hirarki ia tidak mempunyai atasan sebagai pejabat yang berwenang untuk menghukum, maka dalam hal ini tentunya hakim dapat memilih pengenaan uang paksa (dwangsom). Langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk merevisi Pasal 116 UU No. 5 tahun 1986, menjadi UU No. 9 tahun 2004, merupakan salah satu kemajuan dari perkembangan kepastian hukum. Namun ketentuan Pasal 116 UU No. 9 tahun 2004 tersebut masih belum efektif dilaksanakan. Untuk melaksanakan Pasal 116 UU No. 9 tahun 2004 tersebut diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan dan petujnjuk teknis. Diharapkan dengan adanya revisi
tersebut pelaksanaan otonomi daerah dapat terkontrol dengan seimbang dan adil sehingga membawa kemakmuran bagi masyarakat. Pada hakekatnya supremasi hukum hanya dapat tercapai kalau putusan pengadilan c.q. putusan PTUN dapat dieksekusi sehingga menimbulkan efek jera kepada para pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Sehingga masyarakat tidak lagi pesimis dan apatis dengan penegakan hokum saat ini. E. KESIMPULAN Sebenarnya penerapan pasal 116, UU No. 9 tahun 2004 sudah menjadi lebih baik dari pada sebelom di revisi.Hal ini dapat dilihat dari sangsi yang lebih berat didalamnya. Namun Uang paksa (dwangsom) masih menimbulkan permasalahan, antara lain jenis putusan apa yang dapat dikenakan uang paksa (dwangsom), siapa yang akan dibebankan uang paksa (dwangsom), dan sejak kapan uang paksa (dwangsom) diberlakukan. Bahwa penerapan dwangsom tidak dapat dapat diterapkan pada semua putusan PTUN. Penerapan dwangsom hanya dapat dibebankan pada putusan PTUN yang bersifat penghukuman (putusan condemnatoir). Langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk merevisi Pasal 116 UU No. 9 tahun 2004 merupakan salah satu kemajuan
dari perkembangan kepastian hukum. Namun ketentuan Pasal 116 UU No. 9 tahun 2004 tersebut masih belum efektif dilaksanakan. Untuk melaksanakan Pasal 116 UU No. 9 tahun 2004 tersebut diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Diharapkan nantinya dengan adanya kepastian tentang pejunjukpetunjuk tersebut pelaksanaan UU Pasal 116 No. 9 tahun 2004 dapat terkontrol dengan seimbang dan adil sehingga membawa kepastian hukum bagi masyarakat. F. SARAN Kaitanya dengan kesimpulan tersebut diatas, penulis
memberikan saran sebagai berikut : 1) Perlunya merevisi kembali pasal 116 UU No. 9 tahun 2004 guna didapatkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang efektif, terjamin, demokratis dan jelas. Dengan revisi tersebut semoga pelaksanaan UU No. 9, tahun 2004. Terutama pada pasal 116, lebih efektif, demokratis dan terjamin. 2) Perlunya penerapan prinsip good governance sehingga
pelaksanaan pemerintahan akan lebih transparan, berpihak pada demokrasi dan kemakmuran rakyat. Dan konflik-konflik mengenai sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, bisa lebih berkurang. Jika sudah diputus oleh Pengadilan TUN, maka
pelaksanaannya lebih mudah ditaati dan terselesaikan dengan kepastian hokum yang konkrit.
DAFTAR PUSTAKA Mukthie Fadjar, Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik, InTrans, Malang, 2003, hlm (3-4). Indroharto, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara BogorJakarta, 1995, hlm. (16-17). Zairin Harahap. 1997. HukumAcara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: PT.Raja Grafindo Persada Indroharto,SH, UU No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002. Prof. Drs, C. S. T. Kansil, SH. Dan Cristine S. T. Kansil, SH., MH. UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. PT. PRADNYA PARAMITA, Jakarta, 2006. Prof. Drs, C. S. T. Kansil, SH. Dan Cristine S. T. Kansil, SH., MH. Kitab UU Hukum Acara Peradilan, PT. PRADNYA PARAMITA, Jakarta, 2006. PP No. 30 tahun 1999 Tentang Disiplin Pegwai Negeri. http:// Wikipedia.com
You might also like
- Materi Ipp Kel.9Document6 pagesMateri Ipp Kel.9Alya RahmadellaNo ratings yet
- Bab I PendahuluanDocument27 pagesBab I PendahuluanAdipati DoakenNo ratings yet
- Pengantar Ilmu PolitikDocument7 pagesPengantar Ilmu PolitikAmbulu88 TravelNo ratings yet
- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik FixDocument15 pagesAsas Umum Pemerintahan Yang Baik FixBtiarAshariImanuddinNo ratings yet
- HanDocument5 pagesHanilmiyatiaidaNo ratings yet
- Fungsi Beschikking Sebagai Pengisi Ketiadaan AturanDocument15 pagesFungsi Beschikking Sebagai Pengisi Ketiadaan AturanbonethankzNo ratings yet
- Jurnal Penegakan Hukum - PTUN 2007Document22 pagesJurnal Penegakan Hukum - PTUN 2007Trisna RamadaniNo ratings yet
- ArtikelhtnDocument8 pagesArtikelhtnSofy Aprillia LihawaNo ratings yet
- 4979 12485 1 PBDocument20 pages4979 12485 1 PBItwil4 Itwasum PolriNo ratings yet
- Tugas Makalah PtunDocument13 pagesTugas Makalah PtunRiska Mayangsari Aas50% (8)
- Efektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha NegaraDocument16 pagesEfektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha NegaraKHODIJAHNo ratings yet
- Hukum Tata Usaha NegaraDocument4 pagesHukum Tata Usaha NegaraChandra DewiNo ratings yet
- PutriRamadhona 031152585 T2 ISIP4213Document5 pagesPutriRamadhona 031152585 T2 ISIP4213PutriNo ratings yet
- Bab Ix Peradilan Administrasi NegaraDocument4 pagesBab Ix Peradilan Administrasi NegaraHany CahyaniNo ratings yet
- MUHAMAD RAFI MUHARROM - 1203050092 - 5B - Artikel Hukum Acara Mahkamah Konstitusi PerbaikanDocument10 pagesMUHAMAD RAFI MUHARROM - 1203050092 - 5B - Artikel Hukum Acara Mahkamah Konstitusi PerbaikanMuhamad Rafi MuharromNo ratings yet
- MUHAMAD RAFI MUHARROM - 1203050092 - 5B - Artikel Hukum Acara Mahkamah KonstitusiDocument10 pagesMUHAMAD RAFI MUHARROM - 1203050092 - 5B - Artikel Hukum Acara Mahkamah KonstitusiMuhamad Rafi MuharromNo ratings yet
- HAN KE-4 2Document13 pagesHAN KE-4 2tzf8g7s2hnNo ratings yet
- Makalah Hukum AcaraDocument35 pagesMakalah Hukum Acarayusupspeed0% (1)
- HUKUM ACARA PTUN - Johny Koynja, SH., MH - Fak - Hukum Universitas MataramDocument25 pagesHUKUM ACARA PTUN - Johny Koynja, SH., MH - Fak - Hukum Universitas MataramJOHANNES JOHNY KOYNJA, S.H., MHNo ratings yet
- 3855 5503 1 PBDocument23 pages3855 5503 1 PBsalsa BilNo ratings yet
- Badan YudikatifDocument9 pagesBadan YudikatifDiyaa DibajjNo ratings yet
- 1 SMDocument11 pages1 SMAris Fireman HidayatNo ratings yet
- FUNGSIDocument15 pagesFUNGSIOmas trio prawiraNo ratings yet
- Politik HukumDocument10 pagesPolitik HukumMunawaroh IsrotulNo ratings yet
- Bahan Ajar Diktat Hukum Acara PtunDocument55 pagesBahan Ajar Diktat Hukum Acara PtunNazaruddin LathifNo ratings yet
- Asas Hukum Acara Tata Usaha Negara - IsiDocument16 pagesAsas Hukum Acara Tata Usaha Negara - Isiramadana vikramNo ratings yet
- Tugas Kelompok KEKUASAAN KEHAKIMAN 2Document11 pagesTugas Kelompok KEKUASAAN KEHAKIMAN 2Zahwaa RiskaNo ratings yet
- Jawaban No. 4 & 5 - Uts Hukum PidanaDocument8 pagesJawaban No. 4 & 5 - Uts Hukum PidanaInes TeresaNo ratings yet
- Rehan DheoDocument6 pagesRehan DheoRehan Dheo Pratidina Widaryono PutraNo ratings yet
- Makalah PPKN KELOMPOK 6Document7 pagesMakalah PPKN KELOMPOK 6AprkrstnaNo ratings yet
- Penyimpangan Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Bahan 3Document7 pagesPenyimpangan Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Bahan 3nindyaNo ratings yet
- Kurniawan Tri Wibowo, SH, MHDocument13 pagesKurniawan Tri Wibowo, SH, MHKurniawan Tri WibowoNo ratings yet
- SKRIPSIDocument200 pagesSKRIPSIifalNo ratings yet
- Tugas Hukum Tata Negara 2 Risnalia BairestyDocument8 pagesTugas Hukum Tata Negara 2 Risnalia BairestyDimas Okta VianNo ratings yet
- Tugas Uas Ptun - SuhargilDocument10 pagesTugas Uas Ptun - SuhargilLuyNo ratings yet
- Materi HAPTUN 1Document10 pagesMateri HAPTUN 1SINDY NUR FITRIYANINo ratings yet
- Penggunaan Asas Functionare de FaiteDocument14 pagesPenggunaan Asas Functionare de FaiteChristo ValentinoNo ratings yet
- Tugas Han Mengenai Instrumen PemerintahanDocument12 pagesTugas Han Mengenai Instrumen Pemerintahanchristopher_silabanNo ratings yet
- Ahsan Selayang Pandang MK Relasi JR Dan MK - 13635 - 0Document14 pagesAhsan Selayang Pandang MK Relasi JR Dan MK - 13635 - 0Marwah UddiNo ratings yet
- Teori Perundang-UndanganDocument3 pagesTeori Perundang-UndanganGlenn Kevin Immanuel GiriNo ratings yet
- Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tat 8ab9a9b1Document29 pagesEksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tat 8ab9a9b1Fiska Nadia 1909124052No ratings yet
- 1 SMDocument11 pages1 SMNissa Nii Shasa MuzakkiNo ratings yet
- Proposal SkripsiDocument19 pagesProposal SkripsiWawan DharmawanNo ratings yet
- Suci Aura Nissa - LR IndividuDocument9 pagesSuci Aura Nissa - LR IndividuSarahNo ratings yet
- HUKUM ACARA PTUN - Johny KoynjaDocument48 pagesHUKUM ACARA PTUN - Johny KoynjaJohny KoynjaNo ratings yet
- Nila Permatasari-He Sore-2106784775-72-Makalah Kecil KeduaDocument25 pagesNila Permatasari-He Sore-2106784775-72-Makalah Kecil KeduaNayla AuliaNo ratings yet
- Nila Permatasari-He Sore-2106784775-72-Makalah Kecil KeduaDocument25 pagesNila Permatasari-He Sore-2106784775-72-Makalah Kecil KeduaNayla AuliaNo ratings yet
- 6439 21460 1 PBDocument16 pages6439 21460 1 PBYunasril LGNo ratings yet
- G. Bab 1Document31 pagesG. Bab 1Ehsan KamilNo ratings yet
- Perluasan Objek HAPTUNDocument9 pagesPerluasan Objek HAPTUNCindy Isabelle EkakNo ratings yet
- Tugas Ptun (Anysehe)Document9 pagesTugas Ptun (Anysehe)asriyani SeheNo ratings yet
- J1. Sanksi AdmDocument14 pagesJ1. Sanksi AdmIlham Endriansyah PutraNo ratings yet
- BAB I (Pendahuluan)Document32 pagesBAB I (Pendahuluan)wilchyasgNo ratings yet
- Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan IndonesiaDocument15 pagesKedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesiategar yudistiraNo ratings yet
- Makalah Politik HukumDocument15 pagesMakalah Politik HukumEchoSoepramurbadaNo ratings yet
- Dimas Heriyadi - B1A019264 - Proposal Skripsi - Hukum KepegawaianDocument30 pagesDimas Heriyadi - B1A019264 - Proposal Skripsi - Hukum KepegawaianDimas HeriyadhiNo ratings yet
- MuhraromDocument15 pagesMuhraromLegal mGanikNo ratings yet
- Materi PtunDocument100 pagesMateri PtunAli PetanjNo ratings yet