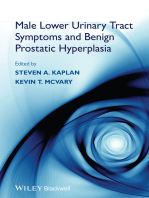Professional Documents
Culture Documents
Perbedaan Pengaruh Pemberian Propofol Dan Etomidat Terhadap Agregasi Trombosit
Perbedaan Pengaruh Pemberian Propofol Dan Etomidat Terhadap Agregasi Trombosit
Uploaded by
David WilsonOriginal Description:
Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Perbedaan Pengaruh Pemberian Propofol Dan Etomidat Terhadap Agregasi Trombosit
Perbedaan Pengaruh Pemberian Propofol Dan Etomidat Terhadap Agregasi Trombosit
Uploaded by
David WilsonCopyright:
Available Formats
Jurnal Anestesiologi Indonesia
PENELITIAN
Perbedaan Pengaruh Pemberian Propofol Dan Etomidat Terhadap Agregasi Trombosit
Sri Tabahhati*, Uripno Budiono*
ABSTRACT Background: Perioperative bleeding is a serious and common problem in surgery. Induction anesthetic agent usage is known for the inhibition of platelet aggregation. Objective: To determine the difference effect of propofol and penthotal administration on platelet aggregation. Method: An experimental study on 40 patients who received general anesthesia. Samples were divided into two groups (n:20, each). The first group received propofol and the second group received etomidat as the induction anesthetic agent during the procedure, and five minutes post induction, with the rate of administration propofol 2,5 mg/ body weight, etomidat 0,3 mg/ body weight and O : NO ratio 50% : 50%. A specimens were taken to the Clinical Pathology Laboratory for Platelet Aggregation testing. Statistical analyses were performed using Paired T-Test and Independent T-Test (with level of significance p<0,05). Result: The result showed significant difference in percentage of maximal platelet aggregation before and after the administration of propofol (p=0,001) and not significant for etomidat group (p=0,089). In the propofol and etomidat group, the mean percentage of maksimal platelet aggregation was 66,07 18,04. Statistically, propofol caused less significant hypo aggregation of plateled compared to etomidate, with (p=0,053). Conclusion: Propofol significantly decreased the percentage of maximal plateled aggregation, however the difference was not significant between two experiment groups. Keywords : Propofol, etomidate, ADP, platelet aggregation
ABSTRAK Latar belakang penelitian: Perdarahan perioperatif merupakan masalah yang sering dihadapi dalam setiap operasi. Penggunaan obat anestesi induksi dikatakan mempunyai pengaruh dalam agregasi trombosit Tujuan: Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian propofol dan etomidat terhadap agregasi trombosit. Metode: Merupakan penelitian eksperimental pada 40 pasien yang menjalani anestesi umum. Penderita dibagi 2 kelompok (n=20), kelompok I menggunakan propofol dan
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
*Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip/ RSUP Dr. Kariadi, Semarang
Jurnal Anestesiologi Indonesia
kelompok II menggunakan etomidat, yang diberi sejak awal induksi dengan besar pemberian propofol 2,5 mg/kg intravena, etomidat 0,3 mg/kg intravena bersama O2 : N2O = 50% : 50%. Masing-masing kelompok akan diambil spesimen sebelum induksi dan 5 menit setelah induksi. Semua spesimen dibawa ke Laboratorium Patologi Klinik untuk dilakukan pemeriksaan Tes Agregasi Trombosit. Uji statistik menggunakan Paired T-Test dan Independent T-Test (dengan derajat kemaknaan <0.05). Hasil: Karakteristik data penderita maupun data variabel yang akan dibandingkan terdistribusi normal. Pada penelitian ini didapatkan perbedaan persen agregasi maksimal trombosit yang bermakna sebelum dan sesudah pemberian propofol (p=0,001) dan tidak bermakna untuk sebelum dan sesudah pemberian etomidat (p=0,089). Pada kelompok propofol didapatkan rerata persen agregasi maksimal trombosit 66,078,28 dan etomidat 56,29+18,04 dan menunjukkan perbedaan yang bermakna antara keduanya (p=0,053). Kesimpulan: Propofol secara bermakna menurunkan persen agregasi maksimal trombosit, dibandingkan etomidat. Kata kunci : Propofol, etomidat, ADP, agregasi platelet koagulasi intrinsik dan ekstrinsik.4 Beberapa penelitian menyatakan bahwa kekurangan dalam kedua pemeriksaan tersebut dalam menilai dua parameter tersebut dalam perannya sebagai uji fungsi koagulasi.5 Uji perdarahan telah dilakukan beberapa dekade dengan metode Duke. Beberapa modifikasi dilakukan oleh Ivy et al dan Mielke et al. Uji pemeriksaan tersebut banyak digunakan pertengahan tahun 1980-an, di mana muncul pertanyaan mengenai validitas pemeriksaan. De Caterina melakukan analisis regresi linier untuk mengetahui sensitifitas, spesifisitas, nilai prediktif positif dan negatif dari BT. Nilai hasil pemeriksaan BT dipengaruhi oleh jumlah trombosit, dinding pembuluh darah, hematokrit, kualitas kulit, dan juga teknik yang digunakan.6 Penelitian lain juga menunjukkan tidak ada korelasi statistika
PENDAHULUAN Penyulit yang mungkin muncul dalam setiap operasi adalah risiko perdarahan. Bila penyulit ini tidak diatasi dengan baik, dapat menyulitkan dan meningkatkan morbiditas dan mortalitas, serta berpengaruh terhadap proses hemodinamika selama dan sesudah operasi.1 Faktor yang terlibat dalam proses hemostasis adalah vasospasme pembuluh darah, reaksi trombosit (adesi, pelepasan, dan agregasi), dan faktor koagulasi.1,2 Interaksi obat-obatan dengan trombosit dapat memperberat risiko komplikasi perdarahan, mengingat peran trombosit yang penting pada proses hemostatis selama dan sesudah 3 pembedahan. Clotting Time (CT) dan Bleeding Time (BT) merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan untuk mengetahui jalur
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
antara BT preoperatif dan jumlah kehilangan darah atau kebutuhan produk darah.7 Anestesi dibutuhkan pada hampir semua tindakan pembedahan, dan sebagian besar dengan anestesi umum. Anestesi umum berpengaruh secara intraseluler dan perlu mendapat perhatian dalam hal interaksi obat anestesi dengan trombosit.8 Sebagian besar operasi yang dilakukan di Instalasi Bedah Sentral RSUP dr. Kariadi Semarang dilakukan dengan anestesi umum. Propofol diketahui merupakan agen anestesi yang berkontribusi terhadap disfungsi trombosit melalui inhibisi mobilisasi kalsium terhadap stimulasi agonis.9 Propofol (2,6 diisopropylphenol) merupakan obat anestesi yang sering digunakan pada anestesi umum selain ketamin.10,11 Propofol memiliki kemiripin struktur serupa dengan alfatokoferol dan asam asetilsalisilat. Efek antioksidannya disebabkan kesamaan struktur dengan alfatokoferol.12,13 Pada penelitian yang dilatarbelakangi oleh keserupaan struktur propofol dengan asam salisilat, memperlihatkan bahwa zat anestesi ini akan menghambat agregasi trombosit pada whole blood secara in vitro dalam kisaran konsentrasi serupa pada plasma manusia setelah pemberian intravena.14 Efek hipoagregasi trombosit ini telah terlihat pada pemberian propofol intravena terhadap pasien bedah.15,16 Propofol memperlihatkan efek anti agregasi ditemukan serupa pada PRC dan whole blood.11,17 Efek ini terkait dengan dua mekanisme dasar yaitu penghambatan sintesis trombosit A2 dan
peningkatan sintesis NO oleh leukosit. Kedua efek dapat bergantian, terkait efek antioksidan propofol.10,18,19 Penelitian Andre Gries (2004) menunjukkan ekspresi P-selectin in vitro diinhibisi oleh Etomidat pada konsentrasi 2 (28 %) dan 20ug/ml (38%). Pasien operasi vaskuler, induksi anestesi pada kelompok ETO memberikan pemanjangan waktu perdarahan in vitro dan inhibisi ADP dan agregasi tromobsit yang diinduksi kolagen.20 Etomodat merupakan gold standar, di RS dr. Kariadi etomidat pernah dipakai sebagai agen induksi, sekarang sudah tidak digunakan lagi. Penelitian tentang etomidat ini merupakan penelitian payung di mana diharapkan sebagai obat gold standar etomidat dapat dipakai kembali. Etomidat mengurangi fungsi trombosit baik eksvivo dan invivo. Hasil penelitian Sarkar M, dkk pemberian etomidat untuk induksi anestesi pada pasien pediatrik dan neonatus memberikan kesan bahwa etomidat tidak mengubah profil klinis hemodinamika secara signifikan.21 Penelitian Aoki dkk di Jepang menunjukkan propofol 2mg/kg/jam menghambat agregasi trombosit. Parolari A, dkk mendapatkan setelah 5 menit pemberian propofol 2,5mg/kg bolus intravena, terjadi penurunan agregasi trombosit secara bermakna pada whole blood.14,22 Agregasi trombosit dinilai melalui pemeriksaan yang disebut Tes Agregasi
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Trombosit (TAT). Pemilihan jenis TAT, tergantung jenis obat yang digunakan. Agonis/induktor yang dapat digunakan adalah trombin, tromboksan A2, asam arakidonat, serotonin, vasopresin, dan ADP yang dipakai pada Laboratorium Patologi Klinik di RSUP Dr. Kariadi. TAT berdasarkan perubahan transmisi cahaya masih dianggap baku memang untuk menilai fungsi agregasi trombosit. Setiap kenaikan transmisi cahaya yang dicatat sebagai suatu agregasi trombosit. Hasilnya akan didapatkan presentase agregasi maksimal trombosit yang terjadi dengan pemberian ADP 2uM; 5uM dan 10uM sebagai induktor agonis 21 trombosit. Berdasarkan temuan dari penelitian di atas, akan dilakukan penelitian perbedaan pengaruh pemberian propofol 2,5mg/kg intravena dan etomidat 0,3mg/kg intravena terhadap agregasi trombosit (Dosis anestesi induksi propofol 2,5 mg/kg ekuivalen dengan dosis induksi etomidat 0,3 mg/kg).6 Pada penelitian ini ditambahkan hasil yang mempertimbangkan interpretasi TAT dengan mengamati gambaran pola kurva agregasi.22 Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan pengaruh pemberian propofol dan etomidate terhadap agregasi trombosit.
rancangan randomized clinical control trial. Penelitian dilakukan di Instalasi Bedah Sentral dan Laboratorium Patologi Klinik RSUP dr. Kariadi Semarang pada bulan Maret 2010 hingga April 2010. Sampel merupakan pasien bedah onkologi di Instalasi Bedah Sentral RSUP dr. Kariadi yang memenuhi kriteria inklusi yaitu menjalani operasi elektif dengan general anestesi, pasien bedah, status fisik ASA I-II, usia 19 - 39 tahun, BB normal. Sampel yang ada dikelompokkan dengan acak menggunakan randomized clinical control trial double blind. Kelompok I menggunakan Etomidat 0,3mg/kg intravena sebagai obat anestesi induksi sedangkan Kelompok 2 menggunakan Propofol 2,5mg/kg intravena sebagai obat anestesi induksi. Sampel dieksklusi jika menderita DM, hipertensi, menggunakan NSAID, kadar trombosit <200.000/uL atau >400.000/mL, riwayat merokok, riwayat pascastrok, riwayat penyakit jantung iskemik. Analisis data menggunakan Alpha = 0,05 perhitungan dengan SPSS 15 for windonws. Etika disetujui Ketua Bagian Anestesi FK UNDIP, dan memperoleh izin dari komisi Etik dan Penelitian FK UNDIP/RSUP dr. Kariadi, dekan FK Undip, dan direktur RSUP dr. Kariadi. Setiap pasien yang dilakukan penelitian dimintai persetujuan. Bila terjadi sesuatu atas diri pasien pada waktu penelitian, segala biaya perawatan akan ditanggung peneliti.
METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental uji klinik fase 4 dengan
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Tabel 1. Karakteristik Umum Subjek pada Masing-Masing Kelompok No 1 2 3 4 5 6 Variabel Umur (tahun) Body Mass Index (kg/m2 Tekanan Darah Sistol (mmHg) Tekanan Darah Diasto(mmHg) Nadi (x/menit) Status ASA ASA I ASA II Kel Etomidat (n=20) 34,5 + 3,7 21,1 + 1,7 127,6 + 9,2 74,6 + 7,7 80,2 + 9,6 17 3 Kel. Propofol (n=20) 33,70 + 3,388 21,2 + 1,9 127,9 + 7,7 73,9 + 6,0 80.8 + 7.9 16 4 P 0,761 0,953 0,569 0,689 0,824
HASIL Uji normalitas one-sample Kolmogorov Smirnov digambarkan pada tabel 1, di mana karakteristik umum subjek pada masing-masing kelompok memiliki distribusi yang normal (p>0,05), sehingga untuk uji homogenitas diperlukan analisis statistik dengan Independent T Test. Hasilnya didapatkan data yang homogen (perbedaan tidak bermakna, p>0,05) dari
semua variabel yaitu umur, BMI, tekanan darah sistole, tekanan darah diastol, nadi, dan status ASA sebelum dilakukan penelitian. Tabel 2 menunjukkan data sebelum dan sesudah penelitian pada kelompok I (etomidat) dan II (propofol) didapatkan hasil uji normalitas menunjukkan nilai % agregasi trombosit maksimal berdistribusi normal dengan induktor 10uM ADP (p>0,05).
Tabel 2. Uji Normalitas Rerata % Agregasi Trombosit Variabel % Agregasi maks. Trombosit % Agregasi maks. Trombosit % Agregasi maks. Trombosit % Agregasi maks. Trombosit Induktor 10 uM ADP 10 uM ADP 10 uM ADP 10 uM ADP Perlakuan Pre Kelp I Pre Kelp II Post Kelp I Post Kelp II P 0,509 0,792 0,942 0,935 Keterangan Distribusi normal Distribusi Normal Distribusi normal Distribusi Normal
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Data kemudian dianalisis secara parametrik menggunakan uji Paired T Test untuk melihat perbedaan % agregasi maksimal trombosit antara sebelum dan sesudah perlakuan dengan 10 uM ADP. Tabel 3 menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah perlakuan dengan induktor ADP 10uM pada kelompok propofol
terbukti menyebabkan penurunan % agregasi maksimal trombosit yang secara statistik berbeda bermakna p=0,001 (p<0,05). Sedangkan pada kelompok etomidat secara statistik tidak terbukti menyebabkan penurunan % agregasi maksimal trombosit dengan nilai p=0,089 (p>0,05).
Tabel 3. Nilai rerata dan simpangan baku persen agregasi maksimal trombosit sebelum dan setelah perlakuan pada kelompok propofol dan etomidat (dengan induktor ADP 10 uM) No 1 2 * = bermakna (p<0,05) Keterangan Kel. Etomidat Kel. Propofol Sebelum 73,45 + 7,33 62,55 + 13,91 Sesudah 66,07 + 8,28 56,29 + 18,04 p 0,089 0,001*
160 140 120 100 80 60 40 20 0 Sebelum Setelah Etomidat Propofol 70 65 60 55 50
% Agregasi maksimal trombosit
% Agregasi maksimal trombosit
Gambar 1. Perbandingan perubahan % agregasi maksimal trombosit antara sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok etomidat dan propofol
Gambar 2. Perbedaan % agregasi maksimal trombosit antara sesudah pemberian propofol dan sesudah pemberian etomidat
Gambar 2 menunjukkan perbedaan rerata % agregasi maksimal trombosit antara sesudah pemberian propofol dan sesudah pemberian etomidat dengan ADP 10 uM sebagai induktor.
Hasil Tes Agregasi Trombosit yang terbaca oleh PACKS-4 selain menunjukkan persen agregasi trombosit juga menggambarkan pola kurva agregasi yang terbentuk oleh masing-masing dosis
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
induktor ADP pada masing-masing kelompok perlakuan. Semua sampel pada kedua kelompok perlakuan sebelum perlakuan mempunyai gambaran normoagregasi. Kemudian setelah dilakukan perlakuan gambaran dari 20 sampel untuk kelompok Etomidat terdapat 2 orang hipoagregasi (10%), 4 orang hipoagregasi ringan (20%) dan sisanya 14 orang normoagregasi (70%). Kelompok propofol terdapat 14 orang hipoagregasi (70%), 3 orang hipoagregasi ringan (15%), dan 3 orang normoagregasi (15%). Secara statistik propofol secara bermakna menyebabkan hipoagregasi daripada pentotal, p=0,01 (p<0,05). Hal ini lebih jelas terlihat pada gambar 3.
antara sebelum dan sesudah perlakuan tidak memberi perbedaan bermakna p=0,089 (p>0,05), hal ini semakin berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa etomidat bisa dikatakan dapat mempengaruhi secara bermakna respon trombosit terhadap ADP.20 Kelompok propofol dengan induktor 10M antara sebelum dan sesudah perlakuan didapatkan perbedaan yang bermakna p=0,001 (p<0,05). Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh de La Cruz, dkk di mana dikatakan propofol 2,5mg/kg intravena menghambat intensitas maksimum agregasi trombosit. Propofol menghambat agregasi trombosit pada whole blood secara in vitro.17,19 ADP 10M diharapkan terjadi pelepasan granula sekunder dari permukaan trombosit dan terbentuklah agregasi sekunder, di mana perlu diingat agregasi sekunder terjadi akibat pelepasan granula pada setelah terjadinya agregasi primer sehingga kembali membuat jalur arakidonat dan terbentuk tromboksan A2. Tromboksan A2 ini akan menurunkan konsentrasi cAPMP yang berfungsi mengendalikan konsentrasi ion kalsium bebas yang dibutuhkan dalam proses agregasi. Kadar cAMP yang tinggi menyebabkan kadar ion kalsium bebas dalam trombosit yang digunakan dalam proses agregasi.23 Hasil penelitian ini memperkuat pernyataan yang mengatakan pemberian propofol secara bermakna menurunkan aktivasi ADP pada proses terjadinya
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Hipo Hipo Normo ringan Etomidat Propofol
Gambar 3. Perbedaan Propofol dan Etomidat dalam menyebabkan hipoagregasi
PEMBAHASAN Hasil dari penelitian ini bahwa dengan ADP 10M untuk kelompok etomidat
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
agregasi trombosit bila dibandingkan dengan etomidat.13,19 Pemberian induktor ADP 10 uM merupakan induktor terkuat yang umumnya digunakan sebagai pedoman untuk penetapan keadaan hipoagregasi bila nilai % agregasi maksimal trombosit lebih rendah dari rentang nilai rujukan terendah dan disertai pola kurva agregasi reversibel. ADP paling tepat dalam menilai fungsi agregasi trombosit, di mana hanya selektif untuk agregasi tromobosit dan stimulasinya bersifat langsung.24 Hasil penelitian ini mendukung penelitian sejenis penelitian de La Cruz, dkk yang menyatakan propofol menurunkan sensitivitas ADP terhadap terjadinya agregasi trombosit, namun penelitian tersebut juga menghubungkan dengan kejadian memanjangnya waktu perdarahan secara signifikan ditemukan hubungan kuat di antaranya. Walaupun peran agregasi trombosit pada manifestasi memanjangnya waktu perdarahan dianggap mempunyai peran besar, namun juga harus dipikirkan penyebab lainnya di mana juga terjadi relaksasi sel otot polos pembuluh darah akibat halotan di samping akibat pengaruh komponen lain seperti faktor pembuluh darah dan faktor koagulasi.25 Sementara etomidat pada penelitian ini dinyatakan tidak bermakna p=0,089 (p>0,05) menurunkan rerata agregasi maksimal trombosit berarti tidak mendukung penelitian - penelitian sebelumnya seperti Gries (2001) dkk di mana etomidat memberikan
penghambatan bermakna.20,25
trombosit
secara
Keterbatasan penelitian ini adalah masih digunakannya ADP sebagai indikator, di mana diketahui etomidat mempengaruhi ADP dalam menghambat agregasi trombosit, dan tidak dilakukannya pemeriksaan pendahuluan untuk menyingkirkan variabel perancu yang dapat mempengaruhi agregasi maksimal trombosit
SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan presentase agregasi maksimal trombosit sebelum dan setelah pemberian propofol 2,5 mg/kg intravena namun tidak terdapat perbedaan presentase agregasi maksimal trombosit sebelum dan sesudah pemberian etomidat 0,3 mg/kg intravena serta propofol menurunkan agregasi maksimal trombosit secara bermakna dibandingkan etomidat. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah pemberian propofol dengan dosis yang lebih kecil dapat mengurangi efek hipoagregasi trombosit dan penelitian ini dapat dijadikan dasar pemilihan obat anestesi induksi, khususnya penderita dengan kelainan koagulasi maupun pada operasi yang cenderung mengakibatkan perdarahan masif.
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
1. Baldy CM. Pembekuan. Dalam: Price SA, Wilson LM. Patofisiologi konsep klinis proses-proses penyakit. Edisi ke-4. Jakarta: EGC, 1995; 264-5 2. Guyton, Hall. Buku Ajar Fisiologi kedokteran. Edisi ke 9. Jakarta: EGC. 1997; 579-82. 3. Kartono D, Thaib MR. Masalah perdarahan pada pembedahan. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1986; 20-6. 4. Macpherson DS. Preoperative laboratory testing: Should any test be routine before surgery? Med Clin North Am 1993; 77:289-90. 5. Rodgers RPC. A critical reappraisal of bleeding time. Semin Thromb Haemost 1990; 16:131-44. 6. Lind SE. The bleeding time does not predict surgical bleeding. Blood 1991; 77:2547-52 7. Lehman CM. Discontinuation of BT without detechable adverse clinical impact. Clin Chem 2001; 47:1204-11. 8. Morgan GE, Mikhail MS, Murry MJ, Larson CP. Inhalational Anesthetic. In Clinical Anesthesiology. 3rd Ed. New York: Lange Medical Book/Mc GrewHill Medical Publishing Edition, 2002; 127-51. 9. Gepts E, Camu F, Cockshott D, Douglas EJ. Disposition of Propofol administered as constant rate intravenous infusion in humans. Anaesth Analg 1987; 66:125663. 10. Stoelting RK, Hillier SC. Propofol. In: Nonbarbiturate intravenous anesthetic drug. In: Pharmacology and Physiologi in aneesthetic Practice, 4th ed. Philadelphia: Lippincott 2006; 156-63. 11. Muacchio E, Rizzoli V, Bianchi M, Bindoli A, Galzigna L. Antioxidant action of propofol on liver microsomes, mitochondria, and brain synaptosomes in rat. Pharmacol. Toxicol 1991; 69:15-17.
12. De la Cruz JP, Villalobos MA, Sedeno G, Sanchez DC. Effect of propofol on oxidative stress in an in vitro model of anoxia-reoxygenation in the rat brain. Brain Res 1998; 800:136-44. 13. De la Cruz JP, Carmona JA, Paez MV, Blanco E, Sanchez DC. Propofol inhibits in vitro platelet aggregation in human whole blood. Anesth Analg 1997; 84: 919-21. 14. Aoki H, Mizobet, Nozuchi S, Hiramatsu N. In vivo and in vitro studies of the inhibitory effect of propofol on human platelet aggregation. Anesthesiology 1998; 88: 362-70. 15. Dogan IV, Ovali E, Eti Z, Yayci A, Gogusf Y. The in vitro effect of isofluorane, isovofluorane, and propofol on platelet aggregation. Anesth Analg 1999; 88: 432-36. 16. De la Cruz JP, Paez MV, Carmona JA, Sanchez DC. Antiplatelet effect of the anesthetic drug propofol influence of red cells and leucocytes. Br Med J Pharmacol 1999; 128: 1538-44. 17. De la Cruz JP, Zanca A, Carmona JA, Sanchez DC. Effect of propofol on oxidative stress in platelets from surgical patients. Anesth Analg 1999; 89: 1050-5. 18. De la Cruz JP, Sedeno G, Carmona JA, Sanchez DC. In vitro effect of propofol on tissular oxidative stress in the rats. Anesth Analg 1998; 87: 1141-615. 19. Mendez D, De la Cruz JP, Arrebola MM, Guerrero A, Gonzalez-Corea, Garcia Temboury E, et al. The effect of propofol on the interaction of platelets with leucocytes and erythrocyts in surgical patients. Anesth Analg 2003; 96: 713-19. 20. Gries A, Weis S, Herr A, Graf BM, Seelos R, Martin E, et al. Etomidate and thiopental inhibit platelet function in patients undergoing infrainguinal vascular surgery. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45: 449-57. 21. Dordoni PL, Frassanito L, Bruno MF, Proietti R, De Cristofaro R, Ciabattoni
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
22.
23.
24.
25.
G, et al. In vivo and in vitro effects of different anaesthetics on platelet function. Br Med J Haematol 2004; 125: 79-82. Palolari A, Guamieri D, Alamanni F, Toscano T, Tantalo V, Gherli T et al. Platelet function and anesthetics in cardiac surger. An in vitro and ex vivo study. Anesth Analg 2007; 89: 26-31. Shafer Al. Effects of nonsteroidal antiinflammatory therapy on platelets. Clin Pharmacol J. 1999; 106: 25 S-36S. Lisyani BS. Hasil tes agregasi trombosit pada subjek sehat kelompok usia 19-39 tahun dibandingkan dengan 40 tahun ke atas. Media Medika Indonesiana 2006; 41: 69-77. Hovarka J, Honkavaara P, Korttila K. Tracheal intubation after induction of anesthesi with thiopentone or propofol without muscle relaxants. Acta Anesthesiol Scand 1991; 35: 326-.
10
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
PENELITIAN Perbedaan Efektifitas Oral Hygiene Antara Povidone Iodine Dengan Chlorhexidinee Terhadap Clinical Pulmonary Infection Score Pada Penderita Dengan Ventilator Mekanik
Kurniadi Sebayang*, Jati Listiyanto Pujo*
ABSTRACT Background : Oral hygiene antiseptic can reduce incidence of Ventilator Associated Pneumonia (VAP) that reduce Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) in patients with mechanical ventilation. Chlorhexidine can prevent formation of biofilm compare with povidone iodine. Objectives : This study was performed to find out wether chlorhexidine 0, 3 % was better than povidone iodine 1 % on Clinical Pulmonary Infection Score in patients with mechanical ventilation. Methods : An experimental study, as consecutive sampling on 32 subjects was decided in two groups (n = 16). Povidone iodine 1% was administrated in first group and cholrhexidin 0,2 % in second group. Clinical Pulmonary Infection Score was determined using Mann-Whitney before and after treatment in each group temperature, blood gas analysis, tracheal secretion, blood analysis and chest x-ray. Statistical analysis was performed with Wilcoxon test to compare CPIS and corelative test to analyzed GC plaque and spearman test to analyzed the correlation between GC plaque score and CPIS. Result : There were significant diference in the first group on CPIS (p<0,05) and no difference in the second group (p>0,05). The difference score before and after treatment in both group were significantly different (p=0,05). GC plaque score in chlorhexidinee group were significantly different (p=0, 0000). There were no correlation between GC plaque score and CPIS. Conclusion : Chlorhexidinee 0,3% is more effective in oropharing decontaminated antisepcic that decrease CPIS than povidone iodine on patients with mechanical ventilation. No correlation between GC plaque score with score of CPIS. Keywords : Povidone iodine 1 %, chlorhexidine 0, 2%, CPIS, mechanical ventilation, GC plaque.
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
*Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip/ RSUP Dr. Kariadi, Semarang
11
Jurnal Anestesiologi Indonesia
ABSTRAK Latar belakang : Antiseptik oral hygiene merupakan salah satu cara non farmakologi yang dapat menurunkan insiden Ventilation Associated Pneumonia (VAP) dengan menurunkan skor Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) pada penderita dengan ventilator mekanik. Chlorhexidine adalah antiseptik yang lebih mampu mencegah pembentukan biofilm dibandingkan dengan povidone iodine. Tujuan : Mengetahui chlorhexidine 0,2% lebih efektif menurunkan angka Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) dibandingkan dengan povidone iodine 1% pada penderita dengan ventilator mekanik. Metode : Merupakan penelitian eksperimental, dua subjek dibagi dua kelompok sama besar (n =16). Kelompok chlorhexidinee 0,2 % dan kelompok kontrol povidone iodine 1%. Kedua kelompok sebelum dan setelah perlakuan dilakukan pemeriksaan CPIS, yaitu: suhu, analisa gas darah, sekret trakea, darah rutin dan foto ronsen dada. Uji wilcoxon adalah uji korelatif untuk melihat GC plaque sebelum dan setelah perlakuan.Sedangkan uji spearman melihat korelasi GC plaque dan skor CPIS pada kelompok perlakuan. Hasil : Hasil skor CPIS berbeda makna pada kelompok I (p<0,05). Analisis komparatif selisih skor sebelum dan sesudah perlakuan kedua kelompok berbeda bermakna (p<0,05). Skor GC plaque sebelum [6,00 (5,60-7,00)] dan setelah aplikasi chlorhexidinee 0,2% [7,00 (6,80-7,20)] menunjukkan hasil berbeda bermakna (p= 0,000). Uji spearman skor GC plaque dan CPIS menunjukkan hasil berbeda tidak bermakna, hasil korelatif negatif. Kesimpulan : Chlorhexidinee 0,2% merupakan antiseptik orofaring yang lebih efektif menurunkan skor CPIS dibandingkan dengan povidone iodine 1% pada pasien dengan ventilator mekanik. Tidak ada korelasi antara kenaikan skor GC plaque dengan penurunan skor CPIS. Kata kunci : Povidone iodine 1%, chlorhexidinee 0, 2%, ventilator mekanik, GC plaque
12
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
PENDAHULUAN Penggunaan antiseptik terhadap oral hygiene merupakan salah satu cara farmakologi yang dapat menurunkan insiden Ventilation Associated Pneoumonia (VAP) dengan menurunkan skor Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) pada penderita dengan ventilator mekanik.1 di Indonesia belum ada data nasional kasus VAP, namun sudah ada data di ICU RSUP Dr. Kariadi Semarang.
2,3,4
sesingkat mungkin, pembagian kerja tenaga kesehatan, intubasi non nasal, menghindari manipulasi yang tidak perlu pada sirkuit ventilator, posisi setengah duduk, dan mencuci tangan dan pemakaian disinfektan sebelum dan sesudah kontak dengan penderita.2,5 Pencegahan VAP secara farmakologi dilakukan dengan cara dekontaminasi selektif menggunakan antibiotika pada saluran cerna (selective decontamination of the digestive tract (SDD)) dan dekotaminasi orofaring (oropharyngeal dencotamination (OD)) menggunakan antiseptik. 8,9 De Riso menyatakan dalam penelitiannya bahwa chlorhexidine yang digunakan dalam dekontaminasi orofaring dapat menurunkan kejadian infeksi nasokomial saluran napas di ICU sampai 69%.8 Fourrier menyatakan bahwa chlorhexidine dapat menurunkan pertumbuhan kuman penyebab VAP sebesar 53%.9 Dengan menurunnya pertumbuhan kuman di orofaring diharapkan insiden VAP juga menurun, hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tantipong dan Chan.9,10 Sedangkan menurut Houston, rerata penderita dengan pneumonia nosokomial lebih rendah dengan peridex chlorhexidine 0,12% daripada kontrol dengan menggunakan phenolic mixture.
11
Patogenesis VAP sangat komplek. Kollef menyatakan insiden VAP tergantung dari lamanya paparan lingkungan, petugas kesehatan dan faktor resiko lain. Penelitian terhadap 130 penderita yang diintubasi, kuman gram negatif ditemukan dalam trakea 58% penderita yang mendapatkan pengobatan antasida dan antagonis H2 serta 30 % penderita yang mendapatkan sukralfat. 4,18 Pemeriksaan CPIS meliputi beberapa komponen yaitu suhu tubuh, leukosit, sekret trakea, indeks oksigenasi, pemeriksaan radiologi dan kultur. Biakan kuman diambil berdasarkan teknik protected specimen brush, bronchoalveolar lavage ataupun blind suctioning sekret. 1,7 Pencegahan non farmakologi lebih mudah dan lebih murah untuk dilaksanakan bila dibandingkan dengan pencegahan VAP secara farmakologi, yang meliputi menghindari intubasi trakhea, penggunaan ventilasi mekanik
Guide control (GC) plaque dan pH mulut merupakan parameter kesehatan mulut yang dapat memberikan hasil diagnosis
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
13
Jurnal Anestesiologi Indonesia
terhadap patogenesis plak. Tetapi belum ada data tentang penelitian GC plaque yang dihubungkan dengan penggunaan antiseptik. 14 Penyempurnaan dari penelitian sebelumnya yang menganalasis dan membandingkan efektifitas dekontaminasi orofaring dengan menggunakan chlorhexidine 2%. Pada penelitian ini yang diberikan dalam dosis yang lebih kecil yaitu 0,2%. Karena berdasarkan penelitian sebelumnya terbukti dapat menurunkan insiden VAP
11,12,13
penelitian. Total sampel adalah 32 dan dibagi menjadi 2 kelompok sama rata. Pada kelompok 1 (C) diberikan chlorhexidine 0,2% sebanyak 25 ml. Pada kelompok 2(P) diberikan povidone iodine 1% sebanyak 25 ml. Semua penderita dengan ventilator mekanik dilakukan pemeriksaan klinis laboratorium, perbandingan tekanan oksigen dengan fraksi oksigen (PaO2/PaO2) dan foto thorak dan tes GC plaque. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel silang, grafik Box Plot. Analisis analitik akan dilakukan untuk menguji Clinical Pulmonary Infection Score pada kedua kelompok perlakuan dengan uji non parametrik Mann Whithney, Wilcoxon, Spearman. Semua uji analitik menggunakan Sofware Statistiscal Package for Social Science (SPSS) 15.
METODE Penelitian ini adalah penelitian eksperimental. Kelompok penelitian dibagi menjadi dua yaitu kelompok I (chlorhexidine 0,2% sebagai antiseptik oral pada penderita dengan ventilator mekanik) dan kelompok II (povidone iodine 1% sebagai antiseptik oral penderita dengan ventilator mekanik). Sampel mengambil semua penderita dengan ventilator mekanik di ICU RSUP Dr. Kariadi pada bulan April- Juni 2010. Sampel dikelompokkan dengan cara berurutan dimana penderita pertama dimasukkan dalam kelompok 1(C), penderita kedua dimasukkan kedalam kelompok 2(P) secara cosecutive sampling. Sampel adalah laki-laki dan perempuan dewasa dengan GCS < 8 serta keluarga setuju diikutsertakan dalam
HASIL Secara berurutan pasien dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok I yang menerima chlorhexidine 0,2% dan kelompok II yang menerima povidone iodine 1%.
14
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Tabel 1. Data karateristik pasien kedua kelompok
Usia < 20 Tahun 2030 tahun 3140 tahun 41-50 tahun 51-60 tahun > 60 tahun Total
Frekuensi 4 3 3 2 10 10 32
Persentase (%) 12,5 9,4 9,4 6,25 31 31 100
Uji normalitas dilakukan pada kedua kelompok dengan menggunakan uji Saphiro-Wilk untuk mengetahui sebaran data masing-masing. Hanya terdapat dua hasil sebaran yang merata (p>0,05) yaitu
pada kelompok II, tepatnya untuk skor sebelum dan sesudah perlakuan, dengan nilai p maisng-masing 0, 166 dan 0,061.
Tabel 2. Uji normalitas sebaran data skor pada kedua kelompok Kelompok Perlakuan Median (min-maks) Nilai p Kelompok I 150 (0,00-4,00) 0,019 Kelompok II 4,00 (1,00- 6,00) 0,166 Skor sebelum perlakuan Kelompok I 0,50 (0,00-4 ,00) 0,001 Kelompok II 4,00 (1,00-7,00) 0,061 Selisih Skor Kelompok I 0,00 (-3,00-2,00) 0,026 Kelompok II 0,50 (-3,00- 2,00) 0,037 Hasil uji Saphiro-Wilk, kelompok II sebelum dan setelah perlakuan adalah p= 0, 166 dan p = 0, 061 Skor sebelum perlakuan
Ketiga puluh dua pasien tersebut dihitung nilai CPIS-nya sebelum dan sesudah perlakuan. Dari hasil uji komparatif Mann Whithey diketahui
bahwa nilai CPIS sebelum perlakuan dan setelah perlakuan antara dua kelompok berbeda bermakna. Selisih skor didapatkan dari hasil pengurangan antara skor CPIS setelah perlakuan dengan skor CPIS sebelum perlakuan per pasien.
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
15
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Tabel 3. Uji komparatif selisih skor sebelum dan sesudah perlakuan kedua kelompok Kelompok I Kelompok II Nilai p [Median (min-maks)] [median (min-maks)] Skor CPIS Sebelum perlakuan 1,50 ( 0,00-4,00 ) 4,00 ( 1,00- 6,00 ) 0,000 Skor CPIS Setelah perlakuan 0,50 (0,00- 4,00) 4,00 ( 1,00- 7,00 ) 0,000 Selisih skor CPIS 0,00 (-3,00- 2,00) 0,50 (-3,00 2,00) 0,051 Hasil uji komparatif selisih skor Mann Whitney adalah p = 0, 051.
Selain itu dilakukan juga uji komparatif antara skor sebelum dan sesudah perlakuan secara terpisah pada
masing-masing kelompok perlakuan dengan menggunakan uji analsis Wilcoxon. Didapatkan hasil yang berbeda bermakna pada kelompok I (p <0,05), namun tidak pada kelompok II (p> 0,05).
Tabel 4. Uji komparatif skor sebelum dan sesudah perlakuan secara terpisah. Skor CPIS sebelum perlakuan [median (min-maks)] (0,00-4,00) 4,00 (1,00-6,00) Skor CPIS setelah perlakuan [median (min-maks)] 0,50 (0,00- 4,00) 4,00 (1,00-7,00)
Nilai p
0,000 0,227
Kel I Kel II
Hasil uji komparatif Wilcoxon adalah p= 0,000 dan p = 0, 227
Penelitian ini juga mengambil data skor GC plaque pada kelompok yang mendapat chlorhexidine 0, 2 %. Skor GC
plaque seperti halnya pada skor CPIS juga diambil sebelum dan sesudah perlakuan.
Tabel 5. Uji korelasi skor GC plaque dan CPIS sebelum dan sesudah perlakuan Jenis Skor Median Nilai p Korelasi Sebelum Perlakuan GC plaque 6,00 (5,60-7,00) 0,122 -0,403 CPIS 1,50 (0,00-4,00) Sesudah Perlakuan GC plaque 7,00 (6,80-7,20) 0,274 -0,291 CPIS 0,50 (0,00- 4,00) Hasil uji Spearman adalah p= 0, 122 (-0, 403) dan p= 0, 274 (-0, 291)
16
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
PEMBAHASAN VAP adalah inefksi nosokomial pneumonia yang terjadi pada pasien dengan bantuan ventilasi mekanik setelah 48 jam. 4,8,11. Etiologi yang paling sering adalah staphylococcus aureus, pseudomonas aeroginosa dan 7,8 enterobacteriacea. CPIS sendiri berdasarkan komponennya dapat CPIS modifikasi tidak disertai pemeriksaan kultur.12 CPIS modifikasi sangat menguntungkan negara-negara berkembang yang belum memiliki system pelayanan kesehatan yang sepenuhnya terjamin oleh asuransi. Tidak adanya pemeriksaan kultur pada negara-negara tersebut tentunya akan mengurangi biaya kesehatan, dan pada akhirnya menguntungkan pasien. Insiden VAP bervariasi antara 9- 27% dan angka kematiannya bisa melebihi 50%. Di Indonesia belum ada data nasional tentang kasus VAP, termasuk di ICU RSUP Dr. Kariadi Semarang, tempat penelitian ini dilakukan2-4. Faktor-faktor resiko terjadinya VAP yang telah dibuktikan lewat berbagai peneitian adalah usia, jenis kelamin, trauma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) dan lama pemakaian ventilator. 4,5 Penelitian ini menggunakan CPIS modifikasi sebagai parameter untuk membandingkan antara antiseptik chlorhexidine 0,2% dan povidone iodine 1 %. Hasil analisis komparatif MannWhitney antara kelompok I dan II
menunjukan perbedaan bermakna baik pada skor CPIS sebelum maupun setelah perlakuan. Namun, hasil ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa chlorhexidine 0,2% lebih efektif dibandingkan dengan povidone iodine 1%. Karena skor CPIS antara kelompok I dan II berbeda secara signifikan sebelum perlakuan, maka akan dijumpai perbedaan yang juga signifikan setelah perlakuan. Untuk itu, dilakukan uji komparatif terhadap selisih skor CPIS sebelum dan sesudah perlakuan antar kedua kelompok perlakuan. Dari hasil uji didapatkan nilai p=0,051, hasil ini berada sangat dekat dengan nilai cutt off signifikasi dalam studi, yaitu 0,05. Selanjutnya dilakukan uji Wilcoxon untuk menganalisis skor CPIS antara kedua kelompok secara terpisah. Hasil uji ini menunjukkan bahwa skor pada kelompok I (p=0,000), namun tidak pada kelompok II (p= 0,227). Hasil ini menunjukkan bahwa chlorhexidine 0,3 % lebih efektif dibandingkan dengan povidone iodine 1% dalam menurunkan kejadian VAP. Walaupun hasil uji komparatif selisih skor CPIS sebelum dan setelah perlakuan antara kedua kelompok hanya menghasilkan nilai p borderline 0, 051. Lebih efektifnya chlorhexidine 0, 2% ditunjang kuat oleh cara kerja antiseptik ini yang tidak hanya membunuh bakteri dalam rongga mulut, namun juga mencegah timbulnya biofilm. Biofilm adalah awal terbentuknya plak dan tempat berkumpulnya bakteri. 15-16
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
17
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Selain CPIS, pada penelitian ini dihitung pula GC plaque pada kelompok I yang mendapat chlorhexidine 0,2 %. Skor GC plaque hanya dihitung pada kelompok I berpegang pada penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan CPIS klasik yang menyatakan bahwa chlorhexidine lebih unggul dibandingkan dengan povidone iodine, selain itu pemberian chlorhexidine telah dianjurkan secara internasional untuk menggantikan 17 povidone iodine. Analisis Wilcoxon menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara skor GC plaque sebelum dan sesudah pemberian chlorhexidine 0,2%. Nilai GC plaque yang lebih tinggi setelah pemakaian chlorhexidine 0,2% menujukkan bahwa chlorhexidine meningkatkan pH intraoral secara signifikan. Hal ini berarti ada hubungan yang berlawanan antara CPIS dan GC plaque pada pasien ICU dengan ventilator mekanik yang menerima chlorhexidine 0,2 %.
publikasinya di tahun 1991 merupakan skor terpadu yang memuat variabel klinis, laboratorik dan radiologis. 19
KESIMPULAN Chlorhexidine 0,2% merupakan antiseptik dekontaminasi orofaring yang lebih efektif dibandingkan dengan povidone iodine 1 %. Tidak ada korelasi antara skor GC plaque dengan skor CPIS. Sebaiknya penggunaan antiseptik chlorhexidine 0,2% dilaksanakan untuk menggantikan povidone iodine 1% sebagai dekontaminasi orofaring pada penderita ventilator mekanik.
DAFTAR PUSTAKA
1. Luna CM, Blanzaco D, Niedman MS, Maturucco W, Brades NC, Desmery P, et.al. Resolution of ventilator associated pneumonia : prospective evaluation of the clinical pulmonary infection score as an early clinical predictor of outcome. Crit Care Med 2003; 31: 676-82. Chastre J, Fragon JY. Ventilator associated pneomina. AM J Respir Crit Care Med 2002:; 65 :67-903. Kollef M. Prevention of hospital associated pneumonia and ventilator associated pneumonia. Crit Care Med 2004; 32: 1396-405. Sallam SA, Arafa MA, Razek AA, Naga M, Hamid MA : Device related nosocomial infection in intensive care units of Alexandria University Students Hospital. East Med. Health J 2005 ;11 : 52-61. Ibrahim EH, Tracy L, Hill C, faser VJ, Kollef MH. The occurrence of ventilator
2.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Tantipong H et al, dan Genuit T et al. Yang mengatakan bahwa chlorhexidine 0,2% merupakan antisptik yang efektif untuk menurunkan insiden VAP, walau penelitian ini menggunakan CPIS modifikasi sedangkan 3 penelitian sebelumnya yang disebtkan di atas menggunakan CPIS klasik. CPIS, seperti yang disampaikan Pugin et al dalam
3.
4.
5.
18
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
associated pneumonia in a comunity hospital. Chest 2001; 120: 555-61. 6. Ewig E, Baueur T, Torres A. The pulmonary phsyician in critical care : nasocomial pneumonia. Thorax 2002 ; 57: 366-71. 7. Cook DJ, Meade MO, Hand LE, et. Al : toward understanding evidence uptake: semirecumbency for pneumonia prevention. Crit Care Med 2002;30 :1427-7. 8. DeRiso AJ, et.al. Chlorhexidine gluconate 0, 12 % oral; rinse reduces the incidence of total nosocomial respiratory infection an non prophylactic systemic antibiotic use in patients undergoing heart sugery. Chest 1996; 109:1556-61. 9. Fpurrier F, Dubois D, Pronnier P, et al. Effect of gingival and dental plaque antiseptic decontamination on nosocomial infections acquired in the intensive care unit : A doubleblind placebo- controlled multicenter study. Crit care Med 2005;33:1728-36. 10. Tntipong H, Morckhareonpong C, jayindee S, Thamlikitkul V. Randomized contrrolled trial and meta- analysis of oral decontamination with 2 % chlorhexidine solution for the prevention of ventilator associated pneumonia infection Control Hosp Epidemiol 2008; 29:131-6. 11. Houstun S, Hougland P, Anderson JJ, LaRocco M, Kenedy V, Gentry LO. Effectiveness of 0, 12% chlorhexidine gluconate oral rinse in recuding prevalence of nosocomial pneumonia in patients undergoing heart surgey. Am J Crit care 2002;(11) : 567-70.
12. Koeman M, Van der van Andre, Hak E, Joore HCA, Kaasjager K, De Smet A, et.al. Oral Decontamination with chlorhexidine 0, 2% Reduces the incidience of ventilator- associated pneumonia. Am J of Resp and Critical care Medeciene 2006; 173: 1348-1355. 13. Genuit T, Bochicchio G, Napolitano LM, Mc Carter RJ, Roghman MC. Surg Infection 2001;2(1):5-18. 14. Pourbbasa R, Delazarb A, Chisaza MT. The effect of german chamomile moyhwash on dental plaque and gingival inflamation Iranian Journal of pharmaceutical research 2005;2:105109. 15. Schiott CR, Loe H. The sensitivity of oral streptococci to chlorhexidine. J. Periodont. Res 1973;12:61. 16. McGee DC, Gould MK : preventing comlications of central venous catherization. N Engl Med 2003;384:1123-33. 17. Gjermo P, Bonesvoll P, Rolla G. Relationship between plaque inhibiting effect and relation of chlorhexidine in the human oral cavity. Arch. Oral Biol. 1974;19:1031. 18. Michel F, franceschini B, Berger P, Arnal JM, Gainier M, Sainty JM, et.al. Early antibiotic treatment for BALconfirmed ventilator associated pneumonia. Chest 2005;127:589-97. 19. Pugin J, Auckenthaler R, mili N. Diagnostic of ventilator associated pneumonia by bacteriologic analysis of bronchocopic and nonbronchocospicblindbronchoalveola r lavage fluid. Am Rev Respir Dis 1991; 143:1121-9.
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
19
Jurnal Anestesiologi Indonesia
PENELITIAN Pengaruh Pretreatment Vitamin C 200 Miligram Terhadap Kadar Kolesterol Serum Pada Induksi Etomidat
Anggraeni R*, Satoto H*
ABSTRACT Background: Etomidate is one of anesthetic agent which has minimal effect on cardiovascular function. However, etomidate depress cortisol production. Vitamin C is one of the agent that hamper the effect of etomidate toward cortisol production. Purpose: To analyze the effect of pre-treatment with vitamin C 200 mg on cortisol serum concentration in elective surgery with general anesthesia. Method: This double blind, Randomized Controlled Trial with 30 subjects which divided into two groups (n=15), control group and treatment group which received etomidate 0,2 mg/kgBW and combination of etomidate and vitamin C 200 mg in pre-operation respectively. Each group was then examined for cortisol serum concentration preanesthesia, 2 hours post induction, and 8 hours post induction. Wilcoxon Signed Rank Test and Paired T Test was performed to compare cortisol serum concentration in each group. While Mann Whitney and Independent Sample T Test was used to compare between control and treatment group. Result: Cortisol serum concentration in control group between pre-anesthesia ;244,15 (181,39-382,75)] and 2 hours post induction [185,52 35,88]; and between 2 hours and 8 hours post induction [349,81 121,28] was significantly different with value 0,002 and 0,000 respectively. It showed that decrement of etomidate dosage mo 0,2 mg/kgBW still able to decrease cortisol serum production significantly. However, in treatment group cortisol serum concentration pre-anesthesia [258,49 1"5,45-369,09)] and 2 hours post induction [202,14 45,3]; and between 2 hours and 8 hours post induction [251,39 122,91] was non significant, with p value 0,256 and 0,691 respectively. It proved the negative effect of vitamin C on cortisol depression effect of etomidate. Cortisol serum concentration between control and treatment group was significantly different on 2 hours post induction, but non significant on 8 hours post induction. It showed that the negative effect of vitamin C in cortisol depression because of etomidate only significant during 8 hours post eduction Conclusion: The effect of Vitamin C 200 mg iv 30 minutes pre-operation can minimize Cortisol depression on administration of etomidate 0,2 mg/kgBW Keyword: Pretreatment, vit c 200 mg, cortisol serum, etomidate
20
*Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip/ RSUP Dr. Kariadi, Semarang
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
ABSTRAK Latar Belakang: Etomidat adalah salah satu agen anestesi yang berefek minimal terhadap kardiovaskular. Namun, etomidat mendepresi produksi kortisol. Salah satu agen yang dapat meminimalisir efek depresi tersebut adalah vitamin C. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pretreatment vitamin C 200 mg pada operasi elektif dengan anestesi umum terhadap kadar kortisol serum. Metode: penelitian ini merupakan penelitian Randomized Contolled Trial dengan 30 subjek yang dibagi dalam dua kelompok sama besar (n=15), yaitu kelompok kontrol yang menerima etomidat 0,2 mg/kgBB dan kelompok perlakuan yang menerima etomidat dan vitamin C 200 mg iv preoperasi. Masing-masing kelompok tersebut selanjutnya diperiksa kadar kortisolnya pre anestesi, 2 jam pasca induksi, 8 jam pasca induksi. Uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test dan Paired T Test digunakan untuk membandingkan kadar kortisol di masing-masing kelompok. Uji Mann Whitney dan Independent Sample T Test digunakan untuk membandingkan antar kelompok kontrol dan perlakuan. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kontrol, kadar kortisol preanestesi 244,15 dan 2 jam pasca induksi 185,52 + 35,88 berbeda bermakna (p=0,002). Begitu pula antara kadar 2 jam dengan 8 jam pasca induksi 349,81 + 121,28 (p=0,000). Sedangkan pada kelompok perlakuan, kadar kortisol antara pre anestesi 258,49 (175,45-369,09) dan 2 jam pasca induksi 202,14 + 45,3 tidak berbeda bermakna (p=0,256), begitu pula 2 jam pasca induksi dengan 8 jam pasca induksi 251,39 + 122,91 (p=0,691). Kesimpulan: Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian vitamin C 200 mg intra vena 30 menit pre operasi dapat menurunkan efek depresi kortisol oleh pemberian etomidat 0,2 mg/kgBB. Kata kunci: pretreatment, vit c 200 mg, koresterol serum,etomidat
PENDAHULUAN Pemberian obat induksi anestesi berpotensi yang diikuti pemberian obat penghambat aktivitas neuromuskuler, bertujuan menghilangkan kesadaran dan paralisis motorik akan menghasilkan keadaan yang optimal dari suatu proses intubasi dan juga dapat menurunkan serendah mungkin risiko aspirasi paru pada pasien-pasien yang tidak puasa1. Sekarang ini tidak hanya satu jenis obat saja yang biasa digunakan pada Rapid Sequence Induction (RSI), tetapi
beberapa obat bias digunakan tergantung dari keuntungan, kondisi klinik, efek samping, serta kontra indikasinya2. Etomidat merupakan obat sedasi-hipnotik yang secara kimia berbeda dengan obatobat induksi sejenis lainnya1. Etomidat mempunyai spesifikasi onset dan durasi yang cepat, efek minimal pada parameter kardiovaskuler, depresi nafas maupun pada mekanisme lepasnya histamin3,4,5. Birnbaumer menyatakan bahwa Etomidat bersifat aman dan efektif untuk menjadi obat pilihan pada RSI di unit gawat darurat Amerika Serikat karena efeknya
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
21
Jurnal Anestesiologi Indonesia
aman untuk aktivitas miokardium dan perfusi serebral, serta insidensi yang rendah terkait hipotensi2. Etomidat diketahui dapat menyebabkan supresi adrenal baik pada pemberian dosis tunggal maupun infus lama1,6. Makna klinis dari efek obat ini terus diperdebatkan, terkait adanya efek supresi adrenal7,8,9. Pada penggunaan dosis tunggal etomidat menyebabkan penurunan fungsi adrenokortikal selama paling tidak 24 jam8. Penggunaan etomidat dosis tunggal pada unit gawat darurat belum pernah dilaporkan menyebabkan supresi adenokortikal yang signifikan hingga menyeabkan kematian7. Penggunaan etomidat dosis tunggal pada pasien syok septik juga masih merupakan kontroversi karena akan mempengaruhi fungsi kelenjar adrenal dalam 24 sampai 72 jam setelah pemakaian etomidat dengan cara menghambat 11 hydroxylase yang akan menambah angka kesakitan serta kematian pasien10. Etomidat seharusnya tidak digunakan untuk sedasi jangka lama di ruangan Intensive Care Unit (ICU) karena menyebabkan supresi adrenal, yang berakibat meningkatnya jumlah kematian di ICU8. Penggunaan vitamin C sebelum tindakan operasi akan mengembalikan kadar kortisol serum yang sama sebelum operasi, setelah pemberian infus etomidat durante operasi11.
Vitamin C berperan sebagai kofaktor dalam sejumlah reaksi hidroksilasi dan amidasi dengan memindahkan elektron ke dalam enzim yang ion metalnya berada dalam keadaan tereduksi, dan dalam keadaan tertentu sebagai antioksidan. Onset kerja dari vitamin C 30 menit pada orang sehat dan 1,5 jam pada orang dengan diabetes mellitus12. Kortisol sangat berperan penting untuk kehidupan, berperan dalam mempertahankan tekanan darah dengan cara meningkatkan sensitivitas vaskular untuk epinefrin dan norepinefrin, ekskresi air oleh ginjal, mempertahankan kadar gula darah, respon imun dan memiliki efek anti inflamasi dengan mengurangi sekresi histamin serta menstabilkan membran lisosomal. Stabilisasi membran lisosomal mencegah robeknya membran, sehingga mencegah kerusakan jaringan sehat. Kadar kortisol yang terlalu rendah mampu menyebabkan hipotensi, syok, demam, koma, dan pada akhirnya dapat berujung pada kematian. Sedangkan kadar kortisol yang meningkat terlalu tinggi, juga akan menimbulkan gangguan hemodinamik13. Pemberian vitamin C 500 mg pre operasi menurut studi Pirbudak L et al akan menormalkan kembali kadar kortisol pada 6 jam post operasi14. Sedangkan menurut Nathan et al pemberian pretreatment infus vitamin C 1 gr dalam 500 ml glukosa sebelum induksi dengan etomidat 0,3 mg/kgBB memberikan gambaran insufisiensi adrenal yang lebih tinggi15. Kontradiksi kedua hasil studi ini menunjukkan adanya dualitas efek vitamin C. Namun, menurut Schraag S et al dalam artikel studinya
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
22
Jurnal Anestesiologi Indonesia
menggunakan vitamin C dosis 500 mg dengan tambahan xylitol 0,25 mg/kg memaparkan hal yang berlawanan dengan kesimpulan studi Pirbudak et al.16 Maka dari itu di penelitian ini digunakan dosis vitamin C yang lebih rendah yaitu 200 mg.
normal (BMI 18-25 kg/m2), dengan kriteria eksklusi: alergi/ kontraindikasi terhadap obat yang dipakai selama penelitian, pasien menggunakan steroid, pasien dengan kadar kolesterol >200 mg, pasien menggunakan kontrasepsi hormonal, pasien yang mengkonsumsi vitamin C. Total sampel adalah 30 orang dibagi menjadi 2 kelompok masing-masing 15 orang. Seleksi penderita dilakukan saat kunjungan prabedah di RSUP Dr. Kariadi Semarang pada penderita yang akan menjalani operasi elektif dengan anestesi umum. Penderita diberikan penjelasan dan mengisi formulir informed consent. Pasien tidak mengetahui perilaku yang akan diterima. Disediakan kertas undian berlabel C dan E yang dilipat, masingmasing berjumlah 15, satu hari sebelum operasi ahli anestesi yang bertugas mengambil undian tersebut. Perlakuan yang dilakukan pada pasien sesuai label yang diambil saat undian. Semua pasien dipuasakan 6 jam sebelum operasi, kebutuhan cairan selama puasa dipenuhi sebelum operasi dengan menggunakan cairan Ringer Laktat. Pengambilan sampel sebelum perlakuan dilakuakan sekitar pukul 08.00 WIB saat pasien tiba di kamar operasi sebelum dilakukan induksi anestesi. Sampel adalah darah vena perifer sebanyak 3 ml, yang kemudian dimasukkan dalam tabung tanpa antikoagulan dan dibiarkan beku secara alami sampai serum/plasma terpisah dari bekuan sesegera mungkin
METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini merupakan uji klinik fase 2 dengan bentuk rancangan eksperimental ulang (pretest and posttest controlled group design). Penelitian ini dilakukan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUP Dr Kariadi Semarang dan Laboratorium GAKY Semarang pada lingkup waktu bulan Maret sampai Mei 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien di IBS RSUP Dr. Kariadi pada bulan Maret sampai Mei 2010 yang menjalani operasi dengan anestesi umum dan diinduksi anestesi antara jam 08.00 sampai 10.00 WIB. Teknik pengambilan sampel menggunakan randomized clinical controlled trial dibagi dalam dua kelompok. Kelompok 1 (E) menggunakan obat anestesi induksi etomidate 0,2 mg/kgBB intravena tanpa pretreatment vitamin C 200 mg intravena. Kelompok 2 (C) menggunakan obat anestesi induksi etomidate 0,2 mg/kgBB intravena dengan pretreatment vitamin C 200 mg intravena 30 menit sebelum induksi. Sampel harus memenuhi kriteria inklusi : status fisik ASA I-II, usia 14-50 tahun, jenis operasi dengan anestesi umum, operasi dilakukan antara jam 08.00 10.00, berat badan
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
23
Jurnal Anestesiologi Indonesia
untuk menghindari hemolisis sel darah merah. Sampel segera dikirim ke Laboratorium GAKY FK Undip untuk dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol serum. Setelah dipastikan jalur intravena lancar, pasien dipremedikasi ondansetron 4 mg 30 menit sebelum operasi dan fentanyl 1g/kg 3 menit sebelum induksi. Selanjutnya dilakukan induksi anestesi dimana kelompok E menggunakan obat anestesi induksi etomidat 0,2mg/kg iv, sedangkan kelompok C menggunakan pretreatment vitamin C 200 mg 30 menit sebelum obat anestesi induksi etomidat 0,2mg/kg iv. Anestesi dipertahankan pada seluruh kasus dengan inhalasi campuran N2O:O2 (50%:50%). Pelumpuh otot menggunakan vecuronium bromide 0,1mg/kg. Pada semua kelompok sampel darah sesudah perlakuan diambil 2 jam dan 8 jam pasca induksi etomidat sebanyak 3ml dimasukkan dalam tabung tanpa antikoagulan dan segera dikirimkan ke Laboratorium GAKY. Sampel diberi nomer well kemudian penambahan sampel dan konugat-HRP. Selanjutnya diinkubasikan selama 60 menit pada suhu 37oC, pada akhir inkubasi isi tiap well dibilas dengan 300 l aqua destilata. Selanjutnya dilakukan pewarnaan dengan substrat TMB, plate diinkubasi pada suhu 37oC selama 15 menit dan dihindarkan dari cahaya kemudian dilakukan penghentian reaksi dan selanjutnya dilakukan pengukuran penyerapan pada 450 nm.
Data yang dikumpulkan mencakup karakteristik umum sampel (umur, jenis kelamin, MAP, tekanan arteri rata-rata, status ASA) dan kadar kortisol serum sebelum dan sesudah perlakuan. Uji statistic Wilcoxon Signed Rank Test dan Paired T Test digunakan untuk membandingkan kadar kortisol di masing-masing kelompok. Uji Mann Whitney dan Independent Sample T Test digunakan untuk membandingkan antar kelompok kontrol dan perlakuan
HASIL DAN PEMBAHASAN Data karakteristik umum sampel yang telah diperiksa (data baseline) dilakukan uji komparatif untuk tiap variable dan didapatkan hasil yang tidak berbeda bermakna. Data kadar kortisol yang didapatkan pada ketiga kelompok: preanestesi, 2 jam pasca induksi, dan 8 jam pasca induksi sebagian besar memperlihatkan distribusi yang merata, kecuali kelompok kontrol preanestesi dan kelompok perlakuan 8 jam post induksi. Kemudian dilakukan analisis data uji hipotesis dan didapatkan hasil analisis yang disajikan dalam tabel berikut.
24
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Tabel 1. Nilai distribusi tiap kelompok Kelompok Pre anestesi E C E C E C 244,15 (181,39-382,75) 258,49 (175,45-369,09) 185,52 + 35,88 202,14 + 45,3 349,81 + 121,28 251,39 + 122,91 Nilai p 0,10 0,47 0,174 0,121 0,487 0,032
2 jam pasca induksi
8 jam pasca induksi
Tabel 2. Hasil uji hipotesis Deskripsi uji hipotesis Etomidat Pre vs 2 jam 2 jam vs 8 jam Pre vs 2 jam 2 jam vs 8 jam Etomidat vs vit C Etomidat vs vit C Nilai p 0,002* 0,000** 0,256* 0,691* 0,300*** 0,036****
Etomidat & vit C
2 jam pasca induksi 8 jam pasca induksi * Wilcoxon Signed Rank Test **Paired T test ***Mann Whitney ****Independent Sample T Test
Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kontrol, kadar kortisol preanestesi dan 2 jam pasca induksi berbeda bermakna (p=0,002). Begitu pula antara kadar 2 jam dengan 8 jam pasca induksi (p=0,000). Hal ini berarti efek depresi kortisol etomidat tetap berlangsung walau kadarnya telah dikurangi sebanyak 0,1 mg/kgBB. Selain itu diperlihatkan pula bahwa efek depresi kortisol tersebut terjadi secara bertahap, sehingga kadar kortisol antara 2 jam dan
8 jam pasca induksi dapat berbeda secara bermakna. Sedangkan pada kelompok perlakuan, kadar kortisol antara pre anestesi dan 2 jam pasca induksi tidak berbeda bermakna (p=0,256), begitu pula 2 jam pasca induksi dengan 8 jam pasca induksi (p=0,691). Hal ini menunjukkan adanya efek negatif dari vitamin C terhadap efek depresi kortisol etomidat. Efek tersebut telah muncul pada 2 jam pasca induksi dan dipertahankan hingga 8 jam pasca 25
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
induksi. Hasil ini jauh lebih cepat dibandingkan hasil yang disajikan oleh studi Pirbudak et al. Pada analisis komparatif antara kelompok kontrol dan perlakuan didapatkan perbedaan yang signifikan pada kadar kortisol 8 jam pasca induksi, namun tidak pada 2 jam pasca induksi. Hal ini menunjukkan bahwa efek depresi kortisol etomidat hanya bertahan kurang dari 8 jam pasca induksi. Temuan ini sekaligus menyangkal kekhawatiran adanya depresi kortisol yang memanjang pada pemberian etomidat. Temuan di atas juga dapat diartikan bahwa pemberian vitamin C mampu menstabilkan kadar kortisol darah pada pemberian etomidat.
lama vitamin C memberikan efek negatif terhadap depresi kortisol yang ditimbulkan etomidat.
DAFTAR PUSTAKA
1. Reves JG, Glass P. Intravenous anesthesia. In: Miller RD, ed Miller anesthesia 7th edition. California: Churchill livingstone; 2005 2. Licille B. Endotracheal intubation. Safe Anesthesia intubation 1996: 113-26 3. Morgan. GE, Mikhail MS, MUrry MJ. Nonvolatile agent anesthesia. In: Clinical Anesthesiology. 3rd ed. New York: Large Medical Books/McGrew-Hill Medical Publishing Edition; 2002, 199-200 4. Stoelting RK, Hillier SC. Pharmacology and physicology in anesthetic practice 3rd edition. Philadelphia: Lippincot-Raven; 1999, 141-3 5. Arden Pharmacology of etomidate. Available from http:/www.metrohealthanesthesia.com 6. Katzung BG. Farmakologi dasar dan klinik, edisi 8 bahasa Indonesia. Bagian Farmakologi Kedokteran Universitas Airlangga. Surabaya: Salemba Medika; 2002, 153-4 7. White PF. Nonopioid intravenous anesthesia. In: Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK. Clinical anesthesia 5th edition. Lippincott Williams & Willkins; 2006,344-5 8. Chung DC, Lam AM, editors. Essential of anesthesiology, 3rd edition. London: W.B Saunders Company; 2001, 177-8 9. Oglesby AJ. Should etomidate be the induction agent of choice for rapid sequence intubation in emergency department. Emergency medical journal 2004; 21: 655-9 10. William L, Jacson jr. Should we use etomidate as an intubation agent for endotracheal intubation in patient with septic shock. CHEST journal 2005; 127: 1031-8 11. Boidin MP, Erdmann. The role of ascorbic acid in etomidate toxicity. Europe journal anesthesiology 1986: 417-22
KESIMPULAN Pemberian Vitamin C 200 mg intra vena 30 menit preoperasi dapat menurunkan efek depresi kortisol oleh pemberian etomidate 0,2 mg/kgBB. Penurunan efek depresi kortisol tersebut tidak ditimbulkan lewat pengurangan dosis etomidat sebesar 0,3 mg/kgBB. Efek depresi kortisol oleh etomidat hanya bertahan kurang dari 8 jam. Di masa depan perlu dilakukan studi serupa dengan jumlah sampel yang lebih banyak atau dengan variasi operasi yang minimal, sehingga hasilnya dapat digeneralisir. Selain itu, diperlukan pula studi efek pemberian etomidat dan vitamin C dengan jenjang pemeriksaan waktu yang lebih banyak, sehingga dapat diketahui mulai kapankah dan berapa
26
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
12. National Academy of Science. Vitamin C In: Dietary reference intakes for vitamin, vitamin e, selenium and carotenoids. Washington DC: National academy press 2000: 95-131 13. Murray RK , Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW. Biokimia Harper, edisi 25 bahasa Indonesia. Jakarta. EGC: 2003, 598612 14. Pirbudak L, Balat O. Effects of ascorbic acid on surgical stress response in gynecologic
surgery. Journal of clinical practice 2004:928-31 15. Nathan N, Vandroux JC. Role of vitamin C and adrenocortical effects of etomidate. Ann fr anesthesiology reanimation journal 1991:329-32 16. Schraag S, Pawlink M, Mohl U. The role of ascorbic acid and xylithol in etomidateinduced adenocortical suppression in human. European journal 1996: 346-51
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
27
Jurnal Anestesiologi Indonesia
PENELITIAN Pengaruh Nitrous Oxide Pada Induksi Sevofluran 8% Dengan Tehnik Single Breath Terhadap Kecepatan Induksi Anestesi
Tinon Anindita*, Witjaksono*
ABSTRACT Background: The addition of Nitrous Oxide increase induction time of anesthesia agent,because of second gas effect and concentration effect. The aims of this study is to compare induction time of 8% sevoflurane with and without Nitrous oxide using a singlebreath vital capacity induction. Methods: Seventy two healthy unpremedicated patients were randomized to inhale a singlebreath, one of three gas mixture : 8% sevoflurane in Oksigen (group I), 8% sevoflurane in 50% Nitrous oxide (group II) and 8% sevoflurane in 66 2/3% Nitrous oxide (group 111).The time to absent of the eyelash reflex and induction-related complications, if present, were noted by independent observer. Blood pressure (systolic, diastolic and mean arterial pressure/MAP), and heart rate were measured pre and post induction. Data was analyzed using student T-Test and ANOVA at significancy level of 0,05. Result: Three groups had similar distribution on sex,age,body weight, and early clinical state. The time to absent of the eyelash reflex with 8% sevofllurane in 50% Nitrous oxide, 24,96 4,14 second ,and for 8% sevoflurane in 66 2/3% Nitrous oxide , 24,81 3,85 second, were less than that with 8% sevoflurane in Oksigen, 27,21 4,14 second, but this was no significant (p = 0,098).Changes in blood pressure (systolic,diastolic, mean arterial pressure), heart rate and oksigen saturation were no significant different on three groups.The induction-related complications in the sevoflurane with Nitrous oxide groups were less than that in the sevoflurane without Nitrous oxide group, but this was no significant different. Conclusion: The addition of Nitrous oxide do not increase induction time of anesthesia with a single-breath of 8% sevoflurane. Keywords: Sevoflurane,nitrous oxide, induction time.
ABSTRAK Latar Belakang : Penambahan nitrous oxide pada induksi anestesi akan mempercepat waktu induksi, oleh karena adanya second gas effect dan concentration effect. Maksud
*Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip/ RSUP Dr. Kariadi, Semarang
28
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
penelitian ini adalah membandingkan kecepatan induksi anestesi sevofluran 8% dengan atau tanpa nitrous oxide, dengan menggunakan tehnik single breath vital capacity induction. Metode: Tujuh puluh dua pasien tanpa diberikan premedikasi , dibagi dalam 3 kelompok secara random dan diminta untuk menghirup salah satu dari tiga campuran gas dengan tehnik single breath vital capacity : kelompok I diberikan sevofluran 8% + Oksigen, keiompok II diberikan sevofluran 8% + 50% nitrous oxide dan kelompok III diberikan sevofluran 8% + 66 2/3% nitrous oxide. Dicatat waktu saat hilangnya reflek bulu mata dan komplikasi yang terjadi. Tekanan darah (sistolik, diastolik, tekanan arteri rerata), laju jantung dan saturasi oksigen diukur sebelum dan sesudah induksi. Data diuji dengan Student T Test dan ANOVA dengan derajat kemaknaan < 0,05. Hasil: Karakteristik penderita (umur, usia, berat badan dan lain-lain) pada ketiga kelompok berbeda tidak bermakna. Waktu saat hilangnya reflek bulu mata untuk kelompok sevofluran 8% + 50% nitrous oxide (24,96 4,14 detik), dan untuk kelompok sevofluran 8% + 66 2/3% nitrous oxide (24,81 3,85 detik) lebih sepat dibandingkan dengan kelompok sevofluran 8% + Oksigen (27,21 4,14 detik) , tetapi perbedaan ini tidak bermakna (/?-0,098), Perubahan tekanan darah (sistolik, diastolik, tekanan arteri rerata), laju jantung dan saturasi oksigen yang terjadi pada ketiga kelompok berbeda tidak bermakna. Komplikasi induksi anestesi yang terjadi pada kelompok sevofluran 8% dengan nitrous oxide lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok sevofluran 8% tanpa nitrous oxide , tetapi perbedaan ini tidak bermakna . Kesimpulan: Penambahan Nitrous oxide pada induksi anestesi dengan sevofluran 8% dengan tehnik single-breath, tidak mempercepat waktu induksi anestesi.
LATAR BELAKANG Sejak ditemukan obat anestesi intravena pada tahun 1935, induksi dengan obat anestesi inhalasi atau induksi inhalasi mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena obat anestesi inhalasi bersifat merangsang/bau kurang enak dan mengiritasi saluran pernafasan sehingga bila digunakan untuk induksi anestesi, tidak menyenangkan bagi pasien dan ahli anestesi karena sifat-sifat tersebut sering menyebabkan pasien batuk, menahan
napas, spasme laring dan waktu induksi yang lama. 1,2 Penemuan halotan pada tahun 1951, yang bersifat tidak merangsang saluran pernafasan serta mempunyai koefisien partisi darah/gas yang rendah, memungkinkan untuk dilakukan kembali induksi inhalasi dan berhasil baik terutama pada pasien anak-anak2. Pada tahun 1968, ditemukan obat anestesi inhalasi baru, yaitu sevofluran. Sevofluran mempunyai sifat-sifat : bau
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
29
Jurnal Anestesiologi Indonesia
enak, koefisien partisi darag/gas rendah (lebih rendah dari halotan, enfluran dan isofluran), dan tidak mengiritasi saluran pernapasan, sehingga mendorong para ahli anestesi untuk mengembangkan kembali induksi inhalasi pada semua pasien1,2. Induksi inhalasi dapat dilakukan dengan berbagai tehnik, yaitu : tehnik gradual induct induction, tehnik, single-breath vital capacity induct ion dan tehnik triple-breath (multiple-breath) vital capacity induction. Tehnik triple-breath vital capacity merupakan variasi dari tehnik single-breath vital capacity induction3. Tehnik single-breath vital capacity induction diperkenalkan oleh Brourne pada tahun 19544. Tehnik ini membutuhkan sifat kooperatif dari pasien dan obat anestesi inhalasi yang bersifat: bau tidak menyengat, iritasi saluran pernapasan minimal, koefisien partisi darah/gas rendah dan dapat digunakan dengan konsentrasi tinggi. Sevofluran memenuhi persyaratan tersebut, sehingga dapat digunakan untuk induksi inhalasi dengan tehnik ini. Tehnik single-breath vital capacity induction menggunakan sevofluran konsentrasi tinggi 8% dan setelah napas dalam sesuai dengan vital capacity, pasien diminta menahan napas selama mungkin (lebih 20 detik), hal ini inenyebabkan konsentrasi sevofluran di alveoli menjadi lebih tinggi, dibandingkan bila pasien langsung mengeluarkan napasnya lagi. Konsentrasi sevolfuran di alveoli yang 30
tinggi, ini menyebabkan konsentrasi obat dalan darah juga akan makin tinggi, sehingga efek terhadap organ tubuh seperti otak dan sistem kardiovaskuler akan makin besar, tetapi konsentrasi dalam darah dibutuhkan hanya untuk menidurkan pasien (sampai reflek bulu mata negatif)4,5,6,7,8 N2O (Nitrous oxide) adalah obat anestesi inhalasi yang mempunyai sifat-sifat: kelarutan dalam darah dan jaringan rendah dan tidak mengiritasi saluran pernapasan sehingga ditoleransi baik untuk induksi dengan masker. Pemberian N2O pada saat induksi akan menyebabkan peningkatan konsentrasi alevolar dari suatu obat anestesi inhalasi, oleh karena sifat second gas effect dan concentration effect dari N2O, sehingga pemberian N2O pada saat induksi anestesi dapat mempercepat induksi anestesi. Seorang penderita menerima 70%-75% N2O, akan menyerap sampai 1000 ml/menit N2O saat fase awal induksi, sehingga menghasilkan perubahan signifikan pada laju penyerapan gas lain. Seorang penderita menerima 10%-25% N2O, akan menyerap hanya 150 ml/menit N2O, hal ini tidak menghasilkan perubahan signifikan pada laju 9,10,11 penyerapan gas lain . N2O menurunkan koefisien partisi darah/gas halotan dan isofluran, sehingga akan mempercepat pengambilan halotan dan isofluran12. Penelitian menggunakan halotan dan isofluran13 dengan tehnik single-breath membuktikan bahwa pemberian N2O pada saat induksi anestesi, akan mempercepat induksi
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
anestesi. Laporan-laporan penelitian tentang pemberian N2O pada induksi dengan sevofluran bersifat kontroversial. Pada orang dewasa, pemberian N2O : O2 ; 2 : 1 pada induksi sevofluran 8% dengan tehnik single-breath ternyata tidak mempercepat induksi anestesi. Begitu pula pada anak-anak, pemberian 66% N2O pada induksi sevofluran 8% dengan tehnik single-breath tidak mempercepat induksi anestesi. 14. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami akan meneliti pengaruh pemberian 50% N2O, 66 2/3% N2O dan O2 saja, terhadap kecepatan induksi anestesi, pada induksi anestesi dengan sevofluran 8%, dengan tehnik single-breath vital capacity induction. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bukti obyektif pengaruh pemberian 50% N2O, 66 2/3% N2O dan O2 saja, terhadap kecepatan induksi anestesi, pada induksi anestesi dengan sevofluran 8%, tehnik single-breath vital capacity induction. METODE Penelitian ini merupakan uji klinik tahap 2. Rancangan penelitian yang digunakan adalah eksperimental sederhana (post test only control group design) untuk variabel waktu induksi dan eksperimental ulang (pretest-posttest control group design) untuk variabel tekanan darah, laju jantung dan saturasi oksigen15,16 Populasi pada penelitian ini adalah penderita yang menjalani operasi elektif di Instalasi Bedah Sentral RSUP dr
Kariadi Semarang dengan anestesi umum, ASA I-II, setelah penderita terseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara consecutive random sampling dimana setiap penderita yang memenuhi kriteria dimasukkan dalam sampel penelitian sampai jumlah yang diperlukan terpenuhi. Data dikumpulkan dan dicatat dalam lembar khusus penelitian yang telah disediakan serta diolah dengan komputer menggunakan program SPSS dan dinyatakan dalam rerata simpang baku (mean SO) disertai kisaran (range). Uji statistik dengan ANOVA, T Test dan Chi Square, Two-Fail Significance, dan derajat kemaknaan< 0,05. Penyajian dalam bentuk tabel dan grafik. Kriteria inklusi : Pasien RSUP Dr. Kariadi yang akan menjalani operasi elektif dengan anestesi umum, laki-laki dan wanita, umur 16-40 tahun, BMI (Body Mass Index) 20-25 kg/m2, dan tanpa pemberian obat-obat premedikasi. Kriteria eksklusi : Kelainan paru-paru, kelainan kardovaskuler. HASIL Telah dilakukan penelitian terhadap 72 sampel yang terbagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok dilakukan induksi anestesi dengan sevofluran 8% dengan tehnik single breath (aliran gas segar sesuai dengan volume semenit), dimana kelompok I (n = 24 ) diberikan O2 murni, kelompok 11 (n=24) diberikan 50% N2O + 50% O2 dan kelompok III (n-
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
31
Jurnal Anestesiologi Indonesia
24) diberikan 66 2/3% N2O + 33 1/3% O2. Penelitian ini membandingkan waktu induksi anestesi antara kelompok I dengan kelompok II, kelompok II dengan kelompok III dan kelompok III dengan kelompok I. Uji statistik dengan ANOVA dan/t test, dengan uji kemaknaan digunakan p dua ekor (two tail significance), dengan derajat kemaknaan p < 0,05.
Karakteristik penderita seperti umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, BMI (body mass index), TDSP (tekanan darah sistolik premedikasi), TDDP (tekanan darah diastolik premedikasi) , LJP (laju jantung premedikasi), LNP (laju napas premedikasi) dan status ASA penderita pada ketiga kelompok ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Penderita pada Kelompok I, II dan III.
Variabel
Kelompok I (n = 24 )
Kelompok II (n - 24)
kelompok III (n = 24)
Umur (tahun) Jenis kelamin laki-laki perempuan BB(kg) TB (cm) BM1 (kg/m2) TDSP (mmHg) TDDP (mmHg) LJP (x/memt) LNP (x/menit) FGF (L/memt) ASA I II
26,79 6,79
27,58 7,29
26,04 6,86
0,747 0,346*
11 13 55,79 7,19 160,7117,36 21,55 1,26 122,29 5,71 76,88 4,62 85,79 + 6,04 14, 13 1,45 7,83 0,76
10 14 58,71 5,52 163,215,09 21,751,32 122,085,50 75,634,73 84,637,11 14,641,33 8, 17 0,82
11 13 57,25 5,67 161,63 5,62 22,08 1,45 12 1,88 7,04 76,67 4,58 85,00 6,23 14,00 1,29 8,000,82 0,269 0,362 0,400 0,973 0,610 0,817 0.949 0,378 0.949*
18 6
19 5
18 6
Keterangan : BB = berat badan, TB = tinggi badan , BMI = body mass index, TDSP=tekanan darah sistolik premedikasi, TDDP = tekanan darah diastolik premedikasi, LJP=laju jantung premedikasi dan LNP = laju napas premedikasi, FGF =fress gas flow.Uji statistik dengan ANOVA dan Chi square* .
32
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Karakteristik penderita pada ketiga kelompok berdasarkan statistik berbeda tidak bermakna (p > 0,05). Kecepatan waktu induksi kelompok lebih cepat dibandingkan dengan kelompok II dan I. sedangkan kelompok II lebih cepat dibandingkan kelompok I, tetapi secara
statistik menunjukkan berbeda tidak bermakna di antara ketiga kelompok tersebut (p=0,098). Berdasarkan uji keorelasi, hubungan konsentrasi N2O dengan waktu induksi menunjukkan hubungan linier negative, dengan koefisien korelasi = r = -0,553 (Tabel 2)
Grafik 1. Waktu Induksi Anestesi pada Kelompok I, II, dan III. Variabel WI Kelompok I 27,214,71 Kelompok II 24,964,14 Kelompok III 24,813,85 P* 0,098
Keterangan : WI = berlaku induksi (dalam detik), p* =uji statistik dengan ANOVA
Grafik 1 menunjukkan waktu induksi kelompok III lebih cepat dibanding kelompok II dan kelompok I , serta kelompok II lebih cepat dibanding kelompok I, tetapi secara statistik berbeda tidak bermakna.
Pada ketiga kelompok terjadi penurunan tekanan darah sistolik, tekanan darah distolik, tekanan arteri rerata dan laju jantung sesudah induksi dibandingkan dengan sebelum induksi, tetapi perbandingan uji statistik antara ketiga
kelompok menunjukkan berbeda tidak bermakna (p>0,05), begitu pula pada masing-masing kelompok juga menunjukkan berbeda tidak bermakna (p 0,05).(Tabel3)
WAKTU INDUKSI
30 25 20 15 10 5 Kel. I Kel.II Kel.III waktu induksi
Induksi sevoflurane 8 % Grafik 1 menunjukkan waktu induksi kelompok III lebih cepat dibanding kelompok II dan kelompok I , serta kelompok II lebih cepat dibanding kelompok I, tetapi secara statistik berbeda tidak bermakna.
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
33
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Tabel 3. Tekanan Darah Sistolik,Tekanan Darah Diastolik, Tekanan arteri Rerata dan Laju jantung Sebelum dan Sesudah Induksi pada Kelompok I, II dan III.. Variabel TDS : -Sebelum induksi -Setelah induksi P' TDD: -Sebelum induksi -Setelah induksi P' TAR: -Sebelum induksi -Setelah induksi P' LJ -Sebelum induksi -Setelah induksi P' 86,04 6,96 84,67 9,41 0,615 86,38 5,24 83,46 6,98 0,179 86,29 + 4,80 83,29 8,46 0,208 0,978 0,824 92,42 5,69 91,29 4,19 0,460 92,25 6,32 90,46 3,49 0,156 92,50 + 6,17 90,75 4,59 0,134 0,989 0,777 78,29 5,42 77,174,10 0,444 78,04 6,05 76,67 3,51 0,258 78,33 + 5,91 76,96 4,58 0,207 0,982 0,914 124,92 6,95 123,42 4,49 0,382 124,71 7,39 123, 13 4,70 0,089 124,83 7,09 122,38 5,27 0,115 0,995 0,636 kelompok. I kelompok. II kelompok III p*
Keterangan : TDS = tekanan darah sistolik, TDD = tekanan darah diastolik, TAR = tekanan arteri rerata, : LJ = Laju jantung, p* = uji statistik denganANOVA, p' = uji statistik dengan / test
34
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
TEKANAN DARAH SISTOLIK 128 126 124 Series 1 122 120 118 Kel. I Kel.II Kel.III Series 2
Induksi sevoflurane 8 % Grafik 2. Tekanan Darah Sistolik Sebelum dan Sesudah Induksi pada Kelompok I, II dan III.
Grafik 2 menunjukkan penurunan takanan darah sistolik antara sebelum dan sesudah induksi pada masing-masing
kelompok dan antara ketiga kelompok, tetapi secara statistik berbeda tidak bermakna
TEKANAN DARAH DIASTOLIK 80
78 76
Sebelum Induksi Setelah Induksi
74 72 Kel.I Kel.II Kel.III
Induksi sevoflurane 8 % Grafik 3. Tekanan Darah Diaslotik Sebelum dan sesudah induksi pada Kelompok I,II, dan III.
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
35
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Grafik 3 menunjukkan penurunan tekanan darah diastolik antara sebelum dan sesudah induksi pada masing-masing
kelompok dan di antara ketiga kelompok, tetapi secara statistik berbeda tidak bermakana.
TEKANAN ARTERI RERATA 94 92 90 88 86 Kel.I Kel.II Kel.III
Sebelum Induksi Setelah Induksi
Induksi sevoflurane 8 % Grafik 4. Tekanan Arteri Rerata Sebelum dan Sesudah Induksi Pada Kel. I, II, dan III.
Grafik 4 menunjukkan penurunan takanan arteri rerata antara sebelum dan sesudah induksi pada masing-masing
kelompok dan antara ketiga kelompok, tetapi secara statistik berbeda tidak bemakna.
LAJU JANTUNG 90 88 86 Sebelum Induksi 84 82 80 Kel.I Kel.II Kel.III Setelah Induksi
Induksi sevoflurane 8 % Grafik 5. Laju jantung Sebelum dan Sesudah Induksi pada Kelompok I. II dan III.
36
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Grafik 5 menunjukkan penurunan laju jantung antara sebelum dan sesudah induksi pada masing-masing kelompok dan antara ketiga kelompok, tetapi secara statistik berbeda tidak bemakna. Perubahan sebelum saturasi oksigen antara dan sesudah induksi,
berdasarkan perbandingan uji statistik antara ketiga kelompok menunjukkan berbeda tidak bennakna (p > 0,05), begitu pula pada masing-masing kelompok juga menunjukkan berbeda tidak bemakna (p > 0,05). (tabel 4)
Tabel 4. Saturasi Oksigen Sebelum dan Sesudah Induksi pada Kelompok I, II dan III. Variabel Sa02 -Sebelum induksi -Setelah induksi P' 99,29 0,62 99,42 0,58 0,450 99,25 0,79 99,33 0,64 0,604 99,29 0,69 99,17 0,56 0,417 0,973 0,340 kelompok. I kelompok. II kelompok III P*
Keterangan : SaO2 = saturasi oksigen, p* = uji statistik dengan v4M9K4, p' = uji statistik dengan t test
SATURASI OKSIGEN 100
99
98
Sebelum Induksi Setelah Induksi
97
96 Kel.I Kel.II Kel.III
Induksi sevoflurane 8 % Grafik 6. Saturasi Oksigen Sebelum dan Sesudah Induksi pada Kelompok I, II dan III.
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
37
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Grafik 6 menunjukkan perubahan saturasi oksigen antara sebelum dan sesudah induksi pada masing-masing kelompok dan antara ketiga kelompok, tetapi secara statistik berbeda tidak bermakna. Komplikasi induksi anestesi menunjukkan hasil berbeda tidak bermakna antara ketiga kelompok (p = 0,259). Komplikasi yang timbul adalah batuk, yaitu , 3 orang pada kelompok yang diberikan O2, 1 orang pada kelompok yang diberikan 50% N2O + 50% 02 dan 1 orang pada kelompok diberikan 66 2/3% N2O + 33 1/3% O2.
setelah napas dalam (sesuai dengan vital capacity, kira-kira 20 detik), hal ini akan menyebabkan konsentrasi sevofluran di alveoli menjadi lebih tinggi, dibandingkan bila sampel mengeluarkan napasnya lagi. Konsentrasi sevofluran di alveoli yang tinggi , menyebabkan konsentrasi obat dalam darah juga makin tinggi, sehingga akan mempercepat waktu induksi anestesi5,6,7,8. Waktu induksi anestesi juga akan dipercepat dengan pemberian N2O, oleh karena sifat second gas effect dan concentration effect19,20. Waktu induksi pada kelompok yang diberikan N2O (kelompok 50% N2O = 24,96 4,14 detik dan kelompok 66 2/3% N2O = 24,81 3,85 detik) lebih cepat dibandingkan kelompok tanpa pemberian N2O (kelompok O2 saja =.27,20 4,71 detik ) dan makin besar konsentrasi N2O yang diberikan akan makin mempercepat waktu induksi (kelompok 66 2/3% N2O - 24,81 3,85 detik, sedangkan kelompok 50% N2O = 24,96 4,14 detik), tetapi berdasarkan uji statistik didapatkan hasil berbeda tidak bermakna sehingga pemberian N2O pada induksi anestesi dengan sevofluran 8% dengan tehnik single breath tidak mempercepat induksi anestesi dan semakin besar konsentrasi N20 tidak semakin mempercepat induksi anestesi. Hasil ini sama dengan penelitianpenelitian induksi sevofluran 8% dengan tehnik single breath yang dilakukan oleh Yurino dan Kimura (kelompok N2O : O2 (2 :1) = 41 16 detik sedangkan kelompok tanpa N20 = 48+16 detik), Ross dkk (kelompok 66 % N2O = 34
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
PEMBAHASAN Karakteristik sampel seperti umur jenis kelamin, berat badan, tinggi badan BMI (Bodv Mass Index), tekanan darah sistolik premedikasi, tekanan darah diastolik premedikasi laju jantung premedikasi laju napas premedikasi dan status ASA berdasarkan uji statistik berbeda tidak bermakna , sehingga ketiga kelompok cukup homogen dan layak diperbandingkan. Induksi Anestesi adalah peralihan dari keadaan sadar dengan reflek perlindungan masih utuh sampai dengan hilangnya kesadaran (ditandai dengan hilangnya reflek bulu mata) akibat 17,18 pemberian obat-obat anestesi Pada Penelitian ini induksi anestesi menggunakan sevofluran 8% dengan tehnik single breath vital capacity induction, yaitu sampel diberikan sevofluran konsentrasi tinggi ( 8%) dan
38
Jurnal Anestesiologi Indonesia
12 detik sedangkan kelompok tanpa N2O = 38 8 detik ) dan penelitian Tatang Bisri pada wanita hamil (kelompok 60% N2O = 24,25 detik sedangkan kelompok tanpa N2O = 25,08 detik), di mana penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemberian N2O pada induksi anestesi dengan sevofluran 8% dengan tehnik single breath tidak mempercepat induksi anestesi (berbeda tidak bermakna2,4,14.21. Penelitian lain menyimpulkan bahwa N2O tidak potensiasi dengan sevofluran tetapi potensiasi dengan halotan dan isofluran (Lerman dkk), serta pemberian N2O akan menurunkan koefisien partisi darah/gas halotan dan isofluran. (Gou dkk)2,12,21. Penelitian induksi anestesi menggunakan halotan dan isoflurane membuktikan bahwa pemberian N2O akan mempercepat induksi anestesi secara bermakna13,14,22. Kecepatan induksi anestesi antara lain dipengaruhi oleh konsentrasi zat anestesi dan pemindahan zat anestesi dari alveoli ke darah. Pemindahan zat anestesi dari alveoli ke darah dipengaruhi oleh koefisien partisi darah/gas dan aliran darah(5,6,24). Pada penelitian ini digunakan sevofluran konsentrasi tinggi yaitu 8% dan sevofluran sendiri mempunyai koefisien partisi darah/gas 0,63 , sedikit lebih tinggi dibanding N2O (0,47) tetapi lebih rendah dibanding halotan, isofluran (1,4) dan enfluran (1,91), sehingga menyebabkan induksi anestesi berlangsung dengan cepat. Konsentrasi sevofluran yang tinggi dan koefisien partisi darah/gas yang rendah tersebut seakan-akan menutup efek N2O (second
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
gas effect dan concentration effect), sehingga N2O tidak dapat bekerja optimal untuk mempercepat peningkatan konsentrasi sevofluran di alveoli dan darah.. Hal tersebut mungkin yang menyebabkan mengapa pemberian N2O tidak mempercepat induksi anestesi dengan sevofluarne7,14,23 Meskipun pemberian N2O tidak mempercepat induksi sevofluran, tetapi berdasarkan uji korelasi, terayata hubungan konsentrasi N2O dengan waktu induksi menunjukkan hubungan linier negatif (koefisisen korelasi = r = - 0, 553) , berarti terdapat kecenderungan makin tinggi konsentrasi N20 yang diberikan ,maka akan makin mempercepat waktu induksi anestesi sevofluran. Penelitian ini menunjukkan bahwa sevofluran dapat menjamin stabilitas kardiovaskuler. Ini terlihat dan hasil pengukuran tekanan darah (sistolik dan diastolik), tekanan arteri rerata dan laju jantung menunjukkan perubahan berbeda tidak bermakna antara keadaan sebelum dengan setelah induksi pada masingmasing kelompok dan antara ketiga kelompok. Penelitianpenelitian sebelumnya menunjukkan bahwa induksi sevofluran 8% dengan tehnik single breath memberikan kestabilan 4,7,14,24 hemodinamik yang baik dan pemberian N2O akan menyebabkan efek klinis yang signifikan terhadap tekanan darah dan laju jantung apabila diberikan lebih 80% 24. Penurunan tekanan darah (sistolik dan diastolik), tekanan arteri rerata dan laju jantung yang terjadi diakibatkan pemberian sevofluran konsentrasi tinggi yaitu 8% sehingga efek 39
Jurnal Anestesiologi Indonesia
terhadap kardiovaskuler akan makin besar , tetapi konsentrasi sevofluran yang tinggi ini dibutuhkan hanya untuk menidurkan pasien sampai hilangnya reflek bulu mata.Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pemberian sevofluran 4% dan sevofluran 8% mempunyai pengaruh penurunan tekanan darah dan laju jantung yang sama pada saat reflek bulu mata negatif, yang berbeda adalah waktu induksinya24,25 Perubahan saturasi oksigen menunjukkan hasil berbeda tidak bermakna antara ketiga kelompok dan antara sebelum dengan sesudah induksi pada masingmasing kelompok. Sehingga penambahan N2O sampai konsentrasi 662/3% tidak mempengaruhi saturasi oksigen pada saat induksi anestesi. Hal ini mungkin disebabkan oleh waktu induksi sevofluran yang cepat dan oksigenasi sebelum induksi cukup efektif untuk meningkatkan cadangan oksigen(4,7,14). Komplikasi induksi anestesi pada masing-masing kelompok adalah minimal dan menunjukkan hasil berbeda tidak bermakna. Komplikasi yang terjadi adalah batuk, yaitu 3 orang pada kelompok 02 , 1 orang pada kelompok 50% N2O dan 1 orang pada kelompok 66 2/3% N2O. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena sifat-sifat sevofluran dan N20 , yaitu iritasi jalan napas minimal dan koefisien partisi darah/gas yang rendah, sehingga induksi berjalan mulus dan cepat. Kelompok yang diberikan N2O, komplikasi induksi lebih sedikit dibandmgkan tanpa N2O., hal ini disebabkan pemberian N2O akan
menyebabkan sedasi ringan (mulai 25%) dan peningkatan konsentrasi akan menyebabkan penurunan sensasi perasaan khusus misalnya bau sehingga mengurangi komplikasi induksi. 4,7,14,26.
KESIMPULAN Pemberian N2O pada induksi anestesi dengan sevofluran 8% dengan tehnik single breath , tidak mempercepat waktu induksi anestesi. Induksi anestesi dengan sevofluran 8% dengan atau tanpa N2O , dengan tehnik single breath menunjukkan gejolak kardiovaskuler yang minimal (tekanan darah, tekanan arteri rerata dan laju jantung). Induksi anestesi dengan sevofluran 8% dengan atau tanpa N2O ,dengan tehnik single breath berjalan lancar tanpa komplikasi yang berarti. Perlu dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar dan bervariasi sehingga akan dapat diketahui dengan tepat pengaruh Nitrous oxide terhadap kecepatan induksi anestesi dengan sevofluran. Perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian Nitrous oxide pada induksi anestesi, dengan menggunakan obat anestesi inhalasi yang mempunyai koefisien partisi darah/ gas sama atau lebih rendah dari Nitrous oxide, sehingga dapat diketahui apakah second gas effect dan concentration effect dari Nitrous oxide masih dapat berefek maksimal atau tidak.
40
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
1. Bisri T. Konsep VIMA dengan sevofluran. Bandung, 1998 : 2-22 2. Bisri T. Sevofluran untuk VIMA pada pediatnk anestesi. Dalam : Kumpulan Makalah Simposium Anestesi Pediatrik. Bandung : Bagian Anestesiologi FK Unpad / RSUP dr. Hasan Sadikin dan IDSAI Jawa Barat, 1998. 3. Rushman GB, Davies NJH, Cashyman JN. Administration of Volatile anaesthetics and gases. In A Synopsis of Anesthesia. 12th ed. Oxford : Butterworth Co, 1999 ; 152-63. 4. Agnor RC, Sikich NB, Leman J. Single-breath vital capacity rapid inhalation induction in children : 8% sevofluran versus 5% halothane. Anesthesiology 1998 ; 89 : 379 - 84. 5. Handoko T. Anestetik umum. Dalam : Gan S, penyunting. Farmakologi dan Terapi. Edisi III. Jakarta : Bagian Farmakologi FK. UI, 1987 ; 103 - 15. 6. Joenoerham J, Latif SA. Anestesia Umum. Dalam : Muhiman M, Sunatrio, Dahlan R, penyunting. Anestesiologi. Jakarta : CV Infomedia, 1989 ; 80- 1. 7. Yurino M, Kimura H. Induction of anesthesia with sevofluran, Nitrous oxide and Oxygen : A Comparison of spontaneus ventilation and vital capacity rapid inhalation induction tehniques. Anesthesia and Analgesia 1993 ; 76 : 598 - 601. 8. Nishiyama T, Aibiki M, Hanaoka K. Haemodynamic and catecholamin changes during rapid sevofluran induction with tidal volume breathing. Canadian Journal of Anesthesia 1997; 44: 1066-1070. 9. Baswell MV, Collins VJ. Pharmacology of Inorganic Gas Anesthetics. In : Collins VJ, ed. Physiologic and Pharmacologic Bases of Anesthesia. Chicago : Willim and Wilkins, 1996; 712-23.
10.Morgan E, Mikhael M. Inhalational Anesthetics. In : Clinical Anesthesiology. 1st ed Connecticut: Prentice-Hall International Inc, 1992 ; 105 - 07. 11.Korman W, Maplesson WW. Concentration and second gas effect : can the accepted explanation be improved ? British Journal of Anaesthesia 1997 ; 78 : 618 - 625. 12.Gou M, Alex M, Rolf L. Nitrous oxide decrease solubility of Halotan and isoflurane in blood. Anesthesia and Analgesia 1993 ; 77 : 761 - 5. 13.Lambert J. Single-breath induction of anesthesia with isoflurane. Br J Anaesth 1987 ; 59 : 1214- 18. 14.Yurino M, Kimura H. Comparison of induction time and characteristics between sevofluran and sevofluran / nitrous oxide. Anaesthesiology 1995 ; 39 : 356 - 8. 15. Smith I, Nathanson HM, White PF. Sevofluran - a long-awaited volatile anaesthetic. British Journal of Anaesthesia 1996 ; 76 : 435 - 45.
16.Cousins M, Seaton H. Volatile anaesthetic agents and their delivery systems. In : Healy T, Cohen PJ, eds. A Practise of Anaesthesia 6lh ed. London : Edward Arnold, 1995 ; 117 119. 17.Baswell MV, Collins VJ. Fluorinated Ether Anesthetic. In : Collins VJ, ed. Physiologic and Pharmacologic Bases of Anesthesia. Chicago : William and Wikins, 1996 ; 700 - 3. 18.Lennon P. Intravenous and Inhalation Anesthetic. In : Davison KJ, Eckhardt WF, Perese DA, eds. Clinical Anesthesia Procedures of the Masachusetts General Hospital. 4th ed. Boston : Little, Brown and Company, 1993 ; 143 - 50. 19.Guyton AC. Fisiologi Kedokteran. Edisi 5. Jakarta : EGC, 1983 : 6 - 8.
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
41
Jurnal Anestesiologi Indonesia
20.Price SA, Wilson LM. Patofisiologi : Konsep klinis proses-proses penyakit. Cetakan I. Jakarta: EGC, 1995 : 667 -77. 21.Colins VJ. Anatomical aspects of respiration. In : Physiologic and Pharmacologic Bases of Anesthesia. Chicago : Williams and Wilkins, 1996 ; 2 - 12. 22.Haloday DA. Elimination of inhalation anesthetics. In : Collins VJ, ed. Physiologic and Pharmacologic Bases of Anesthesia. Chicago : Williams and Wilkins, 1996 ; 730. 23.Tatang B. Neuroanestesi. Edisi 1. Bandung 1996 : 1 - 15. 24.Walpole R, Logan M. Effect of sevofluran concentration on inhalation induction of anaesthesia in the elderly. British Journal of Anaesthesia 1999 ; 82 : 2 - 24. 25.Baum VC, Yemen TA. Immediate 8% sevofluran induction in children : A Comparison with incremental sevofluran anf incremental halothane. Anaethesia and analgesia 1997 ; 85:313-16. 26.Philip BK, Lombard LL, Roaf ER. Comparison of vital capacity induction with sevofluran to intravenous with propofol for adult ambulatory anesthesia. Anesthesi and analgesia, 1999 ; 89 : 623 7.
42
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
TINJAUAN PUSTAKA Pengaruh Anestesi Epidural Terhadap Supresi Imun Yang Diinduksi Stres Operasi Selama Pembedahan Ifar Irianto Yudhowibowo*, Doso Sutiyono*
ABSTRACT Major surgery associated with dysfunction of the innate immune system. More recently, demonstrated that the stress of surgery can rapidly induce a temporary reduction of the blood response to endotoxin from 2 h after incision and that plasma IL-10 increased during surgery, contributes to reducing the response. It has been reported that epidural anesthesia has beneficial effects on immune reactions and response to the stress of surgery. Some researchers have reported that epidural anesthesia maintains NK cell activity and reduced stress response in patients undergoing hysterectomy. Epidural block from T4 to S5 dermatomal segments, starting before surgery, to prevent an increase in cortisol and glucose concentrations in the hysterectomy. Regional anesthesia techniques for major surgery may reduce the release of cortisol, adrenaline (epinephrine) and other hormones, but has little effect on the cytokine response. Recent studies (Kawasaki et al., 2007) suggests that the innate immune system, such as phagocytosis, suppressed by the stress of surgery and that epidural anesthesia did not prevent this decline in immune responsiveness during upper abdominal surgery ABSTRAK Operasi besar berhubungan dengan disfungsi sistem kekebalan tubuh bawaan. Baru-baru ini, dibuktikan bahwa stres akibat pembedahan dapat dengan cepat menginduksi penurunan respon sementara dari darah terhadap endotoksin sejak 2 jam setelah insisi dan bahwa IL-10 plasmayang meningkat selama pembedahan, berperan dalam penurunan respon ini. Telah dilaporkan bahwa anestesi epidural memiliki efek menguntungkan pada reaksi imunitas dan respon terhadap stres akibat pembedahan.Beberapa peneliti telah melaporkan bahwa anestesi epidural mempertahankan aktivitas sel NK dan mengurangi respon stres pada pasien yang menjalani histerektomi. Blok epidural dari segmen dermatom T4 sampai S5, dimulai sebelum pembedahan, mencegah peningkatan konsentrasi kortisol dan glukosa pada histerektomi. Teknik anestesi regional untuk operasi besar dapat mengurangi
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
*Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip/ RSUP Dr. Kariadi, Semarang
43
Jurnal Anestesiologi Indonesia
pelepasan kortisol, adrenalin (epinefrin) dan hormon lain, namun memiliki pengaruh kecil pada respon sitokin. Penelitian terbaru (kawasaki et al.,2007) menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh bawaan, misalnya fagositosis, ditekan oleh stres akibat pembedahan dan bahwa anestesi epidural tidak mampu mencegah penurunan respon kekebalan tubuh ini selama operasi perut bagian atas.
PENDAHULUAN Banyak peneliti telah melaporkan bahwa stres akibat pembedahan dapat menginduksi imunosupresi. Operasi besar berhubungan dengan disfungsi sistem kekebalan tubuh bawaan. Baru-baru ini, dibuktikan bahwa stres akibat pembedahan dapat dengan cepat menginduksi penurunan respon sementara dari darah terhadap endotoksin sejak 2 jam setelah insisi dan bahwa IL-10 plasma yang meningkat selama pembedahan, berperan dalam penurunan respon ini. Penurunan ini meningkatkan risiko terjadinya komplikasi paska operasi, seperti SIRS (systemic inflammatory response syndrome), sepsis, dan kegagalan multi organ. Telah dilaporkan bahwa anestesi epidural memiliki efek menguntungkan pada reaksi imunitas dan respon terhadap stres akibat pembedahan.Beberapa peneliti telah melaporkan bahwa anestesi epidural mempertahankan aktivitas sel NK dan mengurangi respon stres pada pasien yang menjalani histerektomi. Blok saraf simpatis yang disebabkan oleh anestesi epidural dapat mengurangi respon stres akibat pembedahan dari katekolamin dan kortisol plasma serta meningkatkan
beberapa respon imun, seperti sitotoksisitas sel Natural Killer(NK) pada pasien yang menjalani pembedahan perut bagian bawah.Namun demikian, beberapa peneliti telah melaporkan bahwa anestesi epidural tidak berefek terhadap stres operasi pada pasien yang menjalani pembedahan perut bagian atas.
RESPON IMUN TERHADAP STRES OPERASI Sitokin memilikiperan utama dalam respon inflamasi terhadap pembedahan, trauma dan mekanisme nyeri. Sitokin memiliki efek lokal menjadi mediator dan mempertahankan respon inflamasi pada jaringan yang cedera, dan juga memacu terjadinya beberapa perubahan sistemik. Setelah operasi besar, sitokin utama yang diproduksi adalah interleukin-1(IL-1), tumor necrosing factor(TNF-)dan interleukin-6(IL-6). IL-6 adalah sitokin utama yang bertanggung jawabuntuk menginduksi perubahan sistemik yang dikenal sebagai respon fase akut.1,2,3,4 Dalam 30-60 menit setelah pembedahan dimulai,konsentrasi IL-6mulai meningkat; perubahan konsentrasinya menjadi signifikan setelah 2-4 jam. Produksi sitokin mencerminkan tingkat kerusakan
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
44
Jurnal Anestesiologi Indonesia
jaringan, sehingga prosedur dengan tingkat invasif dan traumatis minimal dapat menyebabkan pelepasan sitokin paling sedikit, misalnyabedah laparoskopi. Peningkatan IL-6 terbesar terjadi setelah operasibesar seperti operasi penggantian sendi, operasi pembuluh darah utamadan operasi kolorektal. Setelah operasi ini,konsentrasi sitokin mencapai tingkat maksimal setelah 24 jam dan tetap tinggi sampai 48-72 jam setelah operasi (Sheeran danHall, 1997).2
Tabel 1. Jenis jenis sitokin pada inflamasi akut. SITOKIN YANG INFLAMASI AKUT Sitokin TNF- Aksi Pro-inflamasi; pelepasan leukosit olehsumsum tulang; aktivasi leukosit dansel endotel Demam; aktivasi sel T dan makrofag Pertumbuhan dan diferensiasi limfosit;aktivasi respon protein faseakut Kemotaksis untuk neutrofil dan sel T Menghambat fungsi kekebalan tubuh TERLIBAT DALAM
menginduksi penurunan respon sementara dari darah terhadap endotoksin sejak 2 jam setelah insisi dan bahwa IL-10 plasmayang meningkat selama pembedahan, berperan dalam penurunan respon ini.6 Berdasarkan hasil penelitian (kawasaki et al,2007) terhadap 20 pasien yang menjalani operasi gastrektomi parsial didapatkan: Aktivitas fagositosis neutrofil menurun secara signifikan 2 jam setelah operasi dimulai dan pulih ke tingkat praoperasi pada hari keempat paska operasi, konsentrasi IL-10 plasma meningkat secara signifikan2 jamsetelah operasi dimulai dan mencapai puncaknyapada akhiroperasi, konsentrasi IL-10 kembali ke tingkat pra-operasi pada hari keempat paska operasi; produksi TNF- menurun secara signifikan 2 jam setelah operasi dimulai dan mencapai nilai minimum pada akhir operasi. Produksi TNF- yang diinduksi-LPS pulih ke tingkat pra-operasi pada hari pertama paska operasi.6
IL-1 IL-6
IL-8 IL-10
(TNF = tumor necrosis factor; IL = interleukin)
PENGARUH ANESTESI EPIDURAL TERHADAP SUPRESI IMUN YANG DIINDUKSI STRES OPERASI Telah dilaporkan bahwa anestesi epidural memiliki efek menguntungkan pada reaksi imunitas dan respon terhadap stres akibat pembedahan.6,7,8Beberapa peneliti telah melaporkan bahwa anestesi epidural mempertahankan aktivitas sel NK dan mengurangi respon stres pada pasien yang menjalani histerektomi.9 Blok epidural dari segmen dermatom T4 sampai S5, dimulai sebelum pembedahan, mencegah 45
SUPRESI IMUN YANG DIINDUKSI STRES OPERASI Banyak peneliti telah melaporkan bahwa stres akibat pembedahan dapat menginduksi imunosupresi. Operasi besar berhubungan dengan disfungsi sistem kekebalan tubuh bawaan. Baru-baru ini, dibuktikan bahwa stres akibat pembedahan dapat dengan cepat
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
peningkatan konsentrasi kortisol dan glukosa pada histerektomi.10Teknik anestesi regional untuk operasi besar dapat mengurangi pelepasan kortisol, adrenalin (epinefrin) dan hormon lain, namun memiliki pengaruh kecil pada respon sitokin.3 Anestesi lokal dapat mengurangi respon inflamasi pascaoperasi melalui dua cara: memblokir transmisi sarafpada lokasikerusakan jaringan dan mengurangi inflamasi neurogenik(Coderre et al, 1993); anestesi lokal juga memiliki sifat anti-inflamasi sistemik sendiri (Hollmann danDurieux, 2000).Tampaknya hanya teknik anestesi regional saja yang dapat menurunkan respon stres jangka panjang.2 Terdapat perbedaan produksi IL-6 yang signifikan antara pasien yang mendapat analgetik terkontrol (patient controlled analgesia-PCA), pasien yang mendapat analgetik epidural terkontrol (patientcontrolled epidural analgesia-PCEA) dan pasien yang mendapat rejimen opiat intermiten(intermittent opioates-IOR) selama 72 jam. Kadar IL-6tidak terlalu meningkat pada kelompok PCEA, hampir kembali ke nilai preoperatif setelah 72 jam. Sebaliknya, IL-6 paling banyak meningkat pada kelompok IOR dan masih meningkat setelah 72 jam, sedangkan kadar IL-6 di kelompok PCA naik secara intermediet (Beilin et al., 2003).2,11 Hole dkk,Menunjukkan bahwa fungsi limfosit dan monositakan tersupresi di bawah anestesi umum, namun bisa dipertahankan di bawah anestesi epidural pada pasien yang menjalani penggantian
panggul total. Selain itu, mereka juga menunjukkan bahwa anestesi epidural menekan peningkatan konsentrasi kortisol serum selama pembedahan.Sebaliknya, pada pasien yang menjalani operasi perut bagian atas, ada beberapa laporan bahwa anestesi epidural tidak memperbaiki penekanan sistem imun atau respon terhadap stres. Tonnesen dkk, Melaporkan bahwa aktivitas sel NK selama operasi perut bagian atas menurun secara signifikan selama anestesi umum dan anestesi umum yang digabung dengan anestesi epidural.6 Penelitian terbaru (kawasaki et al.,2007) menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh bawaan, misalnya fagositosis, ditekan oleh stres akibat pembedahan dan bahwa anestesi epidural tidak mampu mencegah penurunan respon kekebalan tubuh ini selama operasi perut bagian atas.6
RINGKASAN Operasi besar berhubungan dengan disfungsi sistem kekebalan tubuh bawaan. Baru-baru ini, dibuktikan bahwa stres akibat pembedahan dapat dengan cepat menginduksi penurunan respon sementara dari darah terhadap endotoksin sejak 2 jam setelah insisi dan bahwa IL-10 plasmayang meningkat selama pembedahan, berperan dalam penurunan respon ini. Telah dilaporkan bahwa anestesi epidural memiliki efek menguntungkan pada reaksi imunitas dan respon terhadap stres akibat
46
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
pembedahan.Beberapa peneliti telah melaporkan bahwa anestesi epidural mempertahankan aktivitas sel NK dan mengurangi respon stres pada pasien yang menjalani histerektomi. Blok epidural dari segmen dermatom T4 sampai S5, dimulai sebelum pembedahan, mencegah peningkatan konsentrasi kortisol dan glukosa pada histerektomi. Teknik anestesi regional untuk operasi besar dapat mengurangi pelepasan kortisol, adrenalin (epinefrin) dan hormon lain, namun memiliki pengaruh kecil pada respon sitokin. Penelitian terbaru (kawasaki et al.,2007) menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh bawaan, misalnya fagositosis, ditekan oleh stres akibat pembedahan dan bahwa anestesi epidural tidak mampu mencegah penurunan respon kekebalan tubuh ini selama operasi perut bagian atas.
5.
6.
[update 2005 Okt 21; cited 2011 Sep 26]. Available from: http://xa.yimg.com/kq/groups/1864568/287187 149/name/Interleukin10+Production.pdf Hermawan A G. Sitokin yang berperan dalam SIRS dan sepsis. SIRS, sepsis dansyok septik. Surakarta: UNS press, 2008; 23. Kawasaki T, Ogata M, Kawasaki C, Okamoto K, Sata T. Effects of epidural anaesthesia on surgical stress-induced immunosuppression during upper abdominal surgery [homepage on the Internet]. c2006 [update 2007 Jan 11; cited 2011 Sep 26]. Available from: http://bja.oxfordjournals.org/content/98/2/196.f ull.pdf
7.
DAFTAR PUSTAKA
1. Choileain N N, Redmond H P. Cell response to surgery [homepage on the Internet]. c2006 [cited 2011 Okt 5]. Avalaible from: http://archsurg.amaassn.org/cgi/reprint/141/11/1132.pdf Goluovska I, Vanags I. Anaesthesia and stress response to surgery [homepage on the Internet]. c2008 [cited 2011 Sep 26]. Available from: http://versita.metapress.com/content/17101800 28u232l2/fulltext.pdf Walsh T S. The metabolic response to injury [homepage on the Internet]. c2007 [cited 2011 Sep 26]. Available from: http://www.medicaltextbooksrevealed.com/file s/11217-53.pdf Kato M, Honda I, Hitoshi Suzuki H, Murakami M, Matsukawa S, Hashimoto Y. Interleukin-10 production during and after upper abdominal surgery [homepage on the Internet]. c2005
2.
3.
Sendasgupta C, Makhija N, Kiran U, Choudhary S K, Lakshmy R, Das S N. Caudal epidural sufentanil and bupivacaine decreases stress response in paediatric cardiac surgery [homepage on the Internet]. c2008 [update 2010 Apr 6; cited 2011 Sep 26]. Available from: http://www.anestesiadolor.org/repositorio/Anestesia-enpediatria/regional/Sufentabupi%20caudal%20en%20ninos.pdf 8. Wilmore D W, Kehlet H. Management of patients in fast track surgery [homepage on the Internet]. c2001 [cited 2011 Sep 26]. Avalaible from: http://www.bmj.com/content/322/7284/473.full .pdf 9. Gottschalk A, Ford J G, Regelin C C, You J, Mascha E J, Sessler D I, et al. Association between epidural analgesia and cancer recurrence after colorectal cancer surgery [homepage on the Internet]. c2010 [cited 2011 Sep 26]. Available from: http://www.mendeley.com/research/association -between-epidural-analgesia-and-cancerrecurrence-after-colorectal-cancer-surgery/ 10. Desborough J P. The stress response to trauma and surgery [homepage on the Internet]. c2000 [cited 2011 Sep 26]. Available from: http://bja.oxfordjournals.org/content/85/1/109.f ull.pdf 11. Yokoyama M, Itano Y, Katayama H, Morimatsu H, Takeda Y, Takahashi T, et al. The effects of continuous epidural anesthesia and analgesia on stress response and immune function in patients undergoing radical esophagectomy [homepage on the Internet]. c2005 [cited 2011 Sep 26]. Available from: http://www.anesthesiaanalgesia.org/content/101/5/1521.full.pdf
4.
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
47
Jurnal Anestesiologi Indonesia
TINJAUAN PUSTAKA Mekanisme Kerja Obat Anestesi Lokal Ratno Samodro*, Doso Sutiyono*
ABSTRACT Regional anesthesia is growing and expanding its use, given the variety of benefits offered, such as relatively cheap, minimal systemic effects, produce adequate analgesia and the ability to prevent the stress response is more perfect. Local anesthetic drug is chemically divided into two major categories, namely the class of Amide and ester groups. These chemical differences are reflected in differences in the metabolism of the place, where the ester group is mainly metabolized by the enzyme pseudo-cholinesterase in the plasma while the Amide groups mainly through enzymatic degradation in the liver. This difference is also related to the magnitude of the possibility of allergies, in which the ester group derived from p-amino-benzoic acid has a greater frequency of allergic tendencies. Local anesthetic commonly used in our country for the class of esters are procaine, whereas the Amide groups are lidocaine and bupivacaine. Mechanism of action of local anesthetic drugs to prevent transmission of nerve impulses (conduction blockade) by inhibiting the delivery of sodium ions through selective sodium ion gates in neuronal membranes. Failure of the sodium ion permeability of the gate to increase the speed of depolarization of the slowdown as a potential threshold was not reached so that action potentials are not propagated. Local anesthetic did not alter the resting potential or transmembrane potential threshold. Pharmacokinetics of the drug include absorption, distribution, metabolism and excretion. Complications of local anesthetic is a local side effects can occur at the injection site hematoma and abscess while systemic side effects such as neurological in the central nervous, respiratory, cardiovascular, immunological, musculoskeletal, and hematologic Some local anesthetic drug interactions include coadministration may increase the potency of each drug. decreased metabolism of local anesthetics as well as increase the potential for intoxication.
ABSTRAK Anestesi regional semakin berkembang dan meluas pemakaiannya, mengingat berbagai keuntungan yang ditawarkan, diantaranya relatif lebih murah, pengaruh sistemik yang minimal, menghasilkan analgesi yang adekuat dan kemampuan mencegah respon stress secara lebih sempurna. 48
*Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip/ RSUP Dr. Kariadi, Semarang
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Secara kimiawi obat anestesi lokal dibagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan ester dan golongan amide. Perbedaan kimia ini direfleksikan dalam perbedaan tempat metabolisme, dimana golongan ester terutama dimetabolisme oleh enzim pseudokolinesterase di plasma sedangkan golongan amide terutama melalui degradasi enzimatis di hati. Perbedaan ini juga berkaitan dengan besarnya kemungkinan terjadinya alergi, dimana golongan ester turunan dari p-amino-benzoic acid memiliki frekwensi kecenderungan alergi lebih besar. Obat anestesi lokal yang lazim dipakai di negara kita untuk golongan ester adalah prokain, sedangkan golongan amide adalah lidokain dan bupivakain. Mekanisme kerja obat anestesi local mencegah transmisi impuls saraf (blokade konduksi) dengan menghambat pengiriman ion natrium melalui gerbang ion natrium selektif pada membrane saraf. Kegagalan permeabilitas gerbang ion natrium untuk meningkatkan perlambatan kecepatan depolarisasi seperti ambang batas potensial tidak tercapai sehingga potensial aksi tidak disebarkan. Obat anestesi lokal tidak mengubah potensial istirahat transmembran atau ambang batas potensial. Farmakokinetik obat meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Komplikasi obat anestesi lokal yaitu efek samping lokal pada tempat suntikan dapat timbul hematom dan abses sedangkan efek samping sistemik antara lain neurologis pada Susunan Saraf Pusat, respirasi, kardiovaskuler, imunologi ,muskuloskeletal dan hematologi Beberapa interaksi obat anestesi lokal antara lain pemberian bersamaan dapat meningkatkan potensi masing-masing obat. penurunan metabolisme dari anestesi lokal serta meningkatkan potensi intoksikasi.
PENDAHULUAN Anestesi regional semakin berkembang dan meluas pemakaiannya, mengingat berbagai keuntungan yang ditawarkan, diantaranya relatif lebih murah, pengaruh sistemik yang minimal, menghasilkan analgesi yang adekuat dan kemampuan mencegah respon stress secara lebih sempurna. Namun demikian bukan berarti bahwa tindakan anestesi lokal tidak ada bahayanya. Hasil yang baik akan dicapai apabila selain persiapan yang optimal seperti halnya anestesi umum juga disertai
pengetahuan tentang farmakologi obat anestesi lokal.1
SEJARAH Carl Koller (1884), seorang ahli mata telah memperkenalkan untuk yang pertama kali penggunaan kokain secara topikal pada operasi mata. Gaedicke (1885) mendapatkan kokain dalam bentuk ester asam benzoat yang diisolasi dari tumbuhan koka (erythroseylon coca) yang banyak tumbuh di pegunungan Andes.
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
49
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Kemudian olah Albert Naiman (1860) dalam bentuk ekstrak. William Halsted (1884), seorang ahli bedah telah menggunakan kokain intradermal dan blok saraf fasialis, pudendal, tibialis posterior dan plexus brachialis. Selanjutnya August Bier (1898), menggunakan 3 ml kokain 0,5% intratekal untuk anestesi spinal dan pada 1908 memperkenalkan anestesi regional intravena (Bier Block). Alfred Einhorn (1904) mensintesa prokain dan pada tahun yang sama digunakan untuk anestesi lokal oleh Heinrich Braun. Penambahan epinefrin untuk memperpanjang aksi anestetik lokal dilakukan pertama kali oleh Heinrich Braun. 1,2,3 Ferdinand Cathelin dan Jean Sicard (1901) memperkenalkan anestesi epidural kaudal dan Frigel Pages (1921) memperkenalkan anestesi epidural lumbal yang diikuti oleh Achille Doglioti (1931). Selanjutnya Lofgren (1943) mensintesa anestesi lokal amide, yaitu lidokain yang menghasilkan blokade konduksi lebih kuat daripada Prokain dan menjadi pembanding semua anestesi lokal. Penggunaan klinis lidokain sejak 1947. Sebelumnya dibukain (1930), tetrakain (1932) dan sesudah itu kloroprokain (1955), mepivakain (1957), prilokain (1960), bupivakain (1963), etidokain (1972). Ropivakain dan levobupivakain adalah obat baru dengan aksi durasi hampir sama seperti bupivacain tetapi kardio dan neurotoksisitasnya lebih kecil.1-4
Penggolongan Obat Anestesi Lokal Secara kimiawi obat anestesi lokal dibagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan ester dan golongan amide. Perbedaan kimia ini direfleksikan dalam perbedaan tempat metabolisme, dimana golongan ester terutama dimetabolisme oleh enzim pseudo-kolinesterase di plasma sedangkan golongan amide terutama melalui degradasi enzimatis di hati.1,2,3,4 Perbedaan ini juga berkaitan dengan besarnya kemungkinan terjadinya alergi, dimana golongan ester turunan dari pamino-benzoic acid memiliki frekwensi kecenderungan alergi lebih besar.3 Untuk kepentingan klinis, anestesi lokal dibedakan berdasarkan potensi dan lama kerjanya menjadi 3 group. Group I meliputi prokain dan kloroprokain yang memiliki potensi lemah dengan lama kerja singkat. Group II meliputi lidokain, mepivakain dan prilokain yang memiliki potensi dan lama kerja sedang. Group III meliputi tetrakain, bupivakain dan etidokain yang memiliki potensi kuat dengan lama kerja panjang.2,3 Anestesi lokal juga dibedakan berdasar pada mula kerjanya. Kloroprokain, lidokain, mepevakain, prilokain dan etidokain memiliki mula kerja yang relatif cepat. Bupivakain memiliki mula kerja sedang, sedangkan prokain dan tetrakain bermula kerja lambat.3 Obat anestesi lokal yang lazim dipakai di negara kita untuk golongan ester adalah prokain, sedangkan golongan amide adalah lidokain dan bupivakain. Secara
50
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
garis besar ketiga obat ini dapat dibedakan sebagai berikut : 1-4
Tabel 1. Jenis anestesi lokal Prokain Golongan Mula Kerja Lama Kerja Metabolisme Dosis maksimal (mg/kgBB) Potensi Toksisitas Ester 2 menit 30 45 menit Plasma 12 Lidokain Amide 5 menit 45 90 menit Hepar 6 Bupivakai n Amide 15 menit 24 jam Hepar 2
Perbedaan penting antara obat anestesi lokal ester dan amide berkaitan dengan tempat metabolisme dan kemapuan menyebabkan reaksi alergi.2-7
1 1
3 2
15 10
HUBUNGAN STRUKTUR AKTIVITAS
Gambar 1. Obat anestesi local terdiri dari bagian lipofilik dan hidrofilik yang dihubungkan dengan ikaran rantai hidrokarbon.
Anestesi lokal terdiri dari kelompok lipofilikbiasanya dengan cincin bezenedibedakan dari kelompok hidrofilikbiasanya amin tersier berdasarkan rantai intermediat yang memiliki cabang ester atau amida. ). Kelompok hidrofilik biasanya amine tersier, seperti dietilamine, dimana bagian lipofilik biasanya merupakan cincin aromatic tak jenuh, seperti asam paraaminobenzoat. Bagian lipofilik penting untuk aktivitas obat anestesi, dan secara terapeutik sangat berguna untuk obat anestesi local yang membutuhkan keseimbangan yang bagus antara kelarutan lipid dan kelarutan air. Pada hampir semua contoh, ikatan ester (-CO-) atau amide (-NHC-) menghubungkan rantai hidrokarbon dengan rantai aromatic lipofilik. Sifat dasar ikatan ini adalah dasar untuk mengklasifikasikan obat yang menghasilkan blockade konduksi impuls saraf seperti obat anestesi local ester atau obat anestesi amide (Gambar 2).
Gambar 2. Obat anestesi local ester dan amide. Mepivacaine, bupivacaine dan ropivacaine adalah obat khiral karena molekulnya memiliki atom karbon asimetris.
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
51
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Potensi berkorelasi dengan kelarutan lemak, karena itu merupakan kemampuan anestesi lokal untuk menembus membran, lingkungan yang hidrofobik. Secara umum, potensi dan kelarutan lemak meningkat dengan meningkatnya jumlah total atom karbon pada molekul. Onset dari kerja obat bergantung dari banyak faktor, termasuk kelarutan lemak dan konsentrasi relatif bentuk larut-lemak tidak-terionisasi (B) dan bentuk larut-air terionisasi (BH+), diekspresikan oleh pKa. Pengukurannya adalah pH dimana jumlah obat yang terionisasi dan yang tidak terionisasi sama. Obat dengan kelarutan lemak yang lebih rendah biasanya memiliki onset yang lebih cepat.2,3 Anestesi lokal dengan pKa yang mendekati pH fisiologis akan memiliki konsentrasi basa tak-terionisasi lebih tinggi yang dapat melewati membran sel saraf, dan umumnya memiliki onset yang lebih cepat. Onset dari kerja anestesi lokal dalam serat saraf yang terisolasi secara langsung berkorelasi dengan pKa. Onset klinis dari kerja anestesi lokal dengan pKa yang sama tidak identik. Faktor-faktor lain, seperti kemudahan berdifusi melalui jaringan ikat, dapat mempengaruhi onset kerja in vivo. Lebih lagi, tidak semua anestesi lokal berubah menjadi bentuk terionisasi (contoh: benzocaine) anestesi ini kemungkinan beraksi dengan mekanisme yang bergantian (contoh: memperlebar membran lipid).2,4 Hal yang penting dari bentuk ionisasi dan tak-terionisasi adalah implikasi klinisnya. Larutan anestesi lokal dipersiapkan secara komersial dalam bentuk garam
hidroklorida yang larut-air (pH 6-7). Karena epinefrin tidak stabil dalam suasana alkali, maka larutan anestesi lokal yang tersedia, yang mengandung epinefrin, dibuat dalam suasana asam (pH 4-5). Sebagai konsekuensi langsung, sediaan ini memiliki konsentrasi basa bebas yang lebih rendah dan onset yang lebih lambat dibanding dengan epinefrin yang ditambahkan oleh klinisi saat akan digunakan. Hal yang sama, rasio basakation ekstraselular diturunkan dan onset dihambat sewaktu anestesi lokal diinjeksi ke dalam jaringan yang bersifat asam (misal: jaringan yang terinfeksi). Walaupun masih merupakan kontroversi, beberapa peneliti melaporkan bahwa alkalinisasi larutan anestesi lokal (biasanya sediaan komersial, yang mengandung epinefrin) dengan menambahkan sodium bikarbonat (misal, 1 mL 8,4% sodium bikarbonat dalam tiap 10 mL lidokain) akan mempercepat onset, memperbaiki kualitas dari blokade dan memperpanjang durasi blokade dengan meningkatkan jumlah basa bebas yang tersedia. Yang menarik, alkalinisasi juga menurunkan nyeri saat dilakukan infiltrasi pada jaringan.2,3 Durasi kerja umumnya berkorelasi dengan kelarutan lemak. Anestesi lokal dengan kelarutan lemak tinggi memiliki durasi yang lebih panjang, diperkirakan karena lebih lama dibersihkan dari dalam darah. . Mekanisme Kerja Obat anestesi local mencegah transmisi impuls saraf (blokade konduksi) dengan
52
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
menghambat pengiriman ion natrium melalui gerbang ion natrium selektif pada membrane saraf (Butterworth dan Strichartz, 1990). Gerbang natrium sendiri adalah reseptor spesifik molekul obat anestesi local. Penyumbaatn gerbang ion yang terbuka dengan molekul obat anestesi local berkontribusi sedikit sampai hampir keseluruhan dalam inhibisi permeabilitas natrium. Kegagalan permeabilitas gerbang ion natrium untuk meningkatkan perlambatan kecepatan depolarisasi seperti ambang batas potensial tidak tercapai sehingga potensial aksi tidak disebarkan. Obat anestesi local tidak mengubah potensial istirahat transmembran atau ambang batas potensial. Lokal anestesi juga memblok kanal kalsium dan potasium dan reseptor Nmethyl-D-aspartat (NMDA) dengan derajat yang berbeda-beda. Beberapa golongan obat lain, seperti antidepresan trisiklik (amytriptiline), meperidine, anestesi inhalasi, dan ketamin juga memiliki efek memblok kanal sodium. Tidak semua serat saraf dipengaruhi sama oleh obat anestesi lokal. Sensitivitas terhadap blokade ditentukan dari diameter aksonal, derajat mielinisasi, dan berbagai faktor anatomi dan fisiologi lain. Diameter yang kecil dan banyaknya mielin meningkatkan sensitivitas terhadap anestesi lokal. Dengan demikian, sensitivitas saraf spinalis terhadap anestesi lokal: autonom > sensorik > motorik2,4,6
FARMAKOLOGI KLINIS Farmakokinetik Karena anestesi lokal biasanya diinjeksikan atau diaplikasikan sangat dekat dengan lokasi kerja maka farmakokinetik dari obat umumnya lebih dipentingkan tentang eliminasi dan toksisitas obat dibanding dengan efek klinis yang diharapkan.2,3,6 A. Absorpsi Sebagian besar membran mukosa memiliki barier yang lemah terhadap penetrasi anestesi lokal, sehingga menyebabkan onset kerja yang cepat. Kulit yang utuh membutuhkan anestesi lokal larut-lemak dengan konsentrasi tinggi untuk menghasilkan efek 2 analgesia. Absorpsi sitemik dari anestesi lokal yang diinjeksi bergantung pada aliran darah, yang ditentukan dari beberapa faktor di bawah ini 2,5 1. Lokasi injeksilaju absorpsi sistemik proporsional dengan vaskularisasi lokasi injeksi : intravena > trakeal > intercostal > caudal > paraservikal > epidural > pleksus brakhialis > ischiadikus > subkutaneus. 2. Adanya vasokonstriksi penambahan epinefrinatau yang lebih jarang fenilefrin menyebabkan vasokonstriksi pada tempat pemberian anestesi. Sebabkan penurunan absorpsi dan peningkatan pengambilan neuronal, sehingga meningkatkan
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
53
Jurnal Anestesiologi Indonesia
kualitas analgesia, memperpanjang durasi, dan meminimalkan efek toksik. Efek vasokonstriksi yang digunakan biasanya dari obat yang memiliki masa kerja pendek. Epinefrin juga dapat meningkatkan kualitas analgesia dan memperlama kerja lewat aktivitasnya terhadap resptor adrenergik 2. 3. Agen anestesi lokalanestesi lokal yang terikat kuat dengan jaringan lebih lambat terjadi absorpsi. Dan agen ini bervariasi dalam vasodilator intrinsik yang dimilikinya.
anestesi lokal karena massa dari otot yang besar.
Metabolisme dan Ekskresi Metabolisme dan ekskresi dari lokal anestesi dibedakan berdasarkan 2,5 strukturnya : 1. Esteranestesi lokal ester dominan dimetabolisme oleh pseudokolinesterase (kolinesterase palsma atau butyrylcholinesterase). Hidrolisa ester sangat cepat, dan metabolitnya yang larut-air diekskresikan ke dalam urin. Procaine dan benzocaine dimetabolisme menjadi asam paminobenzoiz (PABA), yang dikaitkan dengan reaksi alergi. Pasien yang secara genetik memiliki pseudokolinesterase yang abnormal memiliki resiko intoksikasi, karena metabolisme dari ester yang menjadi lambat. 2. Amidaanestesi lokal amida dimetabolisme (N-dealkilasi dan hidroksilasi) oleh enzim mikrosomal P-450 di hepar. Laju metabolisme amida tergantung dari agent yang spesifik (prilocine > lidocaine > mepivacaine > ropivacaine > bupivacaine), namun secara keseluruhan jauh lebih lambat dari hidrolisis ester. Penurunan fungsi hepar (misal pada sirosis hepatis) atau gangguan aliran darah ke hepar (misal gagal
B. DISTRIBUSI Distribusi tergantung dari ambilan organ, yang ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini :1,6 1. Perfusi jaringanorgan dengan perfusi jaringan yang tinggi (otak, paru, hepar, ginjal, dan jantung) bertanggung jawab terhadap ambilan awal yang cepat (fase ), yang diikuti redistribusi yang lebih lambat (fase ) sampai perfusi jaringan moderat (otot dan saluran cerna 2. Koefisien partisi jaringan/darah ikatan protein plasma yang kuat cenderung mempertahankan obat anestesi di dalam darah, dimana kelarutan lemak yang tinggi memfasilitasi ambilan jaringan. 3. Massa jaringanotot merupakan reservoar paling besar untuk
54
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
jantung kongestif, vasopresor, atau blokade reseptor H2) akan menurunkan laju metabolisme dan merupakan predisposisi terjadi intoksikasi sistemik. Sangat sedikit obat yang diekskresikan tetap oleh ginjal, walaupun metabolitnya bergantung pada bersihan ginjal.
mengejutkan jika anestesi lokal dapat menyebabkan intoksikasi sistemik. 2,4,5,7,11 A. Neurologis Sistem saraf pusat merupakan bagian yang paling rentan terjadi intoksikasi dari anestesi lokal dan merupakan sistem yang dimonitoring awal dari gejala overdosis pada pasien yang sadar. Gejala awal adalah rasa kebas, parestesi lidah, dan pusing. Keluhan sensorik dapat berupa tinitus, dan penglihatan yang kabur. Tanda eksitasi (kurang istirahat, agitasi, gelisah, paranoid) sering menunjukkan adanya depresi sistem saraf pusat (misal, bicara tidak jelas/pelo, mudah mengantuk, dan tidak sadar). Kontraksi otot yang cepat, kecil dan spontan mengawali adanya kejang tonik-klonik. Biasanya diikuti dengan gagal nafas. Reaksi eksitasi merupakan hasil dari blokade selektif pada jalur inhibitor. Anestesi lokal dengan kelarutan lemak tinggi dan pontensi tinggi menyebabkan kejang pada konsentrasi obat lebih rendah dalam darah dibanding agen anestesi dengan potensi yang lebih rendah. Dengan menurunkan aliran darah otak dan pemaparan obat, benzodiazepin dan hiperventilasi meningkatkan batas ambang terjadinya kejang karena anestesi lokal. Thiopental (1-2mg/kg) dengan cepat dan tepat menghentikan kejang. Ventilasi dan oksigenasi yang baik harus tetap dipertahankan. Lidokain intravena (1,5mg/kg) menurunkan aliran darah otak dan menurunkan peningkatan tekanan intraranial yang biasanya timbul pada intubasi pasien dengan penurunan
Komplikasi obat Anestesi lokal. 1.Efek samping lokal Pada tempat suntikan, apabila saat penyuntikan tertusuk pembuluh darah yang cukup besar, atau apabila penderita mendapat terapi anti koagulan atau ada gangguan pembekuan darah, maka akan dapat timbul hematom. Hematom ini bila terinfeksi akan dapat membentuk abses Apabila tidak infeksi mungkin saja terbentuk infiltrat dan akan diabsorbsi tanpa meninggalkan bekas. Tindakan yang perlu adalah konservatif dengan kompres hangat, atau insisi apabila telah terjadi abses disertai pemberian antibiotika yang sesuai. Apabila suatu organ end arteri dilakukan anestesi lokal dengan campuran adrenalin, dapat saja terjadi nekrosis yang memerlukan tindakan nekrotomi, disertai dengan antibiotika yang sesuai.9-10
2. Pengaruh Pada Sistem Organ Karena blokade kanal sodium mempengaruhi bangkitan aksi potensial di seluruh tubuh, sehingga bukan hal yang
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
55
Jurnal Anestesiologi Indonesia
komplians intrakranial. Lidokain dan prokain infus selama ini digunakan sebagai tambahan dalam teknik anestesi umum, karena kemampuannya menurunkan MAC dari anestesi inhalasi sampai 40%. Dosis lidokain berulang 5% dan 0,5% tetracaine dapat menjadi penyebab dari neurotoksik (sindroma kauda ekuina) setelah dilakukan infus kontinu melalui keteter bore-kecil pada anestesi spinal. Hal in terjadi mungkin karena adannya pooling obat di kauda ekuina, yang sebabkan peningkatan konsentrasi obat dan kerusakan saraf yang permanen. Penelitian pada hewan menunjukkan neurotoksisitas pada pemberian berulang melalui intratekal bahwa lidokain = tetracaine > bupivacaine > ropivacaine. Gejala neurologis transien, yang terdiri dari disestesia, nyeri terbakar, dan nyeri pada ekstremitas dan bokong pernah dilaporkan setelah dilakukan anestesi spinal dengan berbagai agent anestesi. Penyebab dari gejala ini dikaitkan dengan adanya iritasi pada radiks, dan gejala ini biasanya menghilang dalam 1 minggu. Faktor resikonya adalah penggunaan lidokain, posisi litotomi, obesitas, dan kondisi pasien.
polos bronkhus. Lidokain intravena (1,5mg.kg) terkadang mungkin efektif untuk memblok refleks bronkokonstriksi saat dilakukan intubasi. Lidokain diberikan sebagai aerosol dapat sebabkan bronkospasme pada beberapa pasien yang menderita penyakit saluran nafas reaktif.
B. Respirasi Lidokain mendepresi respon hipoksia. Paralisis dari nervus interkostalis dan nervus phrenicus atau depresi dari pusat respirasi dapat mengakibatkan apneu setelah pemaparan langsung anestesi lokal. Anestesi lokal merelaksasikan otot 56
C. Kardiovaskular Umumnya, semua anestesi lokal mendepresi automatisasi miokard (depolarisasi spontan fase IV) dan menurunkan durasi dari periode refraktori. Kontraktilitas miokard dan kecepatan konduksi juga terdepresi dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Pengaruh ini menyebabkan perubahan membran otot jantung dan inhibisi sistem saraf autonom. Semua anestesi lokal, kecuali cocaine, merelaksasikan otot polos, yang sebabkan vasodilatasi arteriolar. Kombinasi yang terjadi, yaitu bradikardi, blokade jantung, dan hipotensi dapat mengkulminasi terjadinya henti jantung. Intoksikasi pada jantung mayor biasanya membutuhkan konsentrasi tiga kali lipat dari konsentrasi yang dapat sebabkan kejang. Injeksi intravaskular bupivicaine yang tidak disengaja selama anestesi regional mengakibatkan reaksi kardiotoksik yang berat, termasuk hipotensi, blok atrioventrikular, irama idioventrikular, dan aritmia yang dapat mengancam nyawa seperti takikardi ventrikular dan fibrilasi. Kehamilan, hipoksemia, dan adisosis respiratorik merupakan faktor predisposisi.
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Ropivacaine memiliki banyak kesamaan dalam psikokimia dengan bupivacaine kecuali bahwa sebagian dari ropivacaine adalah larut-lemak. Waktu onset dan durasi kerja sama, namun ropivacaine memblok motorik lebih rendah, yang sebabkan potensi lebih rendah, ditunjukkan dalam beberapa penelitian. Yang paling menjadi perhatian, ropivacaine memiliki index terapi yang besar karena 70% lebih sedikit menyebabkan intoksikasi kardia dibandingkan dengan bupivacaine. Ropivacain dikatakan memiliki toleransi terhadap sistem saraf pusat yang lebih besar. Keamanan dari ropivacaine ini mungkin disebabkan karena kelarutan lemaknya yang rendah atau availibilitasnya sebagai isomer S(-) yang murni, yang bertolak belakang dengan struktur dari bupivacaine. Levobupivacaine, merupakan isomer S(-) dari bupivacain, yang tidak lagi tersedia di Amerika Serikat, dilaporkan memiliki efek samping terhadap cardiovaskular dan serebral yang lebih kecil dari pada struktur campuran; penelitian mengatakan bahwa efeknya terhadap kardiovaskular hampir menyerupai efek ropivacaine. D. Imunologi Reaksi hipersensitivitas murni terhadap agent anestesi lokalyang bukan intoksikasi sistemik karena konsentrasi plasma yang berlebihanmerupakan hal yang jarang. Ester memiliki kecenderungan menginduksi reaksi alergi karena adanya derivat ester yaitu asam paminobenzoic, yang merupakan suatu alergen. Sediaan komersial multidosis dari amida biasanya mengandung
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
methylparaben, yang memiliki struktur kimia mirip dengan PABA. Bahan tambahan ini yang bertanggung jawab terhadap sebagian besar reaksi alergi. Anestesi lokal dapat membantu mengurangi respon inflamasi karena pembedahan dengan cara menghambat pengaruh asam lysophosphatidic dalam mengaktivasi neutrofil.
E. Muskuloskeletal Saat diinjeksikan langsung ke dalam otot skeletal (trigger-point injeksi), anestesi lokal adalah miotoksik (bupivacaine > lidocaine > procaine). Secara histologi, hiperkontraksi miofibril menyebabkan degenarasi litik, edema, dan nekrosis. Regenerasi biasanya timbul setelah 3-4 minggu. Steroid tambahan atau injeksi epinefrin memperburuk nekrosis otot. Data penelitian hewan menunjukkan bahwa ropivacaine menghasilkan kerusakan otot yang tidak terlalu berat dibanding bupivacaine.
F. Hematologi Telah dibuktikan bahwa lidokain menurunkan koagulasi (mencegah trombosis dan menurunkan agregasi platelet) dan meningkatkan fibrinolisis dalam darah yang diukur dengan thromboelastography. Pengaruh ini mungkin berhubungan dengan penurunan efikasi autolog epidural setelah pemberian anestesi lokal dan insidensi terjadinya emboli yang lebih rendah pada pasien yang mendapatkan anestesi epidural.
57
Jurnal Anestesiologi Indonesia
Interaksi Obat Anestesi lokal meningkatkan potensi blokade otot non-depolarisasi. Suksinil kolin dan anestesi lokal ester bergantung pada pseudokolinesterase untuk metabolismenya. Pemberian bersamaan dapat meningkatkan potensi masingmasing obat. Dibucaine, anestesi lokal amida, menghambat pseudokolinesterase dan digunakan untuk mendeteksi kelainan genetik enzim. Inhibitor pseudokolinaesterase dapat menyebaban penurunan metabolisme dari anestesi lokal ester. Cimetidine dan propanolol menurunkan aliran darah hepatik dan bersihan lidokain. Level lidokain yang lebih tinggi dalam darah meningkatkan potensi intoksikasi. Opioid (misal, fentanil, morfin) dan agonis adrenergik 2 (contoh: epinefrin, klonidin) meningkatkan potensi penghilang rasa nyeri anestesi lokal. Kloroprokain epidural dapat mempengaruhi kerja analgesik dari morfin intraspinal.2-5
mencegah respon stress secara lebih sempurna. Secara kimiawi obat anestesi lokal dibagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan ester dan golongan amide. Perbedaan kimia ini direfleksikan dalam perbedaan tempat metabolisme, dimana golongan ester terutama dimetabolisme oleh enzim pseudo-kolinesterase di plasma sedangkan golongan amide terutama melalui degradasi enzimatis di hati. Perbedaan ini juga berkaitan dengan besarnya kemungkinan terjadinya alergi, dimana golongan ester turunan dari p-aminobenzoic acid memiliki frekwensi kecenderungan alergi lebih besar. Obat anestesi lokal yang lazim dipakai di negara kita untuk golongan ester adalah prokain, sedangkan golongan amide adalah lidokain dan bupivakain. Mekanisme kerja obat anestesi local mencegah transmisi impuls saraf (blokade konduksi) dengan menghambat pengiriman ion natrium melalui gerbang ion natrium selektif pada membrane saraf. Kegagalan permeabilitas gerbang ion natrium untuk meningkatkan perlambatan kecepatan depolarisasi seperti ambang batas potensial tidak tercapai sehingga potensial aksi tidak disebarkan. Obat anestesi lokal tidak mengubah potensial istirahat transmembran atau ambang batas potensial. Farmakokinetik obat meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Komplikasi obat anestesi lokal yaitu efek samping lokal pada tempat suntikan dapat timbul hematom dan abses sedangkan efek samping sistemik antara lain
RINGKASAN Anestesi regional semakin berkembang dan meluas pemakaiannya, mengingat berbagai keuntungan yang ditawarkan, diantaranya relatif lebih murah, pengaruh sistemik yang minimal, menghasilkan analgesi yang adekuat dan kemampuan
58
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
Jurnal Anestesiologi Indonesia
neurologis pada Susunan Saraf Pusat, respirasi, kardiovaskuler, imunologi ,muskuloskeletal dan hematologi Beberapa interaksi obat anestesi lokal antara lain pemberian bersamaan dapat meningkatkan potensi masing-masing obat. penurunan metabolisme dari anestesi lokal serta meningkatkan potensi intoksikasi.
DAFTAR PUSTAKA 1. Marwoto, Primatika DA. Anestesi lokal/Regional. Dalam : Soenarjo, Jatmiko DH. editor. Anestesiologi. Semarang : Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas kedokteran UNDIP, 2010: 309-22. 2. Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ. Local Anesthetics. In: Clinical Anesthesiology. 4th edition. New York: Mc Graw Hill Lange Medical Books, 2006 : 151-52, 263-75. 3. Brown DL, Factor DA. Regional Anesthesia and Analgesia. Philadelphia :WB Saunders, 1996 : 188 205. 4. Miller RD. Anesthesia. 5th edition . Philadelphia : Churchill & Livingstone, 2000 : 491 515. 5. Stoelting R Hillier SC. Pharmacology and Physiology in Anesthetics Practice. 4th ed. Philladelphia : JB Lippincott Raven, 2006: 179 - 83. 6. Gaiser RR. Pharmacology of Local Anesthetic. In : Longnecker DE,
Murphy SL, ed. Introduction to Anaesthesia. Philadelphia : WB Saunders Company, 1997 : 201-14. 7. Longnecker DE , Murphy FL . Introduction to anesthesia . 9th edition .Philadelphia : WB Saunders , 1997 : 201 14 8. Marwoto, Mudzakkir. Komplikasi anestesi lokal dan penanganannya. Majalah Ilmiah PKMI Mantap. Penerbit : Perkumpulan Kontrasepsi Mantap.Indonesia, No. 2 Tahun XII, April Juni 1992 : 44-9 9. Raj Prithvi P. Local Anaesthetics In : Ross A, editors. Textbook of regional anesthesia. Philadelphia : Elsevier Science. 2003 :120-27. 10. Sweitzer B. Local Anaesthetics. In : Davidson JK, Eckhardt WF, Perese DA. Clinical Anaesthesia Procedure of the Massacluisets General Hospital, 4th ed, Little Brown & Co Boston, Toronto, London 1993 : 197 205. 11. Mehrkens H, Geiger MP. . Local Anaesthetics. In : Peripheral regional Anaesthesia. 3rd. ed. Ulm 2005 : 169.
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
59
Jurnal Anestesiologi Indonesia
60
Volume III, Nomor 1, Tahun 2011
You might also like
- Etomidate and General Anesthesia: The Butterfly Effect?: Matthieu Legrand, MD, PHD and Benoît Plaud, MD, PHDDocument3 pagesEtomidate and General Anesthesia: The Butterfly Effect?: Matthieu Legrand, MD, PHD and Benoît Plaud, MD, PHDOussamaBàidjiNo ratings yet
- Late Results After Splenectomy in Adult Idiopathic Thrombocytopenic PurpuraDocument7 pagesLate Results After Splenectomy in Adult Idiopathic Thrombocytopenic PurpuraBogdan TrandafirNo ratings yet
- Quick and Owren PDFDocument5 pagesQuick and Owren PDFpieterinpretoria391No ratings yet
- Perbandingan Antara Ondansetron 4 MG IV Dan Deksametason 5 MG IV Dalam Mencegah Mual-Muntah Pada Pasien Laparotomi Dengan Anestesia UmumDocument7 pagesPerbandingan Antara Ondansetron 4 MG IV Dan Deksametason 5 MG IV Dalam Mencegah Mual-Muntah Pada Pasien Laparotomi Dengan Anestesia UmumDianAyu SuciDwi KusumastutiNo ratings yet
- Da 70 Bratu A 12 19iodatedDocument8 pagesDa 70 Bratu A 12 19iodatedMihaela SpinacheNo ratings yet
- Revista Brasileira DE AnestesiologiaDocument5 pagesRevista Brasileira DE AnestesiologiaAngie OrtizNo ratings yet
- Bivalirudin Anticoagulant1Document6 pagesBivalirudin Anticoagulant1walid hassanNo ratings yet
- Bipolar Versus Monopolar Resection of Benign Prostate Hyperplasia: A Comparison of Plasma Electrolytes, Hemoglobin and TUR SyndromeDocument7 pagesBipolar Versus Monopolar Resection of Benign Prostate Hyperplasia: A Comparison of Plasma Electrolytes, Hemoglobin and TUR Syndromefabian arassiNo ratings yet
- Ying Li 2016Document8 pagesYing Li 2016Bogdan TrandafirNo ratings yet
- Abstrak TiikgDocument12 pagesAbstrak TiikgAnggiLiesHalimNo ratings yet
- Bja 2013Document9 pagesBja 2013Gihan NakhlehNo ratings yet
- Application of Autologous Platelet Rich Plasma (P.R.P.) in The Extraction of Third Impacted Mandibular MolarDocument8 pagesApplication of Autologous Platelet Rich Plasma (P.R.P.) in The Extraction of Third Impacted Mandibular MolarRegia AristiyantoNo ratings yet
- Etomidat Menurunkan Kadar Gula Darah Pasca Induksi Anestesi: Oddi Riffayadi, Heru Dwi Jatmiko, Himawan SasongkoDocument8 pagesEtomidat Menurunkan Kadar Gula Darah Pasca Induksi Anestesi: Oddi Riffayadi, Heru Dwi Jatmiko, Himawan SasongkoFarah Basotjatjo KaharNo ratings yet
- Comparison of The Efficacy of Propofol TCI and Midazolam For Patients Undergoing ESWL - RCTDocument5 pagesComparison of The Efficacy of Propofol TCI and Midazolam For Patients Undergoing ESWL - RCTharvardboyNo ratings yet
- Carmignani Et Al. - 2013 - Clinical Course of Patients Receiving Anti-Platelets Therapy Who Underwent Thulium Laser Enucleation of The ProstateDocument1 pageCarmignani Et Al. - 2013 - Clinical Course of Patients Receiving Anti-Platelets Therapy Who Underwent Thulium Laser Enucleation of The ProstateNicolas FarkasNo ratings yet
- Journal Pone 0030539Document6 pagesJournal Pone 0030539shrie007No ratings yet
- JurnalDocument5 pagesJurnalkadekNo ratings yet
- Peroral Endoscopic Myotomy (POEM) For Treatment of Esophageal AchalasiaDocument7 pagesPeroral Endoscopic Myotomy (POEM) For Treatment of Esophageal AchalasiaBenni Andica SuryaNo ratings yet
- Stabilitas Hemodinamik Propofol - Ketamin Vs Propofol - Fentanyl Pada Operasi Sterilisasi / Ligasi Tuba: Perbandingan Antara Kombinasi Propofol 2Document11 pagesStabilitas Hemodinamik Propofol - Ketamin Vs Propofol - Fentanyl Pada Operasi Sterilisasi / Ligasi Tuba: Perbandingan Antara Kombinasi Propofol 2BagusIrawanWahidilmanNo ratings yet
- Ijms 40958-2Document8 pagesIjms 40958-2Manolin KinNo ratings yet
- Perbandingan Pemberian Heparin Subkutan Dan Intravena Terhadap Studi Koagulasi Dan D-Dimer Pasien Dengan Risiko Trombosis Vena DalamDocument7 pagesPerbandingan Pemberian Heparin Subkutan Dan Intravena Terhadap Studi Koagulasi Dan D-Dimer Pasien Dengan Risiko Trombosis Vena DalamNoveldy PitnaNo ratings yet
- Steroid For Management of Pseudo-OthematomaDocument9 pagesSteroid For Management of Pseudo-OthematomaElisbeth PurbaNo ratings yet
- WJMH 33 88Document7 pagesWJMH 33 88cjmrioNo ratings yet
- Conclusion: Table 1: The Most Commonly Incorrectly Answered QuestionsDocument1 pageConclusion: Table 1: The Most Commonly Incorrectly Answered Questionsbhaskaracharya dontabhaktuniNo ratings yet
- Fphar 14 1260599Document11 pagesFphar 14 1260599mimi.mca.1921No ratings yet
- 35-Article Text-37-1-10-20190121 PDFDocument7 pages35-Article Text-37-1-10-20190121 PDFPutra BsaNo ratings yet
- LPL - Lpl-Rohini (National Reference Lab) Sector - 18, Block - E Rohini DELHI 110085Document6 pagesLPL - Lpl-Rohini (National Reference Lab) Sector - 18, Block - E Rohini DELHI 110085hemendrasingNo ratings yet
- 10 36516-Jocass 1240290-2908682Document5 pages10 36516-Jocass 1240290-2908682yyyyx842No ratings yet
- Nefrología CríticaDocument10 pagesNefrología CríticaDobson Flores AparicioNo ratings yet
- Jurnal AnastesiDocument5 pagesJurnal AnastesiNadya Tenriany NajibNo ratings yet
- Toradol To Reduce Ureteroscopy Symptoms Trial (TRUST)Document5 pagesToradol To Reduce Ureteroscopy Symptoms Trial (TRUST)Oscar GarciaNo ratings yet
- Chen 2008Document3 pagesChen 2008Teodor CabelNo ratings yet
- Javaneh Jahanshahi, Farnaz Hashemian, Sara Pazira, Mohammad Hossein Bakhshaei, Farhad Farahani, Ruholah Abasi, Jalal PoorolajalDocument7 pagesJavaneh Jahanshahi, Farnaz Hashemian, Sara Pazira, Mohammad Hossein Bakhshaei, Farhad Farahani, Ruholah Abasi, Jalal PoorolajalfriscahalimNo ratings yet
- Iqbal Et Al 2000 State of The Art Review Thrombolytic Drugs in Acute Myocardial InfarctionDocument13 pagesIqbal Et Al 2000 State of The Art Review Thrombolytic Drugs in Acute Myocardial Infarctionparkviewinternending2023No ratings yet
- Angka Kejadian Komplikasi Lambat Pascaoperasi Prostatektomi Transvesikal Dan Reseksi Transuretral Pada Pasien Pembesaran Prostat JinakDocument5 pagesAngka Kejadian Komplikasi Lambat Pascaoperasi Prostatektomi Transvesikal Dan Reseksi Transuretral Pada Pasien Pembesaran Prostat JinakteckongNo ratings yet
- Jurnal LinezolidDocument6 pagesJurnal LinezolidAprilia SyafraniNo ratings yet
- PT InrDocument3 pagesPT InrJeniah Lerios OcsioNo ratings yet
- Membrane Versus Centrifuge-Based Therapeutic Plasma Exchange, A Randomized Prospective Crossover StudyDocument6 pagesMembrane Versus Centrifuge-Based Therapeutic Plasma Exchange, A Randomized Prospective Crossover Studyalida romeroNo ratings yet
- PropofolDocument9 pagesPropofolarturschander3614No ratings yet
- A Comparison of Hemodynamic Changes During Laryngoscopy and Endotracheal Intubation by Using Three Modalities of Anesthesia InductionDocument5 pagesA Comparison of Hemodynamic Changes During Laryngoscopy and Endotracheal Intubation by Using Three Modalities of Anesthesia Inductionammaa_No ratings yet
- Carmignani Et Al. - 2012 - Comparison Between Monopolar Trans-Urethral Resection of Prostate and Thulium Laser Enucleation of The ProstateDocument1 pageCarmignani Et Al. - 2012 - Comparison Between Monopolar Trans-Urethral Resection of Prostate and Thulium Laser Enucleation of The ProstateNicolas FarkasNo ratings yet
- RCT TamsulosineDocument7 pagesRCT TamsulosineRikaNo ratings yet
- 2022 - Cytokine Hemoadsorption During Cardiac Surgery Versus Standard Surgical Care For Infective Endocarditis (REMOVE) - Results From A Multicenter, Randomized, Controlled Trial - BDocument2 pages2022 - Cytokine Hemoadsorption During Cardiac Surgery Versus Standard Surgical Care For Infective Endocarditis (REMOVE) - Results From A Multicenter, Randomized, Controlled Trial - Brodrigo sacchiNo ratings yet
- Fitoterapia: Sae-Kwang Ku, In-Chul Lee, Jeong Ah Kim, Jong-Sup BaeDocument8 pagesFitoterapia: Sae-Kwang Ku, In-Chul Lee, Jeong Ah Kim, Jong-Sup BaekarinaputridamasariNo ratings yet
- Nishiyama2006 Article EffectsOfAProteaseInhibitorUliDocument4 pagesNishiyama2006 Article EffectsOfAProteaseInhibitorUliOleksandr RotarNo ratings yet
- СтатьяDocument6 pagesСтатьяAnonymous Vy5f33EdP9No ratings yet
- Laparoskopi AdrenalektomiDocument7 pagesLaparoskopi AdrenalektomimustafidNo ratings yet
- ID Prostatektomi Radikal Morbiditas Dan MorDocument6 pagesID Prostatektomi Radikal Morbiditas Dan MorarikamanjayaNo ratings yet
- An Update On Transurethral Surgery For Benign Prostatic ObstructionDocument4 pagesAn Update On Transurethral Surgery For Benign Prostatic ObstructionprashanthNo ratings yet
- New Insights Into The Pa Tho Physiology of Idiopathic Nephrotic SyndromeDocument9 pagesNew Insights Into The Pa Tho Physiology of Idiopathic Nephrotic SyndromeMartina Alarcon AcevedoNo ratings yet
- Nitrous Oxide and Long-Term Morbidity and Mortality in The ENIGMA TrialDocument7 pagesNitrous Oxide and Long-Term Morbidity and Mortality in The ENIGMA TrialAlex BogdanovNo ratings yet
- 10 1007@BF02549523Document11 pages10 1007@BF02549523rachel0301No ratings yet
- Liver Biopsy: Complications and Risk Factors: Pornpen Thampanitchawong and Teerha PiratvisuthDocument4 pagesLiver Biopsy: Complications and Risk Factors: Pornpen Thampanitchawong and Teerha PiratvisuthMauricio XimenesNo ratings yet
- CC 12031Document200 pagesCC 12031Arti Tyagita KusumawardhaniNo ratings yet
- Botox en Distonia OrofacialDocument6 pagesBotox en Distonia Orofacialcarolina vega hernandezNo ratings yet
- Pal 2011Document6 pagesPal 2011royNo ratings yet
- Perbedaan Kadar SGPT Pada Pasien TuberkuDocument10 pagesPerbedaan Kadar SGPT Pada Pasien TuberkuagneyulianaNo ratings yet
- Male Lower Urinary Tract Symptoms and Benign Prostatic HyperplasiaFrom EverandMale Lower Urinary Tract Symptoms and Benign Prostatic HyperplasiaSteven A. KaplanNo ratings yet
- Complementary and Alternative Medical Lab Testing Part 17: OncologyFrom EverandComplementary and Alternative Medical Lab Testing Part 17: OncologyNo ratings yet
- Histopathology of Preclinical Toxicity Studies: Interpretation and Relevance in Drug Safety EvaluationFrom EverandHistopathology of Preclinical Toxicity Studies: Interpretation and Relevance in Drug Safety EvaluationNo ratings yet