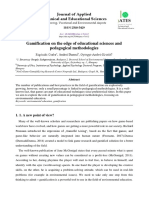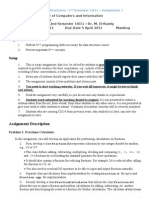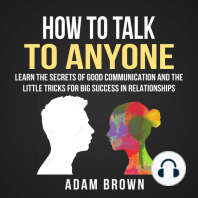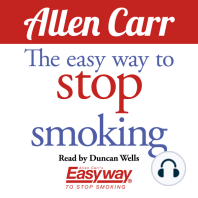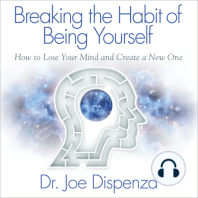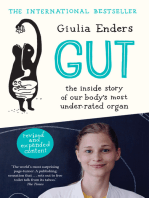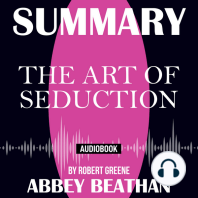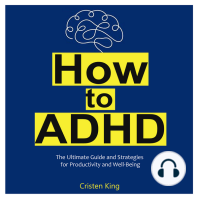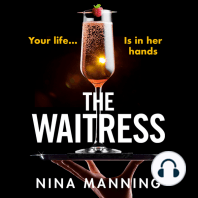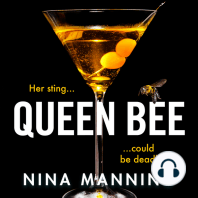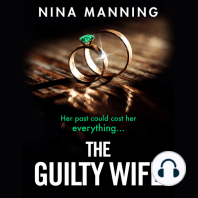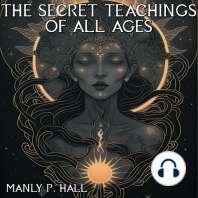Professional Documents
Culture Documents
Simulation - New Media
Uploaded by
Salmient FarisCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Simulation - New Media
Uploaded by
Salmient FarisCopyright:
Available Formats
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future
VIDEO GAMES DAN FILSAFAT PENDIDIKAN:
PENDEKATAN TEORI SIMULACRA
JEAN BAUDRILLAD
RR. Siti Murtiningsih
Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
st_murti@yahoo.com.sg ; rr_murtiningsih@yahoo.com.sg
Abtract
Education plays an important role in the information age and technology, especially since
education provides direction on the transition and development of science. Children are the most
important subject of education in the process of survival of civilization. In the era of digital age,
we are witnessing how video games penetrating the children daily life and it is believed to be an
impact on their cognitive and affective processes. The engagement power bringing by video
games has opened a new issue related to the internalization of values and identity formation in
children. The tradition of learning, working hard, and perseverance are threatened by the effects
of video game games. Children seem to be alienated from their real social relations. At an early
age, they are trapped by the false reality. The video games are believed to change the way
children view the world. The world presented by video games as "a sub-reality". As an expert
on video games, Jesper Juul, said that video games are "half real" (Jon Cogburn and Silcox
Marx, 2009:234). Video games seem to represent what is called by Jean Baudrillard as a
simulation of reality. Baudrillard, through his book "Simulations" (1985), said the hallmark of
modern society is a society of simulation, living with chaotic codes, signs, and models which
are set as the production and reproduction within a simulacra. Simulacra is the space where the
simulation mechanism takes place. Humans trapped in the space of reality which he considered
real, but superficial. Reality is no longer a mirror reality, but only the models (Baudrillard,
1987: 17). The results of this new technology reality tends to defeat the real reality, which
then become a prime reference to modern society. Through simulacra theory approach, the
author wants to analyse the effects of video games in the process of internalizing the value of
education especially in children, as well as to investigate the formation of identity and selfperception of children. It would be answered the question whether video games creating a real
identity or its only forged false consciousness in children. This research hopefully could provide
a critical contribution to the current problems of education in Indonesia.
Keywords: video games, education, Baudrillard, simulacra
A. Pendahuluan
Pendidikan adalah alat penting untuk menjawab adanya tuntutan perubahan
pengetahuan dan nilai pada masyarakat dewasa ini, utamanya dalam rangka
mengimbangi perubahan yang cepat. Pendidikan berkaitan pula dengan gambaran dan
formasi kehidupan yang dicita-citakan di masa depan. Pada pendidikan terjadi proses
internalisasi nilai dan pembentukan identitas. Pendidikan bagi generasi baru, dalam hal
789
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future
ini pendidikan bagi anak, sangat penting dalam proses transformasi pengetahuan dan
nilai.
Namun demikian, di era perkembangan teknologi informasi, pendidikan bagi
anak juga menghadapi tantangan penting. Jika permainan dianggap sebagai bagaian
pendidikan, maka perkembangan teknologi digital dewasa ini telah menghadirkan
berbagai jenis permainan virtual, yang kini mulai menjadi bagian dari kehidupan anakanak. Mereka yang lahir pada awal abad 21 ini sangat mungkin mengenal permainan
komputer khususnya video games, melebihi apa yang dialami oleh generasi sebelumnya.
Pada tahun 1970-an, kemunculan permainan komputer dimulai dengan hadirnya
permainan elektronik Pong atau PacMan, yang menyajikan konsep matriks digital
sederhana. Namun, sejak ditemukannya teknologi pencitraan tiga dimensi dan efek
khusus pada gambar yang mampu menyalin realitas asli, permainan video games
menjadi permainan popular di kalangan jutaan anak-anak di dunia, tak terkecuali di
Indonesia.
Riset yang pernah dilakukan Siti Murtiningsih (2004) pada anak-anak usia
sekolah di Yogyakarta, menemukan anak-anak usia sekolah kini gemar bermain Play
Station dan I-Box, dua jenis permainan video games yang mampu menghadirkan dunia
permainan sebagai suatu dunia lain. Dunia yang dihadirkan oleh teknologi digital,
adalah dunia yang mampu mengolah cerita dengan kecanggihan gambar dan suara.
Anak-anak berhadapan dengan satu realitas virtual yang berbeda dengan realitas asli, di
mana konsep ruang dan waktu menjadi tak terbatas. Permainan video game online
melaui internet, misalnya, mampu menghubungkan para anak yang bermain di suatu
tempat ke tempat lain, lintas daerah, negara dan bangsa.
Dalam bukunya Homo Ludens (1990; 190-203), Johan Huizinga membahas
pentingnya elemen permainan dalam budaya dan masyarakat. Bagi Huizinga, permainan
mengambil tempat penting dalam ruang konseptual, atau yang disebutnya lingkaran
magis (the Magic Circle), bahwa berbagai macam aksi bermain itu membutuhkan
pemaknaan yang diatur khusus, dimana makna kegiatan itu mungkin tak bisa diterima di
luar konteks permainan.
Betapapun, tidaklah mudah menarik garis perbedaan tegas antara lingkaran
magis dari suatu permainan (game) virtual dan cara ungkap simbolik lainnya sebagai
perwujudan dunia sebagaimana seharusnya. Perbedaan yang jelas adalah bahwa suatu
permainan melekat dalam realitas dan ditafsirkan baik dari dalam maupun dari luar
ruang konseptualnya. Permainan bisa juga dilihat sebagai kegiatan yang meniru
kehidupan sebenarnya tapi dalam konteks yang lebih aman, misalnya permainan
perang-perangan.
Bermain bukan hanya kegiatan khas manusia. Hewan pun juga mengenal
kegiatan bermain. Dalam kasus keduanya, permainan digunakan sebagai pola
pembelajaran bertingkah laku dan untuk berkomunikasi. Bermain dan permainan,
permainan berdasarkan aturan, tampaknya tak bisa dipisahkan dari sikap kecerdasan
menghadapi hidup. Relasi paling mendasar dari manusia, seperti cinta, kekerabatan,
hirarki sosial seperti atasan atau bawahan secara akrab terhubungkan dengan ritual
permainan. Suatu perayaan seringkali dimeriahkan dengan bermain, dan kadangkala
juga menghadirkan permainan, bermain adalah salah satu ciri dari ritus perkawinan dan
berbagai perayaan agama.
790
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future
Permainan juga menjadi alat bagi transfer nilai dan pengetahuan. Pada titik ini,
permainan juga menjadi bagian dari pendidikan. Lewat permainan, anak diantarkan
untuk mengenal dunia. Maka jika suatu permainan dipahami sebagai sebuah
konseptualisasi tentang dunia, maka analisis tentang peran permainan dalam filsafat
pendidikan akan mempertimbangkan fungsi epistemologi dan ontologi dari suatu
permainan. Arti penting epistemologis dari permainan dapat dikaji dari hubungan
pembelajaran yang interaktif. Dalam hal ini, permainan komputer seperti video games
adalah alat sangat berpengaruh yang akan mengubah cara pandang anak-anak kita
tentang dunia, dan peran anak-anak kita sebagai agen di dalamnya.
Dunia yang dihadirkan dalam video games adalah sebuah sub-realitas Begitu
juga Jesper Juul (Agger Ben, 2003 ) berpendapat bahwa video games adalah separuh
nyata. Fenomena video games ini tampaknya bisa dikaji lebih kritis dengan pendekatan
melihat hakikat realitas yang dihadirkan oleh teknologi digital itu. Permainan video
games agaknya mewakili apa yang disebut oleh Jean Baudrillard sebagai simuasi atas
realitas.
Melalui bukunya Simulacra and Simulations (1985), Baudrillard mengatakan
ciri khas masyarakat Barat dewasa ini sebagai masyarakat simulasi. Inilah masyarakat
yang hidup dengan carut marut kode, tanda, dan model yang diatur sebagai produksi
dan reproduksi dalam sebuah simulacra. Simulacra adalah ruang dimana mekanisme
simulasi berlangsung. Dalam konteks perkembangan teknologi virtual, mengutip
Baudrillard, manusia dijebak dalam ruang realitas yang dianggapnya nyata, padahal
sesungguhnya semu dan penuh rekayasa. Dalam dunia simulasi, bukan realitas yang
menjadi cermin kenyataan, melainkan model-model (Baudrillard, 1987; 17). Teknologi,
kata Baudrillard, bukan lagi sekedar perpanjangan tubuh atau sistem syaraf manusia.
Misalnya, prosesor komputer, memory card, DVD, video games, atau internet, telah
mampu mereproduksi realitas, masa lalu dan nostalgia. Bahkan menciptakan realitas
baru dengan citra buatan dan menyulap fantasi, ilusi bahkan halusinasi menjadi
kenyataan, serta melipat realitas ke dalam sebuah flashdisk atau bank memori. Lebih
jauh, realitas yang dihasilkan teknologi baru ini telah mengalahkan realitas yang
sesungguhnya dan menjadi model acuan yang baru bagi masyarakat.
Dengan memahami hakikat permainan sebagai sebuah lingkaran magis,
kemudian menelisik evolusi permainan anak kontemporer semisal video games, maka
menarik untuk melihat video games ini menjadi alat transfer pengetahuan tentang
realitas dalam praktik pendidikan anak.
Melalui pendekatan teori simulacra Baudrillard ini, penulis hendak mengurai
beberapa persoalan pendidikan anak terkait dengan efek-efek negatif video games pada
proses internalisasi nilai pada anak. Diselidiki pula pengaruh video games pada
pembentukan identitas dan persepsi diri anak. Hendak dijawab pula apakah jika ditinjau
dari perspektif teori simulacra Baudrillard, permainan anak video games mengantar
pada pembentukan identitas nyata ataukah identitas semu dan kesadaran semu.
Refleksi berdasar filsafat Baudrillard atas pengaruh video games pada
internalisasi nilai dan pembentukan identitas anak ini diharapkan dapat memberi
sumbangan penting bagi kritik terhadap problem pendidikan di Indonesia dewasa ini.
Karena, bagaimanapun juga, proses transfer pengetahuan dan pengalaman lewat video
games ini akan memunculkan persoalan penting dalam filsafat pendidikan, yaitu tentang
masalah struktur dasar realitas yang diserap oleh anak, dan bagaimana mereka
791
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future
membangun dan memahami dunia permainan itu dalam video games. Berbeda dengan
permainan tradisional yang mengandalkan kekuatan naratif, maka permainan video
games bertumpu pada satu bangunan logika yang separuh nyata dimana konsep ruang
dan waktu, serta eksistensi subjek yang bermain, mampu melewati batas ruang
konseptual dengan berbagai kemungkinan logis yang tak terbatas.
B. Video Games, Jean Baudrillard, dan Problem Pendidikan Anak
Fenomena paling mencolok dari orde digital ini adalah berkembangnya
teknologi permainan video games yang menciptakan virtual worlds bagi anak-anak di
seluruh dunia. Huizinga, dalam bukunya Homo Ludens (1990) mengatakan
permainan bisa diibaratkan sebagai lingakaran magis, di dalamnya ada pergeseran
tentang ruang, dari real menuju ke ruang konseptual.
Dalam hal ini, video games, telah menghadirkan lingkaran magis itu melalui
konstruksi realitas yang berbeda. Dengan kemampuan teknologi menghadirkan citra
digital melalui kolaborasi perangkat keras dan lunak, anak masuk dalam augmented
reality, suatu kenyataan virtual yang ditopang oleh perangkat keras dan lunak itu.
Teknologi virtual telah membuat dunia tak berjarak, antara yang real dengan yang tidak
real.
Pakar psikologi perkembangan anak, Jean Piaget, mengatakan bermain adalah
keadaan tidak seimbang dimana asimilasi lebih dominan daripada akomodasi. Imitasi
juga mencerminkan keadaan tidak seimbang karena akomodasi mendominasi asimilasi.
Situasi yang tidak seimbang dengan sendirinya tidak menunjang proses belajar seorang
anak, atau secara intelektual tidak adaptif. Saat bermain, menurut Piaget, seorang anak
tidak sedang belajar sesuatu yang baru, namun mereka belajar mempraktekkan dan
mengkonsolidasi ketrampilan yang baru diperoleh.
Jadi, walaupun bermain bukan penentu utama untuk perkembangan kognisi anak
dalam suatu proses pendidikan, bermain memberi sumbangan penting. Contohnya, pada
episode bermain peran yang dilakukan seorang anak bersama kawan-kawannya, terjadi
beberapa transformasi simbolik seperti pura-pura menggunakan balok sebagai telur.
Dari permainan itu, seorang anak tidak belajar ketrampilan baru, namun dia belajar
mempraktekkan ketrampilan merepresentasikan apa saja yang telah dipelajari
sebelumnya, yang telah diperolehnya dalam konteks bukan bermain (Meyke, 2001:8).
Dari kacamata perspektif Kantian, fenomena permainan teknologi modern video
games ini bisa dipahami dari perspektif tentang fenomenologi realitas, bahwa realitas ini
selalu menampakkan diri sebagai das ding ansich, yang selalu terdiri dari dua distingsi
realitas yakni realitas noumenon dan realitas fenomenon (dua distingsi realitas). Jadi,
pengetahuan adalah hasil dari buah pikiran (knower) dan fenomena (data inderawi).
Fenomena berasal dari noemena (dunia real tertinggi dari benda dalam dirinya sendiri
yang tidak dapat diketahui). Hanya fenomena (data inderawi) saja yang dapat diketahui
sebagai pengetahuan ilmiah atau faktual, dan itu hanya karena pikiran (knower)
memiliki kemampuan yang memungkinkan pengalaman mengorganisasikan pengetahuan itu. Benda berkesesuaian dengan kategori-kategori yang ada dalam pikiran tetapi
tidak sebaliknya seperti yang ada dalam realisme Aristotelian misalnya. Namun
demikian, menurut Kant, konsep tanpa persepsi tiada artinya sebagaimana persepsi
tanpa konsep adalah buta (Milton, 2004;30).
792
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future
Video games telah menjadi fenomena tersendiri dalam proses komunikasi
massa dewasa ini bahkan ketergantungan manusia pada media massa sudah sedemikian
besar. Media komunikasi massa abad ini yang tengah digandrungi anak-anak adalah
permainan video games. Rob Shields dalam bukunya The Virtual (2003),
menyatakan;
the average children spend 2600 hours per years playing video games or watching
television. Thats same 325 eight-hour days. Children spend another 900 hours
with other media, including, newspaper, books, magazines, music, film, and the
internet, that about hours of media use more time than children spend on
anything else, including schooling or sleeping.
Di Indonesia berdasarkan survei AC Nielsen di tahun 2009 (Media Indonesia, 16
November 2009) bahwa 61% sampai 91% anak-anak Indonesia suka bermain video
games. Hasil ini lebih lanjut dijelaskan bahwa hampir 8 dari 10 anak-anak di kota-kota
besar bermain video games setiap hari daripada membaca dan bermain di lapangan.
Hal ini menunjukkan bermain video games adalah aktivitas utama anak-anak
Indonesia yang seakan tak bisa ditinggalkan, sama halnya dengan aktivitas anak-anak
kita menonton televisi. Realitas ini sebuah bukti bahwa permainan anak video games
ataupun kegiatan menonton televisi, mempunyai kekuatan menghipnotis berjuta anak
Indonesia, sehingga seolah-olah permainan video games dan juga menonton televisi
telah mengalienasi anak-anak, bahkan juga orang dewasa, dalam agenda
tersembunyinya.
Perkembangan permainan video games di Indonesia dua tahun terakhir ini
memang amat menarik, dalam hal perkembangannya. Di pasar kini tersedia beragam
permainan digital video Games, dari jenis Nintendo, I-Box, sampai Playstation dengan
beragam versi mutakhirnya. Permainan digital itu pelan-pelan telah menggantikan
permainan anak tradisional yang mulai tergerus oleh zaman.
Namun realitasnya, di sisi lain ada problem aksiologis dalam permainan anak
modern video games tersebut, yaitu ketegangan aksiologis antara tuntutan selera pasar
dan misi pendidikan. MediaWatch mencatat selama ini atas nama mekanisme pasar,
pilihan format isi permainan video games tidak pernah lepas dari pertimbangan
tuntunan khalayak menurut perspektif pembuat. Berbagai program permainan ini
dibuat hanya untuk melayani kelompok budaya mayoritas yang potensial menguntungkan, notabene kebanyakan mereka adalah anak-anak, sementara kelompok minoritas
tersisihkan dari dunia simbolik video games.
Jika kita cermati tampaknya pembuat produk permainan anak modern video
games ini mengklaim sebagai sebuah produk permainan yang seringkali berorientasi
bukan pada efek yang timbul dalam masyarakat tetapi produk komersial tersebut
apakah mampu terjual dan mempunyai nilai ekonomis atau tidak, sehingga tidak
memperhatikan apa manfaatnya bagi pendidikan anak-anak yang notabene adalah
pangsa pasar utamanya.
Fenomena ini menandakan adanya persoalan nilai filosofis pada permainan
anak video games itu. Permainan anak modern terutama video games, semakin hari
semakin memperlihatkan kecenderungan mencampuradukan antara nilai edukasi dengan
nilai ekonomis. Keuntungan ekonomis menjadi tujuan utama bagi produsen permainan
793
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future
video games ini untuk mengejarnya. Hal ini tentu saja disebabkan di antaranya oleh
tekanan pasar yang makin meningkat.
Menurut pandangan objektivisme aksiologis, penetapan nilai adalah sesuatu
yang dianggap objektif (Milton, 2004:56). Nilai, norma ideal, dan sebagainya
merupakan unsur atau berada pada realitas objektif. Penetapan suatu nilai memiliki
makna, yakni benar atau salah, meskipun penilaian itu tidak dapat diverifikasi, yaitu
tidak dapat dijelaskan melalui suatu istilah tertentu. Nilai berada dalam suatu objek
seperti halnya kenikmatan ketika bermain video games. Nilai terletak dalam realitas.
Pandangan objektivisme aksiologis inilah yang sering disebut juga dengan istilah
realisme aksiologis.
Atas dasar problem aksiologis tersebut di atas maka dapat dikatakan manfaat
video games dititikberatkan kepada aspek hiburan daripada aspek pedagogisnya. Ruang
konseptual permainan anak video games ini akhirnya menarik audiens hanya dengan
menyajikan model permainan anak yang hanya berfungsi sebagai permainan yang asyik
dilihat sebagai sebuah strategi bisnis yang sarat muatan ekonomis. Hal ini tentu akan
berdampak pada kejiwaan anak. Padahal anak adalah pemegang estafet utama
kehidupan generasi bangsa. Produsen permainan anak video games dalam hal ini tidak
lagi mempertimbangkan moral sebagai pengontrol langkah mereka sehingga begitu
mengabaikan kepentingan anak-anak generasi penerus bangsa. Hal itulah yang terjadi
dengan perkembangan permainan modern anak video games di Indonesia, beberapa
kaidah yang semestinya dijalankan malah diabaikan demi kepentingan meraup
keuntungan.
Situasi yang dibangun sebagai akibat perkembangan teknologi mainan video
games inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan orde virtual worlds, yang jauhjauh hari telah disinyalir kuat oleh filsuf Perancis, Jean Baudrillard, dengan konsepnya
tentang simulasi dan hiperrealitas. Inti pemikiran Baudrillard adalah teori tentang
hyper-reality dan simulation. Konsep ini sepenuhnya mengacu pada kondisi realitas
budaya yang virtual ataupun artifisial di dalam era komunikasi massa dan konsumsi
massa. Realitas-realitas itu mengungkung anak-anak kita dengan berbagai bentuk
simulasi (penggambaran dengan peniruan). Simulasi itulah yang mencitrakan sebuah
realitas yang pada hakikatnya tidak senyata realitas yang sesungguhnya. Realitas yang
tidak sesungguhnya tetapi dicitrakan sebagai realitas yang mendeterminasi kesadaran
anak-anak kita itulah yang disebut dengan realitas semu (hyper-reality). Realitas ini
tampil melalui media-media yang menjadi kiblat utama masyarakat massa. Melalui
media, realitas-realitas dikonstruksikan dan ditampilkan dengan simulators, dan pada
gilirannya menggugus menjadi gugusan-gugusan imaji yang menuntun manusia
modern pada kesadaran yang ditampilkan oleh simulator-simulator tersebut, inilah yang
disebut gugusan simulacra.
Baudrillard, bernama lengkap Jean Baudrillard, lahir pada 1929 dari pasangan
petani kecil dan miskin dikota kecil Reims, Perancis. Pendidikannya banyak
dipengaruhi oleh kondisi perang Aljazair tahun 1950-an, sehingga pemikiran kritis akan
kondisi-kondisi sosiologis muncul dari iklim ini. Sebelum selesai kuliah dia sudah
mengampu Bahasa Jerman di Lycee. Di bawah bimbingan Henri Lefebvre, Baudrillard
banyak menggeluti persoalan filsafat social, budaya maupun pendidikan populer, dan
dengan kecerdasan yang dimilikinya mulai September 1966 dia dipercaya oleh Lefebvre
untuk mengasisteninya di Universitas Nanterre Paris X. Di samping itu dia juga
794
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future
berkolega dengan Roland Barthes, seorang pionir semiotik, sehingga karya pertamanya
yang menguraikan analisis semiotik terhadap budaya, yakni The System of Object
(1968), banyak dipengaruhi oleh Barthes.
Dalam pemikiran sosiologinya, khususnya tentang budaya permainan teknologi
modern ini, banyak dipengaruhi oleh Marshall McLuhan. Ketika tahun 1968 terjadi
peristiwa demonstrasi besar oleh mahasiswa di universitasnya, Baudrillard bergabung
dengan jurnal kiri, Utopie, yang dijadikan mediasi untuk menuangkan ide-idenya
tentang kritik budaya dan kritik teknologi dari perspektif Struktural-Marxis dalam teoriteori tentang media dan pendidikan populer. Tahun 1970 Baudrillard menjadi Maitreassistant di Universitas Nanterre, dan tahun 1987 dia pensiun. Karier akademiknya juga
dititinya di EGS (European Graduate School) di Saas-Fee, Swiss, dan di sini pula dia
menjadi professor dalam filsafat budaya dan kritik media (Mark Poster (ed.), 1988).
Tokoh-tokoh yang mempengaruhi analisis kritisnya tentang media, pendidikan
popular, dan teknologi, selain yang telah disebutkan di atas, adalah Marcel Mauss dalam
objektivitas dan analisis sosio-linguistiknya, juga masuk dalam lini ini adalah
strukturasi Levi-Staruss dan sosiologi Durkheimian. Kemudian Bataille, Sartre,
Dostoyevsky, dan Nietzsche mengisi warna-warna situasionisme dan surealisme dalam
analisisnya, sedangkan Freud dalam psikoanalisis. Sekalipun demikian, pengaruh
terbesar adalah Marxisme. Oleh karena itu pemikirannyapun dibedakan dalam tiga fase:
pertama, aktualisasi paradigma, strategi, tujuan dan penekanan analisis daripada muatan
yakni era post-Marxisme (1968-1971); kedua, akurasi analisis sosio-linguistik dalam
pemikirannya (1972-1977); ketiga, kritisisasi budaya teknologis, pendidikan popular,
dan media, sehingga dalam fase ini dia dikenal dengan the prophet of the implosion of
meaning that attends the postmodern condition(Rex Butler, 1999).
C. Dunia Simulacra Sebagai Ruang Konseptual dalam Permainan Anak Video
Games
Albert Bandura melalui teori Social Learning yang populer pada dekade 1960-an
menyimpulkan maraknya perkembangan video games, seperti PlayStation, telah
membuat medium itu menjadi alternatif media belajar baru bagi masyarakat, terutama
anak-anak. Kenyataan ini kian menguat ketika kehadiran permainan ini kian menyebar
secara global melalui internet, yang memungkinkan games dilakukan secara interaktif,
dan menerabas batas-batas teritorial.
Di Amerika Serikat, rata-rata anak-anak menghabiskan waktu selama 4 jam
bermain video games, semisal PlayStation. Empat jam bukan waktu yang sedikit bila
dibandingkan dengan waktu yang harus dihabiskan anak untuk sekolah (6-8 jam), tidur
(4-6 jam) dan menjalankan fungsi sosial maupun individual lainnya (Shulman, 2001).
Data lembaga riset pemasaran MARS tahun 2004 menyimpulkan bahwa rata-rata waktu
dihabiskan anak-anak di dunia, tak terkecuali Indonesia untuk bermain games berkisar 4
jam sehari. Jumlah ini diperkirakan lebih banyak lagi, mengingat anak-anak pada
masyarakat modern meluangkan jauh lebih banyak waktu di depan televisi, PlayStation,
internet, atau online game dibanding dengan orangtuanya (Rob Shields, 2003).
Inilah tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia akibat dari perkembangan
kemajuan teknologi permainan anak-anak. Idealisme pendidikan yang menawarkan
nilai-nilai kultural dihadapkan pada saluran lain yang menawarkan ragam nilai lain,
yang sayangnya, menyimpang jauh dari idealisme keluhuran budi pekerti dan
795
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future
intelektual. Permainan video games dengan sendirinya menawarkan hidden curriculum
dengan agenda ekonomi politik ataupun penguasaan kesadaran dan tingkat konsumsi
tinggi. Sialnya, di tengah ruang yang bebas diisi oleh siapa saja dalam sistem yang
demokratis, video games justru muncul mendominasi ruang dan waktu anak-anak di
seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia.
Dalam konteks zaman sekarang, zaman yang terlalu hingar bingar dengan
membanjirnya kultur besar, mayor dan dominan, ke dalam komunitas yang berbasis
kultur kecil (minor), hadirnya sebuah pemikiran yang mampu menjelaskan fenomena
dunia hiperrealitas pada permainan anak video games tersebut secara jelas dan akademis
sangat diperlukan. Potret zaman yang nampak pada video games adalah realitas yang
dipresentasikan oleh permainan itu yang menjembatani aliran arus budaya mayor ke
budaya minor, sehingga pencitraan-pencitraan atas realitas juga mengikuti irama
presentasi permainan itu.
Dari perspektif teori simulacra Jean Baudrillard, fenomena video games ini
sepenuhnya mengacu pada kondisi realitas budaya yang virtual ataupun artifisial di
dalam era konsumsi massa sekarang ini. Realitas-realitas itu mengungkung anak-anak
kita dengan berbagai bentuk simulasi (penggambaran dengan peniruan). Simulasi
itulah yang mencitrakan realitas yang pada hakikatnya tidak senyata realitas
sesungguhnya. Realitas yang tidak sesungguhnya tetapi dicitrakan sebagai realitas
yang mendeterminasi kesadaran anak-anak kita itulah yang disebut dengan realitas
semu (hyper-reality). Realitas ini tampil melalui beragam media yang menjadi kiblat
utama masyarakat massa. Melalui media, realitas-realitas dikonstruksikan dan
ditampilkan dengan simulators, dan pada gilirannya menjadi gugusan-gugusan imaji
yang menuntun anak-anak kita pada kesadaran yang ditampilkan oleh aneka simulator
tersebut, inilah yang disebut gugusan simulacra. Simulator itulah yang kemudian
muncul dalam bentuknya yang paling nyata pada permainan anak modern video games
ini.
Baudrillard tampaknya mengikuti tradisi berfikir Claud Levi-Strauss dalam
membuat relasi antara pendidikan kritis, sosiologi dan semiotika, meskipun Baudrillard
jauh melampaui tradisi sosiologi itu sendiri. Baudrillard mengkonsepkan masyarakat
dengan menggunakan mass (massa) yang merupakan konseptualisasi masyarakat yang
telah terdeterminasi oleh faktor budaya yang berada dalam selubung gugusan
simulacra. Di sinilah tampak sekali bahwa Baudrillard mengadopsi kritik situasionisme
dari marxisme. Berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, yang diklaim
sebagai wujud nyata dari modernitas, telah memposisikan realitas-realitas menjadi
sebatas imaji yang dihasilkan oleh proses simulasi. Permainan anak video games, sekali
lagi, telah menciptakan makna pesan yang dipublikasikan sebagai sesuatu yang terputus
dari asal-usulnya, sehingga tidak salah kalau Baudrillard menyatakan bahwa konstruksi
budaya dewasa ini mengikuti pola-pola simulasi, yakni penciptaan model-model nyata
tanpa asal-usul dari realitas, inilah yang disebutnya hyper-reality. Jean Baudrillard,
dalam Simulacra and Simulations (1985;55), lebih lanjut menyatakan bahwa,
we must think of the media as if they were, in outer orbit, a sort of genetic code
which controls the mutation of the real into the hyper-real". Selanjutnya
Baudrillard (1994;142) juga menegaskan bahwa, The hyper-real represents a
much more advanced phase in the sense that even this contradiction between the
real and the imaginary is effaced.
796
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future
Dengan demikian, menurut Baudrillard, dunia yang dibangun oleh permainan
anak video games, tidak saja berhenti menjadi cerminan realitas, bahkan menjadi
realitas itu sendiri atau bahkan lebih nyata dari realitas dalam dunia video games
tersebut.
D. Penutup: Mempertanyakan Subjektivitas, Kenyataan, dan Identitas Anak
(Suatu Pemetaan Masa Depan dan Penjelasan Masa Kini ala Baudrillardian)
Penjelasan di atas menggambarkan fenomena video games memberikan
pemetaan berharga tentang kemungkinan perjalanan dari masa kini menuju masa depan,
dan menunjukkan perkembangan penting dalam teknologi yang akan menghasilkan
masa depan berbeda. Video games bagi Baudrillard menawarkan pandangan
meyakinkan dan realistis tentang kekuatan yang membentuk dunia anak-anak kita, suatu
dunia simulasi yang jika dikelola dengan baik maka sebenarnya kita dapat berinvestasi
menciptakan generasi bangsa yang berkualitas ke depannya, dengan cara diintegrasikan
di kurikulum pendidikan, baik melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan
keluarga.
Meskipun demikian, bagi Baudrillard, video games di sisi lainnya juga
menyisakan pertanyaan filosofis mendalam tentang hakikat kenyataan, subjektivitas,
dan manusia di dunia yang serba canggih oleh teknologi. Apa hakikatnya manusia,
ketika garis antara manusia dan teknologi dalam video games mengabur? Apakah
identitas manusia dapat diprogram? Bagaimana kenyataan terkikis sekarang dan apa
akibatnya? Secara jelas Baudrillard tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tapi
setidaknya, pandangan Baudrillard memaksa kita untuk memikirkannya.
Rangkaian persoalan pelik di atas telah mengancam dunia pendidikan anak-anak
kita menuju kerusakan sistemik. Mengurai benang merah yang terlanjur berkelindan tak
tentu ujung-pangkalnya, Baudrillard menekankan pentingnya pengharapan dan impian.
Dua hal ini jelas bukan sekadar ilusi dan tipu daya.
Mimpi dan harapan memberi kita energi mewujudkan dunia yang lebih baik.
Tak ada perubahan tanpa impian, begitu pula tak ada impian tanpa harapan. Tapi
harapan dan impian harus ditindak lanjuti dengan aktualisasi, sehingga kekhawatiran
akan efek ekstase dari dunia simulasi tadi tidak terjadi dan berlanjut.
DAFTAR PUSTAKA
Agger Ben, 2003, Teori Sosial Kritis, Kreasi Wacana, Yogyakarta
Baggott, Jim, 2005, Reality, Penguin Books Ltd., London
Bambang Sugiharto, I., 1996, Postmodernisme, Tantangan bagi Filsafat, Kanisius,
Yogyakarta
Baudillard, Jean, 1985, Simulacra and Simulation, Galilee & University of Michigan
Press
_____________, 1987, Forget Foucault & Forget Baudrillard, Pequin Books
797
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future
_____________, 1993, The Transparency of Evil: Essays on Extreme Phenomena,
London Press: Verso
_____________, 1994, The Illusion of the End, Stanford University Press: Palo Alto
_____________, 2004, Masyarakat Konsumsi (diterjemahkan oleh Wahyunto), Kreasi
Wacana, Yogyakarta
Best Steven, Kellner Douglas, 1991, Postmodern Theory: critical interrogations,
Macmillan Education Ltd., London
Harland, Richard, 2006, Superstrukturalisme, Jalasustra, Yogyakarta
Hollis, Martin.,1994, The Philosophy of Social Science, Cambridge University Press
Imam Aziz (ed.), 2001, Galaksi Simularcra, LKiS, Yogyakarta
Johan Huizinga, 1990, Homo Ludens, LP3ES, Jakarta
Jon Cogburn, 2009, Philosophy Through Video Games, Routledge, New York
Kellner, Douglas, 1995, Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between
the Modern and the Postmodern, Routledge, London & New York
Kneller, George F., 1984, Movements of Thought in Modern Education, John Wiley &
Sons, Inc., USA
Lechte, John, 2001, 50 Filsuf Kontemporer, Kanisius, Yogyakarta
Mansour Fakih dkk., 2001, Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis, Read
Book, Yogyakarta
Meyke Tedjasaputra, 2005, Bermain, Mainan, dan Permainan, Grasindo, Jakarta
Milton D.Hunnex, 2004, Peta Filsafat; Pendekatan Kronologis dan Tematis, Teraju,
Jakarta
Novak, Joseph D., 1977, A Theory of Education, Cornell University Press, Ithaca
London
Omi Intan Naomi, 1999, Menggugat Pendidikan, Fundamentalis, Konservatif, Liberal,
Anarkis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Palmer, Richard E., 2005, Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta
Poster, Mark (ed.), 1988, Jean Baudillard, Selected Writtings, Stanford University
Press, Stanford
Rex Butler, 1999, Jean Baudrillard, The Defence of the Real, Sage Publication Ltd.,
London
Rob Shields, 2003, The Virtual, Routledge, London & New York
Rorty, Amelie Oksenberg, 2000, Philosophers on Education, Routledge, London
Simon Egenfeldt Nielsen, 2008, Understanding Video Games, Routledge, London
Siti Murtiningsih, 2004, Pendidikan Alat Perlawanan, Resist Books, Yogyakarta
Shulman, C., To The Joystick Born, dalam Ottawa Citizen, 12 Februari 2001, p.B2-3
798
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future
Travinor, Grant, 2009, The Art of Video Games, Willey-Blackwell, United Kingdom
Trifonas, Peter Pericles (ed.), 2000, Revolutionary Pedagogies, Routledge, London
Umberto Eco, 1986, Travels in Hyper Reality, Essyas, Orlando, Florida
William F.Oneil, 2002, Ideologi-Ideologi Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
799
You might also like
- Gamification: Another Perspective of PedagogyDocument6 pagesGamification: Another Perspective of PedagogyIjahss JournalNo ratings yet
- Sumienie Graczy Podejmowanie DecyzjDocument18 pagesSumienie Graczy Podejmowanie DecyzjsethNo ratings yet
- Cloud Lab and A DIY Robotics Kit That People Can Use To Play and Experiment With and LearnDocument7 pagesCloud Lab and A DIY Robotics Kit That People Can Use To Play and Experiment With and LearnJomari RamirezNo ratings yet
- Video Games and The Future of Learning: December 2004Document21 pagesVideo Games and The Future of Learning: December 2004Monolith.456No ratings yet
- Empathy, Perspective and ComplicityDocument27 pagesEmpathy, Perspective and ComplicityDavid Gómez-ValenciaNo ratings yet
- Gamification: Applying The Playful Through Digital GamesDocument7 pagesGamification: Applying The Playful Through Digital GamesIJAR JOURNALNo ratings yet
- Gamification As Transformative Assessment inDocument15 pagesGamification As Transformative Assessment instrife47No ratings yet
- Digital Educational Games - Inclusive Design Principles For Children With ADHDDocument371 pagesDigital Educational Games - Inclusive Design Principles For Children With ADHDAmandaNo ratings yet
- Fleer-2018-British Journal of Educational TechnologyDocument16 pagesFleer-2018-British Journal of Educational Technology赵青No ratings yet
- Alternate Reality Game in Museum: A Process To Construct Experiences and Narratives in Hybrid ContextDocument9 pagesAlternate Reality Game in Museum: A Process To Construct Experiences and Narratives in Hybrid ContextPaula CaroleiNo ratings yet
- Video Games As Tools For EducationDocument5 pagesVideo Games As Tools For EducationSEC BUAPNo ratings yet
- Games As Tool For EducationDocument14 pagesGames As Tool For EducationCRX Games InteractiveNo ratings yet
- Relevance of Videogames in The Learning and Development of Young ChildrenDocument18 pagesRelevance of Videogames in The Learning and Development of Young ChildrenAdam ChabchoubNo ratings yet
- VR Storytelling in EducationDocument8 pagesVR Storytelling in Educationapi-394843896No ratings yet
- Videogames: Opportunities For Learning: María-Esther Del-MoralDocument1 pageVideogames: Opportunities For Learning: María-Esther Del-MoralClaudiu KlauNo ratings yet
- Exploring The Potential Use of Game Walkthrough in Education: Comparison of Various Forms of Serious GamesDocument14 pagesExploring The Potential Use of Game Walkthrough in Education: Comparison of Various Forms of Serious GamesijiteNo ratings yet
- Designing Digital Educational Games Based On Literary Texts: The Educational AspectDocument12 pagesDesigning Digital Educational Games Based On Literary Texts: The Educational AspectArisNo ratings yet
- 8 1 Article Worlding Through PlayDocument27 pages8 1 Article Worlding Through Playapi-300545887No ratings yet
- Proof of ConceptDocument20 pagesProof of ConceptEllie RowNo ratings yet
- Group 1 CIP Literature ReviewDocument20 pagesGroup 1 CIP Literature ReviewTas IrhNo ratings yet
- Securing Belonging and Gamification 1Document14 pagesSecuring Belonging and Gamification 1api-310200658No ratings yet
- Paper 35 Ahmed Gamal Ahemd FinalDocument13 pagesPaper 35 Ahmed Gamal Ahemd FinalZa LeNo ratings yet
- Gamification Essay: Cristian Ferney Castaño EscalanteDocument4 pagesGamification Essay: Cristian Ferney Castaño EscalanteChristian EscalanteNo ratings yet
- Research EssayDocument11 pagesResearch Essayapi-707468268No ratings yet
- Aspects of Game-Based Learning: Cite This PaperDocument11 pagesAspects of Game-Based Learning: Cite This PaperHilary CantoriaNo ratings yet
- Everett Watkins Power of PlayDocument24 pagesEverett Watkins Power of PlayToon HeesakkersNo ratings yet
- Serious Games ΒιβλιογραφίαDocument8 pagesSerious Games ΒιβλιογραφίαjxkjxkNo ratings yet
- Edtech504-Gamification and Game Based Learning in The 21st Century Constructivist ClassroomDocument14 pagesEdtech504-Gamification and Game Based Learning in The 21st Century Constructivist ClassroomNicolas HernandezNo ratings yet
- Toys Games and MediaDocument262 pagesToys Games and MediaChakma Nhiki100% (1)
- Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo EmailDocument11 pagesInstitut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo EmailWahyudi RamdhanNo ratings yet
- A2 4328 Play FinalDocument14 pagesA2 4328 Play Finalapi-223120833No ratings yet
- From The Constitution of Knowledge To Playing The Game Slice FractionsDocument16 pagesFrom The Constitution of Knowledge To Playing The Game Slice FractionsInternational Journal of Innovative Science and Research TechnologyNo ratings yet
- MaythegamesbeginDocument13 pagesMaythegamesbeginTajaNo ratings yet
- Tan2021 - Integration of Serious Games in Modern Learning and Its Effectiveness in The Twenty-First CenturyDocument32 pagesTan2021 - Integration of Serious Games in Modern Learning and Its Effectiveness in The Twenty-First CenturyKendrick Chua TanNo ratings yet
- Ger Shen FeldDocument6 pagesGer Shen FeldkadauberNo ratings yet
- Video Games and The Future of LearningDocument13 pagesVideo Games and The Future of LearningnandyshaNo ratings yet
- Gamification of Learning and Teaching in Schools - A Critical StanceDocument20 pagesGamification of Learning and Teaching in Schools - A Critical StancenabilahNo ratings yet
- PR1 G7 Chap12 DeweyDocument13 pagesPR1 G7 Chap12 DeweyCarlo AplacadorNo ratings yet
- ISTRAŽIVANJEDocument5 pagesISTRAŽIVANJEnisamja22No ratings yet
- Video Games As Cultural Artifacts: January 1970Document11 pagesVideo Games As Cultural Artifacts: January 1970W. Eduardo Castellanos H.No ratings yet
- Artículo 2Document4 pagesArtículo 2Angelica Maria Torregroza EspinosaNo ratings yet
- The Study On The Effect of Educational Games For The Development of Students' Logic-Mathematics of Multiple IntelligenceDocument4 pagesThe Study On The Effect of Educational Games For The Development of Students' Logic-Mathematics of Multiple IntelligenceDinoNo ratings yet
- Modsix Reflection WicklineDocument5 pagesModsix Reflection Wicklineapi-203403435No ratings yet
- A Fresh Look at Play-Objects - Bernard SchwartzDocument5 pagesA Fresh Look at Play-Objects - Bernard SchwartzMartina EspositoNo ratings yet
- Programme of StudyDocument2 pagesProgramme of StudyIgnotas KuprysNo ratings yet
- Essay 2 Draft 2Document7 pagesEssay 2 Draft 2api-608916227No ratings yet
- Gamification As Transformative Assessment in Higher EducationDocument16 pagesGamification As Transformative Assessment in Higher Educationserul1930No ratings yet
- Gamifikacio DolgozatDocument10 pagesGamifikacio DolgozatAnastase KatalinNo ratings yet
- Article - Play, Imagination and CreativityDocument6 pagesArticle - Play, Imagination and CreativityDespina KalaitzidouNo ratings yet
- Elindra,+2 +agasi+ (9-13)Document5 pagesElindra,+2 +agasi+ (9-13)Muthmainnah MitaNo ratings yet
- 10.4324 9781315537658-1 ChapterpdfDocument18 pages10.4324 9781315537658-1 ChapterpdfIrina TNo ratings yet
- Digital Communities and Videogames As Educational Tools in Participatory CultureDocument19 pagesDigital Communities and Videogames As Educational Tools in Participatory CultureBetina BellNo ratings yet
- Video Games, Learning, and The Shifting Educational LandscapeDocument15 pagesVideo Games, Learning, and The Shifting Educational LandscapeMarcelo SabbatiniNo ratings yet
- 2 PBDocument10 pages2 PBoneonetwothree260No ratings yet
- Game-Based Learning in Museums-Cultural Heritage ADocument13 pagesGame-Based Learning in Museums-Cultural Heritage AELDREI VICEDONo ratings yet
- Pred420 Si̇mge Çi̇çekDocument7 pagesPred420 Si̇mge Çi̇çekSimge CicekNo ratings yet
- Dissertation Katya Dolgobrodova PDFDocument20 pagesDissertation Katya Dolgobrodova PDFLimutan JullianeNo ratings yet
- Jurnal KULTIVASI DALAM BERMAIN GAME (Studi Kasus Pembentukan Realitas Subyektif Dalam Pola HidupDocument19 pagesJurnal KULTIVASI DALAM BERMAIN GAME (Studi Kasus Pembentukan Realitas Subyektif Dalam Pola HidupRegita ArumNo ratings yet
- Refleksi Cikgu DinDocument28 pagesRefleksi Cikgu DinMastura SabryNo ratings yet
- Objectives: Assignment DescriptionDocument3 pagesObjectives: Assignment DescriptionEng Samar MostafaNo ratings yet
- State of Barangay Governance ReportDocument100 pagesState of Barangay Governance ReportBrgylusongNo ratings yet
- Marketing Research Quiz 005: CheckDocument4 pagesMarketing Research Quiz 005: CheckFayesheli DelizoNo ratings yet
- FlySense 250 Spec Sheet - NOV2018Document2 pagesFlySense 250 Spec Sheet - NOV2018Rich OlsonNo ratings yet
- Prof. Ranjan MohapatraDocument3 pagesProf. Ranjan MohapatraengineeringwatchNo ratings yet
- Personality and CultureDocument31 pagesPersonality and CultureDavid Green100% (1)
- Flood EstimationDocument24 pagesFlood EstimationsitekNo ratings yet
- 6587-Article Text-23111-1-10-20220829Document11 pages6587-Article Text-23111-1-10-20220829crussel amuktiNo ratings yet
- Plantequipmentprocedure PDFDocument7 pagesPlantequipmentprocedure PDFKhan MohhammadNo ratings yet
- Kamigakari Expansion 1 - Requiem For The God SoulDocument177 pagesKamigakari Expansion 1 - Requiem For The God SoulLuciano Júnior100% (2)
- TKT Module 2 Selection and Use of Teaching Aids PDFDocument6 pagesTKT Module 2 Selection and Use of Teaching Aids PDFMona Gomez F.No ratings yet
- Unit 3 MKIS and Buyer BehaviorDocument38 pagesUnit 3 MKIS and Buyer BehaviorBHAKT Raj BhagatNo ratings yet
- Cs 501 Solved Final Term PapersDocument13 pagesCs 501 Solved Final Term PapersMahmmood Alam100% (1)
- The Narcissism of Small DifferencesDocument12 pagesThe Narcissism of Small DifferencesFrashër KrasniqiNo ratings yet
- Usntps FTM 103Document684 pagesUsntps FTM 103unstamper100% (1)
- Karanasan NG Isang Batang Ina Isang PananaliksikDocument5 pagesKaranasan NG Isang Batang Ina Isang PananaliksikFemarose TelanNo ratings yet
- Seduction Trends:: Beliefs - Attitudes - BehavioursDocument3 pagesSeduction Trends:: Beliefs - Attitudes - BehavioursisykaexNo ratings yet
- PEB Work Risk Assessment 17.4.17Document10 pagesPEB Work Risk Assessment 17.4.17Syed Ali HassanNo ratings yet
- OBIA Overview PDFDocument13 pagesOBIA Overview PDFDilip Kumar AluguNo ratings yet
- Vultures The I Revolution Ecology and ConservationDocument2 pagesVultures The I Revolution Ecology and ConservationpulpopulpoNo ratings yet
- JAC Chandigarh Information BrochureDocument115 pagesJAC Chandigarh Information BrochureMota ChashmaNo ratings yet
- Chefs ResumeDocument3 pagesChefs Resumeapi-452231230No ratings yet
- Is Dante Trudel's Doggcrapp Training System The Next Big Thing in Bodybuilding - SimplyShreddedDocument11 pagesIs Dante Trudel's Doggcrapp Training System The Next Big Thing in Bodybuilding - SimplyShreddedPeter Lenghart LackovicNo ratings yet
- Kajian Kriteria Perencanaan Dan Metode P 2643f4a7Document9 pagesKajian Kriteria Perencanaan Dan Metode P 2643f4a7singgihNo ratings yet
- Enhancing Security Using Digital Image ProcessingDocument9 pagesEnhancing Security Using Digital Image ProcessingArulmozhi PugazhenthiNo ratings yet
- Elliott PaperDocument28 pagesElliott PaperRonnachai SutthisungNo ratings yet
- Appendix A SolutionsDocument126 pagesAppendix A Solutionstechsengo100% (1)
- Our Lady Babalon and Her Cup of Fornicat PDFDocument11 pagesOur Lady Babalon and Her Cup of Fornicat PDFvladaalisterNo ratings yet
- BSC (Physics) SyllabusDocument16 pagesBSC (Physics) SyllabusAlok ThakkarNo ratings yet
- OpenFrame Base 7 Fix#3 TSAM Guide v2.1.4 enDocument80 pagesOpenFrame Base 7 Fix#3 TSAM Guide v2.1.4 enborisg3No ratings yet
- Summary of The 4-Hour Body: An Uncommon Guide to Rapid Fat-Loss, Incredible Sex, and Becoming Superhuman by Timothy FerrissFrom EverandSummary of The 4-Hour Body: An Uncommon Guide to Rapid Fat-Loss, Incredible Sex, and Becoming Superhuman by Timothy FerrissRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (81)
- How to Talk to Anyone: Learn the Secrets of Good Communication and the Little Tricks for Big Success in RelationshipFrom EverandHow to Talk to Anyone: Learn the Secrets of Good Communication and the Little Tricks for Big Success in RelationshipRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (1135)
- The Bridesmaid: The addictive psychological thriller that everyone is talking aboutFrom EverandThe Bridesmaid: The addictive psychological thriller that everyone is talking aboutRating: 4 out of 5 stars4/5 (131)
- Breaking the Habit of Being YourselfFrom EverandBreaking the Habit of Being YourselfRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (1457)
- Briefly Perfectly Human: Making an Authentic Life by Getting Real About the EndFrom EverandBriefly Perfectly Human: Making an Authentic Life by Getting Real About the EndNo ratings yet
- Gut: the new and revised Sunday Times bestsellerFrom EverandGut: the new and revised Sunday Times bestsellerRating: 4 out of 5 stars4/5 (392)
- The Obesity Code: Unlocking the Secrets of Weight LossFrom EverandThe Obesity Code: Unlocking the Secrets of Weight LossRating: 4 out of 5 stars4/5 (5)
- Peaceful Sleep Hypnosis: Meditate & RelaxFrom EverandPeaceful Sleep Hypnosis: Meditate & RelaxRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (142)
- Neville Goddard Master Course to Manifest Your Desires Into Reality Using The Law of Attraction: Learn the Secret to Overcoming Your Current Problems and Limitations, Attaining Your Goals, and Achieving Health, Wealth, Happiness and Success!From EverandNeville Goddard Master Course to Manifest Your Desires Into Reality Using The Law of Attraction: Learn the Secret to Overcoming Your Current Problems and Limitations, Attaining Your Goals, and Achieving Health, Wealth, Happiness and Success!Rating: 5 out of 5 stars5/5 (284)
- Raising Good Humans: A Mindful Guide to Breaking the Cycle of Reactive Parenting and Raising Kind, Confident KidsFrom EverandRaising Good Humans: A Mindful Guide to Breaking the Cycle of Reactive Parenting and Raising Kind, Confident KidsRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (169)
- Summary of The Art of Seduction by Robert GreeneFrom EverandSummary of The Art of Seduction by Robert GreeneRating: 4 out of 5 stars4/5 (46)
- How to Walk into a Room: The Art of Knowing When to Stay and When to Walk AwayFrom EverandHow to Walk into a Room: The Art of Knowing When to Stay and When to Walk AwayRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (5)
- Sleep Stories for Adults: Overcome Insomnia and Find a Peaceful AwakeningFrom EverandSleep Stories for Adults: Overcome Insomnia and Find a Peaceful AwakeningRating: 4 out of 5 stars4/5 (3)
- Forever Strong: A New, Science-Based Strategy for Aging WellFrom EverandForever Strong: A New, Science-Based Strategy for Aging WellNo ratings yet
- ADHD is Awesome: A Guide to (Mostly) Thriving with ADHDFrom EverandADHD is Awesome: A Guide to (Mostly) Thriving with ADHDRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- The Happiest Baby on the Block: The New Way to Calm Crying and Help Your Newborn Baby Sleep LongerFrom EverandThe Happiest Baby on the Block: The New Way to Calm Crying and Help Your Newborn Baby Sleep LongerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (58)
- Prisoners of Geography: Ten Maps That Explain Everything About the WorldFrom EverandPrisoners of Geography: Ten Maps That Explain Everything About the WorldRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (1145)
- Outlive: The Science and Art of Longevity by Peter Attia: Key Takeaways, Summary & AnalysisFrom EverandOutlive: The Science and Art of Longevity by Peter Attia: Key Takeaways, Summary & AnalysisRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- Summary: I'm Glad My Mom Died: by Jennette McCurdy: Key Takeaways, Summary & AnalysisFrom EverandSummary: I'm Glad My Mom Died: by Jennette McCurdy: Key Takeaways, Summary & AnalysisRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (2)
- How to ADHD: The Ultimate Guide and Strategies for Productivity and Well-BeingFrom EverandHow to ADHD: The Ultimate Guide and Strategies for Productivity and Well-BeingNo ratings yet
- The Waitress: The gripping, edge-of-your-seat psychological thriller from the bestselling author of The BridesmaidFrom EverandThe Waitress: The gripping, edge-of-your-seat psychological thriller from the bestselling author of The BridesmaidRating: 4 out of 5 stars4/5 (65)
- The Three Waves of Volunteers & The New EarthFrom EverandThe Three Waves of Volunteers & The New EarthRating: 5 out of 5 stars5/5 (179)
- Queen Bee: A brand new addictive psychological thriller from the author of The BridesmaidFrom EverandQueen Bee: A brand new addictive psychological thriller from the author of The BridesmaidRating: 4 out of 5 stars4/5 (132)
- The Guilty Wife: A gripping addictive psychological suspense thriller with a twist you won’t see comingFrom EverandThe Guilty Wife: A gripping addictive psychological suspense thriller with a twist you won’t see comingRating: 4 out of 5 stars4/5 (71)
- The Secret Teachings Of All Ages: AN ENCYCLOPEDIC OUTLINE OF MASONIC, HERMETIC, QABBALISTIC AND ROSICRUCIAN SYMBOLICAL PHILOSOPHYFrom EverandThe Secret Teachings Of All Ages: AN ENCYCLOPEDIC OUTLINE OF MASONIC, HERMETIC, QABBALISTIC AND ROSICRUCIAN SYMBOLICAL PHILOSOPHYRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (4)