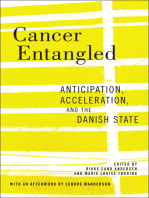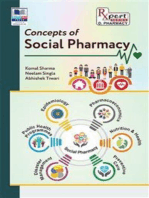Professional Documents
Culture Documents
Tugas Jurnal Reading - Malaria
Tugas Jurnal Reading - Malaria
Uploaded by
athilshipateOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Tugas Jurnal Reading - Malaria
Tugas Jurnal Reading - Malaria
Uploaded by
athilshipateCopyright:
Available Formats
JURNAL MALARIA
PUBLIC HEALTH SYSTEM READINESS TO TREAT MALARIA IN
ODISHA STATE OF INDIA
(Kesiapan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Mengendalikan Malaria di
Odisha Negara India)
Mohammad A Hussain, Lalit Dandona, David Schellenberg
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tema dalam penelitian ini adalah kesiapan sistem kesehatan masyarakat
dalam mengendalikan malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang
disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam
sel darah merah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan oleh gigitan
nyamuk Anopheles betina.
Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi
masalah kesehatan masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Penyakit ini
mempengaruhi tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil. Setiap
tahun lebih dari 500 juta penduduk dunia terinfeksi malaria dan lebih dari
1.000.000 orang meninggal dunia. Kasus terbanyak terdapat di Afrika dan
beberapa negara Asia, Amerika Latin, Timur Tengah dan beberapa bagian
negara Eropa. Untuk mengatasi masalah malaria, dalam pertemuan WHO 60
tanggal 18 Mei 2007 telah dihasilkan komitmen global tentang eliminasi
malaria bagi setiap negara. Petunjuk pelaksanaan eliminasi malaria tersebut
telah di rumuskan oleh WHO dalam Global Malaria Programme.
(Kementrian Kesehatan RI, 2009)
Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), secara
global estimasi kematian yang diakibatkan oleh penyakit malaria pada tahun
2010 adalah 655.000 kasus malaria di seluruh dunia. Selain itu, tercatat 86%
kematian terjadi pada anak di bawah umur 5 tahun. Penderita penyakit ini
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 1
tersebar di daerah di seluruh dunia terutama di daerah endemis seperti afrika
dan asia. Alokasi dana dari WHO dalam program penanggulangan Malaria
adalah 2 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan perlunya komitmen
setiap negara untuk menanggulangi kejadian penyakit malaria. Berdasarkan
luasnya dampak yang diakibatkan oleh penyakit ini maka Negara-negara di
dunia sepakat untuk menjalankan suatu program pemberantasan malaria yang
di sebut Global Malaria Action Plan (GMAP). Organisasi Kesehatan dunia
menetapkan pemberantasan penyakit Malaria hingga prevalensi minimal
sebagai salah satu target Millenium Development Goals (MDGs). (WHO,
2011)
Peningkatan kesakitan dan kematian akibat malaria di dunia telah dapat
diatasi antara tahun 2001-2010 dengan angka tertinggi pada tahun 2000.
Kejadian malaria dan angka kematian pada tahun 2000 tidak berubah selama
satu dekade (1990-2000), yang mana terdapat 274 juta lebih kasus dan 1,1 juta
kematian. Mayoritas kasus dapat ditangani (52%) dan nyawa dapat
diselamatkan (58%) berada di 10 negara yang memiliki beban malaria
tertinggi pada tahun 2000. Diperkirakan terdapat 216 juta kasus malaria dan
655.000 kematian pada tahun 2010. 80% kematian akibat malaria
diperkirakan terjadi hanya dalam 14 negara dan sekitar 80% dari kasus
diperkirakan terjadi di 17 negara. (Kementrian kesehatan RI, 2013)
Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berisiko terhadap
malaria. Pada tahun 2007 di Indonesia terdapat 396 Kabupaten endemis dari
495 Kabupaten yang ada, dengan perkiraan sekitar 45% penduduk berdomisili
di daerah yang berisiko tertular malaria. Jumlah kasus pada tahun 2006
sebanyak 2.000.000 dan pada tahun 2007 menurun menjadi 1.774.845.
Menurut perhitungan para ahli berdasarkan teori ekonomi kesehatan, dengan
jumlah kasus malaria sebesar tersebut diatas dapat menimbulkan kerugian
ekonomi yang sangat besar mencapai sekitar 3 triliun rupiah lebih. Kerugian
tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah. (Kementrian
kesehatan RI, 2009)
Indonesia mengalami kemajuan dalam pemberantasan malaria, seperti
diketahui mayoritas penduduk yang bertempat di daerah dengan API (Annual
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 2
Parasite Incident) <1 per 1000 (75% populasi). Sisanya masih berada di
daerah dengan API >1 per 1000. Pada tahun 2012 Angka API Malaria di
Indonesia sebesar 1.69 per 1.000 penduduk, angka ini menurun dibandingkan
dengan tahun 2011 yaitu sebesar 1,75 per 1.000 penduduk, dan terdapat
465.764 kasus positif malaria pada tahun 2010 dan menurun pada tahun 2012
menjadi 417.819 kasus. (Kementrian kesehatan RI, 2013)
Kementerian Kesehatan mempunyai kebijakan program dengan
mendiagnosis Malaria dimikroskopis atau dengan Uji Reaksi Cepat Rapid
Diagnostic Test (RDT), pengobatan menggunakan Artemisinin Combination
Therapy (ACT), pengendalian vector dengan cara peningkatan perlindungan
penduduk berisiko dan pencegahan penularan malaria khususnya melalui
kegiatan integrasi pembagian kelambu berinsektisida dengan program
Imunisasi lengkap pada bayi balita, ANC (skrining ibu hamil), pendistribusian
kelambu gratis secara massal di daerah endemis malaria tinggi dan sedang
seperti di Wilayah Timur Indonesia, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,
memperkuat desa siaga dengan pembentukan Pos Malaria Desa (Posmaldes),
dan kemitraan melalui Forum Gebrak Malaria. (Kementrian kesehatan RI,
2013).
Adapun latar belakang peneliti melakukan penelitian ini di Odisha oleh
karena Negara bagian Odisha di pantai timur India ini merupakan daerah
terpencil dan luas memiliki populasi 42 juta jiwa, sekitar 3% dari total
penduduk India dan sekitar 40% dari populasi hidup di bawah garis
kemiskinan dan membawa lebih dari 25% beban malaria nasional, termasuk
42% dari infeksi Plasmodium Palcifarum dan merupakan penyebab penting
morbiditas dan mortalitas di Negara tersebut dengan perkiraan lebih dari
50.000 kematian pertahun. Dari angka tersebut India merupakan penyumbang
dua pertiga dari parasitological kasus malaria di wilayah Asia tenggara.
India juga telah memberlakukan pengendalian malaria dengan diagnosis
dini dan pengobatan dengan terapi kombinasi artemisinin (ACT) menjadi
pengobatan lini pertama untuk malaria plasmodium palcifarum dan tes
diagnostic (RDT) kit cepat juga direkomendasikan untuk mendiagnosis dini
malaria.
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 3
B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menilai kesiapan sistem kesehatan untuk
menyebarkan RDT dan ACT untuk pengendalian malaria di seluruh Negara.
C. Metode Penelitian
1. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan
pendekatan cross-sectional yang dilakukan pada bulan Februari sampai Juli
2012.
Odhisa terdiri 30 kabupaten masing-masing dibagi dalam blok administrasi
dengan populasi rata-rata 120.000 sampai 15.000. Sistem kesehatan
masyarakat memiliki 3 lapis struktur disetiap kabupaten, dimana terdapat
rumah sakit yang menyediakan perawatan sekunder di setiap kabupaten.
Pada tingkat blok Pusat Kesehatan Masyarakat (CHC) menyediakan
pelayanan kesehatan preventif dan kuratif. Dibawah setiap CHC terdapat 3-
5 PHC (puskesmas) menyediakan pelayanan kesehatan primer dengan
populasi masing-masing sekitar 25.000 sampai 30.000. Dibawah setiap
PHC terdapat 4 sampai 6 subcenters, masing-masing dikelola oleh bidan-
perawat pembantu (ANM) yang melayani penduduk sekitar 3.000 sampai
8.000. Setiap subcenter mencakup 5 sampai 6 desa yang masing-masing
terdapat petugas kesehatan masyaarakat yang dikenal sebagai aktivis social
kesehatan (ASHA) yang diawasi oleh ANM yang memberikan pelayanan
untuk sekitar 1.000 orang.
2. Variable Penelitian
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:
Variabel independen : Kesiapan sistem kesehatan
Variabel dependen : Pengendalian malaria
3. Populasi dan Sampel
Populasi target dari penelitian ini adalah semua fasilitas kesehatan di
Odisha. Populasi terjangkau adalah semua fasilitas kesehatan dasar di
Odisha. Sampel penelitian diperoleh dari populasi terjangkau dengan
kriteria sebagai berikut:
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 4
Kriteria inklusi :
1) Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan diagnostik dan
pengobatan pada berbagai tingkat sitem kesehatan
2) Petugas kesehatan (ANM) dan ASHA yang masuk dalam kategori I, II
Metode penentuan sampel (sampling):
a. Fasilitas kesehatan ditentukan dengan menggunakan probability
sampling secara multistage stratified sampling berdasarkan waktu
dimaksudkan roll-uot dari ACT dan RDT. Berdasarkan revisi kebijakan
obat Negara tahun 2008 merekomendasikan ACT roll-out daerah dalam
kategori-kategori yaitu 13 kabupaten endemis sebagai (kategori I), 11
kabupaten cukup endemis (kategori II). Daerah tersebut yang dijadikan
sasaran oleh kebijakan obat Negara oleh karena tingkat resistensi CQ
plasmodium, beban penyakit falciparum dan transmisi. Kategori III
adalah malaria non endemic dimana ACT seharusnya dilaksanakan
sesuai revisi kebijakan tahun 2010 pada 6 kabupaten. Sebanyak lima
kabupaten dipilih dengan menggunakan stratified random sampling
dimana dua kabupaten terpilih dari kategori I, dua kabupaten dari
kategori II dan satu kabupaten dari kategori III.
b. Peserta study
Petugas kesehatan yang dipilih untuk wawancara adalah semua
ANMs pada blok yang terpilih. Sebanyak 50 ANMs dipilih dari
masing-masing blok setiap kabupaten. Jika jumlah ANMs dalam
dua blok yang dipilih di kabupaten itu kurang dari 50, maka blok
tambahan dipilih secara acak dan ANMs dipilih secara acak dari
blok baru sampai ukuran sampel tercapai.
ASHA dipilih secara acak untuk setiap subcenter sebanyak 1 orang
untuk wawancara.
Dalam rangka untuk mengukur pemahaman mendalam tentang
diagnosis malaria dan praktek pengobatan umum di daerah mereka,
sub-sampel diambil satu dari tujuh ANMs dan ASHAs secara
sistematis dipilih untuk wawancara secara rinci.
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 5
Metode sampling yang digunakan dapat dilihat dalam skema yang
terlampir pada jurnal.
4. Alat dan teknik pengumpulan data
Ada tiga strategi yang berbeda yang digunakan untuk pengumpulan data;
pertama, semua ANMs dan AHSAs dipilih diwawancarai dengan
menggunakan kuesioner semi-struktur. Kedua, penilaian fasilitas kesehatan
dilakukan untuk CHCs dan PHCs terpilih dengan kuesioner. Ketiga,
wawacara mendalam diadakan dengan pemangku kepentingan utama dalam
pengendalian malaria ditingkat kabupaten dan Negara dengan kuesioner
semi-terstruktur. Analisis rekam diberbagai tingkatan juga dilakukan untuk
memeriksa keaslian informasi.
5. Uji Statistik
Analisis data dilakukan dengan SPSS 20.0.0 (SPSS Inc 1989-2007).
Analisis deskriptif dilakukan pada fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan
(ANM dan ASHA), Uji Chi-square digunakan untuk menilai peredaan
dalam bagian, dan regresi logistic digunakan untuk menentukan hubungan
antara pengetahuan dan kesiapan untuk diagnosis dan pengobatan dengan
mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia, status pendidikan dan
jenis pelatihan, banyaknya pelatihan yang telah didapatkan oleh petugas
kesehatan, ketersediaan obat, dan pengalaman kerja. Perbedaan dianggap
signifikan bila nilai p < 0,05.
D. Hasil Penelitian
1. Dari 220 ANMs dilakukan wawancara sebanyak 51,4% telah dilatih dalam
manajemen kasus malaria, termasuk penggunaan ACT dan RDT. Sebagian
besar (80%) dari ANM dan (77%) dari ASHAs memiliki tingkat
pengetahuan yang diperlukan untuk dapat menggunakan RDT untuk
mendiagnosis malaria.
2. Proporsi ASHAs yang telah dilatih tentang manajemen kasus malaria
sebanyak 88,9% (209/235). Namun 71% dari ANMs dan 55% dari ASHAs
merujuk pasien falciparum positif ke fasilitas kesehatan untuk pengobatan
karena ketidaktersediaan obat di tingkat ANM dan ASHA.
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. TINJAUAN TENTANG SISTEM KESEHATAN
1. Pengertian
Sistem Kesehatan menurut WHO : Sistem Kesehatan adalah
semua kegiatan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan,
mengembalikan dan memelihara kesehatan. Cakupannya meliputi formal
health services yang mencakup pula promosi kesehatan, pelayanan
kesehatan oleh tenaga medik profesional, pengobatan tradisional, dan
pengobatan alternatif. Pendekatan Sistemik yang biasa digunakan ada
dua cara yaitu :
a. Identifikasi komponen pembentuk sistem dan
b. Menganalisis interconnection, saling keterkaitan antar komponen
dalam pola tertentu.
2. Tujuan dan Indikator
Tujuan dan indikator sistem kesehatan menurut Roberts dkk (2007), antara
lain :
a. Status Kesehatan
b. Perlindungan Resiko
c. Kepuasan Publik
d. Status Kesehatan
Secara tradisional ukuran status kesehatan: AKB, AKI, dan AKBA.
Akhir‐akhir ini berkaitan dengan beban penyakit (misalnya DALY)
mencakup morbiditas maupun mortalitas. Penyakit kronis yang semakin
meningkat menjadi beban baru bagi sistem pelayanan kesehatan.
Kelayakan juga penting apa yang bisa dilakukan (nilai tolok ukur)
kepuasan masyarakat dapat diukur melalui survei penduduk yang
dirancang baik. Secara tipikal dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, akses
dan pembayaran tunai bisa sesuai atau tidak sesuai dengan pelayanan yang
costeffective misalnya, pasien meminta resep yang tidak cocok) Juga
terkait dengan pertimbangan pemerataan Perlindungan terhadap Risiko
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 7
Setiap tahunnya, ada sebagian penduduk yang mengeluarkan biaya
pelayanan kesehatan yang tinggi Tanpa perlindungan, bisa jatuh miskin
atau mendapat pelayanan yang kurang Masalahnya menjadi lebih buruk
bagi mereka yang berpenghasilan rendah dapat dihindari melalui asuransi
atau sektor publik yang efektif dan hampir bebas biaya. Berbagai fungsi
dalam Sistem Kesehatan (WHO 2000)
3. Regulasi/stewardship
4. Pembiayaan
5. Pelaksanaan kegiatan kesehatan
6. Pengembangan SDM dan sumber daya lain
7. Kebijakan Kesehatan
Kebijakan (Policy): Sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang
bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu Kebijakan Publik
(Public Policy): kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau
Negara Kebijakan Kesehatan (Health Policy): Segala sesuatu untuk
mempengaruhi faktor–faktor penentu di sektor kesehatan agar dapat
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan bagi seorang dokter
kebijakan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan
kesehatan (Walt, 1994).
8. Pentingnya Kebijakan kesehatan :
Sektor kesehatan merupakan bagian penting perekonomian di berbagai
Negara Kesehatan mempunyai posisi yang lebih istimewa dibanding
dengan masalah sosial yang lainnya Kesehatan dapat dipengaruhi oleh
sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan
(misal: kemiskinan, polusi) Memberi arahan dalam pemilihan teknologi
kesehatan Segitiga Analisis Kebijakan terdiri dari : 1. Konteks 2. Aktor/
pelaku yang terdiri dari Individu dan Organisasi dan isi/ Konten Proses
Keuntungan Analisis Kebijakan Kaya penjelasan mengenai apa dan
bagaimana hasil (outcome) kebijakan akan dicapai Piranti untuk membuat
model kebijakan di masa depan dan mengimplementasikan dengan lebih
efektif. Contoh penggunaan Analisis Kebijakan Kasus: Kebijakan Tarif
RS untuk meningkatkan efisiensi di pelayanan kesehatan Konteks: kondisi
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 8
ekonomi, ideologi, dan budaya Konten/ Isi: Apa tujuan yang ingin
dicapai? Apakah ada pengecualian? Aktor/ Pelaku: Siapa yang mendukung
dan menolak kebijakan tarif RS? Proses : Pendekatan Top‐ Down? Dan
bagaimana kebijakan ini akan dikomunikasikan Faktor Kontekstual yang
Mempengaruhi Kebijakan Faktor situasional: Faktor yang tidak permanen
atau khusus yang dapat berdampak pada kebijakan (contoh: kekeringan)
Faktor struktural: bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah (misal:
sistem politik) Faktor Budaya: Faktor yang dapat berpengaruh seperti
hirarki, gender, stigma terhadap penyakit tertentu, Faktor Internasional
atau eksogen: faktor ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan antar
negara dan mempengaruhi kemandirian dan kerja sama internasional
dalam kesehatan. Proses Penyusunan Kebijakan Identifikasi Masalah dan
Isu Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Kebijakan
Menggunakan Segitiga Kebijakan Kesehatan. Segitiga kebijakan
kesehatan digunakan untuk memahami kebijakan tertentu dan menerapkan
untuk merencanakan kebijakan khusus dan dapat bersifat : Retrospektif
(meliputi evaluasi dan monitoring kebijakan) dan Prospektif (Memberi
pemikiran strategis, advokasi dan lobi kebijakan)
B. SEJARAH PEGENDALIAN MALARIA DI INDONESIA
1. Periode 1959 – 1968 (Periode Pembasmian Malaria)
Upaya pengendalian penyakit malaria dimulai sejak tahun 1959
dengan adanya KOPEM (Komando Pembasmian Malaria) di pusat dan di
daerah didirikan Dinas Pembasmian Malaria yang merupakan integrasi
institut Malaria, serta untuk pelatihan didirikan Pusat Latihan Malaria di
Ciloto dan 4 pusat latihan lapangan di luar Jawa.
Pada periode ini pengendalian malaria disebut sebagai periode
pembasmian, dimana fokus pembasmian dilaksanakan di pulau Jawa, Bali
dan Lampung. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah dengan
penyemprotan insektisida, pengobatan dengan Klorokuin dan profilaksis.
Baru pada tahun 1961 -1964 penyemprotan insektisida dilakukan juga di
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 9
luar wilayah Jawa dan Bali. Upaya ini cukup berhasil di daerah Jawa dan
Bali dengan adanya penurunan parasite rate.
Tahun 1966, upaya pemberantasan malaria menghadapi berbagai
kendala, yang disebabkan karena pembiayaan menurun baik dari
pemerintah maupun dari bantuan luar, meluasnya resistensi Anopheles
aconitus terhadap DDT dan Dieldrin di Jawa Tengah dan Jawa Timur,
adanya resistensi Plasmodium falciparum dan Plasmodium malariae
terhadap Pirimetamin dan Proguanil serta meningkatnya toleransi
Plasmodium falciparum terhadap Primakuin di Irian Jaya.
Selanjutnya tahun 1968, KOPEM diintegrasikan ke dalam Ditjen
P4M (Pencegahan Pemberantasan dan Pembasmian Penyakit Menular),
sehingga tidak lagi menggunakan istilah pembasmian melainkan
pemberantasan.
2. Periode 1969 – 2000 (Pemberantasan Malaria)
Dengan terintegrasinya upaya pengendalian malaria dengan sistim
pelayanan kesehatan, maka kegiatan malaria dilaksanakan oleh
Puskesmas, RS maupun sarana Pelayanan kesehatan lainnya. Seiring
dengan perubahan ekologi, tahun 1973 mulai dilaporkan adanya resistensi
Plasmodium falciparum di Yogyakarta, bahkan tahun 1975 di seluruh
provinsi di Indonesia, disertai dengan kasus resistensi Plasmodium
terhadap Sulfadoksin-Pirimethamin (SP) di beberapa tempat di Indonesia.
Tahun 1973 ditemukan penderita import dari Kalimantan Timur di
Yogyakarta. Tahun 1991 dilaporkan adanya kasus resistensi Plasmodium
vivax terhadap Klorokuin di Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara.
3. Periode 2000 – sekarang
Sejak dilaporkan adanya resistensi Plasmodium falciparum
terhadap Klorokuin (hampir di seluruh provinsi di Indonesia) dan
terhadap Sulfadoksin-Pirimethamin (SP) di beberapa tempat di Indonesia,
maka sejak tahun 2004 kebijakan pemerintah menggunakan obat pilihan
pengganti Klorokuin dan SP yaitu dengan kombinasi Artemisinin
(Artemisinin-based Combination Therapy/ACT).
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 10
Pada tahun 2000 dilahirkan Penggalakkan pemberantasan malaria
melalui gerakan masyarakat yang dikenal dengan Gerakan Berantas
Kembali Malaria atau ”Gebrak Malaria”. Gerakan ini merupakan embrio
pengendalian malaria yang berbasis kemitraan dengan berbagai sektor
dengan slogan “Ayo Berantas Malaria”. Selanjutnya tahun 2004 dibentuk
Pos Malaria Desa Sebagai bentuk Upaya Kesehatan berbasis masyarakat
(UKBM).
Mengingat malaria masih menjadi masalah di tingkatan global,
dalam pertemuan WHA 60 tanggal 18 Mei 2007 telah dihasilkan
komitmen global tentang eliminasi malaria bagi setiap negara. Indonesia
termasuk salah satu negara yang berkomitmen untuk mengeliminasi
malaria di Indonesia. Eliminasi Malaria sangat mungkin dilaksanakan
mengingat telah tersedia 3 kunci utama yaitu :
a. Ada obat ACT
b. Ada teknik diagnosa cepat dengan RDT (Rapid Diagnose Test)
c. Ada teknik pencegahan dengan menggunakan kelambu LLIN (Long
Lasting Insectized Net), yang didukung oleh komitmen yang tinggi
dari pemda setempat.
Malaria sebagai salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah
kesehatan masyarakat, berdampak kepada penurunan kualitas sumber
daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial,
ekonomi, bahkan berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Disadari
bahwa penyebaran malaria tidak mengenal batas wilayah administrasi,
oleh karena itu upaya pengendalian malaria memerlukan usaha bersama
dari kita sebagai warga masyarakat.
C. PENTAHAPAN DAN KEGIATAN ELIMINASI MALARIA
1. Pentahapan Eliminasi Malaria
Dalam program malaria Global (Global Malaria Programme) terdapat 4
tahapan menuju eliminasi malaria yaitu: pemberantasan, pra eliminasi,
eliminasi dan Pemeliharaan (pencegahan penularan kembali). Skema
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 11
pentahapan Eliminasi malaria adalah sebagai berikut : Situasi yang dicapai
pada masing-masing tahap Eliminasi Malaria adalah sebagai berikut :
a. Tahap Pemberantasan
Belum semua unit pelayanan kesehatan mampu memeriks kasus
secara laboratorium (Mikroskopis).
Cakupan pelayanan dan sumber daya terbatas.
Bila semua penderita demam di unit pelayanan kesehatan sudah
dilakukan pemeriksaan sediaan darah, maka Slide Positif Rate
(SPR) masih > 5%.
Adanya upaya pengendalian malaria secara intensif untuk mencapai
SPR < 5 %.
Adanya keterlibatan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, LSM,
organisasi Profesi, Lembaga Internasional dan lembaga donor
lainnya (pembentukan Tim Gebrak Malaria atau forum kerja sama
lain yang sudah ada di Provinsi dan Kabupaten/kota).
b. Tahap Pra Eliminasi
Semua unit pelayanan kesehatan sudah mampu memeriksa kasus
secara laboratorium (mikroskopis).
Semua penderita malaria klinis di unit pelayanan kesehatan sudah
dilakukan pemeriksaan sediaan darah dan SPR mencapai < 5%.
Adanya peningkatan kualitas dan cakupan upaya pengendalian
malaria (Surveilans, penemuan dan pengobatan, pemberantasan
vektor) untuk mencapai Annual Parasite Incidence (API) < 1/1000
penduduk berisiko.
Adanya peningkatan keterlibatan pemerintah, pemerintah daerah,
swasta, LSM, organisasi profesi, lembaga internasional, lembaga
donor dan lain-lain (Tim Gebrak Malaria atau forum kerja sama lain
yang sudah ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota).
Tersedianya peraturan perundangan di tingkat Provinsi/Kabupaten /
Kota yang mendukung kebijakan dan sumber daya untuk
pelaksanaan eliminasi malaria.
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 12
c. Tahap Eliminasi
API sudah mencapai < 1/1000 penduduk berisiko dalam satuan
wilayah minimal setara dengan Kabupaten / Kota.
Surveilans sudah berjalan dengan baik termasuk Active Case
Detection (ACD).
Re-orientasi program menuju Tahap Eliminasi kepada semua
petugas kesehatan pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam
eliminasi sudah dicapai dengan baik.
Lintas sektor terkait telah berperan secara penuh dan sinergis mulai
dari pemerintah, pemerintah daerah, LSM, organisasi profesi,
lembaga internasional, lembaga donor dan lain-lain dalam eliminasi
malaria yang tertuang didalam Peraturan Perundangan daerah.
Upaya penanggulangan malaria dilakukan secara intensif sehingga
kasus dengan penularan setempat (indigenous) tidak ditemukan
dalam periode waktu satu tahun terakhir.
d. Tahap Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali)
Mempertahankan Kasus indigenous tetap nol.
Kegiatan surveilans yang baik masih dipertahankan.
Re-orientasi program menuju Tahap Pemeliharaan kepada semua
petugas kesehatan, pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam
eliminasi sudah dicapai dengan baik.
Adanya konsistensi tanggung jawab pemerintah daerah dalam tahap
pemeliharaan secara berkesinambungan dalam kebijaksanaan,
penyediaan sumber daya baik sarana dan prasarana serta sumber
daya lainnya yang tertuang dalam Peraturan Daerah atau Peraturan
Perundangan yang diperlukan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Dalam Eliminasi Malaria
a. Tahap Pemberantasan
Tujuan utama pada Tahap Pemberantasan adalah mengurangi tingkat
penularan malaria disatu wilayah minimal kabupaten/kota, sehingga
pada akhir tahap tersebut tercapai SPR < 5 %. Sasaran intervensi
kegiatan dalam Tahap Pemberantasan adalah seluruh lokasi endemis
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 13
malaria (masih terjadi penularan) di wilayah yang akan dieliminasi.
Untuk mencapai tujuan Tahap Pemberantasan, perlu dilakukan pokok-
pokok kegiatan sebagai berikut :
1) Penemuan dan Tata Laksana Penderita
2) Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko
3) Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
4) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
5) Peningkatan sumber daya manusia
b. Tahap Pra Eliminasi
Tujuan utama pada tahap Pra Eliminasi adalah mengurangi jumlah
fokus aktif dan mengurangi penularan setempat di satu wilayah
minimal kabupaten/kota, sehingga pada akhir tahap tersebut tercapai
API < 1 per 1000 penduduk berisiko. Sasaran intervensi kegiatan dalam
Tahap Pra Eliminasi adalah fokus aktif (lokasi yang masih terjadi
penularan setempat) di wilayah yang akan dieliminasi. Pokok-pokok
kegiatan yang dilakukan adalah :
1) Penemuan dan tata laksana penderita
2) Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko
3) Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
4) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
5) Peningkatan sumber daya manusia
c. Tahap Eliminasi
Tujuan utama pada tahap Eliminasi adalah menghilangkan focus aktif
dan menghentikan penularan setempat di satu wilayah, minimal
kabupaten/kota, sehingga pada akhir tahap tersebut kasus penularan
setempat (indigenous) nol (tidak ditemukan lagi). Sasaran intervensi
kegiatan dalam Tahap Eliminasi adalah sisa fokus aktif dan individu
kasus positif dengan penularan setempat (kasus indigenous).
Pokok-pokok kegiatan yang dilakukan adalah :
1) Penemuan dan tata laksana penderita
2) Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko
3) Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 14
4) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
5) Peningkatan sumber daya manusia
Tahap Eliminasi sudah tercapai apabila :
1) Penderita dengan penularan setempat sudah dapat diturunkan
sampai nol dalam periode satu tahun terakhir.
2) Kegiatan surveilans di unit pelayanan kesehatan pemerintah dan
swasta, mampu mendeteksi dan menghentikan bila terjadi penularan
malaria.
d. Tahap Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali)
Tujuan utama pada Tahap Pemeliharaan adalah mencegah munculnya
kembali kasus dengan penularan setempat.Sasaran intervensi kegiatan
dalam Tahap Pemeliharaan adalah individu kasus positif, khususnya
kasus impor.
Pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan adalah :
1) Penemuan dan tata laksana penderita
2) Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko
3) Surveilance epidemilogi dan penanggulangan waba
4) Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
5) Peningkatan Sumber Daya Manusia
e. Penilaian Status Eliminasi
1) Sertifikat Eliminasi Malaria Dari Pemerintah
Wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang sudah tidak ditemukan
lagi penderita dengan penularan setempat (kasus indigenous)
selama 3 tahun berturut-turut dan dijamin adanya pelaksanaan
surveilans yang baik dapat mengusulkan/ mengajukan ke pusat,
untuk dinilai apakah sudah layak mendapatkan Sertifikat Eliminasi
Malaria dari Pemerintah (Departemen Kesehatan RI).
2) Sertifikat Eliminasi Malaria Dari WHO
Sertifikasi WHO diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia
apabila seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah
memenuhi persyaratan yang ditentukan seperti pada butir A, nomor
1-11. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Eliminasi Nasional
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 15
bersama Tim WHO. Berdasarkan laporan hasil penilaian Tim
tersebut, bila memang layak, DirJen WHO mengeluarkan Sertifikat
Status Bebas Malaria untuk Indonesia.
3) Tindak Lanjut Dari Status Eliminasi Malaria
Sertifikat Status Bebas Malaria dari WHO dikeluarkan berdasarkan
penilaian situasi terakhir, maka sedapat mungkin dipertahankan
untuk seterusnya.
WHO meminta laporan tahunan secara rutin tentang pemeliharaan
status bebas malaria tersebut, temasuk laporan tahunan tentang:
a) Konfirmasi penderita malaria yang ditemukan dalam periode
laporan, dirinci:
Per spesies parasit dan klasifikasi asal penularan penderita;
Penderita impor per spesies parasit dan asalnya.
b) Riwayat singkat semua kematian karena malaria yang
dilaporkan dan kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi.
c) Laporan singkat upaya pencegahan yang dilaksanakan untuk :
Menurunkan penderita impor;
Menurunkan reseptivitas dilokasi fokus yang masih terjadi
penularan.
Terjadinya KLB malaria oleh P. Falciparum dan adanya penularan
kembali malaria diwilayah yang telah dinyatakan bebas malaria,
harus segera dilaporkan kepada WHO. Indikasi terjadinya penularan
kembali malaria di suatu fokus adalah adanya 3 atau lebih kasus
introduced dan atau kasus indigenous di wilayah fokus tersebut,
dalam periode waktu 2 tahun berturut-turut untuk P. Falciparum
dan 3 tahun berturut-turut untuk P. vivax.
D. PERAN PEMERINTAH, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, SWASTA,
CIVIL SOCIETY, DAN LEMBAGA DONOR
Salah satu strategi dalam Eliminasi Malaria adalah meningkatkan komitmen
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan menggalang kemitraan dengan
berbagai sektor terkait termasuk sektor swasta, LSM, organisasi profesi dan
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 16
organisasi kemasyarakatan melalui forum Gebrak Malaria atau forum lain
yang ada di daerah sebagai wadah kemitraan.
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka peran pemerintah, provinsi,
kabupaten/kota, Swasta, LSM dan Lembaga Donor sebagai berikut.
1. Peran Pemerintah
2. Peran Pemerintah Daerah Provinsi
3. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peran Swasta, Civil Society Dan Lembaga Donor
E. MONITORING – EVALUASI DAN PELAPORAN
1) Monitoring dan evaluasi
2) Pelaporan
F. PEMBIAYAAN
Untuk mendukung terlaksananya upaya eliminasi malaria, maka diharapkan
semua instansi dan sektor terkait dapat merencanakan serta menyediakan
anggaran yang diajukan setiap periode/tahun sesuai dengan tugas/fungsi dan
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya untuk
mendapatkan hasil yang optimal Dinas Kesehatan berperan membantu
mengidentifikasi peran dari masing-masing instansi dan sektor terkait melalui
forum Gebrak Malaria.
Anggaran yang diperlukan untuk mendukung upaya eliminasi malaria dapat
diupayakan melalui sumber-sumber, seperti: APBN, APBD, bantuan dari
lembaga donor baik dalam negeri maupun luar negeri, swasta, serta sumber-
sumber lain yang sah sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku.
G. HASIL-HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA TERKAIT DENGAN
SISTEM KESEHATAN DAN PENGENDALIAN MALARIA
Berikut beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan
dengan pengendalian malaria:
1. Betty Roosihermiatie dan Rukmini “Analisis Implementasi Kebijakan
Eliminasi Malaria di Provinsi Bali”. Yaitu studi yang mengkaji
implementasi SK Menkes No. 293 tahun 2009 tentang kebijakan eliminasi
malaria di Provinsi Bali, dengan tujuan khusus mengkaji pemahaman,
penerapan, inovasi, pendanaan dan peran Pemda dalam mendukung
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 17
kebijakan eliminasi malaria di Provinsi Bali. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan eliminasi malaria oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem sudah sesuai dengan
strategi pusat. Kegiatan lintas sektor secara langsung maupun tidak
langsung telah bersinergi dengan kebijakan eliminasi malaria. Kegiatan
inovasi dalam rangka mendukung eliminasi malaria sudah dikembangkan
di daerah. Pendanaan terhadap kebijakan eliminasi malaria di Provinsi
Bali dan Kabupaten Karangasem masih mengandalkan dana dari APBD.
Peran pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan dalam bentuk
dukungan kebijakan/peraturan, penganggaran dan kegiatan sosialisasi.
Pengobatan harus mengacu pada strategi pengobatan terbaru dengan
artemisinin untuk mencegah resistensi.
2. Basundari Sri Utami, Lesi Estiana, Sekar Tuti “Penggunaan RDT oleh
Kader sebagai Alat Bantu dalam Penemuan Kasus Malaria di desa
Guntur Kecamatan Baner Kabupaten Purworejo” studi tentang peran
kader malaria dalam melakukan pemeriksaan RDT dengan baik. Dari
hasil didapatkan RDT dapat dipakai sebagai alat bantu kader dalam
melakukan diagnosa malaria namun perlu pertimbangan yang hati-hati
untuk mencegah pemborosan akibat adanya kesalahan teknis yang terjadi
3. Rita Kusriastuti, Asik Surya “Kebijakan Baru Pengobatan Malaria
sebagai Bagian dari Pengendalian Malaria Program di Indonesia”
Pengumpulan rutin data oleh pemerintah menunjukkan dari 1.322.451
dugaan kasus malaria; sekitar sembilan puluh dua persen telah diteliti
dengan menggunakan baik mikroskop atau RDT. Dari 256,592
dikonfirmasi malaria; 66% diterima ACT treatment. Inkoordinasi
mengenai ketersediaan obat adalah dilaporkan dari beberapa daerah.
Tantangan utama adalah komunikasi selalu tidak tepat antara masing-
masing rumah sakit fasilitas kesehatan yaitu, praktek swasta, atau fasilitas
lainnya dengan Dinkes pada pasokan obat. Pada tahun 2004, berdasarkan
sejumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia, penggunaan klorokuin
dihentikan dan terapi kombinasi artemisinin atau berbasis artemisinin
terapi kombinasi (ACT) dimulai. Untuk kasus berat untuk, diperkenalkan
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 18
penggunaan Artesunat intravena (IV), yakni untuk kasus-kasus yang
ditangani di Rumah Sakit Dan Artemeter intramuskular (IM) untuk
kasus-kasus yang ditangani di pusat layanan kesehatan primer. ACT,
Artesunat IV, Dan Artemeter IM, semuanya disediakan untuk seluruh
pelosok Negeri melalui sistem pengadaan barang dan jasa (sistem
pengadaan). Untuk pengobatan radikal, rekomendasi di Indonesia adalah
menambahkan primakuin (PQ) pada pengobatan act pada infeksi
Plasmodium vivax, Plasmodium ovale dan guna mencegah kekambuhan
dan pada infeksi Plasmodium falciparum untuk membunuh gametosit.
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 19
BAB III
PEMBAHASAN
Berdasarkan tujuan dan hasil dalam penelitian ini, menurut penyusun
penelitian ini sangat dapat diaplikasi dalam tatanan pelayanan
kesehatan/keperawatan di Indonesia. Dan bahkan penelitian tersebut sejalan
dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia melalui
kementrian kesehatan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sejarah
pengendalian malaria di Indonesia dimulai dari tahun 1959-1968 yaang disebut
sebagai periode pembasmian malaria, tahun 1969-2000 sebagai periode
pemberantasan malaria, dan periode tahun 2000 sampai sekarang, sejak
dilaporkan adanya resistensi plasmodium palcifarum terhadap kloroquin di
seluruh daerah Indonesia dan terhadap sulfadoksin-pirimethamin (SP) di beberapa
tempat di Indonesia, sehingga tahun 2004 dikeluarkan kebijakan pemerintah
menggunakan obat pil pengganti kloroquin dan SP dengan Artesinin combination
theraphy (ACT). Dan pada tahun 2009 Indonesia telah memulai mencanangkan
menghilangkan malaria di negara pada tahun 2030. Tujuan pencapaiannya secara
bertahap, pada tahun 2015 untuk Jawa, Bali, Kepulauan Riau, dan Aceh. Dan
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020, dan
bagian timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan
Papua Barat pada tahun 2030 sebagai wujud komitmen Negara dalam
pemberantasan malaria dalam mewujudkan komitmen global eliminasi malaria.
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan komitmen WHO dalam mengatasi
masalah malaria, yang dihasilkan dalam pertemuan WHO 60 tanggal 18 Mei 2007
yang menghasilkan komitmen global tentang eliminasi malaria bagi setiap negara.
Petunjuk pelaksanaan eliminasi malaria tersebut telah di rumuskan oleh WHO
dalam Global Malaria Programme. Meskipun pada hasil penelitian kurang efektif
karena berdasarkan hasil penelitian ketidak efektifan program pemberantasan di
lapangan karena terkendala oleh ketidaktersediaan ACT dan RDT di tingkat
pelayanan paling dasar yaitu ANMs dan ASHAs namun penelitian ini pula
mengungkapkan bahwa penanggulangan malaria telah sampai pada tingkat dasar.
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 20
Selain dari itu hasil penelitian ini pula sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan Betty Roosihermiatie dan Rukmini tentang “Analisis Implementasi
Kebijakan Eliminasi Malaria di Provinsi Bali”. Yaitu studi yang mengkaji
implementasi SK Menkes No. 293 tahun 2009 tentang kebijakan eliminasi malaria
di Provinsi Bali, dengan tujuan khusus mengkaji pemahaman, penerapan, inovasi,
pendanaan dan peran Pemda dalam mendukung kebijakan eliminasi malaria di
Provinsi Bali. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan
eliminasi malaria oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem
sudah sesuai dengan strategi pusat, pengobatan harus mengacu pada strategi
pengobatan terbaru dengan artemisinin (ACT) untuk mencegah resistensi. Dan
penelitian yang dilakukan Rita Kusriastuti dan Asik Surya tentang “Kebijakan
Baru Pengobatan Malaria sebagai Bagian dari Pengendalian Malaria Program
di Indonesia” yang dalam hasilnya dikatakan pada tahun 2004, berdasarkan
sejumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia, penggunaan klorokuin
dihentikan dan terapi kombinasi artemisinin atau berbasis artemisinin terapi
kombinasi (ACT) dimulai. Artesunat IV, Dan Artemeter IM, semuanya disediakan
untuk seluruh pelosok Negeri melalui sistem pengadaan barang dan jasa (sistem
pengadaan). Dari 256,592 dikonfirmasi malaria; 66% menggunakan ACT
treatment. Namun inkoordinasi mengenai ketersediaan obat adalah dilaporkan dari
beberapa daerah.
Dan juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Basundari
Sri Utami, Lesi Estiana, dan Sekar Tuti “Penggunaan RDT oleh Kader sebagai
Alat Bantu dalam Penemuan Kasus Malaria di desa Guntur Kecamatan Baner
Kabupaten Purworejo” studi tentang peran kader malaria dalam melakukan
pemeriksaan RDT dengan baik. Dari hasil didapatkan RDT dapat dipakai sebagai
alat bantu kader dalam melakukan diagnosa malaria namun perlu pertimbangan
yang hati-hati untuk mencegah pemborosan akibat adanya kesalahan teknis yang
terjadi. Dari semua paparan diatas maka terlihat bahwa penelitian ini juga
sebagian telah dilakukan di Indonesia seperti contoh kebijakan eliminasi malaria
di Bali, kebijakan pengobatan baru malaria, dan penggunaan RDT oleh kader,
sebagaimana saat ini masih tetap dilakukan.
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 21
BAB IV
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
1. Penanggulangan penyakit malaria merupakan program global, seluruh
negara-negara di dunia sepakat untuk menjalankan suatu program
pemberantasan malaria yang di sebut Global Malaria Action Plan
(GMAP). Organisasi Kesehatan dunia menetapkan pemberantasan
penyakit Malaria hingga prevalensi minimal sebagai salah satu target
Millenium Development Goals (MDGs)
2. Indonesia pada tahun 2009 telah memulai mencanangkan menghilangkan
malaria di negara pada tahun 2030. Tujuan pencapaiannya secara
bertahap, pada tahun 2015 untuk Jawa, Bali, Kepulauan Riau, dan Aceh.
Dan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat pada
tahun 2020, dan bagian timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara, Maluku,
Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat pada tahun 2030 sebagai wujud
komitmen Negara dalam pemberantasan malaria dalam mewujudkan
komitmen global eliminasi malaria.
3. Dari hasil penelitian didapatkan sebanyak 51,4% telah dilatih dalam
manajemen kasus malaria, termasuk penggunaan ACT dan RDT.
Sebagian besar (80%) dari ANM dan (77%) dari ASHAs memiliki tingkat
pengetahuan yang diperlukan untuk dapat menggunakan RDT untuk
mendiagnosis malaria dan ASHAs yang telah dilatih tentang manajemen
kasus malaria sebanyak 88,9% (209/235). Namun 71% dari ANMs dan
55% dari ASHAs merujuk pasien falciparum positif ke fasilitas kesehatan
untuk pengobatan karena ketidaktersediaan obat di tingkat ANM dan
ASHA.
4. Hasil penelitian ini sejalan dengan program pemberantasan malaria baik
ditingkat dunia maupun di Indonesia dan sejalan dengan hasil-hasil
penelitian yang dilakuakn di Indonesia sehingga hasil penelitian ini juga
disimpulkan dapat diterapkan di Indonesia
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 22
B. Saran
Hasil penelitian menunjukkan kesiapan petugas dalam penanggulangan atau
eliminasi malaria cukup namun kesiapan sistem lainnya masih kurang seperti
terkendala oleh ketidaktersediaan ACT dan RDT di tingkat pelayanan paling
dasar. Demikian juga dengan halnya hasil-hasil penelitian yang dilakuakn di
Indonesia, sehingga disarankan pada pengambil kebijakan dalam hal ini
pemerintah lewat kementrian kesehatan bersama dengan lembaga yang di
bawahnya dapat berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan eliminasi
malaria terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa utamanya ACT dan
RDT sampai di tingkat dasar yaitu puskesmas, pustu, poskesdes dan kader.
Selain itu pelatihan bagi petugas kesehatan dan kader malaria tetap perlu
dilaksanakan dan ditingkatkan sehingga semakin terampil dan mengurangi
kesalahan terutama di tingkat kader malaria.
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 23
DAFTAR PUSTAKA
Basundari Sri Utami, Lesi Estiana, Sekar Tuti (Agustus 2008), “Penggunaan RDT
oleh Kader sebagai Alat Bantu dalam Penemuan Kasus Malaria di desa
Guntur Kecamatan Baner Kabupaten Purworejo”, Balitbangkes. Jurnal
Ekologi Kesehatan vol 7 no. 2 hal 740-746.
Betty Roosihermiatie dan Rukmini. (April 2012). Analisis Implementasi
Kebijakan Eliminasi Malaria di Provinsi Bali. Balitbang Kemenkes RI -
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan- Vol.15, No.2. Hal 143-153
Herdiana, et.al. (2013). Progress towards malaria elimination in Sabang
Municipality, Aceh, Indonesia. Biomed Central-Malaria Journal, 12;42
Jendela Informasi Kesehatan. (2013). Artiktel. Sejarah pengendalian malaria di
Indonesia. Retrieved from info-kes.com website http://www.info-
kes.com/2013/07/sejarah-pengendlian-malaria-indonesia.html diakses
tanggal 21 Desember 2013
Kusuma, Kelana Darma. (2011). Metodologi penelitian keperawatan: Pedoman
melaksanakan dan menerapkan hasil penelitian. Jakarta : Trans Info
Media
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
293/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Eliminasi Malaria di Indonesia
Sugiyono. (2007). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif,
kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta
Sugiyono. (2012). Metode penelitian keperawatan. Jakarta : Trans Info Media
University of Huston Victoria. (2010). APA Quick Reference Guide, 6th edition.
Victoria : Academic Center staff
Mardhiah_Tugas Jurnal Reading 24
You might also like
- National Health Programmes in IndiaDocument33 pagesNational Health Programmes in IndiaNaveesh Vijay P K100% (3)
- Jurnal Malaria Kota Ternate 2012Document10 pagesJurnal Malaria Kota Ternate 2012mvcambeyNo ratings yet
- 98-Article Text-338-1-10-20200209Document12 pages98-Article Text-338-1-10-20200209akmal rosamaliNo ratings yet
- Malaria 2Document20 pagesMalaria 2Pretty EdnaNo ratings yet
- NACODocument10 pagesNACOkammanaiduNo ratings yet
- 97 491 2 PBDocument14 pages97 491 2 PBfathurNo ratings yet
- Malaria Elimination in Malaysia and The Rising Threat of Plasmodium KnowlesiDocument9 pagesMalaria Elimination in Malaysia and The Rising Threat of Plasmodium Knowlesiqusyairi_muhammadNo ratings yet
- Management - Guidelines - of - Malaria - in - Malaysia - (Final) v2 PDFDocument63 pagesManagement - Guidelines - of - Malaria - in - Malaysia - (Final) v2 PDFaiyuanNo ratings yet
- k18 - Malaria & Permasalahannya Di KabDocument32 pagesk18 - Malaria & Permasalahannya Di KabRizqi Husni MudzakkirNo ratings yet
- Evaluasi Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018Document12 pagesEvaluasi Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018yowan wandikboNo ratings yet
- Artikel Kti Marlia SusantidocxDocument4 pagesArtikel Kti Marlia SusantidocxsantiNo ratings yet
- Jurnal Kesehatan Masyarakat IKKDocument9 pagesJurnal Kesehatan Masyarakat IKKWerson wendamillyNo ratings yet
- Empirical Investigation Into The Patterns and Trends of Occurrences of Malaria Cases in Ekiti State, Nigeria: An Analysis of The Skewed ARMADocument24 pagesEmpirical Investigation Into The Patterns and Trends of Occurrences of Malaria Cases in Ekiti State, Nigeria: An Analysis of The Skewed ARMAIre AndrésNo ratings yet
- ChennaiCancerEpidemiologystudyIJCMPH PDFDocument8 pagesChennaiCancerEpidemiologystudyIJCMPH PDFpraveen kumarNo ratings yet
- Evaluation of The Challenges Faced by Health Workers Managing Patients With Severe Malaria in Kanyabwanga Health Centre III Mitooma District UgandaDocument16 pagesEvaluation of The Challenges Faced by Health Workers Managing Patients With Severe Malaria in Kanyabwanga Health Centre III Mitooma District UgandaKIU PUBLICATION AND EXTENSIONNo ratings yet
- Anti Malaria PPT SajidDocument18 pagesAnti Malaria PPT SajidAaban AdilaNo ratings yet
- HaniDocument12 pagesHaniAsiaNo ratings yet
- Can India Succeed in Eliminating Kala-Azar in Near Future?Document7 pagesCan India Succeed in Eliminating Kala-Azar in Near Future?Advanced Research PublicationsNo ratings yet
- Gambaran Pengetahuan, Perilaku Dan Pencegahan Malaria Oleh Masyarakat Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dan Maluku Barat DayaDocument8 pagesGambaran Pengetahuan, Perilaku Dan Pencegahan Malaria Oleh Masyarakat Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dan Maluku Barat DayaResvian RemboyNo ratings yet
- Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Malaria Pada Murid Sekolah Dasar Di Kabupaten Bolaang Mongondow UtaraDocument7 pagesHubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Malaria Pada Murid Sekolah Dasar Di Kabupaten Bolaang Mongondow UtaraSigit Harya HutamaNo ratings yet
- JURNALDocument5 pagesJURNALPuji RahmaniaNo ratings yet
- Theory of Planned Behaviour (TPB)Document18 pagesTheory of Planned Behaviour (TPB)Afiq Wahyu AjiNo ratings yet
- National AIDS Control Program: Dr. Kanupriya ChaturvediDocument42 pagesNational AIDS Control Program: Dr. Kanupriya ChaturvedifahimalikNo ratings yet
- Factors Affecting The Success of Multi Drug Resistance (MDR-TB) Tuberculosis Treatment in Residential SurakartaDocument13 pagesFactors Affecting The Success of Multi Drug Resistance (MDR-TB) Tuberculosis Treatment in Residential SurakartaDWI HERU CAHYONONo ratings yet
- Analisis Jurnal KeperawatanDocument2 pagesAnalisis Jurnal Keperawatanferdy zuliansyahNo ratings yet
- 130-Article Text-510-2-10-20180715Document13 pages130-Article Text-510-2-10-20180715AmyNo ratings yet
- Analisis Jurnal Keperawatan HivDocument2 pagesAnalisis Jurnal Keperawatan HivMuhammad Khairul ZedNo ratings yet
- Factors Associated With Utilization of Malaria Preventive and Control Measures Among Pregnant Women Attending Antenatal Clinic at Kisumu County Referral Hospital in Kisumu City Western KenyaDocument22 pagesFactors Associated With Utilization of Malaria Preventive and Control Measures Among Pregnant Women Attending Antenatal Clinic at Kisumu County Referral Hospital in Kisumu City Western KenyaInternational Journal of Innovative Science and Research TechnologyNo ratings yet
- 4945 8238 1 SMDocument12 pages4945 8238 1 SMGanang FaisalNo ratings yet
- Abstract. Malaria Is A Public Health Problem in Indonesia. One of The Problems Encountered in TheDocument7 pagesAbstract. Malaria Is A Public Health Problem in Indonesia. One of The Problems Encountered in TheKarunia RezehstaillNo ratings yet
- Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Dengan Upaya Pencegahan Penyakit Tuberkulosis Di Puskesmas Kamonji Tahun 2016Document20 pagesHubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Dengan Upaya Pencegahan Penyakit Tuberkulosis Di Puskesmas Kamonji Tahun 2016Lilis Endah SulistiyawatiNo ratings yet
- Chapter1Document6 pagesChapter1Erma JanuartiNo ratings yet
- Faktor Penderita Yang Berhubungan Dengan KesembuhanDocument9 pagesFaktor Penderita Yang Berhubungan Dengan KesembuhansindiNo ratings yet
- Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Mengenai Perilaku Pencegahan Malaria Di Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Tahun 2012Document10 pagesGambaran Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Mengenai Perilaku Pencegahan Malaria Di Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Tahun 2012Asmau SaadahNo ratings yet
- Mjhid 6 1 E2014070Document8 pagesMjhid 6 1 E2014070Khoiril AnwarNo ratings yet
- Primary Health Care Reform in 1CARE For 1 Malaysia: Family Health Development Division, Ministry of Health MalaysiaDocument7 pagesPrimary Health Care Reform in 1CARE For 1 Malaysia: Family Health Development Division, Ministry of Health MalaysiaSabrina AzizNo ratings yet
- Bab IbabDocument16 pagesBab IbabIriadin LukmanNo ratings yet
- Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kader Kesehatan Dalam Penanganan Tuberkulosis (TBC) Di Wilayah Kerja Puskesmas Gemolong Ii SragenDocument9 pagesPelatihan Peningkatan Kemampuan Kader Kesehatan Dalam Penanganan Tuberkulosis (TBC) Di Wilayah Kerja Puskesmas Gemolong Ii SragenArdaKrisnataNo ratings yet
- Hiv PregnancyDocument44 pagesHiv PregnancyElizabeth HidalgoNo ratings yet
- Malaria Elimination Program in Indonesia AbstractDocument8 pagesMalaria Elimination Program in Indonesia AbstractRio Aristo BirawaNo ratings yet
- National Health ProgrammesDocument8 pagesNational Health ProgrammesRohit SharmaNo ratings yet
- Efektivitas Metode DiskusiDocument9 pagesEfektivitas Metode DiskusimartinNo ratings yet
- Guidelines Malaria Di MalaysiaDocument61 pagesGuidelines Malaria Di MalaysianalmifaNo ratings yet
- Article TextDocument6 pagesArticle TextBruno FernandesNo ratings yet
- FINAL SET 2 Health-Administration-2okDocument16 pagesFINAL SET 2 Health-Administration-2okpritha_deshpandeNo ratings yet
- Keywords: Knowledge Attitude Action MalariaDocument6 pagesKeywords: Knowledge Attitude Action MalariaAbdul RamalangiNo ratings yet
- Inhibitors To Control of Malaria Among Resident of Eleme Local Government Area of Rivers StateDocument9 pagesInhibitors To Control of Malaria Among Resident of Eleme Local Government Area of Rivers Stateemmanuelnwa943No ratings yet
- Jurnal Malaria Deteksi DiniDocument6 pagesJurnal Malaria Deteksi DiniAhmad SyawqiNo ratings yet
- Environmental and Community Behavior Factor Associated With The Incidence of Filariasis in Sambas DistrictDocument9 pagesEnvironmental and Community Behavior Factor Associated With The Incidence of Filariasis in Sambas DistrictAsjatGapurNo ratings yet
- Bab IDocument7 pagesBab IleeNo ratings yet
- Maternal Mortality in Africa (Part I), Regional Trends (1990-2015)Document14 pagesMaternal Mortality in Africa (Part I), Regional Trends (1990-2015)franciscoNo ratings yet
- Jurnal Parasit DivDocument9 pagesJurnal Parasit DivGrosirButikNo ratings yet
- Chapter 1 of Research Study PDFDocument3 pagesChapter 1 of Research Study PDFAasif KohliNo ratings yet
- Kezia Yunis H 1751032 Health in AfricaDocument5 pagesKezia Yunis H 1751032 Health in AfricarajasagalaNo ratings yet
- Theory of Planned Behaviour (TPB) : Mycobacterium Tuberculosa. Tuberkulosis KhususnyaDocument19 pagesTheory of Planned Behaviour (TPB) : Mycobacterium Tuberculosa. Tuberkulosis KhususnyaSucii Syukrina FahmiNo ratings yet
- Maternal Mortality in Africa, Regional Trends (2000-2017)Document27 pagesMaternal Mortality in Africa, Regional Trends (2000-2017)franciscoNo ratings yet
- Penerapan Konsep Manajemen Lingkungan Untuk Pengendalian Vektor Malaria (Suatu Konsep Pemikiran)Document8 pagesPenerapan Konsep Manajemen Lingkungan Untuk Pengendalian Vektor Malaria (Suatu Konsep Pemikiran)muhamad abdul kodirNo ratings yet
- Cancer Entangled: Anticipation, Acceleration, and the Danish StateFrom EverandCancer Entangled: Anticipation, Acceleration, and the Danish StateRikke Sand AndersenNo ratings yet