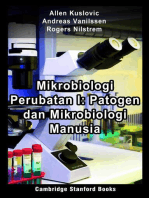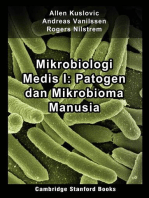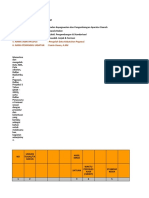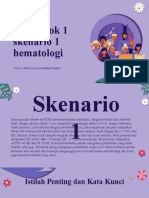Professional Documents
Culture Documents
Konsep Medis Psoriasis
Konsep Medis Psoriasis
Uploaded by
Sisilia Himam0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views11 pagesOriginal Title
KONSEP MEDIS PSORIASIS
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views11 pagesKonsep Medis Psoriasis
Konsep Medis Psoriasis
Uploaded by
Sisilia HimamCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 11
KONSEP MEDIS
PENYAKIT PSORIASIS
OLEH
Sartika Bachmid
NIM. 841422185
JURUSAN ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2022
KONSEP MEDIS PSORIASIS
1. Definisi
Menurut Brunner & Suddart tahun 2002 psoriasis merupakan penyakit
inflamasi non infeksius yang kronik pada kulit dimana produksi sel-sel
epidermis terjadi dengan kecepatan ±6 hingga 9 kali lebih besar dari pada
kecepatan yang normal (Tio, 2017).
Psoriasis adalah penyakit kulit kronis dengan ciri yang khas berupa
bercak-bercak merah eritema berbatas tegas dengan ditutupi oleh skuama
tebal berlapis-lapis berwarna putih mengkilat (Siregar, 2015).
2. Epidemiologi
Walaupun psoriasis terjadi secara universal, namun prevalensinya
pada tiap populasi bervariasi di berbagai belahan dunia. Studi epidemiologi
dari seluruh dunia memperkirakan prevalensi psoriasis berkisar antara 0,6
sampai 4,8% Prevalensi psoriasis bervariasi berdasarkan wilayah geografis
serta etnis. Di Amerika Serikat, psoriasis terjadi pada kurang lebih 2%
populasi dengan ditemukannya jumlah kasus baru sekitar 150,000 per tahun.
Pada sebuah studi, insidensi tertinggi ditemukan di pulau Faeroe yaitu sebesar
2,8%. Insidensi yang rendah ditemukan di Asia (0,4%) misalnya Jepang dan
pada ras Amerika-Afrika (1,3%). Sementara itu psoriasis tidak ditemukan
pada suku Aborigin Australia dan Indian yang berasal dari Amerika Selatan.
Terdapatnya variasi prevalensi psoriasis berdasarkan wilayah geografis dan
etnis menunjukkan adanya peranan lingkungan fisik ( psoriasis lebih sering
ditemukan pada daerah beriklim dingin), faktor genetik, dan pola tingkah laku
atau paparan lainnya terhadap perkembangan psoriasis. Pria dan wanita
memiliki kemungkinan terkena yang sama besar. Beberapa pengamatan
terakhir menunjukkan bahwa psoriasis sedikit lebih sering terjadi pada pria
dibanding wanita. Sementara pada sebuah studi yang meneliti pengaruh jenis
kelamin dan usia pada prevalensi psoriasis, ditemukan bahwa pada pasien
yang berusia lebih muda (<20 tahun) prevalensi psoriasis ditemukan lebih
tinggi pada wanita dibandingkan pria (Pratopo, 2017).
3. Etiologi
Menurut Tio (2017), secara pasti penyebab psoriasis belum diketahui
tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadi psoriasis yaitu:
a. Faktor genetik (Herediter) : Penyakit ini diturunkan melalui satu
gen yang dominan.
b. Defek pada epidermis : ditemukan dengan adanya peningkatan dari
ribonuklease dan penurunan dari deoxyribonuklease pada sel-sel
epidermis.
c. Defek enzim pada kulit : pada epidermis yang normal proses
keratinisasi berlangsung dalam 24 hari, sedangkan pada psoriasis
proses tersebut berlangsung sangat cepat yakni 3-4 hari.
d. Hormonal : terutama pada wanita dimana insiden psoriasis
meningkat pada masa pubertas dari pada masa klimakterium.
e. Tekanan mental terutama pada orang dewasa.
f. Infeksi : infeksi merupakan faktor pencetus dan memperberat
timbulnya psoriasis seperti infeksi akut tonsilitis. Pada anak-anak
sering ditemukan psoriasis yang timbul 2 minggu setelah tonsilitis.
g. Sinar matahari : di negara-negara yang sering terkena sinar
matahari jarang terkena psoriasis.
4. Patofisiologi
Mekanisme imun yang diperantarai oleh sel memainkan peranan
penting dalam perkembangan psoriasis. Aktivasi imun yang diperantarai sel T
inflamator pada kulit membutuhkan dua sinyal sel T yang dimediasi oleh
interaksi sel-sel antara permukaan protein dengan APC (antigen-presenting
cells), seperti sel dendritik atau makrofag. Sinyal pertama merupakan interaksi
antara reseptor sel T dengan antigen yang diperkenalkan oleh APC, sedangkan
sinyal kedua (disebut sebagai kostimulasi) diperantarai oleh berbagai interaksi
permukaan (Pratopo, 2017).
Ketika sel T diaktivasi, sel tersebut bermigrasi dari nodus limfa dan
aliran darah ke kulit dan mensekresikan berbagai sitokin. Sitokin psoriasis
adalah protein yang disekresikan oleh sel-sel imun yang berikatan dengan
reseptor yang sangat spesifik pada permukaan sel, mempengaruhi keratinosit
dan sel-sel lain untuk menghasilkan perubahan patologis karakteristik
psoriasis, terutama interferon-ℽ dan interleukin-2, yang menginduksi
perubahan patologis yang dikenal sebagai psoriasis. Keratinosit lokal dan
neutrofil menginduksi dihasilkannya sitokin lain, seperti TNF-α (tumor
necrosis factor-α) dan IL-8 (interleukin-8). Sebagai akibat dari produksi dan
aktivasi sel T patogenik, sel epidermal psoriasis berproliferasi pada laju 7x
lebih cepat daripada sel epidermal normal. Proliferasi sel epidermal rupanya
meningkat juga pada kulit normal pasien yang berisiko psoriasis. Lesi kulit
psoriasis melibatkan epidermis dan dermis. Terdapat penebalan epidermis,
disorganisasi stratum korneum akibat hiperproliferasi epidermis dan
peningkatan kecepatan mitosis, disertai peningkatan ekspresi intercellular
adhesion molecule 1(ICAM 1) serta abnormalitas diferensiasi sel epidermis
(Pratopo, 2017).
Aktivasi sel T terutama dipengaruhi oleh sel Langerhans. Sel T serta
keratinosit yang teraktivasi akan melepaskan sitokin dan kemokin, dan
menstimulasi inflamasi lebih lanjut. Selain itu, kedua komponen ini akan
memproduksi tumor necrosis factor α (TNF α), yang mempertahankan proses
inflamasi. Oleh karena itu, psoriasis bukan hanya disebabkan oleh
autoimunitas terkait sel limfosit T seperti teori terdahulu, tetapi melibatkan
proses yang lebih kompleks termasuk abnormalitas mikrovaskuler dan
keratinosit (Pratopo, 2017).
5. Manifestasi Klinis
Muncul bercak-bercak merah benjol pada kulit yang ditutupi oleh sisik
berwarna perak. Bercak bersisik tersebut terbentu karena penumpukan kulit
yang hidup dan mati akibat peningkatan kecepatan pertumbuhan serta
pergantian sel-sel kulit yang sangat besar. Jika bercak tersebut
digaruk/dikerok akan terlihat dasar lesi yang berwarna merah gelap dan titik-
titik perdarahan. Bercak-bercak ini bisa terasa gatal ataupun tidak (Tio, 2017).
Psoriasis dapat menimbulkan masalah lainnya seperti kosmetika yang
mengganggu hingga keadaan yang menimbulkan cacat dan ketidakmampuan
fisik. Tempat-tempat tertentu pada tubuh yang cenderung terkena kelainan ini
adalah kulit kepala, daerah sekitar siku serta lutut, punggung bagian bawah
dan genitalia. Psoriasis juga dapat ditemukan pada ekstremitas lengan dan
tungkai, daerah sekitar sakrum serta lipatan intergluteal. Distribusi simetris
bilateral merupakan ciri khas psoriasis. Psoriasis juga mengenai kuku pasien
yang menyebabkan terjadi pitting, perubahan warna kuku serta penggumpalan
dan pemisahan lempeng kuku. Jika psoriasis terjadi pada telapak kaki dan
tangan keadaan ini menimbulkan lesi pustuler (Tio, 2017).
6. Bentuk Klinis
a. Psoriasis Vulgaris
Bentuk ini paling lazim ditemukan sehingga disebut dengan tipe
vulgaris dimana karena tipe lesinya berbentuk plak-plak (Tio, 2017). Para
plak sering berkembang pada kulit kepala, punggung bawah, siku dan
lutut. Mereka juga dapat muncul pada lengan dada, dan kaki tetapi jarang
pada wajah. Dalam beberapa kasus, mereka berada di daerah terisolasi
atau terpisah dari tubuh, atau bentuk bersama. Psoriasis kulit kepala
memberikan ketidaknyamanan fisik seperti gatal tak tertahankan, dengan
lesi mengangkat dan membangun-up dari skala yang mengelupas seperti
ketombe, membuat kulit kepala meradang dan bengkak (Pratopo, 2017).
b. Psoriasis Gutata
Psoriasis Guttate (GUH-tate) adalah salah satu bentuk dari psoriasis
yang mulai timbul sejak waktu anak-anak atau remaja. Kata guttate
berasal dari bahasa Latin yang berarti “jatuh” (drop). Bentuk psoriasis ini
menyerupai bintik-bintik merah kecil di kulit. Bercak guttate biasanya
timbul pada badan dan kaki. Bintik-bintik ini biasanya tidak setebal atau
bersisik seperti bercak-bercak pada psoriasis plak (Pratopo, 2017).
c. Psoriasis Inversa (Psoriasis Fleksural)
Sesuai dengan namanya psoriasis ini berada ditempat predileksi pada
daerah fleksus (Tio, 2017). Inversa psoriasis ditemukan pada ketiak,
pangkal paha, dibawah payudara, dan di lipatan-lipatan kulit di sekitar
kemaluan dan panggul. Tipe psoriasis ini pertama kali tampak sebagai
bercak yang sangat merah. Bercak itu bisa tampak licin dan bersinar
(Pratopo, 2017).
d. Psoriasi Eksudativ
Biasanya kelainan psoriasis kering, tetapi pada psioriasis eksudativ
bentuk psoriasis basah seperti dermatitis akut (Tio, 2017).
e. Psoriasis Seroboik
Psoriasis seboroik merupakan kelainan kulit berupa perdangan
superfisial dengan papuloskuamosa yang kronik dengan tempat predileksi
di daerah-daerah seboroik yakni daerah yang kaya akan kelenjar sebasea,
seperti pada kulit kepala, alis, kelopak mata, naso labial, bibir, telinga,
dada, axilla, umbilikus, selangkangan, dan glutea. Pada dermatitis
seboroik kelainan kulit yang berupa eritem, edema, serta skuama yang
kering atau berminyak dan berwarna kuning kecoklatan dalam berbagai
ukuran disertai adanya krusta (Pratopo, 2017).
Dermatitis seboroik paling sering terjadi pada dua puncak umur yakni
pada kelompok anak dan dewasa. Pada kelompok anak sering didapatkan
pada 3 bulan pertama kehidupan dan kelompok dewasa dalam decade
keempat hingga ketujuh. Dermatitis seboroik pada anak khusunya pada
kelompok bayi, dapat sembuh spontan dalam usia 6 hingga 12 bulan,
sementara dermatitis seboroik pada orang dewasa dapat bersifat kronik
dan membutuhkan perawatan seumur hidup (Pratopo, 2017).
f. Psoriasis Pustula
Kasus Psoriasis Pustular (PUHS-choo-ler) terutama banyak ditemui
pada orang dewasa. Karakteristik dari penderita PUHS-choo-ler ini adalah
timbulnya Pustules putih (blisters of noninfectious pus) yang dikelilingi
oleh kulit merah. Pus ini meliputi kumpulan dari sel darah putih yang
bukan merupakan suatu infeksi dan juga tidak menular. Bentuk psioriasis
yang pada umumnya tidak biasa ini mempengaruhi lebih sedikit dari 5 %
dari seluruh penderita psoriasis. Psoriasis ini, bisa terkumpul dalam daerah
tertentu pada tubuh, contohnya, pada tangan dan kaki. Psoriasis Pustular
juga dapat ditemukan menutupi hampir seluruh tubuh, dengan
kecenderungan membentuk suatu siklus - reddening yang diikuti oleh
pembentukan pustules dan scaling (Pratopo, 2017).
g. Psoriasis Eritroderma
Tipe psoriasis ini sangat berbahaya, seluruh kulit penderita menjadi
merah matang dan bersisik, fungsi perlindungan kulit hilang, sehingga
penderita mudah terkena infeksi. Hanya 1-2% dari orang yang menderita
psoriasis memiliki psoriasis eritroderma. Jenis psoriasis dapat dihitung
sebagai yang terburuk dari semua. Hasilnya kemerahan luas, gatal parah,
nyeri dan ketidaknyamanan, dehidrasi dan demam. Ini biasanya dipicu
oleh kortikosteroid, kulit terbakar parah atau sensitivitas terhadap cahaya
selama pengobatan fototerapi, atau jenis lain dari psoriasis yang tidak
terkontrol (Pratopo, 2017).
7. Diagnosis
Diagnosis psoriasis biasanya ditegakkan berdasarkan anamnesis dan
gambaran klinis lesi kulit. Pada kasus-kasus tertentu, dibutuhkan pemeriksaan
penunjang seperti pemeriksaan laboratorium darah dan biopsi histopatologi.
Pemeriksaan penunjang yang paling umum dilakukan untuk mengkonfirmasi
suatu psoriasis ialah biopsi kulit dengan menggunakan pewarnaan
hematoksilin-eosin. Pada umumnya akan tampak penebalan epidermis atau
akantosis serta elongasi rete ridges. Terjadi diferensiasi keratinosit yang
ditandai dengan hilangnya stratum granulosum. Stratum korneum juga
mengalami penebalan dan terdapat retensi inti sel pada lapisan ini yang
disebut dengan parakeratosis. Tampak neutrofil dan limfosit yang bermigrasi
dari dermis. Sekumpulan neutrofil dapat membentuk mikroabses Munro. Pada
dermis akan tampak tanda-tanda inflamasi seperti hipervaskularitas dan
dilatasi serta edema papila dermis. Infiltrat dermis terdiri dari neutrofil,
makrofag, limfosit dan sel mast. Selain biopsi kulit, abnormalitas
laboratorium pada penderita psoriasis biasanya bersifat tidak spesifik dan
mungkin tidak ditemukan pada semua pasien. Pada psoriasis vulgaris yang
luas, psoriasis pustular generalisata, dan eritroderma tampak penurunan serum
albumin yang merupakan indikator keseimbangan nitrogen negatif dengan
inflamasi kronis dan hilangnya protein pada kulit. Peningkatan marker
inflamasi sistemik seperti C-reactive protein, α-2 makroglobulin, dan
erythrocyte sedimentation rate dapat terlihat pada kasus-kasus yang berat.
Pada penderita dengan psoriasis yang luas dapat ditemukan peningkatan kadar
asam urat serum. Selain daripada itu penderita psoriasis juga menunjukkan
gangguan profil lipid (peningkatan high density lipoprotein, rasio kolesterol-
trigliserida serta plasma apolipoprotein- A1) (Pratopo, 2017).
8. Penatalaksanaan
a. Terapi Topikal
Ada beberapa obat yang dapat dianggap sebagai anti psoriasis yaitu:
1) Preparat Ter yang digunakan untuk pengobatan psoriasis adalah
preparat ter dari kayu dan batu bara. Preparat ter dari batu bara
efeknya lebih kuat dari ter kayu tetai daya erosi terhadap kulit lebih
besar. Jadi untuk psoriasis yang kronik diberikan prepara ter dari batu
bara sedangkan untuk kasus psoriasis baru diberikan preparat ter kayu.
Efek dari preparat ter adalah anti gatal, keratolitik, vasokontriksi, dan
menaikkan ambang rangsang (Tio, 2017).
- Ter dari kayu : oleum cadini, pix liquid, oleum nisci.
- Ter dari batu bara : liantral, liquor carbonis detergent
- Ter dari fosil : ictiol
2) Mercury Praecipitatum Album
Preparat ini mengandung Hg yang dapat menimbulkan
dermatitis kontak dan bila dipakai terlalu banyakdan terlalu lama
terjadi kelainan ginjal (Nefritis). Perlu dikombinasikan dengan asam
salisilat untuk memperkuat daya kerja pemakaian obat ini sebaiknya
sesudah mandi. Disamping itu harus diperiksa kadar kadar protein urin
tiap minggu. Hal ini juga perlu dilakukan pada pemakaian obat-obat
tersebut jangka panjang. Bila terjadi komplikasi eritroderma,
pengobatan dengan preparat ini harus dihentikan kemudian diberi
prednison tablet 3 x 10 mg/hari. Untuk melunakkan kulit dan
menghilangkan skuama dapat diberikan lanolin 5 (10%) dan vaselin ad
50 (Tio, 2017).
b. Terapi Sistemik
1) Kortikosteroid
Kortikosteroid hanya digunakan pada psoriasis eritroderma dan
psoriasis pustula. Dosis permulaan 40-60mg prednison perhari. Jika
telah sembuh dosis diturunkan perlahan-lahan (Tio, 2017).
2) Obat Sitostatik
Obat yang biasa diberikan metotreksat. Indikasinya ialah untuk
psoriasis pustula, artritis dengan lesi kulit, dan eritoderma karena
psoriasis yang sukar terkontrol dengan obat standar. Kontraindikasinya
adalah jika terdapat kelainan hepar, ginjal, sistem hematopoetik,
kehamilan, penyakit infeksi aktif (TB), ulkus peptikum, kolitis
ulserosa dan psikosis (Tio, 2017).
3) Levodova
Sebenarnya levodova dipakai untukpenyakit parkison.
Diantaranya penderita parkison sekaligus juga menderita psoriasis ada
yang membaik psoriasisnya dengan levodova. Efek samping yaitu
muntah, mual, anoreksia, hipotensi, gangguan pada jantung (Tio,
2017).
4) DDS
DDS (Diaminodifenilsulfon) dipakai sebagai pengobatan
psoriasis pustulosa tiper barber dengan dosis 2 x 100mg sehari. Efek
samping yaitu anemia hemolitik, methemoglobinemia, dan
agranulositosis (Tio, 2017).
DAFTAR PUSTAKA
Pratopo, M.H., dkk. 2017. Psioriasi. Bandung: Prodi Profesi Apoteker Universitas
Jenderal Achmad Yani
Siregar, R. 2015. Saripati Penyakit Kulit Edisi 2. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
Tio. 2017. Tingkat Keparahan Pasien Psoriasis. Jakarta: Pustaka Taman Ilmu
You might also like
- Mikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaFrom EverandMikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaRating: 2.5 out of 5 stars2.5/5 (2)
- Coronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.From EverandCoronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Rating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Mikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaFrom EverandMikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaRating: 4 out of 5 stars4/5 (11)
- Laporan Keuangan Kuliah Kerja Nyata Profesi KesehatanDocument7 pagesLaporan Keuangan Kuliah Kerja Nyata Profesi Kesehatanyusril latinapaNo ratings yet
- Nama Di Undang Di 7 HariDocument3 pagesNama Di Undang Di 7 Hariyusril latinapaNo ratings yet
- Pembagian Dusun Dan JadwalDocument2 pagesPembagian Dusun Dan Jadwalyusril latinapaNo ratings yet
- Serti PanitiaDocument1 pageSerti Panitiayusril latinapaNo ratings yet
- Sertifikat Putra Putri ScoutDocument1 pageSertifikat Putra Putri Scoutyusril latinapaNo ratings yet
- Kep Kritis Ka SartikaDocument2 pagesKep Kritis Ka Sartikayusril latinapaNo ratings yet
- Tugas 4 KifliDocument27 pagesTugas 4 Kifliyusril latinapaNo ratings yet
- Soal DHFDocument1 pageSoal DHFyusril latinapaNo ratings yet
- Struktur KKN PentadioDocument1 pageStruktur KKN Pentadioyusril latinapaNo ratings yet
- Pengelola Rujukan KesehatanDocument60 pagesPengelola Rujukan Kesehatanyusril latinapaNo ratings yet
- Soal Keperawatan Anak Pneumonia Kelompok 1Document2 pagesSoal Keperawatan Anak Pneumonia Kelompok 1yusril latinapaNo ratings yet
- Etin Kti PPNDocument15 pagesEtin Kti PPNyusril latinapaNo ratings yet
- Fix Kepdas Kelompok 3Document16 pagesFix Kepdas Kelompok 3yusril latinapaNo ratings yet
- Kel.2 Soal Kep. AnakDocument5 pagesKel.2 Soal Kep. Anakyusril latinapaNo ratings yet
- Kel.3 Soal ThypoidDocument1 pageKel.3 Soal Thypoidyusril latinapaNo ratings yet
- KEL 2B - Tugas 1 Keperawatan GerontikDocument13 pagesKEL 2B - Tugas 1 Keperawatan Gerontikyusril latinapaNo ratings yet
- SinopsisDocument1 pageSinopsisyusril latinapaNo ratings yet
- Skenario 1 KMB 3Document26 pagesSkenario 1 KMB 3yusril latinapaNo ratings yet
- Nama 1Document2 pagesNama 1yusril latinapaNo ratings yet
- SOP TariDocument2 pagesSOP Tariyusril latinapaNo ratings yet
- NamaDocument2 pagesNamayusril latinapaNo ratings yet
- Kasus 2Document31 pagesKasus 2yusril latinapaNo ratings yet
- Eliminasi Alvi Kel 2Document8 pagesEliminasi Alvi Kel 2yusril latinapaNo ratings yet
- Kepdas Kelompok 3Document7 pagesKepdas Kelompok 3yusril latinapaNo ratings yet
- Skenario 3 Kelompok 1Document23 pagesSkenario 3 Kelompok 1yusril latinapaNo ratings yet
- Askep Sesuai Tumbuh KembangDocument33 pagesAskep Sesuai Tumbuh Kembangyusril latinapaNo ratings yet
- Kasus 3Document22 pagesKasus 3yusril latinapaNo ratings yet
- Kasus 1Document11 pagesKasus 1yusril latinapaNo ratings yet
- KMB 3 Sistem NeurosensoriDocument32 pagesKMB 3 Sistem Neurosensoriyusril latinapaNo ratings yet
- Kepdas Kel4Document13 pagesKepdas Kel4yusril latinapaNo ratings yet