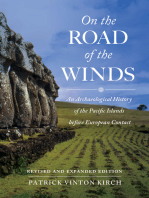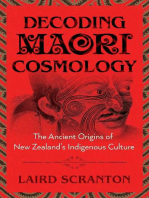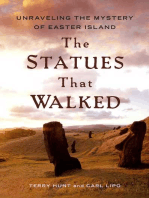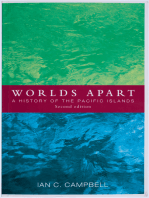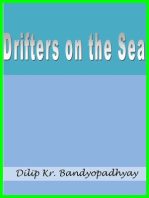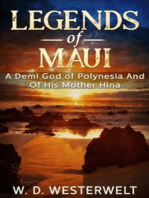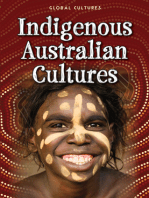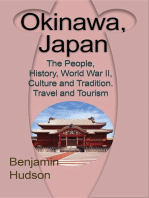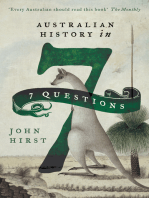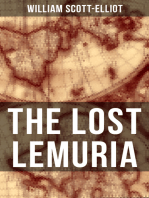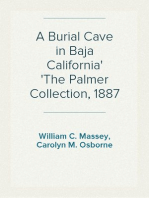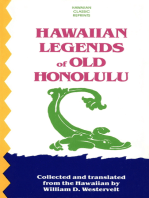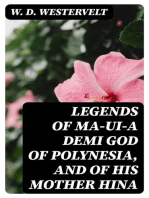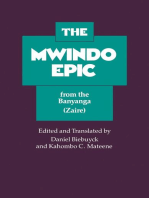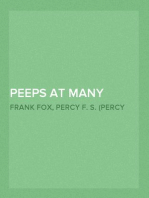Professional Documents
Culture Documents
Budaya Austronesia Di Papua
Budaya Austronesia Di Papua
Uploaded by
Valentina RodinoCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Budaya Austronesia Di Papua
Budaya Austronesia Di Papua
Uploaded by
Valentina RodinoCopyright:
Available Formats
Hari Suroto, Budaya Austronesia di Papua
BUDAYA AUSTRONESIA DI PAPUA
Hari Suroto
(Balai Arkeologi Jayapura)
Abstract
Papua has a strategic location in the western Pacific region, as a connector between
South East Asia and Pacific Region that makes it a strategic place to transit from
both west and east. On 1500 to 1000 BC there were a new wave of migration from
Austronesia. The colonist left a vivid track about their journey through ocean and
islands which can be seen form their archaeological sites. These sites were found in
Admiralty island on the north of New Guinea to the east of Samoa island on West
Polynesia. The strongest evidence on the migration of the Austronesian in Pacific
is the language. The imigrant from Austronesia who came to Pacific settled accross
the coastal area of north Papua. The influence of Austronesian culture in Papua that
is only on north coast Papua, the Cendrawasih bay and the Bird’s Head Peninsula is
particularly the Melanesian language, which actually a development of local Papua
language influenced by the Austronesian language. Other influence they made is the
tradition of the making and utilization of vessels. It is because this tradition was widely
unknown in mid Papua mountains and south-coast Papua. Then the other Austronesian
characteristics are the structured hierarchical organization, which applied hereditary
and tattoo tradition.
Keywords: Austronesian narrator, the influence of Austronesian culture, North-coast
Papua
Pendahuluan
Banyak orang Papua saat ini menganggap dirinya sebagai keturunan
Melanesia, karena merujuk pada arti ‘Melanesia’ (=penghuni pulau berkulit hitam).
Kata ‘Melanesia’ secara harafiah berarti ‘pulau-pulau hitam’. Istilah ini pertama kali
digunakan pada tahun 1827 oleh nahkoda kapal Astrolabe asal Perancis bernama
Dumont d’Urville. Kata ini sebenarnya untuk menunjuk areal geografis semata.
Walaupun begitu, para ahli yang telah menyelidiki bahasa dan prasejarah Papua
dan Melanesia sepakat untuk membedakannya. Bahasa-bahasa Papua sebagai Non-
Austronesia dan bahasa-bahasa Melanesia termasuk dalam filum Austronesia.
Selama kurun bertahun-tahun, sebelum adanya kajian yang komprehensif
tentang bahasa di Pasifik, baik orang Papua maupun orang Melanesia yang tinggal
Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009 59
Hari Suroto, Budaya Austronesia di Papua
di Pulau Solomon, Vanuatu, Kaledonia baru, dan Fiji sama-sama digolongkan
dalam kategori penutur bahasa Melanesia (Muller, 2008: 58). Moeliono (1963:28)
berpendapat yang tergolong dalam penutur bahasa Melanesia, daerahnya antara
lain New Britain, New Ireland, New Hebrides dan Pulau Fiji. Sementara itu Peter
Bellwood (2005:266) berpendapat yang termasuk dalam penutur bahasa Melanesia
adalah Fiji, Biak, Vanuatu, New Britain, New Ireland, Sepik, dan Admiralty.
Pada 1500 hingga 1000 SM di Pasifik Barat datang gelombang penduduk
baru. Pendatang baru ini adalah migran yang berbahasa Austronesia. Para kolonis
Austronesia meninggalkan jejak-jejak yang amat jelas akan keperintisan mereka
melintasi lautan dan pulau-pulau pada situs-situs arkeologi yang ditemukan mulai
dari Kepulauan Admiralty di utara New Guinea sampai ke timur sejauh Samoa, di
Polinesia barat (Bellwood, 2000:341).
Bukti paling kuat migrasi Austronesia di Pasifik adalah bahasa (Bellwood,
1978:244). Diperkirakan kelompok ini juga menetap di Pulau Biak dan Yapen.
Perkiraan ini didukung oleh bukti linguistik meskipun secara arkeologis belum
ditemukan (Muller, 2008: 52).
Orang Austronesia ini meninggalkan Taiwan 5000 tahun yang lalu dan
menyebar ke arah selatan. Mereka mengadakan perjalanan laut menggunakan perahu
sampan maupun perahu layar, pertama-tama mencapai Filipina bagian utara. Mereka
kemudian mengadakan perjalanan ke arah selatan. Dari selatan Filipina mereka
memisahkan diri dalam 2 kelompok: kelompok pertama berlayar ke arah barat daya,
sedangkan kelompok kedua berlayar ke arah tenggara. Kelompok pertama kemudian
mencapai Pulau Kalimantan, Malaysia, Sumatera dan Jawa. Bisa dikatakan kelompok
pertama inilah yang menjadi nenek moyang orang Malaysia serta orang Indonesia Barat.
Kelompok kedua-yang bergerak ke arah tenggara- akhirnya mencapai Halmahera dan
Kepulauan Bismarck. Dari Bismarck, mereka melanjutkan perjalanannya ke Pulau
Solomon, Vanuatu, New Kaledonia, Fiji, dan terus ke arah timur sampai akhirnya
mereka menetap di wilayah Polinesia (Muller, 2008:48-49).
Kebudayaan dan teknologi orang Austronesia ini sudah sangat maju. Mereka
telah menjinakkan berbagai jenis hewan (ayam, anjing dan babi) serta membiakkan
tanaman impor yang bermanfaat. Perkakas yang mereka pergunakan sudah lebih baik.
Organisasi kemasyarakatannya pun sudah terstruktur dengan sistem hirarki dimana
60 Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009
Hari Suroto, Budaya Austronesia di Papua
para pemimpinnya dijabat secara turun-temurun. Dengan keahliannya, mereka juga
mampu menghasilkan karya berupa ornamen-ornamen dan perkakas dengan bahan
kulit kerang. Ornamen atau alat-alat berbahan kerang yang mereka buat termasuk
beliung, manik-manik, mata kail, gelang tangan, dan terompet (Muller, 2008:53).
Imigran Austronesia yang datang ke Pasifik bermukim di sepanjang
tepi pantai. Penghunian wilayah pesisir yang dapat dilakukan dengan mudah dan
cepat rupanya lebih diminati daripada penghunian wilayah pedalaman yang lebih
membutuhkan tenaga, dan lagi di beberapa tempat sudah dihuni oleh penduduk lain
yang mungkin tidak bisa menerima mereka. Pertanian biji-bijian menjadi kurang
penting, para pemukim Austronesia di Pasifik mendasarkan ekonomi mereka
semata-mata pada umbi-umbian, pohon buah, dan tanaman pangan bertunas lainnya
(Bellwood, 2000:354).
Interaksi penutur Austronesia dengan Papua kemudian menciptakan suatu
budaya yang sangat kompleks, yang dikenal sebagai budaya Lapita. Kata ‘Lapita’
berasal dari sebuah tempat di New Kaledonia yang terkenal sebagai tempat penghasil
kerajinan tembikar yang sangat indah. Tembikar ini umumnya berwarna kemerah-
merahan dan dihiasi dengan gambar gigi-gigi kecil yang berbeda diantaranya diberikan
warna putih kontras menggunakan tanah liat atau kapur (Muller, 2008:62).
Hubungan Asia Tenggara dengan Pasifik dapat diketahui dari perdagangan
jarak jauh orang-orang Lapita. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah obsidian
yang banyak didapatkan di Pulau New Britania serta tembikar dengan ciri khas warna
kemerah-merahan dengan gambar gigi-gigi kecil di bagian atas.
Temuan serpihan obsidian di Situs Bukit Tengkorak (Sabah) yang berasal
dari Talasea, New Britain di Melanesia, menambah luas penyebaran obsidian pada
sekitar 1000 SM, berdasarkan hal ini luas penyebarannya mencapai 6.500 km, dari
Kalimantan hingga Fiji (Bellwood, 2000:330).
Bukti arkeologis lainnya, berupa fragmen perunggu yang ditemukan di
Kepulauan Admiralty sebelah utara Papua New Guinea, ada kemungkinan benda-
benda itu didatangkan dari Indonesia (Ambrose, 1988). Kendi bercerat ganda dari
Lobang Jeragan, Niah, bentuk serupa juga terdapat di Kepulauan Admiralty, utara
Papua New Guinea dan mungkin bertarikh sekitar 2000 tahun yang lalu (Bellwood,
2000: 347).
Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009 61
Hari Suroto, Budaya Austronesia di Papua
Letak geografis Papua yang sangat strategis, bagian dari wilayah Pasifik
paling ujung barat, sebagai daratan penghubung kawasan Asia Tenggara dengan
kawasan Pasifik dan merupakan tempat yang strategis untuk persinggahan lalu lintas
dari barat ke timur. Tulisan ini mencoba menguraikan tentang bukti-bukti arkeologis
dan hasil budaya lainnya yang membuktikan keberadaan budaya Austronesia di Papua.
Pembahasan
Secara genetis dan linguistik perpaduan penutur Austronesia dengan
Papua masih bisa ditelusuri sampai hari ini. Di sebagian wilayah barat Papua, bisa
dijumpai di pulau-pulau di wilayah Biak, Yapen, Raja Ampat, serta di sepanjang
pesisir utara. Namun, mereka tak bisa ditemukan di wilayah dataran tinggi dan
sepanjang pesisir selatan (Muller, 2008:59). Lain halnya J. C. Anceaux (1953:293)
berpendapat bahwa di bagian baratlaut Papua, yaitu Pulau Biak, sebagian dari Pulau
Yapen, Teluk Saireri, Teluk Berau hingga Teluk Etna terdapat sejumlah bahasa yang
tergolong dalam bahasa Melanesia. Anceaux menduga bahwa bahasa Melanesia
merupakan hasil perkembangan bahasa-bahasa Papua yang mendapat pengaruh dari
bahasa Austronesia, hal ini terlihat pada strukturnya (tata bahasa) dan sedikit dalam
perbendaharaan kata-katanya. Sementara itu menurut A.M. Moeliono (1963:32)
wilayah Papua yang termasuk ke dalam golongan bahasa Melanesia adalah bahasa di
Pulau Yapen, Raja Ampat, Biak, Waropen, daerah Teluk Wandamen, sepanjang pantai
Teluk Cenderawasih, ujung barat Pulau Papua dari Sorong ke arah selatan sepanjang
pantai Selat Sele, daerah sekitar Teluk Bintuni, Teluk Arguni hingga daerah pesisir
Teluk Etna. Ciri budaya Austronesia lainnya adalah organisasi kemasyarakatannya
terstruktur dengan sistem hirarki dimana para pemimpinnya dijabat secara turun-
temurun. Hal ini terlihat pada masyarakat yang tinggal di Fak-Fak, Raja Ampat,
Teluk Youtefa (Tobati, Enggros, Nafri, Kayu Batu), Waena dan Sentani.
Secara tradisional penduduk kampung di Waena dan Sentani dibagi
dalam dua lapisan sosial, yaitu lapisan sosial atas dan lapisan sosial bawah. Lapisan
sosial atas mempunyai status terpandang karena memegang hak turun temurun atas
kepemimpinan di dalam kampung atau disebut ondoafi dan yang kedua adalah lapisan
sosial bawah yang terdiri dari masyarakat biasa.
62 Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009
Hari Suroto, Budaya Austronesia di Papua
Stefanus Ngadimin (1994:70) dalam tulisannya mengenai Suku Baliem
di Pegunungan Tengah menyatakan Orang Baliem cenderung menganggap sesama
mereka memiliki derajat dan martabat yang sama. Orang Baliem tidak membuat
klasifikasi ataupun stratifikasi sosial ataupun menjadikan stratifikasi pemimpin
mereka.
Merajah (tato) adalah ciri budaya Austronesia (Bellwood, 2000:225). Ciri
budaya Austronesia yang terdapat di pesisir utara Papua, Teluk Cenderawasih dan
Kepala Burung selain bahasa, adalah tato. Suku-suku bangsa yang menerapkan
tato ditubuhnya, diantaranya Suku Meybrat di Kepala Burung (Wanane, 2007:64),
Suku Waropen (Held, 2006:38; Sujatni, 1963:146), Suku Biak-Numfor (Budjang,
1963:121), dan orang Sentani (Flassy, 2007:95-96).
Gerabah ditemukan di sepanjang pesisir utara Papua, Teluk Cenderawasih
dan pesisir Kepala Burung. Motif hias pada gerabah di Yenbekaki (Raja Ampat)
menunjukkan dibuat dengan teknik tera dan gores, dengan motif geometrik, spiral
dan topeng. Di Warweri Urang (Sentani), ditemukan pecahan tempayan dengan
hiasan geometrik. Diantara pecahan-pecahan ini ditemukan beberapa tulang manusia
yang menunjukkan berlangsungnya tradisi penguburan dengan tempayan (Soejono,
1963:48). Diperkirakan teknologi pembuatan gerabah di New Guinea dibawa oleh
orang-orang Austronesia. Menurut Kal Muller (2008:59) sebelum kedatangan orang-
orang Austronesia, kerajinan gerabah tidak dikenal di New Guinea. Secara etnografis
daerah pembuat gerabah di Papua adalah Kayu Batu (Jayapura), Saberi (Sarmi), dan
Abar (Sentani), dan Kurudu (Teluk Cenderawasih).
Memasak menggunakan gerabah tidak dikenal di daerah pegunungan.
Menurut Koentjaraningrat (1963:222), penduduk Pegunungan Tengah Papua
umumnya tidak mengenal gerabah. Wadah dibuat dari kayu. Benda cair disimpan
dalam kulit buah labu yang sudah dikeringkan. Makanan pokok adalah ubi yang
dimasak dengan batu panas. J. Tan Soe Lin (1963:273) dalam tulisannya mengenai
orang Muyu, menyatakan bahwa Orang Muyu tak mengenal cara memasak dengan
menggunakan gerabah sehingga semua bahan makanan dipanggang langsung di atas
api atau dimasukkan ke dalam abu panas. Merebus makanan tidak dikenal mereka. M.
Amir Sutaarga (1963:284) menyatakan orang Mimika di pesisir selatan Papua tidak
mengenal Gerabah. Sebagai wadah air digunakan bambu, baki dari kayu untuk tempat
Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009 63
Hari Suroto, Budaya Austronesia di Papua
makanan. Makanan dimasak dengan batu panas. Hal yang sama diungkapkan oleh
Peter Bellwood (2000:129) bahwa gerabah tidak ditemukan di Dataran Tinggi New
Guinea.
Terdapat bukti konkrit tentang transaksi antara Asia Tenggara dan Papua.
Barang-barang yang dijadikan komoditi transaksi adalah benda-benda perunggu
produksi Dongson. Kepingan-kepingan dari tiga nekara perunggu telah ditemukan
dekat Danau Aimaru di daerah Kepala Burung, dan barang-barang perunggu lain yang
berasal dari Dongson juga ditemukan jauh ke timur di wilayah Danau Sentani.
Teknologi metalurgi praktis tidak dijumpai di daerah Pasifik (Soejono,
1998:10). Diperkirakan benda-benda perunggu ini dibawa oleh penutur Austronesia
yang dari Kepulauan Indonesia bagian barat, benda perunggu ini dipertukarkan
dengan komoditi Papua. Karena hingga saat ini belum ditemukan bukti arkeologis
mengenai barang-barang yang dibarter pedagang Papua dengan pedagang Austronesia,
diperkirakan komoditi dagang dari Papua adalah hasil hutan, hasil laut, bulu burung
cenderawasih, kayu masoi dan budak.
Penutup
Pengaruh budaya Austronesia di Papua hanya terdapat di pesisir utara,
Teluk Cenderawasih dan pesisir Kepala Burung, pengaruh ini berupa bahasa
Melanesia, merupakan hasil perkembangan bahasa-bahasa Papua yang mendapat
pengaruh dari bahasa Austronesia. Ciri budaya Austronesia lainnya adalah organisasi
kemasyarakatannya terstruktur dengan sistem hirarki dimana para pemimpinnya
dijabat secara turun-temurun, selain itu adalah seni menghias tubuh dengan rajah
(tato).
Gerabah ditemukan di pesisir Kepala Burung, Teluk Cenderawasih, dan
pesisir utara Papua. Namun tradisi pembuatan gerabah dapat dijumpai di pesisir utara
Papua dan Teluk Cenderawasih. Tradisi ini tidak dikenal di pegunungan tengah Papua
dan pesisir selatan Papua. Diperkirakan tradisi pembuatan gerabah di Papua dibawa
oleh orang Austronesia.
Letak geografis Papua sangat strategis menghubungkan kawasan Asia
tenggara dengan kawasan Pasifik, bukti arkeologis berupa benda-benda perunggu
64 Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009
Hari Suroto, Budaya Austronesia di Papua
menunjukkan Papua merupakan bagian dari suatu jaringan perdagangan dari Indonesia
bagian barat ke timur.
Ciri budaya Austronesia lainnya yang ditemukan di pesisir utara Papua,
pesisir Kepala Burung, dan Teluk Cenderawasih adalah budaya minum cairan hasil
sadapan nira pohon kelapa, atau nira pohon aren. Minuman ini di Kampung Waena
dikenal dengan nama sagero.
Penutur Austronesia yang datang ke Papua, melakukan perdagangan dengan
penduduk pesisir Papua, perdagangan ini menggunakan sistem barter. Bukti arkeologis
yang membuktikan hal ini adalah artefak perunggu buatan Dongson yang di temukan
di sekitar Danau Sentani dan sekitar Danau Ayamaru. Benda perunggu ini ditukar
dengan komoditi asal Papua, yang hingga saat ini secara arkeologis belum ditemukan,
diperkirakan komoditas unggulan Papua adalah bulu burung cenderawasih, hasil laut,
dan hasil hutan.
Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009 65
Hari Suroto, Budaya Austronesia di Papua
DAFTAR PUSTAKA
Ambrose, W. 1988. An Early Bronze Artifact from Papua New Guinea. Antiquity 62.
Hlm. 483-491.
Anceaux, J. C. 1953. De huidige stand van het taal-onderzoek op Nieuw Guinea’s
westhelft. Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde, CIX. Hlm. 231-248.
Bellwood, Peter. 1978. Man Conquest of the Pacific. The Prehistory of South East
Asia and Oceania. Auckland: William Collins Publisher Ltd.
_____________.2000. Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.
_____________.2005. First Farmers. The Origin of Agricultural Societies. Oxford:
Blackwell Publishing.
Budjang, Anis. 1963. “Orang Biak-Numfor” dalam Penduduk Irian Barat
(Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar eds.). Jakarta: PT Penerbitan
Universitas. Hlm. 113-135.
Elmberg, J. E. 1959. “Further Notes on the Northern Mejbrats (Vogelkop, Western
New Guinea)” dalam Ethnos XXIV. Hlm. 70-81.
Flassy, Don A.L. 2007. Etno Artistik Sentani Motif Gaya Rias. Jakarta: Balai
Pustaka.
Held, G. J. 2006. Waropen dalam Khasanah Budaya Papua. Pasuruan: Pedati.
Howel, W.W. 1943. “The Racial Elements of Melanesia” dalam Coon C. S. dan J. M.
Andrews (ed.). Hlm. 38-49.
Jacob, T. 2008. “Ras, Etnik, dan Bangsa dalam Arkeologi Indonesia” dalam PIA IX
Kediri 23-28 Juli 2002. Jakarta: IAAI.
Koentjaraningrat.1963. “Orang Timorini” dalam Penduduk Irian Barat
(Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar eds.). Jakarta: PT Penerbitan
Universitas. Hlm. 216-231.
66 Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009
Hari Suroto, Budaya Austronesia di Papua
Lin, J. Tan Soe. 1963. “Orang Muyu” dalam Penduduk Irian Barat (Koentjaraningrat
dan Harsja W. Bachtiar eds.). Jakarta: PT Penerbitan Universitas. Hlm. 233-
251.
Moeliono, A. M. 1963. “Ragam Bahasa di Irian Barat” dalam Penduduk Irian Barat
(Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar eds.). Jakarta: PT Penerbitan
Universitas. Hlm. 28-37.
Muller, Kal. 2008. Introducing Papua. Daisy World Books.
Naber, S.P.P.H. 1915. “Nieuw-Guinea, Nova Guinea, Nieuw Guinee” dalam Tijdshrift
van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijksundig Genootschap. XXXII. Hlm.
527-533.
Ngadimin, Stefanus. 1994. “Sistem Kepemimpinan Tradisional Suku Baliem
Sebagai Penunjang Pembangunan Daerah Jayawijaya” dalam Kebudayaan
Jayawijaya dalam Pembangunan Bangsa (Astrid S. Susanto-Sunario ed.).
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 70-96.
Soejono, R. P. 1963. “Prehistori Irian Barat” dalam Penduduk Irian Barat
(Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar eds.). Jakarta: PT Penerbitan
Universitas. Hlm.39-93.
___________.1998. “Indonesia dalam Lingkup Prasejarah Asia Tenggara dan Pasifik”
dalam Jurnal Arkeologi Indonesia No. 3. Jakarta: IAAI. Hlm. 9-12.
Sujatni. 1963. “Orang Waropen” dalam Penduduk Irian Barat (Koentjaraningrat dan
Harsja W. Bachtiar eds.). Jakarta: PT Penerbitan Universitas.Hlm. 136-158.
Sutaarga, M. Amir. 1963. “Orang Mimika” dalam Penduduk Irian Barat
(Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar eds.). Jakarta: PT Penerbitan
Universitas. Hlm.273-300.
Wanane, Teddy K dan Trien Kambu, 2007. “Ragam Rias Orang Mey Brat Jazirah
Kepala Burung Tanah Papua” dalam Refleksi Seni Rupa di Tanah Papua (Don
A. L. Flassy ed.). Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 64-71.
Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009 67
Hari Suroto, Budaya Austronesia di Papua
Gerabah Hasil Produksi Masyarakat Kampung Abar, Sentani, Jayapura
68 Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- On the Road of the Winds: An Archaeological History of the Pacific Islands before European Contact, Revised and Expanded EditionFrom EverandOn the Road of the Winds: An Archaeological History of the Pacific Islands before European Contact, Revised and Expanded EditionRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Decoding Maori Cosmology: The Ancient Origins of New Zealand's Indigenous CultureFrom EverandDecoding Maori Cosmology: The Ancient Origins of New Zealand's Indigenous CultureNo ratings yet
- Journey Through Indonesia: An Unforgettable Journey from Sumatra to PapuaFrom EverandJourney Through Indonesia: An Unforgettable Journey from Sumatra to PapuaNo ratings yet
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Statues that Walked: Unraveling the Mystery of Easter IslandFrom EverandThe Statues that Walked: Unraveling the Mystery of Easter IslandRating: 4 out of 5 stars4/5 (12)
- A New Human: The Startling Discovery and Strange Story of the "Hobbits" of Flores, IndonesiaFrom EverandA New Human: The Startling Discovery and Strange Story of the "Hobbits" of Flores, IndonesiaRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (4)
- The Avifauna of Micronesia, Volume 3 Its Origin, Evolution, and DistributionFrom EverandThe Avifauna of Micronesia, Volume 3 Its Origin, Evolution, and DistributionNo ratings yet
- Throwim Way Leg: Tree-Kangaroos, Possums, and Penis Gourds: On the Track of Unknown Mammals in Wildest New GuineaFrom EverandThrowim Way Leg: Tree-Kangaroos, Possums, and Penis Gourds: On the Track of Unknown Mammals in Wildest New GuineaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Gale Researcher Guide for: Transcultural Connections in the Pacific WorldFrom EverandGale Researcher Guide for: Transcultural Connections in the Pacific WorldNo ratings yet
- Kava: The Pacific Elixir: The Definitive Guide to Its Ethnobotany, History, and ChemistryFrom EverandKava: The Pacific Elixir: The Definitive Guide to Its Ethnobotany, History, and ChemistryRating: 4 out of 5 stars4/5 (2)
- Legends Of Maui: A Demi God of Polynesia And Of His Mother HinaFrom EverandLegends Of Maui: A Demi God of Polynesia And Of His Mother HinaNo ratings yet
- Okinawa, Japan: The People, History, World War II, Culture and Tradition. Travel and TourismFrom EverandOkinawa, Japan: The People, History, World War II, Culture and Tradition. Travel and TourismNo ratings yet
- Legends of Old Honolulu (Mythology): Collected and Translated from the HawaiianFrom EverandLegends of Old Honolulu (Mythology): Collected and Translated from the HawaiianNo ratings yet
- New Guinea: Nature and Culture of Earth's Grandest IslandFrom EverandNew Guinea: Nature and Culture of Earth's Grandest IslandRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- THE LOST LEMURIA: The Story of the Lost Civilization (Ancient Mysteries)From EverandTHE LOST LEMURIA: The Story of the Lost Civilization (Ancient Mysteries)No ratings yet
- Feet to the Fire: CIA Covert Operations in Indonesia, 1957-1958From EverandFeet to the Fire: CIA Covert Operations in Indonesia, 1957-1958Rating: 3 out of 5 stars3/5 (2)
- LEGENDS of MAUI - 15 Polynesian Legends: Legends, Tales and Myths from the PacificFrom EverandLEGENDS of MAUI - 15 Polynesian Legends: Legends, Tales and Myths from the PacificRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Legends of Ma-ui—a demi god of Polynesia, and of his mother HinaFrom EverandLegends of Ma-ui—a demi god of Polynesia, and of his mother HinaNo ratings yet
- A Burial Cave in Baja California The Palmer Collection, 1887From EverandA Burial Cave in Baja California The Palmer Collection, 1887No ratings yet
- The Legends and Myths of Hawaii: Complete Legends of Maui, of Old Honolulu, Gods and Ghost-Gods, Myths of Volcanoes and Historical LegendsFrom EverandThe Legends and Myths of Hawaii: Complete Legends of Maui, of Old Honolulu, Gods and Ghost-Gods, Myths of Volcanoes and Historical LegendsNo ratings yet
- Legends of Ma-ui—a demi god of Polynesia, and of his mother HinaFrom EverandLegends of Ma-ui—a demi god of Polynesia, and of his mother HinaNo ratings yet
- Navigators Forging a Culture and Founding a Nation Volume 1: Navigators Forging a Matriarchal Culture in Polynesia: NavigatorsFrom EverandNavigators Forging a Culture and Founding a Nation Volume 1: Navigators Forging a Matriarchal Culture in Polynesia: NavigatorsNo ratings yet
- Systematics of Megachiropteran Bats in the Solomon IslandsFrom EverandSystematics of Megachiropteran Bats in the Solomon IslandsNo ratings yet
- Bondoc Jake S-Act2Document3 pagesBondoc Jake S-Act2Jake BondocNo ratings yet
- Kajian Sosio Biologi Minuman Baram Masya A01412f2Document9 pagesKajian Sosio Biologi Minuman Baram Masya A01412f220 15No ratings yet
- Cari Kata Arahan: Cari Perkataan Tersembunyi Di Dalam Petak TersebutDocument1 pageCari Kata Arahan: Cari Perkataan Tersembunyi Di Dalam Petak TersebutScha Wan Md SukriNo ratings yet
- 5052 11950 1 SMDocument20 pages5052 11950 1 SMMuhammad MuzzammilNo ratings yet
- For New VasssDocument71 pagesFor New VasssGanie Mar BiasonNo ratings yet
- History of Zapin Tradition Office at Tanjung Medang Subscribes of Rupat Utara of Bengkalis RegencyDocument11 pagesHistory of Zapin Tradition Office at Tanjung Medang Subscribes of Rupat Utara of Bengkalis RegencyKuy NgerintisNo ratings yet
- Mangyan - Google Search PDFDocument1 pageMangyan - Google Search PDFReane MarquezNo ratings yet
- Pleted.20220528 20220627Document135 pagesPleted.20220528 20220627Muhammad JefriNo ratings yet
- Sekolah - Senarai Calon Berdaftar Mengikut PusatDocument3 pagesSekolah - Senarai Calon Berdaftar Mengikut Pusatahmadsabarani ahmadNo ratings yet
- Registered Electrical ConsultantSWK - SESCODocument7 pagesRegistered Electrical ConsultantSWK - SESCOZulkarnain TahirNo ratings yet
- CAR BLGF Covid Response UpdateDocument8 pagesCAR BLGF Covid Response UpdatenormanNo ratings yet
- Analisis Bm&Sej Trial Ting 5 2022Document17 pagesAnalisis Bm&Sej Trial Ting 5 2022SHAMSINAR BT JAMALUDINNo ratings yet
- Letter Writing Task - PairingDocument4 pagesLetter Writing Task - PairingAmirul AqielNo ratings yet
- Origins of KadazanDocument3 pagesOrigins of KadazanAlexanderNo ratings yet
- Rumah KuningDocument6 pagesRumah KuningSarah WilsonNo ratings yet
- H - CBMS Updates - Pilot and National Roll OutDocument7 pagesH - CBMS Updates - Pilot and National Roll OutAlfrainerNo ratings yet
- The Indeginous PeopleDocument2 pagesThe Indeginous PeopleShane De VillaNo ratings yet
- Maklumat GuruDocument86 pagesMaklumat Guruhafizah kamalNo ratings yet
- Adoc - Pub Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Dan WDocument30 pagesAdoc - Pub Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Dan Wsesian sewuNo ratings yet
- IGOROTDocument1 pageIGOROTAerone C AntolinNo ratings yet
- Sukan & Permainan Mac 2024Document58 pagesSukan & Permainan Mac 2024lim chin guanNo ratings yet
- SSP22 Unit2B Task1Document2 pagesSSP22 Unit2B Task1BACAGAN Zinnia PadallaNo ratings yet
- Final Consolidation IP Enrolment Report 2019 2020Document148 pagesFinal Consolidation IP Enrolment Report 2019 2020Norlyn Sadsad Teh BaribarNo ratings yet
- T2 - 2 Ibnu Battuta - 222Document3 pagesT2 - 2 Ibnu Battuta - 222NURUL ADILLANo ratings yet
- Mediums and TechniquesDocument11 pagesMediums and TechniquesRenz VizcondeNo ratings yet
- Senarai NAMA RUMAH SUKANDocument19 pagesSenarai NAMA RUMAH SUKANazmansgaraNo ratings yet
- Rawat Inap Hasroni 2019Document13 pagesRawat Inap Hasroni 2019winda siregarNo ratings yet
- Seb Eod 15.06.23Document86 pagesSeb Eod 15.06.23aryantopallunanNo ratings yet
- Senarai Nama Murid Prasekolah 2020 SK SemukoiDocument2 pagesSenarai Nama Murid Prasekolah 2020 SK SemukoiStap DugiNo ratings yet
- Excel PAJSK SMKB (KELAB PEENCINTA ALAM 2020)Document59 pagesExcel PAJSK SMKB (KELAB PEENCINTA ALAM 2020)Nor Hayati KamismanNo ratings yet