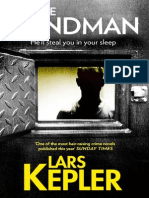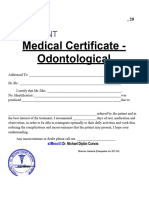Professional Documents
Culture Documents
Uji Antagonis Trichoderma Harzianum Terhadap Fusarium Spp. Penyebab Penyakit Layu Pada Tanaman Cabai (Capsicum Annum) Secara in Vitro
Uji Antagonis Trichoderma Harzianum Terhadap Fusarium Spp. Penyebab Penyakit Layu Pada Tanaman Cabai (Capsicum Annum) Secara in Vitro
Uploaded by
miftaOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Uji Antagonis Trichoderma Harzianum Terhadap Fusarium Spp. Penyebab Penyakit Layu Pada Tanaman Cabai (Capsicum Annum) Secara in Vitro
Uji Antagonis Trichoderma Harzianum Terhadap Fusarium Spp. Penyebab Penyakit Layu Pada Tanaman Cabai (Capsicum Annum) Secara in Vitro
Uploaded by
miftaCopyright:
Available Formats
Uji Antagonis Trichoderma harzianum Terhadap Fusarium spp.
Penyebab Penyakit
Layu pada Tanaman Cabai (Capsicum annum) Secara In Vitro
[Antagonistic Test of Trichoderma harzianum Against Fusarium spp., a Causal Agent of
Wilt Disease on Pepper (Capsicum annum)]
MUKARLINA, SITI KHOTIMAH, DAN RENY RIANTI
Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Tanjungpura
Jl. Ahmad Yani, Pontianak Kalimantan Barat
J. Fitomedika. 7 (2): 80 85 (2010)
ABSTRACT Fusarium spp., the causal agent of Fusarium wilt disease, infect sweet pepper inflicting damages
on the roots, stems, leaves, flowers, and fruits. Infection of Fusarium spp. on some crops can be controlled by
using Trichoderma harzianum as a biological control agent. The aims of this study were to determine: 1) the
species of Fusarium infecting sweet pepper; and 2) the in vitro antagonistic potential of T. harzianum in
controlling Fusarium spp. in vitro. The study was conducted from September 2008 to February 2009. Fusarium
spp. were isolated from plant organs showing symptoms of Fusarium wilt; while T. harzianum was isolated from
healthy soil in sweet pepper plantation area. In vitro antagonistic test was carried out using multiple test method
in which Fusarium spp. and T. harzianum were placed in the same antagonistic test space. The percentages of
antagonistic level were determined by measuring the diameter of T. harzianum colony every 24 h during a 7-day
incubation time. The results indicated two species of Fusarium which infected sweet pepper, namely: F.
sambucinum infecting stems, leaves, flowers, and fruits; and F. oxysporum infecting leaves only. The average of
antagonistic percentage of T. harzianum against Fusarium spp. ranged from 71.2% to 94.2%.
KEYWORDS : Capsicum annum L, Trichoderma harzianum, Fusarium spp., antagonistic test
Cabai (Capsicum annum L.) merupakan komoditas
yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di Indonesia dan diusahakan secara komersial baik dalam
skala besar maupun kecil. Daerah-daerah sentra pertanaman cabai di Indonesia tersebar mulai dari Sumatera
Utara sampai Sulawesi Selatan dengan rata-rata total
produksi cabai di sentra pertanaman berkisar 841.015
ton per tahun (Winarsih & Syafrudin 2001).
Budidaya tanaman cabai mempunyai resiko tinggi
akibat adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang dapat menyebabkan kegagalan panen.
Cendawan adalah OPT yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas produksi cabai sampai 100%
(Asian Vegetable Research and Development Center
1990 dalam Syamsuddin 2003). Beberapa cendawan
penyebab penyakit pada tanaman cabai adalah Gleosporium piperatum dan Colletotrichum capsici penyebab penyakit antraknosa atau busuk buah, Cercospora capsici penyebab penyakit bercak daun dan
Fusarium spp. penyebab penyakit layu Fusarium
dan penyakit rebah kecambah (Semangun 1996,
Syamsuddin 2003).
Cendawan Fusarium spp. merupakan cendawan
yang sangat merugikan karena dapat menyerang tanaman cabai mulai dari masa perkecambahan sampai
dewasa. Meskipun dikenal sebagai patogen tular tanah,
infeksi cendawan ini tidak hanya di perakaran tetapi
E-mail : mukar.lina@gmail.com
dapat juga menginfeksi organ lain seperti batang, daun,
bunga, dan buah, misalnya melalui luka. Penularan
penyakit selain dengan spora yang terdapat di dalam
tanah dapat juga dengan spora yang terbawa angin
dan air (Mulyaman et al. 2002, Semangun, 2000).
Spesies dari cendawan Fusarium yang dapat menyerang
tanaman cabai di antaranya adalah F. oxysporum, F.
solani, F. moniliforme dan F. clamidosporium (Mulyaman
et al. 2002, Semangun 2000, Syamsuddin 2003, Zahara &
Harahap 2007).
Cendawan Fusarium spp. membentuk polipeptida
yang disebut likomarasmin yaitu suatu toksin yang
mengganggu permeabilitas membran plasma tanaman.
Selain itu, Fusarium spp. juga membentuk senyawa
yang lebih sederhana, yaitu asam fusarat dan menghasilkan enzim pektolitik, terutama pektinmetilesterase
(PME) dan depolimerase (DP). PME menghilangkan
metil pada rantai pektin menjadi asam pektat. Depolimerase memecah rantai asam pektat menjadi poligalakturonida dengan bermacam-macam berat molekul.
Enzim-enzim tersebut memecah bahan pektin yang
ada dalam dinding sel xilem. Fragmen-fragmen asam
pektat masuk ke dalam pembuluh xilem yang kemudian
membentuk massa koloidal yang mengandung bahan
non pektin yang dapat menyumbat pembuluh. Berkas
pembuluh akan menjadi cokelat disebabkan karena
fenol-fenol yang terlepas masuk ke dalam berkas
pembuluh. Fenol-fenol tersebut oleh enzim fenol
oksidase yang dihasilkan tumbuhan inang akan
mengalami polimerisasi menjadi melanin yang berwarna
81
JURNAL FITOMEDIKA
coklat. Bahan berwarna ini terutama diserap oleh
pembuluh xilem yang berlignin yang menyebabkan
warna cokelat yang khas pada penyakit layu Fusarium
(Gaumann & Jaag 1947 dalam Semangun 1996).
Pengendalian biologi dengan memanfaatkan agen
pengendali hayati (APH) merupakan alternatif untuk
mengurangi penggunaan pestisida kimia. Penggunaan
APH semakin berkembang karena selain membatasi
pertumbuhan dan perkembangan OPT dalam waktu
relatif lama, APH juga mempunyai keunggulan dalam
menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan pertanian (Soesanto 2002). Trichoderma harzianum merupakan salah satu cendawan potensial untuk dikembangkan sebagai APH dalam upaya mencari alternatif pengganti penggunaan pestisida kimia (Widyastuti
et al. 2001, Winarsih & Syafrudin 2001).
Trichoderma harzianum merupakan jenis cendawan nonmikoriza yang dapat ditemukan hampir di
semua macam tanah dan di berbagai habitat. Trichoderma
tumbuh sangat baik dan berlimpah di dalam tanah di
sekitar perakaran yang sehat dan bermanfaat dengan
menyerang patogen yang ada di sekitar perakaran
tanaman (Subba-Rao 1986 dalam Prabowo et al. 2006,
Wijaya 2002). Cendawan ini berperan pula sebagai
biodekomposer karena mampu memanfaatkan bahan
organik di alam terutama selulosa sebagai sumber
karbon dan energi untuk kebutuhan hidupnya (Harman
2001, Martin 1977 dalam Winarsih & Syafrudin 2001,
Widyastuti et al. 2001).
Cendawan T. harzianum diketahui mempunyai
kemampuan antagonis yang tinggi dalam menghambat
perkembangan cendawan patogen tular tanah. Mekanisme antagonis yang terjadi belum dapat dijelaskan
secara pasti, namun diperkirakan ada tiga fenomena
yang bekerja secara sinergis yaitu kompetisi ruang
tumbuh dan nutrisi, mekanisme antibiosis dan interaksi
sistem hifa. (Harjono & Widyastuti 2001a, Lorito
1998 dalam Harjono & Widyastuti 2001b, Sudheim
& Transmo 1987 dalam Winarsih & Syafrudin 2001).
Penelitian untuk mengkaji kemampuan T. harzianum
sebagai APH terutama dalam mengendalikan serangan Fusarium telah banyak dilaporkan. Penelitian
Suharjono et al. (2004) menginformasikan bahwa
kemampuan Trichoderma sp. (77,8%) lebih baik dari
Gliocladium sp. (73,3%) dalam mengendalikan
Fusarium pada tanaman pisang. Penelitian Prabowo
et al. (2006) membuktikan bahwa dengan penambahan
T. harzianum mampu menekan perkembangan cendawan F. oxysporum Schelect. f.sp. zingeberi Trijillo
pada tanaman kencur dengan hasil berkisar antara
7,9% sampai dengan 56,3%. Purnomo (2006) dalam
hasil penelitiannya menginformasikan bahwa Trichoderma sp. termasuk ke dalam cendawan yang memiliki
kemampuan untuk mengendalikan penyakit layu
Fusarium pada tanaman jahe.
Untuk itu dianggap perlu untuk melakukan suatu
penelitian guna mengetahui: 1) species Fusarium
Vol. 7, no. 2, DESEMBER 2010: 80 - 85
yang menyebabkan penyakit layu pada cabai; dan 2)
potensi antagonis T. harzianum terhadap Fusarium
spp., penyebab penyakit layu pada tanaman cabai.
Bahan Dan Metode
Isolat T. harzianum
Isolat T. harzianum diperoleh dengan cara mengambil
contoh tanah 100gram dari lima titik pengambilan
contoh yang ditentukan secara acak di sekitar perakaran tanaman cabai yang sehat pada kedalaman
0-20 cm. Contoh tanah kemudian dihomogenkan dan
dibuat larutan pengenceran (Dharmaputra 2001, Ernawati
2003). Proses pengenceran dilakukan sampai seri
pengenceran 10-3. Hasil dari tiap-tiap pengenceran 10-1,
10-2 dan 10-3 dipipet sebanyak 1 ml kemudian dituang
ke dalam media PDA dengan metode pour plate.
Media yang telah padat diinkubasi pada suhu ruang
(28oC) selama dua sampai lima hari (Ernawati 2003).
Isolat murni T. harzianum diperoleh dengan mengisolasi potongan agar berukuran 5x5 mm dari miselium
cendawan T. harzianum hasil identifikasi (metode
fragmentasi hifa) kemudian diinkubasi pada suhu ruang.
Peremajaan isolat dilakukan ketika isolat telah memenuhi cawan petri ( 7 hari).
Isolat Fusarium spp.
Isolat cendawan panyebab penyakit dilakukan
dengan cara mengoleksi jaringan tanaman yang menunjukkan gejala terserang cendawan Fusarium spp.
Jaringan akar, batang, daun, bunga, dan buah tersebut
diambil dan dimasukkan ke dalam kantong plastik
untuk dibawa ke laboratorium.
Identifikasi di laboratorium dilakukan untuk memastikan jenis OPT yang menyerang tanaman, terutama yang disebabkan oleh cendawan Fusarium
spp. Cara yang dilakukan untuk mengetahui penyebab
penyakit yang disebabkan oleh cendawan adalah dengan
mengorek bagian tanaman yang menunjukkan gejala
terserang penyakit dengan jarum dan dilihat di bawah
mikroskop (Imas & Setiadi 1987). Apabila cendawan
penyebab penyakit adalah Fusarium spp., maka diisolasi ke dalam media PDA.
Tahap identifikasi lanjut dilakukan pada bagian
tanaman yang tidak ditemukan spora yaitu dengan
cara bagian tanaman terserang penyakit dipotong
berukuran 1 cm kemudian dicuci dengan akuades
dan dibilas dengan alkohol 70%. Potongan tersebut
diisolasi ke dalam cawan petri yang beralaskan
kertas saring lembab dan diinkubasi pada suhu kamar
selama dua sampai dengan lima hari. Apabila terdapat hifa pada potongan tanaman, maka penyebab
penyakit adalah cendawan. Hifa cendawan ditumbuhkan pada media PDA dan diinkubasi selama
sekitar lima hari kemudian diidentifikasi untuk memastikan cendawan penyebab penyakit adalah cendawan Fusarium spp. Cendawan hasil identifikasi
selanjutnya diperbanyak dan diremajakan kembali
MUKARLINA ET AL.: Uji Antagonis Trichoderma Harzianum Terhadap Fusarium spp.
dengan metode fragmentasi hifa (5x5 mm) dari
cendawan Fusarium spp. dan ditumbuhkan di media
PDA dalam cawan petri (Agrios 1996, Imas & Setiadi
1987).
Uji Antagonis
Uji antagonis dilakukan dengan metode uji ganda,
yaitu potongan miselium isolat cendawan Fusarium
spp. asal jaringan tertentu dari tanaman cabai dengan
ukuran 5x5 mm dan potongan miselium isolat T. harzianum dengan ukuran 5x5 mm diletakkan di media
PDA dalam cawan petri berdiameter 90 mm. Jarak
antara kedua isolat tersebut 30 mm. Setiap perlakuan
mempunyai lima ulangan. Sebagai kontrol positif,
potongan miselium isolat murni T. harzianum ditumbuhkan di media PDA dalam cawan petri. Kontrol
negatif adalah berupa penanaman potongan miselium
Fusarium spp. di media PDA dalam cawan petri.
Pengamatan terhadap luas miselium T. Harzianum
dilakukan mulai hari ke-0 sampai dengan hari ke-7
(Winarsih & Syafrudin 2001).
Analisis Data
Luas miselium harian T. harzianum dan Fusarium spp. di media PDA dalam cawan petri dipetakan
dengan menggunakan program Corel Draw lalu
dihitung secara manual.
Persentase kemampuan antagonis T. harzianum
dalam mengendalikan Fusarium spp. pada masingmasing jaringan tanaman cabai dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Maryono 2007):
% antagonis = luas miselium T. harzianum pada hari
ke-7 (mm2) x 100% Luas ruang uji antagonis (mm).
Hasil dan Pembahasan
Isolat T. harzianum.
Cendawan T. harzianum diisolasi dari tanah di
sekitar perakaran tanaman cabai yang sehat kemudian
ditumbuhkan pada media PDA. Warna isolat mulamula putih kemudian berubah kehijauan pada pengamatan hari ke-3 dan menjadi hijau sampai hijau
gelap pada hari ke-7. Miselium T. harzianum tampak
seperti kapas dan telah memenuhi petri pada hari ke-5
dan hari ke-6. Menurut Raka (2006) dan Wijaya
(2002), miselium T. harzianum tumbuh dengan cepat
mencapai diameter pertumbuhan lebih dari 9 cm
82
dalam waktu lima hari pada media PDA atau OA.
Miselium mula-mula berwarna putih dengan permukaan halus seperti kapas, kemudian kehijauan
dan akhirnya berwarna hijau gelap.
Isolat Fusarium spp.
Eksplorasi cendawan Fusarium spp. dilakukan di
lokasi penanaman cabai dewasa, yaitu pada masa
berbunga dan berbuah. Berdasarkan hasil eksplorasi,
ditemukan beberapa organ dari tanaman cabai yang
menunjukkan gejala terserang penyakit Layu Fusarium,
yaitu pada organ batang, daun, bunga dan buah.
Menurut Mulyaman, et al. (2002), cendawan Fusarium
spp. dapat menyerang tanaman cabai mulai dari masa
perkecambahan sampai dewasa. Meskipun dikenal
sebagai patogen tular tanah, cendawan ini dapat juga
menginfeksi bagian tanaman lainnya. Hal ini dikarenakan penularan penyakit selain dengan spora
yang terdapat di dalam tanah dapat juga dengan
spora yang terbawa angin dan air kemudian menginfeksi tanaman melalui luka.
Berdasarkan hasil identifikasi terhadap isolat cendawan yang menginfeksi organ-organ pada tanaman
cabai, diketahui terdapat dua spesies Fusarium yang
menginfeksi organ-organ tanaman cabai, yaitu F.
sambucinum yang menginfeksi batang, daun, bunga
dan buah; dan F. oxysporum yang menginfeksi daun.
Uji Antagonis
Hasil pengamatan dan perhitungan rerata luas
miselium T. harzianum dalam uji antagonis in vitro
mulai dari hari ke-0 sampai hari ke-7 dapat dilihat
pada Gambar 1. Luas miselium T. Harzianum dalam
setiap perlakuan uji antagonis bervariasi. Rerata luas
miselium T. harzianum terendah adalah pada uji
antagonis terhadap F. sambucinum pada daun (4441
mm2), selanjutnya pada uji antagonis terhadap F.
sambucinum pada buah (4979 mm2) dan pada uji
antagonis terhadap F. oxysporum pada daun (5066 mm2).
Rerata luas miselium T. harzianum pada uji antagonis terhadap F. sambucinum pada bunga (5334
2
mm ) dan pada uji antagonis terhadap F. oxysporum
2
pada batang (5879 mm ).
Miselium T. harzianum dalam uji antagonis terhadap Fusarium spp. belum memenuhi ruang uji pada
hari terakhir pengamatan. Hal ini diduga disebabkan
83
JURNAL FITOMEDIKA
adanya persaingan ruang tumbuh dan nutrisi. Persaingan terjadi ketika terdapat dua mikroorganisme
atau lebih yang secara langsung memerlukan sumber
nutrisi yang sama (Soesanto 2008, Maryono 2007,
dan Raka 2006). Persaingan yang terlihat di ruang uji
antagonis antara T. harzianum dan Fusarium spp.
disebabkan adanya kebutuhan cendawan-cendawan
tersebut akan nutrisi yang terkandung di dalam
media uji antagonis untuk keber langsungan hidupnya
yaitu berupa karbohidrat, protein, asam amino esensial,
mineral dan elemen-elemen mikro seperti fosfor (P),
magnesium (Mg) dan Kalium (K), vitamin C (asam
askorbat), beberapa vitamin B (tiamin, niasin, vitamin
B6). Karbohidrat dan gula memiliki peran sebagai
sumber karbon untuk menghasilkan energi dan juga
untuk biosintesis senyawa-senyawa karbon. Karbohidrat dirombak menjadi asam oganik tertentu dan
karbon dioksida. Perombakan ini melibatkan enzim
ekstraseluler yang terikat di dinding sel dan hanya
beberapa organisme tanah saja yang dapat melakukan perombakan tersebut, salah satunya adalah T.
harzianum (Chalvignac 1953 dalam Imas & Setiadi,
1987). Gula dan karbohidrat dimanfaatkan oleh T.
harzianum sebagai sumber karbon yang memiliki
peran sebagai prekursor dari metabolit sekunder
untuk menghambat perkecambahan spora cendawan
patogen (Soesanto 2008, Maryono 2007, Hilme &
Shark 1970 dalam Suwahyono 2000). Miselium T.
harzianum cenderung lebih luas dibandingkan miselium Fusarium spp. diduga karena adanya kemampuan T. harzianum untuk menghasilkan asam
organik tertentu yang tidak dapat dimanfaatkan Fusarium spp. serta adanya kemampuan dari T. harzianum
untuk menghasilkan metabolit sekunder berupa antibiotika yang bersifat menghambat perkecambahan
spora cendawan Fusarium spp. (Soesanto 2008,
Suwahyono 2000).
T. harzianum menghasilkan beberapa antibiotik,
di antaranya antibiotik peptaibol yang bekerja secara
sinergis dengan enzim (1,3) glukanase, senyawa 3(2-hidroksipropil)-4-(2-heksadienil)-2(5H) furanon
yang membantu proses penghambatan terhadap F.
oxysporum dan senyawa alkil piron (6-n-pentil-2Hpiran-2-on atau 6PP) yang bersifat fungistasis dan
mampu mengubah penyebaran biomassa cendawan
dengan kisaran luas. Asam amino bebas seperti asam
aspartat, asam glutamat, alanin, leusin dan valin serta
dua senyawa ninhidrin positif lainnya yang dihasilkan
T. harzianum secara in vitro juga dapat menurunkan patogenitas cendawan patogen (Soesanto 2008,
Suwahyono 2000).
Antagonis T. harzianum terhadap Fusarium spp.
diduga turut melibatkan mekanisme mikoparasitisme.
T. harzianum mulai membentuk cabang-cabang hifa
yang tumbuh ke arah Fusarium spp. pada tahap pertumbuhan kemotrof. Tahap pengenalan bersifat khusus
yaitu cendawan antagonis hanya menyerang patogen
Vol. 7, no. 2, DESEMBER 2010: 80 - 85
tertentu. Pertumbuhan miselium T. harzianum ke
arah miselium patogen distimulasi oleh adanya protein
-lektin yang berikatan dengan kitin penyusun dinding sel patogen. Selanjutnya, pada tahap pelekatan,
hifa cendawan T. harzianum dapat tumbuh sepanjang
hifa inang atau membelit di sekeliling hifa inang.
Taju penetrasi yang terbentuk dari hifa T. harzianum
akan melubangi dinding sel atau memecah dinding
sel Fusarium spp. Dengan memproduksi enzim pada
tahap penguraian dinding sel inang (Soesanto 2008).
Imas dan Setiadi (1987) menjelaskan bahwa
dinding sel Fusarium mengandung kitin yang dilindungi oleh lapisan-lapisan glukan. Berdasarkan
struktur tersebut, pada tahap penguraian atau lisis
dinding sel cendawan Fusarium spp., T. harzianum
diduga menghasilkan enzim (1,3) glukanase terlebih
dahulu untuk merombak lapisan glukan menjadi
senyawa gula yang lebih sederhana dan selanjutnya
T. harzianum menghasilkan enzim kitinase untuk
merombak kitin menjadi monomer N-asetilglukosamin.
Hasil persentase antagonis T. harzianum terhadap
Fusarium spp. dapat dilihat pada Tabel 1. Persentase
antagonis terendah taitu 71,2 % terjadi pada uji
antagonis in vitro T. harzianum terhadap F. sambucinum
pada daun. Hal ini diduga disebabkan oleh tingginya
kemampuan kompetisi dan pertumbuhan miselium
dari isolat murni F. sambucinum yang berasal dari
daun. Berdasarkan hasil pengamatan luas miselium
harian, pertumbuhan isolat F. sambucinum yang diisolasi dari daun paling baik jika dibandingkan
dengan pertumbuhan miselium Fusarium spp. yang
diisolasi dari organ lainnya.
Kemampuan kompetisi yang lebih tinggi dari F.
sambucinum yang diisolasi dari daun diduga didukung
oleh faktor lingkungan biotik tempat isolat cendawan
ini berasal. Menurut Campbell et al. (2002) miselium
cendawan tumbuh dengan sangat cepat sesuai dengan
banyaknya molekul organik yang diserapnya dari
medium tumbuhnya. Daun merupakan organ terpenting
bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena
karbohidrat, air, oksigen, energi dan molekul organik
lainnya yang dibutuhkan tanaman dihasilkan melalui
proses fotosintesis, transpirasi dan respirasi yang
terjadi pada daun. Molekul organik dimanfaatkan
sebagai sumber nutrisi diantaranya untuk untuk
pembentukan dinding sel hifa.
Biosintesis kitin sebagai bahan utama penyusun
dinding sel hifa pada cendawan diawali dengan perubahan glukosa-6-fosfat hasil fotosintesis menjadi
uridin difosfat N-asetilglukosamin sebagai prekursor kitin.
Pengabsorbsian molekul organik yang optimal oleh
F. sambucinum yang menginfeksi organ daun akan
mengoptimalkan pula pembentukan dinding sel hifa
cendawan tersebut, misalnya pembentukan dinding
sel yang semakin kompak (rapat) dan tebal. Dinding
sel hifa yang kompak dan tebal diduga menjadi pertahanan cendawan F. sambucinum ketika menghadapi
MUKARLINA ET AL.: Uji Antagonis Trichoderma Harzianum Terhadap Fusarium spp.
84
Tabel 1. Rerata persentase antagonis in vitro T. harzianum terhadap Fusarium spp.
Isolat
T.
T.
T.
T.
T.
T.
harzianum (isolat murni/kontrol)
harzianum terhadap F. sambucinum pada batang
harzianum terhadap F. sambucinum pada bunga
harzianum terhadap F. oxysporum pada daun
harzianum terhadap F. sambucinum pada buah
harzianum terhadap F. sambucinum pada daun
serangan dari T. harzianum. T. harzianum membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mematikan
inangnya dalam proses mikoparasitisme maupun dalam
proses antibiosis.
Kesimpulan dan Saran
T. harzianum dalam kondisi in vitro mampu menekan pertumbuhan Fusarium spp. yang menginfeksi tanaman cabai dengan persentase antagonis
yang bervariasi, yaitu :
a. Fusarium sambucinum yang diisolasi dari jaringan
batang mampu dikendalikan secara in vitro dengan
persentase antagonis 94,2%.
b. Fusarium sambucinum yang diisolasi dari jaringan
bunga mampu dikendalikan secara in vitro dengan
persentase antagonis 85,5%.
c. Fusarium oxysporum yang diisolasi dari jaringan
daun mampu dikendalikan secara in vitro dengan
persentase antagonis 81,2%.
d. Fusarium sambucinum yang diisolasi dari jaringan
buah mampu dikendalikan secara in vitro dengan
persentase antagonis 79,8%.
e. Fusarium sambucinum yang diisolasi dari organ
buah mampu dikendalikan secara in vitro dengan
persentase antagonis 71,2%.
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara in
vivo terhadap keefektifan T. harzianum dalam mengendalikan F. sambucinum dan F. oxysporum yang menginfeksi organ-organ tanaman cabai.
Daftar Pustaka
Agrios, G. N. 1996. Ilmu Penyakit Tumbuhan (Edisi
ke-3). Terjemahan oleh M. Busnia, 1997. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Campbell, N. A., J. B. Reece, L. G.. Mitchell. 2002.
Biologi, Jilid I, Edisi Kelima, Erlangga,. Jakarta.
Dharmaputra, O. S., A. S. R. Putri, I. Retnowati,
dan S. Ambarwati. 2001. Soil Mycobiota of Peanut
Field in Wonogiri Regency Central Java: Their
Effect on the Growth and Aflatoxin Production of
Aspergillus flavus In Vitro, J. Biotropia, Seameo
Biotrop, Bogor.
Ernawati. 2003. Potensi Mikroorganisme Tanah
Antagonis Untuk Menekan Pseudomonas sollanacearum pada Tanaman Pisang Secara in Vitro Di
Pulau Lombok. Makalah Falsafah Sains Program
Rerata
Persentase Antagonis
(%)
94,2
85,5
81,2
79,8
71,2
Pasca Sarjana (S3).
Harjono dan Widyastuti, S. M. 2001. Optimasi
Produksi Endokitinase dari Jamur Mikroparasit
Trichoderma reesei. J. Perlindungan Tanaman
Indonesia, 7(1):55-58,
Imas, T. dan Y. Setiadi. 1987. Mikrobiologi Tanah,
Pusat Antar Universitas-IPB. Bogor.
A. Machmud, M., M. Sudjadi, dan Y. Suryadi. 2003.
Seleksi dan Karakterisasi Mikroba Antagonis
http://www.indobiogen.or.id/terbitan/prosiding/
fulltext_pdf/prosiding2003_118_127_machmud_
antagonis.pdf. Diakses September 2008).
Maryono T. 2007. Uji Antagonis Trichoderma sp.
Terhadap Phytophthora palmivora Penyebab
Busuk Buah Kakao, http://www.digilib.unila. ac.id/
laptunilapp_gdlres.2008_trimaryono_1228_.
Diakses 16 Oktober 2008).
Mulyaman., S. Sukamto, A. Kustaryati, dan U.
Damiati. 2002. Hasil Identifikasi dan Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman
Sayur, Dirjen Bina Produksi Hortikultura Direktorat
Perlindungan Hortikultura.
Prabowo, A. K. E., N. Prihatiningsih dan L. Soesanto.
2006. Potensi Trichoderma harzianum Dalam
Mengendalikan Sembilan Isolat Fusarium oxysporum Schelecht. f. sp. zingiberi Trijillo Pada
Kencur, J. Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia, 8(2):
76-84.
Purnomo, B. 2006. Seleksi Jamur Rizosfer NonPatogenik Untuk Pengendalian Penyakit Layu
Fusarium Pada Tanaman Jahe Di Bengkulu. J.
Ilmu-ilmuPertanian Indonesia, 8(1):6-11.
Raka, I. G.2006. Eksplorasi dan Cara Aplikasi
Agensia Hayati Trichoderma sp. Sebagai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT),
Dinas Pertanian Tanaman Pangan UPTD Balai
Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bali.
Semangun, H.1996. Penyakit-Penyakit Tanaman
Hortikultura Di Indonesia. Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta.
Semangun, H. 2000. Penyakit-Penyakit Tanaman
Hortikultura Di Indonesia, Cetakan ke-4, Gadjah
Mada University Press, Yogyakart.
Soesanto, L.2008. Pengantar Pengendalian Hayati
Penyakit Tanaman, Rajawali Pers, Jakarta.
Suharjono., T.H. Kurniati, Soejono dan S. Dewi.
2004. Uji Antagonis Trichoderma sp. dan Glioc-
85
JURNAL FITOMEDIKA
ladium sp. terhadap Fusarium Penyebab Penyakit
Layu pada Beberapa Jenis Tanaman Pisang di
Kebun Raya Purwodadi secara in-vitro http://www2.
uajy.ac.id/biota/abstrak%5C2004-2-9.doc.
Diakses 15 Desember 2008.
Suwahyono, U. 2000. Pengendalian Penyakit Tanaman
Secara Mikrobiologis: Menuju Komunitas Berkelanjutan, J. NEED: Lingkungan Manajemen
Ilmiah, 2(8).
Syamsuddin. 2003. Pengendalian Penyakit Terbawa
Benih (Seedborne Diseases) Pada Tanaman Cabai
(Capsicum annum L.) Menggunakan Agenbiokontrol Dan Ekstrak Botani, www.tumotou.net/
702_07134/syamsuddin.htm. Diakses 15 Desember
2008.
Widyastuti, S. M., Sumardi dan P. Sumantoro. 2001.
Efektifitas Trichoderma spp. Sebagai Pengendali
Hayati Terhadap Tiga Patogen Tular Tanah Pada
Beberpa Jenis Tanaman Kehutanan, J. Perlindungan
Tanaman Indonesia, 7(2):98-107.
7, no. 2, DESEMBER 2010: 80 - 85
Wijaya, S. K. S. 2002. Isolasi Kitinase dari Scleroderma
columnare dan Trichoderma harzianum, J. Ilmu
Dasar, 3(1):30-35.
Winarsih, S. dan Syafrudin. 2001. Pengaruh
Pemberian Trichoderma viridae Dan Sekam Padi
Terhadap Penyakit Rebah Kecambah Di Persemaian Cabai. J. Ilmu-Ilmu Pertanian, 3(1): 4955.
Yurnaliza. 2002. Senyawa Kitin dan Kajian Aktifitas
Enzim Mikrobial Pendegradasinya, USU Digital
Library,http:www.library.usu.ac.id/download/
fmipa/bilogi_yurnaliza2.pdf. Diakses 17 Januari
2009.
Zahara, H. dan L. H. Harahap. 2007. Identifikasi
Jenis Cendawan Pada Tanaman Cabai (Capsicum
annum), http://www.bbkt-belawan. info/pdf/karya_
tulis/cendawan.pdf. Diakses 3 September 2008).
Diterima tanggal 15 Maret 2010; disetujui untuk di publikasi
tanggal 20 Juni 2010
You might also like
- Interprofessional Collaboration in Advance Practice Nursing: Angela Morgan-Young Mn501 Unit 4 AssignmentDocument10 pagesInterprofessional Collaboration in Advance Practice Nursing: Angela Morgan-Young Mn501 Unit 4 AssignmentEarthangel Angie100% (1)
- Program at Glance WECOC 2021-Updated Juli 2021Document1 pageProgram at Glance WECOC 2021-Updated Juli 2021Bambang SupriadiNo ratings yet
- Tensiómetros Jet Fill Soilmoisture® 2011Document7 pagesTensiómetros Jet Fill Soilmoisture® 2011linaNo ratings yet
- THE SANDMAN by Lars Kepler - ExtractDocument12 pagesTHE SANDMAN by Lars Kepler - ExtractAnonymous ikUR753am0% (1)
- NNDrugsAidsDocument96 pagesNNDrugsAidslosangelesNo ratings yet
- Antagonisme Trichoderma Spp. Terhadap Jamur Rigidoporus Lignosus PD Karet PDFDocument9 pagesAntagonisme Trichoderma Spp. Terhadap Jamur Rigidoporus Lignosus PD Karet PDFArgus SavageNo ratings yet
- UJI VIABILITAS POLEN JERNANG (Daemonorops Draco (Willd.) Blume.) DENGAN TEKNIK PEWARNAAN DAN GERMINASI SECARA in Vitro SETELAH DIAWETKAN DALAM BEBERAPA PELARUT ORGANIKDocument12 pagesUJI VIABILITAS POLEN JERNANG (Daemonorops Draco (Willd.) Blume.) DENGAN TEKNIK PEWARNAAN DAN GERMINASI SECARA in Vitro SETELAH DIAWETKAN DALAM BEBERAPA PELARUT ORGANIKImas-hendryNo ratings yet
- Hatch and Carry Technique For Increasing Oil Palm Fruit Set: Elaeidobius Kamerunicus: APPLICATION OFDocument8 pagesHatch and Carry Technique For Increasing Oil Palm Fruit Set: Elaeidobius Kamerunicus: APPLICATION OFHilman ManurungNo ratings yet
- TT 501Document0 pagesTT 501perico1962No ratings yet
- Elaeidobius KamerunicusDocument56 pagesElaeidobius Kamerunicussyu100% (1)
- Mucuna BracteataDocument4 pagesMucuna BracteataIsya ApriliyanaNo ratings yet
- 4.R. FertilizerDocument10 pages4.R. FertilizerSaqlain HameedNo ratings yet
- Manajemen Pengendalian Gulma Kelapa Sawit BerdasarDocument10 pagesManajemen Pengendalian Gulma Kelapa Sawit Berdasarmaydya arismaNo ratings yet
- Kelapa SawitDocument8 pagesKelapa Sawithutbunbanyuasin100% (2)
- Palm Oil Mill EffluentDocument6 pagesPalm Oil Mill Effluentankitsaxena123100% (2)
- Indonesian Palm Oil Smallholders - Briefing PaperDocument11 pagesIndonesian Palm Oil Smallholders - Briefing PaperSri Wahyudi100% (1)
- Modern Oil Palm CultivationDocument12 pagesModern Oil Palm CultivationLip Hock Chan100% (1)
- 2017 Book GeneticImprovementOfTropicalCr PDFDocument331 pages2017 Book GeneticImprovementOfTropicalCr PDFMaya FadhillahNo ratings yet
- Module 3 3rd Edition 2016 08 Oil PlamDocument57 pagesModule 3 3rd Edition 2016 08 Oil PlamjingsiongNo ratings yet
- Ganoderma Boninsense of Oil Palm - DR Richard CooperDocument12 pagesGanoderma Boninsense of Oil Palm - DR Richard CooperRichar Manuel Simanca FontalvoNo ratings yet
- Replanting Program For IndonesianDocument17 pagesReplanting Program For IndonesianKonco TaniNo ratings yet
- Palm Oil Mill by ProductDocument14 pagesPalm Oil Mill by ProductSulaiman FairusNo ratings yet
- Co-Composting of Palm Oil Mill WasteDocument6 pagesCo-Composting of Palm Oil Mill Wasteedison58No ratings yet
- Oil Palm Nutrient Deficiency SymptomsDocument7 pagesOil Palm Nutrient Deficiency Symptomsdwikadhi100% (1)
- C3 Field Planting PDFDocument102 pagesC3 Field Planting PDFAmirul Fathi100% (1)
- Bananas WordDocument2 pagesBananas WordMoechanis HidayatNo ratings yet
- Integrated Weed Management of OP 2008Document56 pagesIntegrated Weed Management of OP 2008عبدالحاليم بودين83% (6)
- Family: Palmae Scientific Name: Elaeis GuineensisDocument124 pagesFamily: Palmae Scientific Name: Elaeis GuineensisRosita MatsaidinNo ratings yet
- Uum PPT 8 Diseases and Their ManagementDocument77 pagesUum PPT 8 Diseases and Their Managementzakuan790% (1)
- Oil Palm Fertilization - Sharing Some PerspectivesDocument7 pagesOil Palm Fertilization - Sharing Some PerspectivesLucy LimNo ratings yet
- ID Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kelapa Sawit Rakyat Di KabupatDocument10 pagesID Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kelapa Sawit Rakyat Di KabupatMuhammad AfdalNo ratings yet
- Oil PalmDocument131 pagesOil PalmfaradayzzzNo ratings yet
- Oil Palm IndonesiaDocument28 pagesOil Palm Indonesiawahyu100% (1)
- Hama Dan Penyakit Kelapa SawitDocument3 pagesHama Dan Penyakit Kelapa SawitNopi MulyantoNo ratings yet
- A General Review of Palm Oil Mill EffluentDocument3 pagesA General Review of Palm Oil Mill EffluentMykel-Deitrick Boafo DuoduNo ratings yet
- A Guide To Palm Oil in IndonesiaDocument87 pagesA Guide To Palm Oil in IndonesiaclarissaNo ratings yet
- Jurnal ResurgensiDocument10 pagesJurnal ResurgensiIlonaNo ratings yet
- Standard For Essential Composition of VCO PDFDocument11 pagesStandard For Essential Composition of VCO PDFUbais AliNo ratings yet
- MetarhiziumDocument16 pagesMetarhiziumjawad_ali1No ratings yet
- A12 WcaDocument92 pagesA12 WcaAndi Alfian HutagalungNo ratings yet
- Kelimpahan Populasi Dan Persentase Serangan Lalat Buah (Bactrocera SPP.) (Diptera: Tephritidae) Pada Tanaman Mentimun (Cucumis Sativus L.) Di Beberapa Kabupaten Provinsi BaliDocument9 pagesKelimpahan Populasi Dan Persentase Serangan Lalat Buah (Bactrocera SPP.) (Diptera: Tephritidae) Pada Tanaman Mentimun (Cucumis Sativus L.) Di Beberapa Kabupaten Provinsi BaliarghaNo ratings yet
- Organisme Pengganggu TanamanDocument26 pagesOrganisme Pengganggu TanamanLydia OktavianiNo ratings yet
- Presentasi RILO - Sosialisasi RSPO Di BSP - 7 Apr08Document27 pagesPresentasi RILO - Sosialisasi RSPO Di BSP - 7 Apr08Karis SyaputraNo ratings yet
- GamalDocument11 pagesGamalAnonymous DxKiceCnuw100% (1)
- Deskriptor Kacang PanjangDocument3 pagesDeskriptor Kacang PanjangM.Iqbal. W100% (1)
- Manajemen Pemeliharaan Burung PuyuhDocument54 pagesManajemen Pemeliharaan Burung PuyuhKang U CinNo ratings yet
- Kelapa SawtDocument113 pagesKelapa SawtKasmir NasutionNo ratings yet
- Pupuk Hayati (Biofertilizers) Dan PGPR (Plan Growth PromotingDocument48 pagesPupuk Hayati (Biofertilizers) Dan PGPR (Plan Growth PromotingIndra DiRa PermanaNo ratings yet
- 5 Factors Affecting Morphogenesis in VitroDocument20 pages5 Factors Affecting Morphogenesis in VitroAlec Liu0% (3)
- Analisis Faktor Yang Memengaruhi Produktivitas Kelapa Di Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon ProgoDocument10 pagesAnalisis Faktor Yang Memengaruhi Produktivitas Kelapa Di Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progosulistyo jogjaNo ratings yet
- Development of A Palm Fruit Bunch Chopper and Spikelet StripperDocument7 pagesDevelopment of A Palm Fruit Bunch Chopper and Spikelet Stripperinventionjournals100% (1)
- Jurnal Internasional Tomat PDFDocument8 pagesJurnal Internasional Tomat PDFPrimaldo marmoraNo ratings yet
- Research Paper Etl Esi Ije - 82Document301 pagesResearch Paper Etl Esi Ije - 82DWARKA PRASAD ATHYANo ratings yet
- Promoting Growth With PGPRDocument3 pagesPromoting Growth With PGPRbansoy03_02719No ratings yet
- ResistanceDocument1 pageResistanceisamat07No ratings yet
- The Diffusion of Methionine in Water HyacinthDocument5 pagesThe Diffusion of Methionine in Water HyacinthNicole Corteza100% (1)
- Coconut Cultivation TechnologyDocument24 pagesCoconut Cultivation Technologypriya selvarajNo ratings yet
- Ratnasari & Cintamulya, 2021Document10 pagesRatnasari & Cintamulya, 2021A R CANDY POTOTNo ratings yet
- Ta Jilid 1Document71 pagesTa Jilid 1Wisnu IndraNo ratings yet
- The Coconut PalmDocument21 pagesThe Coconut PalmRajeNurNabiehaNo ratings yet
- UITM Mechanical ResearchDocument89 pagesUITM Mechanical ResearchFauzan ZakariaNo ratings yet
- Ubat Tradisional Kunyit HitamDocument5 pagesUbat Tradisional Kunyit HitamHazilah AbdullahNo ratings yet
- Genebank Standards for Plant Genetic Resources for Food and AgricultureFrom EverandGenebank Standards for Plant Genetic Resources for Food and AgricultureNo ratings yet
- Fusarium Wilt Disease Control With Trichoderma Sp. On Two Varieties of TomatoesDocument6 pagesFusarium Wilt Disease Control With Trichoderma Sp. On Two Varieties of TomatoesHerold Riwaldo SitindaonNo ratings yet
- Neurological Monitoring During Cardiopulmonary BypassDocument22 pagesNeurological Monitoring During Cardiopulmonary BypassSashivaraman RajanNo ratings yet
- Safety and Healty MGT 340Document4 pagesSafety and Healty MGT 340Imam FatihahNo ratings yet
- A Nomogram For Lateral Lymph Nodes That Have MetasDocument12 pagesA Nomogram For Lateral Lymph Nodes That Have MetasAbo-ahmed ElmasryNo ratings yet
- Measured-Removal-Rates PDFDocument16 pagesMeasured-Removal-Rates PDFCristian David VargasNo ratings yet
- Human Dignity, Rights and Common GoodDocument95 pagesHuman Dignity, Rights and Common GoodJerry De Leon LptNo ratings yet
- Tugas Bahasa Inggris SINDYDocument7 pagesTugas Bahasa Inggris SINDYSindy yolandaNo ratings yet
- Ubc 2011 Fall Peralta ChristineDocument70 pagesUbc 2011 Fall Peralta ChristineKristine PuenteNo ratings yet
- Handbook: #Think Digital Think IndiaDocument11 pagesHandbook: #Think Digital Think IndiaChirag TrivediNo ratings yet
- 05 - Weekly Safety Audit and Inspection ReportDocument4 pages05 - Weekly Safety Audit and Inspection ReportGyanendra Narayan NayakNo ratings yet
- Grade 7 PE DLL Week 2Document9 pagesGrade 7 PE DLL Week 2Pagsibigan PONo ratings yet
- External and Internal Transfer ProcessDocument18 pagesExternal and Internal Transfer Processshadi alshadafanNo ratings yet
- Theuseofthe Operating Microscopein Endodontics: Gary B. Carr,, Carlos A.F. MurgelDocument24 pagesTheuseofthe Operating Microscopein Endodontics: Gary B. Carr,, Carlos A.F. MurgelVidhi ThakurNo ratings yet
- Readers Digest Asia Feburary 2021Document134 pagesReaders Digest Asia Feburary 2021FURY FURIONNo ratings yet
- Multi-Source Feedback: 360 Team Assessment of Behaviour (TAB)Document3 pagesMulti-Source Feedback: 360 Team Assessment of Behaviour (TAB)craig101No ratings yet
- IGS 1104 Final Exam 2020 PRINTDocument3 pagesIGS 1104 Final Exam 2020 PRINTchristinemomanyi616No ratings yet
- Dental 3D PrintingDocument1 pageDental 3D Printing3D2GO PhilippinesNo ratings yet
- Cystic Fibrosis (CF) Gene Mutations Testing - LabDocument2 pagesCystic Fibrosis (CF) Gene Mutations Testing - LabHiwa SanAhmedNo ratings yet
- Kindergarten DLL Week 25Document6 pagesKindergarten DLL Week 25Monina ApalNo ratings yet
- Unit IB1: Principles of Chemical Control, Toxicology and EpidemiologyDocument41 pagesUnit IB1: Principles of Chemical Control, Toxicology and Epidemiologysamer alrawashdeh100% (1)
- E-Learning - and - CST - Status - For - Personnel - On - Board - EBKKDocument10 pagesE-Learning - and - CST - Status - For - Personnel - On - Board - EBKKHarman SandhuNo ratings yet
- Core CompetenciesDocument4 pagesCore CompetenciesKris PitmanNo ratings yet
- D-Eminence ProfileDocument3 pagesD-Eminence ProfilemydeargauravNo ratings yet
- The New Method: A Modern Man's Guide To Ecstasy AKA Ecstacy Rock MethodDocument81 pagesThe New Method: A Modern Man's Guide To Ecstasy AKA Ecstacy Rock MethodFarfaraway1No ratings yet
- Dental Medical CertificateDocument1 pageDental Medical CertificateScribdTranslationsNo ratings yet
- Root Cause Analysis BasicDocument7 pagesRoot Cause Analysis BasicGianfrancoMangiapaneNo ratings yet
- Vanshika Kalpeshbhai SolankiDocument1 pageVanshika Kalpeshbhai Solankilab oswalaayushNo ratings yet