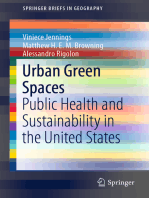Professional Documents
Culture Documents
Aplikasi Infrastruktur Data Spasial Nasional, IDSN Untuk Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, Studi Kasus Di Kab Sanggau Kalbar PDF
Aplikasi Infrastruktur Data Spasial Nasional, IDSN Untuk Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, Studi Kasus Di Kab Sanggau Kalbar PDF
Uploaded by
Dewa WadeOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Aplikasi Infrastruktur Data Spasial Nasional, IDSN Untuk Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, Studi Kasus Di Kab Sanggau Kalbar PDF
Aplikasi Infrastruktur Data Spasial Nasional, IDSN Untuk Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, Studi Kasus Di Kab Sanggau Kalbar PDF
Uploaded by
Dewa WadeCopyright:
Available Formats
Aplikasi Infrastruktur Data Spasial Nasional..- B.J. Pratondo..et.
al
APLIKASI INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL NASIONAL
(IDSN) UNTUK PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN
(Studi Kasus di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)
Application of National Spatial Data Infrastructure (NSDI) for Forest and
Land Fires Control (Case study in Regency of Sanggau West Kalimantan)
Oleh :
B.J. Pratondo1, Hadi S. Alikodra2, Bambang H. Sahardjo2, Priyadi Kardono3
ABSTRACT
The study is aim to find out the application of National Spatial Data Infrastructure (NSDI)
for Forest and Land Fires control in Regency of Sanggau West Kalimantan. The data are collected
by secondary and primary data resources. Primary data are collected by indepth interview and
questioner. Secondary data are collected by documentation technique. The spatial are collected
from custodian.There are same analysis technique to be used in this research that are spatial
analysis to identified sensitivity rate by using GIS, policy analysis and institution to formulate using
data strategy by PRA and FGD. To determine priority strategy by AWOT. IDSN Development is
conducted by improving seven data infrastructure functions: data development, data maintanance,
data integration, data access, data management, coordination, guidelines, resources management,
monitoring and evaluation. The sensitivity of forest and land fire are determine in three factors;
physical factor: that are soil classification, geology, landscape, activity factors: land use and forest
status and accessibility factor: distance to settlement, distance to road and distance to river. The
value of sensitivity of land and forest fire are not sensitive (24,64%), less sensitive (31,10%),
rather sensitive (22,64%), sensitive (11,50%) and very sensitive (2,74%). To implement IDSN
framework in order to control and mitigate land and forest fire are done in same steps: identified
custodian, data standarizied, data sharing, acquisition, and partnership.
Keywords : NSDI, forest fires and land, spatial data, sensitivity, policy and institution
PENDAHULUAN
Infrastruktur data spasial nasional (IDSN) merupakan suatu terobosan baru
untuk memudahkan setiap orang mengakses data spasial. Sasaran IDSN adalah untuk
memudahkan pengguna data spasial menggunakan dataset secara konsisten sesuai
dengan kebutuhan, meskipun data dikumpulkan oleh berbagai pihak/instansi yang
berbeda. Implementasi IDSN memerlukan insfrastruktur yang solid berdasarkan
kebijakan dan manajemen, sumberdaya manusia dan teknologi, dan berbagai hal yang
1
2
3
Mahasiswa S3 program studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) IPB
Dosen pascasarjana pada program studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) IPB
Peneliti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
62
Jurnal Ilmiah Geomatika Vol.12 No.2 Desember 2006
memungkinkan data spasial dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Infrastruktur
ini dapat dibandingkan dengan pelayanan fasilitas umum seperti, jalan, kereta api,
jaringan listrik (ASDI, 2003). Konsep IDSN tidak untuk membangun pusat database
tetapi untuk membangun jaringan distribusi database yang dikelola oleh pemerintah dan
industri kustodian.
Data spasial dikenal sebagai data geospasial atau informasi geografi. IDSN
berperan dalam perolehan dan penyebarluasan informasi spasial (Bakosurtanal, 2004).
Dalam penerapan infrastruktur data spasial nasional memerlukan sebuah infrastruktur
yang berperan dalam interkoneksi basis data terdistribusi dengan pemanfaatan
informasi, komputer dan teknologi. Data spasial dapat menunjang sistem sebagai upaya
dalam menghasilkan informasi tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan
perspektif pengguna, pengadaan data merupakan salah satu kegiatan yang memerlukan
biaya tinggi dan alokasi waktu yang cukup lama. Oleh karena itu konsep berbagi data
dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas (FGDC, 2004).
Banyak organisasi dan pemerintahan telah melakukan investasi besar dalam
pengumpulan data spasial. Data ini adalah asset nasional yang penting untuk
pengambilan keputusan. Pengelolaan informasi ini telah menjadi perhatian utama bagi
negara maju. Di USA tahun 1994, presiden menandatangani perintah khusus untuk
koordinasi akuisisi dan akses data geografi National Spatial Data Infrastructure (OMB,
2005), Canada telah mengembangkan Canadian Geospatial Data Infrastructure, dan
Australia mengembangkan Australian Spatial Data Infrastructure.
Data spasial digunakan dalam berbagai hal yang luas seperti aplikasi ekonomi,
sosial, dan lingkungan seperti: penilaian dan pengelolaan lingkungan, pengelolaan
sumberdaya - pertanian, pertambangan, energi, kehutanan dan kelautan, eksplorasi dan
pengambilan keputusan, cepat tanggap pelayanan darurat, manajemen bencana berupa
pelayanan darurat menggunakan data spasial dalam manajemen bencana seperti
kebakaran, banjir dan untuk membantu mereka memprediksi dampak kejadian (ANZLIC,
2003).
Tingkat kerentanan kebakaran hutan dan lahan merupakan informasi untuk
pencegahan dan analisis terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Salah satu upaya yang
penting untuk dilakukan adalah mengetahui secara dini keadaan lapangan (hutan dan
lahan) sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pemanfaatan data penginderaan jauh
adalah fase yang terkait dengan manajemen kebakaran ini sendiri seperti: deteksi,
pemadaman dan pemetaan areal terbakar. Semakin berkembangnya pemanfaatan SIG
diikuti pula dengan meningkatnya kegiatan pengadaan data. Kemajuan teknologi
komputer, komunikasi dan perangkat lunak SIG telah banyak membantu pengelola hutan
untuk mengelola data hot spot yang diterima dari stasiun penerima (Masser, 2005).
Salah satu persoalan lingkungan yang muncul hampir setiap tahun di Indonesia
terutama pasca tahun 2000 adalah kebakaran hutan, termasuk di wilayah pulau
Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bentuk bencana yang
makin sering terjadi, dan dampak yang ditimbulkan sangat merugikan bila dilihat dari
aspek fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi maupun aspek ekologi (Syumanda, 2003).
Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan menyebabkan menurunnya keanekaragaman
hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro
maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu
transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara (Sahardjo, 2003).
63
Aplikasi Infrastruktur Data Spasial Nasional..- B.J. Pratondo..et.al
Untuk menangani permasalahan tersebut telah dibentuk kelembagaan di tingkat
pusat dan daerah dalam bentuk satuan koordinasi. Namun hingga saat ini belum efektif
menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Informasi mengenai tingkat
kerentanan kebakaran hutan dan lahan di tingkat Kabupaten Sanggau belum dapat
dimanfaatkan untuk deteksi dini. Demikian pula dengan data spasial mengenai kondisi
lahan dan hutan belum dimanfaatkan sebagai sistem deteksi dini dalam upaya
pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta dampak yang ditimbulkannya. Dengan
demikian diperlukan suatu kajian mengenai strategi pemanfaatan IDSN dalam
pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan memanfaatkan informasi tentang
tingkat kerentanan kebakaran dan data spasial.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) membangun konsep IDSN secara terpadu, (2)
menganalisis parameter kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau, dan (3)
merumuskan strategi pemanfaatan data spasial untuk pengendalian kebakaran hutan
dan lahan.
METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian adalah Kabupaten Sanggau yang mempunyai luas 12.857,70
km2 yang terdiri dari 15 kecamatan dengan kepadatan penduduk per km2 pada tahun
2003 rata-rata 29 jiwa. Waktu penelitian selama 12 bulan mulai dari Januari 2003.
Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer
didapatkan dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner dan
wawancara kepada stakeholder serta (Focus Group Discussion) FGD dilakukan untuk
mendapatkan respon masyarakat tentang menentukan strategi pemanfaatan IDSN. Data
sekunder didapatkan dari dokumentasi dari instansi terkait berupa data geologi, jenis
tanah, kemiringan lereng, status hutan, dan penggunaan lahan. Data spasial yang
digunakan adalah: data landsat (Enhanced Thematic Mapper) ETM path/row 121/60 17
Mei 2002 dan 13 Mei 2003; data citra satelit (National Oceanic and Atmospheric
Adminstration) NOAA periode Januari 2003 Juni 2003; peta digital rupabumi Badan
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) skala 1:50.000; data digital
rupabumi Bakosurtanal skala 1 : 250.000; data digital jenis tanah Puslittanak skala
1:250.000; data digital geologi P3G skala 1:250.000; data digital sebaran transmigrasi
skala 1:100.000 dinas pemukiman dan prasarana wilayah dan lingkungan hidup
Kabupaten Sanggau tahun 2002; data digital sebaran hak pengusahaan hutan (HPH) dan
hutan tanaman industri (HTI) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau
skala 1:100.000 tahun 2002; data digital sebaran Perkebunan Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Sanggau skala 1:100.000 tahun 2002. Data tematik yang
digunakan adalah penggunaan lahan, geologi, sebaran transmigrasi, sebaran
perkebunan, sebaran HPH/HTI dan TGHK (Tabel 2). Elemen data dasar spasial yang
harus ada pada basis data yang disesuaikan dengan kebutuhan yang terkait dengan
tujuan, serta peruntukkan SIG dibuat. Elemen data dasar spasial diperoleh dari berbagai
sumber data.
64
Jurnal Ilmiah Geomatika Vol.12 No.2 Desember 2006
Pengumpulan data kebutuhan dan keinginan stakeholder digunakan teknik
(Participatory Rural Appraisal) PRA untuk tingkat masyarakat dan FGD untuk tingkat
pemerintah.
Tabel 1.
No
1
2
3
4
5
6
Elemen Data Tematik yang Digunakan
Jenis Tematik
Penggunaan Lahan
Geologi
Sebaran
Transmigrasi
Sebaran
Perkebunan
Sebaran HPH/HTI
TGHK
Sumber
Citra Landsat 7 ETM
Peta Geologi
Dinas Kimpraswil & LH Kab.
Sanggau
Dinas Hutbun Kab. Sanggau
Metode Perolehan
Interprestasi digital visiual
Digitasi
Digitasi
Dinas Hutbun Kab. Sanggau
Dinas Hutbun Kab. Sanggau
Digitasi
Digitasi
Digitasi
Teknik Analisis
Teknik analisis data yang digunakan adalah: analisis sistem pengembangan
IDSN menggunakan teknik deskriptif melalui wawancara dengan stakeholder kunci dan
studi literatur dengan komparasi antar negara mengenai kerangka IDSN yang
disesuaikan dengan kondisi wilayah penelitian, analisis spasial untuk penentuan tingkat
kerentanan kebakaran hutan dan lahan menggunakan sistem informasi geografis.
Analisis spasial meliputi analisis vektor dan raster, dimana model data vektor
dapat menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan
titik-titik, garis-garis atau kurva, area atau polygon beserta atribut-atributnya. Data-data
spasial di matching sehingga dihasilkan tingkat kerentanan kebakaran hutan dan lahan.
Tingkat kerentanan kebakaran hutan dan lahan harus diuji dengan data kebakaran hutan
dan lahan yang lain sebagai uji spasial. Data yang digunakan sebagai uji spasial adalah
data digital sebaran hot spot dari NOAA.
Kriteria pengkodean yang digunakan dalam analisis tingkat kerentanan
kebakaran hutan dan lahan adalah: (1) faktor fisik yaitu jenis tanah (ada gambut = 1
dan tidak ada gambut = 0), geologi (batubara = 1 dan tidak ada batubara = 0), dan
kemiringan lereng (<15% = 0 dan >15% = 1); (2) faktor aktivitas yaitu status lahan
(HPHTI = 3, HPH = 2, perkebunan = 1, non kehutanan = 0) dan penggunaan lahan
(permukiman = 0, sawah = 0, hutan = 3, ladang = 2, belukar = 3, perkebunan = 2,
pertambangan = 1, rawa = 1); dan (3) faktor aksesibilitas yaitu jarak terhadap
permukiman (<7,5 km = 1 dan >7,5 km = 0), jarak jalan (<3 km = 1 dan >3 km = 0),
jarak sungai (<3 km = 1 dan >3 km = 0). Hasil dari faktor fisik selanjutnya di
gabungkan dengan faktor aktivitas dan faktor aksesibilitas. Prosedur operasi
penggabungan ini seluruhnya dilakukan pada perangkat lunak Arc/Info melalui menu
TABLES, sehingga dihasilkan peta tingkat kerentanan kebakaran hutan dan lahan
(Gambar 1).
Analisis prioritas pengembangan sistem pengendalian kebakaran hutan dan
lahan menggunakan penilaian pakar dengan kerangka analisis AWOT yakni integrasi
antara analisis (Analytical Hierarchy Process) AHP dan analisis (Strentgh, Weaknesses,
Opportunities, Threats) SWOT. Tahapan AWOT dimulai dengan analisis SWOT
65
Aplikasi Infrastruktur Data Spasial Nasional..- B.J. Pratondo..et.al
dilanjutkan dengan AHP. AHP akan membantu meningkatkan analisis SWOT dalam
mengelaborasikan hasil keputusan situasional sehingga keputusan strategi alternatif
dapat diprioritaskan. Tahap terpenting dari AHP adalah penilaian perbandingan
berpasangan, yang pada dasarnya merupakan perbandingan tingkat kepentingan antar
komponen dalam suatu tingkat hirarki (Saaty, 1993).
Penilaian stakeholder diolah dengan software Expert Choice 2000. Expert Choice
merupakan perangkat lunak sistem pendukung keputusan yang didasarkan atas
metodologi pengambilan keputusan yakni AHP.
Faktor Fisik
Peta
Jenis
Tanah
Peta
Geologi
Faktor Aktivitas
Peta
Rupabumi
Peta
Status
Hutan
Landsa
t ETM
Peta
Guna
Lahan
Peta
Pemuki
man
Peta
Lereng
Matching
Faktor Aksesibilitas
Landsat
ETM
Matching
Matching
Peta
Rupabumi
Peta
Rupa
bumi
Peta
Jalan
Peta
Sun
gai
Matching
Matching
Matching
Matching
Peta Tingkat Kerentanan Kebakaran
Hutan dan Lahan (Sementara)
Uji spasial dengan hotspot
Peta Tingkat Kerentanan
Kebakaran Hutan dan Lahan
Gambar 1. Tahapan Analisa Spasial Tingkat Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan
Penentuan aplikasi kerangka IDSN dalam pengendalian kebakaran hutan dan
lahan di Kabupaten Sanggau dilaksanakan dengan teknik PRA untuk masyarakat dan
FGD yang dilaksanakan di provinsi Kalimantan Barat dengan diikuti oleh peserta dari
berbagai instansi pemerintah dan lembaga sosial yakni : pemerintah Kabupaten
Sanggau, pemerintah provinsi, pengguna, perusahaan swasta, perguruan tinggi, dan
lembaga swadaya masyarakat.
66
Jurnal Ilmiah Geomatika Vol.12 No.2 Desember 2006
HASIL DAN PEMBAHASAN
Membangun IDSN
IDSN dibangun dan dikelola melalui usaha kerjasama seluruh partisipan: lokal,
regional, propinsi, dan pusat, perusahaan, institusi pendidikan, LSM, organisasi nirlaba,
dan lainnya. Pengorganisasan dari kerangka kerja ini divisikan sebagai jaringan bukan
hirarki. Kerangka kerja menggunakan keunggulan data geografik yang dibuat dan
digunakan secara internal oleh berbagai organisasi yang berbeda. Keterpaduan dari
sumberdaya yang berbeda ini memerlukan distribusi fungsi yang berbeda diantara
berbagai organisasi. Berbagai fungsi yang berhubungan diperlukan untuk membangun
dan mengoperasikan kerangka kerja. Secara umum terdapat tujuh fungsi utama yaitu:
pengembangan data, pemeliharaan, dan integrasi; akses data; manajemen data;
koordinasi; petunjuk kerja; menajemen sumberdaya; monitoring dan evaluasi. Setiap
fungsi tersebut mempunyai berbagai kegiatan yang berhubungan beserta tanggung
jawab dan masing-masing mempunyai masalah sendiri dan tantangan.
Kegiatan pengembangan, pemeliharaan data menghasilkan dan memperbaharui
kerangka kerja data. Fungsi ini terdiri atas menghasilkan data asli dan data revisi,
penggabungan spasial dan data atributnya dari sumber yang berbeda, dokumentasi data
termasuk membuat metadata, evaluasi dan integrasi data. Infrastruktur data dapat
dibangun melalui berbagai teknik dan sumberdaya termasuk studi lapang, kompilasi
fotogrametrik, digitasi peta, dan konversi dari rekaman lain ke data digital.
Para pembuat data yaitu pemerintah lokal, kabupaten, propinsi dan nasional;
perusahaan-perusahaan sektor privat; universitas; lembaga swadaya masyarakat; dan
yang lainnya. Pemerintah lokal membuat data yang lebih detail atau data beresolusi
tinggi untuk semua materi dan materi-materi ini umumnya dikoordinasikan dengan
sebuah aplikasi GIS.
Akses data memungkinkan partisipan memperoleh data dari infrastruktur.
Aktivitas yang banyak dilakukan termasuk menyediakan akses kepada data dan
metadata, memproses permintaan data, menetapkan dan membentuk penyebaran data
yang diinginkan, dan melaporkan dan memperhatikan yang menjadi perhatian
pengguna. Fungsi ini juga menghubungkan pengguna dengan berbagai sumberdaya.
Infrastruktur ini harus bisa merespon kondisi pasar dan permintaan, seperti data yang
umumnya diinginkan, dan mendisain kumpulan data dan produk. Akses data berfungsi
menunjukkan semua yang diperlukan, juga mengumpulkan informasi yang berguna
untuk mendeteksi kebutuhan dari pengguna.
Manajemen data memastikan keberlanjutan infrastruktur data secara terus
menerus. Kegiatannya termasuk pemeliharaan data, memastikan data terintegrasi dan
aman, pengembangan dan penyusunan definisi data, desain dan modelnya,
pengembangan dan penyusunan spesifikasi teknis lainnya, dan penyediaan untuk arsip
data, penggandaan data, perbaikan data jika terjadi kerusakan. Tujuan utama dari
manajemen data adalah untuk memastikan bagaimana framework dapat disusun dari
berbagai bagian-bagian ini. Kegiatan manajemen data dapat terjadi di banyak tempat
dan banyak organisasi, dan fungsi manajemen framework harus berlandaskan pada
kegiatan ini secara bersama-sama.
Koordinasi memastikan bahwa semua kontribusi; mulai dari data, pendanaan,
teknologi dan SDM, dapat bekerja secara harmonis dan bernilai positif terhadap
67
Aplikasi Infrastruktur Data Spasial Nasional..- B.J. Pratondo..et.al
hubungan antara semua partisipan. Fungsi ini memerlukan kerjasama dan hubungan
yang kondusif antar organisasi, melaksanakan proses dan insentif untuk mendorong
partisipasi yang menyebar secara luas. Kegiatan yang spesifik termasuk membuat
rencana bisnis untuk pengembangan framework, membuat prioritas, membuat berbagai
perjanjian dan praktek bisnis untuk mendorong partisipasi, mengkoordinasikan metode
pengaksesan data, pengembangan konsensus untuk berbagai standardisasi, penyediaan
luaran dan pendidikan.
Petunjuk teknis disediakan untuk melihat dan mengatur pengembangan
kerangka kerja, dan memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya framework. Kegiatan
ini termasuk pengembangan pembagian visi antara stakeholder; pengembangan rencana
strategis untuk perusahaan, menentukan struktur organisasi, lingkungan operasional,
metode pembagian komunikasi, pembuatan keputusan dan berbagai proses kebijakan
publik; kebijakan pengembangan dan pemeliharaan serta dukungan dana untuk usaha
antara eksekutif senior dan bagian yang berpengaruh; dan penyediaan dana legal untuk
kontrak, pertanggungjawaban dan permasalahan lainnya.
Pengaruh pengembangan framework pada berbagai kegiatan dapat
meningkatkan ketersediaan sumberdaya. Manajemen sumberdaya termasuk
pertanggungjawaban terhadap pendugaan penerimaan dan biaya; identifikasi;
penghasilan dan alokasi sumberdaya, termasuk penyediaan dukungan logistik untuk
pengembangan framework. Sumberdaya yang dimaksud adalah dana, data, teknologi
dan SDM. Sumber dana termasuk hibah, pinjaman, kontrak pelayanan, perjanjian
kerjasama, dan biaya serta berbagai sumber pendapatan sejenis. Fungsinya adalah
untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap keberadaan framework, selain itu juga
berfungsi untuk menganalisis pasar. Konsistensi sepanjang wilayah studi dan data
sangat penting. Analisis pasar menggunakan informasi ini untuk memastikan bahwa
framework dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini adalah identifikasi
target pasar, potensi konsumer, pasar sekarang dan luasan potensinya kemudian
kecenderungan pasar serta peramalan.
Model organisasi untuk pengembangan framework ada dua yaitu pendekatan
sentralisasi dan desentralisasi. Pendekatan secara sentralisasi yaitu satu kinerja
organisasi dengan banyak fungsi. Kegiatan utama adalah pengintegrasian data, dimana
peran ini disebut area integrator. Fungsi ini membawa tugas-tugas teknis lainnya seperti
standar implementasi, prosedur jaminan kualitas, aktivitas koordinasi dan pemeliharaan
data diantara organisasi yang memproduksi data untuk wilayah geografis dan
menghubungkan data tersebut ke sentral data. Pendekatan desentralisasi
menggambarkan banyak organisasi dalam satu wilayah geografi mengambil berbagai
peran dengan koordinasi yang erat, dalam suatu struktur jaringan.
Infrastruktur data dibangun dari bawah. Mekanisme koordinasi dibagi kedalam 3
kategori: (1) Koordinasi berbasis propinsi. Pemerintah propinsi memimpin koordinasi
antara dinas-dinas propinsi, pemerintah kabupaten dan yang lainnya; (2) Konsorsium
regional. Organisasi yang mempunyai kepentingan yang saling menunjang dalam satu
wilayah (dalam atau luar batas propinsi). Membentuk sebuah konsorsium untuk
mengembangkan pola pembagian data. Konsorsium ini terdiri dari berbagai dinas
pemerintah lokal dan regional, dinas-dinas propinsi dan wakil pemerintah pusat di
daerah dan yang lainnya; dan (3) Proyek khusus. Dalam kasus yang memiliki
kepentingan yang sama dalam satu wilayah, organisasi membentuk kerjasama untuk
mengembangkan pembagian data dalam memecahkan masalah tertentu.
68
Jurnal Ilmiah Geomatika Vol.12 No.2 Desember 2006
Analisis kerentanan kebakaran hutan dan lahan
Analisa tingkat kerentanan dimulai dari proses pengumpulan sebab-sebab
kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Kebakaran hutan dan lahan di
Kabupaten Sanggau di sebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: kebijakan kehutanan dan
kondisi alam yang memang cukup rentan. Faktor kebijakan kehutanan jelas sangat
mempengaruhi adanya pembakaran hutan dan lahan secara berlebihan dengan adanya
kebijakan pembukaan perkebunan. Faktor alam lebih menentukan dan mendorong
apabila kebakaran telah terjadi. Besar kecilnya volume kebakaran sedikit banyak
ditentukan oleh kondisi alam, karena pada saat kebakaran sudah besar, manusia sudah
tidak mampu lagi mengendalikan api yang sudah terlalu besar. Kondisi lain kadang
kebakaran sudah tidak tampak di permukaan, akan tetapi bara masih menyala dibawah
permukaan. Berdasarkan dua faktor utama tersebut dapat dipilah menjadi tiga faktor
penyebab kebakaran hutan dan lahan yang meliputi: faktor fisik yang terdiri dari
klasifikasi jenis tanah, kondisi geologi, dan kemiringan lereng, faktor aktivitas yang terdiri
dari status hutan dan penggunaan lahan dan faktor aksesibilitas yang terdiri dari jarak ke
pemukiman, jarak ke jalan dan jarak ke sungai. Aksesibilitas sangat mempengaruhi
aktivitas manusia, baik itu manusia dalam lingkungan hutan maupun manusia yang
berkepentingan dengan kehutanan.
Kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau tidak dapat dilepaskan
dari faktor fisik lahan. Pada berbagai wilayah, kebakaran yang terjadi tidak pada
permukaan tanah karena sudah habisnya bahan bakar yang dapat dibakar, tetapi
kebakaran terjadi pada sub permukaan. Kebakaran seperti ini terjadi pada sisipan
batubara yang cukup dekat dengan permukaan karena adanya kontak dengan oksigen
(O2) lebih mempermudah terjadinya api. Spesifikasi kebakaran yang lain adalah
kebakaran yang terjadi pada tanah gambut. Pelapukan bahan organik yang tidak
sempurna kadangkala menjadikan jenis ini mempunyai tekstur yang kasar, kecuali pada
tanah-tanah gambut yang cukup tua. Pada golongan tanah gambut muda, pada kondisi
iklim kemarau, golongan tanah ini mudah sekali berkondisi sangat kering karena
kandungan bahan organiknya sangat tinggi. Sehingga pada saat kebakaran terjadi, jenis
tanah ini juga mudah terbakar (flameable). Klasifikasi kemiringan lereng terbagi menjadi
dua klas yaitu lereng dengan kemiringan <15% termasuk tidak rentan dan lereng
dengan kemiringan >15% termasuk rentan.
35 0000
400000
450000
500000
550000
P ETA
BATAS REN TAN
KABUPATE N S ANGGAU
MA LAY SIA
KABU PAT EN
BEN GK A YA N G
KEC AM AT AN
E NT IKO N G
10100000
10100000
KE CA MA TA N
BAL AIKA RAN G AN
KEC AM AT AN
BE D UA I
KE CA MA TA N
BAT
AN
G TA RA
NG
10000000
KA BUPA T EN
PON T IA NA K
KEC AM AT AN
TA Y AN
KEC AM AT AN
BOD O K
Ba tas Renta n
B atas Neg ara
B atas Ka bup aten
B atas Ke camata n
S un gai
Tid ak Ren ta n
KEC AM
AT
AN
DU K UT
KE
A ga k Re ntan
K ura ng Re ntan
K ECA MA TA N
SA N GG
K APU A S
A U
KA BUPA T EN
SAK AD A U
Re ntan
10000000
10050000
8 12 16 20 Km
:
:
:
:
KEC AM AT AN
AJU
T
ER
SANGGA
U
KEC AM AT AN
J AN G KA NG
Ke teran ga n
Ba tas Adm inistras i
KEC AM AT
AN
KA BUPA
TEN
SO SO
K
KEC AM AT AN
KE MBA YA N
KEC AM AT AN
BO N TI
KA BUPA T EN
L AN D AK
10050000
KA BUPA T EN
SINT AN G
KEC AM AT AN
N OY A N
KEC AM AT AN
ME LIA U
S an gat Ren ta n
Tit ik Api (H ot Spot ) T ahun 2002
108
11 2
11 6
120
124
KA B U P AT E N
S A NGGA U
9950000
9950000
KA BUPA T EN
KE TA PA NG
35 0000
400000
-4
-4
108
450000
500000
11 2
11 6
120
124
550000
Gambar 2. Peta Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Sanggau
69
Aplikasi Infrastruktur Data Spasial Nasional..- B.J. Pratondo..et.al
Tingkat kerentanan kebakaran hutan dan lahan tersaji pada Tabel 2 yaitu
jumlah yang rentan terhadap titik panas yaitu 133 titik panas atau 69,89%, sehingga
peta kerentanan kebakaran hutan dan lahan untuk Kabupaten Sanggau cukup mewakili
untuk analisa uji spasial.
Sebaran titik panas pada jenis tanah (Tabel 3) menunjukkan bahwa pada tanah
gambut jumlah titik api hanya 5,68% hal ini menunjukkan bahwa tanah gambut di
Kabupaten Sanggau bukan merupakan faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan
lahan tetapi hanya merupakan bahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan
sebaran api pada klasifikasi geologi (Tabel 4) menunjukkan bahwa tanah yang
mengandung batubara mempunyai nilai cukup tinggi yaitu 43,75%, sehingga kandungan
batubara sangat berperan dalam terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemiringan
lereng bukan merupakan faktor fisik penyebab terjadinya kebakaran hutan karena di
Kabupaten Sanggau kemiringan lereng dibawah 15% yaitu sebesar 61,36% lebih
dominan daripada kemiringan diatas 15% (Tabel 5).
Sebaran titik api pada status hutan (Tabel 6) menunjukkan jumlah deteksi
tertinggi pada status kawasan areal non kehutanan. Sedangkan areal pada hutan
tanaman industri mempunyai titik api yang cukup tinggi yaitu 36,36% kemudian diikuti
oleh hak pengusahaan hutan sebesar 10.23%. Hal ini menunjukkan pelaku bisnis
kehutanan masih menerapkan land clearing untuk membuka atau merubah status hutan,
sehingga kebakaran masih terjadi pada kedua daerah ini. Sedangkan pada klasifikasi
penggunaan lahan yang paling banyak titik panas pada belukar sebesar 47,16% diikuti
oleh penggunaan lahan hutan sebesar 46,59%, belukar merupakan bahan bakar yang
baik untuk terjadinya api, sehingga belukar di Kabupaten Sanggau harus dikurangi atau
dikonversi menjadi sesuatu yang lebih bernilai ekonomis.
Tabel
No.
1.
2.
3.
4.
5.
2. Tingkat Kerentanan Kebakaran terhadap Titik Panas
Kategori Kawasan
Jumlah Titik Panas
%
Tidak rentan
43
24,43
Kurang rentan
56
31,82
Agak rentan
48
27,27
Rentan
19
10,80
Sangat rentan
10
5,68
Total
176
100
Tabel 3. Tingkat Kerentanan Kebakaran terhadap Klasifikasi Jenis Tanah
No.
Kategori Kawasan
Jumlah Titik Panas
%
1.
Gambut
10
5,68
2.
Tidak ada gambut
166
94,32
Total
176
100
Tabel 4. Tingkat Kerentanan Kebakaran terhadap Klasifikasi Geologi
No.
Kategori Kawasan
Jumlah Titik Panas
%
1.
Batubara
77
43,75
2.
Tidak ada batubara
99
56,25
Total
176
100
70
Jurnal Ilmiah Geomatika Vol.12 No.2 Desember 2006
Tabel 5. Tingkat Kerentanan Kebakaran terhadap Klasifikasi Kemiringan Lereng
No.
Kategori Kawasan
Jumlah Titik Panas
%
1.
Kemiringan lereng > 15%
108
61,36
2.
Kemiringan lereng < 15%
68
38,64
Total
176
100
Tabel
No.
1.
2.
3.
4.
6. Tingkat Kerentanan Kebakaran terhadap Klasifikasi Status Hutan
Kategori Kawasan
Jumlah Titik Panas
%
Hutan tanaman industri
64
36,36
Hak pengusahaan hutan
18
10,23
Perkebunan
0
0
Non Kehutanan
94
53,41
Total
176
100
Tabel
No.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
7. Tingkat Kerentanan Kebakaran terhadap Klasifikasi Penggunaan Lahan
Kategori Kawasan
Jumlah Titik Panas
%
Kampung/Pemukiman
5
2,84
Sawah
0
0
Hutan
82
46,59
Ladang/tegalan
4
2,27
Belukar
83
47,16
Perkebunan
0
0
Pertambangan
0
0
Rawa
2
1,14
Total
176
100
Prioritas pengembangan kelembagaan
Penentuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten
Sanggau dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melibatkan pakar dan stakeholder
kunci. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis AWOT yang merupakan integrasi
antara AHP dan SWOT.
Metode yang digunakan dalam penentuan bobot aspek kelembagaan yang akan
dikembangkan adalah AHP. Penilaian dari semua stakeholder dikalkulasi dan dikombinasi
dengan menggunakan software Expert Choice 2000.
Hasil analisis menunjukkan bahwa komponen kekuatan memiliki bobot tertinggi
(0,565) dalam penentuan aspek kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
di Sanggau, kemudian diikuti oleh komponen peluang (0,262), ancaman (0,118) dan
kelemahan (0,055). Hasil ini menunjukkan bahwa faktor internal dalam penentuan aspek
kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dominan adalah komponen
kekuatan dan faktor eksternal yang dominan adalah komponen peluang. Besarnya faktor
kekuatan dan peluang dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman dalam
penentuan aspek kelembagaan merupakan indikator keberhasilan pengembangan
kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang.
Hasil diskusi dengan stakeholder dan pakar mengenai aspek kelembagaan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau diperoleh 4 aspek
kelembagaan pengendalian yang perlu dikembangkan, yaitu: (1) Penguatan sistem
71
Aplikasi Infrastruktur Data Spasial Nasional..- B.J. Pratondo..et.al
kelembagaan dan mekanisme hubungan antar institusi, (2) Pengembangan kualitas
sumberdaya manusia, (3) Pembangunan infrastruktur pendukung, dan (4) Revisi dan
penyusunan peraturan. Bobot dan prioritas aspek kelembagaan tersebut dapat dilihat
pada Gambar 3.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa aspek sistem merupakan aspek kelembagaan
utama dalam penentuan aspek pengembangan kelembagaan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Hal ini berarti bahwa pengembangan sistem dan
mekanisme kelembagaan menjadi prioritas dalam pengembangan kelembagaan
pengendalian. Hasil ini sejalan dengan kondisi kelembagaan saat ini yang masih lemah
dalam sistem dan mekanisme kerjasama antar instansi baik pusat maupun daerah
sehingga aktivitas pengendalian kebakaran belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Bobot aspek pengembangan kelembagaan mitigasi
kebakaran hutan dan lahan di Sanggau
0.329
Sistem
0.263
Infrastruktur
0.224
SDM
Peraturan
0.184
Gambar 3. Bobot aspek pengembagan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Prioritas aspek kelembagaan kedua adalah pembangunan infrastruktur
pendukung sistem kelembagaan. Hasil ini pada dasarnya mendukung prioritas utama.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur harus dilakukan setelah sistem yang baik
terbangun. Hasil analisis tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan perumusan
pengembangan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Mekanisme
perumusan digunakan metode diskusi dengan semua stakeholder dengan perhatian
utama pada peran serta pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.
Aplikasi IDSN untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Untuk aplikasi kerangka kerja IDSN dalam kaitan dengan mitigasi dan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan tahapan sebagai berikut :
1. Identifikasi pemilik data. Dataset di Indonesia ada 42 dataset, dimana dataset
tersebar dibanyak instansi, identifikasi dataset diperlukan untuk pemanfaatan data
spasial.
2. Standarisasi Data. Pembahasan standarisasi data dilakukan oleh panitia teknis pada
setiap bidang masing-masing dibawah koordinasi Badan Standardisasi Nasional.
3. Sharing Data. Untuk terjadinya sharing data, diperlukan software interoperabialitas
sehingga data-data spasial yang standart dapat dipertukarkan.
72
Jurnal Ilmiah Geomatika Vol.12 No.2 Desember 2006
4. Akuisisi. Kepemilikan data dihubungkan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
sehingga kastodian mempunyai kewenangan untuk menyampaikan atau menolak
memberikan data kepada pengguna.
5. Kerjasama. Kerjasama diperlukan untuk semua pemilik data/kastodian sehingga
diperlukan koordinasi dalam bentuk clearing house.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas disimpulkan:
1. Pembangunan IDSN dilakukan dengan mengembangkan tujuh fungsi infrastruktur
data yaitu: pengembangan data, pemeliharaan, dan integrasi; akses data;
manajemen data; koordinasi; petunjuk kerja; menajemen sumberdaya; monitoring
dan evaluasi. Setiap fungsi tersebut mempunyai berbagai kegiatan yang
berhubungan dan masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri.
2. Tingkat kerentanan kebakaran hutan dan lahan terbagi menjadi tiga faktor yaitu:
faktor fisik yang terdiri dari klasifikasi jenis tanah, kondisi geologi, dan kemiringan
lereng, faktor aktivitas yang terdiri dari status hutan dan penggunaan lahan dan
faktor aksesibilitas yang terdiri dari jarak ke pemukiman, jarak ke jalan dan jarak ke
sungai. Nilai tingkat kerentanan kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut
tidak rentan (24,64%), agak rentan (31,10%), cukup rentan (22,64%), rentan
(11,50%) and sangat rentan (2,74%).
3. Untuk aplikasi kerangka kerja IDSN dalam kaitan dengan mitigasi dan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan dilakukan tahapan: identifikasi pemiliki data, standarisasi
data, sharing data, akuisisi, dan kerjasama.
Saran
IDSN sangat berperanan dalam distribusi data spasial. Indonesia yang
merupakan negara yang selalu mengalami berbagai macam bencana, terutama bencana
kebakaran yang terjadi setiap tahun membutuhkan suatu sistem yang dapat
memecahkan masalah kebakaran hutan dan lahan. Data-data spasial yang sudah
terkumpul dari berbagai macam instansi dapat diolah menjadi peta tingkat kerentanan
kebakaran hutan dan lahan, dengan adanya teknologi internet dan intranet data-data
spasial yang dibutuhkan dapat diakses melalui komputer di wilayah pengguna masingmasing, sehingga waktu dan ruang yang selama ini menjadi kendala dalam penyelesaian
permasalahan dapat dipecahkan dengan adanya IDSN.
IDSN harus segera di terapkan di Indonesia, dengan adanya IDSN permasalahan
bencana yang datang bertubi-tubi akan dapat segera dipecahkan. United State of
Amerika baru mengaplikasikan IDSN untuk bencana pada saat terjadinya badai Katrina
pada tahun 2005. Untuk pembuatan peta kerentanan kebakaran hutan dan lahan perlu
ditambah beberapa parameter pendukung yang lain, sehingga peta tingkat kerentanan
kebakaran hutan dan lahan akan semakin baik.
73
Aplikasi Infrastruktur Data Spasial Nasional..- B.J. Pratondo..et.al
DAFTAR PUSTAKA
Amdahl G. 2001. Disaster Renponse GIS for Public Safety. California Redlands: ESRI
Press.
[ANZLIC] Australia New Zealand Land Information Council. 2003. Natural Resources
Information Management Toolkit: Building Capacity to Implement Natural
Resources Information Management Solutions Version 1. Canberra Australia: The
Australia New Zealand Land Information Council.
[ASDI] The Australian Spatial Data Infrastrucute. 2003. Implementing The Australian
Spatial Data Infrastructure: Action Plan 2003-2004. Canberra Australia:
Australian Spatial Data Infrastructure
[BAKOSURTANAL] Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. 2004. Pedoman
Penyelenggaraan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) Versi 1. Cibinong:
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
Debano L.F., D.G. Neary dan P.F. Ffolliott. 1998. Fires Effect on Ecosystems. New York:
John Wiley and Sons, Inc.
[FGDC] Federal Geographic Data Committee. 2004. Framework Introduction and Guide.
Virginia United States: The Federal Geographic Data Committee.
[IPB] Institut Pertanian Bogor. 1982. Studi Kelayakan Pengendalian Perladangan
Berpindah di Propinsi Kalimantan Selatan. Lembaga Penelitian IPB. Bogor.
Masser I. 2005. GIS Worlds Creating Spatial Data Infrastructures. California Redlands:
ESRI Press.
[NRIMS] Natural Resources Information Management Strategy. 1997. New South Wales
Custodianship Guidelines for Natural Resources Information : Versi 1. New South
Wales: Natural Resources Information Management.
[OMB] Office Management and Budget. 2005. Circular No. A-16 Revised. White House
Website. http://www.whitehouse.gov/omb/circulars/a016/ [4 Oktober 2005]
Sahardjo B.H. 2003. Kebakaran Hutan dan Lahan Pengertian, Produk dan Dampak.
Bogor: Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB.
Stevenson G.G. 1991. Common Property Economics: A General Theory and Land Use
Application.Cambridge University Press.
Syumanda R. 2003. Kebakaran Hutan dan Lahan Riau: Kebijakan dan Dampaknya Bagi
Kehidupan Manusia. Workshop Kebakaran Hutan dan Lahan 23-24 April 2003.
Pekanbaru.
74
You might also like
- Analisis Penataan Ruang Kawasan LindungDocument8 pagesAnalisis Penataan Ruang Kawasan LindungHerry KurniawanNo ratings yet
- B-15811-Article Text-1094352-1-4-20230924 REVDocument13 pagesB-15811-Article Text-1094352-1-4-20230924 REVRizky WahyudiNo ratings yet
- SUBAKDocument9 pagesSUBAKLAASSSNo ratings yet
- Forest Fire DetectionDocument8 pagesForest Fire DetectionEngrHasanuzzamanSumonNo ratings yet
- 1) Application of Gis in Biodiversity Conservation PlanningDocument15 pages1) Application of Gis in Biodiversity Conservation PlanningRitam MukherjeeNo ratings yet
- DocumentDocument8 pagesDocumentJean Jacques Monga KabokoNo ratings yet
- Benteng, SumaryonoDocument18 pagesBenteng, Sumaryonotaufiksetiawan437No ratings yet
- 486 777 1 SMDocument10 pages486 777 1 SMfauzan faridNo ratings yet
- Spatial Distribution Patterns Analysis of Hotspot in Central Kalimantan Using FIMRS MODIS DataDocument11 pagesSpatial Distribution Patterns Analysis of Hotspot in Central Kalimantan Using FIMRS MODIS DataImanuel SinarNo ratings yet
- Pemanfaatan Inderaja Dan Sistem Informasi Geografis (Sig) Dalam Inventarisasi Lahan Kritis Di Kabupaten Kolaka UtaraDocument7 pagesPemanfaatan Inderaja Dan Sistem Informasi Geografis (Sig) Dalam Inventarisasi Lahan Kritis Di Kabupaten Kolaka UtaraapapNo ratings yet
- Ajsad v2n3 May21 p2258Document11 pagesAjsad v2n3 May21 p2258Aminu Sarki Abu-AishatNo ratings yet
- The Effectiveness of Spatial Data Sharing in Indonesia-Sdi: Case Study in Ministry of Environment and Forestry and Provincial Government of West JavaDocument12 pagesThe Effectiveness of Spatial Data Sharing in Indonesia-Sdi: Case Study in Ministry of Environment and Forestry and Provincial Government of West JavaFaridaNo ratings yet
- Forest Fire Susceptibility and Risk MappDocument10 pagesForest Fire Susceptibility and Risk MappMRPNo ratings yet
- Proposal DraftDocument19 pagesProposal DraftSasuke UchihaNo ratings yet
- Galate, Ian Rhey Penaranda, Elmer Wayan, JaysonDocument14 pagesGalate, Ian Rhey Penaranda, Elmer Wayan, JaysonSasuke UchihaNo ratings yet
- Analisis Spasial Kawasan Rawan Longsor Di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Fanny Tri Raditya Dan Bondan Hary SetiawanDocument11 pagesAnalisis Spasial Kawasan Rawan Longsor Di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Fanny Tri Raditya Dan Bondan Hary SetiawanbagusNo ratings yet
- Evaluasi Kesesuaian Dan Kemampuan Lahan Terhadap RTRW Kabupaten Kotabaru, Kalimantan SelatanDocument13 pagesEvaluasi Kesesuaian Dan Kemampuan Lahan Terhadap RTRW Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatanabdul saktiNo ratings yet
- An Intelligent System For Effective Forest FireDocument13 pagesAn Intelligent System For Effective Forest FiresinngakNo ratings yet
- Land-Site Suitability Analysis For Tea Using Remote Sensing and GIS TechnologyDocument10 pagesLand-Site Suitability Analysis For Tea Using Remote Sensing and GIS TechnologyInternational Journal of Innovative Science and Research TechnologyNo ratings yet
- Jurnal Nasional PJDocument7 pagesJurnal Nasional PJDaniel SitanggangNo ratings yet
- GEOIDE Thrusts and Themes Research & DevelopmentsDocument7 pagesGEOIDE Thrusts and Themes Research & Developmentsdasdebabrat89No ratings yet
- Pemetaan Kerentanan Kebakaran Hutan Dan Lahan Non GambutDocument11 pagesPemetaan Kerentanan Kebakaran Hutan Dan Lahan Non GambutNawir SyarifNo ratings yet
- 1 SMDocument8 pages1 SMDavid MansawanNo ratings yet
- DAS Antokan JurnalDocument9 pagesDAS Antokan JurnalNuzulia RahmadhaniNo ratings yet
- Jurnal SIGDocument11 pagesJurnal SIGR RidhoNo ratings yet
- Spatial Dynamic Prediction of Landuse / Landcover Change (Case Study: Tamalanrea Sub-District, Makassar City)Document9 pagesSpatial Dynamic Prediction of Landuse / Landcover Change (Case Study: Tamalanrea Sub-District, Makassar City)Andi YasserNo ratings yet
- Land Use/Land Cover Change Study of District Dehradun, Uttarakhand Using Remote Sensing and GIS TechnologiesDocument11 pagesLand Use/Land Cover Change Study of District Dehradun, Uttarakhand Using Remote Sensing and GIS TechnologiesSnigdha SrivastavaNo ratings yet
- Proposal DefenseDocument20 pagesProposal DefenseKshitiz GiriNo ratings yet
- Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dan Penginderaan Jauh Untuk Pemetaan Penggunaan Dan Kesesuaian Lahan Di Desa Batur Tengah Kabupaten BangliDocument13 pagesAplikasi Sistem Informasi Geografis Dan Penginderaan Jauh Untuk Pemetaan Penggunaan Dan Kesesuaian Lahan Di Desa Batur Tengah Kabupaten BangliMELLA YUSNIZARNo ratings yet
- GIS and Remote Sensing Assignment JaisonDocument8 pagesGIS and Remote Sensing Assignment JaisonJAISON MUNTANGANo ratings yet
- Land Use Planning For Sustained Utilization of Resources Using Remote Sensing & GIS Techniques: A Case Study in Mamit District, Mizoram, IndiaDocument7 pagesLand Use Planning For Sustained Utilization of Resources Using Remote Sensing & GIS Techniques: A Case Study in Mamit District, Mizoram, IndiaAJER JOURNALNo ratings yet
- Analyzing Dynamic of Changes in Land Use and Land Cover in Semi-Arid of Eastern Sudan, Using Remote Sensing and GISDocument13 pagesAnalyzing Dynamic of Changes in Land Use and Land Cover in Semi-Arid of Eastern Sudan, Using Remote Sensing and GISMamta AgarwalNo ratings yet
- 1 Application of Remote and GIS in EnvironmentDocument3 pages1 Application of Remote and GIS in EnvironmentSamarics BhattNo ratings yet
- Article - Adnin 01Document7 pagesArticle - Adnin 01fathooziNo ratings yet
- Long 2021Document19 pagesLong 2021Yonander tomaylla yupanquiNo ratings yet
- Ea11 (3) 01Document14 pagesEa11 (3) 01Intan LestariNo ratings yet
- NR 06 01 08 Perovychetal m00331Document11 pagesNR 06 01 08 Perovychetal m00331mindowaretoolsNo ratings yet
- Analysis of Critical Land in The Musi Watershed Using Geographic Information SystemsDocument6 pagesAnalysis of Critical Land in The Musi Watershed Using Geographic Information SystemsMuhammad AlfiansyahNo ratings yet
- Simulation of Short Term Post Fire Vegetation Recovery by Integration of LANDFIRE Data Products DNBR Data and LANDIS ModelingDocument14 pagesSimulation of Short Term Post Fire Vegetation Recovery by Integration of LANDFIRE Data Products DNBR Data and LANDIS Modelinglaz mejNo ratings yet
- Land Use Change MatrixDocument10 pagesLand Use Change MatrixUrooj FatimaNo ratings yet
- Application of Geographic Information System Gis in Forest Management 2167 0587 1000145Document12 pagesApplication of Geographic Information System Gis in Forest Management 2167 0587 1000145Asih Nastiti AzmiNo ratings yet
- Pemetaan Kepemilikan Lahan Sawah Dan Sumber Daya Manusia Berbasis Geospasial Di Subak Anggabaya, Umadesa, Dan Umalayu Kecamatan Denpasar TimurDocument14 pagesPemetaan Kepemilikan Lahan Sawah Dan Sumber Daya Manusia Berbasis Geospasial Di Subak Anggabaya, Umadesa, Dan Umalayu Kecamatan Denpasar TimurAghunx21No ratings yet
- NASA - Forest Integrity Project - 2019-MinDocument12 pagesNASA - Forest Integrity Project - 2019-MinLuis Fernando Burneo RosalesNo ratings yet
- A Local Spatial Data Infrastructure To Support The Merapi Volcanic Risk Management: A Case Study at Sleman Regency, IndonesiaDocument24 pagesA Local Spatial Data Infrastructure To Support The Merapi Volcanic Risk Management: A Case Study at Sleman Regency, Indonesiaanon_432876393No ratings yet
- Schepaschenko2019 Article RecentAdvancesInForestObservatDocument24 pagesSchepaschenko2019 Article RecentAdvancesInForestObservatStefania IordacheNo ratings yet
- Report PDFDocument76 pagesReport PDFAbir MahmoodNo ratings yet
- Remote Sensing of Environment XXX (XXXX) XXXDocument11 pagesRemote Sensing of Environment XXX (XXXX) XXXAlexGusevNo ratings yet
- Thesis Proposal - ScriptDocument11 pagesThesis Proposal - ScriptRandy FernandezNo ratings yet
- Forest Resource Management Using Geo-Spatial TechnologiesDocument7 pagesForest Resource Management Using Geo-Spatial TechnologiesInternational Journal of Innovative Science and Research TechnologyNo ratings yet
- 26663-Article Text-88905-5-10-20230626Document19 pages26663-Article Text-88905-5-10-20230626cesarnurlita.2023No ratings yet
- ID Analisis Perencanaan Pola Penanganan Per 3Document8 pagesID Analisis Perencanaan Pola Penanganan Per 3gracehia022No ratings yet
- Gis TTSDocument6 pagesGis TTSLeeNo ratings yet
- IJCRT2201454Document8 pagesIJCRT2201454preity.n2397No ratings yet
- GIS Technology in Environmental Protection: Research Directions Based On Literature ReviewDocument8 pagesGIS Technology in Environmental Protection: Research Directions Based On Literature ReviewEdyta SierkaNo ratings yet
- 164 1000 1 PBDocument11 pages164 1000 1 PBNivaldo AlexandreNo ratings yet
- 2017 SBSR Perspectives Rs Mapping SC pg4692 4699Document8 pages2017 SBSR Perspectives Rs Mapping SC pg4692 4699Monitora SCNo ratings yet
- AP M T B S: Jeff Eidenshink, Brian Schwind, Ken Brewer, Zhi-Liang Zhu, Brad Quayle and Stephen HowardDocument19 pagesAP M T B S: Jeff Eidenshink, Brian Schwind, Ken Brewer, Zhi-Liang Zhu, Brad Quayle and Stephen HowardConeyvin Arreza SalupadoNo ratings yet
- Land Use and Spatial Planning: Enabling Sustainable Management of Land ResourcesFrom EverandLand Use and Spatial Planning: Enabling Sustainable Management of Land ResourcesNo ratings yet
- Addressing Earth's Challenges: GIS for Earth SciencesFrom EverandAddressing Earth's Challenges: GIS for Earth SciencesLorraine TigheNo ratings yet
- Urban Green Spaces: Public Health and Sustainability in the United StatesFrom EverandUrban Green Spaces: Public Health and Sustainability in the United StatesNo ratings yet