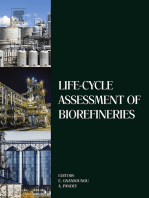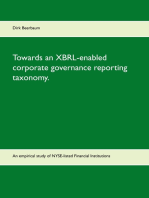Professional Documents
Culture Documents
Penerapan Psak Adopsi Ias 41 Agriculture: Stefanus Ariyanto Heri Sukendar Heny Kurniawati
Penerapan Psak Adopsi Ias 41 Agriculture: Stefanus Ariyanto Heri Sukendar Heny Kurniawati
Uploaded by
Erlangga KusumaOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Penerapan Psak Adopsi Ias 41 Agriculture: Stefanus Ariyanto Heri Sukendar Heny Kurniawati
Penerapan Psak Adopsi Ias 41 Agriculture: Stefanus Ariyanto Heri Sukendar Heny Kurniawati
Uploaded by
Erlangga KusumaCopyright:
Available Formats
PENERAPAN PSAK ADOPSI IAS 41 AGRICULTURE
Stefanus Ariyanto; Heri Sukendar; Heny Kurniawati
Accounting and Finance Department, Faculty of Economic and Communication, BINUS University
Jln. K.H. Syahdan No.9, Palmerah, Jakarta Barat 11480
stefanus.ariyanto@yahoo.com; heris1024@yahoo.com; kurniawati.heny@gmail.com
ABSTRACT
This study aims to determine whether the application of PSAK adopted from IAS 41: Agriculture should
be applied to State-Owned Enterprises, especially the plantation SOE. So that the SOE financial information
produced becomes more useful for decision-making. Furthermore, this study wants to answer what benefits can
be obtained from the implementation of this standard on the plantation-based SOE. The main characteristic of
IAS is the use of fair value model for biological assets owned by the agriculture-based entity. The use of this
model raises a lot of controversy, primarily, associated with relevant quality and reliability of the information it
produces. Research used qualitative method with data collection through literature study, survey, interview, and
observation. Survey and interview were divided into two major parts, which were: on the compilers of financial
statements and the stakeholders. From this study it can be concluded that the PSAK based on IAS 41 have not to
be implemented yet in the near future due to IAS 41 will undergo quite significant revision. Currently, the State-
Owned Enterprises could use the PSAK plantation SOE that has been issued.
Keywords: entity, agriculture, finance
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan PSAK yang diadopsi dari IAS 41:
Agriculture, perlu diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya BUMN Perkebunan agar
informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih berguna bagi pengambilan keputusan. Lebih jauh penelitian
ini ingin menjawab manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan PSAK tersebut pada BUMN berbasis
Perkebunan. Karakteristik utama dari IAS adalah penggunaan model nilai wajar untuk aktiva biologis yang
dimiliki oleh entitas berbasis pertanian. Penggunaan model ini menuai banyak kontroversi terutama terkait
kualitas relevan dan keandalan informasi yang dihasilkannya. Metode penelitian berupa metode penelitian
kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, survei, interview, dan observasi. Survei dan
interview dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pada penyusun laporan keuangan dan pada pemegang
kepentingan. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa PSAK yang berbasis IAS 41 belum akan diterapkan
dalam waktu dekat ini karena IAS 41 sendiri akan mengalami revisi yang cukup signifikan. Saat ini BUMN
perkebunan dapat menggunakan PSAK BUMN Perkebunan yang telah diterbitkan.
Kata kunci: entitas, pertanian, keuangan
186 BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 5 No. 1 Mei 2014: 186-193
PENDAHULUAN
Indonesia, sebagai salah satu anggota G20, telah ikut serta dalam kesepakatan pemimpin
negara G20 di Washington DC, 15 November 2008, mengenai pencanangan prinsip-prinsip G20.
Prinsip G20 tersebut kemudian diperdalam dalam pertemuan G20 di London, 2 April 2009, yang salah
satunya adalah Strengthening Financial Supervision and Regulation dengan salah satu butirnya
berbunyi: “…achieve a single set of high-quality global accounting standards.” Berdasarkan
kesepakatan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melaksanakan amanat dari Pemerintah RI
tersebut dengan melakukan konvergensi standar akuntansi nasional ke standar akuntansi internasional.
Standar akuntansi internasional yang dimaksud adalah standar yang dikembangkan oleh International
Accounting Standard Board (IASB). Dengan demikian, arah standar akuntansi berubah dari yang
semula berkiblat ke United States Generally Accepted Accounting Standard Principle (US GAAP) ke
IFRS. Konvergensi IFRS tersebut diharapkan dapat (1) memudahkan pemahaman atas laporan
keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional
(enhance comparability); (2) meningkatkan arus investasi global melalui transparansi; (3) menurunkan
biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global; (4)
menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
Untuk dapat mencapai hal-hal yang diharapkan tersebut, Dewan Standar IAI telah menyusun
roadmap konvergensi IFRS sebagai berikut. Pertama, tahap adopsi (2008-2010) dengan agenda
mengadopsi seluruh IFRS ke PSAK, mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, dan mengevaluasi
dan mengelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Kedua, tahap persiapan akhir (2011)
dengan agenda menyelesaikan persiapan infrastruktur yang diperlukan dan menerapkan secara
bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS. Ketiga, tahap implementasi (2012) dengan agenda
menerapkan PSAK berbasis IFRS secara bertahap dan mengevaluasi dampak penerapan PSAK secara
komprehensif. Standar akuntansi internasional merupakan satu standar yang diharapkan menjadi
standar dengan kualitas andal dan mempunyai banyak manfaat. Salah satu manfaat pentingnya yaitu
meningkatkan kemampuan daya banding laporan keuangan terutama laporan keuangan perusahaan
multinasional (Saudagaran, 2001). Beberapa manfaat lain dari standar akuntansi internasional menurut
adalah bahwa suatu standar akuntansi internasional dapat membuka kemungkinan perbandingan
laporan keuangan antarnegara, meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, mengurangi
biaya informasi, dan menekan informasi yang tidak simetris (Ball, 2006). Terlebih lagi untuk negara
berkembang, yang belum mampu untuk membuat standar akuntansi yang kuat, adopsi standar
akuntansi internasional dapat memperkuat kemampuan kompetitif dalam pasar modal (Peavy &
Webster, 1990).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BUMN Perkebunan perlu menerapkan
PSAK adopsi IAS 41 Agriculture dan apakah penerapan tersebut dapat bermanfaat bagi pemegang
kepentingan sehingga pelaporan keuangan akuntabel dan transparan; dengan demikian mendorong
pengambilan keputusan yang lebih tepat. Penelitian diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi
dalam mengevaluasi dampak penerapan PSAK khususnya PSAK yang mengadopsi IAS 41
Agriculture pada BUMN Perkebunan di Indonesia.
Tinjauan Pustaka
Secara tradisional, perusahaan-perusahaan berbasis agrikultur menggunakan model biaya
historis (historical cost model) dalam pelaporan keuangannya walaupun model biaya historis ini gagal
menjadi ukuran salah satu aset terpenting perusahaan agrikultur yaitu aset biologis. Aset biologis tidak
dapat secara tepat diukur menggunakan model biaya historis karena keunikan aset ini dengan
karakteristik aset tersebut dapat berkembang dan bereproduksi secara alami (Argiles & Slof, 2001).
Penerapan PSAK Adopsi …… (Stefanus Ariyanto; dkk) 187
Selain itu, pengukuran menggunakan model biaya historis dinilai tidak dapat menangkap dan
mencerminkan fenomena pasar yang berubah secara cepat dalam aset biologis (Cowan, 1972).
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dan Canadian of Chartered
Accountants (CICA) masing-masing pada 1985 dan 1986 menerbitkan pedoman akuntansi khusus
untuk perusahaan-perusahaan berbasis agrikultur. Pedoman ini mensyaratkan pengukuran hasil panen
dan hasil peternakan. Pada Februari 2001, International Accounting Standard Committee menerbitkan
International Accounting Standard 41 yang merupakan standar akuntansi untuk perusahaan-
perusahaan berbasis agrikultur (IASC, 2001). Ciri utama dari standar akuntansi ini adalah penggunaan
model nilai wajar (fair value model) untuk pengukuran aset biologisnya. Penggunaan model nilai
wajar untuk aset biologisnya ini diyakini membuat IAS 41 merupakan standar akuntansi yang
menyediakan a good conceptual framework (Argiles & Slof, 2001). Penggunaan model nilai wajar ini
didukung karena model ini dianggap mendorong transparansi dan pengambilan keputusan yang baik
karena model nilai wajar ini mencerminkan kondisi pasar saat itu (Laux & Leuz, 2009). Meskipun
begitu, IAS 41 juga menimbulkan banyak kontroversi. Salah satu kontroversi tersebut adalah
anggapan bahwa pendekatan yang digunakan IAS 41 too academic dan tidak fokus pada praktik
pelaporan aset biologis (Herbohn & Herbohn, 2006).
Lebih jauh, terkait penggunaan model nilai wajar beberapa penelitian meragukan keunggulan
penggunaan model nilai wajar ini. Penggunaan nilai wajar lemah dari sisi keandalan informasi dan
kemudahan untuk dipahami karena nilai wajar berpijak pada harga pasar arbitrer yang subjektif
(Barlev & Haddad, 2003; Penman, 2007; Benston, 2008). Penggunaan model nilai wajar memakan
biaya dalam mendapatkan informasi harga wajar, terutama untuk entitas-entitas pelapor pada negara-
negara berkembang (Elad, 2004). Selain itu, penggunaan nilai wajar menimbulkan volatilitas pada
laba rugi yang dilaporkan entitas dan sering kali gagal untuk menangkap substansi ekonomi yang
sebenarnya terjadi (Fargher, 2001; Penman, 2007). Gambar 1 menunjukkan perlakuan aset biologis.
Gambar 1 Diagram Ilustrasi Perlakuan Aset Biologis
Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, terdapat empat
karakteristik kualitatif utama dalam pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dapat
memberikan informasi yang berguna bagi pemakai. Empat karakteristik tersebut adalah dapat
dipahami (understandability), relevan (relevance), keandalan (reliability), dapat diperbandingkan
(comparability) (IASB, 2001). Empat karakteristik tersebut harus dicapai agar laporan keuangan dapat
mencapai tujuannya. Akan tetapi, sering kali untuk memperoleh tingkat yang tinggi, suatu
karakteristik harus mengorbankan karakteristik lain; misalnya beberapa pendapat mengatakan bahwa
terdapat trade offs antara karakteristik keandalan dan relevan. Bahkan, beberapa pendapat mengatakan
bahwa keandalan harus lebih tinggi daripada karakteristik relevan (Johnson, 2005).
188 BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 5 No. 1 Mei 2014: 186-193
Informasi yang akan berguna bagi pengguna laporan keuangan adalah informasi yang dapat
dipahami (IASB, 2001). Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa penerapan mark-to-
market sulit dipahami baik oleh penyusun maupun pengguna laporan keuangan karena terlalu
akademis dan akan sangat sulit dipahami lagi pada negara berkembang (Elad, 2004). Sementara dalam
pengambilan keputusan informasi yang relevan diperlukan, yaitu informasi yang dapat memengaruhi
pengambilan keputusan ekonomi dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan
masa depan (IASB, 2001). Informasi yang relevan pada industri pertanian berfokus pada pengukuran
yang secara tradisional menggunakan model biaya historis.
METODE
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh BUMN berbasis perkebunan yang meliputi PTPN I
sampai dengan PTPN XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Sedangkan sampel yang akan
diambil adalah sebagai berikut. Penekanan pada penelitian ini adalah tanaman tebu yang digolongkan
sebagai tanaman semusim.
Tabel 1 Sampel Penelitian
No Nama Perusahaan Lokasi
1 PTPN II Jakarta
2 PTPN VII Lampung
3 PTPN VIII Jawa Barat
4 PTPN IX Jawa Tengah
Metode pengumpulan data berupa tinjauan literatur yang diperoleh dari laman web, literatur
keilmuan terkait, artikel yang dipublikasikan, dan laporan keuangan entitas. Kemudian survei
menggunakan kuesioner berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Lalu
wawancara yang dibagi menjadi dua yaitu penyusun laporan keuangan (dalam hal ini penyusun
laporan keuangan perusahaan sampel) dan pemegang kepentingan yaitu pemerintah sebagai pemegang
saham yang diwakili kementrian BUMN dan kementrian keuangan, auditor internal maupun eksternal,
dan masyarakat diwakili akademisi. Selanjutnya observasi dilakukan on site pada masing-masing
sampel perusahaan.
Validitas penelitian adalah kemampuan untuk mengukur sesuatu yang dimaksudkan untuk
diukur. Penelitian menggunakan metode kualitatif sehingga validitas penelitan sangat penting. Untuk
itu kuesioner berupa pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dikirimkan kepada responden
sebelum proses wawancara untuk memberikan waktu kepada responden mempersiapkan diri. Dengan
demikian, proses wawancara diharapkan akan lebih fokus pada permasalahan dan pengumpulan data
efektif dengan memperoleh hanya informasi yang diperlukan saja. Untuk menjaga validitas,
pewawancara adalah orang yang kompeten dalam subjek penelitian dan mengerti tujuan penelitian.
Proses wawancara direkam dengan seizin responden untuk menjaga ketepatan informasi yang
diperoleh. Reliabilitas mengukur sampai mana tingkat penelitian bebas dari kesalahan. Dalam
penelitian kualitatif, reliabilitas tidak sepenting validitas karena terdapat kemungkinan proses
wawancara akan menghasilkan simpulan yang berbeda. Hasil wawancara akan dikonfirmasikan ulang
kepada responden untuk disetujui agar hasil tersebut bebas dari salah pengertian (misinterpretation).
Selanjutnya, untuk menjaga konsistensi jawaban, suatu permasalahan akan ditanyakan dengan
menggunakan model pertanyaan yang berbeda.
Penerapan PSAK Adopsi …… (Stefanus Ariyanto; dkk) 189
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini mengambil sampel tanaman tebu yang dikategorikan sebagai tanaman semusim.
Tanaman ini merupakan tanaman utama yang dibudidayakan oleh PTPN. Siklus hidup tanaman tebu
dimulai dari penanaman bibit. Bibit tebu yang ditanam umumnya berupa stek tanaman tebu berumur 5
sampai 7 bulan yang dipotong menjadi beberapa bagian. Setiap bagian mengandung 3 sampai 4 mata
tunas. Bibit ini dapat digunakan untuk 3-4 kali masa tanam, bergantung dengan jumlah mata tunasnya.
Pengakuan dan Pengukuran
Menurut IAS 41, aset biologis harus diakui berdasarkan nilai awal yaitu sebesar nilai
perolehannya. Menurut Ditjen Perkebunan, terdapat beberapa biaya dalam proses penanaman tebu
yaitu biaya bibit, persiapan lahan, pengolahan tanah sampai dengan siap tanam, penanaman, dan
keprasan atau penyulaman. Dalam implementasi IAS 41, biaya-biaya tersebut akan dikapitalisasi
sebagai nilai perolehan awal tanaman tebu. Biaya-biaya tersebut akan mudah diidentifikasi karena
dilaporkan melalui kegiatan-kegiatan yang terpisah. Selanjutnya, jika terdapat selisih antara biaya
perolehan dengan nilai wajar bibit dikurangi perkiraan biaya untuk menjual, selisih tersebut harus
diakui sebagi keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi.
Pemeliharaan tanaman tebu dilakukan dengan kegiatan pemupukan dan pengairan. Sebanyak
85-90% dari bobot segar sel-sel dan jaringan tanaman tinggi adalah air (Maynard dan Orcott, 1987).
Noggle dan Frizt dalam Efendi (2009) menjelaskan beberapa fungsi air bagi tanaman di antaranya
sebagai senyawa utama pembentuk protoplasma, sebagai senyawa pelarut bagi masuknya mineral-
mineral dari larutan tanah ke tanaman dan sebagai pelarut mineral nutrisi yang akan diangkut dari satu
bagian sel ke bagian sel lain, maupun sebagai media terjadinya reaksi-reaksi metabolik. Oleh karena
itu, kegiatan pengairan menjadi sebuah keharusan dan memiliki nilai manfaat untuk mempertahankan
kelangsungan hidup tanaman tebu. Prinsip ini sesuai dengan prinsip kapitalisasi aset sehingga biaya
atas kegiatan pengairan perlu dikapitalisasi ke dalam nilai aset biologis.
Berdasarkan pedoman akuntansi perkebunan berbasis IFRS, biaya pemupukan merupakan
biaya proses yang dapat langsung diatribusikan pada tanaman tebu. Setiap biaya yang dikeluarkan
untuk aktivitas pemupukan akan menambah nilai tanaman tebu. Akan tetapi, perlu diperhatikan lebih
lanjut bahwa kapitalisasi ini sangat berhubungan dengan fase hidup tanaman tebu. Setiap varietas tebu
memiliki masa tumbuh optimal yang berbeda-beda. Dalam tahap pertumbuhan dari bibit hingga masa
optimal ini, rendemen tanaman tebu memiliki potensi peningkatan. Sedangkan setelah melewati masa
tersebut, rendemennya akan cenderung mengalami penurunan terkait adanya penuaan tanaman. Nilai
rendemen ini sangat penting dan berpengaruh terhadap jumlah produk agrikultur yang dihasilkan
berupa gula pasir.
Dalam perjalanannya tanaman tebu dapat mengalami kematian dengan berbagai sebab
misalnya kematian secara alami karena serangan hama, kondisi tanah, maupun cuaca yang tidak
mendukung. Proses identifikasi tanaman tebu yang mati akan sulit jika dihitung secara satuan karena
begitu luasnya lahan tebu dan amat rapat jarak setiap tanaman. Oleh karena itu, identifikasi ini dapat
dilakukan dengan melihat pertumbuhan sekelompok tanaman tebu pada petak tertentu. Jika tanaman
tebu sudah mati akan tampak tanda-tanda seperti daun tanaman menguning dan batang tebu menjadi
kering. Atas kematian tanaman tebu tersebut, perusahaan harus mendebit adanya rugi karena
kehilangan masa mafaat dari tanaman tersebut. Sedangkan pada sisi kredit perusahaan harus
memasukkan nilai aset biologis yang hilang pada saat diidentifikasi adanya kematian tanaman tebu.
IAS 41 mewajibkan penggunaan nilai wajar untuk produk agrikultur yang baru saja dipanen.
Lefter dan Roman (2007) berpendapat bahwa hal ini dilakukan agar proses transformasi yang ada bisa
190 BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 5 No. 1 Mei 2014: 186-193
segera terwakili di laporan keuangan sehingga membantu investor dalam mengestimasi keuntungan
ekonomis pada masa depan. Penggunaan nilai wajar bisa diterapkan dengan mudah pada produk
agrikultur tebu yang baru dipanen. Hal ini karena terdapat cukup banyak pasar untuk tebu yang baru
saja dipanen. Pasar yang terjadi antara penjual tebu (petani) dan pembeli tebu (pabrik gula) dapat
dikatakan pasar aktif karena pertama, barang yang dijual homogeny (tebu); kedua, penjual dan
pembeli yang berkeinginan melakukan transaksi dapat dengan mudah ditemukan karena umlah mereka
lebih dari satu sehingga tidak ada pihak yang bisa memengaruhi harga pasar secara dominan; ketiga,
harga tanaman tebu dapat diketahui publik dengan mudah.
Saat panen bisa saja terjadi selisih antara nilai kapitalisasi terakhir dan nilai wajar saat titik
panen dikurangi perkiraan biaya untuk menjual. Selisih tersebut harus diakui sebagai keuntungan atau
kerugian dan dilaporkan dalam laba rugi. Misalnya saat 31 Desember 2012 perusahaan mencatat nilai
tanaman-tanaman tebu (consumable biological assets) adalah Rp1.000.000,00. Saat panen, nilai wajar
dikurangi biaya menjual tanaman tadi menjadi Rp1.200.000,00. Maka entitas harus mengakui
Rp200.000,00 sebagai keuntungan dan melaporkannya dalam laporan laba rugi. Nilai Rp1.200.000,00
selanjutnya dianggap sebagai biaya perolehan persediaan.
Penyajian dan Pengungkapan
Pengklasifikasian tebu siap panen sebagai persediaan seperti yang dilakukan oleh PTPN II dan
Pedoman Penyajian dan PLK Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perkebunan sesuai dengan
Aryanto (2011). Consumable biological assets yang umurnya kurang dari satu tahun sebaiknya
diperlakukan sama dengan persediaan; jika terjadi transformasi biologis sebaiknya diperlakukan
sebagai barang dalam proses (Aryanto, 2011). Namun aset biologis yang berumur kurang dari satu
tahun lebih tepat jika diklasifikasikan sebagai aset biologis, bukan sebagai persediaan. Alasan
pengklasifikasian tersebut adalah adanya transformasi biologis pada aset tersebut. Transformasi
tersebut berkaitan dengan proses accretion (pertambahan), yang pendapatan bisa diperoleh sepanjang
aset tersebut tumbuh (Aryanto, 2011).
SIMPULAN
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pengungkapan aset biologis tanaman tebu
sebaiknya dikelompokkan berdasarkan lokasi jika entitas mempunyai tebu di beberapa lokasi yang
berbeda dengan karakteristik biaya dan kesuburan tanah yang berbeda-beda. Lefter dan Roman (2007)
menyatakan sebaiknya aset biologis dibagi berdasarkan sudut pandang lokasi jika perbedaan lokasi
menyebabkan perbedaan karakteristik dan perbedaan biaya. Terkait perkebunan tebu, keuntungan atau
kerugian akibat perubahan nilai wajar aset biologis dikurangi biaya menjual memang lebih tepat jika
dilaporkan dalam laba rugi. Hal ini karena umur tanaman tebu yang relatif pendek (hanya 8-14 bulan),
sehingga keuntungan akibat revaluasi akan segera terealisasi beberapa bulan kemudian. Pengakuan
keuntungan atau kerugian setelah revaluasi akan membuat laporan keuangan makin relevan dan
mewakili keadaan yang sesungguhnya.
Penerapan PSAK Adopsi …… (Stefanus Ariyanto; dkk) 191
DAFTAR PUSTAKA
Argiles, J., & Slof, E. (2001). New opportunities for farm accounting. The European Accounting
Review, 10(2), 361-383.
Aryanto, Y. H. (2011). Theoretical Failure of IAS 41. Diakses dari
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1808413
Ball, R. (2006). International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors.
Accounting and Business Research, 5-27.
Barlev, B., & Haddad, J. (2003). Fair value accounting and management of the firm. Critical
Perspectives on Accounting, 14(4), 383-415.
Benston, G. (2008). The shortcomings of fair-value accounting described in SFAS 157. Journal of
Accounting and Public Policy, 27(2), 101-114.
Cowan, T. (1972). Fact and fiction in farm accounting. Accountant's Journal , 130-139.
Elad, C. (2004). Fair value accounting in the agricultural sector: Some implications for international
accounting harmonisation. European Accounting Review, 13(4), 621-641.
Fargher, N. (2001). Management perceptions of fair-value accounting for all financial instruments.
Australian Accounting Review, 11(2), 62-72.
Herbohn, K., & Herbohn, J. (2006). International Accounting Standards (IAS) 41: what are the
implications for reporting forest assets. Small-scale Forest Economics, Management and
Policy, 5(2), 175-189.
IASB. (2001). Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. International
Accounting Standards Board.
IASB. (2009). International Accounting Standard 41 Agriculture. Diakses dari
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/ac/ias41_en.pdf
IASC. (2001). International Accounting Standard 41: Agriculture. International Accounting
Standards Committee.
Insitut Akuntan Publik Indonesia (2002). Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan
Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perkebunan. Diakses dari
http://www.iapi.or.id/member_area/PLK/Industri%20Perkebunan.pdf
Johnson, T. L. (2005, February). Relevance and reliability. The FASB Report.
Laux, C., & Leuz, C. (2009). The crisis of fair-value accounting: making sense of the recent debate.
Accounting, Organizations and Society, 34(6-7), 826-834.
Lefter, V., & Roman, C. (2007). The fiscal control and the financial jurisdiction – components of the
competitive management. Theoretical and Applied Economics, 11(11), 53-58.
192 BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 5 No. 1 Mei 2014: 186-193
Maynard, G. H., & Orcott, D. M. (1987). The Physiology of Plants Under Stress. New York:
John Willey and Sons.
Peavy, D., & Webster, S. (1990). Is GAAP the gap to international market? Management Accounting,
72, 31-35.
Pedoman Akuntansi BUMN perkebunan berbasis IFRS.
http://docs.rni.co.id/trainsite/Lists/Announcements/Attachments/8/Pedoman%20Akuntansi%2
0Perkebunan%20BUMN%20-%2005122011.pdf
Penman, S. H. (2007). Financial reporting quality: is fair value a plus or a minus? Accounting and
Business Research. Special issue: International Accounting Policy Forum, 33-44.
PT Perkebunan Nusantara II (2012). Laporan Tahunan PTPN II 2011. Diakses dari
http://ptpn2.com/AnnualReport2011.pdf
Saudagaran, S. (2001). International Accounting: A User Perspective. South Western College.
Penerapan PSAK Adopsi …… (Stefanus Ariyanto; dkk) 193
You might also like
- Implications For GAAP From An Analysis of Positive Research in AccountingDocument41 pagesImplications For GAAP From An Analysis of Positive Research in AccountingZhang PeilinNo ratings yet
- Individual Assignment Cost and Management AccountDocument4 pagesIndividual Assignment Cost and Management AccountSahal Cabdi Axmed100% (2)
- A Project Report ON: Ifrs (International Financial Reporting Standards) & Its Convergence in IndiaDocument80 pagesA Project Report ON: Ifrs (International Financial Reporting Standards) & Its Convergence in IndialalsinghNo ratings yet
- Life-Cycle Assessment of BiorefineriesFrom EverandLife-Cycle Assessment of BiorefineriesEdgard GnansounouNo ratings yet
- Financial Performance Measures and Value Creation: the State of the ArtFrom EverandFinancial Performance Measures and Value Creation: the State of the ArtNo ratings yet
- Manajemen Laba (Earnings Management)Document35 pagesManajemen Laba (Earnings Management)ricky OkNo ratings yet
- Rizky Purwanti Akhmad Riduwan: Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Nilai PerusahaanDocument17 pagesRizky Purwanti Akhmad Riduwan: Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Nilai PerusahaanRambu YanaNo ratings yet
- Analisis Pendekatan Nilai Wajar Dan Nilai Historis Dalam Penilaian Aset Biologis Pada Perusahaan Agrikultur: Tinjauan Kritis Rencana Adopsi IAS 41Document38 pagesAnalisis Pendekatan Nilai Wajar Dan Nilai Historis Dalam Penilaian Aset Biologis Pada Perusahaan Agrikultur: Tinjauan Kritis Rencana Adopsi IAS 41Amir Na'nungNo ratings yet
- Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Adopsi Penuh IfrsDocument16 pagesRelevansi Nilai Informasi Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Adopsi Penuh IfrsRyanNo ratings yet
- 3818 12065 1 PBDocument11 pages3818 12065 1 PBNadia DiaNo ratings yet
- Psak 69 ResearchDocument28 pagesPsak 69 Researchqori qonitaNo ratings yet
- Diffusionofnewmanagementaccountingpractices IndiaDocument26 pagesDiffusionofnewmanagementaccountingpractices IndiaWasis KurniawanNo ratings yet
- The Greater Emphasis On The Conceptual FrameworkDocument10 pagesThe Greater Emphasis On The Conceptual FrameworkMuh Niswar AdhyatmaNo ratings yet
- Adam ZakariaDocument28 pagesAdam ZakariaRajipah OsmanNo ratings yet
- Artikel 3Document34 pagesArtikel 3Vania Dinda AzuraNo ratings yet
- International Accounting Standard Setting - A Network ApproachDocument34 pagesInternational Accounting Standard Setting - A Network ApproachBlaNo ratings yet
- PEU Method: An Analysis of Its Applicability and Implementation Limitations in Brazilian CompaniesDocument16 pagesPEU Method: An Analysis of Its Applicability and Implementation Limitations in Brazilian CompaniesIJAERS JOURNALNo ratings yet
- Week 9Document28 pagesWeek 9khunaina il khafa ainul NazilatulNo ratings yet
- Operationalising The Qualitative Characteristics of Financial ReportingDocument10 pagesOperationalising The Qualitative Characteristics of Financial ReportingFauziah MustafaNo ratings yet
- Earning MGT 5Document12 pagesEarning MGT 5anubhaNo ratings yet
- Effect of Application of PSAK 69: Agriculture On Assets Biological Against The Company Value of Agro-Industry in Indonesia Stock ExchangeDocument11 pagesEffect of Application of PSAK 69: Agriculture On Assets Biological Against The Company Value of Agro-Industry in Indonesia Stock Exchange082368274467No ratings yet
- Accounting Perspectives - 2017 - Jin - DuPont Analysis Earnings Persistence and Return On Equity Evidence From MandatoryDocument31 pagesAccounting Perspectives - 2017 - Jin - DuPont Analysis Earnings Persistence and Return On Equity Evidence From MandatorypedrufakkeNo ratings yet
- A Theoretical Model of Stakeholder PerceptionsDocument16 pagesA Theoretical Model of Stakeholder PerceptionsDiana IstrateNo ratings yet
- Model Managemen LabaDocument14 pagesModel Managemen LabaBima SaktiNo ratings yet
- 2364 6625 1 PBDocument19 pages2364 6625 1 PBOrmanda AryadewaNo ratings yet
- ID Kandungan Prinsip Konservatisme Dalam Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Ifrs I PDFDocument11 pagesID Kandungan Prinsip Konservatisme Dalam Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Ifrs I PDFMuhammad Fauzan H FauzanNo ratings yet
- Article CritiqueDocument5 pagesArticle CritiqueFauzi Al nassarNo ratings yet
- Chapter One Introduction 1.1 Background To The StudyDocument7 pagesChapter One Introduction 1.1 Background To The StudytoyeebNo ratings yet
- Tugas Akuntansi Biaya: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarDocument36 pagesTugas Akuntansi Biaya: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarRachel ThomasNo ratings yet
- Akuntansiku 3 Siap TerbitDocument18 pagesAkuntansiku 3 Siap Terbitputri alisyahNo ratings yet
- Value Relevance of Accounting Information and Firm ValueDocument19 pagesValue Relevance of Accounting Information and Firm ValueRosedian AndrianiNo ratings yet
- شركة المراعي PDFDocument9 pagesشركة المراعي PDFAhmed El KhateebNo ratings yet
- Management Accounting Change: ABC Adoption and ImplementationDocument17 pagesManagement Accounting Change: ABC Adoption and ImplementationAdriana CalinNo ratings yet
- Convergence and Foreign InvestmentsDocument26 pagesConvergence and Foreign InvestmentsFlorie-May Garcia100% (1)
- Investigating and Prioritizing Factors Affecting The Perceptions of Professionals For Implementation of IFRS: An Analytic Hierarch y Process (AHP) ApproachDocument25 pagesInvestigating and Prioritizing Factors Affecting The Perceptions of Professionals For Implementation of IFRS: An Analytic Hierarch y Process (AHP) ApproachutopiaNo ratings yet
- Synthesis - IFRSDocument37 pagesSynthesis - IFRSRoseJeanAbingosaPernito0% (1)
- Project Paper Suraiya Yeasmin Revised On 30 JuneDocument42 pagesProject Paper Suraiya Yeasmin Revised On 30 JuneNifaz KhanNo ratings yet
- Main BodyDocument59 pagesMain Bodyfahim zamanNo ratings yet
- Farjana - FINAL PDFDocument17 pagesFarjana - FINAL PDFJaved Ahsan SamunNo ratings yet
- A Research On Use of Management Accounting Tools and Techniques in Fast Food OperationsDocument14 pagesA Research On Use of Management Accounting Tools and Techniques in Fast Food OperationsNgọc HunterNo ratings yet
- Case Study 2.1: New Accounting Rules Don't Add Up'Document7 pagesCase Study 2.1: New Accounting Rules Don't Add Up'abrori100% (1)
- The Accounting Value Relevance of Psak 71 Adi Susherwanto Rr. Sri HandayaniDocument14 pagesThe Accounting Value Relevance of Psak 71 Adi Susherwanto Rr. Sri HandayaniZainal AbidinNo ratings yet
- Have IFRS Made A Difference To Intra-Country Financial ReportingDocument17 pagesHave IFRS Made A Difference To Intra-Country Financial ReportingDiana IstrateNo ratings yet
- The Impact of IFRS On Financial StatementsDocument84 pagesThe Impact of IFRS On Financial StatementsPrithviNo ratings yet
- Jurnal KeuanganDocument14 pagesJurnal KeuanganJohanno Radithya MarcoNo ratings yet
- Ums24 L K L Tarafa Iklamalarinauyumvedenet Mkom Tes Ver ML L Bisttel Stelenm Rketler Zer Neamp R KB Ranal z740818-11139473Document33 pagesUms24 L K L Tarafa Iklamalarinauyumvedenet Mkom Tes Ver ML L Bisttel Stelenm Rketler Zer Neamp R KB Ranal z740818-11139473Vincent ChuaNo ratings yet
- Ifrs Literature ReviewDocument4 pagesIfrs Literature ReviewAsfawosen DingamaNo ratings yet
- Applications of Contemporary Management Accounting Techniques in Indian Industry: An Empirical Study - PHD (2006), by Liaqat Ali, Faculty ofDocument4 pagesApplications of Contemporary Management Accounting Techniques in Indian Industry: An Empirical Study - PHD (2006), by Liaqat Ali, Faculty ofananth6No ratings yet
- Accounting Theory Assignment 1410531056Document5 pagesAccounting Theory Assignment 1410531056diahNo ratings yet
- Article Review On: Profitable Working Capital Management in Industrial Maintenance CompaniesDocument5 pagesArticle Review On: Profitable Working Capital Management in Industrial Maintenance CompaniesHabte DebeleNo ratings yet
- Habib 2019Document26 pagesHabib 2019Salma ChakrounNo ratings yet
- Impact of IFRS On Current Reporting Practices of Indian CompaniesDocument7 pagesImpact of IFRS On Current Reporting Practices of Indian Companiessandeepkaur25No ratings yet
- A Framework To Assess Sustaining Continuous Improvement in Lean HealthcareDocument21 pagesA Framework To Assess Sustaining Continuous Improvement in Lean HealthcareAhmad HassanNo ratings yet
- An IFRS-based Taxonomy of Financial RatiosDocument16 pagesAn IFRS-based Taxonomy of Financial RatiosWihelmina DeaNo ratings yet
- 12.determinants of IFRSDocument21 pages12.determinants of IFRSOsman HaliduNo ratings yet
- 73 GNJ XCZBF 3 Q 6 Ry Ict 1 o XF7 BLQ Un Ov YEd ZSTZK MHDocument75 pages73 GNJ XCZBF 3 Q 6 Ry Ict 1 o XF7 BLQ Un Ov YEd ZSTZK MHMarcus MonocayNo ratings yet
- Towards an XBRL-enabled corporate governance reporting taxonomy.: An empirical study of NYSE-listed Financial InstitutionsFrom EverandTowards an XBRL-enabled corporate governance reporting taxonomy.: An empirical study of NYSE-listed Financial InstitutionsRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- Value Creation in Management Accounting and Strategic Management: An Integrated ApproachFrom EverandValue Creation in Management Accounting and Strategic Management: An Integrated ApproachNo ratings yet
- Disclosure on sustainable development, CSR environmental disclosure and greater value recognized to the company by usersFrom EverandDisclosure on sustainable development, CSR environmental disclosure and greater value recognized to the company by usersNo ratings yet
- Guidebook for Evaluating Fisheries Co-Management EffectivenessFrom EverandGuidebook for Evaluating Fisheries Co-Management EffectivenessNo ratings yet