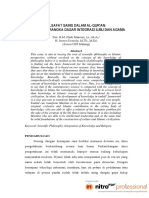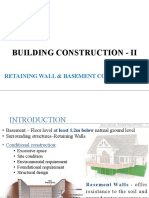Professional Documents
Culture Documents
Agama Dan Tantangan Modernitas: Neneng Munajah
Agama Dan Tantangan Modernitas: Neneng Munajah
Uploaded by
Hengki AjiOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Agama Dan Tantangan Modernitas: Neneng Munajah
Agama Dan Tantangan Modernitas: Neneng Munajah
Uploaded by
Hengki AjiCopyright:
Available Formats
AGAMA DAN TANTANGAN MODERNITAS
https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/view/1433
DOI: https://doi.org/10.34005/tahdzib/v4i1/1433
Neneng Munajah
Universitas Islam As-syafi’iyah
Abstract (In English): Modern as a phase of life that is based on a rational
pattern of thinking and lifestyle. Modern is rational, scientific, in accordance
with the laws that apply in nature. As an understanding that applies science,
there are consequences for absolute obligations and obligations for humans.
Therefore, modernism is seen as God's commandment, thus Islam is
synonymous with modernity. Modernism is an attempt to realize the truth, and
that truth must be constantly sought. Truth, can only be achieved through a
process, and humans will never get that truth perfectly, without real effort. An
earnest search for truth is an attitude demanded by Islamic teachings.
Modernism is the commandment of Islamic teachings, so Islam and modernity
are identical. Rationalism is a paradigm based on the belief in the power of
human reason and reason. In this paradigm, something is declared true, if it
can be proven and can be accepted rationally. The phenomenon of scientism
in the Western world shows us that science has become a new ideology or
religion (pesudo religion). Western society marginalizes religion even if it can
be said to abolish all sacred religious beliefs, and only accepts and believes in
science. This belief emerged around the 18-19 century, science has become
an idol that is worshiped by modern humans. Modernism is recognized to have
brought wealth physically - materially. This phenomenon, becomes a tendency
to dehumanize, is degraded, and reduces the quality of human life. Therefore,
the noble values of humanity, such as compassion, togetherness, solidarity
and human brotherhood are not a concern, and what stands out from modern
society is individualism. Humans in the modern age have become very
vulnerable to disease, because they have actually lost one of the fundamental
aspects, namely spiritualism. Modern man is hit by a spiritual void, he forgets
the center of the circle of existence, namely, Allah SWT. Religion provides a
solution to return to the center of the circle of human existence. Religion
answers complex problems faced by humans, such as death, suffering and
disaster. Religion answers the challenges of modernity, therefore religion must
be a guide for human life who wants to achieve happiness in life both in this
world and in the hereafter.
Keywords: Modernity, Religion, Rational
Abstrak (In Bahasa): Modern sebagai suatu Fase kehidupan yang
berlandaskan pada pola berpikir, dan gaya hidup secara rasional. Modern
bersifat rasional, ilmiah, bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku
dalam alam. Sebagai paham yang menerapkan ilmu pengetahuan melahirkan
konsekunesi atas keharusan dan kewajiban mutlak bagi manusia. Oleh sebab
itu, modernisme dipandang sebagai perintah Tuhan, dengan demikian
keislaman identik dengan kemoderenan. Modernisme sebagai usaha untuk
mewujudkan kebenaran, dan kebenaran itu harus terus-menerus dicari.
83 | Tahdzib Al Akhlak | Vol 4 | No. 1 | 2021
Kebenaran hanya dapat dicapai melalui proses , dan manusia tak akan pernah
memperoleh kebenaran itu secara sempurna, tanpa usaha yang sungguh-
sungguh. Pencarian yang sungguh-sungguh tentang kebenaran, merupakan
sikap yang dituntut oleh ajaran Islam. Modernisme menjadi perintah ajaran
Islam, Dengan begitu Keislaman dan Kemoderenan adalah identik.
Rasionalisme sebuah paradigma berpangkal pada kepercayaan akan kekuatan
akal dan budi manusia. Dalam paradigma ini, sesuatu dinyatakan benar, bila
dapat dibuktikan dan dapat diterima secara rasional. Fenomena saintisme di
dunia Barat memperlihatkan kepada kita, bahwa ilmu telah menjadi ideologi
atau agama baru (pesudo religion). Masyarakat Barat meminggirkan agama
bahkan kalau boleh dikatakan menghapus semua keyakinan agama yang suci,
dan hanya menerima dan percaya kepada ilmu pengetahuan. Keyakinan ini
muncul sekitar abad 18-19, ilmu telah menjadi berhala yang dipertuhankan
oleh manusia modern. Modernisme diakui telah mendatangkan kekayaan
secara fisik – material. Fenomena ini, menjadi kecenderungan dehumanisasi,
mengalami degradasi, dan reduksi terhadap kulitas hidup manusia. Karenanya,
nilai-nilai luhur kemanusiaan, seperti, kasih sayang, kebersamaan, solidaritas
dan persaudaraan kemanusiaan tidak menjadi perhatian, dan yang menonjol
dari masyarakat modern, justru individualisme. Manusia di abad modern
menjadi sangat rentan terhadap penyakit, karena sesungguhnya telah
kehilangan salah satu aspek yang fundamental, yaitu spiritualisme. Manusia
modern dilanda kehampaan spiritual, ia lupa kepada pusat lingkaran eksistensi
yakni, Allah SWT. Agama memberikan solusi untuk kembali ke pusat lingkaran
eksistensi manusia. Agama menjawab persoalan yang kompleks, yang
dihadapi manusia, seperti kematian, penderitaan dan bencana. Agama
menjawab tantangan modernitas, oleh sebab itu agama harus menjadi
pedoman hidup manusia yang ingn mencapai kebahagian hidup baik hidup di
dunia maupun di akhirat.
Kata Kunci : Modernitas, Agama, Rasional
MAKNA MODERNITAS
Pengertian modernitas berasal dari perkataan “modern” dan makna
umum dari perkataan modern adalah segala sesuatu yang bersangkutan
dengan kehidupan masa kini. Lawan kata modern adalah kuno, yaitu segala
sesuatu yang berurusan dengan masa lampau. Jadi, modernitas adalah
pandangan yang dianut untuk menghadapi masa kini. Selain sifat pandangan,
modernitas juga merupakan sikap hidup yang dianut dalam menghadapi
kehidupan masa kini1.
Modernitas sebagai pandangan dan sikap hidup yang bersangkutan
dengan kebiasaan masa kini, banyak dipengaruhi oleh peradaban modern.
Sedangkan yang dimaksud dengan peradaban modern, adalah peradaban
yang dibentuk mula-mula dari Eropa Barat, kemudian menyebar ke seluruh
dunia. Peradaban modern itu terbentuk pada abad ke-16 melalui suatu
perubahan yang penting di Eropa barat dikenal dengan Renaisanse.
Peradaban Barat mempunyai pengaruh besar terhadap modernitas,
oleh karena peradaban Barat pada saat sekarang ini, merupakan peradaban
1 Lihat Sayidiman Suryohaniprojo, “Makna Modernitas dan Tantangannya Terhadap Iman”,
dalam Nurcholish Madjid dkk, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Paramadina,
Jakarta, Cetakan I, 1994, hal 553-554.
Agama Dan Tantangan | 84
yang dominan di dunia, sebagaimana pula Islam pada abad 6 sampai dengan
abad 16 mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan peradaban
Barat. Oleh sebab itu, untuk mengenal dan mengembangkan modernitas,
sangat tidak mungkin tanpa mengetahui unsur-unsur utama peradaban Barat.
Modernisme dipandang sebagai suatu “gerakan” pemikiran pada fase
tertentu dalam perkembangan sejarah manusia untuk menangani “proyek”
pengembangan peradaban dan kemanusiaan, tampil dalam beberapa tema.
Pertama, pemisahan antara bidang sakral dan duniawi, yang dalam
kehidupan praktis tercermin dalam pemisahan antara agama dan negara,
agama dan politik, tepatnya disebut sekularisme. Kedua, kecenderungan
pada reduksionisme. Materi dan benda direduksi kepada elemen-elemennya.
Hal ini tampak pada fisika Newton. Ketiga, pemisahan antara subjektivitas
dan objektivitas dan berujung pada kecenderungan bahwa objektivitas
merupakan keniscayaan dalam menjelaskan sesuatu. Keempat,
antroposentrisme, yang memandang manusia bukan lagi sebagai tamu dunia
(faber mundi), tapi sebagai penentu terhadap dunianya (fitiator mundi).
Kelima, progresifisme, yang dalam konteks sejarah menurut Hasan Hanafi
diwakili dengan baik sekali oleh pemikiran Marx dan Marxisme2.
Modern oleh para modernis Muslim seringkali dimengerti sebagai
dorongan untuk menguasai pendidikan, teknologi dan indrustri Barat, ide
demokrasi dan pemerintahan yang representatif. Oleh sebab itu, kebanyakan
kaum modernis berusaha melakukan sintesis dan mencari keselarasan antara
posisi mereka dan posisi Eropa, sehingga yang menjadi isu sentral dari
modernisme adalah mengupayakan agar keyakinan agama sesuai dengan
pemikiran modern3.
Sedangkan, Nurcholish Madjid memandang modernisasi sebagai
rasionalisasi. Pengertian modernisasi identik dengan rasionalisasi, yaitu
proses perombakan pola berpikir dan tata kerja yang baru yang tidak rasional,
dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja yang baru yang
rasional. Manfaat adalah untuk memperoleh daya guna yang maksimal. Jadi
tandasnya, sesuatu yang disebut modern, jika ia bersifat rasional, ilmiah dan
bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam. Dalam
pandangannya, modernisasi berarti juga penerapan ilmu pengetahuan, dan
ini merupakan keharusan “kewajiban yang mutlak”. Oleh sebab itu,
modernisasi merupakan perintah dan ajaran Tuhan. Keislaman dan
Kemoderenan adalah suatu yang identik4.
Selanjutnya, Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa modernitas
sebagai kebenaran, dan modernisasi sebagai usaha atau proses untuk
mencapai kebenaran itu. Yang modern secara mutlak ialah Tuhan Yang
Maha Esa. Kebenaran adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai dalam
2 Kazuo Shimoghaki, “Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left,
dialihbahasakan oleh M. Imam Azizi dkk, Kiri Islam, LKIS Yogyakarta, 1993, hal 25.
3 A. Ahmed S. “Discovering Islam”, Routledge, London 198, hal 44-46.
4 Nurcholish Madjid, “Islam Kemodernan dan Keindonesiaan,” Bandung, Mizan, 1987,
Cetakan 1, Hal 172.
85 | Tahdzib Al Akhlak | Vol 4 | No. 1 | 2021
proses. Kebenaran adalah tujuan, yang dapat dikatakan, manusia tak akan
pernah mencapainya secara penuh karena, keterbatasannya, tetapi harus
diupayakan dan dicari, jika ia menginginkan pengertian yang mendalam.
Pencarian yang terus-menerus tentang kebenaran (Islam), itulah yang
dinamakan sikap yang modern5.
A. Karakteristik Masyarakat Modern
Pertama, masyarakat modern bercirikan indrustrialisasi. Dikatakan
industrialisasi, karena menjadi tulang punggung dan darah daging
masyarakat modern. Dengan industrialisasi manusia berusaha memanfaatkan
kekuatan dan energi alam untuk kepentingan manusia. Dalam proses ini,
pekerjaan manusia dibantu bahkan sebagian telah dialihkan pada mesin-
mesin atau robot.
Kedua, masyarakat modern ditandai oleh kemajuan sains dan
teknologi (IPTEK) sehingga sering disebut sebagai abad modern, dan dijuluki
sebagai “Abad Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (The Age of Science and
Tecnology)”. IPTEK meneliti terutama kekuatan-kekuatan alam untuk
menopang kepentingan industrialisasi. IPTEK dikembangkan dan diarahkan
untuk peningkatan dan pelipat gandaan produksi industrial. Dengan IPTEK,
manusia modern tidak banyak bergantung pada alam, bahkan menguasai dan
menaklukan mitos ketidak jayaan alam.
Ketiga, masyarakat bercirikan perubahan. Dengan mesin industrialisasi
dan dengan dukungan sains dan teknologi maju telah melahirkan perubahan-
perubahan besar dalam kehidupan umat manusia. Perubahan paling
menonjol terlihat pada bidang komunikasi dan transportasi yang amat padat
dan cepat.
Keempat, ditandai oleh perubahan pola pikir yang sangat mendasar.
Perubahan pola pikir ini dimulai dari timbulnya keyakinan tentang keunggulan
manusia (Humanisme), kemudian berkembangan pemikiran yang
memandang manusia sebagai pusat (antroposentrisme) dan akhirnya timbul
pemikiran rasionalisme yang menjadi karakter masyarakat modern6.
Sejalan dengan paham keunggulan manusia tadi, maka rasionalisme
berpangkal kepada kepercayaan atas kekuatan akal dan budi manusia.
Paham ni mengharuskan segala sesuatu diahami dan dimengerti secara
rasional. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat dipertanyakan secara kritis dan
rasional. Dalam paradigma ini, sesuatu dinyatakan benar bila dapat
dibuktikan dan diterima secara rasional.
Dari ciri-ciri masyarakat modern di atas, tampak jelas bahwa ada bibit-
bibit “ancaman” terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan, spiritualitas dan
agama. Hal inilah merupakan sisi negatif dari kemajuan masyarakat modern
yang seyogianya harus direspon secara insentif oleh kalangan yang
berkompeten dalam masalah tersebut, sudah barang tentu para aktivis
dakwah yang didukung oleh kebijakan pejabat di lingkungan Kementerian
Agama.
5 Ibid.
6 Mazheruddin, op.cit, Hal 1-2.
Agama Dan Tantangan | 86
B. Sisi Negatif Modernitas
Fenomena saintisme di dunia Barat memperlihatkan kepada kita
bahwa ilmu telah menjadi ideologi baru, bahkan agama baru (preudi religion).
Hal ini telah berlangsung sejak abad 17 M, di mana masyarakat Barat
menyingkirkan bahkan membuang sama sekali semua keyakinan agama
yang sacral itu. Mereka menolak semua itu, dan hanya percaya kepada ilmu
pengetahuan, dan kepercayaan ini telah mencapai tingkat yang amat tinggi.
Puncaknya saintisme, yaitu abad 18 dan 19 M, ilmu telah menjadi “berhala”
yang dipertuhankan manusia modern. Seperti Tuhan, ilmu dipandang memiliki
ketetapan yang amat kuat dan tidak terdapat keraguan dan kebatilan di
dalamnya7.
Masyarakat modern menjadi sangat progresif dan agresif dalam
mengejar kemajuan. Dengan bantuan iptek, mereka ingin menguasai dan
menaklukan mitos kekuatan alam semesta. Modernisme diakui telah
mendatangkan kekayaan secara material, tetapi sangat kering dan miskin
secara etika dan moral. Segala sesuatu cenderung dilihat dari sudut
kemajuan material. Ini sesungguhnya dehumanisasi, mengalami degradasi
dan reduksi terhadap kualitas hidup manusia. Akibatnya, nilai-nilai luhur
kemanusiaan, seperti kasih sayang, kebersamaan, solidaritas dan
persaudaraan sesama manusia, kurang mendapat perhatian, yang menonjol
dari masyarakat modern justru individualisme8.
John L Esposito mengemukakan bahwa modernisme tumbuh dari
akar-akar materialisme9. Buktinya, modernisme didukung oleh mesin
ekonomi yang disebut dengan kapitalisme. Kapitalisme merupakan motor dan
penggerak modernisme. Sebagai lanjutan dari materialisme, kapitalisme
merupakan suatu faham yang memberikan nilai dan penghargaan amat tinggi
terhadap kenikmatan lahiriah10. Dalam pandangan seperti itu, jelas kriteria
etika dan moral akan terdesak oleh kriteria manfaat dan kepentingan jangka
pendek.
Dari kenyataan seperti disebutkan tadi, manusia modern kata Nasr,
telah membakar tangannya dengan api yang telah dinyalakannya karena itu
ia telah lupa siapakah ia itu sesungguhnya. Seperti yang dilakukan Faust,
setelah menjual jiwanya untuk memperoleh kekuasaan terhadap lingkungan
alam manusia, ia menciptakan suatu situasi, di mana control terhadap
lingkungan berubah menjadi pencekikan terhadap lingkungan, yang
selanjutnya tidak hanya berubah menjadi kehancuran ekonomi tetapi juga
7 Sayyed Hossein Nasr, “Islam and The Plight of Modern Man,” London & New York:
Longman Group Ltd, 1975, hal 4-5.
8 Komarudin Hidayat, “Agama dan Kegalauan Masyarakat Modern” dalam Nurcholish
Madjid (Ed), “Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern,” Jakarta, Mediacita, 2002, hal 100.
9 Mazheruddin Siddiqi, “Modern Reformist in The Muslim World,” Adam Publisher and
Distributor, India, 1993, hal.1.
10 Frans Magnis Suseno, “Pengembangan Sumber Daya Manusia Menjelang Abad 21,”
Jurnal Ilmu dan Budaya, No. 8, Hal 56-65.
87 | Tahdzib Al Akhlak | Vol 4 | No. 1 | 2021
menjadi perbuatan bunuh diri11.
Oleh sebab itu pula, manusia modern kata Nasr, mengidap penyakit
ketidakseimbangan psikologis akibat usahanya hidup hanya untuk sepotong
roti semata, membunuh semua Tuhan, dan membebaskan diri dari kekuatan
surgawi. Namun, akhirnya masyarakat modern dilanda kehampaan spiritual.
Ia menjadi lupa kepada dirinya sendiri, juga lupa kepada pusat lingkaran
eksistensi, yaitu Allah. Manusia modern menjadi sangat rentan terhadap
penyakit, karena sesungguhnya telah kehilangan salah satu aspek yang
paling fundamental, yaitu spiritualisme. Kemajuan lahiriah yang dicapai
manusia modern telah menjadi berhala yang menghambat komunikasi vertical
dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan, sehingga kehidupan yang
dibangunnya terasa sempit dan gelap, serta jauh dari bimbingan dan
petunjuk-Nya.
Sejalan dengan itu, Sayyed Hossein Nasr lebih jauh menyatakan
bahwa modernism membawa akibat lain, terutama bagi mereka yang kurang
siap, yaitu mengalami dislokasi, disorientasi dan disharmoni. Dislokasi adalah
perasaan tak punya tempat dalam tatanan sosial yang sedang berkembang.
Kenyataan demikian dapat dilihat pada kaum marginal di kota-kota besar.
Disorientasi adalah perasaan tidak punya pegangan hidup akibat yang ada
selama ini tidak lagi dapat dipertahankan karena dirasakan tidak cocok.
Sedangkan, disharmoni adalah perasaan tidak suka terhadap segala bentuk
kemapanan. Perasaan ini biasanya mewujud dalam bentuk radikalisme,
kekerasan, fanatisme dan fundamentalisme12.
Achmad Mubarok berpendapat bahwa timbulnya gangguan psikologis
yang diderita sebagian besar masyarakat modern, utamanya disebabkan
mereka hidup dalam lingkungan peradaban modern. Manusia modern
idealnya adalah manusia yang berpikir logis dan mampu menggunakan
berbagai teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya.
Seharusnya dengan bantuan teknologi tersebut, manusia modern lebih bijak
dan arif, dalam menyelesaikan problemnya. Namun pada kenyataannya
nurani kemanusiaan manusia modern lebih mundur ketimbang kemajuan pola
berpikir dan hasil teknologi yang dicapainya. Akibat dari ketidakseimbangan
ini, maka kemudian menimbulkan gangguan kejiwaan. Ditambah lagi dengan
menggunakan alat transportasi dan alat komunikasi yang canggih, akhirnya
manusia hidup dalam pengaruh global dan dikendalikan oleh terjangan arus
informasi global, padahal kesiapan mental manusia jauh belum siap13.
Meminjam istilah yang digunakan psikolog Humanis, Rollo May,
ketidakberdayaan manusia modern memainkan peranan di panggung global
disebut sebagai “Manusia dalam Kerangkeng”, karena ia telah terjebak dalam
situasi seperti telah disebutkan tadi. Inilah suatu ilustrasi penyakit yang
sesungguhnya telah diderita oleh manusia modern. Manusia seperti itu
11 Seyyed Hossein Nasr, loc.cit.
12 Ibid
13 Achmad Mubarok, “Konseling Agama Teori dan Kasus,” PT. Bina Pariwara, Jakarta 200,
hal 158-159.
Agama Dan Tantangan | 88
sebenarnya sudah kehilangan makna (meaningless-powerless)14. Setiap kali
ia harus mengambil keputusan, setiap saat itu pula ia tidak mampu memilih
keputusan apa yang harus diambil, sebab ia tidak tahu lagi apa yang
sesungguhnya ia inginkan. Para sosiolog menyebutnya sebagai gejala
keterasingan (alienasi), yang disebabkan oleh hal seperti berikut:
1. Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat
2. Hubungan yang damai antar manusia sudah berubah menjadi
hubungan gersang
3. Lembaga tradisional sudah berubah menjadi lembaga rasional
4. Masyarakat yang homogen sudah berubah menjadi heterogen
5. Stabilitas sosial pun berubah menjadi mobilitas sosial
Lebih lanjut Achamad Mubarok menjelaskan, bahwa manusia modern
mengidap gangguan kejiwaan, antara lain berupa:
a. Kecemasan: rasa cemas yang diderita manusia modern adalah
bersumber dari hilangnya makna hidup. Secara fitrah, manusia
memiliki kebutuhan akan makna hidup. Makna hidup dimiliki
oleh seseorang manakala ia memiliki kejujuran dan merasa
hidupnya dibutuhkan oleh orang lain, dan merasa mampu serta
telah mengerjakan sesuatu yang bermakna untuk orang lain.
b. Kesepian: rasa sepi yang diderita manusia modern adalah
bersumber dari pola hubungan antar manusia yang tidak lagi
tulus dan hangat. Kegersangan hubungan antar manusia,
disebabkan karena semua manusia modern menggunakan
topeng-topeng sosial untuk menutupi wajah kepribadian yang
sesungguhnya. Dalam komunikasi interpersonal, manusia
modern tidak memperkenalkan dirinya sendiri, tetapi selalu
menunjukannya sebagai seseorang yang sebenarnya bukan
dirinya.
c. Kebosanan: karena hidup tidak bermakna, dan hubungan
dengan manusia lain terasa hambar karena ketiadaan ketulusan
hati, kecemasan yang selalu mengganggu jiwanya dan kesepian
yang berkepanjangan, menyebabkan manusia modern
menderita gangguan kejiwaan berupa kebosanan.
d. Perilaku yang menyimpang: kecemasan, kesepian dan
kebosanan yang diderita berkepanjangan, menyebabkan
seseorang tidak tahu persis apa yang mesti dilakukan. Ia tidak
bisa memutuskan sesuatu, dan ia tidak tahu jalan mana yang
harus ditempuh. Dalam keadaan jiwa yang kosong dan rapuh
ini, maka seseorang tidak bisa berpikir jauh, kecenderungan
memuaskan motif kepada hal-hal yang rendah sangat kuat,
karena pemuasan atas motif ini sedikit agak terhibur. Dalam
keadaan tak mampu berpikir, apa saja ia mau melakukan asal
memperoleh minuman. Kekosongan jiwa itu bisa mengantar
14 Ibid.
89 | Tahdzib Al Akhlak | Vol 4 | No. 1 | 2021
seseorang kepada perbuatan merampok, meskipun mereka
tidak membutuhkan uang, memperkosa orang tanpa mengenal
siapa yang diperkosa, membunuh tanpa ada sebab-sebab yang
membuatnya harus membunuh. Pokoknya semua perilaku
menyimpang yang secara sepintas seakan-akan dapat
memberikan hiburan.
e. Psikosomatik: ialah gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor-
faktor kejiwaan dan sosial. Penderita psikosomatik, dapat
disebut sebagai penyakit gabungan fisik dan mental. Penderita
penyakit ini, biasanya selalu mengeluh, merasa tidak enak
badan, jantungnya berdebar-debar, merasa lemah dan tidak
konsentrasi. Wujud psikosomatik dapat berbentuk syndrome,
trauma, stress, ketergantungan kepada obat terlarang, atau
berperilaku menyimpang15.
Demikian juga apa yang disinyalir Peter Berger, dahulu agama
memberikan makna baku kepada manusia ketika memandang alam dan
kehidupan. Agama menjawab masalah kematian, penderitaan, dan bencana.
Dalam periode beberapa abad belakangan ini, posisi agama disisihkan oleh
sains. Apa yang dahulu dijawab agama sekarang dijawab sains. Agama
kehilangan otoritasnya, mula-mula dalam menjelaskan alam, dan akhirnya
juga dalam memberikan petunjuk kehidupan. Jelasnya Agama digantikan ilmu
pengetahuan alam untuk memahami dunia, dan digantikan psikologi untuk
menghayati pengalaman subjektif manusia16.
C. Respon Agama Menghadapi Tantangan Modernitas
Berbicara peran agama dalam menjawab tantangan modernitas,
merupakan suatu hal yang sangat penting, oleh karena persoalan hidup dan
kehidupan manusia semakin kompleks. Untuk persoalan tersebut, perlu
adanya usaha dari kelompok yang kompeten guna melahirkan konsep
dakwah yang dapat diterima oleh seluruh umat, sehingga pada gilirannya
mampu menghadirkan Islam sebagai manhaj atau metode, yang dapat
memecahkan problematika kehidupan modern.
Pada hakekatnya semua manusia dalam cita-cita dan realitas
kehidupannya memerlukan ide yang terus berkembang, keahlian tertentu,
kebiasaan yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak, yang disertai dasar-
dasar pergaulan dan tata tertib social, nilai-nilai kemanusiaan. Namun dalam
kenyataannya, kita mengaplikasikan ide-ide tersebut memiliki tata cara atau
sistem yang berbeda satu sama lain, lebih-lebih dalam konteks kehidupan
modern yang kadang-kadang tidak lagi mengindahkan rambu-rambu ajaran-
ajaran agama dalam merealisasikan idenya itu.
Singkatnya di era modern ini, manusia mengalami krisis nilai-nilai
kemanusiaan, disebabkan oleh ketidakmampuan dirinya dalam
mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berimplikasi
pada perubahan-perubahan sosial, politik, budaya dan terutama sosial
15 Ibid, hal 162-166.
16 Jalaluddin Rahmat, “Psikologi Agama Sebuah Pengantar,” Mizan, Bandung, 2005, Hal 153.
Agama Dan Tantangan | 90
keagamaan, termasuk gaya hidup tradisional kepada gaya hidup modern.
Sedangkan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan puncak
produk dari proses upaya perjalanan pemikiran manusia, di samping
kedudukan akal sebagai anugerah Allah yang paling berharga dan yang
menjadi pembeda dari manusia makhluk lainnya17.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak
perubahan yang sangat besar terhadap berbagai tatanan segi kehidupan
manusia, mulai dari cara berpikir, bersikap dan berperilaku. Meski ilmu
pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang besar dan luar
biasa, namun kemajuan itu belum mampu menjawab berbagai problematika
kehidupan manusia di era modern. Manusia di era modern ini dihadapkan
kepada era baru yang disebut globalisasi, yang cenderung menghilangkan
batas-batas negara (borderless) mencakup ideologi, politik, ekonomi dan
sosial budaya18.
Berdasarkan pada fenomena kehidupan masyarakat modern sekarang,
adalah menurunnya penghayatan atas ajaran dan seruan kebaikan
agamanya, melonggarnya ikatan kekeluargaan dan tata pergaulan
masyarakat. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup yang individualistik dan
tampak umumnya kehidupan masyarakat modern disibukkan oleh berbagai
hal yang sifatnya duniawi, sehingga perhatian terhadap agama sebatas tradisi
yang turun-temurun bersifat verbalistik dan ritualistic berkala.
Di samping itu, manusia sebagai makhluk yang sempurna telah
dilengkapi dengan akal dan nafsu. Kedua hal ini, apabila tidak diarahkan ke
jalan yang benar maka manusia akan terjerumus ke jalan yang menyesatkan.
Untuk mengarahkan manusia ke jalan yang lurus jalan yang diridhai Tuhan
diperlukan agama sebagai pedoman dan pegangan hidup. Fungsi dan
peranan agama dalam kehidupan manusia dapat memberikan makna dan
tujuan hidup.
Dengan memperhatikan kondisi seperti itu, kebutuhan manusia
modern terhadap agama menjadi mutlak. Dalam hal ini agar nilai-nilai dan
ajaran agama dapat diketahui, dihayati dan diamalkan, maka diperlukan
upaya untuk menumbuh-kembangkan agama pada jiwa manusia, yaitu
melalui aktivitas dakwah yang komprehensip dan berkesinambungan. Oleh
sebab itu, perlu me-revitalisasi (penguatan) peran agama dalam rangka
menjawab berbagai tantangan dan problematika manusia zaman modern.
Karena sesungguhnya ilmu pengetahuan tidak dapat menggantikan peran
agama dalam memenuhi kekosongan spiritual manusia modern.
Dalam melaksanakan kegiatan dakwah tidak bisa lepas dari dinamika
perubahan yang dialami dalam kehidupan manusia. Dalam arti aktivitas
dakwah tidak bisa tidak harus menyesuaikan diri dengan kemajuan yang
dicapai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena kemajuan tersebut,
telah mendorong manusia dalam menguasai, mengelola dan memanfaatkan
alam untuk kesejahteraan manusia, sehingga dakwah Islam dapat diterima
17 M.Jakfar Puteh, “Dakwah di Era Globalisasi (Strategi Menghadapi Perubahan Sosial),” AK
Group, Yogyakarta, Cetakan 3, 2006, hal 131-132.
18 Ibid.
91 | Tahdzib Al Akhlak | Vol 4 | No. 1 | 2021
oleh seluruh manusia. Dengan demikian, dakwah merupakan tugas suci umat
islam yang identik dengan tugas Rasul, bertujuan mewujudkan tatanan
masyarakat islami yang diridhai Allah SWT.
DAFTAR PUSTAKA
Achmad Mubarok, “Konseling Agama Teori dan Kasus,” PT. Bina Pariwara,
Jakarta 2000, hal 158-159.
A. Ahmed S. “Discovering Islam”, Routledge, London 198, hal 44-46.
Nurcholish Madjid, “Islam Kemodernan dan Keindonesiaan,” Bandung, Mizan,
1987, Cetakan 1, Hal 172.
Frans Magnis Suseno, “Pengembangan Sumber Daya Manusia Menjelang
Abad 21,” Jurnal Ilmu dan Budaya, No. 8, Hal 56-65.
Kazuo Shimoghaki, “Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left,
dialih bahasakan oleh M. Imam Azizi dkk, Kiri Islam, LKIS Yogyakarta,
1993, hal 25
Komarudin Hidayat, “Agama dan Kegalauan Masyarakat Modern” dalam
Nurcholish Madjid (Ed), “Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern,”
Jakarta, Mediacita, 2002, hal 100.
Sayyed Hossein Nasr, “Islam and The Plight of Modern Man,” London & New
York: Longman Group Ltd, 1975, hal 4-5.
Sayidiman Suryohaniprojo, “Makna Modernitas dan Tantangannya Terhadap
Iman”, dalam Nurcholish Madjid dkk, Kontekstualisasi Doktrin Islam
Dalam Sejarah, Paramadina, Jakarta, Cetakan I, 1994, hal 553-554.
Mazheruddin Siddiqi, “Modern Reformist in The Muslim World,” Adam
Publisher and Distributor, India, 1993, hal.1.
Jalaluddin Rahmat, “Psikologi Agama Sebuah Pengantar,” Mizan, Bandung,
2005, Hal 153.
M.Jakfar Puteh, “Dakwah di Era Globalisasi (Strategi Menghadapi Perubahan
Sosial),” AK Group, Yogyakarta, Cetakan 3, 2006, hal 131-132.
Agama Dan Tantangan | 92
You might also like
- Maize Business PlanDocument4 pagesMaize Business Planpreetjukeboxi76% (21)
- BS 8206-2 - Lighting For Buildings - Code of Practice For DaylightingDocument44 pagesBS 8206-2 - Lighting For Buildings - Code of Practice For DaylightingHong Wong100% (1)
- GMAT Quantitative Summary NotesDocument52 pagesGMAT Quantitative Summary Notes908yhjknNo ratings yet
- Troubleshooting LAVM10Document40 pagesTroubleshooting LAVM10Txus NietoNo ratings yet
- Peran Tasawuf Di Era Masyarakat Modern: Peluang Dan TantanganDocument16 pagesPeran Tasawuf Di Era Masyarakat Modern: Peluang Dan TantanganAnintiaNo ratings yet
- Universitas Dinamika Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Muvid@dinamika - Ac.idDocument18 pagesUniversitas Dinamika Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Muvid@dinamika - Ac.idRiza Mar'atus SholihahNo ratings yet
- Pemikiran Tasawuf Hamka Dan Relevansinya Bagi Kehidupan ModernDocument13 pagesPemikiran Tasawuf Hamka Dan Relevansinya Bagi Kehidupan ModernnadiafebiolaNo ratings yet
- Sekularisme Tantangan Pemikiran Islam Kontemporer: December 2016Document15 pagesSekularisme Tantangan Pemikiran Islam Kontemporer: December 2016budhidarmaNo ratings yet
- Urgensi Filsafat Dalam Kehidupan Masyarakat Kontemporer: Tinjauan Filsafat Islam Terhadap Fungsi Moral Dan AgamaDocument22 pagesUrgensi Filsafat Dalam Kehidupan Masyarakat Kontemporer: Tinjauan Filsafat Islam Terhadap Fungsi Moral Dan AgamaAnaLisaNo ratings yet
- ID Epistemologi Ilmu Dakwah KontemporerDocument26 pagesID Epistemologi Ilmu Dakwah KontemporerIrma Hernawati AhmadNo ratings yet
- 19 Modernity and IslamDocument4 pages19 Modernity and IslamSPAHIC OMERNo ratings yet
- 180 218 1 SM PDFDocument14 pages180 218 1 SM PDFRyuzhaNo ratings yet
- 7847 26427 1 PBDocument13 pages7847 26427 1 PBkurataxd50No ratings yet
- Worldview Islam (Sains Berbasis Iman)Document10 pagesWorldview Islam (Sains Berbasis Iman)Zainal IlmiNo ratings yet
- Philosophy HumanityDocument2 pagesPhilosophy HumanityFaiz NrdNo ratings yet
- Relevance of Mutazilah Thinking With The Ulama Intellectual MalayDocument10 pagesRelevance of Mutazilah Thinking With The Ulama Intellectual MalayPikas PikasNo ratings yet
- Peta Kemunculan Pemikiran Modern Dalam Islam Gunawan Institut Agama Islam Ma'Arif (Iaim) Nu MetroDocument11 pagesPeta Kemunculan Pemikiran Modern Dalam Islam Gunawan Institut Agama Islam Ma'Arif (Iaim) Nu MetroYayuh KhufibasyarisNo ratings yet
- 20-Article Text-169-1-10-20191018Document21 pages20-Article Text-169-1-10-20191018Milwan MiloNo ratings yet
- 72-Article Text-220-1-10-20210109Document15 pages72-Article Text-220-1-10-20210109Risky AuliaNo ratings yet
- Krisis Manusia Modern Dan Pendidikan IslamDocument17 pagesKrisis Manusia Modern Dan Pendidikan IslamSyifa Nuraini RhamadhaniNo ratings yet
- Agama Dan Tantangan Budaya Modern Perspektif IslamDocument20 pagesAgama Dan Tantangan Budaya Modern Perspektif IslamFebrians Pratama putraNo ratings yet
- Urgensi Tauhid Dalam Membangun Epistemologi Islam PDFDocument26 pagesUrgensi Tauhid Dalam Membangun Epistemologi Islam PDFmuchyiyuddin muchammadNo ratings yet
- Neo Modernisme Islam Indonesia: Wacana Keislaman Dan Kebangsaan Nurcholish Madjid SuryaniDocument12 pagesNeo Modernisme Islam Indonesia: Wacana Keislaman Dan Kebangsaan Nurcholish Madjid SuryaniYudi HasibuanNo ratings yet
- 3597 9237 1 PBDocument9 pages3597 9237 1 PBasepwrb02No ratings yet
- Filsafat Sains Dalam Al-Qur'An: Melacak Kerangka Dasar Integrasi Ilmu Dan AgamaDocument24 pagesFilsafat Sains Dalam Al-Qur'An: Melacak Kerangka Dasar Integrasi Ilmu Dan AgamaFebriana WidyaningsihNo ratings yet
- Filsafat Sains Dalam Al-qur'AnDocument24 pagesFilsafat Sains Dalam Al-qur'Annajmah namiaNo ratings yet
- Zakaria Fazri - 181370022 - Jurnal Hadis DakwahDocument14 pagesZakaria Fazri - 181370022 - Jurnal Hadis DakwahMuchamad Fajri IslamiNo ratings yet
- Islam and PostmodernityDocument30 pagesIslam and PostmodernityWajid AliNo ratings yet
- Kadivar - Reforming Islamic Thought Through Structural IjtihadDocument8 pagesKadivar - Reforming Islamic Thought Through Structural IjtihadSardor SalimNo ratings yet
- Pemikiran Isu-Isu Kontemporer Dalam Dunia Keislaman: Al-AfkarDocument13 pagesPemikiran Isu-Isu Kontemporer Dalam Dunia Keislaman: Al-AfkarVydNo ratings yet
- Agama Dan Tantangan Budaya Modern Perspektif Islam Arief Rifkiawan Hamzah Dan Heri CahyonoDocument28 pagesAgama Dan Tantangan Budaya Modern Perspektif Islam Arief Rifkiawan Hamzah Dan Heri CahyonoShalsabila MahfiraNo ratings yet
- Dampak Liberalisasi Pemikiran Islam Terhadap Kehidupan SosialDocument26 pagesDampak Liberalisasi Pemikiran Islam Terhadap Kehidupan SosialMujahid ImaduddinNo ratings yet
- (JURNAL) Tasawuf Substantif Santapan Rohani Masyarakat Modern - Muhammad Fauzhan AzimaDocument10 pages(JURNAL) Tasawuf Substantif Santapan Rohani Masyarakat Modern - Muhammad Fauzhan AzimaDanu Rio WaldiNo ratings yet
- Diskursus Islamisasi Ilmu Pengetahuan: AbstractDocument16 pagesDiskursus Islamisasi Ilmu Pengetahuan: AbstractAndi SetiawanNo ratings yet
- Cristian Response To GlobalizationDocument8 pagesCristian Response To GlobalizationSaba ZaidNo ratings yet
- Religious ModernismDocument16 pagesReligious ModernismsanaullahNo ratings yet
- SecularismDocument21 pagesSecularismAida Amira AzmanNo ratings yet
- Ethical Issues - PeaceDocument2 pagesEthical Issues - PeacekarunnalNo ratings yet
- Pemikiran Isu-Isu Kontemporer Dalam Dunia Keislaman: Al-AfkarDocument14 pagesPemikiran Isu-Isu Kontemporer Dalam Dunia Keislaman: Al-AfkarSYARIF HWAHABNo ratings yet
- Pokok-Pokok Ajaran Aswaja Menurut Kh. Ma'Ruf Irsyad Kudus: Email: Fathur - Rohman@unisnu - Ac.idDocument13 pagesPokok-Pokok Ajaran Aswaja Menurut Kh. Ma'Ruf Irsyad Kudus: Email: Fathur - Rohman@unisnu - Ac.idHarrySetyantoNo ratings yet
- Humanism and SecularismDocument6 pagesHumanism and SecularismVenlyn GassilNo ratings yet
- Philosophy: Assignment # 1 DATED:10/10/2010 Marks 20 Submitted by Fatima Zubair Butt BSC I.R, Semester 1Document4 pagesPhilosophy: Assignment # 1 DATED:10/10/2010 Marks 20 Submitted by Fatima Zubair Butt BSC I.R, Semester 1DAFFODILS91No ratings yet
- Karya Ilmiah No. 11Document20 pagesKarya Ilmiah No. 11Khoirunnisa AnnajahNo ratings yet
- M.M. Shah - Muslim Modernism, Iqbal, and Demythologization, A Perennialist Perspective (A)Document25 pagesM.M. Shah - Muslim Modernism, Iqbal, and Demythologization, A Perennialist Perspective (A)psamselNo ratings yet
- Islam and Social ChangeDocument37 pagesIslam and Social ChangeadansamanNo ratings yet
- Moderation - Islamic Socio-Economic StudiesDocument11 pagesModeration - Islamic Socio-Economic Studieswatson davidNo ratings yet
- Impact of Postmodernism On The Radicalisation of IslamDocument6 pagesImpact of Postmodernism On The Radicalisation of IslamJUNAID FAIZANNo ratings yet
- Macpaladmin,+2 +Sains+Modern+Dan+Nilai+TransendentalDocument21 pagesMacpaladmin,+2 +Sains+Modern+Dan+Nilai+TransendentalAzila MitasariNo ratings yet
- Hermeneia Agama ReformisDocument21 pagesHermeneia Agama ReformisIwel NaganNo ratings yet
- Knowledge and Religious ExperienceDocument24 pagesKnowledge and Religious Experienceumairu89No ratings yet
- 2091 7761 1 PBDocument17 pages2091 7761 1 PBIndah Syafiqah LubisNo ratings yet
- Revisionist Ideologies in Light of IslamDocument200 pagesRevisionist Ideologies in Light of IslamZulkifli IsmailNo ratings yet
- Syamsul HidayatDocument52 pagesSyamsul HidayatDandi RiyanNo ratings yet
- LiberalismeDocument13 pagesLiberalismeZarfan QomarulNo ratings yet
- Order 2747951Document4 pagesOrder 2747951Blasio guccuNo ratings yet
- Ahmad Suyuthi, Islam Progresif KontemporerDocument11 pagesAhmad Suyuthi, Islam Progresif KontemporerFathur RahmanNo ratings yet
- Topic 7-Idelogy and RelativismeDocument41 pagesTopic 7-Idelogy and RelativismeKhesoni NairNo ratings yet
- 3206-Article Text-8537-1-10-20181007Document18 pages3206-Article Text-8537-1-10-20181007Ewaldo Siallagan100% (1)
- ID Kritik Terhadap Sekularisme Pandangan Yusuf Qardhawi With Cover Page v2Document27 pagesID Kritik Terhadap Sekularisme Pandangan Yusuf Qardhawi With Cover Page v2AQNI AFAIFNo ratings yet
- Enlightenment and Its FeaturesDocument11 pagesEnlightenment and Its FeaturesAnkur ParasharNo ratings yet
- RUQYAH SEBAGAI METODE PENGOBATAN+BERBASIS+SPIRITUAL+ (Studi+Metode+Ruqyah+di+Jam'iyyah+Ruqyah+Aswaja+Tulungagung)Document27 pagesRUQYAH SEBAGAI METODE PENGOBATAN+BERBASIS+SPIRITUAL+ (Studi+Metode+Ruqyah+di+Jam'iyyah+Ruqyah+Aswaja+Tulungagung)Sitti AisyahNo ratings yet
- 1B 98engDocument58 pages1B 98engDavide AgnellaNo ratings yet
- Mathematics CSSA 1Document29 pagesMathematics CSSA 1ttongNo ratings yet
- Implementation of SCADA Systems For A Real Microgrid Lab TestbedDocument7 pagesImplementation of SCADA Systems For A Real Microgrid Lab TestbedJuan PavaNo ratings yet
- Oversized Primary Pulley Regulator Valve Kit: Jatco/Nissan JF015E (RE0F11A)Document2 pagesOversized Primary Pulley Regulator Valve Kit: Jatco/Nissan JF015E (RE0F11A)marranNo ratings yet
- Oil and Gas Iot Brief 2Document6 pagesOil and Gas Iot Brief 2Zahra GhNo ratings yet
- 1,000 Genre Fiction Writing Pro - Kate M. ColbyDocument279 pages1,000 Genre Fiction Writing Pro - Kate M. ColbyAna AlencarNo ratings yet
- USP Publishes Final Compounding ChaptersDocument3 pagesUSP Publishes Final Compounding Chaptersbarselona 46No ratings yet
- CC5291 Design For Manufacture Assembly and Environments MCQDocument8 pagesCC5291 Design For Manufacture Assembly and Environments MCQVasanth KumarNo ratings yet
- ANNEX VII ASEAN GL Claims and Claims Substantiation TMHS V14 13nov14 PDFDocument19 pagesANNEX VII ASEAN GL Claims and Claims Substantiation TMHS V14 13nov14 PDFaquarianchemNo ratings yet
- Group 3 - History of Science (Reflection)Document7 pagesGroup 3 - History of Science (Reflection)Jayson Berja de LeonNo ratings yet
- GR 4 Module 6 Application ProblemsDocument3 pagesGR 4 Module 6 Application ProblemsVanya NairNo ratings yet
- Lestari, I.P. Analisis Determinasi Fosil Pada Batuan SedimenDocument10 pagesLestari, I.P. Analisis Determinasi Fosil Pada Batuan SedimenIsnaini Permata100% (1)
- Very Low Input /very Low Dropout 2 Amp Regulator With EnableDocument11 pagesVery Low Input /very Low Dropout 2 Amp Regulator With EnableSergio Ricardo NobreNo ratings yet
- Kou2003 PDFDocument6 pagesKou2003 PDFGe EffgenNo ratings yet
- 2022 Mock JEE Main-5 - PaperDocument15 pages2022 Mock JEE Main-5 - PaperAshish GuleriaNo ratings yet
- Treating Spinal Cord Injuries With Zhu's Scalp Acupuncture: Moyee Siu, L.Ac., MTCMDocument8 pagesTreating Spinal Cord Injuries With Zhu's Scalp Acupuncture: Moyee Siu, L.Ac., MTCMCarleta StanNo ratings yet
- Distractor AoDocument15 pagesDistractor AoGenni Jose Leli HernandezNo ratings yet
- Naming Covalent CompoundsDocument2 pagesNaming Covalent CompoundsDVRao100% (1)
- SEGA Model 2 EmulatorDocument5 pagesSEGA Model 2 EmulatorMing EnNo ratings yet
- Air Circuit BreakerDocument18 pagesAir Circuit BreakerTalha SadiqNo ratings yet
- Laos and LaotiansDocument187 pagesLaos and LaotiansMeliodus 7 Deadly sinsNo ratings yet
- NamesDocument5 pagesNamesAMOL KARNKARNo ratings yet
- Conquistadors On The Beach SPANISH COMPANIESDocument6 pagesConquistadors On The Beach SPANISH COMPANIESMazana ÁngelNo ratings yet
- Basement ConstructionDocument25 pagesBasement ConstructionAayu ShNo ratings yet
- CarvaDocument2 pagesCarvaMohammad ImranNo ratings yet
- Lec 7Document29 pagesLec 7ARCHANANo ratings yet