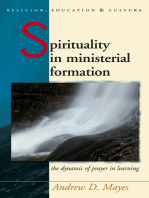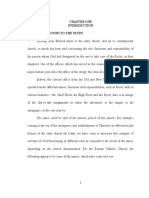Professional Documents
Culture Documents
297 1725 1 PB
297 1725 1 PB
Uploaded by
Cristin WilarOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
297 1725 1 PB
297 1725 1 PB
Uploaded by
Cristin WilarCopyright:
Available Formats
Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual
ISSN 2655-4666 (print), 2655-4682 (online)
Volume 5, No 1, Juni 2022; (135-154) Available at: http://www.jurnalbia.com/index.php/bia
Analisis Komparatif Eklesiologi Tata Gereja 2010 Dan 2021 Gereja
Kristen Pemancar Injil
Julianus Mojau
Fakultas Teologi, Universitas Halmahera
jmojau@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.34307/b.v5i1.297
Abstract: The aims of this research are to examine the ecclesiological reasons the GKPI
pioneers separated from KINGMI in 1959 and to conduct a comparative analysis of the
ecclesiology of the 2010 and 2021 GKPI church order. By using qualitative research methods
through library research, this , this study concluded that: (1) the ecclesiological reasons for
the GKPI pioneer to separate is to go beyond KINGMI’s docetic tendencies and develop a
holistic-empirical ecclesiology that answers the life challenges of congregation members and
the peoples of North and East Kalimantan; (2) the 2010 GKPI church order ecclesiology has
bureaucratic and feudal characteristics; (3) the 2021 Church Order ecclesiology develops
equal and democratic relations between congregations and between congregations and
synod; (4) the ecclesiology of the 2010 Church Order and the 2021 Church Order do not
consider the culture of the Dayak people; (5) both the 2010 and 2021 Church Order has paid
attention to the Church’s social work; but it still needs to integrate it with the liturgy and
understanding of the GKPI faith so that the presence of the GKPI can become the ritual body
of Christ as well as the social body of Christ.
Keywords: ecclesiology, Church Order, GKPI, contextual.
Abstrak: Tujuan penelitian ini ialah menelaah alasan eklesiologis perintis GKPI
memisahkan diri dari KINGMI tahun 1959 dan melakukan analisis perbandingan
eklesiologi Tata Gereja 2010 dan 2021 GKPI. Dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif melalui jenis penelitian kepustakaan penelitian menghasilkan: (1) bahwa alasan
eklesiologis perintis GKPI memsahkan diri adalah ingin melampaui kecenderungan
eklesiologi dokestis KINGMI dan mengembangkan suatu eklesiologi holistik-empirik yang
menjawab tantangan kehidupan sehari-hari warga jemaat dan masyarakat Kalimantan
Utara dan Timur pada saat itu: (2) eklesiologi Tata Gereja 2010 sangat birokratis dan
feudal sehingga melemahkan kemandirian jemaat-jemaat dalam Sinode GKPI; (3) ada
pembaruan eklesiologi Tata Gereja 2021 yang hendak menekankan pola presbyterial-
sinodal di mana ada hubungan setara dan demokratis antarjemaat dan antara jemaat-
sinode; (4) baik eklesiologi Tata Gereja 2010 dan Tata Gereja 2021 tidak
mempertimbangkan budaya orang Dayak; (5) baik Tata Gereja 2010 maupun 2021 cukup
memberi perhatian pada tugas sosial Gereja di tengah-tengah masyarakat; tetapi ttperlu
mengintegrasikan dengan liturgi, pemahaman iman dan pokok-pokok tugas sosial gereja
sehingga dapat menjadikan kehadiran GKPI menjadi Gereja publik yang meragakan tubuh
ritual Kristus sekaligus tubuh sosial Kristus.
Kata-kata Kunci: eklesiologi, Tata Gereja, GKPI, Kontekstual.
Article History : Received:26-07-2021 Revised: 14-03-2022 Accepted:04-04-2022
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 135
Julianus Mojau: Analisis Komparatif Eklesiologi Tata Gereja 2010 dan 2021 Gereja Kristen Pemancar Injil
1. Pendahuluan
Tata Gereja bukanlah sekadar sekumpulan pasal dan ayat peraturan
kelembagaan melainkan juga harus mencerminkan wawasan eklesiologi tertentu.
Melalui tata gereja tersebut dapat dicermati corak eklesiologi seperti apa yang sedang
dihidupi oleh kelembagaan suatu Gereja. Oleh karena itu, melalui Tata Gereja itu, dapat
dikatahui bagaimana suatu Gereja memahami diri dan identitasnya sebagai Gereja
misionar dalam melaksanakan pelayanananya di tengah-tengah masyarakat di mana
Gereja tersebut berada.1
Pada akhir tahun 1950-an perintis Gereja Kristen Pemancar Injil (GKPI)
memisahkan diri dari Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI). Salah satu alasan
eklesiologis perintis GKPI memisahkan diri dari KINGMI ialah ingin mengembangkan
suatu kesadaran eklesiologis dan praktik hidup menggereja yang terhubung dengan
tantangan kehidupan sehari-hari warga Jemaat dan warga masyarakat seperti
kemiskinan ekonomi dan keterbelakang pendidikan. Perintis GKPI (Pdt. Elisa Mou) ingin
melampaui kesadaran eklesiologis dan praktik hidup menggereja yang tidak hanya
memberi perhatian pada kehidupan rohani warga Jemaat dan warga masyarakat tetapi
juga pada kemajuan warga Jemaat dan warga masyarakat di bidang ekonomi dan
pendidikan.2
Sejak memisahkan diri GKPI telah memiliki dua Tata Gereja, yaitu Tata Gereja
2010 dan 2021. Dalam salah satu seminar Lazarus Purwanto pernah membedah Tata
Gereja 2010 GKPI. Lazarus Purwanto menyimpulkan bahwa struktur pelayanan GKPI
dalam bentuk Tata Gereja 2010 GKPI bertumpu pada: (a) kepemimpinan dan bukan
pada umat sebagai komunitas iman; (b) berpusat pada “komunitas” sinodal dan bukan
pada jemaat setempat (lokal) sebagai gereja konkret; (c) kepemimpinan kehilangan sifat
gerejawinya; dan (d) berstruktur hierarkis. Sebagai konsekuensi maka perumusan visi
dan misi serta penyusunan program pelayanan pun cenderung kurang berkaitan
langsung dengan kebutuhan konkret jemaat-jemaat dalam Sinode GKPI.3 Penulis sendiri
pernah melakukan telaah pada Tata Gereja 2010 GKPI.4
1 Lazarus H. Purwanto, “Church Order and Church Identity Challenges and Opportunities for
Churches in Indonesia to Express Their Identity Through Church Order”, dalam The Journal of the Society
for Protestant Church Polity, Volume 1, Number 1, Winter 2020, 20-21.
2 MS GKPI, “Sejarah Berdirinya GKPI Tarakan Kalimantan Timur”, dalam Tim Perumus, Pemancar
Injil: Pembaruan Eklesiologi GKPI (Prosiding Konsultasi Virtual Eklesiologi GKPI, 15-17 April 2021)
(Makassar: Oase Intim, 2021), 96.
3Lazarus Purwanto, “Restrukturisasi GKPI: Sebuah Masukan” (ceramah, GKPI, Malinau, 21
Februari 2020).
4 Julianus Mojau, “Eklesiologi Holistik-Empirik GKPI: Pembacaan Berdasarkan Dokumen-
dokumen GKPI”, dalam Tim Perumus, Pemancar Injil: Pembaruan Eklesiologi GKPI (Prosiding Konsultasi
Virtual Eklesiologi GKPI, 15-17 April 2021), Tarakan-Makassar: MP GKPI dan Oase Intim, 2021, 124-157.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 136
BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, Vol 3, No 2 (Desember 2020)
Menurut Leo J. Koffeman, eklesiologi suatu gereja tidak hanya dapat diamati
dari dokumen pemahaman iman dan/atau pengakuan iman dan Tata Gerejanya
melainkan juga dari liturginya. Leo J. Koffeman menulis: “The liturgy is the locus
ecclesiologicus par excellence”.5 Oleh karena itu, dalam mengkaji eklesiologi Tata Gereja
2010 dan 2021 GKPI, tidak cukup hanya dengan memperhatikan kedua Tata Gereja
tersebut. Dengan kesadaran seperti ini maka dalam kajian ini akan dianalisis juga Tata
Ibadah GKPI 2007 (yang berlaku sampai penelitian ini selesai dilakukan). Mengingat
Gereja sebagai persekutuan orang percaya tidak hidup untuk dirinya sendiri maka
kajian ini juga akan dianalisis Pemahaman Iman 2019 GKPI dan Garis-garis Besar
Pokok-Pokok Tugas GKPI. Maka kebaruan kajian ini dibandingkan dengan telaah
Lazarus Purwanto dan kajian penulis di atas ialah kajian menempatkan Tata Gereja
2010 dan 2021 GKPI dalam hubungan dengan liturgi GKPI, Pemahaman Iman GKPI dan
Pokok-Pokok Tugas GKPI. Selain itu, kajian ini juga memperhatikan alasan eklesiologis
perintis GKPI memisahkan diri dari KINGMI akhir tahun 1950-an.
Pertanyaan-pertanyaan yang digumuli dalam kajian ini ialah: (a) apa dan
bagaimana alasan eklesiologis perintis GKPI memisahkan diri dari KINGMI pada tahun
1959?; (b) apa dan bagaimana perbedaan antara Tata Gereja 2010 dan Tata Gereja 2021
GKPI?; (c) apakah kedua Tata Gereja GKPI tersebut telah memberi perhatian pada
budaya Dayak dan budaya digital mengingat GKPI melayani di tengah-tengah orang-
orang Dayak dan di tengah-tengah perubahan budaya di era digital ini?; (d) apakah
kedua Tata Gereja tersebut bagaimana hubungan kedua Tata Gereja GKPI tersebut
dengan tata ibadah GKPI, pemahaman iman GKPI dan Garis-garis Besar Pokok-pokok
Tugas GKPI? Dengan menggumuli pertanyaan-pertanyaan ini dalam kajian ini maka
diharapkan bahwa kajian ini dapat mengidentifikasi bagaimana GKPI memahami diri
dan memahami Jemaat-jemaat menjadi Gereja dan Jemaat-jemaat Publik dalam konteks
Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Ini penting karena secara teologis Gereja dan
Jemaat-jemaat dalam suatu Sinode Gereja tidak hidup untuk dirinya sendiri.6
2. Metode Penelitian
Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis
penelitian kepustakaan (library-research) tentang alasan eklesiologis perintis GKPI
memisahkan diri dari KINGMI tahun 1959, eklesiologi Tata Gereja 2010 dan 2021, Tata
Ibadah 2007 dan Pemahaman Iman GKPI 2019. Menurut Dèdè Oetomo, metode
penelitian kualitatif tipe ini dapat diterapkan pada analisis dokumen-dokumen tertulis
5LeoJ. Koffeman, “The Vulnerability of the Church—Ecclesiological Observations”, Scriptura 102
(2009), 412.
6Hariman A. Pattianakotta, “Menjadi Jemaat Publik: Menggereja secara Misional, Relasional dan
Inkarnasional di Ruang Publik”, dalam Jurnal Theologia In Loco, Vol.3, No.1, (April 2021): 1-18.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 137
Julianus Mojau: Analisis Komparatif Eklesiologi Tata Gereja 2010 dan 2021 Gereja Kristen Pemancar Injil
sebagai objek kajian.7 Maka data primer dalam kajian ini adalah sejarah GKPI, Tata
Gereja 2010 GKPI, Tata Gereja 2021 GKPI, Tata Ibadah GKPI 2007l dan Pemahaman
Iman GKPI 2019.
Sumber-sumber kajian tersebut akan dianalisis secara komparatif. Melalui
analisis komparatif kajian ini akan menelaah dan membandingkan perbedaan
eklesiologi Tata Gereja 2010 dan 2021. Oleh karena itu, pendekatan ini menggaribawahi
bahwa telaah terhadap eklesiologi dalam dokumen-dokumen gerejawi GKPI tersebut
tidak semata-mata dibaca secara idealis sebagai rumusan-rumusan normatif-dogmatis;
tetapi juga menelaah bagaimana GKPI mengembangkan diri sebagai gereja konkret
operatif dalam perspektif eklesiologi holistik-empirik.8
3. Hasil dan Pembahasan
Eklesiologi Holistik Empirik Elisa Mou
Sejarah GKPI mencatat alasan eklesiologis Pdt. Elisa Mou mengambil insiatif
untuk memisahkan diri dari KINGMI pada 30 Mei 1959 sebagai berikut:
“GKPI Tarakan berdiri pada tanggal 30 Mei 1959 di Desa Tanjung Lapang,
Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Pencetus
berdirinya GKPI adalah Pdt. Elisa Mou, seorang mantan pendeta (Gembala
Sidang) KINGMI di Long Bia. Ia memutuskan hubungan dengan KINGMI karena
kurang puas dengan pelayanan KINGMI yang hanya memperhatikan hal-hal
rohani saja, tanpa memikirkan kesejahteraan warga jemaat. Padahal kehidupan
warga jemaat di pedalaman Kalimantan Timur yang merupakan pelayanan
KINGMI sangat miskin. Dengan keadaan kehidupan jemaat yang demikian,
menurutnya, itu tidak dapat dijawab dengan pengembangan rohani saja, tetapi
juga terkait dengan segi-segi lainnya yang dianggap bersifat duniawi oleh CMA”9
Mencermati catatan sejarah tersebut di atas terlihat beberapa motif Pdt. Elisa Mou
memutuskan untuk memisahkan diri dari KINGMI. Pertama, tampaknya dia sangat
dipengaruhi oleh salah satu sifat kristologis dari visi penginjilan CMA-Pdt. A.B. Simpson,
yaitu: Yesus Kristus sebagai penyembuh (Yakobus 5:15).10 Kedua, Konteks pelayanan
Pdt. Elisa Mou (Kalimatan Utara dan Timur) diwarnai oleh kemiskinan dan
keterbelakangan pendidikan warga jemaat KINGMI dan masyarakat sekitarnya. Jika Pdt.
7Sebagaimana dikutip oleh Jeniffer Pelupessy Wowor, “Partisipasi Pendidikan Kristiani Di Ruang
Publik Dalam Menunjang Deradikalisasi,” Kurios 7, no. 1 (2021): 108
8Bdk. Johannes A. van der Ven, Ecclesiology in Context (Michigan: Eerdmans Publishing, 1996), ix-
xv dan Bintoro, Dhaniel Whisnu. “Metode Refleksi Eklesiologis bagi Warga Gereja Katolik Indonesia yang
Misioner”, dalam Eklesiologi: Langkah demi Langkah: Sudut-Sudut Ziarah Gereja, Peny. B.S, Mardiatmadja,
SJ (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 214-236
9 MS GKPI, “Sejarah Gereja Kristen Pemancara Injil Tarakan,” dalam Pemancar Injil: Pembaruan
Eklesiologi GKPI—Laporan Konsultasi Virtual GKPI, 15-17 April 2021, 96-97.
10Zakaria J. Ngelow, “Sejarah dan Ajaran Kemah Injil/CMA” , dalam Ibid., 76-77.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 138
BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, Vol 3, No 2 (Desember 2020)
A.B. Simpson digerakkan oleh Injil-Kristus yang menyembuhkan itu untuk melayani
mereka yang dikategorikan “sampah masyarakat” seperti pelacur, pekerja pelabuhan
dan tunawisma di New York maka Pdt. Elisa Mou digerakkan oleh Injil-Kristus yang
menyembuhkan itu untuk melayani mereka yang miskin dan tertinggal di daerah-
daerah terpencil di Kalimantan Utara dan Timur) Perbedaan konteks telah
memungkinkan kedua sahabat se-tradisi iman Kristen CMA ini memilih orientasi dan
strategi penerapan Injil-Kristus secara berbeda.
Dengan memaknai secara kontekstual karya Kristus Pdt. Elisa Mou sedang
membenihkan sautu “gereja-konkret-operatif” di tanah Kalimantan Utara dan Timur di
mana masyarakatnya yang sedang bergumul dan bergulat dengan kehidupan sehari-hari
secara ekonomi dan pendidikan. Karena, sejatinya, dalam sejarah KINGMI Injil Yesus
Kristus itu justru tumbuh dari kebutuhan akan pendidikan seperti nyata dari keputusan
penerima pertama Injil (seorang Dayak bernama Jalung Ipui) seperti dicatat dalam
sejarah penginjilan CMA.11 Yang harus perlu diingat bahwa Injil Yesus Kristus itu
mendapat bentuk “gereja-konkret operatif” melalui organisasi kekaryaan sosial yang
dirintis oleh Pdt. Elisa Mou, yaitu: AMTI (Angkatan Muda Tanah Tidung) dan koperasi.
Bahkan dalam bentuk lembaga pendidikan gerejawi dalam bentuk pendidikan teologi
dasar yang tidak saja belajar “hal-hal rohani” tetapi juga “hal-hal jasmaniah” seperti
pertanian.12
Jika dicermati, terdapat tiga hal penting sebagai pelajaran dari inisiatif
eklesiologis Pdt. Elisa Mou seperti telah diuraikan di atas. Pertama, kegelisahan-Injili
yang menawan Pdt. Elisa Mou sehingga membangkitkan kepekaan spiritual (spiritual-
discernment) beliau terhadap kondisi-kondisi de-human (kemiskinan, ketidakadilan dan
diskriminasi) di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kedua, kepekaan spiritual itu telah
memampukan beliau membaca tanda-tanda zaman dalam melakukan pelayanan
gerejawinya di tengah-tengah kehidupan sosial sehari-hari masyarakat Kalimantan
Utara dan Timur pada saat itu. Ketiga, kepekaan spiritual dan kecakapan membaca
tanda-tanda zaman itulah membuat Pdt. Elisa Mou mengambil-langkah kreatif dan
inovatif menghidupi tradisi iman kristologis CMA Pdt. A.B. Simpson untuk menginisiatif
gereja-konkret-operatif yang mengubah dan mentransformasi kehidupan sehari-hari
dalam konteks Kalimantan Utara dan Timur pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun
1960-an.13
Eklesiologi gereja-konkret operatif Pdt. Elisa Mou di atas memperlihatkan usaha
serius perintis GKPI membenihkan eklesiologi holistik empirik untuk menghindarkan
“docetism-ecclesiology” dalam tubuh CMA-KINGMI, terutama dalam sejarah GKPI
dikemudian hari. “Docetism-ecclesiology” adalah paham tentang gereja yang bertumpu
11 MS GKPI, “Sejarah Gereja Kristen Pemancara Injil Tarakan,”Ibid., 92-96.
12Ibid, 96-97.
13 Ibid.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 139
Julianus Mojau: Analisis Komparatif Eklesiologi Tata Gereja 2010 dan 2021 Gereja Kristen Pemancar Injil
pada sejumlah aktvitas ritual gerejawi dengan spiritualitas vertikalistik-dualistis-
platonisme, docetism-spirituality.14 Paham gereja doketis yang dikendalikan oleh
spiritualitas dosetis adalah paham gereja yang bertolak dari definisi hakekat gereja yang
abstrak dan idealistik. Paham gereja seperti ini tidak memiliki kepekaan moral yang
terluka di tengah-tengah tantangan-tantangan keterlukaan lingkungan sosial dan alam
sekitarnya. 15
Eklesiologi Tata Gereja 2010 GKPI
GKPI menyebut Tata Gerejanya dengan sebutan Peraturan Dasar (PD) dan
Peraturan Rumah Tangga (PRT). Dalam PD dan PRT 2010 idak ditemukan secara
eksplisit tentang pemahaman diri GKPI. Dalam Pembukaan PD 2010 yang hanya dapat
dibaca adalah pemahaman tentang Gereja yang bersifat umum dengan mengacu kepada
teks-teks Alkitab seperti Yohanes 17; Efesus 4:16; I Korintus 12:4-5 (Lihat Pembukaan
PD dan PRT 2010:1). Selanjutnya, dalam PD 2010 Bab II pasal 4, tujuan eklesiologis GKPI
adalah mewujudkan kasih Allah kepada dunia agar dunia mengenal dan merasakan
kasih-Nya. Tujuan eklesiologis ini bersendikan tiga panggilan GKPI: (1) memberitakan
Injil kepada semua makhluk dan menyaksikan kasih Allah melalui perkataan dan
perbuatan (Markus 16:15; Yakobus 2:17); (2) mewujudkan persekutuan iman yang
oikoumenis dengan memberitakan Firman Allah dan melaksanakan sakramen Baptisan
dan Perjamuan Kudus (1 Korintus 13:13); dan (3) melakukan perbuatan kasih dan
pelayanan bagi tegaknya keadilan, kebenaran dan perdamaian yang berpola pada karya
Kristus yang holistik.
Tujuan eklesiologis tersebut bermuara pada tri-panggilan GKPI untuk: (1)
meningkatkan kesadaran dan penghayatan warga jemaat untuk lebih menampakkan
persekutuan dalam kesatuan Roh (Efesus 4:3) dengan kebaktian-kebaktian, Baptisan
dan Perjamuan Kudus serta mendorong warga jemaat memberitakan perbuatan-
perbuatan besar dari Dia (Allah!) (1 Petrus 2:9); (2) meningkatkan kebersamaan dalam
pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara (Kisah Para
Rasul 2:42); (3) meningkatkan rasa persaudaraan dan sikap tolong menolong antar
jemaat dan warga jemaat (Galatia 6:2) (Bab V pasal 7 ayat 1). Selanjutnya disebutkan
panggilan misioner ini diatur dalam Garis-garis Besar Tugas panggilan GKPI (lihat Bab V,
pasal 7 ayat 2). Panggilan misioner ini pun menjadi panggilan misioner jemaat-jemaat
dalam Sinode GKPI (lihat PRT Bab XXV, pasal 74).
Cukup jelas di sini, dengan menempatkan pemahaman dirinya dalam kaitan
dengan tujuan dan panggilan misionernya, GKPI hendak memelihara semangat hidup
14Samuel Rayan, “The Search for an Asian Spirituality of Liberation,” dalam Asian Christian
Spirituality: Reclaiming Traditions, Eds. Virginia Fabela, Peter K.H. Lee, David Kwang-sun Suh (New York:
Orbis Books, 1992, 18-19.
15Bnd. Leo J. Koffeman, “The Vulnerability of the Church—Ecclesiological Observations”, Scriptura
102 (2009), 409.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 140
BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, Vol 3, No 2 (Desember 2020)
menggereja holistik empirik seperti dirintis oleh Pdt. Elisa Mou. Tetapi semangat hidup
menggereja ini tidak begitu operatif untuk memperkuat jemaat-jemaat dalam Sinode
GKPI. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kemandirian dan insiatif warga jemaat dan
jemaat-jemaat dalam Sinode GKPI. Hal ini dapat ditelusuri ke dalam tata kelembagaan
GKPI sebagaimana diatur dalam Tata Gereja 2010. Dalam satu percakapan dengan
pimpinan GKPI dan warga Jemaat pada saat berlangsung webinar eklesiologi GKPI, 19-
20 Mei 2021 menjadi nyata bahwa selama ini semua program jemaat-jemaat dalam
Sinode GKPI hanyalah penjabaran program sinodal saja. Tidak pernah ada kesempatan
bagi jemaat-jemaat menggumuli dan membuat program-program sendiri sesuai dengan
konteks dan tantangan pelayanan yang dihadapi setiap hari. Padahal ada keragaman
konteks dan tantangan pelayanan di jemaat-jemaat dalam Sinode GKPI.16 Pengakuan
dan tanggapan warga Jemaat ini dapat dipahami mengingat secara kelembagaan GKPI
mengorganisir diri seperti itu. Hal ini dapat dibaca dalam PD 2010-2015, Bab IV, pasal 6
ayat 1 dan 2. Lebih mengejutkan lagi pasal 6 ayat 1 pola pengorganisasian GKPI itu
mengambil berbentuk: Sinodal Presbiterial. Melalui pola pengorganisasian ini maka
hubungan jemaat-resort-sinode bersifat hirakhis sehingga semua program pelayanan
pun bersifat top-down seperti terlihat dari diagram sebagai berikut:
Gambar 1.
Menurut Rijnardus A. van Kooij, dll. sistem ini “lebih mementingkan keputusan-
keputusan sinodal dibanding keputusan Majelis Jemaat (keputusan Majelis Jemaat lebih
sering mengikut keputusan sinode)”.17 Sistem pengelolaan relasi jemaat-sinode secara
birokratis dan feodal ini merupakan sisa-sisa mentalitas kelembagaan De Nederlandse
Hervormde Kerk (NHK) sejak tahun 1816. Mentalitas kelembagaan ini masih sangat kuat
mempengaruhi sistem pemerintahan Gereja-gereja arus utama (mainstream-churches)
16Wawancara, 19-20 Mei 2021.
17Rijnardus A. van Kooij, Sri Agus Patnaningsih dan Yam’ah Tsalatsa, Menguak Fakta, Menata
Karya Nyata: Sumbangan Teologis Praktis dalam Pencarian Model Pembangunan Jemaat Kontekstual
(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 45.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 141
Julianus Mojau: Analisis Komparatif Eklesiologi Tata Gereja 2010 dan 2021 Gereja Kristen Pemancar Injil
di Indonesia. 18 Mentalitas GKPI berada dalam lingkaran mentalitas ini. Dapat diduga
GKPI, yang sejatinya memiliki semangat kongregasionalisme sebagaimana DNA
kelembagaan KINGMI, mengadopsi sistem ini dari Gereja Kalimantan Evanggelis (GKE).
Karena hanya GKE satu-satunya Gereja-gereja arus utama di Indonesia yang secara
jelas-jelas dalam Tata Gerejanya menyebutkan menganut sistem: Sinodal Presbiterial.19
Menariknya, dalam PRT 2010-2015, Bab XXV, pasal 23, tiba-tiba muncul DNA
kelembagaan KINGMI, seperti yang dapat dibaca sebagai berikut:
“Jemaat GKPI merupakan suatu perwujudan Tubuh Kristus yang didirikan atas
dasar Persekutuan dengan Allah, dibangun dan tumbuh serta berkembang oleh
Roh Kudus”.
Ada tiga hal yang ditekankan dalam rumusan wujud Jemaat-jemaat dalam Sinode GKPI.
Pertama, jemaat-jemaat dalam Sinode GKPI adalah perwujudan Tubuh Kristus. Kedua,
dasar persekutuan jemaat-jemaat adalah persekutuan dengan Allah. Ketiga,
pertumbuhan dan perkembangan jemaat-jemaat adalah karya Roh Kudus. Insentif
eklesiologis ini dapat mengimbangi kewenangan yang begitu kuat di Majelis Sinode dan
Majelis Resort. Tetapi insentif eklesiologis ini perlu dikelola dengan baik agar tidak
terjadi pemisahan jemaat-jemaat dari Sinode GKPI. Jika tidak dikelola dengan baik maka
jemaat-jemaat dalam Sinode GKPI dapat menjadi jemaat-jemaat yang berjalan sendiri-
sendiri. Dengan demikian GKPI lalu jatuh ke dalam tata pemerintahan gereja dengan
sistem kongregasionalisme.20 Dengan kata lain: jemaat-jemaat jatuh ke dalam ekstrim
hidup menggereja yang tidak peduli dengan persekutuan sinodal. Sebaliknya,
pengelolaan insentif eklesiologis dalam PRT akan memungkinkan GKPI dapat
memelihara “ketegangan kreatif” menghidupi “batas-batas kewenangan” antaramajelis
jemaat , antara majelis jemaat dan majelis resort, dan antara majelis-jemaat, majelis
resort dan majelis sinode dalam pengorganisasiannya.
Sejauh uraian di atas dapat dikatakan bahwa pasal dan ayat PD GKPI 2010 lebih
menempatkan pemahaman diri GKPI dalam wujud tujuan eklesiologinya. GKPI
memahami dirinya bentara Kristus di dalam dunia. Pendekatan fungsional PD ini
sebaiknya diletakan dalam bingkai bangunan eklesiologi tentang hakekat dan wujud
jemaat-jemaat dalam Sinode GKPI dan hakekat dan wujud Sinode GKPI. Perbedaan ini
memperlihatkan tidak sinkronnya PD dan PRT. Tentu saja visi eklesiologis PD dan basis
eklesiologis jemaat-jemaat GKPI PRT tidaklah bertentangan. Bisa saling melengkapi.
Tetapi perlu sinkronisasi sehingga PD dan PRT saling memperkuat. Bukan saling
meniadakan seperti nyata dari PD 2010 dan PRT 2010. Selain itu dibutuhkan
pemahaman diri GKPI yang lebih fungsional dan tata kelembagaannya yang lebih
mendukung fungsi pemberdayaan jemaat-jemaat dalam Sinode GKPI.
18 Ibid.
19Zakaria J. Ngelow, “Ringkasan Tata GKE” (Ceramah, Virtual Meeting Bersama GKPI, 15 April
2021).
20J.L.Ch. Abineno, Garis-garis Besar Hukum Gereja, 85-86.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 142
BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, Vol 3, No 2 (Desember 2020)
Eklesiologi Tata Gereja 2021 GKPI
Pada butir 1 Pemahaman Iman 2019 sessuai yang terbaca informasi tentang
definisi diri GKPI yang terintegrasi dengan tujuan kehadirannya di dalam dunia sebagai
berikut:
“GKPI adalah persekutuan orang-orang percaya yang hidup di dalam dunia, tetapi
bukan dari dunia (Yoh. 17:16); yang diutus ke dalam dunia (Yoh. 20:21) untuk
turut berpartisipasi dalam misi Kerajaan Allah di tengah dunia. Itu berarti GKPI
hadir di tengah masyarakat, bangsa dan dunia. GKPI menghadirkan dirinya
sebagai garam dan terang dunia (Mat. 5:14-16) ”.
Pada butir 4 dirumuskan pemahaman diri GKPI sebagai berikut:
“Pengakuan Yesus adalah Tuhan menegaskan bahwa Yesus adalah Kepala Gereja
(Efesus 1:23), yaitu Kepala GKPI, dan GKPI adalah tubuh Kristus (1Kor. 12: 27).
Sebagai tubuh Kristus GKPI tidak bisa dilepaskan dari Yesus Kristus. GKPI ada
karena Yesus Kristus dan untuk Yesus Kristus. Ketika GKPI terlepas atau
melepaskan diri dari Yesus Kristus, maka GKPI bukan lagi tubuh Kristus”.
Dalam visi GKPI dapat juga terbaca informasi tentang pemahaman diri GKPI adalah
umat Allah (1 Pet 2:9-10; 2 Kor 6 : 16-18 ) sekaligus Tubuh Kristus (Kristus (1 Kor 12:
27) dengan tugas menjadi garam dan terang dunia (Matius 5:13-16) dengan
membebaskan orang-orang tertindas (Luk 4 : 18-19). Hal ini diulang lagi dalam Garis-
garis Besar Tugas Panggilan GKPI 2021 (lihat GBTP—Pendahuluan—butir 1 dan 2) dan
dasar-dasar penyusunan GBTP GKI (butir 1—mandat iman dan butir 3—mandat
peraturan dasar GKPI). Dalam materi katekisasi butir 11 dapat juga diketahui
pemahaman diri GKPI yang dikaitkan dengan tugas memberitakan Injil kepada semua
makhluk (Markus 16:16) yang diikuti oleh panggilan Gereja (GKPI) untuk bersekutu
(koinonia-model trinitaris/tritunggal), melayani (diakonia) dan bersaksi (marturia)
serta penatalayanan (oikonomia).
Sejauh dokumen-dokumen di atas secara tipologis dapat dilihat adanya
kecenderungan-kecenderungan eklesiologi GKPI ke depan (setelah Sidang Sinode GKPI
2021) sebagai berikut. Pertama, GKPI hendak memahami diri adalah umat Allah
(eklesiologi 1 Petrus) sekaligus tubuh Kristus (eklesiologi Paulus). Kedua, kepimpinan
dalam GKPI adalah kepemimpinan Kristokrasi. Ketiga, menekankan hubungan personal
warga jemaat dengan Yesus Kristus, Sang Guru Kehidupan (eklesiologi Yohanes) dan Sang
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 143
Julianus Mojau: Analisis Komparatif Eklesiologi Tata Gereja 2010 dan 2021 Gereja Kristen Pemancar Injil
Kepala Gereja (Paulus dan Deutro-Paulin).21 Oleh karena itu, tim revisi tata kelembagaan
GKPI, menata kelembagaan GKPI yang diusulkan kepada Sidang Sinode GKPI 2021
perubahan pola pengorganisasian hubungan antarjemaat, antara jemaat dan
resort/wilayah, antara jemaat-resort/wilayah-sinode tidak lagi berpola struktural dan
hierarkis; tetapi berpola persekutuan jaring laba-laba sebagai berikut:
Gambar 2.
Sumber: Tim Revis Tata Gereja GKPI 2020.
Dalam Tata Gereja 2021 pasal 1 tentang hakekat dan wujud GKPI terbaca jelas
perubahan sistem kelembagaan dan pola pengorganisasian hubungan jaring-laba GKPI
di atas. Melalui perubahan ini GKPI ingin menegaskan identitas eklesial sebagai tubuh
Kristus yang konkret yang mewujud dalam bentuk Jemaat-Jemaat sebagai persekutuan
(koinonia) saling menopang dan saling menghidupkan antarjemaat dalam Sinode GKPI.
GKPI menyadari bahwa kekuatan GKPI itu tidak bertumpu pada Sinode sebagai
Lembaga tetapi bertumpu pada berjalan bersamanya jemaat-jemaat dalam sinode GKPI.
Di sini pada satu pihak terasa sari-sari DNA eklesiologi CMA-KINGMI dan di pihak lain
terasa sari-sari DNA berjalan bersama (bersinhodos) eklesiologi Gereja-gereja Calvinis.
Sari-sari tersebut tidak saling menegasi tetapi saling terikat. Melalui pola relasi setara
antarmajelis inilah, ke depan GKPI, baik secara sinodal maupun jemaat-jemaat setempat,
dapat memerankan diri sebagai gereja konkret operatif utuh dan lengkap yang diikat
oleh kehidupan bersama yang berjejaring untuk saling melengkapi dan saling
memberdayakan di tengah-tengah tantangan pelayanan di Kalimantan Utara dan Timur.
Pembaruan eklesiologi GKPI dalam Tata Gereja 2021 ini ini memperlihatkan
keberhasilan GKPI membentuk eklesiologinya yang bersesuain dengan prinsip dan DNA
kelembagaan eklesiologi Presbiterial-Sinodal. Karena, dalam eklesiologi kelembagaan
Presbiterial Sinodal, sangat ditekankan kewenangan saling berbagi sehingga
21Raymond E. Brown, Gereja yang Apostolis Terjemahan Indra Sanjaya, Sarijatmika, dan Budi
Purnama (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 32-137.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 144
BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, Vol 3, No 2 (Desember 2020)
kewenangan majelis jemaat setempat diberi peran sama dengan peran majelis sinode.22
Kesetaraan, demokratisasi dan kerjasama adalah DNA dan mentalitas eklesiologi
kelembagaan Presbiterial Sinodal.23
Eklesiologi GKPI ini perlu diperkaya oleh identitas budaya orang-orang Dayak. Hal ini
penting karena sebagian besar warga GKPI dan pusat pelayanan GKPI ada di tengah-
tengah orang-orang Dayak.24 Selain itu, GKPI juga tidak bisa menutup diri terhadap
perkembangan budaya digital yang ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Juga GKPI tidak mungkin tanpa Interaksi dengan “budaya hidup menggereja”
gerakan karismatik dan neo-karismatik. Dengan demikian eklesiologi holistik empirik
GKPI harus merupakan hasil dialog dan negosiasi kultural antara identitas kultural
Alkitabiah, identitas kultural ke-Dayak-kan, tradisi/budaya eklesiologi CMA,
tradisi/budaya eklesiologi operatif Gereja-gereja lain (Calvinis-Lutheran, Karismatik dan
Neo-Karismatik) dan budaya digital. Maka desain eklesiologi holistik empirik GKPI ke
depan adalah proses hermeneutik dialogis dan negosiatif antarbudaya dan antartradisi
yang menghasilkan budaya dan tradisi hidup menggereja operatif hybrid GKPI yang
dapat digambarkan proses tersebut sebagai berikut:
Gambar 3.
Eklesiologi GKPI Berbasis Misi Gereja
22Rijnardus A. van Kooij, Sri Agus Patnaningsih dan Yam’ah Tsalatsa, Menguak Fakta, Menata
Karya Nyata, 45; J.L.Ch. Abineno, Garis-garis Besar Hukum Gereja (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 83.
23Julianus Mojau, “Hidup Menggereja Asas Presbiterial Sinodal,” dalam Mata di Halmahera: Buku
Peringatan Hut V Universitas Halmahera (Fakultas Teologi), Editor Sefnat A. Hontong (Yogyakarta:
Kanisius, 2013), 68-74; Julianus Mojau, Menjadi Buah Bungaran Kebun Anggur Allah: Pergulatan
Eklesiologis GMIH Pasca Gereja-Zending (Tobelo: Yayasan Percis Halmahera dan Universitas Halmahera,
2010), 89-93.
24Saya mendapat informasi selain Dayak Lundayeh dan Agabag juga ada Dayak Punan, Berusu dan
Kenyak di Kalimantan Utara dan Timur (wilayah pelayanan GKPI)(Informasi dari Pak Ketum GKPI). Yulius
Daud (Ketua Umum Sinode GKPI), wawancara penulis, via telpon, Indonesia, 15 April 2021.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 145
Julianus Mojau: Analisis Komparatif Eklesiologi Tata Gereja 2010 dan 2021 Gereja Kristen Pemancar Injil
Di atas telah dikemukan bahwa kekuatan PD GKPI 2010 ialah meletakan
pemahaman diri GKPI dalam hubungan dengan tujuan eklesiologisnya. Dalam PD 2010,
Bab V, pasal 7, GKPI merumuskan empat tugas panggilannya, yaitu: (a) persekutuan
(koinonia); (b) kesaksian (marturia); (c) pelayanan kasih (diakonia) dan penatalayanan
(oikonomia). Menarik bahwa GKPI menambahkan satu tugas Gereja, yaitu:
penatalayanan (oikonomia). Penambahan ini mencerminkan masih hidup kesadaran
eklesiologis CMA-KINGMI. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu tradisi
iman CMA-KINGMI yang sangat penting dan berasa Calvinis itu ialah menekankan
terintegrasinya hubungan personal dengan Yesus Kristus, Sang Guru Kehidupan dengan
nilai penatalayanan kehidupan sehari-hari. Di sini dapat dipelajari dari GKPI yang telah
melampaui misi Gereja yang bertumpu pada tri-tugas Gereja klasikal (koinonia,
marturia, diakonia). Harus ada apresiasi atas pendekatan GKPI yang telah memahami
diri secara fungsional ini mengingat GKPI hadir dan melayani di tengah-tengah warga
Jemaat dan warga masyarakat yang masih tergolong tertinggal, baik ekonomi maupun
pendidikan.25 Melalui pembaharuan tugas Gereja ini GKPI ingin Menghayati kehadiran
misionalnya sebagai tubuh Kristus yang meragakan sekaligus tubuh ritual dan sosial
Kristus. Dapat digambarkan secara visual kesalingterhubungan dan keseimbangan
keempat tugas Gereja yang digaribawahi baik PD GKPI 2010 maupun PD 2021 (pasal
14) tersebut dalam bentuk lingkaran kesadaran hermeneutis sebagai berikut:
Gambar 4.
Melalui keseimbangan pelaksanaan keempat tugas Gereja itu diharapkan GKPI
mewujudkan identitas eklesialnya sebagai gereja konkret/empirik operatif dan efektif,
baik secara internal (penyegaran dan pemberdayaan warga jemaatnya) maupun secara
eksternal (penyegaran dan pemberdayaan warga masyarakat). GKPI dapat menjadi
gereja konkret operatif yang mandiri, misioner, terbuka dan dialogis, dan komunikatif di
tengah-tengah penderitaan dan kerlukaan dunia di sekitar GKPI.26 Keseimbangan
25Informasi tentang kebutuhan ini muncul dalam pleno lokakarya dan dalam penyampaian lisan
oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum GKPI, 17 April 2021,
26 Leo J. Koffeman, “The Vulnerability of the Church—Ecclesiological Observations”, Scriptura 102
(2009), 413-414.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 146
BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, Vol 3, No 2 (Desember 2020)
pelaksanaan keempat tugas Gereja di atas juga akan menghindarkan GKPI dari: (a)
menyempitkan makna pekabaran Injil hanya dalam kaitan dengan penyelematan jiwa-
jiwa untuk menambah jumlah anggota Gereja (proselitisme); (b) rutinitas pelaksanaan
kegiatan-kegiatan upacara dan pesta-pesta keagamaan Kristen (seperti ibadah minggu
dan perayaan-perayaan gerejawi) hanya sebagai kewajiban atau hanya sekadar suatu
tuntutan memenuhi tuntutan formal keagamaan Kristen yang melelahkan dan
mematikan inisiatif, kreativitas dan inovasi warga Jemaat dan terlepas dari praktik etis
dalam kehidupan sehari-hari(ritualisme); (c) memisahkan diri dan menjadi kelompok
tertutup dengan urusannya sendiri tanpa peduli dengan dunia sekitarnya (gethoisme);
(d) melakukan aktivitas-aktivitas sosial politik dan sosial-ekonomi terlepas dari
penghayatan spirituaitas Kristiani (aktivisme); dan (e) menyempitkan makna sifat-sifat
Gereja (kudus, esa, am, rasuli) hanya terkait kehidupan anggota Gereja saja.27
Eklesiologi dan Spiritualitas Liturgi GKPI
Jika secara lebih diteil dan diperiksa dengan cermat Tata Ibadah GKPI 2007 dan
pasal dan ayat PRT 2010 yang mengatur tentang ibadah GKPI, maka eklesiologi GKPI
lebih cenderung menekankan eklesiologi bait Allah 1 Petrus sehingga lebih dominan
meragakan liturgi hidup menggereja tubuh ritual Kristus di sekitar pemberitaan Firman
dan pelaksanaan Sakramen-Sakramen dengan sejumlah ritus dan serimoni di mana para
pemimpin ritual (pendeta = imam) memerankan peran sentral sebagai perantara antara
manusia dan Allah (bandingkan Tata Ibadah GKPI, 2007).
Keempat bentuk Tata Ibadah GKPI 2007 (I-IV) tidak mencerminkan keragaman tema
teologis yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan tantangan-tantangan pelayanan
konkret yang dihadapi oleh GKPI. Terksesan dipahami liturgi hanya sebagai urut-urutan
acara. Perhatikan, misalnya, perbedaan tata ibadah minggu III GKPI dan tata ibadah
minggu I, II, IV. Pada tata ibadah minggu III dapat dibaca urut-urutan: Hukum Allah,
Pengakuan Dosa, Berita Anugerah; sementara Liturgi Minggu I, II, IV: Pengakuan Dosa,
Berita Anugerah, Amanat Hidup Baru. Tentu saja ini tidak salah. Karena di sini juga dapat
dirasakan struktur kesadaran teologis berbeda. Tetapi struktur kesadaran teologis ini
sangat kuat hanya mencerminkan karakter eklesiologis bait Allah yang meragakan
tubuh ritual Kristus. Tidak mencerminkan perbedaan ritme dan variasi tantangan
teologis yang sedang digumuli sehingga perbedaan bentuk liturgi itu (I-IV)
mencerminkan perbedaan tantangan dan pergumulan teologisnya.
Sejatinya, liturgi adalah proses berteologi untuk menghayati identitas eklesial
dan panggilan misioner orang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh
Kudus. Maka bentuk-bentuk liturgi itu harus mencerminkan pergulatan teologis-
27Julianus Mojau, “Relevansi Pernyataan Iman bahwa Gereja itu Kudus dan Am”, dalam
Kontekstualisasi Pemikiran Dogmatika di Indonesia: Buku Penghormatan 70 Tahun Prof. DR. Sularso
Sopater. Peny. A.A. Yewangoe, dkk (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 321-329.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 147
Julianus Mojau: Analisis Komparatif Eklesiologi Tata Gereja 2010 dan 2021 Gereja Kristen Pemancar Injil
eklesiologis-misiologis orang beriman atau umat Allah di tengah-tengah pergumulan dan
pergulatan kehidupan sehari-hari dengan menarasikan dan mendasarkan isi iman
dalam bentuk satu tema teologis untuk satu bentuk liturgi pada momentum liturgis
tertentu selaras siklus kalender gerejawi dan tantangan konkret pelayanan. Lewat
bentuk liturgi tertentu untuk momentum liturgis tertentu itulah warga jemaat
berpartisipasi menarikan tarian Allah kehidupan dalam kehidupan sehari-hari dengan
jalan memulihkan dan memuliakan martabat manusia dan alam sekitar sebagai ciptaan
Allah. Maka bentuk-bentuk liturgi seharusnya merupakan bentuk-bentuk kesadaran
teologis-liturgis yang memungkinkan jemaat-jemaat dan warga jemaat dalam Sinode
GKPI menarikan mandat-mandat imannya sebagai tarian kehidupan yang memuliakan
Allah dan memulihkan martabat manusia dan alam sekitarnya.28
Dalam pemahaman iman GKPI 2020 didaftarkan 8 (depan) mandat-mandat
iman GKPI, yaitu: (a) mandat iman dalam bidang politik; (b), mandat iman dalam bidang
ekonomi; (c) mandat iman dalam bidang hukum dan keadilan; (d) mandat iman dalam
bidang kebudayaan; (e) mandat iman dalam bidang sosial; (f) mandat iman membangun
kehidupan bersama antaragama dan keyakinan; (g) mandat iman dalam bidang
lingkungan hidup; dan (h) mandat iman dalam bidang pendidikan dan kesehatan). Jika
mandat-mandat iman ini bergema dalam bentuk-bentuk liturgi GKPI sebagai bentuk-
bentuk kesadaran teologis-liturgis kontekstual yang senafas dengan siklus tahun
gerejawi, maka panggilan sosial-ekologis GKPI itu akan meraga dalam praxis liturgi
kehidupan sehari-hari. Di sini hubungan identitas eklesial GKPI secara ritual dan
pelaksanaan mandat-mandat iman atau panggilan misioner menjadi hubungan
korelasional yang saling menyuburkan dan meneguhkan sehingga membentuk keutuhan
gerakan identitas eklesial GKPI sebagai tubuh ritual Kristus sekaligus tubuh sosial
Kristus.29 Mengintegrasikan mandat-mandat iman dalam keseluruhan proses liturgi
gerejawi sebagai proses berteologi sosial sangatlah penting. Karena, liturgi gereja selalu
ditutup dengan berkat dan pengutusan. Berkat dan pengutusan hendak menegaskan
bahwa secara teologis liturgi gereja mengandung panggilan misioner sosial umat Allah
atau orang-orang percaya.
Mengembangkan eklesiologi dan spiritualitas liturgi GKPI sebagaimana
diuraiakan di atas akan memungkinkan terintegrasinya gairah hidup menggereja secara
ritual (meragakan tubuh ritual Kristus) dengan gairah hidup menggereja secara sosial
(meragakan tubuh sosial Kristus). Pengembangan seperti ini perlu memperhatikan
28Rasid Rahman, Merayakan Tuhan: Topik-Topik Sekitar Liturgi (Jakarta: Grafika Kreasindo,
2016), 61-68.
29 Julianus Mojau, “Gereja sebagai Tubuh Ritual dan Tubuh Sosial Kristus” (Bahan Kuliah, Fakultas
Teologi Universitas Halmahera, Semester Genap Januari-Juni 2021).
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 148
BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, Vol 3, No 2 (Desember 2020)
empat langkah lingkaran hermeneutik sebagai kerangka epistemologi desain
spiritualitas liturgi. Pertama, memastikan tersedianya data empirik tentang tantangan
hidup menggereja secara akurat dan menganalisisnya secara historis, sosiologis dan
antropologis. Kedua, mempertajam kepekaan etis dan pastoral terhadap tantangan
hidup menggereja tersebut. Ketiga, kepekaan etis dan pastoral tadi ditempatkan dalam
hubungan dengan iman yang menghasilkan pemahaman dan penghayatan teologis,
kristologis dan pneumatologis yang relevan dan operatif. Keempat, membangun narasi
liturgis yang relevan dan kontekstual di tengah-tengah hidup menggereja yang
konkret/empirik. Dapat digambarakan lingkaran hermeneutik hidup menggereja dan
menghidupi proses-proses liturgis yang transformasional ini sebagai berikut:
Gambar 5.
Meragakan serentak tubuh ritual Kristus dan tubuh sosial Kristus secara liturgis
adalah sejalan dengan ajaran CMA-KINGMI yang berasa Calvinis yang sangat
menekankan hubungan “keberadaan telah diselamatkan dengan perbuatan nyata”. Salah
satu ajaran penting dalam tradisi iman Calvinis tentang anugerah dan keselamatan
adalah “anugerah berdampak” (efficacious grace). Maka hubungan pribadi dengan Yesus
Kristus harus mengubah kehidupan sehari-hari dengan jalan berani bertindak atau
mengambil-langkah untuk berubah dan mentransformasi kehidupan sehari-hari agar
tidak lagi hidup dalam keadaan keberdosaan.30 Dapat dihargai tekanan ini. Tetapi
sebaiknya juga perlu tetap bersikap kritis terhadap “semangat Calvinis” ini agar tidak
terjebak ke dalam semangat kapitalisme “teologi sukses” yang memprivatisasi iman dan
“eklesiologi-sukses” yang mengukur keberhasilan gereja dengan saldo tunai di bank-
30Tony Lanne, Menjelaja Doktrin Kristen, Terjemahan Paul S. Hidayat (Jakarta: Waskita Publishing
dan STT Cipanas, tt), 246. Topik status keselamatan berdampak ini sangat terkait dengan ajaran Calvinis
kemudian yang dikenal dengan istilah ordo salutis. Lihat J.V. Fesko, Beyond Calvin: Union with Christ and
Justification in Early Modern Reformed Theology (1517-1700) (Göttingen/ Bristol: Vandenhoeck &
Ruprecht GmbH & Co. KG/andenhoeck & Ruprecht, 2012).
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 149
Julianus Mojau: Analisis Komparatif Eklesiologi Tata Gereja 2010 dan 2021 Gereja Kristen Pemancar Injil
bank tetapi tidak peka dan tidak peduli pada penderitaan sekitarnya atau memiliki
gedung-gedung gereja yang megah dan mahal tetapi tidak mengurus dengan baik rumah
sakit dan pendidikan.31
Perlu juga melakukan penghindaran untuk mengglorifikasi penderitaan
kehidupan sehari-hari sebagai bentuk dari memikul salib Kristus di dalam dunia tanpa
menganalisis sebab-sebab penderitaan itu. Baik secara ekonomi maupun politik. Dalam
konteks kemiskinan rakyat dan kerusakan lingkungan/alam sekitar di Kalimantan Utara
dan Timur di tengah-tengah kekayaan sumber daya alam, menghidupi spiritualitas yang
mengglorifikasi penderitaan kehidupan sehari-hari secara ekonomi dan politik tanpa
menganalisis sebab-sebabnya sejatinya sedang mengidap spiritualitas doketis
(docetism-spirituality). Tipe spiritualitas ini dapat mengalienasikan /mengasingkan
orang-orang Kristen atau orang-orang beriman dari kehidupan konkret sehari-hari.
Seolah-olah orang Kristen itu hidup hanya secara semu saja. Tipe spiritualitas ini lahir
dari pembacaan Alkitab yang terlepas dari konteksnya. Tipe spiritualitas ini hanya akan
memperkuat docetism-ecclesiology seperti telah disinggung sebelumnya. 32
Dalam hal pemahaman iman GKPI (Lihat butir 6 Pemahaman Iman GKPI) cukup
memberi perhatian pada makna salib Kristus. Perhatian ini dapat menjadi insentif
teologis dan eklesiologis untuk mengatasi docetism-ecclesiology dan docetism-spirituality
yang mengglorifikasi penderitaan secara ekonomi, politik, budaya dengan alasan
memanggul salib Kristus. Spiritualitas liturgi yang megintegrasikan ibadah kepada Allah
dengan pengabdian untuk penataan kehidupan sehari-hari akan memampukan GKPI
dan juga Gereja-gereja di Indonesia dapat menjadi gereja konkret operatif dan efektif di
tengah-tengah tantangan pelayanan seperti kemiskinan, ketidakadilan dan kerusakan
lingkungan. Dengan kata lain desain bentuk-bentuk liturgi yang mencerminkan
spritualitas liturgi holistik-empirik akan memungkinkan pemahaman dan penghayatan
diri Gereja sebagai Gereja yang meragakan tubuh ritual Kristus di sekitar pemberitaan
firman dan sakramen sekaligus menghidupi dan meragakan tubuh sosial Kristus dalam
kehidupan sehari-hari melalui karya-karya sosial-ekologis di tengah-tengah
ketidakadilan sosial ekonomi, sosial politik dan kerusakan lingkungan.33
4. Kesimpulan
Pertama, sebagaimana nyata dalam latar belakang pemisahan GKPI dari KINGMI
bahwa perintis GKPI (Pdt. Elisa Mou) telah mewariskan kepada GKPI suatu kesadaran
31Julianus Mojau, “Eklesiologi Holistik-Empirik GKPI: Pembacaan Berdasarkan Dokumen-
dokumen GKPI”, dalam Tim Perumus, Pemancar Injil: Pembaruan Eklesiologi GKPI (Prosiding Konsultasi
Virtual Eklesiologi GKPI, 15-17 April 2021), 130-131.
32Ibid.,
129.
33James L. Empereur, SJ dan Christopher G. Kiesling, P.P., Th Liturgy That Does Justice (Minnesota:
The Liturgical Press, 1990), 247-260; Julianus Mojau, Pedoman Liturgi Gereja Masehi Injili di Halmahera
(Tobelo: Yayasan Percis Halmahera dan Universitas Halmahera, 2010), 17.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 150
BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, Vol 3, No 2 (Desember 2020)
eklesiologis holistik-empirik. Pdt. Elisa Mou telah menerjemahkan secara kontekstual
penghayatan tentang karya Yesus Kristus sebagai penyembuh dalam konteks konkret
kehidupan warga jemaat GKPI dan warga masyarakat Kalimantan Utara dan Timur yang
masih dililit oleh kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan pada akhir tahun 1950-
an dan awal tahun 1960-an.
Kedua, ada perbedaan tata kelembagaan antara Tata Gereja 2010 dan 2021.
Dalam Tata Gereja 2010 tata kelembagaan GKPI bersifat struktural-hirarkis dan Majelis
Jemaat-Majelis Jemaat dalam Sinode GKPI tersubordinasi oleh kewenangan Majelis
Sinode. Sementara dalam Tata Gereja 2021 lebih mengedepankan relasi jaring laba-laba
sehingga Majelis Jemaat-Majelis Jemaat dalam Sinode GKPI setara dengan Majelis
Sinode. Dengan kata lain Tata Gereja 2010 GKPI dengan menyebutkan tata kelembagaan
GKPI berpola Sinodal-Presbiterial (yang merupakan pengambil-alian dari Tata Gereja
GKE) adalah tidak lazim dalam hukum gereja. Tata Gereja 2021 sangat menyadari hal
tersebut sehingga telah dilakukan perubahan dengan menekankan otonomi Jemaat-
Jemaat tanpa pemisahan dari Sinode. Tata Gereja 2010 GKPI memahami sinode sebagai
lembaga hirarki. Tata Gereja 2021 GKPI memahami sinode sebagai kesadaran berjalan
bersama (syn-hodos).
Ketiga, sekalipun GKPI hidup dan melayani di tengah-tengah orang-orang
Dayak, namun GKPI belum mengembangkan sensitivitas kultural dan karena itu tidak
terjadi pengembangan hidup menggerejanya secara dialogis dengan budaya Dayak.
Selain itu GKPI juga menghadapi tantangan budaya digital dan perkembangan budaya
hidup menggereja gerakan karismatik dan neo-karismatik. Ini perlu mendapat perhatian
GKPI ke depan agar GKPI dapat menjadi Gereja konkret dan kontekstual tanpa
mengabaikan budaya lokal dan tantangan budaya digital.
Keempat, baik Tata Gereja 2010 maupun Tata Gereja 2021, sama-sama
meletakan pemahaman diri GKPI (eklesiologi GKPI) secara misional. Pemahaman dan
identitas eklesial GKPI ditentukan oleh misinya. Itulah sebabnya, baik Tata Gereja 2010
maupun 2021, sangat menekankan pentingnya empat tugas pokok Gereja (koinonia,
marturia, diakonia dan oikonomia).
Kelima, terlihat ada usaha serius GKPI mengembangkan suatu eklesiologi
holistik-empirik yang operatif. Usaha serius ini membutuhkan spiritualitas liturgi yang
menyeimbangkan dan mengintegrasikan gairah (passion) hidup menggereja ritual
dengan gairah (passion) hidup menggereja sosial dalam praxis hidup menggerejanya.
Dalam hal ini GKPI perlu menata kembali dan memaknai secara teologis bentuk-bentuk
Tata Ibadahnya. Tata Ibadah bukan sekadar urut-urutan acara melainkan bangunan
kontekstual kesadaran teologis-liturgis. Penataan ini akan mengimbangi kecenderungan
eklesiologi bait Allah yang ritualistik dan spiritualitas dosetis sangat menonjol dalam
Tata Ibadah GKPI 2007 dan PRT GKPI 2010. Ini adalah tugas yang masih perlu
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 151
Julianus Mojau: Analisis Komparatif Eklesiologi Tata Gereja 2010 dan 2021 Gereja Kristen Pemancar Injil
dikerjakan oleh GKPI setelah Sidang Sinode 2021. Jika tugas ini dilaksanakan, maka GKPI
(sebagaimana arah pembaruan eklesiologi dalam Tata Gereja 2021) dapat menjadikan
Jemaat-jemaatnya menjadi tubuh ritual Kristus sekaligus menjadi tubuh sosial Kristus di
tengah-tengah masyarakat Kalimatan Utara dan Kalimantan Timur. Bahkan GKPI dapat
menjadi contoh Gereja Publik dalam konteks Indonesia yang masih dililit oleh
kemiskinanan dan ketidakadilan sosial serta kerusakan alam dengan segala sumber
daya yang dikandungnya.
Referensi:
Abineno, J.L.Ch. Garis-garis Besar Hukum Gereja. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
Bintoro, Dhaniel Whisnu. “Metode Refleksi Eklesiologis bagi Warga Gereja Katolik
Indonesia yang Misioner”, dalam Eklesiologi: Langkah demi Langkah: Sudut-Sudut
Ziarah Gereja, Peny. B.S, Mardiatmadja, SJ., 214-236. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
Brown, Gillian dan George Yule, George. Analisis Wacana. Terjemahan I Soetikno.
Jakarta: Gramedia, 1996.
Brown, Rayamond E. Gereja yang Apostolis .Terjemahan Indra Sanjaya, Sarijatmika, dan
Budi Purnama. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
Draft Restrukturisasi Organisasi GKPI
Empereur, SJ., James L dan Kiesling, PP., Christopher G. Th Liturgy That Does Justice.
Minnesota: The Liturgical Press, 1990.
Fesko, J.V. Beyond Calvin: Union with Christ and Justification in Early Modern Reformed
Theology (1517-1700). Göttingen/ Bristol: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
KG/andenhoeck & Ruprecht, 2012.
Haight, Roger. Christian Community in History: Historical Ecclesiology, Vol, 1. New York:
Continuum, 2004.
Hariman A. Pattianakotta, Hariman A. “Menjadi Jemaat Publik: Menggereja secara
Misional, Relasional dan Inkarnasional di Ruang Publik”, dalam Jurnal Theologia In Loco,
Vol.3, No.1, April 2021, 1-18.
Katekisasi Sidi GKPI 2021.
Koffeman, Leo J. “The Vulnerability of the Church—Ecclesiological Observations”,
Scriptura 102 (2009): 412, 409-414
Lanne, Tony. Menjelaja Doktrin Kristen, Terjemahan Paul S. Hidayat. Jakarta: Waskita
Publishing dan STT Cipanas, tt.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 152
BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, Vol 3, No 2 (Desember 2020)
Mojau, Julianus. “Hidup Menggereja Asas Presbiterial Sinodal,” dalam Mata di
Halmahera: Buku Peringatan Hut V Universitas Halmahera (Fakultas Teologi),
Editor Sefnat A. Hontong 68-74. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
Mojau, Julianus. “Relevansi Pernyataan Iman bahwa Gereja itu Kudus dan Am”, dalam
Kontekstualisasi Pemikiran Dogmatika di Indonesia: Buku Penghormatan 70 Tahun
Prof. DR. Sularso Sopater. Peny. A.A. Yewangoe, dkk: 321-329. Jakarta: BPK Gunung
Mulia, 2004.
Mojau, Julianus. Menjadi Buah Bungaran Kebun Anggur Allah: Pergulatan Eklesiologis
GMIH Pasca Gereja-Zending . Tobelo: Yayasan Percis Halmahera dan Universitas
Halmahera, 2010.
Mojau, Julianus. “ Gereja sebagai Tubuh Ritual dan Tubuh Sosial Kristus” bahan Kuliah,
Fakultas Teologi Universitas Halmahera, Semester Genap Januari-Juni 2021.
Mojau, Julianus. “Eklesiologi Holistik-Empirik GKPI: Pembacaan Berdasarkan Dokumen-
dokumen GKPI”, dalam Pemancar Injil: Pembaruan Eklesiologi GKPI (Prosiding
Konsultasi Virtual Eklesiologi GKPI, 15-17 April 2021). Peny. Tim Perumus, 124-157
(Makassar: Oase Intim, 2021).
Mojau, Julianus. Pedoman Liturgi Gereja Masehi Injili di Halmahera. Tobelo: Yayasan
Percis Halmahera dan Universitas Halmahera, 2010.
MS GKPI, “Sejarah Gereja Kristen Pemancara Injil Tarakan,” dalam Pemancar Injil:
Pembaruan Eklesiologi GKPI—Laporan Konsultasi Virtual GKPI, 15-17 April 2021, Peny.
Christin Hutubessy, dkk, 96-97 (Makassar: Oase Intim, 2021.
nes A. Ecclesiology in Context. Michigan: Eerdmans Publishing, 1996.
Ngelow, Zakaria J. “Sejarah dan Ajaran Kemah Injil/CMA”, dalam Pemancar Injil:
Pembaruan Eklesiologi GKPI—Laporan Konsultasi Virtual GKPI, 15-17 April 2021,
Peny. Tim Perumus, 76-77 Maka Ngelow, Zakaria J. “Ringkasan Tata GKE” ceramah,
Lokakarya Virtual Eklesiologi GKPI, 15 April 2021.
Pemahaman Iman GKPI 2019.
Purwanto, Lazarus H. “Church Order and Church Identity Challenges and Opportunities
for Churches in Indonesia to Express Their Identity Through Church Order”, dalam The
Journal of the Society for Protestant Church Polity, Volume 1, Number 1, Winter 2020, 20-
21.
Purwanto, Lazarus. “Restrukturisasi GKPI: Sebuah Masukan” ceramah, GKPI, Malinau, 21
Februari 2020.
Rahman, Rasid. Merayakan Tuhan: Topik-Topik Sekitar Liturgi. Jakarta: Grafika
Kreasindo, 2016.
Rayan, Samuel., “The Search for an Asian Spirituality of Liberation,” dalam Asian
Christian Spirituality: Reclaiming Traditions, Eds. Virginia Fabela, Peter K.H. Lee,
David Kwang-sun Suh, 8-19 New York: Orbis Books, 1992.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 153
Julianus Mojau: Analisis Komparatif Eklesiologi Tata Gereja 2010 dan 2021 Gereja Kristen Pemancar Injil
ssar: Oase Intim, 2021.
Tata Gereja (Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga) GKPI 2021.
Tata Ibadah GKPI 2007.
van der Ven, Joha Tata Gereja (Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga) GKPI
2010
van Kooij, Rijnardus A, Patnaningsih, Sri Agus dan salatsa, Yama’ah. Menguak Fakta,
Menata Karya Nyata: Sumbangan Teologis Praktis dalam Pencarian Model
Pembangunan Jemaat Kontekstual. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
Visi dan Misi GKPI, GBTP GKPI dan Struktur Organisasi Pelayanan GKPI (2021).
Wowor Pelupessy, Jeniffer. “Partisipasi Pendidikan Kristiani Di Ruang Publik Dalam
Menunjang Deradikalisasi,” Kurios 7, no. 1 (2021): 108
Yulius Daud (Ketua Umum Sinode GKPI), wawancara penulis, via telpon, Indonesia, 15
April 2021.
Copyright© 2020; BIA’, ISSN: 2655-4666 (print), 2655-4682 (online) | 154
You might also like
- The Easter Tree VERY SIMPLE Skit For KidsDocument6 pagesThe Easter Tree VERY SIMPLE Skit For KidsPastor Jeanne0% (1)
- Mary Immaculate Star of The MorningDocument1 pageMary Immaculate Star of The Morningjhasonify100% (2)
- Working With Angels - Flowing Wi - Steven BrooksDocument234 pagesWorking With Angels - Flowing Wi - Steven BrooksKoumetio Bryan100% (4)
- Fresh Expressions in the Mission of the Church: Report of an Anglican-Methodist working partyFrom EverandFresh Expressions in the Mission of the Church: Report of an Anglican-Methodist working partyNo ratings yet
- Sword of Light v3Document51 pagesSword of Light v3Shi-hua BaoNo ratings yet
- Judith Butler-Who Owns KafkaDocument21 pagesJudith Butler-Who Owns KafkaStrange ErenNo ratings yet
- Jurnal Trifungsi GerejaDocument11 pagesJurnal Trifungsi GerejaSaiful KuokNo ratings yet
- 4 Transformasi Iman Dalam Kehidupan Gereja Perdana Menuju Gereja SinodalDocument11 pages4 Transformasi Iman Dalam Kehidupan Gereja Perdana Menuju Gereja SinodalnathanioNo ratings yet
- Inkulturasi Dan Tata Perayaan Ekaristi 2020 Gambaran Berinkulturasi Dalam Konteks IndonesiaDocument22 pagesInkulturasi Dan Tata Perayaan Ekaristi 2020 Gambaran Berinkulturasi Dalam Konteks IndonesiaJefrianus Hali YabokiNo ratings yet
- Sorka Abanu ReviewDocument6 pagesSorka Abanu ReviewSorka Jo AbanuNo ratings yet
- Chapter 8 Celibacy Priest Shortageand Married PriesthoodDocument13 pagesChapter 8 Celibacy Priest Shortageand Married Priesthoodcarl4699xanderNo ratings yet
- Komunikasi Iman Umat Katolik Mewujudkan Persekutuan Yang Kokoh Di Stasi Santo Petrus Runggu RayaDocument14 pagesKomunikasi Iman Umat Katolik Mewujudkan Persekutuan Yang Kokoh Di Stasi Santo Petrus Runggu Rayaking hirumaNo ratings yet
- 570 2249 1 PBDocument24 pages570 2249 1 PBr1anamarthaNo ratings yet
- Novel ModelDocument11 pagesNovel Modelshek sonsonNo ratings yet
- Theological Institutional Movement: United Theological College (UTC) Historical BackgroundDocument4 pagesTheological Institutional Movement: United Theological College (UTC) Historical BackgroundAlan100% (2)
- Enduring Legacy: A Trail of Doctrinal Uniqueness and Unity of The Evangelical Church Winning ALL (ECWA)Document12 pagesEnduring Legacy: A Trail of Doctrinal Uniqueness and Unity of The Evangelical Church Winning ALL (ECWA)Titus TankoNo ratings yet
- Ecclesiology - Quilaton Term PaperDocument6 pagesEcclesiology - Quilaton Term PaperWinston QuilatonNo ratings yet
- Gereja Dalam Realitas Sosial Indonesia Masa Kini: JURNAL TERUNA BHAKTI September 2020Document12 pagesGereja Dalam Realitas Sosial Indonesia Masa Kini: JURNAL TERUNA BHAKTI September 2020Ayub BoanaNo ratings yet
- Misi Gereja Dalam Realitas Sosial Indonesia Masa KDocument13 pagesMisi Gereja Dalam Realitas Sosial Indonesia Masa KDendhy KapuguNo ratings yet
- Peran Gerejadalam Transformasi Pelayanan DiakoniaDocument14 pagesPeran Gerejadalam Transformasi Pelayanan DiakoniaJemmz ajNo ratings yet
- 364 1445 2 PBDocument14 pages364 1445 2 PBKeren TndNo ratings yet
- Draft Revised CEAP Christian Formatlon ManualDocument87 pagesDraft Revised CEAP Christian Formatlon ManualPidyey CumpasNo ratings yet
- Principles and Norms On EcumenismDocument217 pagesPrinciples and Norms On EcumenismDarko MajdićNo ratings yet
- Peran PAK Dalam Meningkatkan Keaktifan Pemuda GerejaDocument8 pagesPeran PAK Dalam Meningkatkan Keaktifan Pemuda GerejaMass JejeNo ratings yet
- 2596-Article Text-7942-1-10-20221126Document7 pages2596-Article Text-7942-1-10-20221126kevin.wiliam129No ratings yet
- Impact of Theological Training On Pentecostal Ministries in Uganda: A Case of Churches in Katikamu Sub-County, Luwero DistrictDocument9 pagesImpact of Theological Training On Pentecostal Ministries in Uganda: A Case of Churches in Katikamu Sub-County, Luwero DistrictInternational Journal of Innovative Science and Research TechnologyNo ratings yet
- Pengaruh Sejarah Gereja Dalam Perjalanan Sejarah KDocument24 pagesPengaruh Sejarah Gereja Dalam Perjalanan Sejarah Kbivoso8926No ratings yet
- Italian Catechists Identity and Self-PerceptionDocument5 pagesItalian Catechists Identity and Self-PerceptionmeandmymariaNo ratings yet
- Inkulturasi ArsitekturDocument2 pagesInkulturasi ArsitekturYessi AmandaNo ratings yet
- Strategidan MOdel Pembinaan Rohani Untuk Pendewasaaniman JemaatDocument20 pagesStrategidan MOdel Pembinaan Rohani Untuk Pendewasaaniman JemaatHans SiagianNo ratings yet
- Theological Institutional MovementDocument5 pagesTheological Institutional MovementAlan100% (1)
- Perspective On Contemporary Spirituality Implications For Religious Education in Catholic SchoolsDocument20 pagesPerspective On Contemporary Spirituality Implications For Religious Education in Catholic SchoolsBolethoNo ratings yet
- 106-Article Text-807-3-10-20220822Document20 pages106-Article Text-807-3-10-20220822Patricia LumempouwNo ratings yet
- VirtualRealityChurch TransformationDocument10 pagesVirtualRealityChurch Transformationglenpaais2005No ratings yet
- An Interweaving Ecclesiology: The Church, Mission and Young PeopleFrom EverandAn Interweaving Ecclesiology: The Church, Mission and Young PeopleNo ratings yet
- ReligionDocument69 pagesReligionIvy Myrel OliveraNo ratings yet
- Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama Di Kota BengkuluDocument17 pagesPeranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama Di Kota BengkuluNurzihan AdamNo ratings yet
- Church and SeminaryDocument3 pagesChurch and SeminaryJohn Varghese MathewNo ratings yet
- 32-Article Text-220-1-10-20211005Document18 pages32-Article Text-220-1-10-20211005Kristina SinagaNo ratings yet
- RATIONALE CEAP Capus Ministers ConferenceDocument13 pagesRATIONALE CEAP Capus Ministers ConferenceCher DNo ratings yet
- Efektivitas Ibadah Online Bagi Pertumbuh b44c9b0bDocument10 pagesEfektivitas Ibadah Online Bagi Pertumbuh b44c9b0bRr. Dinar SoelistyowatiNo ratings yet
- Renovasi Dan Pengembangan Gereja Kristen Indonesia Mojosari: (Penekanan Pada Interior Ruang Kebaktian)Document13 pagesRenovasi Dan Pengembangan Gereja Kristen Indonesia Mojosari: (Penekanan Pada Interior Ruang Kebaktian)Farid Jati AnggoroNo ratings yet
- 3 - HumanioraV15 No2Des2018Document53 pages3 - HumanioraV15 No2Des2018julhedioNo ratings yet
- Bible Study 2023Document55 pagesBible Study 2023aboagyewaahoNo ratings yet
- Instruction For The Study of The Church FathersDocument16 pagesInstruction For The Study of The Church FathersKimrey Pintor0% (1)
- 95-Article Text-738-1-10-20220430Document14 pages95-Article Text-738-1-10-20220430liangain2002No ratings yet
- 77 336 1 PBDocument14 pages77 336 1 PBAmran Efraim JoelNo ratings yet
- Spirituality in Ministerial Formation: The Dynamic of Prayer in LearningFrom EverandSpirituality in Ministerial Formation: The Dynamic of Prayer in LearningNo ratings yet
- 10 60 1 PBDocument15 pages10 60 1 PBalat medis apdNo ratings yet
- Jurnal InternasionalDocument9 pagesJurnal InternasionalXander MantalabaNo ratings yet
- The Formation of Late Joseon BuddhismDocument26 pagesThe Formation of Late Joseon BuddhismSung-EunNo ratings yet
- Pastoral Theology FinalDocument15 pagesPastoral Theology Finalsimiyubrian777No ratings yet
- Sabrina Muller - Fresh Expressions of Church and The Mixed EcoonomyDocument16 pagesSabrina Muller - Fresh Expressions of Church and The Mixed EcoonomyDan YarnellNo ratings yet
- Apuron - 2010 CARA Report - Cultivating UnityDocument69 pagesApuron - 2010 CARA Report - Cultivating UnityTimRohrNo ratings yet
- Different Kinds of PastorsDocument9 pagesDifferent Kinds of PastorsZau lum LahpaiNo ratings yet
- Chapter One SommidahDocument12 pagesChapter One Sommidahdogara yusufNo ratings yet
- 2066-Article Text-6714-1-10-20220905Document6 pages2066-Article Text-6714-1-10-20220905CIALING DOMINGGUSNo ratings yet
- Angelito SDocument7 pagesAngelito SJhun DichosaNo ratings yet
- Latest Complete Project Corrected - 8-06-2022Document67 pagesLatest Complete Project Corrected - 8-06-2022dogara yusufNo ratings yet
- Synod On Synodality - National Synthesis of Czech RepublicDocument15 pagesSynod On Synodality - National Synthesis of Czech RepublicREMBERT VINCENT FERNANDEZNo ratings yet
- Ijbmsr 2Document16 pagesIjbmsr 2Damianus AbunNo ratings yet
- 115 ISU FullDocument32 pages115 ISU FullSethNo ratings yet
- IJBMSR-22 Catholic Youth Attitude Toward The Catholic Church and Their Behavioral Intention To Help The Social Action of The Catholic Church in The FutureDocument16 pagesIJBMSR-22 Catholic Youth Attitude Toward The Catholic Church and Their Behavioral Intention To Help The Social Action of The Catholic Church in The FutureDamianus AbunNo ratings yet
- The Vault: Pcs Choose A QuestDocument8 pagesThe Vault: Pcs Choose A Questsally bensNo ratings yet
- K. Psalm 119.81-88 PDFDocument5 pagesK. Psalm 119.81-88 PDFpacurarNo ratings yet
- Jung, Alchemy and Active Imagination - Part 3 of 'Alchemy and The Imagination'Document11 pagesJung, Alchemy and Active Imagination - Part 3 of 'Alchemy and The Imagination'Ian Irvine (Hobson)97% (36)
- LP Sa Music 7Document17 pagesLP Sa Music 7Dyanne de JesusNo ratings yet
- The Character of God in You by Gary SiglerDocument45 pagesThe Character of God in You by Gary Siglerhanako1192No ratings yet
- Shakta 74Document10 pagesShakta 74spirit571No ratings yet
- Atithi Devo Bhava - An Indian TraditionDocument2 pagesAtithi Devo Bhava - An Indian TraditionsaurinjhaveriNo ratings yet
- Salvation HistoryDocument2 pagesSalvation HistoryErica TañoNo ratings yet
- Firaq SectsDocument6 pagesFiraq SectsmubarakSAIFNo ratings yet
- Smith Wigglesworth On The Holy - Smith WigglesworthDocument244 pagesSmith Wigglesworth On The Holy - Smith Wigglesworthsergesch95% (21)
- Young Mister Newman - M. WardDocument507 pagesYoung Mister Newman - M. WardLucianaNo ratings yet
- Structure of The Liturgical Bible Study PDFDocument2 pagesStructure of The Liturgical Bible Study PDFGianfranco Echano HicapNo ratings yet
- Bible College ThesisDocument8 pagesBible College ThesisCarrie Cox100% (2)
- Introduction To The Book of EphesiansDocument12 pagesIntroduction To The Book of EphesiansLanny CarpenterNo ratings yet
- Saint Anthony Mary Claret: Bishop and Founder of The CongregationDocument5 pagesSaint Anthony Mary Claret: Bishop and Founder of The Congregation蔡松柏No ratings yet
- Mass of The Patriarchs FULL SCOREDocument9 pagesMass of The Patriarchs FULL SCORELeo Rander, nSJNo ratings yet
- Kin 4516 ResumeDocument2 pagesKin 4516 Resumeapi-436060342No ratings yet
- The Women of Christmas - Part 3 - 2013-12-15Document4 pagesThe Women of Christmas - Part 3 - 2013-12-15John PartridgeNo ratings yet
- Unit-7 People Who Stand Out: SSC ProgrammeDocument7 pagesUnit-7 People Who Stand Out: SSC ProgrammeTuhidull EamamNo ratings yet
- April 2013 Teaching Outline For Midweek Services - FinalDocument3 pagesApril 2013 Teaching Outline For Midweek Services - Finale_warindaNo ratings yet
- CC Cycle 1 Activity Guide - Sheet1 - 0 PDFDocument2 pagesCC Cycle 1 Activity Guide - Sheet1 - 0 PDFAnonymous OFaj5D3BNo ratings yet
- Egyptian Book of The DeadDocument161 pagesEgyptian Book of The DeadBenne James100% (2)
- William Ward Sample PagesDocument14 pagesWilliam Ward Sample PagesRoy MiddletonNo ratings yet
- Speech To The Troops at TilburyDocument4 pagesSpeech To The Troops at TilburyEdelweiss Sanchez Saez100% (1)
- A Text Book of Church History, Vol 4. AD 1517-1648, Gieseler, Transl. Smithl. 1868Document616 pagesA Text Book of Church History, Vol 4. AD 1517-1648, Gieseler, Transl. Smithl. 1868David BaileyNo ratings yet