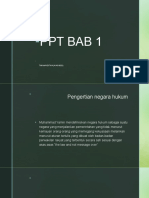Professional Documents
Culture Documents
PDF BAB 1 Tiwi Mayestika PDF
PDF BAB 1 Tiwi Mayestika PDF
Uploaded by
Doni Paok0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views17 pagesOriginal Title
PDF BAB 1 Tiwi Mayestika.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views17 pagesPDF BAB 1 Tiwi Mayestika PDF
PDF BAB 1 Tiwi Mayestika PDF
Uploaded by
Doni PaokCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 17
BABI
PENDAHULUAN
1, Pengertian Negara Hukum
Untuk memahami apa yang dimaksud dengan negara hukum
dalam arti yang sesungguhnya, terlebih dahulu harus dipahami
pengertian negara hukum itu sendiri, sebab tanpa memahami terlebih
dahulu pengertian negara hukum sangat sulit mendeskripsikan secara
utuh, mengenai apa yang dimaksud dengan negara hukum tersebut.
Berbicara mengenai pengertian negara hukum, banyak tulisan atau
pendapat yang diuraikan dalam kepustakaan hukum Indonesia. Dalam
berbagai kepustakaan ditemukan secara jelas pengertian negara hukum
yang diberikan oleh para sarjana, antara lain; Wiryono Projodikoro
(1971:10), memberi pengertian negara hukum sebagai negara dimana
Para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam
melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan
hukum yang berlaku. Muhammad Yamin (1952:74) mendefinisikan
negara hukum sebagal statu negara yang menjalankan pemerntaanr
yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan,
melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan
‘ rat yang tel ‘ara Sah, sesuai dengan asas “the
laws and not menshall govern. Joeniarto (1968:8) memberi definisi
atau_pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana
Fidlakanpenguasanya Parle aibates|-olehhulcuri-yang}bevamar
Sudargo Gautama (1973:73-74) menyatakan bahwa paham negara
hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian
tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat negaranyq
tunduk pada aturan hukum. Sementara itu sarjana lainnya seperti
Soediman Kartohadiprodjo (1953:13) mendefinisikan negara hukum
sebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang di
dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.
Jika dicari inti dari pengertian negara hukum yang dikemukakan
oleh para sarjana Indonesia yang cukup terkemuka itu, tampaknya
mereka semua menekankan tentang tunduknya penguasa terhadap
hukum sebagai esensi negara hukum. Esensi negara hukum yang
demikian itu menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan
Negara pada aturan hukum.
ee
Negara Hukum dan Hak Asasi Mi
kunt merupakan pr
renin to reg nal Ht
perkembangan sejarah, Se ikuti sejarah_perkembangan kehidupa,
itu terus berkembang meng! araan, karena itu dalam Memaha;
manusia dan sejarah koe ara hukum, perlu terlebih dah i
secaa tepat dan perkembangan pemikiran politi dan
diketahui_ gaml 1 ke i
ir dan berkembangnya konsepsj_ pn, ar:
hukum Oa tang negara hukum sebenarnya fed
otoet tua, jauh lebih tua dari usia Iimu Negara ataupun Iimy
Kelstanegaraan itu senditi, Saat ini pemikiran tentang negara hukun,
merupakan gagasan pemikiran modern yang multi perspektif da,
selalu aktual, Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiray
filsafat hukum dan ketatanegaraan, gagasan tentang negara hukyn,
sudah berkembang semenjak seribu delapan ratus tahun sebelym
Masehi (von Schmit, 1988:7). Akar terjauh perkembangan awal
pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Dari
beberapa pemikiran seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddigie
“(1994:11) bahwa tradisi Yunani° kuno menjadi sumber dari gagasan
kedaulatan hukum. Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara
hukum cukup mendapat perhatian dari kalangan intelektual dan para
pemikir, terutama pemikiran-pemikiran tentang negara dan hukum
yang dikembangkan oleh para filsuf besar seperti Socrates, Plato,
Aristoteles dan lain-lain.
Dalam bukunya Politikos yang ditulis pada Penghujung hidupnya,
Plato menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin di-
jalankan dalam negara. Menurut Plato, pada dasarnya ada dua
macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan, yaitu; Pertama;
pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan berdasarkan hukum,
Pemerintahan seperti ini dijalankan oleh Para cendekia, pemerintahan
ditujukan kepada dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kedua;
Pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum, pemerintahan
seperti ini merupakan pemerintahan tiran yang melakukan penindasan
terhadap rakyat. Senada dengan Plato, konsep negara hukum
menurut Aristoteles, adalah negara yang berdiri di atas hukum yang
menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupaka"
syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negarany2,
dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila epee
ana manusia agar ia Menjadi warga negara yang baik. Menuru
ristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusié
2
Bab I, Pendahuluan
sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa
sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.
Pada masa abad pertengahan, pemikiran tentang negara hukum
lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para Raja.
Menurut Paul Scholten (1949:383), istilah negara hukum itu berasal
dari abad ke sembilanbelas, tetapi gagasan tentang negara hukum itu
pada awalnya tumbuh di Eropa sudah hidup dalam abad tujuhbelas.
Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari
Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi
terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang
terkenal sebagai Bil/ of Right 1689, yang berisi hak dan kebebasan
dari warga negara serta peraturan pengganti Raja di Inggris.
Dalam kepustakaan, apa yang dimaksud dengan negara hukum,
sering diterjemahkan dengan istilah rechtstaats atau rule of law.
Paham rechtstaats. pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum
Eropa Kontinental, sedangkan paham rule of /aw bertumpu pada
sistem hukum Anglo Saxon atau common aw system. Ide tentang
rechtstaats mulai populer pada abad ke tujuh belas sebagai akibat
dari situasi sosial politik Eropa yang didominir oleh absolutisme Raja.
Paham rechtstaats ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa
Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl,
Sedangkan Paham rule of /aw mulai dikenal setelah Albert Vann Dicey
pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul Introduction to
Study of The Law of The Constitution. Dalam bukunya Albert Vann
Dicey mengetengahkan tiga arti the rule of law yaitu (Jimly Asshiddigie,
2004:5); ©
1. Supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk
Menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan
kesewenang-wenangan, Jadi berupa discretionary authority yang
luas dari pemerintah;
2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari
semua golongan kepada ordinary law of the land yang
dilaksanakan oleh ordinary court; ini berarti bahwa tidak ada
orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga
negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama,
Jadi tidak perlu ada peradilan administrasi negara;
3. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa
hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi
[Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia
i indivi i i kan oleh
dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegask ar
peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan
peradilan dan Parlemen diperluas hingga membatasi posisi Crown
dan pejabat-pejabatnya.
Dikaji dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya,
terdapat perbedaan antara konsep “rechtsstaat dengan konsep “rule
of jaw, walaupun pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan
dirinya pada satu sasaran utama, yaitu pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia, tetapi Keduanya tetap berjalan
dengan sistem hukum sendiri. Konsep “rechtsstaat” lahir dari suatu
perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner,
sebaliknya konsep “rule of /aw* berkembang secara evolusioner. Hal
ini tampak dari isi atau kriteria “rechtsstaat’ dan kriteria “rule of law”.
Konsep “rechtsstaat’ bertumpu atas sistem hukum kontinental yang
disebut “civil Jaw’ atau “modern roman law", sedangkan konsep “rule
of Jaw’ bertumpu atas sistem hukum yang disebut “common law’.
Karakteristik “ail Jaw" adalah “administratie?, sedangkan karakteristik
“common law’ adalah “judicial .
Perbedaan karakter kedua sistem hukum tersebut terletak pada
kekuasaan Raja, hal ini dapat dilihat dari sejarah kejayaan Raja-raja
pada zaman Romawi, pada masa itu kekuasaan yang menonjol dari
Raja adalah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu
kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif yang
membuat pengarahan-pengarahan atau petunjuk tertulis bagi hakim,
tentang bagaimana menyelesaikan suatu sengketa, kegiatan-kegiatan
pejabat administratif yang demikian setiap saat terus meningkat
sehubungan meningkatnya kasus-kasus dibidang hukum, sehingga
dengan begitu besarnya peranan administrasi negara, tidak meng-
herankan kalau dalam sistem Eropa kontinental inilah asal muasal
munculnya cabang hukum baru yang disebut “droit administratieF
yang intinya adalah hubungan antara administrasi negara dengan
rakyat. Sebaliknya di Inggris, kekuasaan utama dari Raja adalah
memutus perkara sehingga Raja juga sekaligus merupakan hakim
yang memegang badan peradilan. Peradilan oleh Raja ini kemudian
berkembang menjadi suatu peradilan negara, sehingga hakim-hakim
peradilan merupakan delegasi dari Raja, tetapi bukan melaksanakan
kehendak Raja, melainkan bertindak atas nama hukum dan
menjalankan hukum yang berlaku. Intinya hakim harus memutus
4
Bab I. Pendahuluan
perkara berdasarkan kebiasaan umum Inggris (the common custom of
England), sebagaimana dilakukan oleh Raja sendiri sebelumnya.
Mengacu pada hal tersebut, tampak bahwa di Eropa peranan
administrasi negara bertambah maju dan mengemuka, sedangkan di
Inggris peranan peradilan dan para hakim bertambah besar.
Sehubungan dengan perkembangan tersebut, di Eropa dipikirkan
langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara,
sedangkan di Inggris dipikirkan langkah-langkah untuk mewujudkan
suatu peradilan yang adil. Dalam perjalanan waktu kedua konsep itu
berkembang dengan cepat, konsep “rechtstaat’ telah mengalami
perkembangan dari konsep Klasik ke konsep modern. Sesuai dengan
sifat dasarnya, konsep klasik dari rechstaat disebut “ k/asiek /iberale en
democratische rechtstaat'. Sedangkan konsep modern lazimnya
disebut "sociale rechtstaat" atau “sociale democratische rechtstaat"
(Phlipus M. Hadjon, 1987:71-74).
Sifatnya yang liberal bertumpu pada pemikiran kenegaraan dari
John Locke, Montesquieu dan Immanuel Kant, sedangkan sifatnya
yang demokratis bertumpu atas pemikiran kenegaraan dari J.J.
Rousseau tentang kontrak sosial (Crownberg, 1977:25). Prinsip liberal
bertumpu pada “/iberty’ dan prinsip demokrasi bertumpu pada
“equality’. Pengertian “/iberty’ menurut Immanuel Kant adalah “the
free selfassertion of each-limited only by the like liberty of alP. Atas
dasar itu “/iberty“ merupakan suatu kondisi yang memungkinkan,
pelaksanaan kehendak secara bebas dan hanya dibatasi seperlunya,
untuk menjamin koeksistensi yang harmonis antara kehendak bebas
individu, dengan kehendak bebas semua rakyat yang lain. Dari konsep
Pemikiran inilah mengalir prinsip selanjutnya yang dikenal dengan:
“freedom from arbitrary and unreasonable exercise of the Power and
authority’ (Pound, 1957:1-2). Sedangkan konsep “equality
mengandung makna yang abstrak dan formal (abstract-formal
equality) dan dari sini mengalir suatu prinsip yang sangat popular
Gengae-sebutan “one man-one vote’.
Dari sudut pandang ilmu hukum dapat dipahami bahwa asas-asas
demokratis yang melandasi rechtsstaat meliputi lima asas yaitu:
1. asas hak-hak politik;
2. _asas mayoritas;
3. asas perwakilan;
4. asas pertanggungjawaban;
5. _asas publik (apenbaarheidsbeginsel ).
Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dengan demikian, atas dasar sifat liberal dan sifat demokratis
yang ditemukan dalam konsep rechtsstaat maka ciri-ciri 'rechtsstaat”
adalah:
1, Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat
ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan
rakyat; a
2. hems pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi: kekuasaan
pembuat undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan
kehakiman yang bebas dan merdeka, kekuasaan ini tidak hanya
menangani sengketa antar individu rakyat, tetapi juga antara
rakyat dengan penguasa dan pemerintah mendasarkan tindakan-
nya atas undang-undang (wetmatig bestuur); a
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut
“vriiheidsrechten van burger’.
Dalam kaitannya dengan ciri-ciri di atas, menunjukkan dengan
jelas bahwa ide sentral konsep “rechtsstaat’, adalah pengakuan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip
kebebasan dan persamaan. Secara teoritik pengakuan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konsep rechtsstaat
dapat dilihat dari kriteria:
1, Adanya Undang-Undang Dasar yang akan memberikan jaminan
secara konstitusional bagi warga terhadap asas kebebasan dan
persamaan.
2. Adanya pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menghindar dari
penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, karena penumpukan
kekuasaan ini sangat cenderung mengarah kepada penyalah-
gunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan
dan persamaan.
3. Adanya pembuatan undang-undang yang dikaitkan dengan
parlemen, dimaksudkan untuk menjamin bahwa hukum yang
dibuat adalah atas kehendak rakyat, dengan demikian hukum
tersebut tidak akan memperkosa hak-hak rakyat, dan apabila
dikaitkan dengan asas mayoritas, kehendak rakyat diartikan
sebagai kehendak golongan mayoritas,
*: pslerma etmatig Sestuur" agar tindak pemerintahan
kebebassn i fentuan Undang-undang dan tidak memperkosa
Persamaan (heerschappij van de wet).
Bab I, Pendahuluan
Dalam konsep ‘yechtsstaat” yang liberal dan demokratis, inti
perlindungan hukum bagi rakyat adalah perlindungan terhadap
kebebasan individu. Setiap tindak pemerintahan yang melanggar
kebebasan individu, melahirkan hak bagi masyarakat untuk menggugat
di muka pengadilan.
Dalam konsep yuridis, AM, Donner berpendapat bahwa sesungguh-
nya istilah “sociale rechtsstaat’ jauh lebih baik dari istilah "welvaartsstaat’
(Verdam,1976:17). Sedangkan S.W. Couwenberg menjelaskan rechtsstaat
merupakan variant dari “sociale rechtsstaat’ terhadap “Jiberaal-
democratische rechtsstaat’, pemikiran ini antara lain menimbulkan
konsep pemikiran sebagai interpretasi baru terhadap hak-hak klasik
serta merupakan dominasi hak-hak sosial, konsepsi baru tentang
kekuasaan politik dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi,
konsepsi baru tentang makna kepentingan umum, karakter baru dari
“wet' dan “wetgeving’. H. Franken (1983:273) menjelaskan, kebebasan
dan persamaan (vrijheid en gelijkheid) yang semula dalam konsep
Iiberaal-democratische rechtsstaat sifatnya formal yuridis, sedangkan
dalam konsep sociale rechtsstaat ditafsirkan secara rill dalam kehidupan
masyarakat (reele maatschappelijke gelijkheid), hal ini mengandung
pengertian bahwa tidak terdapat persamaan mutlak di dalam
kehidupan masyarakat antara individu yang satu dengan individu
yang lain.
Menurut D.H.M. Meuwissen (1975:140), jika dikaitkan dengan
perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan,
dalam “sociale rechtsstaat’ -prinsip perlindungan hukum terutama
diarahkan kepada perlindungan terhadap hak-hak sosial, hak ekonomi
dan hak-hak kultural. Dikaitkan dengan sifat hak, dalam “rechtsstaat”
yang liberal dan demokratis adalah “the right to do’, dalam "sociale
rechtsstaat’ muncul “the right receive’. Jadi apabila dihubungkan dengan
sasaran perlindungan hukum, maka terlihat semakin kompleks sistem
perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam konsep yuridis “sociale
rechtsstaat’, tugas negara di samping melindungi kebebasan hak-hak
sipil juga melindungi gaya hidup rakyat. Pengaruh negara terhadap
individu menjelma dalam tiga cara yakni:
1. Pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan
terHadap hak-hak sosial;
2. Pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat
pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian;
3. Harapan bahwa problema-problema masyarakat dapat dipecahkan
melalui campur tangan penguasa.
‘Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pandangan murni dan sempit mengenai “rule of Jaw’, sebagaimana
dikemukakan oleh A.V. Dicey, karena inti dari tiga pengertian dasar
yang diketengahkannya adalah “common /aw', sebagai dasar per-
lindungan bagi kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan
oleh penguasa. Demikian pula A.V. Dicey menolak kehadiran Peradilan
Administrasi Negara, adalah sesuai dengan perkembangan hukum dan
kenegaraan di Inggris. Inti kekuasaan Raja di Inggris semula adalah
kekuasaan memutus perkara, kekuasaan itu kemudian didelegasikan
kepada hakim-hakim peradilan yang memutus perkara tidak atas
nama Raja, tetapi berdasarkan "the common custom of england”
sehingga dengan pendelegasian untuk mengadili perkara yang di-
serahkan pada hakim-hakim ini membuat karakteristik dari “common
Jaw" adalah “judicial’, sedangkan karakteristik dari “civil /aw' adalah
administratif.
Pikiran-pikiran lain mengenai konsep rechtsstaat dan rule of law
muncul dari Wade dan Geofrey Philips, pemikiran mereka merupakan
pikiran yang telah terpengaruh oleh pandangan Eropa. Hal ini tampak
dari konsepnya mengenai “rule of Jaw’ dan kritiknya terhadap pikiran
dari Dicey. Dalam kritiknya terhadap A.V. Dicey mengenai “equality’,
tampak di sana pengaruh dari pikiran-pikiran “rechtsstaat’, tentang
kritiknya terhadap “common law’ dari Dicey, dalam kritik itu
dikemukakan mengenai kelemahan dari “written constitution’ yang
menunjukkan pengaruh dari pikiran-pikiran “/iberaldemocratisch”
tentang “grondwet”. Padahal baik konsep “rule of /aw’ maupun
konsep “vechtsstaat’ menampakkan pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentralnya.
Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa perbedaan yang
sangat tajam antara konsep negara hukum rechtsstaat dengan
konsep negara hukum rule of /aw, adalah dalam konsep negara
hukum rechtsstaat terlihat besarnya peranan pejabat pemerintahan,
sehingga yang tunduk dan patuh pada hukum hanyalah rakyatnya
saja, konsep ini kemudian bergeser mengikuti konsep negara hukum
rule of law, seperti negara Swedia tahun 1809 melahirkan lembaga
Ombudsman, yang merupakan kepanjangan tangan parlemen Swedia,
dengan fungsi utamanya melakukan kontrol terhadap pemerintahan
atau Raja Swedia yang saat itu dipimpin oleh Raja yang selalu bertindak
absolute, bahkan cenderung bertindak anarki serta sewenang-wenang
terhadap rakyatnya, sehingga rakyatnya mengalami kesengsaraan.
Mulai saat itu dipikirkanlah oleh Parlemen Swedia untuk membentuk
8
Bab I. Pendahuluan
Peradilan Administrasi, khusus untuk mengadili aparat pemerintahan
di Swedia.
Menurut Roscoe Pound (1957:7). Konsep negara hukum rule of
Jaw berintikan Judicial, artinya selalu menjunjung tinggi lembaga
peradilan (supremacy of law), baik rakyat maupun pemerintah jika
melakukan kesalahan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan,
tidak ada perbedaan perlakuan antara rakyat maupun pemerintah
dimata hukum (equality before the law). Pemikiran lain tentang
konsep negara hukum seperti dikemukakan Immanuel Kant dalam
bukunya Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre, yang pada
pokoknya menguraikan mengenai konsep negara hukum liberal.
Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti
sempit, yang menempatkan fungsi recht pada staat, hanya
sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara
diartikan secara pasif, yaitu hanya bertugas sebagai pemelihara
ketertiban dan keamanan masyarakat (Hadjon, 1987:71-74). Paham
Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan nachiwachkerstaats atau
nachtwachterstaats. Negara harus menjadi negara hukum, itulah
semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong dari perkembangan
pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya
batas-batas kegiatannya, negara harus mewujudkan atau memaksakan
gagasan good government dari segi negara, tegasnya negara itu
bukan hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan
pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan,
negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi dari
Negara semata-mata, melainkan bagaimana cara dan upaya untuk
mewujudkannya.
Sarjana lain seperti Paul Scholten (1935:382) menyebut dua ciri
negara hukum. Ciri utama negara hukum ialah: “er is recht tegenover
den staat’, artinya warga negara itu mempunyai hak terhadap negara,
individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya
meliputi dua segi: Pertama; Manusia itu mempunyai suasana
tersendiri yang pada asasnya terletak di luar wewenang negara;
Kedua; Pembatasan suasana manusia itu, hanya dapat dilakukan
dengan ketentuan undang-undang. Ciri yang kedua negara hukum
Menurut Paul Scholten berbunyi; er és scheiding van machten, artinya
dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Pandangan ini sama
dengan pemikiran Montesquieu yang memisahkan kekuasaan menjadi
ia
Negara Hukum dan Hak Asasl Manus
saan membuat undang-undends kekuasaan Menjlana,
dan kekuasaan mela dari kebijakan atau ting
Untuk melindungi hak 28 fam konsep “rule of law” cilakukgn
sewenang-wenang penguasa, orinsip "equality before the lay"
dengan upaya mengedep> hukum dengan tanpa membedala,
adanya parca Lae edang dalam konsep rechtstaat yay,
status nuk : h “rechtmatigheid" yang menonjolkan Sas legalita,
aluemelan 2 ean tindak pemerintah harus sesual dengan hukum,
Re nese Republik Indonesia yang menghendaki keserasia
hubungan antara pemerintah dan rakyat yang aoe kan adalah asa,
kerukunan, dalam hubungan antara pemerinta lengan rakyat. Daj
asas ini akan berkembang elemen [ain dari konsep negara hukun
Pancasila, yakni terjalinnya hubungan fungsional antara kekuasaan.
kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara Musyawarah,
sedangkan peradilan merupakan sasaran terakhir, dan tentang hale
hak asasi manusia, tidak hanya menekankan hak dan kewajiban sa,
tetapi juga terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban,
tiga, yaitu kekuas
Undang-undang
2. Hubungan Negara Hukum Dengan Hak Asasi Manusia
Pertanyaan mendasar yang dikemukakan pada bagian ini adalah:
Apa hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia?. Jawaban
atas pertanyaan ini sudah barang tentu, tidak begitu sult
mengkajinya dari sudut ilmu hukum, sebab antara negara hukum
dengan hak asasi manusia, tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Argumentasi hukum yang dapat diajukan tentang hal ini, ditunjukkan
dengan ciri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu diantaranye
adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara
hukum hak asasi manusia terlindungi, jika dalam suatu negara hak
asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum
akan tetapi negara diktator dengan Pemerintahan yang sangat
Otoriter. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negalé
fonsttas en eam bentuk Penormaan hak tersebut dalam
g-undar ji
melalui badan-badan ere dan untuk selanjutnya penegakannyé
kehakiman, dilan sebagai pelaksana _kekuasa@"
med an ebaman, Merupakan kekuasaan yang bebas dam
‘ mepas dari pengaruh kekuasaan_ pemerintat:
10
Bab I. Pendahuluan
Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang
tentang kedudukan para hakim. Salah satu ciri negara hukum ialah
dimana terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas dan tidak
dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.
Kebebasan hakim tidak harus diartikan bahwa hakim dapat melakukan
tindakan yang sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang
diperiksanya, akan tetapi hakim tetap terikat pada hukum. Konstitusi
melarang campur tangan pihak eksekutif ataupun legislatif terhadap
kekuasaan kehakiman, bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang
bersangkutan pun, tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi
atau mendiktekan kehendaknya kepada hakim bawahan. Menurut
Oemar Seno Adji (1985:49) dalam bukunya yang berjudul, Peradilan
Bebas Negara Hukum, dijelaskannya bahwa salah satu maxim dari
konstitusionalisme adalah bahwa Pengadilan itu harus bebas dari
pengawasan pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan lain.
Kebebasan kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraannya diserahkan
kepada badan-badan peradilan merupakan salah satu ciri khas negara
hukum.
Pada hakekatnya, kebebasan peradilan ini merupakan sifat pem-
bawaan dari setiap peradilan, hanya saja batas dan isi kebebasannya
dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.
Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial itu pun tidak
mutlak sifatnya, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan
hukum dan keadilan, dengan jalan menafsirkan hukum dan men-
cari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya. Hal ini
dijalankan oleh hakim melalui perkara-perkara yang dihadapkan
kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan
(Mertokoesoemo, 1973:79-88).
Asas perlindungan dalam negara hukum, tampak antara lain
dalam Declaration of Independence, deklarasi tersebut mengandung
asas bahwa orang yang hidup di dunia ini, sebenarnya telah
diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang
tidak dapat dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapat
Perlindungan secara tegas dalam negara hukum. Peradilan tidak
semata-mata melindungi hak asasi perseorangan, melainkan fungsinya
adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas, agar supaya
cita-cita Iuhur bangsa tercapai dan terpelihara.
Peradilan mempunyai maksud membina, tidak semata-mata
Menyelesaikan perkara, hakim harus mengadili menurut hukum dan
11
jan Hak Asasi Manusia.
laran akan kedudukan, fungsi dan sifat
On hakim dalam = menjalankan tugasnya
kepada diri sendiri dan Tons? Yang maha Esa,
dan menegakkan masyarakat yang sejahtera
ti ee enurut Muh. Yamin (1952:9) bahwa untuk me-
0 ntukan apakah suatu negara merupakan negara hukum, semata-
mata didasarkan pada asas legalitas. Senada dengan itu Gouw Giok
Siong menyatakan bahwa asas legalitas hanyalah merupakan salah
satu unsur, atau salah satu corak dari negara hukum, perasaan
keadilan dan perikemanusiaan, baik bagi rakyat maupun pimpinannya,
Mengenai asas_perlindungan, dalam setiap konstitusi dimuat
ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Ketentuan tersebut
antara lain:
Kebebasan berserikat dan berkumpul;
Kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan dan tulisan;
Hak bekerja dan penghidupan yang layak;
Kebebasan beragama;
Hak untuk ikut mempertahankan negara; dan
Hak lain-lain dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia.
ra Hukum
menjalankan den
hukum. Dengan
bertanggung jawab
oy een
Setiap orang dapat menuntut atau’ mengajukan gugatan kepada
negara, bila negara melakukan suatu perbuatan yang melawan
hukum (onrechtmatigadaad), bahwa seseorang dapat melakukan
gugatan terhadap penguasa, jika putusan pejabat yang berwenang
dirasa tidak adil. Banyak peraturan-peraturan yang memberi jaminan
kepada para warga negara, untuk menggunakan hak-haknya mengaju-
kan tuntutan-tuntutan di muka pengadilan, bila hak-hak dasarnya
atau kebebasannya dilanggar.
Dalam kaitannya dengan peradilan yang cepat, murah dan
sederhana, fleksibilitas ini tidak lain untuk memungkinkan upaya
Memenuhi secara cepat dan efisien permintaan yang ajeg akan
keadilan. Dalam hal ini yang dimaksudkan tidak lain, adalah asas
penting dalam peradilan yang tidak asing lagi yakni cepat, tepat,
tuntas, sederhana dan biaya ringan. Cepat, tepat dan tuntas
menyangkut cara penyelesaian atau pemeriksaan perkara. Cepatnya
penyelesaian, berarti bahwa pemeriksaannya tidak bertele-tele atau
Seen, tertunda-tunda tanpa alasan-alasan yang penting, yang
nya akan mengakibatkan terjadinya kongesti atau tunggakan
perkara. Tepat dan tuntas, terutama menyangkut putusan pengadilan.
12
Bab I. Pendahuluan
Putusan pengadilan harus tepat sasarannya, hakim harus tepat
mengetahui apakah yang sesungguhnya yang menjadi pokok
sengketa. Putusan pengadilan baru tepat apabila konstatering
peristiwanya dan kualifikasi peristiwanya itu tepat, yaitu peristiwa
yang dianggap terbukti itu, sesuai dengan apa yang dituntut atau
sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi, dan sesuai pula
dengan pandangan masyarakat. Tuntas berarti bahwa putusannya
sungguh-sungguh menyelesaikan atau mengakhiri perkara, sehingga
tidak memungkinkan timbulnya perkara baru. Asas sederhana
berhubungan dengan hukum acaranya. Hukum acara harus sederhana
tidak berbelit-belit atau tidak formalitis, karena apabila formalitis
akan mudah menimbulkan pelbagai penafsiran, kurang menjamin
kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan
untuk beracara di muka pengadilan. Hukum acara yang sederhana
dan mudah untuk dipahami, kecuali memperlancar jalannya peradilan
juga akan membuat orang tidak segan beracara di pengadilan. Asas
biaya ringan sangat penting artinya, karena biaya perkara yang
tinggi akan membuat orang enggan berperkara. Tidak wajar kalau
seseorang hendak menuntut haknya lewat pengadilan dipungut biaya
yang tinggi. Jadi pada prinsipnya biaya perkara harus dapat dipikul
oleh kebanyakan orang, dengan pengecualian khusus bagi mereka
yang tidak mampu harus dibebaskan dari biaya perkara.
Untuk lebih memantapkan dukungan ilmiah terhadap kebenaran
proposisi kekuasaan kehakiman tunduk pada hukum, perlu dilakukan
pembahasan yang lebih luas tentang keanekaragaman konsep negara
hukum, sebagai batu loncatan untuk sampai pada jawaban apa
hubungan antara negara hukum dengan hak asasi manusia. Dalam
pengkajian Indonesia, penekanan negara hukum akan diletakkan
pada pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman Indonesia juga tunduk
pada hukum. Pemikiran demikian, sangat penting untuk mengantarkan
persepsi, bahwa tunduknya kekuasaan kehakiman pada hukum,
Menyebabkan munculnya pemahaman akan adanya batas-batas
kebebasan kekuasaan kehakiman, dalam memberikan perlindungan
terhadap hak asasi manusia. Sehingga dari apa yang diuraikan di
atas, sangat jelas hubungan antara negara hukum dengan hak asasi
manusia. .
Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi
hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum
sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, ada
13
jara Hukum dan Hak Asasi Manusia
pendapat mengatakan bahwa pada hakikatnya pemimpin tertinggi
negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang
Mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai
supremasi hukum, adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan
hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik, adalah
pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar
masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme. Bahkan, dalam
Republik yang menganut sistem Presidentil yang bersifat murni, wajar
apabila konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut
sebagai kepala negara. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan
presidentil, tidak dikenal adanya pembedaan antara kepala negara
dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan
parlementer (Mahmuda Ismail, 1997:24).
Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakat-
kan secara luas, dalam rangka mempromosikan penghormatan dan
Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagai ciri yang
penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak
kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang
bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula
Penyelenggaraan kekuasaan suatu negara, tidak boleh mengurangi
arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu, oleh
karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak
asasi manusia, merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap
negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara,
hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan
Penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil,
negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum
dalam arti yang sesungguhnya.
Untuk melihat lebih lanjut hubungan negara hukum dengan hak
asasi manusia, dapat dikaji dari sudut pandang demokrasi, sebab hak
asasi manusia dan demokrasi, merupakan konsepsi kemanusiaan dan
relasi sosial yang dilahirkan, dari sejarah peradaban manusia di
seluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat
dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia, untuk mempertahankan
dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya
konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi yang terbukti paling
mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Konsepsi hak asasi
manusia dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa
relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada
14
Bab I. Pendahuluan
manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya
satu yang mutlak dan merupakan prima facie, yaitu Tuhan Yang Maha
Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran,
tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena
yang benar secara mutlak hanya Tuhan, oleh karenanya semua
pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif.
Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang
lain berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan
dengan Kemanusiaan dan Ketuhanan.
Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat
hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang
kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh
sejak kelahirannya, sebagai manusia yang merupakan karunia Sang
Pencipta, hal ini dengan tegas dimuat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang
mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai; seperangkat hak yang
melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia’. Setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat
dengan hak-hak yang sama, prinsip persamaan dan kesederajatan
merupakan hal utama dalam interaksi sosial, akan tetapi kenyataan
Menunjukkan bahwa hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara
individual, pencapaiannya harus melalui organisasi atau perkumpulan,
untuk itu dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan ‘organisasi sosial
tersebut dan diberi kekuasaan secara demokratis.
Konsepsi demokrasi itulah yang memberikan landasan dan mekanis-
me kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan
manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan
yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasar-
kan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia
tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual,
tetapi harus bersama-sama. Untuk itu dibuatlah perjanjian sosial yang
berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak
individual dan siapa yang bertanggung jawab, untuk pencapaian
tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan
batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi
sebagai hukum tertinggi disuatu negara, kemudian dielaborasi secara
15
Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia
konsisten dalam hukum dan kebijakan negara (Jimly Asshiddigie,
2001:12), Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan
umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.
Konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi dalam perkembangannya,
sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam negara hukum,
sesungguhnya yang memerintah adalah hukum bukan manusia.
Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum
yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti, bahwa dalam sebuah
negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi, Supremasi
konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara
hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan’ demokrasi karena konstitusi
adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Selain itu, prinsip demokrasi
atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan
Perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar
mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan
diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan
penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin
kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin
kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara
hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan
democratische rechtsstaat.
Sebagaimana telah dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua
UUD Tahun 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah
mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-
Undang Dasar. Sebagian besar materi UUD ini sebenarnya berasal
dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap
hak-hak asasi manusia, sangat penting dan bahkan dianggap
merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum
disuatu negara. Di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipa-
hami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab
yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya memiliki hak
dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara
dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan
prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia,
karena itu jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedu-
16
Bab I. Pendahuluan
cs ee Pepsi
dukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang dimana pun ia
berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan,
setiap orang dimana pun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi
hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan
kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri
penting pandangan dasar bangsa Indonesia, mengenai manusia dan
kemanusiaan yang adil dan beradab.
Bangsa Indonesia memahami bahwa The Universal Declaration of
Human Rights yang dicetuskan pada tahun 1948, merupakan per-
nyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang
wajib dihormati. Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia juga
memandang bahwa The Universal Deciaration of Human Responsibility
yang dicetuskan oleh Inter Action Council pada tahun 1997 juga
mengandung nilai universal yang wajib dijunjung tinggi untuk
melengkapi 7he Universal Declaration of. Human Rights tersebut.
Kesadaran umum mengenai hak-hak dan kewajiban asasi manusia itu,
menjiwai keseluruhan sistem hukum dan konstitusi Indonesia, oleh
karena itu perlu diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang
Dasar atas dasar pengertian-pengertian dasar yang dikembangkan
sendiri oleh bangsa Indonesia. Sehingga dengan demikian,
perumusannya dalam Undang-Undang Dasar ini mencakup warisan-
warisan pemikiran mengenai hak asasi manusia dimasa lalu dan
mencakup pula pemikiran-pemikiran yang masih terus akan berkem-
bang dimasa-masa yang akan datang.
Dari uraian-uraian di atas terlihat jelas hubungan antara negara
hukum dengan hak asasi manusia, hubungan mana bukan’ hanya
dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan
hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, tapi
juga hubungan tersebut terlihat secara materil. Hubungan secara
materil ini dilukiskan atau digambarkan dengan setiap sikap tindak
penyelenggara negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagai
asas legalitas. Konstruksi yang demikian ini menunjukkan pada
hakekatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa bertujuan
untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan
kehakiman yang bebas dan merdeka, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan
manapun, merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap
hak asasi manusia dalam negara hukum.
17
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5811)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- BAB 5 Indri PratiwiDocument17 pagesBAB 5 Indri PratiwiDoni PaokNo ratings yet
- BAB 2 Tiwi MayestikaDocument18 pagesBAB 2 Tiwi MayestikaDoni PaokNo ratings yet
- BAB 1 Tiwi MayestikaDocument16 pagesBAB 1 Tiwi MayestikaDoni PaokNo ratings yet
- PDF BAB 13 Nuriwan PDFDocument18 pagesPDF BAB 13 Nuriwan PDFDoni PaokNo ratings yet
- PDF BAB 11 Tri Nugroho Romadhon PDFDocument11 pagesPDF BAB 11 Tri Nugroho Romadhon PDFDoni PaokNo ratings yet
- BAB 3 YunisaraDocument21 pagesBAB 3 YunisaraDoni PaokNo ratings yet
- PDF BAB 14 Nuriwan PDFDocument20 pagesPDF BAB 14 Nuriwan PDFDoni PaokNo ratings yet
- Latsar Adm 2 GK JadiDocument1 pageLatsar Adm 2 GK JadiDoni PaokNo ratings yet
- Prinsip-Prinsip Penilaian Kelompok 2 PHBDocument14 pagesPrinsip-Prinsip Penilaian Kelompok 2 PHBDoni PaokNo ratings yet
- Tri Nugroho Romadhon Uas Hi A1a318056Document5 pagesTri Nugroho Romadhon Uas Hi A1a318056Doni PaokNo ratings yet
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Berbasi Profil Pelajar PancasilaDocument2 pagesRENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Berbasi Profil Pelajar PancasilaDoni PaokNo ratings yet
- Norma Dalam Kehidupan MasyarakatDocument2 pagesNorma Dalam Kehidupan MasyarakatDoni PaokNo ratings yet
- Model Pembelajaran KuantumDocument1 pageModel Pembelajaran KuantumDoni PaokNo ratings yet