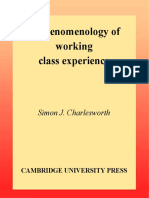Professional Documents
Culture Documents
Tahap Perkembangan Etik Dan Moral Kohleberg
Uploaded by
Anika KartikaOriginal Description:
Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Tahap Perkembangan Etik Dan Moral Kohleberg
Uploaded by
Anika KartikaCopyright:
Available Formats
Ar-Risalah: Media Keislaman,
Pendidikan dan Hukum Islam
Volume XVIII Nomor 1 Tahun 2020
Print ISSN : 1693-0576
Online ISSN : 2540-7783
TAHAPAN PENGEMBANGAN MORAL: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM
(Telaah Terhadap Gagasan Thomas Lickona,
Lawrence Kohlberg dan Al-Qur’an)
Iwan Kuswandi
STKIP PGRI Sumenep Madura, Indonesia
Program Doktoral Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
e-mail: kuswandisumenep87@gmail.com
Abstract
A decline in moral is among the impacts of technological development. For this
reason, Thomas Lickona and Lawrence Kohlberg developed a concept of moral
development, a concept which has also been discussed in the Holy Quran. Lickona
stated that moral development stages are started with the ownership of moral
knowledge (moral knowing) and move to moral feeling and moral action. Kohlberg
stated that there are six stages in moral development. The stages are in three phases.
First phase is called pre-conventional, which consists of stage 1 and stage 2. In this
phase, people are more concerned about being right and wrong and getting reward
or punishment. The next phase is called conventional phase, which consists of stage 3
and stage 4. In this level, people are more driven by internal motivation and how they
are perceived by society. The final phase is post conventional phase, consisting of
stage 5 and stage 6. In this level, people are able to independently interpret moral
values and are driven by more universal values. The Quran divided the stages into
some classes which are mentioned as ulul ilm (those of knowledge), ulin nuha (those
of intelligence), ulil abshar (those of vision), ulil albab (those of understanding), ulil
amri (those in authority), ulil aidi (those of strength) dan ulil azmi (those of
determination).
Keywords: Thomas Lickona, Lawrence Kohlberg, Al-Qur’an
Accepted: Reviewed: Publised:
Maret 09 2020 Maret 25 2020 April 30 2020
A. Pendahuluan
Pembahasan peradaban manusia, tidak hanya pada persoalan analisis tataran
materiil semata, atau urusan jasmani saja. Namun pada saat ini, manusia
berhadapan dengan kemajuan peradaban atau memasuki era mutakhir yang
modern, era global, berteknologi tinggi, dan serba digital, sehingga berdampak
pada mengikisnya rasa kemanusiaan, tidak memedulikan lingkungan sekitarnya.
Salah seorang saintis barat mulai membongkar epistemologinya. Sebagaimana
yang dikatakan Richard Tarnas, bahwa sains Barat saat ini sedang memasuki
“krisis
License Available online on: http://iaiibrahimy.ac.id/index.php/index
This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International
License Available online on: http://iaiibrahimy.ac.id/index.php/index
Iwan
global”, sebuah krisis yang multidimensional yang mengakibatkan kehidupan
manusia semakin terpuruk. Untuk itu, perlu hadirnya nilai-nilai humanism menjadi
landasan formulasi moralitas dan etika di kehidupan masyarakat. Moralitas dan
humanisme adalah roh peradaban, atau perlunya pendidikan yang dikemas dengan
muatan berperspektif integritas dan humanistik (Ilahi, 2012; Malik, 2016;
Manurung, 2012).
Gejala yang menandakan tergerusnya karakter terlihat dalam kehidupan kita
saat ini. Sebagai contoh, di beberapa daerah terjadi tawuran antarpelajar,
menjamurnya penggunaan bahasa yang buruk, seperti penggunaan bahasa prokem
yang secara historis berasal dari komunitas tertentu menjamur di mana-mana.
Semisal,”Titi DJ (hati-hati di jalan), Titi Kamal (hati-hati kalau mlaku), bahkan
sekarang juga marak bahasa alay. Bahkan yang sangat memalukan, di dunia
pendidikan ancaman budaya tidak jujur merebak ketika guru-guru dan siswa
berkonspirasi dalam Ujian Nasional (Barnawi & Arifin., 2012).
Marcus Tulius Cicero, seorang cendekiawan Republik Roma, pernah
mengingatkan warga kekaisaran Roma bahwa kesejahteraan sebuah bangsa
bermula dari karakter kuat warganya. Demikian juga sejarawan ternama, Arnold
Toynbee, pernah mengungkapkan bahwa dari dua puluh satu peradaban dunia
yang dapat dicatat, Sembilan belas diantaranya hancur bukan karena penaklukan
dari luar, melainkan karena pembusukan moral dari dalam (Nida, 2013). Hal
senada juga menjadi perbincangan di kalangan birokrat di Indonesia sejak tahun
2010. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra)
mengeluarkan kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, yang
diharapkan bisa direspon oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian
Agama agar tak sekadar menjadi wacana akan tetapi menjadi action plan dalam
program pendidikan di seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah dua
kementerian tersebut (Thobroni & Dkk, 2018).
Di dunia Barat, dikenal sosok Thomas Lickona dan Lawrence Kohlberg, kedua
pemikir barat tersebut dianggap memiliki perhatian besar terhadap karakter dan
moral. Misalnya penelitian Lawrence Kohlberg, tentang perkembangan kesadaran
moral manusia yang berkaitan dengan perkembangan hati nuraninya. Selain tiga
tahapan, ada juga tahapan otonom, sebuah orientasi prinsip etika yang universal,
yang mana manusia mengatur tingkah laku dan penilaian moralnya berdasarkan
hati nurani pribadinya (Ilahi, 2014). Sebelum Thomas Lickona dan Kohlberg
menyuarakan pendidikan karakter dan moral, sebenarnya Islam sudah terlebih
dahulu memberikan keteladan melalui diutusnya sosok Muhammad saw dalam
rangka memperbaiki akhlak manusia. Kepribadian dan perangai Nabi Muhammad
saw, dapat dilihat pada kandungan al-Qur’an. Bahkan suatu waktu, Hisyam bin
Amir
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 15
Iwan
pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah R.a tentang akhlak Rasulullah S.a.w,
Aisyah menjawab, “Akhlak Nabi S.a.w adalah Al Qur’an.”. (HR Muslim). Dengan kata
lain, bahwa konsep karakter dan moral Al-Qur’an, lebih dahulu mengawali konsep
karakter dunia barat. Semisal Ibn Miskawaih yang berkeyakinan pendidikan etika
atau moral merupakan pendidikan utama bagi manusia, ditambah lagi al-Ghazali
mendudukkan peran moral dalam pendidikan (Kuswandi, 2019).
Berangkat dari hal tersebut, maka tulisan ini ingin mendeskripsikan tentang
tahapan pembentukan moral anak menurut Thomas Lickona dan Lawrence
Kohlberg, serta ingin mendeskripsikan tingkatan manusia bermoral dan beretika
di dalam perspektif al-Qur’an.
B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau
kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengkaji sumber data
primer yaitu kitab suci Al-Qur’an dan buku-buku karya Thomas Lickona dan
Lawrence Kohlberg. Selain itu, juga buku dan artikel hasil penelitian yang
menyediakan data teoritis tentang pendidikan moral, dan beberapa kitab tafsir,
terutama tafsir tentang ayat yang digunakan dalam penelitian ini.
Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisisisi (content
analysis). Adapun langkah-langkah yang digunakan dengan mengikuti urutan
berikut; analisis teks, analisis wacana, study tokoh, dan menarik kesimpulan serta
mensistematikkan pemikiran tahapan moral dalam perspektif Thomas Lickona dan
Lawrence Kohlberg serta konsep moral dalam kitab suci al-Qur’an.
C. Hasil dan Pembahasan
Tahapan mencetak moral anak perspektif Thomas Lickona
Thomas Lickona lahir 4 April 1943. Mendapat gelar Bachelor of Arts dalam
Bahasa Inggris di Siena College pada tahun 1964, selanjutnya pada tahun 1965
meraih gelar Master of Arts dalam Bahasa Inggris di Ohio University, sedangkan
gelar Doktor of Philosophy dalam psikologi di State University of New York di
Albany pada tahun 1971 (Lubis, 2018). Saat ini menetap di Cortland New York
(Lickona, 2004). Memperoleh gelar Ph.D dalam bidang psikologi dengan risetnya
mengenai perkembangan penalaran moral anak-anak (Lickona, 1991). Beberapa
karya Thomas Lickona diantaranya berjudul, “Educating for character: how our
school can teach respect and responsibility” (1991). Sedangkan tulisan di jurnal
ilmiah berjudul, “The return of character education” yang dimuat dalam jurnal
education leadership (November 1993), “Eleven principles of effective character
education”, dimuat dalam journal of moral volume 25 1996 (Husni & Norman,
2015).
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 16
Iwan
Buku terbarunya Character Matter-How to help Our Childern Develop Good
Judgement, Integrity and Other Essential Virtues (2004) dan Character Quotations
(2004), yang ditulis bersama Dr. Matthew Davidson (Lubis, 2018).
Thomas Lickona adalah seorang pendidik karakter dari Cortland University,
yang dikenal sebagai bapak pendidikan karakter Amerika. Sebagai pencetus
pendidikan karakter, Lickona dianggap sebagai pendidik yang mampu menularkan
semangat baru dalam membina generasi muda agar tidak mudah terjebak dengan
pergaulan bebas dan gaya hidup yang semakin tidak terkendali. Lickona
mengatakan bahwa sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran, jika
memiliki sepuluh tanda-tanda zaman, yaitu meningkatnya kekerasan di kalangan
remaja, membudayanya ketidakjujuran, sikap fanatic terhadap kelompok,
rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, semakin kaburnya moral baik
dan buruk, penggunaan bahasa yang memburuk, meningkatnya perilaku merusak
diri seperti penggunaan narkoba, alcohol dan seks bebas, rendahnya rasa tanggung
jawab sebagai individu dan sebagai warga Negara, menurutnya etos kerja dan
adanya rasa saling curiga dan kurangnya kepeduliaan di antara sesama (Ilahi,
2014).
Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona adalah suatu usaha yang
sengaja dilakukan untuk menjadikan seseorang menjadi memahami,
memperhatikan dan melakukan nila-nilai etika yang baik. Untuk mencapai hal
tersebut, maka dibutuhkan proses yang dimulai dengan melibatkan pengetahuan
(moral knowing), perasaan (moral feeling), dan tindakan (moral action). Tahapan
dalam moral knowing (pengetahuan moral), yaitu: moral awarnes (kesadaran
moral), knowing moral values (pengetahuan nilai-nilai moral), perspective-taking
(mampu mengambil pelajaran), moral reasoning (alasan moral), decision-making
(pengambilan keputusan), dan self-knowledge (mengukur diri). Sedangkan
tahapan moral feeling (perasaan moral), yaitu: conscience (kesadaran), self-
esteem (penghargaan diri), empathy (empati), loving the good (mencintai yang
baik), self- control (mengatasi), dan humality (kerendahan hati). Adapun tahapan
moral action (tindakan moral), yaitu: competence (kompetensi), will (kemauan),
dan habit (kebiasaan) (Dalmeri, 2014; Lickona, 1991; Sudrajat, 2011). Selain itu,
menurut Thomas Lickona ada tujuh unsur karakter esensial kepada peserta didik,
yaitu: ketulusan hati atau kejujuran (honesty), belas kasih (compassion),
kegagahberanian (courage), kasih sayang (kindness), kontrol diri (self control),
kerjasama (cooperation) dan kerja keras (diligence or hard work) (Dalmeri, 2014).
Menurut Thomas Lickona, anak didik itu memiliki 5 tingkatan level. Diawali
dari level 0 sampai level 4. Seseorang yang berada di level 0, ia memiliki karakter
suka berbicara dengan keras, seringkali ceroboh atau bodoh, pekerjaan yang
dicapai jumlahnya minimal atau diselesaikan dengan ceroboh, tindakannya
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 16
Iwan
mencampuri
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 16
Iwan
kemampuan anak lain untuk berkonsentrasi, menyalahkan materi. Sedangkan anak
yang berada di level 1, karakteristiknya sangat sedikit atau tidak ada pekerjaan
yang terlihat sama sekali di akhir waktu yang diberikan, berputar-putar, bingung.
Adapun anak level 2, karakteristiknya, pekerjaan diselesaikan dengan pengingat
atau pertanyaan yang diberikan oleh orang dewasa yang hadir, tidak banyak
pekerjaan yang terlihat, melakukan pembicaraan yang tidak baik, mungkin
ceroboh, kadang- kadang bekerja dan kadang-kadang tidak bekerja. Untuk level 3,
karakteristiknya, pekerja keras, melakukan apa yang diharapkan, menghormati
hak-hak dan pekerjaan orang lain, menyelesaikan pekerjaan dengan hati-hati,
menggunakan waktu dengan baik, menggunakan materi dengan hati-hati dan
bertanggung jawab, melakukan pembicaraan dengan baik, bertekun. Sedangkan
kalau seseorang masuk pada level 4, ia memiliki rasa hormat, penuh rasa tanggung
jawab serta suka membantu orang lain, memiliki kreativitas melebihi yang
diharapkan (Husni & Norman, 2015).
Penanaman karakter membutuhkan keteladanan dari seorang guru, seorang
guru harus menghindari sikap pilih kasih, kasar, harus bisa memperlakukan siswa
dengan hormat dan penuh kasih sayang, serta melakukan pembimbingan anak
didik, satu per satu dengan cara mencari tahu bakat khusus yang dimiliki masing-
masing anak, memberikan respon positf atau memuji anak, serta juga
menggunakan pertemuan personal untuk memberikan umpan balik yang korektif
ketika mereka membutuhkannya. Peran guru selain sebagai teladan dan
pembimbing, guru juga berperan dalam membangun masyarakat yang bermoral
dan menciptakan nilai- nilai saling menghargai dan tanggung jawab dalam
kehidupan di kelas. (Husni & Norman, 2015; Lickona, 1991).
Setidaknya ada 11 prinsip dasar dalam pendidikan moral: Pertama,
pendidikan karakter harus mencakup nilai-nilai pokok dari etika sebagai dasar
karakter yang baik. Kedua, "karakter" harus didefinisikan secara menyeluruh
dengan menyertakan kognitif, afektif dan psikomotor. Ketiga, agar pendidikan
karakter efektif, diperlukan pendekatan yang disengaja, proaktif, dan
komprehensif yang mencakup nilai-nilai pokok etika di semua fase kehidupan
sekolah. Keempat, sekolah harus menjadi sebuah komunitas yang saling peduli.
Kelima, peserta didik membutuhkan kesempatan untuk melakukan tindakan moral
agar karakter mereka dapat berkembang. Keenam, pendidikan karakter yang
efektif juga mencakup kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang
menghormati perbedaan individu peserta didik dan mampu membantu mereka
untuk berhasil mencapai target dari tugas-tugas sekolah. Ketujuh, pendidikan
karakter harus diarahkan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik.
Kedelapan, guru dan tenang kependidikan harus menjadi bagian dari komunitas
belajar dan pendidikan moral,
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 16
Iwan
dimana semua pihak berbagi tanggungjawab dalam pendidikan karakter dan
berusaha mematuhi nilai-nilai etika yang sama yang memandu peserta didik ke
arah pendidikan karakter yang ingin dicapai sekolah. Kesembilan, pendidikan
karakter membutuhkan kepemimpinan moral baik dari guru, tenaga kependidikan
dan peserta didik. Kesepuluh, sekolah harus melibatkan orangtua dan masyarakat
sebagai partner utama pendidikan karakter peserta didik. Dan Kesebelas, tiga hal
yang harus dievaluasi dari sebuah program pedidikan karakter yaitu; karakter
sekolah, peran yang sudah dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan sebagai
pendidik karakter, dan perkembangan karakter-karakter yang tertanam dalam diri
peserta didik (Lickona, 1996).
Tahapan mencetak moral anak perspektif Lawrence Kohlberg
Lawrence Kohlberg dilahirkan di Bronxville, New York, Amerika Serikat, pada
25 Oktober 1927. Ia dilahirkan dari seorang pengusaha kaya raya, sehingga masa
kanak-kanak dan pendidikannya, terbilang mewah dan istimewa. Semua fasilitas
terpenuhi dan dididik di sekolah unggul tentunya (Jumiyati, 2016). Namun akhir
hidup Kohlberg tidak seindah kehidupannya, ia melakukan bunuh diri. Ia tertular
sebuah penyakit tropis pada 1971 ketika ia melakukan pekerjaan lintas budaya
di Belize. Akibatnya, ia bergumul dengan depresi dan penderitaan fisik selama 16
tahun kemudian. Pada 19 Januari 1987, ia meminta cuti satu hari dari Rumah Sakit
Massachusetts tempat ia dirawat, lalu pergi dengan mobilnya ke pantai, dan
kemudian bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di Samudera Atlantik.
Umurnya 59 tahun ketika ia meninggal dunia.
Karir puncak Kohlberg sebagai profesor di Universitas
Chicago serta Universitas Harvard. Ia terkenal karena karyanya dalam pendidikan,
penalaran, dan perkembangan moral. Dalam proses mewujudkan tahap
perkembangan moralnya, setidaknya pemikiran Kohlberg dipengaruhi oleh John
Dewey, Baldwin, Jean Pieget, dan Emile Durkheim (Jumiyati, 2016), serta juga
dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber (Suryawan, 2018).
Menurut Kohlberg, moralitas pada dasarnya mengalami perkembangan dan
berpusat pada ranah kognitif, bersifat interaksional dan dilandasi oleh prinsip-
prinsip keterbukaan, kesamaan, resiprositas, dan keadilan. Atau mudahnya, moral
itu dipengaruhi oleh bangunan pengetahuan yang dimiliki sebagaimana pemikiran
Jean Pieget, namun menurut Kohlberg bangunan pikiran membutuhkan pola
interaksi sosial sebagaimana pemikiran Durkheim dan Max Weber. Kohlbeg juga
memiliki kepercayaan sebagaimana Lickona bahwa moral membutuhkan
keteladanan. Menurut Kohlberg bahwa moralitas tanpa perbuatan adalah mayat.
Maka semua teladan moral dijadikan sebagai pendidik moral (Suryawan, 2018).
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 16
Iwan
Tahapan perkembangan menurut Moral Kohlberg ada enam tahapan.
Tahapan Pertama adalah pra-konvensional. Pada tingkat pra-konvensional
(tingkat 1 dan 2), orientasi pada ketaatan terhadap aturan karena ukuran benar
dan salah, mendapat reward atau punishman. Sedangkan Tahapan Kedua adalah
konvensional atau kebiasaan (tingkat 3 dan 4), pada level ini sudah hadir motivasi
dalam dirinya untuk tetap eksis dan menjaga citra stereotipe dalam kehidupan
masyarakatnya. Tahapan Ketiga adalah post-konvensional atau post-kebiasaan
(tingkat 5 dan 6), yang mana seseorang sudah memberikan tafsir sendiri akan nilai
moral dan prinsip yang benar secara universal. Pada level ini biasanya moral yang
berorientasi pada keputusan hati nurani berdasarkan prinsip-prinsip etika pilihan
sendiri, secara rasional, dan komprehensif (Suryawan, 2018).
Dengan kata lain, pada tahap pra-konvensional yang terdiri dari tingkat 1 dan
2. Pada tingkat 1, pemahaman anak tentang ketaatan yang dihukumkan pada benar
dan salah. Anak usia dini akan beranggapan bahwa sesuatu yang mendapatkan
hukuman adalah yang dianggapnya sebagi suatu kesalahan. Anak masih dapat
melihat dunia dari perspektif orang lain (egosentrisme Pieget), dan perilaku
sebagian besar dipandu oleh prinsip kesenangan Freud (yang didominasi). Tahap
kedua, pada tahap ini anak mengakui bahwa ada faktor saling menguntungkan.
Tahap ini beranggapan bahwa anak akan melakukan sesuatu jika apa yang mereka
lakukan adalah suatu keuntungan atau timbal balik terhadap dirinya dengan istilah
lain bahwa “apa untungnya bagi saya”. Pada tahap yang ke dua ini anak itu sedikit
berkurang egosentrisnya, serta mengakui bahwa jika salah satu yang baik untuk
orang lain maka mereka akan mendapatkan keuntungan bagi dirinya (Jumiyati,
2016).
Lebih jelasnya, pada tahap pra-konvensional, tingkat 1, adalah masa orientasi
patuh dan takut hukuman. Anak menganggap perbuatannya baik apabila ia
memperoleh ganjaran atau tidak mendapat hukuman. Sedangkan pada tingkat 2,
orientasi naïf egoistis/hedonism instrumental. Pada tahap ini, seseorang
menghubungkan apa yang baik dengan kepentingan, minat dan kebutuhan dirinya
sendiri serta ia mengetahui dan membiarkan orang lain melakukan hal sama.
Dengan kata lain, anggapan benar jika kedua belah pihak mendapat perlakukan
yang sama, semacam moralitas jual beli. Pada tahap konvensional,tingkat 3 yaitu
orientasi anak yang baik. Pada tahap ini individu telah menyadari nilai dalam suatu
kelompok, ia berusaha bertingkah laku sesuai dengan tuntutan kelompok tersebut.
Pada tingkat 4, moralitas pelestarian otoritas dan aturan sosial. Pada tahap ini
kebenaran diartikan sebagai menjunjung tinggi hukum yang disetujui bersama,
sehingga berbuat sesuai dengan aturan sistem sosial. Pada tahap pasca
konvensional, tingkat 5, yaitu moralitas kontrak sosial dan hak-hak individu. Pada
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 16
Iwan
tahap ini, individu meyakini bahwa harus ada keluwesan dalam keyakinan-
keyakinan moral yang memungkinkan modifikasi dan perubahan standar moral
apabila terbukti akan menguntungkan kelompok sebagai suatu keseluruhan. Pada
tingkat 6, moralitas prinsip-prinsip individu dan conscience. Pada tahap ini
kebenaran didasari oleh kata hati sendiri yang mengandung konsitensi,
pemahaman yang logis dan prinsip universal seperti keadilan, persamaan hak-hak
asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat manusia (Nurhayati, 2006).
Keenam sub-skala dari Moral Reasoning Scale Items tampak saling
berhubungan secara signifikan, kecuali hubungan antara tahap 1 dan tahap 5.
Perlu dicatat bahwa korelasi antara tahap menjadi semakin kecil dengan semakin
besarnya jarak antar tahap. Tahap 1 dan 2 (Pre-Conventional) banyak dipengaruhi
oleh eksternal (reward and punishment), sedangkan tahap 3 hingga 6
(Conventional dan Post-Conventional) lebih banyak dipengaruhi oleh internal diri
individu. Hasil menunjukkan Tahapan Moral terdiri dari dua faktor yang terdiri
dari faktor 1 (tahap 1 dan 2), faktor 2 (tahap 3 -6). Tahapan Conventional dan
Post-Conventional tidak terbukti berkorelasi dengan perilaku moral. Implementasi
hasil tahap 2 mengarah pada kesimpulan bahwa setiap kejahatan mendapatkan
hukuman. Hanya tahap 3 dan 4 mencegah kriminalitas. Individu pada tahap
preconventional cenderung bersikap ‘anti sosial’ sedangkan individu pada tahap
conventional dan post conventional cenderung bersikap ‘pro-sosial’. Tahapan
moral dan evoluasi sosial saling berkaitan. Orang yang berada pada tahap
Preconventional cenderung fokus pada diri sendiri. Sedangkan tahap 3
(conventional) akan focus pada diri pasangan, anak, orangtua, saudara dan teman
(organisasi sosial pemburu dan pengumpul). Tahap 4 fokus kepada pasangan,
anak, orangtua, saudara dan sesama warga negara (organisasi social
negara/bangsa). Tahap 5 fokus kepada pasangan, anak, orangtua dan sesama
warga negara (organisasi social negara/bangsa). Tahapan 6 fokus kepada semua
target kecuali diri sendiri (Mathes, 2019).
Berkenaan dengan hal di atas, menarik untuk dikaji hasil penelitian James
Weber dan Dawn R. Elm pada mahasiswa di sebuah Universitas di Amerika Serikat
(Jurusan Pemasaran, Akuntansi, Keungan, Manajemen, Manajemen Sistem
Informasi dan Manajemen Supply Chain), Secara umum, alasan moral subjek pada
penelitian (generasi milenials) ini berada pada level pre-conventional dan
conventional, di bawah generasi yang sebelumnya. Subjek perempuan ternyata
memiliki nilai Pscore (nilai MRI) yang lebih tinggi di Evelyn Dilemma, sedangkan
yang laki-laki memiliki nilai yang lebih tinggi di Roger Dilemma. Menarik, karena
subjek mendapatkan nilai lebih tinggi saat tokoh utama dalam kasusnya memiliki
jenis kelamin yang sama. Meski IPK tidak berhubungan langsung dengan tingkat
alasan moral (nilai keseluruhan PScore – dari dua dilemma), hasil penelitian
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 16
Iwan
menunjukkan bahwa IPK memiliki hubungan yang signifikan jika dibandingkan
dengan nilai per dilema (permasalahan). Meski hubungan antara pengalaman kerja
dan tingkat alasan moral tidak signifikan, tetapi hasil menunjukkan bahwa nilai
PScore meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja (Weber & Elm,
2018).
Tahapan moral dalam perspektif Al-Qur’an
Setidaknya ada beberapa tingkatan manusia di dalam al-Qur’an, tetapi tidak
dalam artian penulis ingin mengatakan bahwa tingkatan yang disebut pertama
lebih rendah kedudukannya dari tingkatan berikutnya. Namun penyebutan
tingkatan tersebut untuk mempermudah dalam penulisan saja. Di masing-masing
tingkatan, terkandung di dalamnya nilai moral dan karakter adiluhung yang sangat
mengagumkan untuk dikaji. Penulis hanya fokus mengambil istilah yang diawali
dengan kata “ulil atau ulu”, walaupun di al-Qur’an juga ada istilah ahlu, dzu/dzi dan
lain sebagainya.
Dimulai dari tingkatan Ulul Ilmi. Pada surat ali Imran ayat 18-20, dijelaskan di
dalam al-Qur’an berkenaan dengan pernyataan Allah tentang keesaan dan
keadilan- Nya serta agama yang diridhai-Nya (Ashshiddiqi et al., 1971). Kata ulul
ilmi di Al- Qur’an, bisa dilihat pada surat al Imran ayat 18, “Allah menyaksikan
bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia. Para Malaikat dan orang-orang yang
Mempunyai Ilmu (Ulul 'Ilmu) (juga menyatakan yang demikian itu), Yang
menegakkan Keadilan. Tak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana”. Dalam hal ini merupakan keistimewaan yang besar bagi para
ulama dalam memberikan kesaksian tauhid bahwa tiada tuhan selain Allah.
Kesaksian orang-orang yang berilmu berdasarkan dalil-dalil logika yang tidak
terbantahkan, juga pengalaman- pengalaman ruhani mereka dapatkan, serta fitrah
yang melekat pada diri mereka dan yang mereka asah dan asuh setiap saat
(Shihab, 2002).
Dengan demikian, hanya orang yang berilmu, yang akan mengakui kebenaran
bahwa Allah adalah satu-satunya tuhan. Dalam ayat tersebut, Nampak tentang
keutamaan ulama, karena Allah mengkhususkan mereka dalam penyebutan tanpa
menyertakan manusia lainnya (As-Sa’di, 2012). Pengakuan terhadap Allah sebagai
satu-satunya Tuhan mengandung kesempurnaan kepercayaan kepada-Nya dari
dua sisi. Pertama, Rububiyah yakni sifat Tuhan yang menciptakan alam,
memelihara dan mendidiknya. Kedua, Uluhiyah yang berarti hanya zat yang
bernama Allah saja sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib disembah dan tempat
meminta pertolongan. Syahadat adalah intisari dari Arkanul Iman (rukun-rukun
iman). Mempercayai syahadat adalah membenarkan adanya Allah dan Muhammad
yang akhirnya membuat kita percaya dengan Al-Qur’an. Dalam kitab suci ini
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 16
Iwan
dijelaskan mengenai
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 16
Iwan
iman kepada malaikat, rasul, hari akhir serta qada dan qadar. Akhirnya, melaui
syahadat, kita menyempurnakan rukun-rukun iman tersebut (Razak, 1982).
Syahadat gerakan hati sebagai bentuk penyaksian akan ke-Maha Esa-an Allah
swt, merasa selalu dilihat dan diawasi Allah swt (khusyu), tidak hanya pada saat
melaksanakan shalat, namun di luar kegiatan shalat pun, orang yang telah
melakukan kesaksian dengan benar kepada Allah akan selalu merasa dalam
kondisi shalat dari setiap detik kehidupannya. Seseorang yang seluruh hidupnya
dalam kondisi “salat” akan membuat dirinya malu untuk bermaksiat dan berbuat
durhaka kepada Allah swt sehingga dirinya terhindar dari perbuatan yang keji dan
munkar. Seseorang yang seluruh hidupnya dalam kondisi “salat” akan terhindar
dari berbuat riya serta ingin disanjung dan dipuja. Dia sadar berbuat riya pertanda
sifat kemunafikan dan akan membuat seluruh amalan menjadi tidak berharga dan
tidak bernilai. (Mulyanti, 2019).
Tentu syahadat seseorang itu, tergantung seberapa besar ilmu Allah yang
diberikan kepadanya (bukan gelar akademiknya). Seseorang yang benar-benar
memiliki ilmu, maka ia akan terselamatkan dari kelakuan yang tidak baik. Kalau
ada orang berilmu tetapi tidak jujur, tidak pemaaf, serakah, mengambil yang bukan
haknya maka hakikatnya ia tidak pandai (Yusuf, 2014).
Tingkatan yang lain di al-Qur’an, juga ada golongan Ulin Nuha. Dalam surat
Thaha ayat ke 53-56, Al-Qur’an berkisah tentang dialog Nabi Musa bersama Nabi
Harusn dengan Fir’aun tentang kebesaran kekuasaan Allah. Namun yang perlu jadi
penekanan pada tulisan ini, tentang kata ulin nuha di akhir ayat ke 54. Secara
termonologi, Ulin Nuha adalah orang yang mempunyai penahanan diri. Firman
Allah pada ayat tersebut. “Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu.
Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi
orang-orang yang berakal”. Kata an-nuha adalah bentuk jamak dari kata nuhyah
yang bermakna akal. Kata tersebut seakar dengan kata naha yang berarti
melarang. Akal dinamai nuhyah karena dia berfungsi melarang dan menghalangi
penggunannya terjerumus dalam kesalahan/kejahatan (Shihab, 2002). Atau
dengan kata lain, maksud ayat ini adalah bagi orang-orang yang memiliki akal-akal
yang matang, dan pikiran-pikiran yang lurus, terdapat tanda-tanda keutamaan,
limpahan kebaikan, rahmat, luasnya kedermawananNya dan kesempurnaan
perhatianNya (As-Sa’di, 2012). Seseorang yang melakukan praktek agama dengan
baik, yang tujuannya adalah semata-mata hanya untuk menyembah Allah, yang
mana hal itu bisa menjadikan hubungan dengan Tuhannya baik dan kokoh, serta
dapat meluruskan tingkah lakunya, maka dengan hal ini seseorang dapat
mengontrol perilakunya atau dengan kata lain meningkatkan kontrol dirinya. Dan
apabila
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 16
Iwan
religiusitas dan kontrol diri yang baik akan dapat membuat seseorang terhindar
dari tingkah laku negatif yang tidak sesuai dengan norma sosial (Khairunnisa,
2013).
Ada juga tingkatan yang disebut sebagai Ulul Abshar. Di dalam al-Qur’an
istilah ulul abshar paling tidak disebut sebanyak 4 kali yaitu pada QS. 3:13, 24:44,
38:45, 59:2. Dari berbagai ayat yang ada, secara tematik istilah tersebut
mempunya beragam makna juga pengertian, yaitu: orang yang mempunyai hati
yang lapang, mampu berpikir secara mendalam, juga memiliki pandangan yang
luas dalam mengejawantahkan ajaran-ajaran agama Islam. Para nabi yang sering
dihubungkan dengan sebutan ini adalah Ibrahim, Ishaq, dan Ya’kub. Pada
wilyah pemamahan inilah, Ulil Abshar dapat diartikan sebagai dimensi spritualitas
manusia (Nur, 2018). Sebagai contoh, firman Allah tentang Ulil Absar yang
terdapat pada surat An-
Nur ayat 44, “Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai
penglihatan”. Kata al-abshar pada ayat ini adalah bentuk jamak dari kata bashirah
yang berarti pandangan hati. Ayat ini menegaskan bahwa: Allah mempergantikan
secara terus menerus malam yang penuh kegelapan dan siang yang disirami
cahaya, dan dengan pergantian itu lahirlah panas dan dingin. Dipergantikan oleh-
Nya panjang dan pendek keduanya, sebagaimana dipergantikannya pula malam
dan siang untuk menjadi saat turunnya siksa dan nikmat, dan dipergantikan-Nya
pula agar yang berdosa di waktu malam dapat bertaubat di siang hari dan
demikian pula yang memperoleh nikmat di siang hari dan lupa bersyukur, dan
dapat mensyukuri- Nya di waktu malam. Sesungguhnya pada yang demikian itu,
terdapat pelajaran yang besar dan bermanfaat untuk dijadikan bukti kekuasaan
dan anugerah Allah bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan dengan mata
hati dan pikiran (Shihab, 2002).
Beda halnya makna ulil abshar pada surat Ali 'Imran ayat 13, “Sesungguhnya
telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur).
Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan
mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka.
Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang
mempunyai mata hati”. Di dalam tafsir al-Mishbah (Shihab, 2002), istilah uli al-
abshar adalah orang- orang yang mempunyai pandangan mata, bukan mata hati,
karena yang mereka lihat adalah suatu kenyataan di lapangan. Selain itu, menurut
ulama tafsir yang lain, bahwa ayat ini mengandung pelajaran pelajaran bagi orang-
orang yang memiliki mata hati, bahwa sekiranya ini bukan kebenaran yang apabila
menghadapi kebatilan pasti akan melenyapkan dan merendahkannya, maka
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 17
Iwan
pastilah, jika diukur dari sebab-sebab yang konkret, kenyataannya akan terbalik
(As-Sa’di, 2012).
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 17
Iwan
Selanjutnya ada tingkatan Ulul Albab, ada sebanyak 16 kali disebut di dalam
Al Qur'an. Istilah ini digunakan oleh al-Qur’an untuk menyebut sejumlah manusia
terpilih yang berkonotasi intelektual. Istilah tersebut paling tidak tercantum
sebanyak enam belas kali di al-Qur’an, yaitu: QS. 2: 179, 2:197, 2: 269, 3:7, 3: 190,
5:
100, 12:111, 13: 19, 14:52, 38: 29, 38: 43, 39: 9, 39:18, 39:21, 40: 54, 65:10. Pakar
tafsir dari Indonesia yakni M. Quraish Shihab (1993) memaparkan bahwa kata
Albab adalah suatu bentuk kata jamak dari kata lubb yang artinya adalah
saripati sesuatu. Tanaman kacang sebagai misal, isinya tertutup oleh adanya
kulit, karenanya isi dari kacang tersebutlah yang kemudian diberi nama lubb.
Ulul Albab merupakan manusia-manusia yang mempunyai rasio atau ‘aqal yang
murni, tak tertutup dan terselubung oleh kulit atau kabut ide yang bisa
menjadikan berpikir menjadi rancu, hal ini sebagaimana bisa ditemukan pada QS.
Ali Imran: 190-191. Quraish Shihab juga memaparkan bahwa orang yang berfikir
secara murni dan berdzikir atau secara mendalam merenung tentang fenomena
alam semesta, akan bisa membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah dengan bukti
yang sangat nyata. Ada juga yang memberikan arti lubb tersebut dengan “otak”
atau “pikiran”. Apabila merujuk pada makna ini, maka makna kata tersebut lebih
berkonotasi intelektual, yaitu orang yang mempunyai dan mempergunakan
kemampuan intelek (daya pikirnya) untuk bekerja atau menjalankan aktifitasnya
(Nur, 2018).
Apabila memperhatikan berbagai ayat al-Qur’an yang terkait dengan ulul
albab kiranya akan didapatkan beberapa ciri yang merupakan karakteristik
manusia yang memiliki gelar ulul albab yakni; Pertama, berupaya secara sungguh-
sungguh dalam mendalami ilmu pengetahuan. Mengamati serta menyelidikki
seluruh rahasia wahyu (baik al-Qur’an juga fenomena-fenomena semesta),
mengungkap berbagai hukum yang ada padanya, selanjutnya mengaplikasikannya
pada masyarakat guna kemaslahatan bersama (QS, Ali Imran: 190). Kedua, untuk
selalu teguh berpegang pada keadilan serta kebaikan. Ia dapat memilah yang baik
dari yang jahat. Selalu mempertahankan kebaikan dan kebenaran walaupun harus
berjuang sendirian (QS, Al- Maidah:100). Ketiga, kritis serta teliti saat
mendapatkan informasi, dalil, ataupun teori yang didapatkan dari sesorang.
Keempat, bisa mendapat ibrah atau pelajaran dan pelajaran dari cerita serta
sejarah umat di masa lalu (Nur, 2018). Seseorang yang sudah masuk pada fase ulul
albab, maka ia akan memiliki sikap ilmiah, atau dengan kata lain dia akan memiliki
kemampuan untuk mendayagunakan segala potensi intelektualnya serta potensi
dzikirnya untuk memahami fenomena ciptaan Tuhan dan dapat mendayagunakan
untuk kepentingan kemanusiaan (Tobroni, 2008).
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 17
Iwan
Ada juga tingkatan ulul Amri. Kata Ulil Amri merupakan kata yang akrab
ditelinga kita. Seringkali dalam perbincangan sehari-hari kita menggunakan istilah
ini. Istilah Ulil Amri sebenarnya dirujuk dari Al-Quran Surat An-Nisa: 59 : “Hai
orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di
antara kamu…“. Uli al-Amr ada yang memaknai sebagai para
penguasa/pemerintah, ada juga pendapat meraka adalah para ulama, ada juga
yang mengatakan bahwa meraka adalah yang mewakili masyarakat dalam
berbagai kelompok atau profesinya (Shihab, 2002).
Ada juga istilah Ulil Aidi yang terdapat pada surat Sad ayat 45, “Dan ingatlah
hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub - (mereka adalah) Ulil Aidi. Kata al-
aydi adalah bentuk jamak dari kata al-yad yang pada mulanya berarti tangan.
Karena tangan digunakan untuk melakukan hal-hal yang berat dan memberi
sesuatu, maka kata tersebut dipahami juga dalam arti kuat/teguh juga pemberian.
Yang dimaksud disini adalah keteguhan beragama. Ayat ini menyatakan bahwa
“Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya’qub yang mempunyai
keteguhan dalam beragama juga pengabdian serta pandangan mata hati yang
jernih (Shihab, 2002).
Dan yang terakhir, ada juga tingkatan Ulul Azmi. Adapun ayat yang berkaitan
dengan Ulul Azmi terdapat dalam surat Al Ahqaf ayat 35, “Maka bersabarlah kamu
seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-rasul telah
bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. pada hari
mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak
tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (inilah) suatu pelajaran yang
cukup, Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik”. Ulul azm yakni mereka
yang memiliki keteguhan hati dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan serta
tekad yang membaja untuk mewujudkan kebaikan. Ulul Azmi menurut ar-Razi
adalah mereka yang tidak lagi dipengaruhi oleh syahwatnya sehingga secara rela
menyerahkan diri kepada Allah, karena nafsunya telah tunduk kepada kesucian
hatinya. Merujuk kepada al-Qur’an. Maka paling tidak ada dua hal pokok yang
merupakan syarat mutlah ulul azmi yaitu kesabaran/ketabahan serta kesediaan
memberi maaf/lapang dada, dan tekad yang kuat untuk melaksanakan tuntunan
Allah (Shihab, 2002).
Kalau boleh dikategorikan, ulil ilmi mereka yang berstatus seorang muslim
yang berilmu (intelek Muslim), selanjutnya Ulin Nuha adalah orang yang memiliki
control diri, Ulul Abshar gelar bagi orang yang memiliki cara pandang visioner, ulul
albab adalah gelar bagi orang yang menggunakan akal dan hatinya selalu
terkoneksi dengan Tuhan dalam menggerakan aktivitasnya, ulil amri adalah
golongan ulama yang mampu menjalankan kekuasaan dengan ilmunya, dan kedua
yang terakhir ulul
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 17
Iwan
aidi dan Ulul azmi, adalah gelar bagi para Nabi yang memiliki kekuatan dan
kesabaran yang luar biasa (Khaerani, 2014).
D. Simpulan
Setelah dilakukan kajian, disimpulkan bahwa menurut Thomas Lickona, anak didik
itu memiliki 5 tingkatan level. Diawali dari level 0 sampai level 4. Seseorang yang
berada di level 0, ia memiliki karakter suka berbicara dengan keras, seringkali
ceroboh atau bodoh, pekerjaan yang dicapai jumlahnya minimal atau diselesaikan
dengan ceroboh, tindakannya mencampuri kemampuan anak lain untuk
berkonsentrasi, menyalahkan materi. Sedangkan anak yang berada di level 1,
karakteristiknya sangat sedikit atau tidak ada pekerjaan yang terlihat sama sekali
di akhir waktu yang diberikan, berputar-putar, bingung. Adapun anak level 2,
karakteristiknya, pekerjaan diselesaikan dengan pengingat atau pertanyaan yang
diberikan oleh orang dewasa yang hadir, tidak banyak pekerjaan yang terlihat,
melakukan pembicaraan yang tidak baik, mungkin ceroboh, kadang-kadang
bekerja dan kadang-kadang tidak bekerja. Untuk level 3, karakteristiknya, pekerja
keras, melakukan apa yang diharapkan, menghormati hak-hak dan pekerjaan
orang lain, menyelesaikan pekerjaan dengan hati-hati, menggunakan waktu
dengan baik, menggunakan materi dengan hati-hati dan bertanggung jawab,
melakukan pembicaraan dengan baik, bertekun. Sedangkan kalau seseorang
masuk pada level 4, ia memiliki rasa hormat, penuh rasa tanggung jawab serta
suka membantu orang lain, memiliki kreativitas melebihi yang diharapkan.
Sedangkan tahapan perkembangan menurut Moral Kohlberg ada enam tahapan.
Tahapan Pertama adalah pra-konvensional. Pada tingkat pra-konvensional
(tingkat 1 dan 2), orientasi pada ketaatan terhadap aturan karena ukuran benar
dan salah, mendapat reward atau punishman. Sedangkan Tahapan Kedua adalah
konvensional atau kebiasaan (tingkat 3 dan 4), pada level ini sudah hadir motivasi
dalam dirinya untuk tetap eksis dan menjaga citra stereotipe dalam kehidupan
masyarakatnya. Tahapan Ketiga adalah post-konvensional atau post-kebiasaan
(tingkat 5 dan 6), yang mana seseorang sudah memberikan tafsir sendiri akan nilai
moral dan prinsip yang benar secara universal. Adapun tahapan moral dalam al-
Qur’an, ada yang digolongkan pada ulul ilmi, ulin nuha, ulil abshar, ulil albab, ulil
amri, ulil aidi dan ulil Azmi.
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 17
Iwan
Daftar Rujukan
As-Sa’di, A. bin N. (2012). Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan.
Jakarta: Pustaka Sahifa.
Ashshiddiqi, T. M. H., Ghani, B. A., Jahya, M., Omar, M. T. J., Ali, A. M., Muchtar, K., …
Madjiji, B. (1971). Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an.
Barnawi, & Arifin., M. (2012). Strategi & kebijakan pembelajaran pendidikan
karakter. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Dalmeri. (2014). Pendidikan untuk pengembangan karakter (telaah terhadap
gagasan Thomas Lickona dalam Educating for Character). Al-Ulum, 14(1),
269– 288.
Husni, R., & Norman, E. (2015). Deliberalisasi pendidikan karakter respect and
responsibility Thomas Lickona. Jurnal Tawazun, 8(2), 257–274.
Ilahi, M. T. (2012). Revitalisasi pendidikan berbasis moral. Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media.
Ilahi, M. T. (2014). Gagalnya pendidikan karakter: analisis dan solusi pengendalian
karakter emas anak didik. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Jumiyati, S. (2016). Perbandingan pendidikan moral anak usia dini menurut Nashih
Ulwan dan Kohlberg (tinjauan psikologis dan metodologis). Prosiding
Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 3rd. Yogyakarta: Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY).
Khaerani, I. F. R. (2014). Pemimpin berkarakter ulul albab. Jurnal Kepemimpinan
Pendidikan Islam Multikultural, 1(1).
Khairunnisa, A. (2013). Hubungan religiusitas dan kontrol diri dengan perilaku
seksual pranikah remaja di MAN 1 Samarinda. eJournal Psikologi, 1(2), 220–
229.
Kuswandi, I. (2019). Akhlaq Education Conception of ibn Miskawaih and al-Ghazali
and Its Relevancy to The Philosophy of Muhammadiyah Pesantren. Proceeding
of International Conference on Islamic Education: Challenges in Technology and
Literacy, 186–197. Retrieved from http://conferences.uin-
malang.ac.id/index.php/icied/article/view/1084
Lickona, T. (1991). Educating for character: how our school can teach respect and
responsibility. New York: Bantam Books.
Lickona, T. (1996). Eleven Principles of Effective Character Education. Journal of
Moral Education, 25(1), 93–100.
https://doi.org/10.1080/0305724960250110
Lickona, T. (2004). Character Matters. New York: Somon & Schuster.
Lubis, M. (2018). Konsep pendidikan karakater dalam perspektif Islam dan Barat
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 17
Iwan
(studi komparatif pemikiran Nashih Ulwan dan Thomas Lickona). Jurnal Al-
Fikru, XII(2), 55–64.
Malik, H. (2016). Membangun generasi berperadaban. Yogyakarta: INDeS Publishing.
Manurung, R. T. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran
berkarakter dan humanistik. Jurnal Sosioteknologi, 11(27), 227–239.
Mathes, E. W. (2019). An evolutionary perspective on Kohlberg’s theory of moral
development. Current Psychology.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12144-019-00348-0
Mulyanti, S. (2019). Menanamkan Tiga Simbolisasi Nilai Masjid pada Anak-Anak
Yatim dalam Program Santunan. DIMAS, 19(1).
Nida, F. L. K. (2013). Intervensi Teori Perkembangan moral Lawrence Kohlberg
dalam dinamika pendidikan karakter. Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan
Islam, 8(2).
Nur, M. (2018). Paradigma Keilmuan UIN Raden Intan Lampung. Analisis: Jurnal
Studi Keislaman, 18(1).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v18i1.3378
Nurhayati, S. R. (2006). Telaah kritis terhadap teori perkembangan moral
Lawrence Kohlberg. Paradigma, 1(2).
Razak, N. (1982). Dienul Islam. Bandung: PT Alma’arif.
Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah. In Tafsir al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati.
Sudrajat, A. (2011). Mengapa pendidikan karakter? Jurnal Pendidikan Karakter,
1(1),
47–58.
Suryawan, M. H. (2018). Pendidikan politik: konsep nilai etika universal perspektif
kohlberg dan Islam. LoroNG, 7(1).
Thobroni, & Dkk. (2018). Memperbincangkan pemikiran pendidikan Islam dari
idealisme substantif hingga konsep aktual. Jakarta: Prenada Media Grup.
Tobroni. (2008). Pendidikan Islam paradigma teologis, filosofis dan spritualitas.
Malang: UMM Press.
Weber, J., & Elm, D. R. (2018). Exploring and Comparing Cognitive Moral Reasoning
of Millennials and Across Multiple Generations. Bussiness and Society Review,
123(3), 415–458. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/basr.12151
Yusuf, M. (2014). Pendidikan karakter berbasis Qurani dan kearifan lokal. Karsa,
22(1).
Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1, 17
You might also like
- Who Are The NephilimDocument16 pagesWho Are The Nephilimo100% (2)
- THW Legalize AbortionDocument3 pagesTHW Legalize AbortionRaymond ArifiantoNo ratings yet
- Cleric Spell ListDocument6 pagesCleric Spell ListTheodore Arnold-MooreNo ratings yet
- Write These Laws On Your ChildrenDocument241 pagesWrite These Laws On Your ChildrenBasma Al-KershNo ratings yet
- BrahmacharyaDocument151 pagesBrahmacharyaAmritpal Bhagat100% (8)
- The Role of Christian Religious Studies in Character Formation of Secondary School StudentsDocument69 pagesThe Role of Christian Religious Studies in Character Formation of Secondary School StudentsIchipi-ifukor Patrick Chukuyenum100% (10)
- London by William BlakeDocument52 pagesLondon by William Blakeanon_384573512No ratings yet
- Islamic Calendar-Basic FactsDocument3 pagesIslamic Calendar-Basic FactsmusarhadNo ratings yet
- Michel Chodkiewicz Two Essays On Ibn Al-ArabiDocument21 pagesMichel Chodkiewicz Two Essays On Ibn Al-ArabinidavanNo ratings yet
- Charlesworth, S. - Phenomenology of Working Class PDFDocument325 pagesCharlesworth, S. - Phenomenology of Working Class PDFVasiliki Petsa100% (1)
- Best Book On CSS Syllabus Suggested by Seniors CSP - SDocument6 pagesBest Book On CSS Syllabus Suggested by Seniors CSP - SSohaib AkramNo ratings yet
- Psikologi Pendidikan Islam GhazaliDocument20 pagesPsikologi Pendidikan Islam Ghazalimohammad affanNo ratings yet
- 6576 21258 1 PBDocument23 pages6576 21258 1 PBluckyadi377No ratings yet
- 188-Article Text-515-1-10-20200221Document21 pages188-Article Text-515-1-10-20200221Soli Lokui100% (1)
- Keywords:: Volume 1, Nomor 1, Juni 2016 PDocument26 pagesKeywords:: Volume 1, Nomor 1, Juni 2016 Prahma 12No ratings yet
- Studi Pemkiran IslamDocument23 pagesStudi Pemkiran IslamjuhasdiNo ratings yet
- Implications of Moral Education Lawrence Kohlberg and KH Ahmad Dahlan On The Religious Behavior of StudentsDocument24 pagesImplications of Moral Education Lawrence Kohlberg and KH Ahmad Dahlan On The Religious Behavior of StudentsUPhy AxdomNo ratings yet
- Christian Religious Education and The Development of Moral Virtues - A Neo-Thomistic ApproachDocument13 pagesChristian Religious Education and The Development of Moral Virtues - A Neo-Thomistic ApproachClement Ma. MembelaNo ratings yet
- Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah Terhadap Gagasan Thomas Lickona Dalam Educating For Character)Document21 pagesPendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah Terhadap Gagasan Thomas Lickona Dalam Educating For Character)sutajiNo ratings yet
- M Ridhwan,+3.+muvid+131-158Document28 pagesM Ridhwan,+3.+muvid+131-158Honny Pigai ChannelNo ratings yet
- Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah Terhadap Gagasan Thomas Lickona Dalam Educating For Character)Document21 pagesPendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah Terhadap Gagasan Thomas Lickona Dalam Educating For Character)Rahmita WindyNo ratings yet
- 2785-Article Text-8493-1-10-20230630Document22 pages2785-Article Text-8493-1-10-20230630rafimochammad18No ratings yet
- Jurnal MSI Metodologi Studi IslamDocument13 pagesJurnal MSI Metodologi Studi Islamrivalmaulana4681No ratings yet
- Q.1 Explain by Giving Examples The Levels of Cognitive Domain of Educational Objectives. What Is Its Influence On Our Educational System? Answer: Islamic Foundation of EducationDocument28 pagesQ.1 Explain by Giving Examples The Levels of Cognitive Domain of Educational Objectives. What Is Its Influence On Our Educational System? Answer: Islamic Foundation of EducationWareeha vLogsNo ratings yet
- Karya Ilmiah No. 11Document20 pagesKarya Ilmiah No. 11Khoirunnisa AnnajahNo ratings yet
- Tugas Cari BukuDocument6 pagesTugas Cari Bukuapriyantichicha210No ratings yet
- Strategi Membentuk Karakter SpiritualitasDocument22 pagesStrategi Membentuk Karakter SpiritualitasNely FitrianaNo ratings yet
- Filsafat Pendidikan IslamDocument34 pagesFilsafat Pendidikan IslamnisrinaNo ratings yet
- Scientific Tradition in Indonesia and India - M.mujabDocument18 pagesScientific Tradition in Indonesia and India - M.mujabMujab MuhammadNo ratings yet
- Chapter 01Document5 pagesChapter 01Pakiza's SadiqNo ratings yet
- Pemurnian Sistem Pendidikan Islam Berdasarkan Metod Risalah An-Nur: Analisis Kajian Di Negara MalaysiaDocument19 pagesPemurnian Sistem Pendidikan Islam Berdasarkan Metod Risalah An-Nur: Analisis Kajian Di Negara MalaysiaSyahida AmirrudinNo ratings yet
- Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol. 07/no.1, April 2018Document34 pagesJurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol. 07/no.1, April 2018LiaNo ratings yet
- Tawhid in Al-Islam PesantrenDocument7 pagesTawhid in Al-Islam PesantrenEmzack Fahmi ZulkifliNo ratings yet
- Pendidikan Islam Di Keluarga Dalam Perspektif Demokrasi (Studi Pemikiran Hasan Langgulung Dan Abdurrahman An Nahlawi)Document54 pagesPendidikan Islam Di Keluarga Dalam Perspektif Demokrasi (Studi Pemikiran Hasan Langgulung Dan Abdurrahman An Nahlawi)Sulastri OliiNo ratings yet
- Islam Dalam Perspektif Pendidikan: STPI Bina Insan Mulia YogyakartaDocument23 pagesIslam Dalam Perspektif Pendidikan: STPI Bina Insan Mulia YogyakartaErfan ArizkiNo ratings yet
- Pandangan Abdullah Nashih Ulwan TentangDocument16 pagesPandangan Abdullah Nashih Ulwan Tentangfajri ardianNo ratings yet
- Pendidikan Untuk Membentuk KarakterDocument25 pagesPendidikan Untuk Membentuk KarakterMuhammad Isa AnshoryNo ratings yet
- Institusi IIQ PDFDocument22 pagesInstitusi IIQ PDFSri WidyastriNo ratings yet
- Jurnal Miftah AnsoriDocument13 pagesJurnal Miftah AnsoriMUFIN MUBAROKNo ratings yet
- Radikalisme: Pendekatan Analisa Konseling Rational-EmotifDocument11 pagesRadikalisme: Pendekatan Analisa Konseling Rational-EmotifMyR4No ratings yet
- 2581-Article Text-4284-1-10-20211004Document18 pages2581-Article Text-4284-1-10-20211004Oci AnggrainiNo ratings yet
- Masbur: Jurnal Ilmiah Edukasi Vol 1, Nomor 1, Juni 2015Document19 pagesMasbur: Jurnal Ilmiah Edukasi Vol 1, Nomor 1, Juni 2015Yehezkiel Rizky PratamaNo ratings yet
- Rujukan Bab IVDocument22 pagesRujukan Bab IVLiaa AaaNo ratings yet
- Jurnal Evaluasi Pembelajaran Dan Pendidikan 1..2Document15 pagesJurnal Evaluasi Pembelajaran Dan Pendidikan 1..2FaisalNo ratings yet
- 791 2255 1 SMDocument10 pages791 2255 1 SMaulapratama999No ratings yet
- Lonergan, Social Transformation, and Sustainable Human DevelopmentFrom EverandLonergan, Social Transformation, and Sustainable Human DevelopmentNo ratings yet
- A Comparative Study of Moral Development of Students From Private Schools N Deeni MadrasahDocument11 pagesA Comparative Study of Moral Development of Students From Private Schools N Deeni Madrasahcity campusNo ratings yet
- New Face of Religious Affair Minister and The Epistemology of Qur'Anic Ethics A Synchronic-Diachronic Reading On QS. Al-Hujurāt (49) : 11-13Document17 pagesNew Face of Religious Affair Minister and The Epistemology of Qur'Anic Ethics A Synchronic-Diachronic Reading On QS. Al-Hujurāt (49) : 11-13Egi Tanadi TaufikNo ratings yet
- 9050 32096 1 PBDocument25 pages9050 32096 1 PBHIDAYAT 78No ratings yet
- Dakwah Dalam Bingkai Politik: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Papua BaratDocument34 pagesDakwah Dalam Bingkai Politik: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Papua Baratmuna syahidahNo ratings yet
- The Moral AgentDocument3 pagesThe Moral AgentMaden betoNo ratings yet
- Internet and Religiousness The Examination of Indonesian Muslim Youth Population's Use of The InternetDocument16 pagesInternet and Religiousness The Examination of Indonesian Muslim Youth Population's Use of The InternetRestu FauziNo ratings yet
- An Assessment of The Concept, Content and Methodologies For Teaching Islamic Studies in Ogun State, Nigeria Between (1995 - 2013)Document8 pagesAn Assessment of The Concept, Content and Methodologies For Teaching Islamic Studies in Ogun State, Nigeria Between (1995 - 2013)Ts. Dr. Zulkifli Mohd SidiNo ratings yet
- Studi Islam Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan: Agus AditoniDocument12 pagesStudi Islam Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan: Agus AditoniNina AlfianaNo ratings yet
- Teologi IslamDocument17 pagesTeologi Islamnurul latifahNo ratings yet
- Abstract Keyword PendahuluanDocument26 pagesAbstract Keyword PendahuluanKELVIN ytNo ratings yet
- Q: What Is The Islamic Concept, Meaning and Nature of Education ? AnsDocument8 pagesQ: What Is The Islamic Concept, Meaning and Nature of Education ? AnsNayab Amjad Nayab Amjad100% (1)
- Keywods Anomalies, Islamic Edcatations, Moral Strengthened, DihonestDocument17 pagesKeywods Anomalies, Islamic Edcatations, Moral Strengthened, DihonestMUSTAINNo ratings yet
- Jurnal Demokrasi Pendidikan Pak PaizaluddinDocument12 pagesJurnal Demokrasi Pendidikan Pak PaizaluddinBimas Buqien Ahmed QorieNo ratings yet
- Artikel Kel. 1 - Konsep Dasar Filsafat Pendidikan Islam-DikonversiDocument14 pagesArtikel Kel. 1 - Konsep Dasar Filsafat Pendidikan Islam-Dikonversihima malayaNo ratings yet
- Siddiqui - Ethics in Islam FinalDocument8 pagesSiddiqui - Ethics in Islam FinalmezraitmenberNo ratings yet
- Syamsul HidayatDocument52 pagesSyamsul HidayatDandi RiyanNo ratings yet
- Deradikalisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) Model Keberagamaan Inklusif Dikalangan Siswa SMADocument17 pagesDeradikalisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) Model Keberagamaan Inklusif Dikalangan Siswa SMAASEP ABDUL WACHID HASYINo ratings yet
- Analisis Bahan Ajar Kb1Document17 pagesAnalisis Bahan Ajar Kb1ASEP ABDUL WACHID HASYINo ratings yet
- CH - 8 Philosophy Relationship With Education, Science, and ReligionDocument22 pagesCH - 8 Philosophy Relationship With Education, Science, and ReligionMuhammad Jamil KaneraaNo ratings yet
- Mckenzie 2016Document28 pagesMckenzie 2016Camilo Andrés Salas SandovalNo ratings yet
- Goals and Methods On Ethical Training From Allamah Jafari's PerspectiveDocument7 pagesGoals and Methods On Ethical Training From Allamah Jafari's PerspectiveinventionjournalsNo ratings yet
- Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas Y de NegociosDocument6 pagesEscuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas Y de NegociosLina MarcelaNo ratings yet
- (The Role of Morality in Life: Islamic Discourse Review) Peranan Akhlak Dalam Kehidupan: Tinjauan Wacana Akhlak IslamDocument17 pages(The Role of Morality in Life: Islamic Discourse Review) Peranan Akhlak Dalam Kehidupan: Tinjauan Wacana Akhlak Islamputri525No ratings yet
- 789-Article Text-2763-1-10-20171129Document18 pages789-Article Text-2763-1-10-20171129ifa muallifaNo ratings yet
- RL 207 2019 02 0Document56 pagesRL 207 2019 02 0Rahul SureshNo ratings yet
- FRANCIS SUNIL LOBO CRIMINAL Case For Crimes Against The Catholic Church and HSIDocument1 pageFRANCIS SUNIL LOBO CRIMINAL Case For Crimes Against The Catholic Church and HSIDominic Dixon BangaloreNo ratings yet
- My Antonia Research Paper TopicsDocument5 pagesMy Antonia Research Paper Topicstigvxstlg100% (1)
- Readings in Philippine History: Isabel Annesley AbaoDocument6 pagesReadings in Philippine History: Isabel Annesley AbaoRykeil BorromeoNo ratings yet
- Baccalaureate MassDocument11 pagesBaccalaureate MassDonna Flor NabuaNo ratings yet
- Wenstrom - Inspiration PDFDocument53 pagesWenstrom - Inspiration PDFAnonymous kFOvr86No ratings yet
- Remembering James Hillman: An Enterview With Thomas Moore: Rob HendersonDocument10 pagesRemembering James Hillman: An Enterview With Thomas Moore: Rob HendersonJorge Ramírez VelazcoNo ratings yet
- Austin CSR December EnewsDocument8 pagesAustin CSR December EnewswandamannNo ratings yet
- First Performance Task in ChristologyDocument3 pagesFirst Performance Task in ChristologyJanice LelisNo ratings yet
- AstrologyDocument215 pagesAstrologyPrasadNo ratings yet
- 2 Kings 6 1-7Document5 pages2 Kings 6 1-7Sugar CanibanNo ratings yet
- Data For TMEDocument28 pagesData For TMELOAN DESKNo ratings yet
- Sola Scriptura: by Scripture AloneDocument8 pagesSola Scriptura: by Scripture AloneLalpu HangsingNo ratings yet
- The Farmer and His Lazy SonsDocument1 pageThe Farmer and His Lazy SonsTipuNo ratings yet
- 30 Bible Verses About ChildrenDocument15 pages30 Bible Verses About ChildrenStephenJosephEpiliAtienzaNo ratings yet
- From An Islamic Perspective Health Is Viewed As One of The Greatest Blessings That God Has Bestowed On MankindDocument15 pagesFrom An Islamic Perspective Health Is Viewed As One of The Greatest Blessings That God Has Bestowed On MankindSuhana SelamatNo ratings yet
- 1 Circular For The 2021 NCF ConferenceDocument2 pages1 Circular For The 2021 NCF ConferenceRuel LumajenNo ratings yet
- Sports and Games in Ancient IndiaDocument11 pagesSports and Games in Ancient IndiaHimanshu RanjanNo ratings yet
- My Belief - Joe Isaac GauthierDocument193 pagesMy Belief - Joe Isaac GauthierLorenz Adam DamaraNo ratings yet