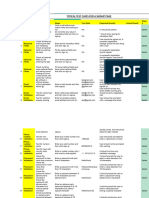Professional Documents
Culture Documents
Model Sistem Rujukan Gelandangan Dan Pengemis Di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Model Sistem Rujukan Gelandangan Dan Pengemis Di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Uploaded by
romeo wayanOriginal Description:
Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Model Sistem Rujukan Gelandangan Dan Pengemis Di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Model Sistem Rujukan Gelandangan Dan Pengemis Di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Uploaded by
romeo wayanCopyright:
Available Formats
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Asep Jahidin dan Sarif
Abstract
This article disucesses referral system model of beggars and homeless treatment as part of social
problems solution in Yogyakarta. The government of Yogyakarta has published the Special Regulation of
Yogyakarta, among others Regulation No. 16 of 1956, (16/1956) and Provincial Regulation No. 1 year
2014 on Handling Homeless and Beggars. The goal is doing outreach to prevent homeless and beggars
in cooperation with the police, Provincial Satpol PP and Dinsosnakertrans in Yogyakarta province
are Kota, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, and Kulonprogo utilizing Social Service Assessment Camp
for identification and assessment. Camp Assessment is a temporary shelter for homeless and beggars
(Gepeng). The finding shows that in the Assesment Camp, these groups have access to social services
in the form of basic needs, medical health and coaching/guidance. In addition, social services guidance
or coaching provided by the Assesment Camp for the sprawl is in the form of guidance of motivation,
sports, religion, art, Mental Social and Citizenship. Upon obtaining social services, clients are involved
in Case Conference meetings to determine whether a client can be repatriated or referred to social
welfare institutions in accordance with the client’s source system. The research utilises a qualitative
approach by field research and literature review. This article suggests for instensification of supervision
and monitoring on the program to ensure sustainability aspect.
Keywords: assessment, homeless, beggars, social services assessment camp, referral system model.
Pendahuluan
Permasalahan sosial di Indonesia secara kualitas dan kuantitas masih banyak yang belum
tertangani dengan baik, salah satu diantaranya adalah problematika gelandangan dan pengemis yang
tidak kunjung selesai. Gelandangan dan pengemis hadir di kota-kota besardan telah sekian lama
menjadi bagian dari permasalahan sosial.
Pemerintah daerah turut bertanggungjawab menangani masalah gelandangan dan pengemis
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial. Selain itu, dalam Konstitusi Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan “kewajiban negara memelihara fakir miskin dan
anak terlantar.”1 Dalam penanganan gelandangan dan pengemis ini Daerah Istimewa Yogyakarta
memiliki peraturan daerah yang diterbitkan khusus untuk merespon permasalahan gelandangan dan
pengemis ini.
Pemerintah DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16
Tahun 1956 (16/1956) tentang penampungan pengemis-pengemis, fakir miskin, orang-orang/anak-
anak gelandangan dan terlantar di luar daerah Kota Besar Yogyakarta, selanjutnya Pemerintah DIY
juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan
Pengemis tujuannya untuk mencegah munculnya gelandangan dan pengemis atau gepeng, sebab
kehadiran gepeng dirasakan mengganggu pemandangan kota dan ketertiban umum. Selain itu,
ada potensi yang mungkin timbul yaitu terjadinya kekerasan, pelecehan seksual, pencurian serta
kejahatan lainnya.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial DIY bekerjasama dengan
pihak kepolisian, Satpol PP Provinsi, dan Dinsosnakertrans kabupaten-kabupaten di DIY, yaitu Kota
1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Vol. 6 No. 1 Juni 2017 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 39
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, serta Kulonprogo dalam melakukan penjangkauan.
Hasil penjangkaun tersebut dibawa ke Camp Assesment Dinas Sosial DIY untuk diidentifikasi
dan diassesment. Camp Assesment adalah tempat penampungan sementara bagi gelandangan dan
pengemis.
Camp Assesment ini berbeda dengan Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Swadaya
Masyarakat lainnya. Perbedaannya yaitu bahwa Camp Assesment ialah tempat yang dapat
menampung semua kategori jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari hasil
penjangkauan dan kiriman masyarakat. Sedangkan Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Swadaya
Masyarakatlainnya tidak menerima semua hasil penjangkauan maupun masyarakat yang memiliki
bermacam-macam jenis PMKS, mereka hanya menerima PMKS yang sesuai dengan visi misi
lembaga. Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat mau menerima PMKS
sesuai dengan kriteria-kriteria dan kuota yang mereka miliki. Hal inilah yang menjadi bahan kajian
yang dipelajari dalam tulisan ini, bagaimana model sistem rujukan bagi gelandangan dan pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY. Apasaja hambatan bagi model sistem rujukan gelandangan
dan pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY.
Sistem Rujukan
Istilah rujukan banyak dikenal dalam berbagai aktifitas pelayanan, khususnya pelayanan
kemanusiaan. Jika kita mengacu pada istilah rujukan yang digunakan dalam dunia pelayanan
sosial kita dapat memahami istilah rujukan sebagai suatu kegiatan merancang, melaksanakan,
mensupervisi, mengevaluasi, dan menyusun laporan berupa kegiatan rujukan penerima program
pelayanan kesejahteraan sosial.2 Menurut Bambang Rustanto, rujukan adalah proses untuk membantu
klien dan keluarganya memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan secara optimal, kemungkinan
dirujuk kepada institusi atau pelayanan lain yang tidak dapat diberikan oleh pekerja sosial maupun
panti sosial.3
Dalam pelayanan kesehatan kita dapat memahami rujukan berdasarkan SK Menteri Kesehatan
RI Nomor 23/1972, pengertian sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang
melaksanakan pelimpahan tanggungjawab timbal-balik terhadap suatu kasus (kesehatan) secara
vertikal dalam arti dari unit berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu, atau secara
horizontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya.4
Sistem rujukan dapat didefinisikan sebagai kerangka kelembagaan yang komprehensif yang
menghubungkan berbagai entitas, didefinisikan dengan baik dan digambarkan sebagai mandat,
tanggungjawab, dan kekuasaan, dan menjadi jaringan kerjasama, dengan tujuan untuk memastikan
perlindungan dan bantuan keselamatan, untuk membantu dalam pemulihan dan pemberdayaan, serta
pencegahan.5 Sistem rujukan ialah peningkatan pelaksanaan sistem rujukan dengan instansi lain
2
Proses Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, http://peksosjatim.
blogspot.co.id/2011/07/proses-pelayanan-dan-rehabilitasi. html/diunduh pada tanggal 7 februari 2015.
3
Bambang Rustanto, “Tahapan Rujukan Sosial”, diakses dari http://bambang-rustanto. blogspot.co.
id/2015/11/tahapan-rujukan-sosial. html/diunduh pada tanggal 8 februari 2016.
4
Sitti Noor Zaenab, “Sistem Rujukan dan Pengembangan Manual Rujukan KIA”. https://docs.
google.com/document/d/1p5NdlL7bbFuxYNasxsrrJH_MM5CxwpdDLsKXlpy2L3g/edit?pli=1/diunduh
pada tanggal 05 Oktober 2015.
5
http://www. health-genderviolence. org/programming-for-integration-of-gbv-within-health-system/
practical-steps-and-recommendations-for-in-0, /diunduh pada tanggal 9 Oktober 2015.
40 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 6 No. 1 Juni 2017
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
yang melaksanakan usaha kesejahteraan bagi PMKS.6
Jadi yang dimaksud dengan sistem rujukan disini ialah bahwa gelandangan dan pengemis
setelah diidentifikasi, ditempatkan di klaster, di assesment, mereka memperoleh pelayanan sosial
berupa bimbingan/pembinaan, kebutuhan sehari-hari, kesehatan bagi yang sakit atau memiliki
gejala-gejala sakit, kemudian dirujuk ke lembaga sosial baik pemerintah maupun swasta. Sebelum
klien dirujuk, petugas pendamping harus mengetahui terlebih dahulu kelemahan dan potensi yang
dimiliki klien, tujuannya agar klien yang dirujuk ke lembaga sosial sesuai dengan sistem sumber
klien.
Model Sistem Rujukan
Model rujukan harus memperhatikan jalur rujukan dan prosedur dengan langkah-langkah
berurutan yang sistematis, sederhana dan efektif. Sistem rujukan harus melibatkan pemerintah, non-
pemerintah bahkan organisasi internasional yang relevan. Dalam rangka memastikan kerjasama
antar pemangku kepentingan didasarkan pada struktur yang berkelanjutan, daripada mengandalkan
kontribusi dari individu yang berkomitmen, pengoperasian mekanisme rujukan harus didasarkan
pada undang-undang atau standar protokol yang mendefinisikan peran dan tanggungjawab dari
semua organisasi yang terlibat.7
Mekanisme rujukan meniscayakan adanya komunikasi antar instansi yang siap merujuk dan
yang siap menerima rujukan. Dalam melakukan rujukan didasarkan pula pada sistem sumber klien
agar rehabilitasi sosial lanjutan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan yang diharapkan oleh
klien maupun lembaga pemberi pelayanan.
Manajemen Pelayanan Rujukan
Secara umum, prinsip-prinsip manajemen meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), pengarahan/pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Prinsip-prinsip
manajemen apabila diterapkan dalam pelayanan rujukan berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan
rujukan direncanakan dan diorganisasikan, bagaimana mengarahkan dan melaksanakan proses
pelayanan rujukan, dan bagaimana mengawasi atau mengevaluasi pelayanan rujukan. Penerapan
prinsip-prinsip manajemen di atas secara terintegrasi dalam pelayanan rujukan akan berkenaan
dengan bagaimana secara umum pelayanan rujukan itu dikelola.
Manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni
untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan
aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan.8 Dengan demikian yang
dimaksud dengan manajemen pelayanan rujukan adalah perencanan rujukan yang disusun dan
dipersiapkan, kemudian dibahas secara bersama-sama oleh seluruh petugas terkait.
Gelandangan dan Pengemis
Istilah “gelandangan” berasal dari kata “gelandang” yang berarti “yang selalu mengembara,
” yang berkelana (lelana) menurut istilah dahulu dan yang lebih netral sifatnya. Istilah gelandangan
6
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial, Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik
Sistem Dalam Panti (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008), hlm. 13.
7
http://www. health-genderviolence. org/programming-for-integration-of-gbv-within-health-system/
practical-steps-and-recommendations-for-in-0, /diunduh pada tanggal 9 Oktober 2015.
8
Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual,
Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 4.
Vol. 6 No. 1 Juni 2017 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 41
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
itu dilukiskan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan layak serta tidak
memiliki tempat tinggal tetap dan layak, dengan ditambah “makan di sembarangan tempat”.9
Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2012, gelandangan didefinisikan
sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang
layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap
serta mengembara di tempat umum. Seseorang disebut gelandangan apabila mereka tidak memiliki
Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap, tanpa penghasilan yang tetap,
tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.10 Menurut Sri Hartinnovmi, gelandangan
memiliki kriteria-kriteria sendiri, diantaranya sebagai berikut:11
a. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal dan hidup
mengembara atau menggelandang di sembarangan tempat dan tempat-tempat umum,
biasanya di kota-kota besar;
b. Mereka tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, hidup bebas/liar, terlepas
dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya;
c. Mereka tidak punya pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau
barang bekas atau tidur di emperan toko dan kolong jembatan.
Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-
minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang
lain.12 Menurut Sri Hartinnovmi, kriteria-kriteria pengemis yaitu:
1) Anak sampai dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun;
2) Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu
lintas), pasar, tempat ibadah dengan tempat umum lainnya;
3) Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih, dan
kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, meminta sumbangan
untuk organisasi;
4) Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk
pada umumnya.13
Dari paparan di atas, menurut peneliti, ada beberapa hal perlu ditambahkan bahwa yang
menjadi kriteria-kriteria pengemis ialah pertama berpakaian yang sobek, kotor, bau, dan ada yang
memiliki penyakit yang tak kunjung sembuh. Kedua, mereka mengemis tidak hanya mengulurkan
tangan, tetapi juga dengan modal joget tanpa alat musik, dan membawa tempat uang.
Faktor Penyebab
Ada beberapa faktor penyebab orang hidup menggelandang dan mengemis. Menurut Sri
Hartinnovmi bermuculan fenomena sosial terutama gelandangan dan pengemis, karena:14
1. Masalah Kemiskinan
9
Widiyanto Paulus, Gelandangan, “Pandangan Ilmuan Sosial”, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 2.
10
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012tentang Pedoman Pendataan
dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
11
Sri Hartinnovmi, Petunjuk Teknis Rehabilitasi Gepeng, (Yogyakarta: PSBK, 2014), hlm. 2.
12
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Paduan Pendataan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Potensi, hlm. 8.
13
Sri Hartinnovmi, Petunjuk Teknis Rehabilitasi, hlm. 2.
14
Ibid. , hlm. 4-5.
42 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 6 No. 1 Juni 2017
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar
minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan
kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak. Tentulah ini akan berdampak pada
seseorang lambat mengakses fasilitas pelayanan yang ada diantaranya bantuan modal
usaha. Selain itu, masalah kemiskinan juga membuat seseorang takut melangkah lebih
jauh meskipun pihak swasta/pemerintah meminjam modal untuk membuka usaha.15
2. Masalah Pendidikan
Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah
sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu,
seseorang yang pendidikan yang rendah akan; a). dengan cepat terpengaruh dengan
lingkungan bebas, seperti minuman keras, berprilaku kurang sopan dan sebagainya; b).
malas bekerja keras; c). tidak mau diatur dalam hidupnya baik dari keluarga maupun
tempat kerja. Alasan ini juga membuat gelandangan dan pengemis lebih memilih hidup
di jalanan dengan mengemis agar mendapatkan uang dengan muda dan cepat.16
3. Masalah Keterampilan Kerja
Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang
sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Keterampilan memang dibutuhkan dalam pekerjaan,
misalnya keterampilan mekanik/elektronik, keterampilan tangan, dan keterampilan-
keterampilan lainnya. Untuk mendapatkan keterampilan, gelandangan dan pengemis
harus mendapatkan informasi. Setelah itu, mereka harus bersungguh-sungguh
mempelajari pelatihan keterampilan tersebut agar keterampilan itu bisa diterapkan di
masyarakat maupun dunia kerja. Realitasnya gelandangan dan pengemis ini meskipun
diberikan pelatihan dan dibina oleh pemerintah serta diberikan bantuan peralatan usaha,
mereka memilih menjualnya daripada menjalankan usaha.17
4. Masalah Sosial Budaya
Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi
gelandangan dan pengemis. Pertama, rendahnya harga diri. Rendahnya harga diri pada
sekolompok orang mengakibatkan hilangnya rasa malu untuk meminta-minta. Kedua,
sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka
sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib sehingga tidak ada kemauan untuk
melakukan perubahan. Ketiga, kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang.
Ada kenyamanan tersendiri bagi sebagian besar gelandang dan pengemis yang hidup
menggelandang karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang
kadang-kadang membebani mereka. Karena itu, mengemis menjadi salah satu mata
pencaharian.18
5. Masalah Tempat Tinggal
Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal
tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti
taman-taman, bawah jembatan, atau pinggiran kali. Oleh karena itu, kehadiran mereka
15
Ibid.
16
Ibid.
17
Ibid.
18
Ibid.
Vol. 6 No. 1 Juni 2017 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 43
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
di kota-kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat, dan
kebersihan serta keindahan kota.19
6. Masalah Kesehatan
Dari segi kesehatan, gelandangan dan pengemis termasuk kategori warga
negara dengan tingkat kesehatan fisik yang rendah akibat rendahnya gizi makanan
dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan.20 Kesehatan gelandangan dan pengemis
yang relative rendah, disebabkan oleh kondisi yang tidak terurus secara mandiri. Bisa
dilihat dari pakaian, budaya makan mereka di jalanan tanpa mencuci tangan terlebih
dahulu, melakukan aktivitas tersebut dibawah teriknya matahari yang panas tanpa
memperdulikan kesehatannya. Sedangkan di malam hari khususnya, gelandangan yang
tidak memiliki rumah tidur di emperan toko, di jalanan, dan di depan pasar. Dengan
hal itu mereka mudah diserang oleh berbagai penyakit, sehingga timbul gejala kondisi
tubuhnya semakin menurun, wajah pucat, penyakit kulit yang tidak diobati.
7. Masalah Kependudukan
Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalanan dan tempat-
tempat umum, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang
tercatat di kelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besar mereka hidup bersama
sebagai suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah.21 Hal ini disebabkan mereka
keluar dari rumah tanpa membawa atau membuat identitas diri dan lama tidak kembali
lagi ke alamat asal yang disebabkan faktor keluarga, lingkungan sosial, masyarakat dan
sebagainya. Kebebasan dan kenyamanan mereka hidup di jalanan akhirnya menemukan
pasangan tanpa ada ikatan resmi sehingga melahirkan seorang anak yang tumbuh
dilingkungan yang kurang layak.
8. Masalah Keamanan dan Ketertiban
Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan
kerawanan sosial, serta mengurangi keamanan dan ketertiban wilayah tersebut. Masalah
yang muncul terhadap seseorang/individu yang menggelandang dan pengemis tidak
hanya masalah kemiskinan dan ketiadaan tempat tinggal, akan tetapi ada beberapa
masalah yang akan mereka hadapi, seperti masalah kekerasan, diskriminasi, atau
kebebasan berekspresi.22 Dalam perkembangan diskursus kontemporer, persoalan
gelandangan dan pengemis tidak semata-mata dikaitkan dengan isu-isu kemiskinan,
namun lebih dilihat sebagai komponen atau bentuk kelompok tertentu yang tersingkir
dari sistem sosial kemasyarakatan.23
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dialami oleh
gelandangan dan pengemis, pertama dari dalam individu berupa tekanan psikologis dan kesehatan.
Kedua, dari lingkungan atau keluarga yang kurang harmonis sehingga gepeng memutuskan hidupnya
di jalanan.
19
Ibid.
20
Ibid.
21
Ibid.
22
Tim Dinas Sosial DIY, ‘Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Gelandangan dan Pengemis’,
(Yogyakarta: Dinas Sosial DIY Bidang Rehabilitasi Sosial, 2014), hlm. 61
23
J. Minnery, “Approaches to Homelessness Policy in Europe, the United States, and Australia”,
Journal of Sosial Issues, (2007), 63 (3), hlm. 641-642.
44 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 6 No. 1 Juni 2017
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
CampAssesment
Kapasitas berbagai lembaga yang dimiliki oleh pemerintah tidak cukup untuk menampung
gelandangan dan pengemis di Yogyakarta. Maka, Dinas Sosial DIY membentuk suatu kegiatan
baru berupa Rumah Perlindungan Sosial yakni sebagai penampungansementara bagi gelandangan
dan pengemis yang didatangkan dari hasil penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas
Sosialdi seluruh kabupaten/kota yang menyebar diberbagai wilayah, seperti di Pasar Bringharjo,
Masjid Agung terutama pada hari Jum’at, di persimpangan lampu merah di jalan-jalan dan di tempat
umum lainnya di seluruh DIY. Camp Assesment merupakan salah satu kegiatan yang berada di Seksi
Rehabilitasi Tuna Sosial/Korban Napza (RTS/KN) Dinas Sosial DIY. Kegiatan Camp Assesment
berupa pembinaan yang diberikan selama para gepeng tersebut berada di Rumah Perlindungan
Sosial (Camp Assesment).
Menghadapi permasalahan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta, Dinas Sosial DIY
menyediakan unit pelaksana untuk menangani gelandangan dan pengemis. Unit pelaksana ini
ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian sosial gelandangan dan pengemis melalui pelatihan
keterampilan hingga menyelenggarakan program transmigrasi ke luar Jawa.
Kelompok Sasaran Camp Assesment
Berdasarkan Peraturan Daerah tentang penanganan gelandangan dan pengemis, sasaran
Camp Assessment adalah gelandangan dan pengemis yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta. Sebagian gelandangan dan pengemis ada juga yang mengajukan diri dengan membawa
surat pengantar dari kepolisian dan memberikan alasan yang jelas. Camp Assessment menerima
semua kategori gelandangan dan pengemis baik laki-laki maupun perempuan yang berusia di atas
18 tahun. Namun jika terdapat anak-anak, mereka tetap akan diterima tetapi setelah itu akan dirujuk
ke Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA) yang menangani permasalahan anak.
Pengelola Camp Assesment
Camp Assessment sebagai salah satu program jangka panjang di Dinas Sosial DIY dikelola
oleh Dinnas Sosial DIY dengan melibatkan beberapa profesi, seperti case manager, administrasi,
pendamping (pekerja sosial), perawat, psikiater, dokter, driver, psikolog, petugas kebersihan,
pramurukti, security, dan juru masak.
Setiap profesi di CampAssessment dikoordinasi dalam suatu garis struktur yang dibawahi
oleh Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penanggungjawab. Setiap petugas
memiliki tanggungjawab terhadap tugasnya masing-masing. Meskipun demikian setiap petugas
saling membantu satu sama lain demi kelancaran dan tercapainya tujuan program.
Aktivitas dan Program di Camp Assesment
Camp Assesment sebagai pihak yang menerima hasil penertiban juga menyediakan Berita
Acara Penerimaan sebagai bukti penerimaan gelandangan dan pengemis dari Satpol PP dan Dinas
Sosial. Berita Acara Penerimaan dari Camp Assesment ditandatangani oleh empat orang; satu orang
yang menyerahkan, satu orang yang menerima dan dua orang saksi.24 Setelah proses penyerahan dan
penerimaan selesai, sebelum klien dirujuk ke balai rehabilitasi sosial ataupun ke lembaga swadaya
masyarakat ada beberapa kegiatan yang disebut sebagai pra rujukan, diantaranya yaitu:
24
Dokumentasi Berita Acara Penerimaan Camp Assessmen Dinas Sosial DIY.
Vol. 6 No. 1 Juni 2017 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 45
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
1. Proses Awal Identifikasi
Identifikasi merupakan langkah awal untuk mengetahui identitas diri, keluarga,
alamat klien, dan jenis permasalahan klien. Proses identifikasi tidak hanya dilakukan
oleh petugas Camp Assesment, melainkan juga oleh petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja,
dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten/Kota. Dalam melakukan identifikasi
yang perlu dilihat ialah jenis permasalahan gelandangan dan pengemis apakah psikotik
atau non-psikotik. Sebagian besar gepeng psikotik tidak dapat diidentifikasi secara jelas,
gepeng psikotik tidak dapat mengingat identitas diri. Gepeng psikotik dengan gepeng
non psikotik di tempatkan terpisah. Gepeng non-psikotik dimasukan dalam ruang
penerimaan sebelum mereka dipindahkan ke klaster masing-masing, kecuali gepeng
psikotik yang mengalami gangguan kejiwaan maka langsung dipindahkan ke klaster
psikotik. Ketika penempatan gepeng non-psikotik ditempatkan di ruang penerimaan,
pihak petugas Camp Assesment bersama Satpol PP memberikan pengarahan dan
gambaran mengenai Camp Assesment secara singkat.
Ketika ada kiriman dari Satpol PP/Dinas Sosial Kabupaten/Kota ke Camp
Assesment Dinas Sosial DIY, petugas langsung melakukan identifikasi dengan tujuan
mendapat informasi mengenai identitas diri, keluarga, dan permasalahan yang dihadapi
oleh klien. Identifikasi sangat penting dilakukan agar dapat dengan mudah melakukan
assesment.
2. Pembagian Tempat Berdasarkan Cluster
Setelah melalui identifikasi awal, para gelandangan dan pengemis yang terjaring
ditempatkan di dalam ruang penerimaan, di tempat tersebut gelandangan dan pengemis
ditampung selama tiga hari. Ruang penerimaan ada dua macam, yaitu ruang penerimaan
perempuan dan ruang penerimaan laki-laki. Mereka mendapatkan kebutuhan makan,
minum, dan peralatan mandi. Bimbingan diberikan setelah mereka ditempatkan di
klaster masing-masing.
3. Proses Assesment
Assesment merupakan tahapan yang dilakukan petugas pendamping/pekerja
sosial untuk menggali permasalahan dan potensi klien dengan tujuan untuk mendapatkan
informasi lebih mendalam mengenai penyebab masalah klien di jalanan yang melakukan
aktivitas mengemis, mengamen, dan menggelandang.
Dalam melakukan assesment, petugas pendamping mempersiapkan peralatan
assesment berupa formulir assesment serta alat tulis. Assesment dilakukan secara
face-to-face di dalam ruangan yang tersedia di Camp Assesment. Selain itu, petugas
pendamping juga melihat situasi kondisi klien, apakah kondisi klien sehat, tenang, atau
bahkan kondisinya sedang emosional. Jika kondisinya sakit maka petugas pendamping
tidak melakukan assesment.
Jika petugas pendamping menemukan permasalahan klien dengan tingkat
depresi atau tekanan psikologis lebih mendalam maka petugas pendamping dapat
meminta bantuan kepada psikolog untuk mengasessment permasalahan yang dialami
klien dan membandingkan hasil tersebut. Dengan hal itu, petugas pendamping dapat
mengambil kesimpulan dari hasil assesment yang dilakukan.
46 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 6 No. 1 Juni 2017
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
4. Kunjungan Rumah
Setelah melakukan assesment dan mendapatkan informasi mengenai
permasalahan yang dihadapi oleh klien, maka petugas pendamping melakukan home
visit ke alamat tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang klien lebih
mendalam melalui keluarga dan tetangga klien. Dapat dikatakan bahwa tujuan home
visit adalah membanding informasi dari klien dengan keluarga dan tetangga klien. Home
visit dapat dilakukan oleh petugas pendamping dengan menyelusuri secara langsung
alamat rumah klien dan bertatap muka dengan keluarga maupun tetangga klien demi
mendapatkan informasi. Sedangkan untuk klien dari luar DIY, petugas pendamping
melakukan home visit sebagai penggalian data atau untuk mendapatkan informasi
mengenai klien, sekaligus memberitahukan keberadaan klien kepada pihak keluarga.
5. Penguatan Individu dan Bimbingan Sosial
Pertama kali klien masuk Camp Assesment, mereka akan mendapat pembinaan
selama 1-3 bulan maksimal. Selama mereka di Camp Assesment, mereka mendapatkan
pembinaan yang diberikan langsung oleh instruktur Camp Assesment yang sesuai
dengan bidangnya. Pembinaan-pembinaan yang diberikan ialah sebagai berikut:
a. Keagamaan/Kerohanian
Instruktur keagamaan adalah takmir masjid yang bernama Ustadz Yusuf
yang telah mendapat kepercayaan untuk membimbing aktivitas keagamaan di
Camp Assessment. Tujuan dari bimbingan agama ini agar mereka dapat mensyukuri
hidup yang mereka jalani, tidak putus asa, saling menghargai/menghormati orang
lain dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, menjalankan ibadah
dan pembinaan akidah akhlak.
b. Pelatihan Kesenian
Kesenian diisi oleh instruktur dari seorang dosen ISI Yogyakarta. Dalam
bimbingan kesenian ini instruktur mengajarkan berbagai hal dari tari, bermain gitar,
pengelohan gambar berwarna, dan sebagainya. Tujuan bimbingan adalah mengenal
atau mengembangkan bakat yang dimiliki klien. Aktivitas tersebut sangat baik
untuk peningkatan psikologis klien,
c. Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT)
Bimbingan motivasi bertujuan agar gelandangan dan pengemis tidak mudah
putus asa menjalani hidup, dan terdorong untuk selalu berfikir maju. Motivasi ini
diberikan oleh instruktur dengan metode sharing film/video. Selain itu, instruktur
juga memberikan bimbingan berupa gerakan motivasi dengan senam jari, dan
sebagainya. Aktivitas ini dapat membantu pendamping dalam menambah data dari
instruktur karena dapat membaca karakter klien.
d. Kegiatan Olahraga
Instruktur Korem Sewon Bantul memberikan pembinaan olahraga.
Tujuan dari pembinaan ini agar kesehatan klien tetap terjaga dan berfikir positif.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk seluruh klien baik non-psikotik maupun
psikotik. Pelaksanaan bimbingan olahraga dilaksanakan pada pagi hari. Ketika ada
pembinaan maka petugas pendamping mendampingi instruktur meskipun hanya
Vol. 6 No. 1 Juni 2017 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 47
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
sebentar. Dalam mengkondisikan klien petugas security dan pendamping membantu
instruktur dalam mengumpulkan klien dengan cara memanggil klien yang masih di
dalam kamar untuk ikut dalam bimbingan tersebut dan mempersiapkan peralatan
musik jika digunakan.
e. Penguatan Mental Sosial
Aktivitas ini di instrukturi oleh pekerja sosial dari Balai Rehabilitasi Sosial
Bina Karya (BRSBK) atas rekomendasi pihak RTS untuk mengisi bimbingan
mental sosial. Bimbingan ini bertujuan agar para klien memiliki mental yang kuat
(tidak putus asa), semangat dalam menjalani hidup atau berfikir positif. Metode
yang diterapkan termasuk nasehat, memberikan gambaran dampak hidup di jalan,
dan bernyanyi bersama-sama dengan musik supaya tidak jenuh selama mereka
mendapatkan bimbingan. Selain itu, untuk mempromosikan dan memperkenalkan
Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya kepada klien bahwa disana terdapat bimbingan
keterampilan.
Proses Rujukan
Dalam melaksanakan rujukan kepada lembaga lembaga penerima, diperlukan adanya pola
dan proses baik yang dapat diikuti oleh setiap pihak yang terlibat. Penerapan pola manajemen
layanan rujukan di Camp Assesment Dinas Sosial DIY dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:
1. Perencanaan (planing) rujukan
Merencanakan pada hakikatnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan.
Kegiatan ini dilakukan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai
sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hubungannya dengan perencanaan layanan
rujukan di Camp Assesment ada beberapa aspek kegiatan penting yang perlu dilakukan
yaitu:
a) Menemukan permasalahan klien;
b) Mengetahui kelemahan dan kelebihan klien;
c) Analisis kebutuhan klien;
d) Penentuan tujuan layanan yang hendak dicapai;
e) Analisis situasi dan kondisi di Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Swadaya
Masyarakat yang menjadi tempat rujukan klien;
f) Penentuan jenis kegiatan yang akan dilakukan;
g) Penetapan metode dan teknik yang akan digunakan dalam kegiatan assesment;
h) Persiapan fasilitas dan administrasi pelaksanaan kegiatan rujukan yang
direncanakan, dan;
i) Perkiraan tentang hambatan yang akan ditemui dan cara untuk mengatasinya.
Petugas pendamping/pekerja sosial dan tugas yang berkaitan dengan
pengorganisasian kegiatan layanan rujukan di Camp Assesment sebagai berikut:
a) Case Manager
Case manager sebagai penanggungjawab kegiatan rujukan dari Camp Assesment
ke Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang
meliputi:
48 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 6 No. 1 Juni 2017
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
• Mengkoordinasikan seluruh petugas pendamping, untuk menyusun laporan
case conference;
• Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam
kegiatan rujukan;
• Bersama petugas pendamping menentukan tempat rujukan yang tepat bagi
klien. Hal ini dilakukan ketika dalam rapat case conference (CC);
• Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan rujukan yang bermasalah;
• Mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan
kegiatan rujukan.
b) Petugas Pendamping/Pekerja Sosial
Pekerja sosial membantu case manager dalam hal:
• Menyusun case record klien;
• Melakukan supervisi bersama peksos dan case manager Camp Assesment;
• Menginformasikan sekaligus meminta persetujuan klien;
• Berkoordinasi dengan Balai Rehabilitasi Sosial atau lembaga swadaya
masyarakat sebagai penerima rujukan;
• Melaksanakan kebijakan case manager terutama dalam hal rujukan.
2. Pelaksanaan Rujukan
Perencanaan layanan rujukan melalui tahap:
• Mempersiapkan administrasi perlengkapan rujukan klien berupa berita acara
penyerahan klien, surat rujukan, dan assesment awal klien;
• Menyiapkan case record yang telah disetujui oleh case manager;
• Berkoordinasi dengan pihak lembaga sosial penerima rujukan, pada H-1 atau pada
hari H;
• Menyiapkan mental klien untuk siap dirujuk;
• Menyerahkan berita acara yang ditanda tangani kedua belah pihak, beserta surat
rujukan, hasil assesment, sekaligus penitipan klien;
• Pengambilan foto sebagai dokumentasi laporan.
3. Pengawasan (controlling)
Untuk mengetahui rujukan berjalan dengan lancar, diperlukan adanya pengawasan untuk
memonitoring kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan. Fachruddin mengatakan
pengawasan adalah kegiatan untuk meneliti jalannya program dan melihat apakah
segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau belum dengan rencana yang di
rencanakan. 25Pengawasan sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk menemukan
faktor-faktor penghambat/kelemahandan faktor-faktor pendukung.
Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung
Pembinaan tidak cukup jika hanya dilakukan di Camp Assesment, dikarenakan hanya satu
bulan saja para gepeng berada di Camp Assesment sebelum akhirnya mereka dirujuk ke lembaga
terkait. Camp Assesment juga hanya bersifat pembinaan awal dalam artian bukan tempat rehabilitasi
25
Fachruddin, Administrasi Pendidikan, (Medan, Cipta Pustaka, 2002), hlm. 67.
Vol. 6 No. 1 Juni 2017 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 49
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
sosial. Oleh sebab itu, rujukan ke Balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat
diharapkan adanya perubahan perilaku dan memiliki skill, agar klien dapat secara mandiri dan hidup
secara wajar dalam masyarakat.
Implementasi sistem rujukan gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan oleh petugas
pendamping Camp Assesment ke Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat tidak
mudah. Dalam penerapan rujukan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan, yaitu
sebagai berikut:
1. Faktor Penghambat
a. Penolakan dari Klien
Praktek pekerja sosial tidak lepas dari prinsip pekerja sosial. Salah satunya
adalah self determination (keputusan klien), dalam melakukan rujukan pekerja
sosial (petugas pendamping) tidak hanya berkoordinasi dengan sesama petugas
pendamping, case manager, psikolog, dan psikiater, tetapi perlu juga berkomunikasi
dengan klien, karena tidak sedikit yang memilih untuk pulang bersama keluarga.
Jika klien tidak mau untuk dirujuk, maka petugas pendamping/pekerja
sosial tetap melakukan motivasi terhadap klien bekerjasama dengan psikolog,
bahkan petugas pendamping Camp Assesment Dinas Sosial menghubungi instansi
melalui pekerja sosial balai rehabilitasi sosial untuk memberikan motivasi sekaligus
memberikan gambaran mengenai balai rehabilitasi sosial yang menjadi rujukan. Jika
klien tetap tidak mau, maka tindaklanjut akhir ialah memulangkan klien bersama
keluarganya dengan surat perjanjian untuk tidak menggelandang/mengemis lagi.
b. Keterbatasan Kuota
Beberapa hal yangberpotensi menjadi faktor penghambat pelaksanaan
sistem rujukan klien di Camp Assesment adalah penolakan oleh Balai Rehabilitasi
Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan alasan terbatasnya kuota. Hal
ini berdampak pada penumpukan gelandangan dan pengemis di Camp Assesment.
Padahal Camp Assesment adalah Rumah Perlindungan Sosial (tempat penampungan)
sementara bagi gelandangan dan pengemis.
Dari hasil wawancara beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa
terjadinya penolakan oleh Balai Rehabilitasi Sosial ketika Camp Assesment
melakukan rujukan ialah pertama, terbatasnya kuota, karena permasalahan kuota
ini menyangkut administrasi logistik seperti makan dan minum, pakaian dan
tempat tidur (sandang, pangan, dan papan) yang sudah ditentukan. Kedua, tidak
adanya tindaklanjut dari kepala dinas sosial DIY yang menyatakan bahwa semua
panti sosial milik pemerintah dikenal dengan Balai Rehabilitasi Sosial yang dapat
menerima rujukan gelandangan dan pengemis di Camp Assesment.
c. Kriteriayang Berlaku pada Lembaga Penerima Rujukan
Permasalahan yang dihadapi dalam melakukan rujukan juga terkait standar
balai rehabilitasi sosial yang memiliki ketentuan khusus. Misalnya lembaga yang
menerima rujukan dengan kriteria dan syarat bahwa klien harus bisa mandiri seperti
mandi, berpakaian, makan dan minum sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini
tentu tidak sama dengan jenis lansia hasil penjangkauan Satpol PP, terkadang orang
50 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 6 No. 1 Juni 2017
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
lanjut usia itu tidak bisa melakukan apa-apa, seperti mandi, dan makan sendiri,
begitu juga dengan balai rehabilitasi sosial lainnya yang memiliki kriteria-kriteria
yang sudah ditetapkan oleh unit pelaksana teknis masing-masing.
2. Faktor- Faktor yang Menjadi Pendukung
Penanganan gelandangan dan pengemis Camp Assesment, tidak lepas dari beberapa
faktor pendukung, terutama dalam penerapan sistem rujukan agar kebutuhan klien
terpenuhi, berikut faktor pendukung dalam penanganan gelandangan dan pengemis:
a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang baik
Sumber daya manusia yang baik dengan berbagai keahlian yang lengkap
dapat membantu pelaksanakan tugas suatu instansi/organisasi berjalan sesuai
dengan visi dan misi. Penanganan gelandangan dan pengemis khususnya di camp
assesment terdiri dari pekerja sosial, psikolog, psikiater, dokter, perawat, staff
administrasi, case manager, tenaga keamanan atau satpam, instruktur pembina,
pramurukti, juru masak, driver dan petugas kebersihan.
b. Adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan
dan Pengemis
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 merupakan naungan hukum sebagai
strategi penanganan gelandangan dan pengemis yang bertujuan untuk: pertama
mencegah terjadinya penggelandangan atau pengemis; kedua memberdayakan
gelandangan dan pengemis; ketiga mengembalikan gelandangan dan pengemis
dalam kehidupan yang bermartabat; dan keempat, menciptakan ketertiban umum.
Penanganan ini diselenggarakan melalui upaya yang bersifat: preventif, koersif,
rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dengan hal ini perilaku hidup yang dijalanan
dapat dicegah dan hak-hak mereka selama ini terpenuhi, serta eksistensi mereka
dimasyarakat diakui.
c. Keberadaan Balai-Balai Rehabilitasi Sosial Milik Pemerintah
Camp Assesment adalah tempat penerimaan awal hasil penjangkauan
gelandangan dan pengemis di seluruh kabupaten/kota di DIY. Dengan hal itu, Camp
Assesment penuh berbagai jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial, dari
masalah lanjut usia, disabilitas, psikotik, PSK, gelandangan, anak jalanan, balita
terlantar, orang dengan penyakit kulit, dan sebagainya.
Oleh sebab itu dengan adanya Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga
Swadaya Masyarakat maka jenis-jenis permasalahan gelandangan dan pengemis
dapat dirujuk sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya.
d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani masalah gepeng. Lembaga
sosial yang dikelola oleh masyarakat yang memberikan pelayanan kepada
gelandangan dan pengemis turut berkontribusi untuk dapat menerima rujukan
gepeng dari Camp Assesment.
e. Kerjasama Lintas Provinsi
Camp Assesment berupaya untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan
gelandangan dan pengemis baik gepeng berasal dari DIY maupun di luar DIY
Vol. 6 No. 1 Juni 2017 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 51
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
dengan semua UPTD milik Pemerintah DIY atau Lembaga Swadaya Masyarakat
yang menangani masalah kesejahteraan sosial khususnya gelandangan dan
pengemis dapat menerima rujukan dari Camp Assesment. Begitu juga dengan Dinas
Sosial Luar DIY, pemerintah DIY melalui Dinas Sosial DIY membuat MoU untuk
bekerjasama menangani masalah gelandangan dan pengemis.
Kerjasama Dinas Sosial DIY dengan Dinas Sosial Luar DIY melalui Mitra
Praja Utama. Kerjasama ini memberikan kemudahan bagi setiap instansi dalam
penanganan gelandangan dan pengemis. Melalui Dinas Sosial setempat dapat
dengan mudah menyelusuri keberadaan keluarga gelandangan dan pengemis yang
berasal dari kota hingga pelosok desa. Dinas sosial Luar DIY bekerjasama dengan
TKSK Kecamatan dan pekerja sosial dalam mencari keberadaan keluarga klien
baik psikotik maupun non-psikotik. Dengan diketahuinya keberadaan asal klien,
maka mempermudah dalam mendapatkan informasi permasalahan yang dihadapi
klien. Selain itu, dengan adanya kerja sama ini, Dinas Sosial khususnya DIY dapat
memulangkan ke rumahnya atau merujuk klien ke panti sosial melalui dinas sosial
setempat supaya mendapatkan pembinaan lanjutan.
Rujukan yang diterapkan oleh Camp Assesment tidak hanya berpusat pada
Balai Rehabilitasi Sosial DIY saja, melainkan juga pada Panti Sosial Luar DIY,
serta pemulangan kembali ke rumah asal, hal ini atas kerjasama atau putusan antara
Dinas Sosial setempat dengan Dinas Sosial luar DIY.
Penutup
Camp Assesment adalah tempat penampungan sementara bagi gelandangan dan pengemis.
Selama berada di Camp Assesment para gepeng mendapatkan pelayanan sosial berupa kebutuhan
dasar, kesehatan medis dan pembinaan lainnya.
Penerapan polasistem rujukan di Camp Assesment Dinas Sosial DIY dapat dijelaskan sebagai
pola yang dilakukan melalui tahap-tahap yang telah di ukur yaitu mulai dari tahap perencanaan
rujukan. Perencanaan pada hakikatnya menentukan kegiatan yang hendak dijalankan. Kegiatan ini
dilakukan untuk mengatur berbagai sumber daya yang dimiliki camp assesment agar hasil yang
dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
Petugas yang berkaitan dengan pengorganisasian kegiatan layanan rujukan di Camp
Assesment diantaranya adalah case manager sebagai penanggungjawab kegiatan rujukan ke berbagai
lembaga penerima rujukan seperti Balai Rehabilitasi Sosial yang dikelola pemerintah atau Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam melaksanakan kegiatannya, case manager ini dibantu oleh
pekerja sosial yang memiliki keahlian dan profesi tersendiri dalam melakukan intervensi kepada
klien.
Proses rujukan dilaksanakan secara teknis oleh pekerja sosial yang berkoordinasi dengan
pihak terkait untuk penyerahaan data kelengkapan klien yang sudah ditentukan diawal. Untuk
mengetahui rujukan sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan maka diperlukan adanya
pengawasan untuk memonitor kegiatan yang sedang dan sudah berlangsung. Pengawasan sangat
penting dilakukan dengan tujuan untuk menemukan faktor penghambat/kelemahanatau pendukung.
Dapat diketahui bahwa beberapa faktor yang berpotensi menjadi penghambat dalam
52 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 6 No. 1 Juni 2017
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
melakukan rujukan ialah adanya standar yang diberlakukan oleh lembaga penerima rujukan baik
berupa Balai Rehabilitasi Sosial milik pemerintah maupun LSM yang menerima rujukan dari Camp
Assesment dengan syarat dan kriteria tertentu sehingga berpotensi menghambat penerimaan rujukan.
Kapasitas tempat penampungan lembaga yang terbatas sehingga berimplikasi pada penumpukan
gepeng.
Sedangkan faktor pendukung dalam penanganan gelandangan dan pengemis diantaranya
ialah pertama, adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan
dan Pengemis. Kedua, adanya sumber daya manusia yang memadai. Ketiga, adanya tujuh Balai
Rehabilitasi Sosial milik pemerintah yang menerima rujukan dari Camp Assesment. Keempat,
adanya lembaga swadaya masyarakat yang menangani masalah gelandangan dan pengemis, dan mau
menerima rujukan dari Camp Assesment. Kelima, adanya kerjasama lintas provinsi antar pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah daerah para gelandangan dan pengemis berasal.
Vol. 6 No. 1 Juni 2017 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 53
Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis
di Camp Assesment Dinas Sosial DIY
Bibliografi
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Proses Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, http://
peksosjatim.blogspot.co.id/2011/07/proses-pelayanan-dan-rehabilitasi.html/ diunduh pada
tanggal 7 februari 2015.
Rustanto, Bambang Rustanto, “Tahapan Rujukan Sosial”, diakses dari http://bambang-rustanto.
blogspot.co.id/2015/11/tahapan-rujukan-sosial.html/diunduh pada tanggal 8 februari 2016.
Zaenab, Sitti Noor, “Sistem Rujukan dan Pengembangan Manual Rujukan KIA”. https://docs.google.
com/document/d/1p5NdlL7bbFuxYNasxsrrJH_MM5CxwpdDLsKXlpy2L3g/edit?pli=1/
diunduh pada tanggal 05 Oktober 2015.
http://www.health-genderviolence.org/programming-for-integration-of-gbv-within-health-
system/practical-steps-and-recommendations-for-in-0/ diunduh pada tanggal 9 Oktober 2015.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial, Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik
Sistem Dalam Panti (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008), hlm. 13.
http://www.health-genderviolence.org/programming-for-integration-of-gbv-within-health-system/
practical-steps-and-recommendations-for-in-0/diunduh pada tanggal 9 Oktober 2015.
Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual,
Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015), hlm. 4.
Paulus, Widiyanto, Gelandangan, “Pandangan Ilmuan Sosial”, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 2.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan
dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial.
Hartinnovmi, Sri, Petunjuk Teknis Rehabilitasi Gepeng, (Yogyakarta: PSBK, 2014), hlm. 2.
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Paduan Pendataan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Potensi, hlm. 8.
Tim Dinas Sosial DIY, ‘Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Gelandangan dan Pengemis’,
(Yogyakarta: Dinas Sosial DIY Bidang Rehabilitasi Sosial, 2014), hlm. 61.
Minnery,J.“ Approaches to Homelessness Policy in Europe, the United States, and Australia”,
Journal of Sosial Issues, (2007), 63 (3), hlm. 641-642.
Dokumentasi Berita Acara Penerimaan Camp Assessmen Dinas Sosial DIY.
Fachruddin, Administrasi Pendidikan, (Medan, Cipta Pustaka, 2002), hlm. 67.
54 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 6 No. 1 Juni 2017
You might also like
- MSW 009 Community Organization Management For Community DevelopmentDocument504 pagesMSW 009 Community Organization Management For Community DevelopmentMahesh Vanam33% (3)
- Social Work Applied Social ScienceDocument13 pagesSocial Work Applied Social ScienceVhiinXoii Berioso100% (2)
- Draft Letter Regarding Source Approval For Bituminous Concrete Grade-1 With BPCL - VG - 30 BitumenDocument3 pagesDraft Letter Regarding Source Approval For Bituminous Concrete Grade-1 With BPCL - VG - 30 BitumenAmol Jadhav50% (4)
- Diass q2 Social Work Humss 12Document7 pagesDiass q2 Social Work Humss 12Denver DerapizaNo ratings yet
- Social Welfare AdministrationDocument33 pagesSocial Welfare AdministrationMohit AdhikariNo ratings yet
- Ellie Malmin Makeup 101 E Book PDFDocument18 pagesEllie Malmin Makeup 101 E Book PDFDoreenNo ratings yet
- Power BI Beyond The Basics PublicDocument74 pagesPower BI Beyond The Basics Publicsharas77No ratings yet
- Theoretical Model in Social Work PracticeDocument4 pagesTheoretical Model in Social Work PracticeammumonuNo ratings yet
- Introduction To Social WorkDocument12 pagesIntroduction To Social WorkShumaila KhakiNo ratings yet
- TPI-MTN-SOP-004 Corrective Maintenance PLTUDocument18 pagesTPI-MTN-SOP-004 Corrective Maintenance PLTUsas13No ratings yet
- SWC14 Fields of Social Work ReviewerDocument21 pagesSWC14 Fields of Social Work ReviewerJane D Vargas100% (1)
- Flexibilise Care An Evaluation of Vision For Social Care 2010Document6 pagesFlexibilise Care An Evaluation of Vision For Social Care 2010Malcolm PayneNo ratings yet
- Social Work: Humanities and Social Sciences Disciplines and Ideas in The Applied Social SciencesDocument14 pagesSocial Work: Humanities and Social Sciences Disciplines and Ideas in The Applied Social SciencesAngelica Sibayan QuinionesNo ratings yet
- Sales & Marketing Plan - CompletedDocument20 pagesSales & Marketing Plan - CompletedAna Nurul LailaNo ratings yet
- Power and Politics in OrganizationDocument31 pagesPower and Politics in OrganizationindermankooNo ratings yet
- The Negative Effects of Minimum Wage Laws, Cato Policy Analysis No. 701Document16 pagesThe Negative Effects of Minimum Wage Laws, Cato Policy Analysis No. 701Cato InstituteNo ratings yet
- SOCI 309 SOCIAL POLICY AND ADMINISTRATION - Notes19TH AUG 2018Document38 pagesSOCI 309 SOCIAL POLICY AND ADMINISTRATION - Notes19TH AUG 2018catherine mutanu100% (9)
- Welfare ModelDocument9 pagesWelfare ModelJananee Rajagopalan100% (4)
- Lesson 10Document9 pagesLesson 10Daisuke Inoue50% (2)
- Bahan Penelitian Terdahulu (Contoh 3)Document10 pagesBahan Penelitian Terdahulu (Contoh 3)rosma watiNo ratings yet
- Social Work Interaction With Communities and InstitutionsDocument468 pagesSocial Work Interaction With Communities and InstitutionsmaniNo ratings yet
- Jurnal Penelitian Kel.8Document10 pagesJurnal Penelitian Kel.8kaprawi422No ratings yet
- Research Methodology - Report: A Study OnDocument39 pagesResearch Methodology - Report: A Study OnSudharshan RajagopalanNo ratings yet
- Report - Reimagining The Social Service Sector - 131216Document10 pagesReport - Reimagining The Social Service Sector - 131216Ankur BhardwajNo ratings yet
- Unit VI Unit VI-Administration, Welfare and Development ServicesDocument33 pagesUnit VI Unit VI-Administration, Welfare and Development ServicesMary Theresa JosephNo ratings yet
- 602-File Utama Naskah-1528-1-10-20220716Document29 pages602-File Utama Naskah-1528-1-10-20220716Muh Faisal TanjungNo ratings yet
- The Role of Social Workers in Social Rehabilitation Services at BinaNetraWytaGuna Social HouseDocument8 pagesThe Role of Social Workers in Social Rehabilitation Services at BinaNetraWytaGuna Social HouseInternational Journal of Innovative Science and Research TechnologyNo ratings yet
- Bswe-003 Block-2-UNIT-10-small Size PDFDocument17 pagesBswe-003 Block-2-UNIT-10-small Size PDFSiya VargheseNo ratings yet
- Bswe-003 Block-2-UNIT-10-small Size PDFDocument17 pagesBswe-003 Block-2-UNIT-10-small Size PDFSiya VargheseNo ratings yet
- Bswe-003 Block-2-UNIT-10-small Size PDFDocument17 pagesBswe-003 Block-2-UNIT-10-small Size PDFSiya VargheseNo ratings yet
- Inclusion Through Care: An Analysis of How Long-Term Care Policies Can Promote Social Inclusion For People With DisabilitiesDocument24 pagesInclusion Through Care: An Analysis of How Long-Term Care Policies Can Promote Social Inclusion For People With DisabilitiesRooseveltHousePPINo ratings yet
- Approaches To SD TranscriptDocument6 pagesApproaches To SD TranscriptJohnAnthonyNo ratings yet
- Case of Study.2 Sure Najud NiDocument5 pagesCase of Study.2 Sure Najud NiRazzie EmataNo ratings yet
- Client Satisfaction To Social Services in Social Rehabilitation Institutions For Drug AbusersDocument16 pagesClient Satisfaction To Social Services in Social Rehabilitation Institutions For Drug AbusersIthaNo ratings yet
- Community ServiceDocument13 pagesCommunity ServiceAbhimanyu SinghNo ratings yet
- Philippine Association of Social WorkerDocument19 pagesPhilippine Association of Social WorkerREdValeraBonillaNo ratings yet
- Desain Penanganan Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota BandungDocument24 pagesDesain Penanganan Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota BandungGesy Lamak MarianusNo ratings yet
- The Council of Social Workers ZimbabweDocument8 pagesThe Council of Social Workers ZimbabweTawanda MatiasheNo ratings yet
- Chapter 3 Community ImmersionDocument14 pagesChapter 3 Community Immersionalyssadelaluna005No ratings yet
- ILMs 5 Asks For A Better Health and Social Care Integration August 2013Document5 pagesILMs 5 Asks For A Better Health and Social Care Integration August 2013Priyadershi RakeshNo ratings yet
- SW 104Document1 pageSW 104Bitchy May DaayataNo ratings yet
- Sociology AssignmentDocument3 pagesSociology AssignmentoofNo ratings yet
- Module 5 7 DIASSDocument16 pagesModule 5 7 DIASSmayethmosteraNo ratings yet
- 5.invatamintul in Asistenta Sociala in RMDocument6 pages5.invatamintul in Asistenta Sociala in RMOlesea CerneiNo ratings yet
- The Kenya Psychosocial Disability Watch Edition - August 2013Document8 pagesThe Kenya Psychosocial Disability Watch Edition - August 2013gkanyi100% (1)
- Unit 5 Task 3Document30 pagesUnit 5 Task 3Abigail Adjei A.HNo ratings yet
- Project ISR Ritesh Dhuri HPGD JL14 3471Document44 pagesProject ISR Ritesh Dhuri HPGD JL14 3471Rohit ThakurNo ratings yet
- Tieng Anh Chuyen Nganh CTXHDocument29 pagesTieng Anh Chuyen Nganh CTXHKATIE_3011No ratings yet
- Community Action PlanDocument14 pagesCommunity Action PlanAlexis Mae SantosNo ratings yet
- Kebijakan Rencana Pembangunan Desa Sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa CidokomDocument13 pagesKebijakan Rencana Pembangunan Desa Sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa CidokomRaden Putra Tabah AlfuthuhNo ratings yet
- Informe - Adulto MayorDocument19 pagesInforme - Adulto MayorMERCEDES ESTEFANY ORDINOLA VALDIVIANo ratings yet
- Ethical Aspects at Work of Personal AssistentsDocument12 pagesEthical Aspects at Work of Personal AssistentsIjahss JournalNo ratings yet
- CriminologyDocument18 pagesCriminologyAvantika GaudNo ratings yet
- Aralin 3 Individual Activity SheetDocument3 pagesAralin 3 Individual Activity SheetShaira RajimNo ratings yet
- PRELIM-FIELDS - 1st LectureDocument25 pagesPRELIM-FIELDS - 1st Lecturenuel mabatanNo ratings yet
- MUDHRA ReportDocument4 pagesMUDHRA ReportTREESANo ratings yet
- The Role of The Social Worker With Older PersonsDocument15 pagesThe Role of The Social Worker With Older PersonsAaqibNo ratings yet
- Social WorkDocument8 pagesSocial WorkMuhammad Amir BachaNo ratings yet
- Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kota ParepareDocument8 pagesAnalisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kota ParepareAmirsan IrsanNo ratings yet
- Professionals and Practitioners in Social Work: What I Need To KnowDocument11 pagesProfessionals and Practitioners in Social Work: What I Need To KnowBenilda Pensica SevillaNo ratings yet
- Gemilang Ramadhan (KDK 2 RANGKUMAN 6)Document6 pagesGemilang Ramadhan (KDK 2 RANGKUMAN 6)Gemilang Ramadhan ヅNo ratings yet
- Diass Week 8 ActivityDocument2 pagesDiass Week 8 ActivityRv BlancoNo ratings yet
- Scope and Impotance of SociologyDocument4 pagesScope and Impotance of SociologyHibbaNo ratings yet
- ESC Module 6Document19 pagesESC Module 6MHRED_UOLNo ratings yet
- BSSW 1B Topic 9-1-1Document4 pagesBSSW 1B Topic 9-1-1carlabelgica379No ratings yet
- Reconstruction of Social Work Through Personalisation: The Need for Policy and Practice Shift in Social Care: Family Directed Support Care Systems.From EverandReconstruction of Social Work Through Personalisation: The Need for Policy and Practice Shift in Social Care: Family Directed Support Care Systems.No ratings yet
- A Self Help Group Approach and Community Organization in a Rural VillageFrom EverandA Self Help Group Approach and Community Organization in a Rural VillageNo ratings yet
- ECE 611 SP17 Homework 1Document3 pagesECE 611 SP17 Homework 1hanythekingNo ratings yet
- PROGRAMACIONDocument76 pagesPROGRAMACIONEdson HernándezNo ratings yet
- Assignment Noor BBM4114Document7 pagesAssignment Noor BBM4114cyrusNo ratings yet
- DN034Document29 pagesDN034Roberto FelicioNo ratings yet
- 311exam3 NeedtoKnowDocument3 pages311exam3 NeedtoKnowBebeto GoenhaNo ratings yet
- Nec 4106 Module 1Document28 pagesNec 4106 Module 1Jessie Rey MembreveNo ratings yet
- Office For Civil Rights Letter To Howard UniversityDocument2 pagesOffice For Civil Rights Letter To Howard UniversityThe College FixNo ratings yet
- Unit 1 The Oil Industry: Spelling / JobsDocument1 pageUnit 1 The Oil Industry: Spelling / Jobslahcen48No ratings yet
- Bos 050121 Interp 2 CDocument155 pagesBos 050121 Interp 2 CRahul AgrawalNo ratings yet
- Cse M1Document4 pagesCse M1GPNNo ratings yet
- Fuchs & Lederer 2007Document20 pagesFuchs & Lederer 2007Marco R. ColombierNo ratings yet
- Mecano Smart1600 Induction Motor 1600 W 5Document20 pagesMecano Smart1600 Induction Motor 1600 W 5dasarathramsNo ratings yet
- Typical Test Cases For A Signup PageDocument3 pagesTypical Test Cases For A Signup PageJoseph AremuNo ratings yet
- Human Area NetworkDocument9 pagesHuman Area NetworkLakshman ReddyNo ratings yet
- Ownership Structure, Corporate Governance and Firm Performance (#352663) - 363593Document10 pagesOwnership Structure, Corporate Governance and Firm Performance (#352663) - 363593mrzia996No ratings yet
- DPWH Tranformer PadDocument1 pageDPWH Tranformer PadAl-fin KaytingNo ratings yet
- Eticketing 170408Document20 pagesEticketing 170408Saurav RawatNo ratings yet
- BEC ReportDocument20 pagesBEC ReportSuyash KerkarNo ratings yet
- Face-to-Face Dimensions For Integral Flanged Globe-Style Control Valve Bodies (ANSI Classes 125, 150, 250, 300, and 600)Document14 pagesFace-to-Face Dimensions For Integral Flanged Globe-Style Control Valve Bodies (ANSI Classes 125, 150, 250, 300, and 600)Ranganathan SekarNo ratings yet
- Project Report PDFDocument66 pagesProject Report PDFTEAM LUASKARTNo ratings yet
- Asus GL553VDDocument70 pagesAsus GL553VDAlisaab CharkazovNo ratings yet
- Chapter 7Document46 pagesChapter 7Deivasigamani SubramaniyanNo ratings yet
- Ball Valves: 3-Way SeriesDocument8 pagesBall Valves: 3-Way SerieslorenzoNo ratings yet